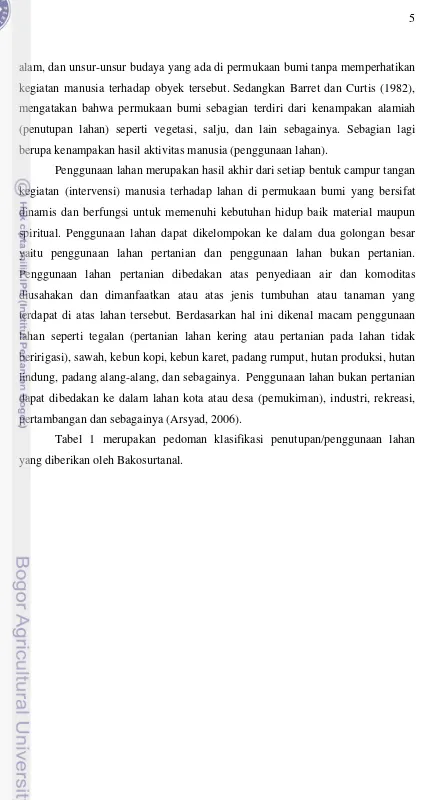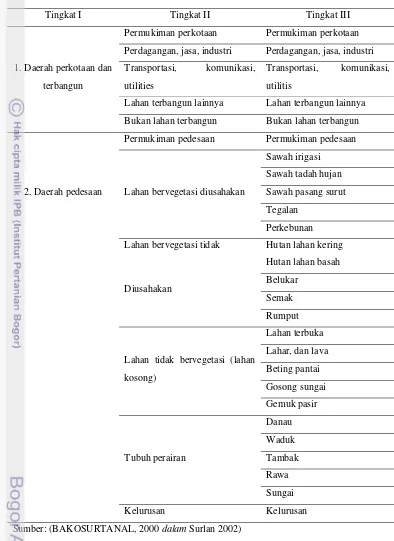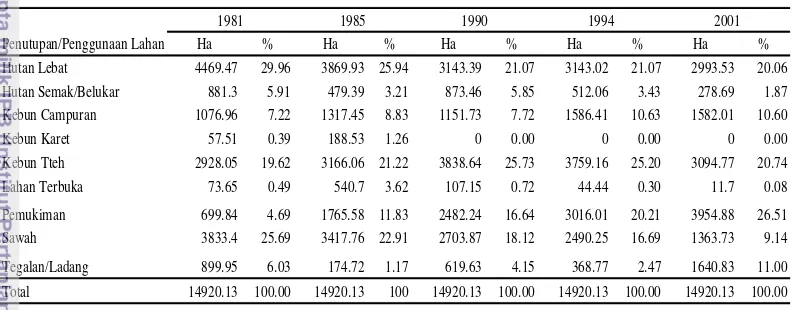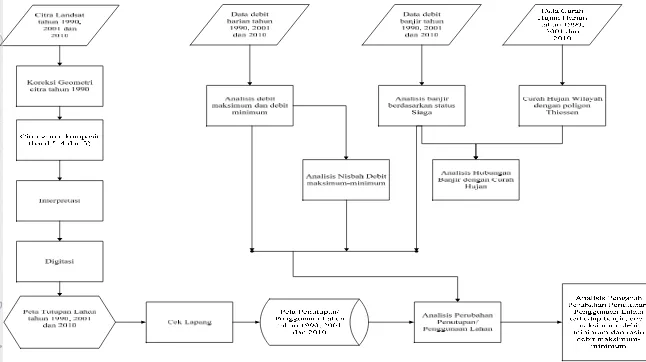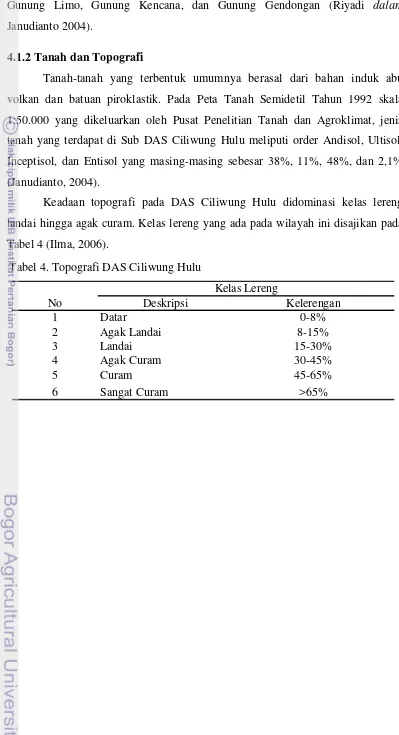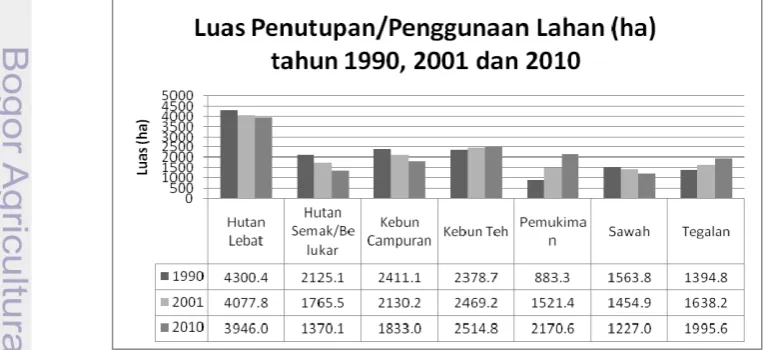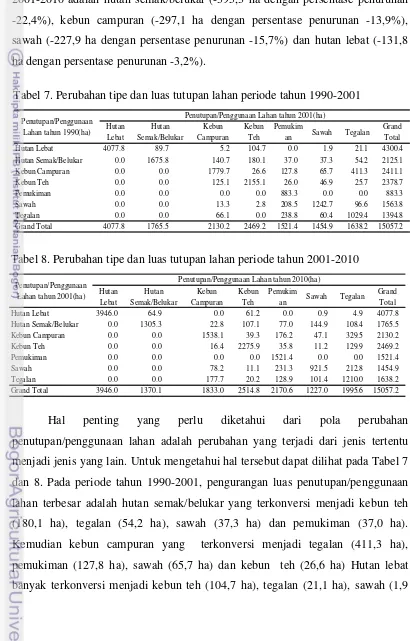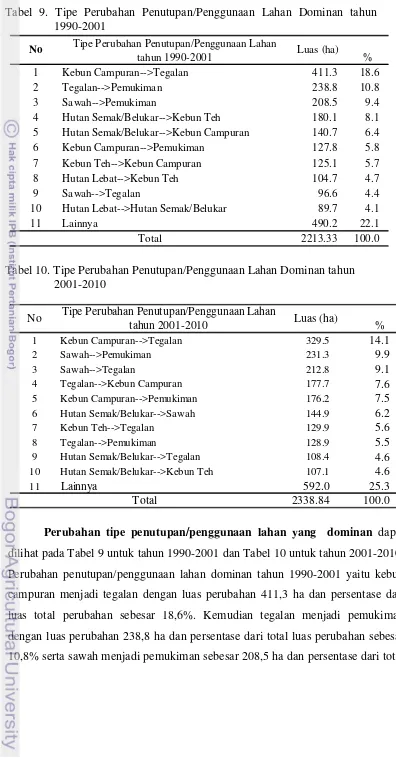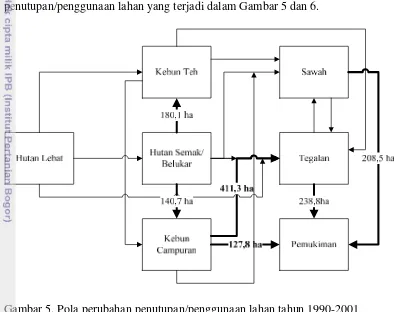OLEH :
SITI NUR HOLIPAH A14070031
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN
FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
RINGKASAN
SITI NUR HOLIPAH. Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi Sub DAS Ciliwung Hulu. Di bawah bimbingan
ERNAN RUSTIADI dan SURIA DARMA TARIGAN.
DAS adalah daratan yang satu kesatuan dengan sungai dan anak
sungainya. DAS merupakan satu ekosistem yang terdiri dari hulu, tengah dan
hilir. Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting karena mempunyai fungsi
perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. DAS Ciliwung termasuk dalam DAS
super prioritas yang harus segera dilakukan upaya konservasi pada wilayah DAS
karena dipandang dari berbagai faktor DAS telah mengalami gangguan. Menurut
Suripin (2002), komponen hidrologi yang terkena dampak kegiatan pembangunan
di dalam DAS meliputi koefisien aliran permukaan, koefisien regim sungai,
nisbah debit maksimum-minimum, kadar lumpur atau kandungan sedimen sungai,
laju, frekuensi dan periode banjir serta keadaan air tanah.
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penutupan/penggunaan lahan,
perubahan penutupan/penggunaan lahan di sub DAS Ciliwung hulu dan
menganalisis pengaruh perubahan penutupan/penggunaan lahan terhadap
karakteristik hidrologi (banjir dan debit maksimum-minimum) DAS. Dalam
penelitian ini digunakan citra landsat tahun 1990, 2001 dan 2010 untuk
menganalisis penutupan/penggunaan lahan. Kondisi perubahan
penutupan/penggunaan lahan dan karakteristik hidrologi kemudian dibandingkan
dan dievaluasi.
Penelitian menghasilkan informasi penutupan lahan tahun 1990 dan 2001
didominasi secara berturut-turut oleh hutan lebat, kebun campuran dan kebun teh.
Sedangkan penggunaan lahan tahun 2010 didominasi secara berturut-turut oleh
hutan lebat, kebun teh dan pemukiman. Pola perubahan penutupan lahan yang
terjadi pada periode tahun 1990-2001 menunjukkan perubahan dari lahan
budidaya pertanian yaitu sawah, tegalan dan kebun campuran menjadi
pemukiman. Luas perubahan yang terjadi secara berturut-turut yaitu 238,8 ha,
238,5 ha dan 127,8 ha. Hutan semak/belukar kemudian berubah menjadi budidaya
pertanian yaitu kebun teh (180,1 ha), kebun campuran (140,7 ha) dan budidaya
pertanian lain. Kebun campuran mengalami konversi yang tinggi ke area tegalan
2001-2010 pola umum perubahan penutupan/penggunaan terjadi tidak terlalu
berbeda namun dalam skala yang lebih besar. Luas perubahan ke area pemukiman
dari konversi lahan budidaya pertanian sawah sebesar 231,3 ha, kebun campuran
sebesar 176,2 ha dan tegalan sebesar 128,9 ha. Luas perubahan ke area tegalan
dari kebun campuran sebesar 329,5 ha dan dari sawah sebesar 212,8 ha. Luas
perubahan hutan semak/belukar ke area kebun teh sebesar 107,1 ha, ke area sawah
144,9 ha dan area tegalan 108,4 ha. Terjadi penurunan kualitas hidrologi pada sub
DAS Ciliwung Hulu dilihat dari karakteristik frekuensi banjir, kualitas banjir,
debit maksimum, debit minimum dan rasio debit maksimum-minimum.
Perubahan pola penutupan/penggunaan lahan yang mengarah kepada pemukiman
dan tegalan serta terkonversinya area hutan semak/belukar dan kebun campuran
menyebabkan menurunnya kualitas karakteristik hidrologi sub DAS Ciliwung
hulu.
SUMMARY
SITI NUR HOLIPAH. Impact of Land Use/Cover Change On Hydrology Characteristics of Sub Watershed Ciliwung. Under supervision of ERNAN RUSTIADI and SURIA DARMA TARIGAN.
Watershed is an ecosystem consisting of upstream, middle and
downstream. Upstream watershed ecosystem is play an important role, because its
function to regulate hydrologic characteristics of the watershed. Ciliwung
watershed is one of the superpriority watershed that must be taken high priority
effort to rehabilitation. According to Suripin (2002), hydrological components
affected by development activities in the watershed includes surface flow
coefficient, coefficient of discharge regim river, the ratio between
maximum-minimum river discharge, mud content or sedimentary deposits in the river, the
rate of frequency and period of floods, and also the state of groundwater.
The aim of the research is to analyze land use/cover, changes of land
use/cover in upstream ciliwung watershed and to analyze its influence on
watershed hydrology (flood and maximum-minimum river discharge). In this
research landsat image of 1990, 2001 and 2010 was used to analyze the land
use/cover changes. After that the condition of land use changes and characteristics
of watershed hydrology were compared and evaluated.
Based on image interpretation of land cover in 1990 and 2001, the area
dominated respectively by dense jungle, mixed farms and tea plantation. While
land use in 2010 is dominated respectively by dense jungle, tea plantation and
settlement. Patterns of land use/cover change at period 1990-2001 indicates
substantially conversion of agriculture land such as the rice field, dryland farming
and mixed farms into settlements. Area that converted respectively are 238.8 ha,
238,5 ha and 127,8 ha. Bush land is transformed into agriculture land as well,
which are tea plantation (180,1 ha), mixed farms (140,7 ha) and other agricultural
cultivation. Mixed farms is the most intensively converted land into dryland
farming (411,3 ha). In the period 2001-2010, pattern of landuse/cover changes
that occured is not too different but in a much larger scale. Large conversion of
agriculture land occurred toward settlement (rice field 231,3 ha, mixed farms
farming are 329,5 ha and rice field 212,8 ha. Amount of bush land converted to
tea plantation, rice field and dryland farming were respectivally 107,1 ha, 144,9
ha and 108,4 ha. A decline in the quality of the upstream ciliwung watershed
hydrology can be seen from characteristic of flood frequency, the quality of a
flood, minimum river discharge and the ratio between
maximum-minimum river discharge. Increase of settlement and dryland farming area in the
upstream ciliwung watershed contribute to declining of upstream ciliwung
sub watershed hydrology characteristics.
PENGARUH PERUBAHAN PENUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP KARAKTERISTIK HIDROLOGI
SUB DAS CILIWUNG HULU
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor
OLEH :
SITI NUR HOLIPAH A14070031
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN
FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi Sub DAS Ciliwung Hulu Nama Mahasiswa : Siti Nur Holipah
Nomor Pokok : A14070031
Menyetujui :
Pembimbing I Pembimbing II
(Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr) (Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc) NIP. 196510111990021002 NIP.196203051987031002
Mengetahui :
Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
(Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc) NIP. 196211131987031003
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Tegal tepatnya di Desa Kambangan Kecamatan
Lebaksiu pada tanggal 11 Juni 1989, putri terakhir dari tiga bersaudara dari
pasangan Ibu Surimi dan Bapak Sumitro.
Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2001 di SD Negeri 13 Jakarta
Selatan, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2004 di SMP Negeri 31 Jakarta
dan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2007 di SMA Negeri 32 Jakarta. Pada
tahun 2007 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan
Seleksi Masuk IPB (USMI).
Penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yaitu Forum Kemahasiswaan
Rohis Departemen (FKRD) Fakultas Pertanian IPB, Dewan Perwakilan
Mahasiswa (DPM) Fakultas Pertanian IPB dan Badan Eksekutif Mahasiswa
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirrabbil’aalamiin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah
SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya selama ini. Terutama saat
menyelsaikan penelitian ini. Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari
sampai Oktober 2011 berjudul Analisis Hubungan Perubahan
Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi. Berhasilnya
penelitian ini dapat berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.
Ucapan Terima kasih penulis sampaikan kepada :
1. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M. Agr dan Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M. Sc atas
arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Ir. D. P. Tejo Baskoro, M. Sc selaku dosen penguji.
3. Ir. Laode Syamsul Iman, M.Si yang telah memberikan ilmunya.
4. Dosen Departemen Manajemen Sumber Daya Lahan atas ilmu yang telah
diberikan selama ini.
5. Dosen dan staf Laboratorium Perencanaan Pengembangan Wilayah.
6. Bapak Andi selaku Pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Ciliwung-Cisadane Kota Bogor atas data yang diberikan, Bapak Sudirman
selaku Kepala pintu air Katulampa dan Ibu Leni selaku staf BMKG
Dramaga atas bantuannya dalam memperoleh data.
7. Bapak, Mama, Kakak dan Keponakan atas segala kasih sayang, doa,
motivasi, semangat dan inspirasi yang telah diberikan selama ini.
8. Teman seperjuangan laboratorium Pengembangan Wilayah dan
teman-teman yang sudah membantu penelitian ini Aci, Andi, Endang, Dita,
Nindi, Lili, Citra, Febri, Sis dan Ufi.
9. Teman-teman seperjuangan Soil 44 yang tidak bisa disebutkan satu
persatu.
10.Keluarga Pesantren Mahasiswa Al-Iffah IPB, Team Lingkaran Lollypop,
keluarga Salam ISC 2011 atas kebersamaannya selama ini.
11.Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.
Bogor, Desember 2011
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ...x
DAFTAR TABEL ... xii
DAFTAR GAMBAR ... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ... xiv
I. PENDAHULUAN ...1
1.2 Latar Belakang ...1
1.2 Tujuan ...2
II. TINJAUAN PUSTAKA ...3
2.1 Citra Landsat ...3
2.2 Penutupan/Penggunaan Lahan ...5
2.3 Jenis Penutupan/Penggunaan Lahan ...6
2.4 Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ...7
2.5 Daerah Aliran Sungai ...8
2.6 Siklus Hidrologi ...9
2.7 Aliran Permukaan ...10
2.8 Banjir ...11
2.9 Sistem Peringatan Dini Banjir ...12
2.10 Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi ...13
III. METODE PENELITIAN ...15
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...15
3.2 Bahan dan Alat ...15
3.3 Metode Penelitian ...16
3.3.1 Stacking Image ...16
3.3.2 Koreksi Geometri ...17
3.3.3 Penajaman Citra ...17
3.3.4 Digitasi ...17
3.3.5 Cek Lapang ...18
3.3.7 Poligon Thiessen ...19
3.3.8 Banjir ...20
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ...22
4.1 Kondisi Fisik Sub DAS Ciliwung Hulu ...22
4.1.1 Geologi dan Geomorfologi ...22
4.1.2 Tanah dan Topografi ...23
V. HASIL DAN PEMBAHASAN ...24
5.1 Interpretasi Citra Landsat Tahun 1990, 2001 dan 2010 ...24
5.2 Pola Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ...25
5.3 Perubahan Penutupan Penggunaan Lahan ...27
5.4 Analisis Debit Maksimum-Minimum ...37
5.5 Analisis Banjir ...39
5.6 Hubungan Curah Hujan dengan Banjir ...40
5.7 Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan dengan Karakteristik Hidrologi DAS (Banjir dan Debit Maksimum- Minimum). ...42
VI. KESIMPULAN DAN SARAN ...45
6.1 Kesimpulan ...45
6.2 Saran ...45
DAFTAR PUSTAKA ...47
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rekomendasi Klasifikasi Penutupan/Penggunaan Lahan untuk
Pemetaan Tematik Dasar Indonesia ...6
Tabel 2. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Sub DAS Ciliwung Hulu ...8
Tabel 3. Pembobotan Curah Hujan Poligon Thiessen ...19
Tabel 4. Topografi DAS Ciliwung Hulu ...23
Tabel 5. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan 2010 ...25
Tabel 6. Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan 2010 ...28
Tabel 7. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 1990-2001...29
Tabel 8. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 2001-2010...30
Tabel 9. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun 1990-2001 ...31
Tabel 10. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun 2001-2010 ...31
Tabel 11. Debit maksimum dan Debit Minimum tahun 1990, 2001 dan 2010 ...38
Tabel 12. Kejadian Banjir dengan Curah Hujan Sama ...40
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Peta Administrasi wilayah Sub DAS Ciliwung Hulu ...15
Gambar 2. Bagan Alir Penelitian ...21
Gambar 3. Grafik Luas Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990, 2001 dan 2010 ...27
Gambar 4. Grafik Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990-2010 ...28
Gambar 5. Pola perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 1990-2001 ...34
Gambar 6. Pola perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 2001-2010 ...35
Gambar 7. Frekuensi Banjir berdasarkan Status Siaga ...39
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Peta Penutupan Lahan tahun 1990 ...50
Lampiran 2. Peta Penutupan Lahan tahun 2001 ...51
Lampiran 3. Peta Penggunaan Lahan tahun 2010 ...52
Lampiran 4. Penampakan citra landsat untuk masing-masing tipe penutupan lahan ...53
Lampiran 5. Foto penggunaan lahan existing di wilayah penelitian ...54
Lampiran 6. Kombinasi perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 1990-2001 ...56
Lampiran 7. Kombinasi perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 2001-2010 ...57
Lampiran 8. Data Kejadian Banjir tahun 1990 ...58
Lampiran 9. Data Kejadian Banjir tahun 2001 ...58
Lampiran 10. Data Kejadian Banjir tahun 2010 ...59
Lampiran 11. Curah Hujan wilayah Sub DAS Ciliwung hulu tahun 1990 ...60
Lampiran 12. Curah Hujan wilayah Sub DAS Ciliwung hulu tahun 2001 ...61
Lampiran 13. Curah Hujan wilayah Sub DAS Ciliwung hulu tahun 2010 ...62
Lampiran 14. Debit maksimum bulanan tahun 1990, 2001 dan 2010 ...63
I. PENDAHULUAN 1.2 Latar Belakang
Sebagian besar wilayah DKI Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih
rendah dari permukaan laut. Kota ini dialiri oleh tiga belas sungai yang bermuara
di Laut Jawa. Saat ini Jakarta juga merupakan kota dengan jumlah penduduk
tertinggi di Indonesia dan jumlah ini terus bertambah karena daya tarik kota ini
sebagai pusat perekonomian. Perpaduan antara kondisi geografis dengan dataran
yang rendah dan dialiri oleh banyak sungai, serta kian rusaknya lingkungan hidup
akibat tekanan pertumbuhan penduduk, menyebabkan Jakarta kian lama kian
rentan terhadap ancaman bencana banjir (Kompas, 2007).
Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan
merendam daratan. Banjir di Kota Jakarta berkaitan erat dengan banyak faktor
seperti antara lain, pembangunan fisik di kawasan tangkapan air di hulu yang
kurang tertata baik, urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan ekonomi dan
perubahan iklim global.
Salah satu sungai yang bermuara di Jakarta adalah sungai Ciliwung, hulu
sungai ini berada di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor
dan Kabupaten Cianjur, atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango dan
daerah Puncak serta melintasi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan Jakarta.
DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan
sungai beserta anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan,
dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara
alami. DAS merupakan satu ekosistem yang terdiri dari hulu, tengah dan hilir.
Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting karena mempunyai fungsi
perlindungan terhadap seluruh bagian DAS (Asdak, 2010).
DAS Ciliwung merupakan satu dari beberapa DAS yang tergolong kritis,
dan termasuk DAS super prioritas. Penetapan DAS Prioritas ini dilakukan oleh
Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan
Umum karena suatu DAS telah mengalami gangguan sehingga diperlukan upaya
konservasi dengan segera. Pada dasarnya, DAS Ciliwung mempunyai
karakteristik yang hampir sama dengan DAS kritis lainnya, akan tetapi ada
wilayah hilir DAS Ciliwung mencakup ibukota Negara (DKI Jakarta) yang sangat
kaya akan berbagai aset nasional dan pemukiman penduduk. Kedua kerusakan
wilayah hulu DAS Ciliwung tidak semata-mata sebagai akibat dari kegiatan
pertanian, tetapi juga oleh tumbuhnya pemukiman dan prasarana lainnya yang
tidak berwawasan lingkungan. Ketiga wilayah hulu DAS Ciliwung merupakan
kawasan wisata yang terus berkembang sehingga hal itu mengakibatkan terjadinya
tekanan terhadap sumberdaya air semakin berlanjut (Lewolaba, 1997).
Leopold dan Dunne (1978) dalam Sudadi et al. (1991) mengatakan secara
umum perubahan penggunaan lahan akan mengubah: (1) karakteristik aliran
sungai, (2) total aliran permukaan, (3) kualitas air dan (4) sifat hidrologi yang
bersangkutan. Komponen hidrologi yang terkena dampak kegiatan pembangunan
di dalam DAS meliputi koefisien aliran permukaan, koefisien regim sungai,
nisbah debit maksimum-minimum, kadar lumpur atau kandungan sedimen sungai,
laju, frekuensi dan periode banjir serta keadaan air tanah (Suripin, 2002).
Berkaitan dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu
dilakukan suatu kajian mengenai perubahan penutupan/penggunaan lahan di
daerah sub DAS Ciliwung Hulu dan dinamikanya. Khususnya mengenai pengaruh
perubahan penutupan/penggunaan lahan terhadap perubahan karakteristik
hidrologi DAS.
1.2 Tujuan
1. Menganalisis penutupan/penggunaan lahan dan perubahannya di kawasan sub
DAS Ciliwung Hulu pada tahun 1990, 2001 dan 2010.
2. Menganalisis pengaruh perubahan penutupan/penggunaan lahan terhadap
karakteristik hidrologi DAS (frekuensi banjir, kualitas banjir, debit
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Citra Landsat
Landsat 5 diluncurkan pada 1 Maret 1984, sekarang ini masih beroperasi
pada orbit polar membawa sensor TM (Thematic Mapper) yang mempunyai
resolusi spasial 30 x 30 m pada band 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Sensor TM mengamati
obyek-obyek di permukaan bumi dalam 7 band spektral yaitu band 1, 2 dan 3
adalah sinar tampak (visible), band 4, 5 dan 7 adalah infra merah dekat, infra
merah menengah, dan band 6 adalah infra merah termal yang mempunyai resolusi
spasial 120 x 120 m. Luas liputan satuan citra adalah 175 x 185 km pada
permukaan bumi. Landsat 5 mempunyai kemampuan untuk meliput daerah yang
sama pada permukaan bumi pada setiap 16 hari pada ketinggian orbit 705 km
(Sitanggang dalam Siddik, 2008).
Program Landsat merupakan yang tertua dalam program observasi bumi.
Landsat dimulai tahun 1972 dengan satelit Landsat-1 yang membawa sensor MSS
multispektral. Setelah tahun 1982, Thematic Mapper TM ditempatkan pada sensor
MSS. Pada April 1999 Landsat-7 diluncurkan dengan membawa ETM+scanner.
Saat ini, hanya Landsat-5 dan 7 yang masih beroperasi.
Sistem Landsat merupakan milik Amerika Serikat yang mempunyai tiga
instrument pencitraan, yaitu RBV (Return Beam Vidicon), MSS (multispectral
Scanner) dan TM (Thematic Mapper) (Jaya dalam Siddik, 2008). RBV
merupakan instrumen semacam televisi yang mengambil citra snapshot dari
permukaan bumi sepanjang track lapangan satelit pada setiap selang waktu
tertentu. MSS merupakan suatu alat scanning mekanik yang merekam data
dengan cara men-scanning permukaan bumi dalam jalur atau baris tertentu TM
juga merupakan alat scanning mekanis yang mempunyai resolusi spectral, spatial
dan radiometric.
Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan
maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya objek tersebut.
Di dalam pengenalan obyek yang tergambar pada citra, ada tiga rangkaian
kegiatan yang diperlukan yaitu deteksi, identifikasi dan analisis. Deteksi ialah
pengamatan atas adanya obyek, identifikasi ialah upaya mencirikan obyek yang
ialah tahap mengumpulkan keterangan lebih lanjut. Interpretasi citra dapat
dilakukan secara visual maupun digital (Somantri, 2009).
Interpretasi visual dilakukan pada citra hardcopy atau yang tertayang pada
monitor komputer. Interpretasi visual adalah aktivitas visual untuk mengkaji
gambaran muka bumi yang tergambar pada citra untuk tujuan identifikasi objek
dan menilai maknanya. Unsur-unsur dalam interpretasi yaitu :
a.Bentuk: merupakan konfigurasi atau kerangka suatu obyek. Bentuk beberapa obyek demikian mencirikan sehingga citranya dapat
diidentifikasi langsung hanya berdasarkan kriteria ini.
b.Ukuran obyek: dipertimbangkan sehubungan dengan skala foto udara. c.Pola: Hubungan spasial obyek. Pengulangan bentuk umum tertentu atau
pola hubungan merupakan karakteristik bagi banyak obyek alamiah
maupun bangunan dan akan memberikan suatu pola yang memudahkan
penafsir untuk mengidentifikasi pola tersebut.
d.Bayangan: Bentuk atau kerangka bayangan dapat memberikan gambaran profil suatu obyek dan obyek di bawah bayangan hanya dapat
memantulkan sedikit cahaya dan sukar diamati pada foto.
e.Rona: adalah warna atau kecerahan relatif suatu obyek pada foto. f.Tekstur: Frekuensi perubahan rona pada citra fotografi.
g.Situs: Lokasi obyek dalam hubungannya dengan obyek yang lain. (Liliesand and Kiefer, 1997)
Interpretasi citra digital yaitu aktivitas mengkaji gambaran muka bumi
dengan menggunakan bantuan software untuk menginterpretasi citra satelit seperti
Erdas Imagine atau ENVI.
2.2 Penutupan/Penggunaan Lahan
Istilah penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di
permukaan bumi. Istilah penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia
pada bidang lahan tertentu (Liliesand and Kiefer, 1997). Karakteristik
penutupan/penggunaan lahan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi
bio-fisik maupun sosial ekonomi masyarakatnya (Haryadi, 2007).
Dalam artikel Beni Raharjo mengutip Townshend dan Justice (1981)
alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan
kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Sedangkan Barret dan Curtis (1982),
mengatakan bahwa permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah
(penutupan lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya. Sebagian lagi
berupa kenampakan hasil aktivitas manusia (penggunaan lahan).
Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan
kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat
dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun
spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokan ke dalam dua golongan besar
yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian.
Penggunaan lahan pertanian dibedakan atas penyediaan air dan komoditas
diusahakan dan dimanfaatkan atau atas jenis tumbuhan atau tanaman yang
terdapat di atas lahan tersebut. Berdasarkan hal ini dikenal macam penggunaan
lahan seperti tegalan (pertanian lahan kering atau pertanian pada lahan tidak
beririgasi), sawah, kebun kopi, kebun karet, padang rumput, hutan produksi, hutan
lindung, padang alang-alang, dan sebagainya. Penggunaan lahan bukan pertanian
dapat dibedakan ke dalam lahan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi,
pertambangan dan sebagainya (Arsyad, 2006).
Tabel 1 merupakan pedoman klasifikasi penutupan/penggunaan lahan
Sumber: (BAKOSURTANAL, 2000 dalam Surlan 2002)
2.3 Jenis Penutupan/Penggunaan Lahan
Penelitian ini membagi/mengelompokkan penutupan/penggunaan lahan
menjadi tujuh kategori, masing-masing yaitu hutan lebat, hutan semak/belukar,
kebun teh, kebun campuran, pemukiman, sawah, dan tegalan.
Tingkat I Tingkat II Tingkat III
1. Daerah perkotaan dan terbangun
Permukiman perkotaan Permukiman perkotaan Perdagangan, jasa, industri Perdagangan, jasa, industri Transportasi, komunikasi,
utilities
Transportasi, komunikasi, utilitis
Lahan terbangun lainnya Lahan terbangun lainnya Bukan lahan terbangun Bukan lahan terbangun
2. Daerah pedesaan
Permukiman pedesaan Permukiman pedesaan
Lahan bervegetasi diusahakan
Sawah irigasi Sawah tadah hujan Sawah pasang surut Tegalan
Perkebunan Lahan bervegetasi tidak Hutan lahan kering
Diusahakan
Hutan lahan basah Belukar
Semak Rumput
Lahan tidak bervegetasi (lahan kosong)
Lahan terbuka Lahar, dan lava Beting pantai Gosong sungai Gemuk pasir Tubuh perairan Danau Waduk Tambak Rawa Sungai Kelurusan Kelurusan
Harimurti dalam Janudianto (2004) memberikan definisi dan batasan yang
jelas mengenai tipe penggunaan lahan di atas. Definisi dari masing-masing
penggunaan lahan di atas yaitu :
• Hutan Lebat: Wilayah yang ditutupi oleh vegetasi pepohonan baik alami
maupun yang dikelola dengan tajuk yang rimbun dan besar/lebat.
• Hutan Semak/Belukar: Hutan yang telah dirambah atau dibuka, merupakan area transisi dari hutan lebat menjadi kebun atau lahan
pertanian, bisa berupa hutan dengan semak atau belukar dengan tajuk yang
relatif kurang rimbun.
• Kebun Campuran: Daerah yang ditumbuhi vegetasi tahunan satu jenis
maupun campuran baik dengan pola acak, maupun teratur sebagai
pembatas tegalan.
• Permukiman: Kombinasi antara jalan, bangunan, pekarangan dan bangunan itu sendiri.
• Sawah: Daerah pertanian yang ditanami padi sebagai tanaman utama
dengan rotasi tertentu yang biasanya diairi sejak saat pertanaman hingga
beberapa hari sebelum panen.
• Tegalan: Daerah yang umumnya ditanami tanaman semusim, namun pada
sebagian lahan tidak ditanami dengan vegetasi. Vegetasi yang umum
dijumpai seperti padi gogo, singkong, jagung, kentang, kedelai, dan
kacang tanah.
• Kebun Teh: merupakan daerah yang digunakan sebagai perkebunan teh
baik yang diusahakan pemerintah maupun pihak swasta.
2.4 Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan
Identifikasi perubahan penggunaan lahan pada suatu DAS merupakan
suatu proses mengindentifikasi perbedaan keberadaan suatu objek atau fenomena
yang diamati pada waktu yang berbeda di DAS tersebut. Indentifikasi perubahan
penggunaan lahan memerlukan suatu data spasial temporal (Suarna et al., 2008).
Penggunaan lahan secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu
faktor alami seperti iklim, topografi, tanah atau bencana alam dan faktor manusia
berupa aktivitas manusia pada sebidang lahan. Faktor manusia dirasakan
besar perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia dalam
memenuhi kebutuhannya pada sebidang lahan yang spesifik (Vink dalam Sudadi
et al., 1991).
Tabel 2 adalah hasil analisis perhitungan luas penutupan/penggunaan
lahan menurut penelitian Sudadi et al. tahun 1981, 1985 dan 1990. Serta hasil
analisis perhitungan luas penutupan/penggunaan lahan menurut penelitian
Janudianto tahun 1994 dan 2001 di wilayah sub DAS Ciliwung Hulu.
Sumber: Sudadi et al. (1991) dan Janudianto (2004) 2.5 Daerah Aliran Sungai
Definisi daerah aliran sungai dapat berbeda-beda menurut pandangan dari
berbagai aspek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,
yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.
Menurut Departemen Kehutanan (2001), daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alaminya sedemikian rupa,
sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang
melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari
curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai
utamanya (single outlet). Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
Hutan Lebat 4469.47 29.96 3869.93 25.94 3143.39 21.07 3143.02 21.07 2993.53 20.06
Hutan Semak/Belukar 881.3 5.91 479.39 3.21 873.46 5.85 512.06 3.43 278.69 1.87
Kebun Campuran 1076.96 7.22 1317.45 8.83 1151.73 7.72 1586.41 10.63 1582.01 10.60
Kebun Karet 57.51 0.39 188.53 1.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kebun Tteh 2928.05 19.62 3166.06 21.22 3838.64 25.73 3759.16 25.20 3094.77 20.74
Lahan Terbuka 73.65 0.49 540.7 3.62 107.15 0.72 44.44 0.30 11.7 0.08
Pemukiman 699.84 4.69 1765.58 11.83 2482.24 16.64 3016.01 20.21 3954.88 26.51
Sawah 3833.4 25.69 3417.76 22.91 2703.87 18.12 2490.25 16.69 1363.73 9.14
Tegalan/Ladang 899.95 6.03 174.72 1.17 619.63 4.15 368.77 2.47 1640.83 11.00
Total 14920.13 100.00 14920.13 100 14920.13 100.00 14920.13 100.00 14920.13 100.00
Penutupan/Penggunaan Lahan
1981 1985 1990 1994 2001
dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi
habis ke dalam sub DAS – sub DAS.
Menurut Asdak (2010), DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara
topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan
menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melaluli sungai
utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (DTA atau
catchment area) yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri
atas sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai
pemanfaat sumberdaya alam.
Menurut Suripin (2002), DAS dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah
yang dibatasi oleh alam, seperti punggung-punggung bukit atau gunung maupun
batas buatan seperti jalan atau tanggul dimana air hujan turun di wilayah tersebut
memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet). Menurut Kamus Webster
dalam Suripin (2002), DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah
topografi, yang menerima hujan, menampung, menyimpan dan mengalirkan ke
sungai dan seterusnya ke danau atau ke laut.
Daerah Aliran Sungai merupakan satu ekosistem yang terdiri atas
komponen biotis dan abiotis yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan
yang teratur. Aktivitas satu komponen ekosistem selalu mempengaruhi ekosistem
yang lain. DAS dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Secara biogeofisik,
daerah hulu DAS dicirikan oleh hal-hal berikut merupakan daerah konservasi,
mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, merupakan daerah dengan
kemiringan lereng besar (lebih dari 15%), bukan merupakan daerah banjir,
pengaturan pemakaian air dipengaruhi oleh pola drainase dan jenis vegetasi
umumnya merupakan tegakan hutan. Ekosistem DAS hulu merupakan bagian
yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian
DAS (Asdak, 2010).
2.6 Siklus Hidrologi
Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari proses penambahan,
penampungan dan kehilangan air di bumi. Air yang jatuh ke bumi dalam bentuk
ke udara menjadi awan dalam bentuk hujan, salju dan embun yang kemudian akan
kembali jatuh ke bumi.
Sebagian besar air hujan yang jatuh menguap sebelum sampai ke bumi
(evaporasi). Pada tempat yang terdapat tumbuhan atau benda lain air hujan akan
ditahan (intersepsi), air hujan yang tertahan sebagian akan menguap ke udara,
sebagian lagi jatuh ke permukaan tanah (lolosan tajuk/through fall) sedangkan
sebagian yang lain akan mengalir di permukaan tumbuhan kemudian sampai ke
permukaan tanah (aliran batang/stem flow). Bagian air hujan yang sampai ke
permukaan tanah akan mengalir di permukaan tanah disebut aliran permukaan
(runn off) atau masuk ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air infiltrasi bisa menjadi
air bawah tanah, menguap ke udara atau diserap tanaman.
Presipitasi atau curah hujan merupakan curahan atau jatuhnya air dari
atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk berbeda. Presipitasi adalah
faktor utama yang mengendalikan proses daur hidrologi suatu DAS (Arsyad,
2006).
2.7 Aliran Permukaan
Aliran Permukaan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah atau
bumi. Bentuk aliran inilah yang paling penting sebagai penyebab erosi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan/run off terdiri dari dua kelompok, yakni
kelompok meteorologi yang diwakili oleh hujan dan elemen daerah pengaliran
yang menyatakan sifat fisik dari daerah pengaliran. Elemen meteorologi terdiri
dari jenis presipitasi, intensitas curah hujan, lamanya curah hujan, distribusi curah
hujan dalam daerah limpasan, arah pergerakan hujan serta curah hujan terdahulu
dan kelembaban tanah. Elemen daerah pengaliran terdiri dari kondisi penggunaan
tanah (land use), luas daerah pengaliran, kondisi topografi daerah pengaliran dan
jenis tanah (Arsyad, 2006).
Aliran permukaan memiliki sifat-sifat yang mempengaruhi
kemampuannya untuk menimbulkan erosi. Sifat-sifat tersebut yaitu diantaranya
jumlah aliran permukaan menyatakan jumlah air yang mengalir di permukaan
tanah untuk suatu massa hujan atau massa tertentu dinyatakan dalam tinggi kolom
air (mm atau cm) atau dalam volume air (m3) dan laju aliran permukaan (debit)
waktu dinyatakan dalam m/detik atau m/jam. Besarnya debit dinyatakan dengan
persamaan:
Q = AV
Q adalah debit air, A adalah luas penampang saluran dan V adalah kecepatan air melalui penampang tersebut.
Debit aliran permukaan berubah menurut waktu yang dipengaruhi oleh
terjadinya hujan. Pada musim hujan debit akan mencapai maksimum dan pada
musim kemarau akan mencapai minimum. Rasio debit maksimum (Qmax) terhadap
debit minimum (Qmin) menunjukkan keadaan DAS yang dilalui sungai. Semakin
kecil rasionya, semakin baik keadaan vegetasi dan penggunaan lahan DAS dan
sebaliknya (Arsyad, 2006).
2.8 Banjir
Banjir adalah air yang melebihi kapasitas tampung di dalam tanah, saluran
air, sungai, danau atau laut karena kelebihan kapasitas air dalam tanah, saluran air,
sungai, danau, dan laut akan meluap dan mengalir cukup deras menggenangi
dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Hal itu sesuai dengan sifat air
yang selalu mengalir dan mencari tempat-tempat yang lebih rendah (Kristianto,
2010).
Dalam istilah teknis, banjir adalah aliran air sungai yang mengalir
melampaui kapasitas tampung sungai dan dengan demikian aliran air akan
melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya (Asdak, 2010).
Faktor-faktor Penyebab Banjir:
1. Pengaruh aktivitas manusia: pembangunan pemukiman, mengubah
pemanfaatan hutan menjadi budidaya, pembangunan di sekitar sepadan
sungai, sampah dll.
2. Kondisi Alam yang bersifat tetap: kondisi geografi daerah yang sering
terkena badai, angin muson barat daya membuat hujan deras terutama
india dan asia tenggara. Daerah dengan topografi cekung.
3. Peristiwa Alam yang bersifat dinamis: hujan dalam jangka waktu panjang
atau hujan deras berhari-hari, penurunan muka tanah atau amblesan,
Jenis-jenis Banjir berdasarkan Penyebabnya dan Proses terjadinya di Indonesia
menurut Kristianto (2010):
1. Banjir Bandang
Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut
berlangsung sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu
berkumpul dan mengalir dengan cepat di daerah-daerah dengan permukaan
rendah. Akibatnya, segala macam yang dilewatinya dikelilingi oleh air dengan
tiba-tiba. Banjir bandang terjadi begitu cepat sehingga setiap detik begitu sangat
berharga.
2. Banjir Sungai
Banjir sungai umumnya terjadi akibat curah hujan yang terjadi di daerah aliran
sungai (DAS) secara luas yang berlangsung cukup lama. Selanjutnya air hujan
yang tidak tertampung lagi di sungai meluap sehingga menimbulkan banjir dan
genangan di daerah sekitarnya. Banjir sungai umumnya akan menjadi banjir besar
secara perlahan, dan tergolong banjir musiman yang dapat berlanjut sampai
berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
3. Banjir Pantai
Banjir pantai adalah banjir yang terkait dengan terjadinya badai tropis. Air laut
membanjiri daratan akibat satu atau perpaduan dampak gelombang pasang, badai,
atau tsunami (gelombang pasang).
2.9 Sistem Peringatan Dini Banjir
Early warning system (EWS) atau Sistem Peringatan Dini merupakan
sebuah tatanan penyampaian informasi hasil prediksi terhadap sebuah ancaman
kepada masyarakat sebelum terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan
resiko. EWS bertujuan untuk memberikan peringatan agar penerima informasi
dapat segera siap siaga dan bertindak sesuai kondisi, situasi dan waktu yang tepat.
Prinsip utama dalam EWS adalah memberikan informasi cepat, akurat, tepat
sasaran, mudah diterima, mudah dipahami, terpercaya dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Pengendalian Banjir Dinas PU DKI Jakarta, informasi dari
petugas pemantau ketinggian air di hulu menempati poisisi yang sangat penting
Peringatan dini dikeluarkan sesaat sebelum terjadinya bencana banjir.
Selama ini, sistem peringatan dini banjir di Indonesia disampaikan berdasarkan
tahapan kondisi siaga yang didasarkan tinggi muka air di beberapa pos
pengamatan dan pintu air. Contohnya di DKI Jakarta, kondisi siaga ditentukan
berdasarkan tinggi muka air di pos Depok, Katulampa dan Manggarai. Berikut ini
contoh kondisi siaga di DKI Jakarta berdasarkan tinggi muka air dari ketiga pos
tersebut:
• Siaga IV : Kondisi normal dimana Katulampa <80 cm, Depok <200 cm dan Manggarai <750 cm
• Siaga III : Katulampa 80 cm, Depok 200 cm dan Manggarai 750 cm
• Siaga II : Katulampa 150 cm, Depok 270 cm dan Manggarai 850 cm
• Siaga I : Katulampa 200 cm, Depok 350 cm dan Manggarai 950 cm (Promise Indonesia, 2009)
2.10 Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi
Leopold dan Dunne (1978) dalam Sudadi et al. (1991) mengatakan secara
umum perubahan penggunaan lahan akan mengubah: (1) karakteristik aliran
sungai, (2) total aliran permukaan, (3) kualitas air dan (4) sifat hidrologi yang
bersangkutan. Alih fungsi lahan memberikan pengaruh terhadap perubahan debit
banjir melalui kemampuan tanah menyerap air hujan berdasarkan
penutupan/penggunaan lahannya (Yustina, 2007).
Berkurangnya kawasan bervegetasi dan meningkatnya area terbangun,
menyebabkan kecenderungan naiknya nilai koefisien run off, yang berkaitan erat
dengan meningkatnya debit maksimum sungai dan menurunnya debit minimum
sungai. Selanjutnya fenomena yang kerap terjadi adalah banjir di musim hujan
dan kekeringan di musim kemarau (Sarminingsih, 2007).
Kegiatan tataguna lahan yang bersifat mengubah bentang lahan dalam
suatu DAS seringkali dapat mempengaruhi hasil air (wateryield). Pada batas
tertentu, kegiatan tersebut juga dapat mempengaruhi kondisi kualitas air.
Pembalakan hutan, perubahan dari satu jenis vegetasi hutan menjadi jenis vegetasi
hutan lainnya, perladangan berpindah, atau perubahan tataguna lahan hutan
sering dijumpai di negara berkembang. Terjadinya perubahan tataguna lahan dan
jenis vegetasi tersebut, dalam skala besar dan bersifat permanen, dapat
mempengaruhi besar-kecilnya hasil air (Asdak, 2010).
Menurut Arsyad (2006), vegetasi mempengaruhi siklus hidrologi melalui
pengaruhnya terhadap air hujan yang jatuh dari atmosfir ke permukaan bumi, ke
tanah dan batuan di bawahnya. Pengaruh vegetasi terhadap aliran permukaan dan
erosi dapat dibagi dalam (1) intersepsi air hujan, (2) mengurangi kecepatan aliran
permukaan dan kekuatan perusak hujan dan aliran permukaan, (3) pengaruh akar,
bahan organik sisa-sisa tumbuhan yang jatuh dipermukaan tanah, dan
kegiatan-kegiatan biologi yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif dan
pengaruhnya terhadap stabilitas struktur porositas tanah, dan (4) transpirasi yang
III. METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Sub-DAS Ciliwung hulu, kegiatan analisis
dolakukan di laboratorium Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Fakultas
Pertanian IPB dan P4W LPPM IPB. Sub-DAS Ciliwung hulu merupakan wilayah
penelitian yang terletak pada koordinat geografis 6036’45” sampai 6 046’30”
Lintang Selatan 106048’45” sampai 107000’30”. Pengolahan citra dan analisis data
dilakukan di laboratorium Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Fakultas
Pertanian IPB dan P4W LPPM IPB. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan
Januari 2011 sampai Oktober 2011.
3.2 Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi :
1. Citra landsat tahun:
• Citra Landsat TM 1990, path/row: 122/65 (sumber: P4W LPPM IPB)
• Citra Landsat ETM 2001, path/row: 122/65 (sumber:
http://usgsglovis.gov)
• Citra Landsat ETM 2010, path/row: 122/65 (sumber:
http://usgsglovis.gov)
2. Data Curah hujan harian wilayah Sub DAS Ciliwung Hulu tahun
• 1990: stasiun katulampa (sumber BPSDA Ciliwung-Cisadane), stasiun Gunung Mas (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane) dan stasiun Citeko
(sumber BMKG Dramaga)
• 2001: stasiun katulampa (sumber BPSDA Ciliwung-Cisadane), stasiun
Gunung Mas (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane) dan stasiun Citeko
(sumber BPSDA Ciliwung Cisadane)
• 2010: stasiun katulampa (sumber BPSDA Ciliwung-Cisadane dan BMKG Dramaga), stasiun Gunung Mas (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane) dan
stasiun Citeko (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane dan BMKG
Dramaga)
3. Data debit harian dan debit banjir DAS Ciliwung (outlet Katulampa) tahun
1990, 2001 dan 2010 (sumber: Kantor Bendung Katulampa DAS Ciliwung).
4. Peta Tanah semi detail Daerah Aliran Sungai Ciliwung Hulu Propinsi Jawa
Barat Skala 1:50.000 Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 1992.
5. Data Lapangan berupa penggunaan lahan eksisting.
Alat yang digunakan
1. Software Arc GIS 9.3, Arc View, Mirosoft Exel, Microsoft word.
2. Laptop atau komputer.
3. GPS.
4. Kamera.
3.3 Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: (i) studi pustaka, (ii)
pengumpulan data, (iii) analisis data, (iv) interpretasi data atau hasil dan
pembahasan dan (v) tahap penulisan skripsi.
3.3.1 Stacking Image
Citra landsat yang didapatkan, masing-masing band masih dalam layer
yang berbeda sehingga perlu disatukan dalam satu layer. Stacking image adalah
image dan disimpan dalam file .img. Pada penelitian ini digunakan software
Arcview untuk melakukan stack image pada citra. Hal yang dilakukan untuk
melakukan stack image yaitu pertama add semua file landsat yang masih terpisah
satu-satu dengan format analysis data source, kemudian urutkan file pada layer
sesuai urutan bandnya dari terendah sampai tinggi. Aktifkan semua image citra
landsat. Setelah itu klik Image Analysis lalu klik stack image.
3.3.2 Koreksi Geometri
Terkadang citra yang didapatkan belum terkoreksi sehingga perlu
dikoreksi geometri agar posisi citra cocok dengan koordinat peta dunia yang
sesungguhnya. Ada beberapa cara dalam pengkoreksian, antara lain triangulasi,
polynomial, orthorektifikasi dengan menggunakan titik-titik kontrol lapangan
(ground control point), proyeksi peta ke peta, dan registrasi titik yang telah
diketahui (known point registration) (Supriatna dan Sukartono, 2002). Penelitian
ini menggunakan koreksi dengan cara menyiapkan citra satelit yang telah
terkoreksi di daerah yang sama dengan citra yang akan dikoreksi. Koreksi citra
berdasarkan citra satelit lain yang telah dikoreksi disebut image to image
3.3.3 Penajaman Citra
Penajaman citra (image enhancement) dilakukan untuk memperjelas
visualisasi citra agar dapat dilakukan interpretasi citra. Citra landsat yang terdiri
dari berbagai macam band dikombinasikan untuk menghasilkan visualisasi yang
jelas agar mudah diinterpretasi. Kombinasi band yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Red (5), Green (4) dan Blue (3). Kombinasi ini sangat tergantung pada
intrepeter, sesuai dengan kejelasan yang dapat dilihat dari masing-masing
interpreter. Untuk mengatur kombinasi band di Arc GIS 9.3 caranya klik dua kali
citra yang akan diatur pada layer kemudian pilih menu symbology lalu atur band
yang diinginkan.
3.3.4 Digitasi
Digitasi adalah kegiatan membatasi daerah-daerah yang memiliki
karakteristik unsur interpretasi yang berbeda yang menunjukkan perbedaan
penutupan lahan dari citra. Citra yang didigitasi adalah citra landsat tahun 1990,
layar komputer (digitasi onscreen). Proses digitasi ini menggunakan software Arc
GIS 9.3 dengan wilayah penelitian yang didapatkan dari peta tanah Sub DAS
Ciliwung Hulu sebagai poligon luar.
Prosesnya, masukan citra landsat satu titik tahun kemudian masukan
feature peta batas Sub DAS Ciliwung Hulu. Untuk melakukan pembatasan sesuai
dengan unsur-unsur interpretasi menggunakan cut poligon feature serta created
new feature sesuai kebutuhan. Peta penutupan lahan hasil digitasi satu tahun tetap
digunakan untuk mendigitasi penutupan lahan tahun lainnya sehingga tidak
memerlukan proses intersect.
3.3.5 Cek Lapang
Pengecekan lapang dilakukan untuk mengecek kebenaran hasil
interpretasi, terutama ditujukan pada obyek/daerah yang berbeda atau berubah dan
terdeteksi pada saat menginterpretasikan data. Pengecekan lapang dilakukan
selama 5 hari sebanyak 56 titik.Titik yang telah didapatkan kemudian di masukan
pada peta penutupan lahan tahun 2010 kemudian di cocokan kesesuaian
penutupan/penggunaan lahannya dengan kenyataan di lapang. Hasilnya, peta
penggunaan lahan existing tahun 2010.
3.3.6 Menghitung Luas Penutupan/Penggunaan Lahan dan Perubahannya.
Luas masing-masing penutupan/penggunaan lahan dihitung menggunakan
software Arc GIS 9.3. Untuk menghitung luas wilayah menggunakan calculate
geometry dengan property area. Secara otomatis field tersebut akan terisi dengan
luas dari masing-masing poligon penutupan/penggunaan lahan dengan satuan
meter, dengan syarat satuan koordinatnya dalam UTM (Universal Transfere
Mercator). Apabila luasnya ingin diubah menjadi hektar maka buat field baru dan
gunakan formula untuk menghitung.
Luas dalam field tersebut masih untuk per poligon. Untuk memperoleh
luas seluruh penutupan/penggunaan lahan untuk masing tipe dan
masing-masing tahun serta perubahan luas penutupan/penggunaan lahan perlu proses
lebih lanjut. Tabel atribut dalam Arc GIS di export ke Ms.Excel kemudian dalam
tabel, kemudian menghitung dengan excel luas perubahan penutupan/penggunaan
lahannya.
Perubahan luas (%) = {(TL i t1 – TL i t0) / TL i t0} x 100
TL i adalah Penutupan/penggunaan Lahan tahun ke i t0 adalah tahun awal analisis
t1 adalah tahun akhir analisis
3.3.7 Poligon Thiessen
Teknik poligon thiessen dilakukan dengan cara menghubungkan satu alat
penakar hujan dengan lainnya menggunakan garis lurus. Pada peta daerah
tangkapan air untuk masing-masing alat penakar hujan, daerah tangkapan tersebut
dibagi menjadi beberapa poligon (jarak garis pembagi dua penakar hujan yang
berdekatan lebih kurang sama).
Hasil pengukuran pada setiap alat penakar hujan terlebih dahulu diberi
bobot dengan menggunakan bagian-bagian wilayah dari total daerah tangkapan air
yang diwakili oleh alat penakar hujan masing-masing lokasi, kemudian
dijumlahkan. Curah hujan tahunan rata-rata di daerah tersebut diperoleh dari
persamaan berikut:
(R1 a1/A) + (R2 a2/A) + … + (Rn an/A)
Keterangan:
R1, R2, …, Rn = curah hujan untuk masing-masing wilayah a1, a2, ….., an = luas untuk masing-masing daerah poligon (ha) A adalah luas total daerah tangkapan air (ha)
(Asdak, 2010).
Pada penelitian ini, stasiun penakar hujan yang digunakan untuk menentukan curah hujan wilayah ada tiga yaitu Stasiun Katulampa, Stasiun
Gunung Mas dan Stasiun Citeko. Untuk mengetahui pembobotan curah hujan
pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan software arcgis, dengan cara
memasukan titik koordinat dari masing-masing stasiun kemudian diproses di
analysis tool --> poligon thiesseen. Berikut pembobotannya :
Tabel 3. Pembobotan Curah Hujan Poligon Thiessen
No Stasiun CH Pembobotan
1 Citeko 0.43
2 Katulampa 0.16
3.3.8 Banjir
Kejadian banjir pada tahun 1990, 2001 dan 2010 diketahui dari data debit
sungai pada outlet bendung Sub DAS Ciliwung Hulu di Katulampa serta pedoman
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Siaga Banjir yang digunakan oleh
DKI Jakarta sebagai karakteristik pedoman banjir. Dari pedoman SPD/EWS ini,
dapat ditentukan frekuensi serta kualitas banjir. Berikut ini status kondisi siaga di
DKI Jakarta berdasarkan tinggi muka air dari Pos Katulampa tersebut :
• Siaga IV : Kondisi normal dimana Katulampa <80 cm
• Siaga III : Katulampa 80 cm
• Siaga II : Katulampa 150 cm
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Kondisi Fisik Sub DAS Ciliwung Hulu
Berdasarkan Agus dan Hadihardja (2011) penentuan batas sub DAS pada
wilayah Ciliwung bagian hulu didasarkan pada bentang alam dan administrasi
adalah sebagai berikut luas DAS Ciliwung Bagian Hulu adalah 14.876 ha terbagi
kedalam 4 (empat) Sub DAS yaitu Sub DAS Ciesek seluas 2.452,78 ha, Sub DAS
Hulu Ciliwung seluas 4.593,03 ha, Sub DAS Cibogo Cisarua seluas 4.110,34 ha,
Sub DAS Ciseuseupan Cisukabirus seluas 3.719,85 ha.
DAS Ciliwung Bagian Hulu mempunyai curah hujan rata-rata sebesar
2929 – 4956 mm/ tahun. Perbedaan bulan basah dan kering sangat mencolok yaitu
10,9 Bulan Basah per tahun dan hanya 0,6 Bulan Kering per tahun.
Tipe iklim DAS Ciliwung Bagian Hulu menurut sistem klasifikasi Smith dan
Ferguson (1951) yang didasarkan pada besarnya curah hujan, yaitu Bulan Basah
(> 200 mm) dan Bulan Kering (< 100 mm) adalah termasuk ke dalam Tipe A.
4.1.1 Geologi dan Geomorfologi
Formasi batuan yang menutupi wilayah sekitar Bogor terdapat 4 satuan ,
yaitu bahan volkan, aluvial sungai, breksi bersusunan andesit dan bahan napal
(LPT 1986 dalam Aditya, 2007).
Jurusan Tanah IPB (1990) menyatakan bahwa kondisi geologi daerah
penelitian dapat dibagi atas 4 formasi geologi, yaitu formasi Qvu: terletak pada
bagian atas dari Sub DAS yang mempunyai lereng rata-rata di atas 40%. Formasi
ini merupakan endapan lahar, aliran lava, breksi gunung api, batu pasir tufa.
Formasi Qvba: terletak pada bagian atas Sub DAS, formasi ini merupakan aliran
basal dari Geger Bentang. Formasi Qvb: terdiri dari breksi gunung api, lahar.
Formasi Qv: Formasi ini terletak pada outlet dengan luasan yang kecil, merupakan
lempeng tufa, pasir tufa, konglomerat, dan endapan lahar.
Geomorfologi Sub DAS Ciliwung Hulu didominasi oleh dataran volkanik
tua dengan bentuk wilayah bergunung, hanya sebagian kecil yang merupakan
dataran alluvial. Geomorfologi daerah ini dibentuk oleh dua gunung api muda,
yaitu Gunung Salak (2.211 m) dan Gunung Gede Pangrango (3.019 m).
Gunung Limo, Gunung Kencana, dan Gunung Gendongan (Riyadi dalam
Janudianto 2004).
4.1.2 Tanah dan Topografi
Tanah-tanah yang terbentuk umumnya berasal dari bahan induk abu
volkan dan batuan piroklastik. Pada Peta Tanah Semidetil Tahun 1992 skala
1:50.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, jenis
tanah yang terdapat di Sub DAS Ciliwung Hulu meliputi order Andisol, Ultisol,
Inceptisol, dan Entisol yang masing-masing sebesar 38%, 11%, 48%, dan 2,1%
(Janudianto, 2004).
Keadaan topografi pada DAS Ciliwung Hulu didominasi kelas lereng
landai hingga agak curam. Kelas lereng yang ada pada wilayah ini disajikan pada
Tabel 4 (Ilma, 2006).
Tabel 4. Topografi DAS Ciliwung Hulu
Deskripsi Kelerengan
1 Datar 0-8%
2 Agak Landai 8-15%
3 Landai 15-30%
4 Agak Curam 30-45%
5 Curam 45-65%
6 Sangat Curam >65%
[image:37.595.107.506.87.822.2]V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Interpretasi Citra Landsat Tahun 1990, 2001 dan 2010
Interpretasi citra landsat dilakukan dengan melihat karakteristik dasar
kenampakan masing-masing penutupan/penggunaan lahan pada citra yang dibantu
dengan unsur-unsur interpretasi. Masing-masing penutupan/penggunaan lahan
memiliki karakteristik yang unik. Citra landsat dari masing-masing tahun
memiliki kualitas citra yang berbeda, sehingga kenampakan yang terlihat juga
berbeda.
Hutan Lebat menunjukkan bentuk dan pola yang tidak teratur dengan ukuran yang cukup luas. Berwarna hijau tua sampai gelap, tekstur relatif kasar,
ada bayangan igir-igir puncak gunung yang menunjukan sebaran hingga daerah
curam. Identik dengan letak di sekitar puncak gunung. Hutan Semak/Belukar
memiliki kenampakan bentuk dan pola yang hampir sama dengan hutan lebat.
Berwarna hijau agak terang dibandingkan hutan lebat, tekstur lebih halus dari
hutan lebat. Umumnya dijumpai di perbatasan antara hutan lebat dan lahan
budidaya (kebun teh, kebun campuran atau tegalan).
Kebun Teh memiliki kenampakan bentuk dan pola yang lebih teratur, berwarna hijau muda campur ungu dan merah muda halus. Dengan tekstur relatif
halus dan seragam pada lereng-lereng yang relatif landai hingga curam. Kebun Campuran memiliki kenampakan tekstur yang relatif agak kasar berwarna hijau agak gelap bercampur magenta atau ungu. Bentuk dan pola relatif kurang teratur
dan menyebar. Biasanya berbatasan dengan tegalan, sawah, pemukiman dan hutan
lebat.
Pemukiman menunjukan bentuk petak-petak dengan pola menyebar di sepanjang jalan utama. Berwarna magenta, ungu kemerahan dengan tekstur relatif
agak kasar sampai kasar. Sawah mempunyai warna hijau agak gelap bercampur biru tua, ungu tua, hijau tua atau magenta dengan tekstur relatif kasar. Bentuknya
berpetak-petak, polanya menyebar di daerah dataran dengan lereng landai.
Tegalan menunjukan warna hijau terang bercampur kuning terang dan magenta dengan tekstur agak kasar. Bentuk tegalan berpetak-petak, pola sebaran seperti
Citra landsat dari masing-masing tahun memiliki kenampakan yang sedikit
berbeda, namun secara umum masih banyak kesamaan. Perbedaan penampakan
citra masing-masing tahun untuk setiap penutupan lahan terlihat pada perbedaan
rona citra. Tingkat kecerahan dari ketiga citra yaitu 1990, 2010 kemudian 2001.
Namun secara keseluruhan citra tahun 2010 memiliki kualitas gambar yang lebih
baik dari dua citra landsat lainnya. Penampakan penutupan lahan dari
masing-masing citra dapat dilihat dalam Tabel Lampiran 1. Foto penggunaan lahan
existing terdapat pada Tabel Lampiran 2.
5.2 Pola Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan
Pola penutupan/penggunaan lahan wilayah sub DAS Ciliwung Hulu tahun
1990, 2001 dan 2010 masing-masing disajikan pada lampiran 1, 2 dan 3.
Berdasarkan peta tersebut, daerah penelitian memiliki luas 15.057 hektar dengan 7
tipe penutupan/penggunaan lahan yaitu hutan lebat, hutan semak/belukar, kebun
camapuran, kebun teh, pemukiman, sawah dan tegalan. Luas masing-masing tipe
penutupan/penggunaan lahan untuk masing-masing tahun tersaji dalam Tabel 5 .
Perlu diketahui sebelumnya bahwa terdapat perbedaan makna dari
penutupan dan penggunaan lahan. Berdasarkan Liliesand Kiefer (1997) istilah
penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan
bumi. Istilah penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang
lahan tertentu. Dalam artikel Beni Raharjo mengutip Townshend dan Justice pada
tahun 1981 penutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi,
benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa
memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Peta yang dihasilkan
dari analisis citra pada tahun 1990 dan 2001 merupakan peta penutupan lahan
dikarenakan tidak terdapat data lapangan mengenai penggunaan lahan sebenarnya Tabel 5. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan 2010
Luas (ha) % Peringkat Luas (ha) % Peringkat Luas (ha) % Peringkat
Hutan Lebat 4300.4 28.6 1 4077.8 27.1 1 3946.0 26.2 1
Hutan Semak/Belukar 2125.1 14.1 4 1765.5 11.7 4 1370.1 9.1 6
Kebun Campuran 2411.1 16.0 2 2130.2 14.1 3 1833.0 12.2 5
Kebun Teh 2378.7 15.8 3 2469.2 16.4 2 2514.8 16.7 2
Pemukiman 883.3 5.9 7 1521.4 10.1 6 2170.6 14.4 3
Sawah 1563.8 10.4 5 1454.9 9.7 7 1227.0 8.1 7
Tegalan 1394.8 9.3 6 1638.2 10.9 5 1995.6 13.3 4
2010 Penutupan/Penggunaan
pada tahun tersebut. Namun peta hasil analisis citra pada tahun 2010 merupakan
peta penggunaan lahan karena dilakukan pengecekan lapang terhadap penggunaan
lahan sesungguhnya pada tahun yang berdekatan.
Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa penutupan pada tahun 1990 masih
didominasi berturut-turut oleh hutan lebat, kemudian kebun campuran dan kebun
teh. Masing-masing memiliki luas wilayah sebesar 4300,4 ha, 2411,1 ha dan
2378,7 ha. Dengan persentase untuk masing-masing dari seluruh wilayah
penelitian yaitu 28,6%, 16% dan 15,8%. Penutupan/penggunaan lahan lainnya
yaitu hutan semak (2125,1 ha dengan persentase 14,1%), sawah (1563,8 ha dan
persentase 10,4 %), tegalan (1394,8 ha dan persentase 9,3%) dan pemukiman
(883,3 ha dan persentase 5,9%).
Untuk tahun 2001 tutupan lahan didominasi secara berturut-turut oleh
hutan lebat dengan luas area dan persentase sebesar 4077,8 ha dan 27,1%,
kemudian kebun teh dengan luas area dan persentase sebesar 2469,2 ha dan 16,4%
dan kebun campuran dengan luas area dan persentase sebesar 2130,2 dan 14,1%.
Untuk penutupan lahan lainnya yaitu hutan semak/belukar (1765,5 ha dan
persentase 11,7%), tegalan (1638 ha dan persentase 10,9%), pemukiman (1521 ha
dan persentase 10,1%) dan sawah (1454,9 ha dan persentase 9,7%).
Penggunaan lahan tahun 2010 menunjukkan pola yang agak berbeda
dengan dua tahun yang lain yaitu hutan lebat menjadi dominasi utama dengan luas
area dan persentase sebesar 3946,0 ha dan 26,2%, kemudian kebun teh dengan
luas area dan persentase 2514,8 ha dan 16,7% lalu pemukiman dengan luas area
2170,6 ha dan persentase 14,4%. Pola penutupan/penggunaan lahan lainnya yaitu
tegalan (1995,6 ha dan persentase 13,3%), kebun campuran (1833 ha dan
persentase 12,2%), hutan semak/belukar (1370,1 ha dan persentase 9,1%) dan
sawah (1227 ha dan 8,1%).
Dari pola penutupan/penggunaan lahan masing-masing tahun dapat dilihat
bahwa tipe penutupan/penggunaan lahan yang mengalami perubahan pesat adalah
pemukiman dari peringkat terakhir di tahun 1990 kemudian naik satu peringkat di
tahun 2001 dan naik tiga peringkat di tahun 2010 menjadi peringkat ke tiga.
Penutupan/penggunaan lahan lain yang mengalami peningkatan yang tinggi
penutupan/penggunaan lahan yang mengalami penurunan yaitu kebun campuran,
sawah dan hutan semak/belukar. Penutupan/penggunaan lahan yang cenderung
tetap adalah hutan lebat dan kebun teh.
Persentase proporsi penutupan/penggunaan lahan dalam wilayah penelitian
yang terjadi dari tahun 1990, 2001 dan 2010 menunjukkan bahwa pemukiman
mengalami peningkatan tertinggi yaitu dari tahun 1990 sebesar 5,9% kemudian
tahun 2001 sebesar 10,1% dan tahun 2010 sebesar 14,4%. Tegalan juga
mengalami peningkatan yaitu di tahun 1990 sebesar 9,3%, tahun 2001 sebesar
10,9% dan tahun 2010 sebesar 13,3%. Penutupan/penggunaan lahan yang
mengalami penurunan persentase tertinggi adalah hutan semak/belukar yaitu di
tahun 1990 persentasenya adalah 14,1%, tahun 2001 sebesar 11,7% dan tahun
2010 sebesar 9,1%. Kemudian kebun campuran pada tahun 1990 adalah 16%,
tahun 2001 14,1 dan 2010 12,2%. Penutupan/penggunaan lahan lain yang
mengalami penurunan persentase lainnya adalah sawah yaitu 10,4 pada tahun
1990, 9,7% tahun 2001% dan 8,1% tahun 2010.
5.3 Perubahan Penutupan Penggunaan Lahan
Gambar 3 merupakan grafik yang menggambarkan luas masing-masing
tipe penutupan/penggunaan lahan tahun 1990, 2001 dan 2010. Dari grafik tersebut
diketahui bahwa penutupan/penggunaan lahan yang mengalami penurunan luasan
area pada dua periode tahun yaitu hutan semak/belukar, kebun campuran, hutan
lebat dan sawah. Sedangkan penutupan/penggunaan lahan yang mengalami
[image:41.595.110.492.558.733.2]kenaikan luasan area yaitu kebun teh, pemukiman, dan tegalan.
Dari Grafik 4 dan Tabel 6 dapat diketahui bahwa pertambahan luas area
tertinggi terdapat pada lahan pemukiman baik pada periode tahun 1990-2001
(638,1 ha dengan persentase 72,2% dari penutupan/penggunaan lahan pemukiman
sebelumnya) dan periode tahun 2001-2010 (649,1 ha dengan persentase 42,7%
dari penutupan/penggunaan lahan pemukiman sebelumnya).
Untuk periode tahun 1990-2001 luas penutupan/penggunaan lahan lain
yang bertambah adalah tegalan (243,4 ha dengan persentase pertambahan 17,5%)
kemudian kebun teh (90,4 ha dengan persentase kenaikan 3,8%). Pada periode
tahun 2001 – 2010 luas penutupan/penggunaan lahan yang bertambah adalah
tegalan (357.4 ha dengan persentase pertambahan 21.8 %) dan kebun teh (45.6 ha
dengan persentase kenaikan 1.8%).
Sedangkan tipe penutupan/penggunaan lahan yang berkurang luasannya
pada periode 1990-2001 adalah hutan semak/belukar (-359,6 ha dengan persentase
penurunan -16,9%) , kebun campuran (-280,9 ha dengan persentase penurunan Tabel 6. Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan
2010
Gambar 4. Grafik Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990, 2001 dan 2010
1990 2001 2010 ha % ha %
Hutan Lebat 4300.4 4077.8 3946.0 -222.6 -5.2 -131.8 -3.2 Hutan Semak/Belukar 2125.1 1765.5 1370.1 -359.6 -16.9 -395.3 -22.4 Kebun Campuran 2411.1 2130.2 1833.0 -280.9 -11.7 -297.1 -13.9 Kebun Teh 2378.7 2469.2 2514.8 90.4 3.8 45.6 1.8 Pemukiman 883.3 1521.4 2170.6 638.1 72.2 649.1 42.7 Sawah 1563.8 1454.9 1227.0 -108.8 -7.0 -227.9 -15.7 Tegalan 1394.8 1638.2 1995.6 243.4 17.5 357.4 21.8
Penutupan/Penggunaan Lahan
Luas (ha) Luas Perubahan
luas -11,7%), hutan lebat (-222,6 ha dengan persentase penurunan -5,2 %) dan
sawah (-108,8 ha dengan persentase penurunan -7,0%). Tipe
penutupan/penggunaan lahan yang mengalami penurunan luasan untuk periode
2001-2010 adalah hutan semak/belukar (-395,3 ha dengan persentase penurunan
-22,4%), kebun campuran (-297,1 ha dengan persentase penurunan -13,9%),
sawah (-227,9 ha dengan persentase penurunan -15,7%) dan hutan lebat (-131,8
ha dengan persentase penurunan -3,2%).
Hal penting yang perlu diketahui dari pola perubahan
penutupan/penggunaan lahan adalah perubahan yang terjadi dari jenis tertentu
menjadi jenis yang lain. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7
dan 8. Pada periode tahun 1990-2001, pengurangan luas penutupan/penggunaan
lahan terbesar adalah hutan semak/belukar yang terkonversi menjadi kebun teh
(180,1 ha), tegalan (54,2 ha), sawah (37,3 ha) dan pemukiman (37,0 ha).
Kemudian kebun campuran yang terkonversi menjadi tegalan (411,3 ha),
pemukiman (127,8 ha), sawah (65,7 ha) dan kebun teh (26,6 ha) Hutan lebat
[image:43.595.102.512.155.796.2]banyak terkonversi menjadi kebun teh (104,7 ha), tegalan (21,1 ha), sawah (1,9 Tabel 7. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 1990-2001
Tabel 8. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 2001-2010
Hutan Lebat 4077.8 89.7 5.2 104.7 0.0 1.9 21.1 4300.4
Hutan Semak/Belukar 0.0 1675.8 140.7 180.1 37.0 37.3 54.2 2125.1
Kebun Campuran 0.0 0.0 1779.7 26.6 127.8 65.7 411.3 2411.1
Kebun Teh 0.0 0.0 125.1 2155.1 26.0 46.9 25.7 2378.7
Pemukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 883.3 0.0 0.0 883.3
Sawah 0.0 0.0 13.3 2.8 208.5 1242.7 96.6 1563.8
Tegalan 0.0 0.0 66.1 0.0 238.8 60.4 1029.4 1394.8
Grand Total 4077.8 1765.5 2130.2 2469.2 1521.4 1454.9 1638.2 15057.2
Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990(ha)
Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 2001(ha) Hutan Lebat Hutan Semak/Belukar Kebun Campuran Kebun Teh Pemukim
an Sawah Tegalan
Grand Total
Hutan Lebat 3946.0 64.9 0.0 61.2 0.0 0.9 4.9 4077.8
Hutan Semak/Belukar 0.0 1305.3 22.8 107.1 77.0 144.9 108.4 1765.5
Kebun Campuran 0.0 0.0 1538.1 39.3 176.2 47.1 329.5 2130.2
Kebun Teh 0.0 0.0 16.4 2275.9 35.8 11.2 129.9 2469.2
Pemukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 1521.4 0.0 0.0 1521.4
Sawah 0.0 0.0 78.2 11.1 231.3 921.5 212.8 1454.9
Tegalan 0.0 0.0 177.7 20.2 128.9 101.4 1210.0 1638.2
Grand Total 3946.0 1370.1 1833.0 2514.8 2170.6 1227.0 1995.6 15057.2
Penutupan/Penggunaan
Lahan tahun 2001(ha) Kebun
Campuran
Kebun Teh
Pemukim
an Sawah Tegalan
ha) dan kebun campuran (5,2 ha). Terakhir sawah yang terkonversi menjadi
pemukiman (208,5 ha), tegalan (96,6 ha), kebun campuran (13,3 ha) dan kebun
teh (2,8 ha).
Dari Tabel 7 dan 8, juga dapat diketahui pertambahan luas tipe
penutupan/penggunaan lahan tertentu adalah hasil konversi dari
penutupan/penggunaan lahan yang lain. Pertambahan luas penutupan/penggunaan
lahan yang tertinggi pada periode tahun 1990-2001 adalah pemukiman hasil
konversi dari tegalan (238,8 ha), sawah (208,5 ha), kebun campuran (127,8 ha)
dan kebun teh (26,6 ha). Kemudian tegalan adalah hasil konversi dari kebun
campuran (411,3 ha), sawah (96,6 ha), hutan semak/belukar (54,2 ha), kebun teh
(25,7 ha) dan hutan lebat (21,1 ha). Kebun teh adalah hasil konversi dari
penutupan/penggunaan lahan hutan semak/belukar (180,1 ha), hutan lebat (104,7
ha), kebun campuran (26,6 ha), dan sawah (2,8 ha).
Pada periode tahun 2001-2010, pengurangan luas penutupan/penggunaan
lahan terbesar adalah hutan semak belukar yang terkonversi menjadi sawah (144,9
ha), tegalan (108,4 ha), kebun teh (107,1 ha), pemukiman (77,0 ha) dan kebun
campuran (22,8 ha). Kebun campuran terkonversi menjadi jenis
penutupan/penggunaan lahan tegalan (329,5 ha), pemukiman (176,2 ha), sawah
(47,1 ha) dan kebun teh (39,3 ha). Hutan lebat terkonversi menjadi kebun teh
(61,2 ha), hutan semak/belukar (64,9 ha), tegalan (4,9 ha) dan sawah (0,9 ha).
Sawah terkonversi menjadi pemukiman (231,3 ha), tegalan (212,8 ha), kebun
campuran 78,2 ha dan kebun teh (11,1 ha).
Pertambahan luas penutupan/penggunaan lahan periode tahun 2001-2010
yang tertinggi adalah pemukiman merupakan hasil konversi dari lahan sawah
(231,3 ha), kebun campuran (176,2 ha), tegalan (128,9 ha), hutan semak/belukar
(77 ha) dan kebun teh (35,8 ha). Kebun teh merupakan hasil konversi tipe
penutupan/penggunaan lahan hutan semak/belukar (107,1 ha), hutan lebat (61,2
ha), kebun campuran (39,3 ha), tegalan (20,2 ha), dan sawah (11,1 ha). Tegalan
konversi dari kebun campuran (329,5 ha), sawah (212,8 ha), kebun teh (129,9 ha),
Perubahan tipe penutupan/penggunaan lahan yang dominan dapat dilihat pada Tabel 9 untuk tahun 1990-2001 dan Tabel 10 untuk tahun 2001-2010.
Perubahan penutupan/penggunaan lahan dominan tahun 1990-2001 yaitu kebun
campuran menjadi tegalan dengan luas perubahan 411,3 ha dan persentase dari
luas total perubahan sebesar 18,6%. Kemudian tegalan menjadi pemukiman
dengan luas perubahan 238,8 ha dan persentase dari total luas perubahan sebesar
[image:45.595.106.502.84.842.2] [image:45.595.109.497.119.344.2]10,8% serta sawah menjadi pemukiman sebesar 208,5 ha dan persentase dari total Tabel 9. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun
1990-2001
Tabel 10. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun 2001-2010
1 Kebun Campuran-->Tegalan 411.3 18.6
2 Tegalan-->Pemukiman 238.8 10.8
3 Sawah-->Pemukiman 208.5 9.4
4 Hutan Semak/Belukar-->Kebun Teh 180.1 8.1 5 Hutan Semak/Belukar-->Kebun Campuran 140.7 6.4
6 Kebun Campuran-->Pemukiman 127.8 5.8
7 Kebun Teh-->Kebun Campuran 125.1 5.7
8 Hutan Lebat-->Kebun Teh 104.7 4.7
9 Sawah-->Tegalan 96.6 4.4
10 Hutan Lebat-->Hutan Semak/Belukar 89.7 4.1
11 Lainnya 490.2 22.1
2213.33 100.0 Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan
tahun 1990-2001
Total
Luas (ha) No
%
1 Kebun Campuran-->Tegalan 329.5 14.1
2 Sawah-->Pemukiman 231.3 9.9
3 Sawah-->Tegalan 212.8 9.1
4 Tegalan-->Kebun Campuran 177.7 7.6
5 Kebun Campuran-->Pemukiman 176.2 7.5
6 Hutan Semak/Belukar-->Sawah 144.9 6.2
7 Kebun Teh-->Tegalan 129.9 5.6
8 Tegal