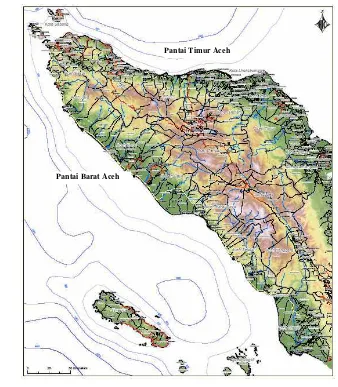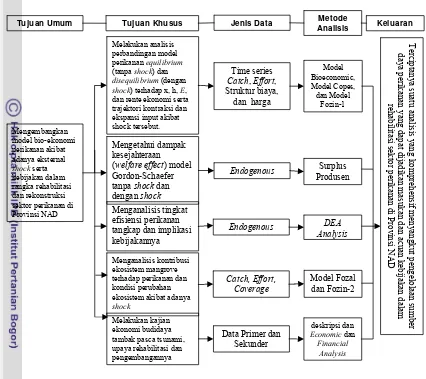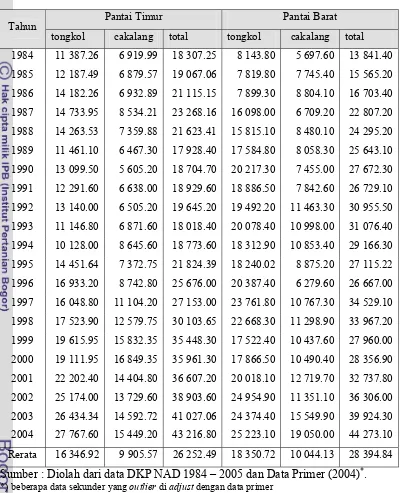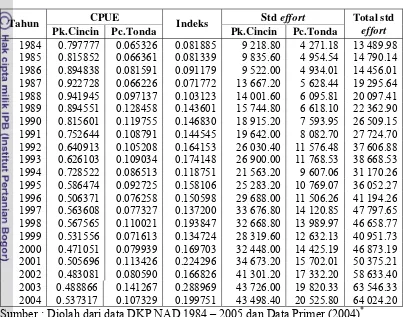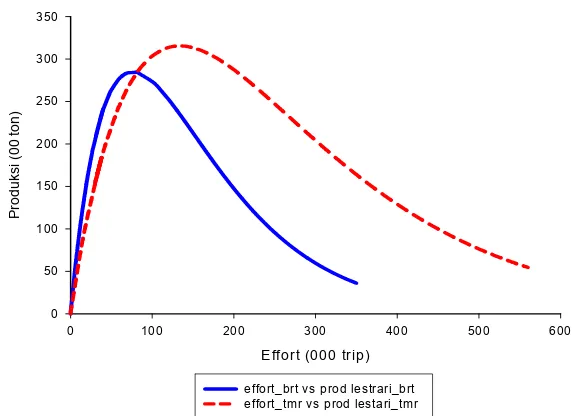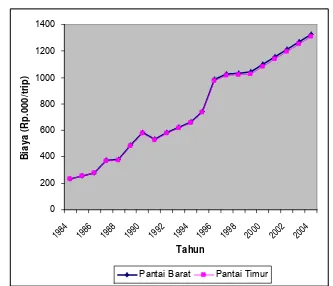1.1. Latar Belakang
Sektor perikanan dan kelautan diharapkan menjadi prime mover bagi pemulihan ekonomi Indonesia, karena prospek pasar komoditas perikanan dan
kelautan ini terus meningkat dan Indonesia dikenal memiliki sumber daya pesisir
dan lautan yang cukup melimpah, seperti: mangrove, terumbu karang, padang
lamun, dan estuaria yang menghasilkan sumber daya ikan dan biota lainnya,
migas, mineral, dan jasa-jasa lingkungan. Indonesia mempunyai banyak perairan,
teluk, dan pulau kecil yang relatif tenang dan bersih, lebih dari 12 genera hutan
mangrove (diperkirakan luas areal mangrove di Indonesia 2.25 – 4.45 juta ha), 70
genus terumbu karang yang tersebar dalam hamparan seluas 85.000 km2 (terluas di dunia), dan padang lamun yang cukup luas, walaupun sebagian dari sumber
daya di atas berada dalam kondisi rusak akibat campur tangan manusia.
Indonesia mempunyai panjang garis pantai 81 000 km (14 persen dari
total garis pantai bumi dan merupakan garis pantai kedua di dunia terpanjang
setelah Kanada), perairan darat 0.55 juta km2, luas laut 5.8 juta km2, potensi (ikan) lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY) 6.4 juta ton/tahun, jumlah tangkapan (tahun 2001) 4.0 juta ton, artinya masih punya peluang untuk
meningkatkan produksi 1.12 – 2.40 juta ton/tahun. Indonesia juga mempunyai 141
820 ha perairan umum dengan potensi produksi 356 020 ton ikan/tahun (Dahuri
2002).
Untuk perikanan budidaya, Indonesia mempunyai potensi luas budidaya
laut (marikultur) lebih dari 2 juta ha, yang dapat dibudidaya ikan kakap, kerapu,
tiram, kepiting, teripang, dan lain-lain dengan potensi produksi mencapai ± 46.73
juta ton/tahun. Disamping itu, Indonesia juga potensi lahan tambak 866 550 ha
yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 40 persen. Menurut Dahuri (2002),
jika dari luas potensi tambak tersebut dapat dimanfaatkan 500.000 ha saja dengan
produksi rata-rata 2 ton/ha/tahun, maka Indonesia akan menghasilkan udang 1 juta
ton/tahun, dan jika nilai ekspor udang US$ 2/kg, maka akan menghasilkan devisa
Melimpahnya sumber daya di kawasan pesisir seperti disebutkan di atas,
tidak tercermin pada penerimaan PDB dan keadaan sosial ekonomi masyarakat
pesisir (nelayan) yang berkaitan langsung dengan sumber daya tersebut.
Kenyata-an menunjukkKenyata-an bahwa lebih dari 80 persen masyarakat pesisir masih tergolong
miskin (BPS 1998). Paradoks kemiskinan nelayan Indonesia identik dengan apa
yang pernah diucapkan Peter Pearse, seorang ekonom Kanada, ketika melihat
kenyataan pahit nelayan di pantai timur Kanada yang terbelenggu oleh
kemis-kinan di tengah melimpahnya sumber daya perikanan di daerah tersebut. Kondisi
yang sama dialami oleh nelayan Indonesia. Sebuah ironi kehidupan masyarakat
pesisir, yaitu miskin di tengah kekayaan potensi sumber daya perikanan yang ada
di sekitarnya. Berbagai pertanyaan kemudian muncul mengapa hal ini bisa
terjadi?. Apakah ini semata-mata karena natural resource curse? (kutukan sumber daya alam), yakni suatu fenomena dimana wilayah dengan sumber daya alam
yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada
akhirnya menyebabkan kemiskinan bagi penduduknya? (Fauzi 2003).
Dari sisi penerimaan, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional
pada Tahun 1998 sebesar 20.06 persen dan kontribusi sektor perikanan saja hanya
2.16 persen dengan nilai ekspor US$ 1.76 milyar jauh lebih kecil dibanding
negara Irlandia, Norwegia, Cina dan Jepang dengan kontribusi sektor perikanan
terhadap PDB masing-masing sebesar 65%, 25%, 48%, dan 54% (Dahuri 2002).
Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 km mempunyai nilai ekspor
perikanan US$ 4.2 milyar dan dengan luas lahan tambak 80 000 ha menghasilkan
300 000 ton udang pada Tahun 2000, pada periode yang sama Indonesia dengan
luas lahan tambak 344 759 ha hanya menghasilkan 120 000 ton udang.
Ketidaksesuaian antara kelimpahan sumber daya dan kondisi sosial
ekonomi masyarakat, pada tingkat regional juga terjadi di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD). Aceh juga dikenal mempunyai sumber daya pesisir dan
lautan yang melimpah. Terdapat 17 Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan
pantai, panjang garis pantai 2 467 km (Medrilzam et al. 2005), potensi lestari (MSY) di Pantai Barat 366 260 ton/tahun dan Pantai Timur 127 670 ton/tahun
(PT. Oxalis Subur 2006). Luas areal budidaya 43 173.5 ha, yang terdiri dari
budidaya 30 572.9 ton dengan nilai 637 milyar (DKP 2004b). Disamping itu,
Aceh juga mempunyai sumber daya budidaya laut yang cukup baik, terumbu
karang, ekosistem mangrove, dan lain-lain. Dari tahun 70-an, Aceh dikenal
dengan keunggulan udang windu dan udang putih yang diekspor ke Eropah
sebagai udang pealed (sudah dikupas kulitnya) untuk dihidangkan sebagai shrimp cocktail (FP Unsyiah 2000).
Kekayaan sumber daya alam di atas masih belum mampu mengangkat
harkat masyarakat Aceh. Tahun 1996 persentase orang miskin di NAD 10.79
persen dan tahun 2000 meningkat menjadi 26.50 persen, lebih tinggi dari rata-rata
nasional pada periode yang sama, yaitu 16.07 persen (Abidin 2004). Pada Tahun
2004, jumlah penduduk NAD 4.2 juta orang dan diperkirakan jumlah penduduk
miskin mencapai 40 persen, sekitar 1.7 juta orang (Nazamuddin 2004), dan
sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di kawasan pesisir adalah
tergolong miskin, karenanya hampir seluruh desa di kawasan pesisir termasuk
desa tertinggal. Sebelum tsunami, penduduk miskin di Aceh mencapai 29% dari
jumlah penduduk dan merupakan provinsi ke-4 termiskin di Indonesia dan setelah
tsunami penduduk miskin meningkat menjadi 36%, daerah termiskin ke di
Indonesia (Word Bank 2006).
Akibat gempa bumi dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004,
telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada sektor perikanan di Provinsi
NAD. Diperkirakan sekitar 1000 km garis pantai tersapu tsunami, hampir setara
dengan jarak Jakarta – Surabaya jalan darat (Mangkusubroto 2006), 17 552
nelayan hilang/tewas atau 22.8% dari total nelayan di NAD yang berjumlah 76
970 orang pada tahun 2004 (DKP 2005a), 11 124 armada hilang/rusak (FAO
2005a), 38 PPI rusak/hilang (Meldrilzam et al. 2005), 20 429 ha tambak rusak atau 42.9% dari total luas tambak di NAD 47 621 ha dan paling kurang 40 000
pembudidaya tambak kehilangan pekerjaan (FAO 2005b), 105 260 ha hutan
mangrove rusak (Dephut 2005, diacu dalam Meldrilzam et al. 2005).
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sedang dilakukan di Provinsi NAD,
namun sejauh ini belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu penyebabnya
adalah informasi dan data yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan
untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang keragaan (performance) sumber daya perikanan tangkap dan budidaya (tambak) di Provinsi NAD.
Keragaan sumber daya ini penting diketahui karena akan menentukan konsep dan
strategi kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para
stakeholder khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya di lokasi penelitian. Yang diharapkan adalah setiap kegiatan pembangunan dalam zona
pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai,
sehingga membentuk suatu mozaik yang harmonis. Untuk pemanfaatan sumber
daya yang dapat pulih (renewable resources), laju ekstraksinya tidak boleh melebihi kemampuannya untuk memulihkan diri pada suatu periode tertentu,
sedangkan pemanfaatan sumber daya pesisir yang tak dapat pulih (non-renewable resources) harus dilakukan dengan cermat sehingga efeknya tidak merusak lingkungan sekitarnya.
1.2. Perumusan Masalah
Seperti telah disebutkan di atas, Provinsi NAD memiliki potensi produksi
perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang cukup tinggi. Namun
tingginya potensi ini tidak tercermin dari kondisi sosial ekonomi masyarakat
pesisir, khususnya para nelayan. Hampir semua desa nelayan di Indonesia dan
juga di NAD tergolong dalam desa tertinggal dan berpenduduk miskin.
Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya produktivitas di sektor
perikanan, antara lain adalah : (1) kapasitas (stok) sumber daya ikan yang telah
menurun di beberapa daerah penangkapan ikan, (2) sumber ekonomi perikanan
mengalami terdistorsi, dimana beberapa produk perikanan memiliki pasar
monopsoni sedangkan inputnya bersifat monopolistik, (3) kualitas sumber daya
manusia di sektor perikanan relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya,
(4) eksploitasi perikanan di beberapa daerah telah melebihi kapasitas sumber
dayanya, (5) di beberapa daerah penangkapan, diduga telah terjadi degradasi dan
depresiasi sumber daya ikan, (6) belum terintegrasi pengembangan wilayah pesisir
dengan pembangunan sektor perikanan.
menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya open access. Tidak seperti sumber daya alam lainnya, seperti pertanian dan peternakan yang sifat
kepemilikannya jelas, sumber daya ikan relatif bersifat terbuka. Siapa saja bisa
berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Gordon menyatakan
bahwa tangkap lebih secara ekonomi (economic overfishing) akan terjadi pada perikanan yang tidak terkontrol ini. Menurut beberapa hasil penelitian, di Selat
Malaka dan Laut Jawa telah terjadi tangkap lebih, biological overfishing. Namun, yang umum terjadi di Indonesia, termasuk di NAD, adalah economical overfishing
yang ditandai dengan tingginya penggunaan input, tetapi tidak dibarengi dengan
peningkatan output dan returns secara proporsional.
Gordon memulai analisisnya berdasarkan asumsi konsep produksi biologi
kuadratik yang dikembangkan oleh Verhulst pada tahun 1883 yang kemudian
diterapkan dalam bidang perikanan oleh Schaefer pada tahun 1957. Dari sinilah
teori Schaefer kemudian dikenal. Secara eksplisit model
Gordon-Schaefer (GS) menjelaskan bahwa dalam kondisi pengelolaan yang bersifat
terbuka (open access), keseimbangan akan tercapai pada tingkat upaya E∞, dimana penerimaan total (TR) sama dengan biaya total (TC). Dalam hal ini pelaku
perikanan sudah tidak menerima rente ekonomi sumber daya (manfaat ekonomi),
karena seluruh rente ekonomi telah terkuras habis (driven to zero) sehingga tidak lagi intensif untuk masuk (entry) dan keluar (exit) serta tidak ada perubahan pada tingkat upaya yang sudah ada. Tingkat upaya pada posisi ini adalah upaya dalam
kondisi keseimbangan yang oleh Gordon disebut sebagai “Bioeconomic Equilibrium of Open Access Fishery” atau keseimbangan bionomik dalam kondisi akses terbuka (Fauzi 2004).
Keuntungan lestari yang maksimum diperoleh pada tingkat upaya dimana
yang lebih produktif. Hal inilah inti prediksi Gordon bahwa perikanan yang open access akan menimbulkan kondisi economicoverfishing.
Model GS seperti dijelaskan di atas mengasumsikan sumber daya dalam
kondisi keseimbangan (equilibrium). Namun, dalam kenyataannya kondisi sumber daya tidak selalu equilibrium. Dengan faktor “shock” (seperti tsunami) dapat menyebabkan sumber daya tidak seimbang (disequilibrium). Disamping itu, model GS hanya melihat perikanan dalam suatu perairan. Pada kenyataannya
kondisi perairan dipengaruhi oleh ekosistem pantai, seperti hutan mangrove, yang
berfungsi selain sebagai tempat pemijahan (spawning ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan tempat berlindung beberapa biota laut (termasuk ikan) juga dengan produksi serasah (bahan organik) dapat menyuburkan perairan
sehingga akan mempengaruhi tingkat populasi ikan (tingkat biomas) di perairan
tersebut.
Pertanyaan umum yang muncul dari bahasan di atas adalah bagaimana
model Gordon-Schaefer (GS) melihat kondisi perikanan yang mengalami
“shock”?. Beberapa pertanyaan yang dapat diturunkan secara khusus adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perbandingan model perikanan equilibrium (tanpa shock) dan
disequilibrium (dengan shock) terhadap biomas, hasil tangkapan, effort, dan rente ekonomi serta trajektori kontraksi dan ekspansi input akibat adanya
shock tersebut?
2. Bagaimana dampak kesejahteraan (welfare effect) model Gordon-Schaefer tanpa shock dan dengan shock?
3. Apakah pengelolaan perikanan tangkap di daerah penelitian sudah efisien?
4. Bagaimana kontribusi ekosistem mangrove terhadap perikanan dan kondisi
perubahan ekosistem akibat adanya shock?
5. Bagaimana keragaan perikanan budidaya (tambak), permasalahan, strategi
rehabilitasi dan pengembangannya di daerah penelitian serta apakah perikanan
budidaya tersebut dapat menjadi substitusi dan komplementer ketika
perikanan tangkap mengalami shock?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka dibuat alur pemikiran yang
Gambar 1. Kerangka pemikiran
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model
bio-ekonomi perikanan akibat adanya eksternal shock serta kebijakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan di Provinsi NAD yang harmonis,
lestari, dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat di daerah
penelitian.
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :
1. Melakukan analisis perbandingan model perikanan equilibrium (tanpa shock) dan disequilibrium (dengan shock) terhadap biomas, hasil tangkapan, effort, dan rente ekonomi serta trajektori kontraksi dan ekspansi input akibat adanya
shock tersebut.
2. Mengetahui dampak kesejahteraan (welfare effect) model Gordon-Schaefer tanpa shock dan dengan shock.
3. Menganalisis tingkat efisiensi perikanan tangkap dan implikasi kebijakannya.
Equilibrium Disequilibrium
TSUNAMI
Input
Teori Gordon-Schaefer (GS)
Output Gordon Schaefer
Equilibrium
Output Baru Gordon-Schaefer
Disequilibrium
Rehabilitasi Rekonstruksi
Kebijakan Analisis
Comparative
Model Copes Analisis Degradasi dan
Depresiasi
Analisis DEA
Interaksi Mangrove-Sumber
Daya Ikan
Input ??
Output ?? Mangrove
Tambak
Assessment dan Analisis Ekonomi
4. Menganalisis kontribusi ekosistem mangrove terhadap perikanan dan kondisi
perubahan ekosistem akibat adanya shock.
5. Melakukan kajian ekonomi budidaya tambak pasca tsunami, upaya
rehabilitasi dan pengembangan serta hubungannya dengan produksi perikanan
tangkap setelah shock.
Dari penelitian ini diharapkan akan terciptanya suatu analisis yang
komprehensif menyangkut pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat
dijadikan masukan dan acuan kebijakan dalam rehabilitasi sektor perikanan di
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sumber Daya Pesisir
Pesisir merupakan suatu jalur daratan yang kering dan ruang laut dekatnya,
termasuk kolom air dan daratan dibawahnya, dimana ekosistem darat dan
penggunaannya berdampak terhadap ekosistem laut dan sebaliknya (Rais 2002).
Wilayah pesisir merupakan wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut, batas
di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang maupun yang tidak tergenang
air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin
laut, dan intrusi garam sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang
dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan
mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh
kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen 2002). Secara ekologis, batasan
kawasan pesisir dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Batasan Wilayah Pesisir (Pernetta and Milliman 1995, diacu dalam Dahuri 2001)
Karakteristik utama wilayah pesisir adalah : (1) terdiri dari berbagai
macam habitat/ekosistem (seperti pantai, mangrove, padang lamun, terumbu
karang, dan estuaria) yang menghasilkan berbagai sumber daya (ikan, migas,
CONTINENTAL INTERIOR OPEN OCEAN COASTAL ZONE z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z RIVER BASIN UPLAND LOWLAND CONTINENTAL SHELF
INNER SHELF OUTER SHELF NEARSHORE ESTUARY SALTMARSH DUNES SHELF SEA NEARSHORE WATERS ESTUARINE WATERS ESTUARINE PLUME SHELF
EDGE ZONE
OCEAN FLOOR CONTINENTAL SLOPE SHEL F BR E AK SH EL F SEA / OC EAN IN TE RF A C E SH OR E LIN E LA
ND / SE
A IN TERF ACE CONTINENTAL INTERIOR OPEN OCEAN COASTAL ZONE z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z RIVER BASIN UPLAND LOWLAND CONTINENTAL SHELF
INNER SHELF OUTER SHELF NEARSHORE ESTUARY SALTMARSH DUNES SHELF SEA NEARSHORE WATERS ESTUARINE WATERS ESTUARINE PLUME SHELF
EDGE ZONE
OCEAN FLOOR CONTINENTAL SLOPE SHEL F BR E AK SH EL F SEA / OC EAN IN TE RF A C E SH OR E LIN E LA
ND / SE
A
IN
TERF
mineral, dan lain-lain) dan jasa-jasa lingkungan (seperti proteksi alamiah terhadap
badai dan gelombang, rekreasi, dan penyerapan limbah) bagi masyarakat,
khususnya yang bermukim di pesisir, (2) kompetisi pemanfaatan sumber daya
lahan dan laut oleh berbagai stakeholders yang seringkali mengakibatkan konflik/pertikaian diantara mereka serta perusakan integritas fungsional dari
ekosistem, (3) biasanya berkepadatan penduduk tinggi dan lokasi yang disukai
untuk pengembangan perkotaan, dan (4) sumber utama ekonomi nasional, di mana
menyumbang devisa negara secara signifikan (Dahuri et al. 2001).
Secara umum, wilayah pesisir (yang termasuk kedalamnya estuaria,
coastal wetlands, mangrove, karang, continental shelves, dan lain-lain) memberikan penghidupan yang cukup besar bagi manusia yang ditandai dengan
50 – 70% manusia hidup dan bekerja di wilayah ini. Walaupun luas wilayah
pesisir hanya 8% dari permukaan bumi, namun memberikan kontribusi produksi
biologi global sebesar 26%. Angka ini cukup besar bila dibandingkan dengan
luas daratan yang mencapai 27% dari permukaan bumi dengan produksi biologis
41% dan luas lautan 65% dengan produksi biologis 33% (Rais 2002). Lebih jauh,
Odum (1976), Berwick (1983), dan FAO (1998), diacu dalam Dahuri (2002)
menyatakan bahwa 85% kehidupan biota tropis tergantung pada ekosistem pesisir
dan 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir. Beberapa pernyataan
di atas menunjukkan bahwa kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung
potensi pembangunan yang cukup tinggi, karenanya menjadi pilihan tempat
tinggal dan mencari nafkah potensial bagi manusia.
Wilayah pesisir, sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut,
merupakan kawasan di permukaan bumi yang paling padat dihuni oleh manusia.
Bengen (1999), diacu dalam Sjafi’i (2000) mengatakan terkonsentrasinya
kehidupan di wilayah pesisir disebabkan oleh tiga alasan yaitu : (1) wilayah
pesisir merupakan salah satu kawasan yang secara biologi sangat produktif, (2)
wilayah pesisir menyediakan berbagai kemudahan praktis dan relatif lebih murah
bagi kegiatan industri, pemukiman, dan lainnya, dibandingkan dengan daerah
lahan atas, (3) wilayah pesisir pada umumnya memiliki panorama keindahan yang
dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata yang sangat menarik dan
tekanan yang serius dan membahayakan kelestariannya. Tekanan-tekanan ini
dapat berupa eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hayati, polusi dari
aktivitas di darat dan laut serta degradasi fisik dari habitat pesisir. Melihat
pentingnya wilayah pesisir untuk kehidupan manusia, maka eksistensinya harus
dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah
pesisir dan lautan ini harus mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan
(sustainable development).
2.2. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Istilah pembangunan berkelanjutan mulai dikenal setelah diterbitkan
laporan mengenai pembangunan dan lingkungan serta sumber daya alam oleh
Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan - PBB (UN World on Environment and Development - WCED) yang diketuai oleh Harlem Brundtland (Conrad 1999). Dalam laporan tersebut didefinisikan pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat
memenuhi kebutuhannya. Lebih jauh, dikatakan bahwa pada tingkat yang
minimum, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam
yang mendukung semua kehidupan di muka bumi.
Pada tahun 1992, dalam Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, pembangunan
berkelanjutan menjadi tema umum yang mengaitkan sejumlah konvensi yang
bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk melestarikan
keanekaragaman hayati. Konvensi ini dihadiri oleh lebih dari 140 negara
sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dapat
diterima di seluruh dunia.
Menurut Perman et al. (1996), setidaknya ada tiga alasan mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya
alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan
tidak mengekstraksi sumber daya alam yang merusak lingkungan sehingga
menghilangkan kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk menikmatinya.
Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya
tidak diarahkan pada yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan
karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum
memenuhi kriteria keberlanjutan. Disisi lain, dimensi ekonomi keberlanjutan
sendiri cukup komplek, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini
hanya dibatasi pada kesejahteraan antar generasi (inter generation welfare maximization)
Selanjutnya Perman et al. (1996), mencoba mengelaborasi konseptual keberlanjutan dengan mengajukan lima alternatif pengertian, yaitu :
1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak
menurun sepanjang waktu (non declining consumption).
2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian
rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang.
3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stok) tidak berkurang sepanjang waktu (non declining).
4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk
mempertahankan produksi jasa sumber daya alam.
5. Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dan
daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.
Senada dengan pemahaman di atas, Daly (1990), diacu dalam Fauzi (2004)
menambahkan beberapa aspek mengenai definisi pembangunan berkelanjutan,
antara lain:
1. Untuk sumber daya alam yang terbarukan (renewable resources): Laju pemanenan paling tinggi harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari).
2. Untuk masalah lingkungan: Laju pembuangan limbah harus setara dengan
3. Sumber daya energi yang tidak terbarukan (non renewable resources) harus dieksploitasi secara quasi sustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.
Haris (2000), diacu dalam Fauzi (2004) melihat konsep keberlanjutan
dapat dirinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:
1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu
menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara
keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan
sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus
mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber
daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut
pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi
ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem
yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk
kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.
Arti berkelanjutan secara ekstrim dapat dikatakan sebagai keseimbangan
statis, dimana dalam keseimbangan tersebut tidak terdapat perubahan, meskipun
tentu saja terdapat perubahan dalam lokasi dari waktu ke waktu (Boulding 1991
dan Pezzey 1992). Berkelanjutan dapat pula berarti keseimbangan yang dinamis
(Clark 1989) yang memiliki dua arti. Pertama, keseimbangan sistem yang mengalami perubahan, dimana parameter perubahan dalam keseimbangan tersebut
bersifat konstan. Kedua, keseimbangan suatu sistem yang setiap parameternya mengalami perubahan, sehingga setiap perubahan, misalnya, dalam populasi akan
memicu restorasi nilai populasi awal tersebut.
Ekonomi seringkali didefinisikan sebagai ilmu pengalokasian sumber daya
di antara pihak-pihak yang berkepentingan (Clark 1989). Tujuan ekonomis dari
alokasi sumber daya (alam) adalah efisiensi, yaitu mendapatkan hasil yang
tertinggi dari pemanfaatan dan ekstraksi sumber daya tersebut. Sumber daya
diasumsikan tidak terbatas karena kemajuan teknologi dan preferensi individual
dalam kerangka ekonomi, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu
kerangka yang statis dan mengacu pada konsep keseimbangan (steady state) sebagai perangkat optimisasi (Daly 1991). Lebih jauh, steady state mengacu pada karakteristik sistem sumber daya alam dimana laju produksi/ekstraksi dibatasi
pada aliran komponen sistem dan sediaan sumber daya alam tidak berubah
sepanjang waktu (Burt and Cummings 1977). Optimisasi statis kemudian
dikembangkan untuk menggambarkan trade-off yang tercakup dalam alokasi sumber daya, antara konsumsi (pemanfaatan) dan sediaan (stock). Karakteristik dari sumber daya alam adalah dinamis, demikian pula halnya dengan implikasi
sosial dari pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, ekstraksi optimal dari
sumber daya alam secara inherent adalah dinamis.
Pada kenyataannya, efisiensi tidak dapat menjadi ukuran suatu
pembangunan yang berkelanjutan. Dalam ukuran ekonomi, pembangunan
berkelanjutan bermakna sediaan total dari sumber daya digunakan dalam sistem
ekonomi menentukan kesempatan ekonomi yang luas, yang juga berarti jaminan
kesejahteraan bagi generasi kini dan yang akan datang. Seringkali, efisiensi
ekonomi dan sustainability dianggap memiliki obyektif yang sama, yaitu menyinambungkan pembangunan dengan memastikan bahwa generasi yang akan
datang memiliki kesempatan ekonomi yang sama. Sehingga efisiensi ekonomi
(inter temporal) merupakan isu utama pembangunan berkelanjutan. Meskipun suatu pembangunan dapat bersifat efisien secara ekonomi dan berkelanjutan pada
saat yang sama, efisiensi tidak menjamin sustainability. Dengan demikian, bila kegiatan pembangunan ekonomi bertujuan berkelanjutan dan efisien, alokasi
optimal dari sumber daya ekonomi dan lingkungan harus memenuhi kriteria yang
bertujuan untuk mencapai kedua objektif ini.
Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan
mengharuskan adanya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian
lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Djajadiningrat (1997), diacu dalam
Efrizal (2005) bahwa apabila semua kegiatan ekonomi dihentikan dengan harapan
melindungi lingkungan, maka tindakan ini dapat menimbulkan proses degradasi
lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk.
berjalan dengan cepat, tanpa mengindahkan pelestarian sumber daya alam dan
pengendalian pencemaran. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka tujuan
kebijakan pengelolaan ekonomi harus difokuskan pada pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan, dengan cara menyeimbangkan antara kebijakan pertumbuhan
mutu lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.
Howart dan Norgard (1990), diacu dalam Fauzi (2004) memperlihatkan
konsep keberlanjutan ini dengan mengembangkan kerangka Overlapping Generation Model (OLG). Dengan memasukkan aspek antar generasi, tampak bahwa pemenuhan konsumsi sepanjang waktu akan sangat diperbaharui oleh
distribusi kesejahteraan antar generasi. Secara matematis, formula OLG dapat
ditulis sebagai berikut :
⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − α ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ + + ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = π + + + 1 1 1 1 1 1 t t t t t t h x ch p h x ch p
max (2.1)
dengan kendala :
( )
t tt
t x F x h
x +1 = + − (2.2)
Dimana F(xt) adalah fungsi pertumbuhan sumber daya alam, dan (1/(1+∂)) adalah discount factor sebagai konsekuensi perbandingan manfaat antar generasi. Dengan
mensubstitusi persamaan (2.2) kedalam persamaan (2.1), maka diperoleh
persamaan manfaat ekonomi generasi sekarang yang telah mempertimbangkan
konsumsi dan ketersediaan stok untuk generasi mendatang dalam bentuk:
( )
(
)
⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − + ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ α ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ + + ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − =π t t t t
t
t x F x h
c p h x ch p max 4 1 1 2
1 (2.3)
Jika diasumsikan bahwa variabel sumber daya alam bersifat given
(eksogen), maka persamaan (2.3) dapat dipecahkan untuk menentukan tingkat
panen generasi kini yang tidak akan mengurangi tingkat panen generasi
mendatang. Dengan menurunkan persamaan (2.3) terhadap ht akan diperoleh solusi optimal dari ht sebesar:
(
)
[
]
(
+∂)
α − ∂ + = 1 8 1 4 c x p c p h tSolusi optimal di atas menggambarkan tingkat panen yang harus dilakukan
oleh generasi t yang didasarkan pada harapan untuk mewariskan panen yang
positif pada generasi mendatang. Dengan mengetahui fungsi F(x) yang eksplisit,
kita dapat menentukan solusi biomas yang optimal untuk generasi kini yang
kemudian, dengan teknik substitusi, akan kita ketahui nilai panen yang optimal
generasi mendatang.
Aspek keberlanjutan dapat juga diukur dengan pendekatan depresiasi.
Konsep ini telah pernah dilakukan oleh Fauzi dan Anna (2002) yang mengukur
keberlanjutan sumber daya perikanan.
2.3. Teori Optimasi Sumber daya Perikanan
Perikanan, seperti halnya sektor ekonomi lainnya, merupakan salah satu
aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan terhadap suatu
bangsa. Sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui
(renewable), pengelolaan sumber daya ini memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati. Jika tidak, maka ketersediaan (stok) sumber daya ini
dipastikan akan berkurang atau bahkan, pada spesies (ikan) tertentu, akan habis.
Telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa sebagian daerah penangkapan
ikan, baik di dunia maupun di Indonesia, telah mengalami kelebihan tangkap
(over fishing). Pertanyaan bagaimana sebaiknya mengelola sumber daya ini telah menjadi topik yang hangat dibidang pengelolaan sumber daya perikanan.
Pada awalnya, pengelolaan sumber daya perikanan banyak didasarkan
pada faktor biologis semata dengan pendekatan Maximum Sustainable Yield
(MSY) atau tangkap maksimum yang lestari. MSY adalah penangkapan rata-rata
tertinggi yang dapat diambil secara kontinyu (sustained) dari suatu stok ikan dibawah kondisi lingkungan rata-rata. MSY ini sering digunakan sebagai suatu
tujuan pengelolaan sumber daya. Inti pendekatan ini adalah bahwa setiap spesies
ikan memiliki kemampuan untuk berproduksi yang melebihi kapasitas produksi
Dalam model surplus produksi, dinamika dari biomas digambarkan
sebagai selisih antara produksi dan mortalitas alami (Biomas pada t + 1 = biomas
pada t + produksi - mortalitas alami). Artinya, jika produksi melebihi mortalitas
alami, maka biomas akan meningkat, sebaliknya jika mortalitas alami lebih tinggi
dari pada produksi, maka biomas akan menurun. Istilah surplus produksi sendiri
menggambarkan perbedaan atau selisih antara produksi dan mortalitas alami di
atas. Hal ini senada dikemukakan oleh Hilborn and Walter (1992), diacu dalam
Anna (2003), bahwa surplus produksi menggambarkan jumlah peningkatan stok
ikan dalam kondisi tidak ada aktivitas penangkapan atau dengan kata lain jumlah
yang bisa ditangkap, jika biomas dipertahankan dalam tingkat yang tetap.
Salah satu tipe surplus produksi yang biasa digunakan adalah yang
dikembangkan oleh Schaefer (1954). Model Schaefer ini dapat dijelaskan sebagai
berikut : Jika dimisalkan x adalah biomas dari stok, r adalah laju pertumbuhan
alami dari populasi, K adalah daya dukung lingkungan, maka dalam kondisi tidak
ada aktivitas penangkapan (non-fishing), laju perubahan biomas sepanjang waktu dapat diformulasikan:
) (x f dt dx
= (2.5)
dimana f(x) adalah fungsi pertumbuhan. Salah satu fungsi pertumbuhan yang
sering digunakan adalah fungsi pertumbuhan logistik, yang dapat diformulasikan
sebagai berikut :
) 1 (
K x rx dt dx
−
= (2.6)
dengan mengintroduksi fungsi penangkapan, H=qxE ke dalam model di atas,
kemudian diasumsikan bahwa penangkapan berkorelasi linier terhadap biomas (x)
dan input produksi (E), maka laju pertumbuhan biomas menjadi :
qxE K
x rx dt dx
− −
= (1 ) (2.7)
Kemudian apabila diasumsikan bahwa laju pertumbuhan mendekati nol (dx/dt =
0), maka diperoleh suatu hubungan antara hasil tangkapan lestari dengan input
Gambar 3. Kurva Yield Effort (Fauzi 2004)
Kurva di atas dapat dilihat bahwa jika tidak ada aktivitas perikanan (effort
= 0), maka produksi nol. Kemudian effort akan mencapai titik maksimum pada EMSY kaitannya dengan tangkap maksimum lestari (HMSY). Dalam pendekatan ini, pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal dilakukan pada titik HMSY, karena pada titik ini diperoleh tingkat produksi yang maksimum.
Konsep pengelolaan sumber daya perikanan dengan pendekatan MSY
seperti yang disebutkan di atas, belakangan banyak dikritik oleh berbagai pihak
sebagai pendekatan yang terlalu sederhana dan tidak mencukupi. Kritik yang
paling mendasar di antaranya adalah karena pendekatan MSY tidak
mempertimbangkan sama sekali aspek-aspek sosial ekonomi pengelolaan sumber
daya alam. Conrad dan Clark (1987), diacu dalam Fauzi (2004), menyatakan
bahwa beberapa kelemahan pendekatan MSY antara lain:
1. tidak bersifat stabil, karena perkiraan stok yang meleset sedikit saja bisa
mengarah ke pengurasan stok (stockdepletion),
2. didasarkan pada konsep steady state (keseimbangan) semata, sehingga tidak berlaku pada kondisi non-steady state,
3. tidak memperhitungkan nilai ekonomis apabila stok ikan tidak dipanen
(imputed value),
4. mengabaikan aspek interdependensi dari sumber daya, dan
5. sulit diterapkan pada kondisi dimana perikanan memiliki ciri ragam jenis
(multi species) Hmsy
Effort (E) Emsy
Pr
odu
ksi Lestar
i
Menyadari beberapa kelemahan dari konsep MSY seperti yang
dikemukakan di atas, maka pada tahun 1950-an, Gordon mengembangkan model
Schaefer di atas dengan memasukkan faktor ekonomi, harga dari output (harga ikan per satuan berat) dan biaya dari input (cost per unit effort). Gordon mentransformasikan kurva yield effort dari Schaefer menjadi kurva yang menggambarkan manfaat bersih, yaitu selisih antara Total Revenue (TR) yang dihasilkan dari sumber daya perikanan dan Total Cost (TC) dari input produksi (effort) yang digunakan. Model Gordon-Schaefer adalah model ekonomi perikanan yang didasarkan pada faktor input (effort). Model ini kemudian dikenal dengan model Gordon-Schaefer, yang secara grafik dapat dilihat pada Gambar 4.
Inti dari teori Gordon berawal dari sintesis Hardin (1968) mengenai
“Tragedy of the Common” yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang berada dalam rezim common property dengan akses yang terbuka (open access) akan menyebabkan hilangnya rente ekonomi optimal (dissipated) yang semestinya diperoleh.
Gambar 4 menunjukkan bahwa dalam kondisi open access, sumber daya perikanan akan mencapai titik keseimbangan pada tingkat EOA dimana Total Revenue (TR) sama dengan Total Cost (TC). Dalam hal ini pelaku perikanan hanya menerima biaya opportunitas saja dan rente ekonomi sumber daya atau
profit tidak ada. Tingkat effort pada posisi ini disebut sebagai tingkat effort
keseimbangan yang dikenal sebagai bio-economic equilibrium of open access fishery (keseimbangan bionomic dalam kondisi akses terbuka).
Gambar 4. Model Gordon-Schaefer
Effort (E) Emsy
Revenue-Cos
t TC=c.E
MEY MSY
TR=p.Y(E)
EOA E*
A C
Dari Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa pada setiap tingkat effort di bawah EOA, penerimaan total akan melebihi biaya total sehingga para pelaku perikanan (nelayan) akan berusaha (lebih tertarik) untuk masuk dalam usaha perikanan.
Sementara sebaliknya, pada tingkat effort di atas EOA, biaya total akan melebihi penerimaan total, sehingga banyak pelaku perikanan (nelayan) akan keluar dari
usaha perikanan.
Keuntungan maksimum secara lestari akan diperoleh pada tingkat effort
E*. Pada titik ini rente ekonomi yang diperoleh pelaku perikanan (nelayan)
adalah maksimal, yang pada Gambar 4 di atas ditunjukkan oleh selisih TR dan TC
terbesar (garis AC). Tingkat upaya ini disebut sebagai Maximum Economic Yield (MEY). Dengan demikian konsep MEY menggambarkan kondisi pengelolaan perikanan yang optimal secara ekonomi, dimana faktor input yang dimanfaatkan
seefisien mungkin sehingga diperoleh rente sumber daya yang maksimum.
Kondisi MEY diperoleh pada tingkat effort yang lebih rendah dibandingkan dengan titik keseimbangan pada kondisi open access. Biomas yang dipertahankan (menjadi stok) relatif lebih banyak, tangkapan per unit effort tinggi, dan profit juga tinggi. Perikanan yang dikelola untuk mendapatkan MEY disebut juga
perikanan yang dikelola dengan cara yang sangat conservative secara biologi. Jika dibandingkan dengan model pendekatan biologi di atas, model
Gordon-Schaefer lebih baik, karena menekankan pada efisiensi input dengan rente
ekonomi yang maksimum mengingat jumlah input produksi yang digunakan pada
model ini sedikit jauh lebih daripada EMSY dan EOA. Jika dibandingkan tingkat upaya pada keseimbangan open akses dengan tingkat upaya optimal secara sosial
(E*), maka dapat dilihat bahwa pada kondisi open access tingkat upaya yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari yang semestinya untuk mencapai keuntungan
optimal yang lestari. Sehingga keseimbangan open access ini dapat menyebabkan timbulnya alokasi sumber daya alam yang tidak benar, karena kelebihan sumber
daya input (tenaga kerja, modal) yang dibutuhkan untuk perikanan seharusnya
bisa dialokasikan untuk kegiatan ekonomi lainnya yang lebih produktif. Hal inilah
disimpulkan bahwa tingkat effort Emey terlihat lebih “conservative minded” dibandingkan dengan tingkat effort Emsy.
Dalam kaitannya dengan depresiasi sumber daya, pada pendekatan biologi,
depresiasi sumber daya tidak diperhitungkan sama sekali, sementara pada model
Gordon, depresiasi sumber daya perikanan dilihat sebagai hilangnya rente
ekonomi (dissipated) akibat mismanagement sumber daya perikanan yang open access.
Copes (1972) mencoba mengisi kekurangan model Gordon dengan
memasukkan faktor welfare effect di dalam modelnya, berdasarkan keterkaitan antara output dari sumber daya perikanan (ikan) dengan biaya dan harga. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal bisa dilihat dari
berbagai sisi stakeholder yakni, pemerintah, masyarakat (konsumen) dan pelaku sendiri (produsen). Dari ketiga aspek ini, Copes melihat surplus yang mungkin dihasilkan dari pengelolaan sumber daya perikanan. Salah satu hal yang penting
dari teori Copes adalah mengenai "back ward bending supply curve" dari perikanan. Kurva itu menggambarkan bahwa suplai dari produk perikanan tidak
tak terbatas karena faktor daya dukung lingkungan tidak akan mampu terus
menerus mendukung produksi. Dengan demikian pengelolaan perikanan juga
sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya.
Sebagaimana dikemukakan di atas, baik model Gordon maupun model
Copes menganalisis pengelolaan perikanan di dalam framework statis. Artinya aspek intertemporal (antar waktu) yang terkait dengan sumber daya perikanan
maupun pelaku industri sendiri tidak diperhitungkan. Misalnya, di dalam model
Gordon, pengalihan excess effort dari kondisi open access ke EMEY dilakukan seketika tanpa memperhitungkan faktor penyesuaian. Padahal, stok ikan sendiri
memerlukan waktu untuk tumbuh, demikian juga pengurangan input dari tingkat EOA ke EMSY memerlukan waktu untuk penyesuaian. Menyadari kelemahan inilah Clark dan Munro mengembangkan model dinamis pengelolaan sumber daya
perikanan yang optimal. Di dalam model mereka, sumber daya ikan diperlakukan
sebagai aset yang memiliki opportunity cost atau biaya korbanan. Artinya di dalam mengelola sumber daya ikan kita dihadapkan pada pilihan intertemporal,
dibiarkan diperairan sehingga bisa tumbuh dan bisa dipanen di masa mendatang
sehingga bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Trade-off antara memanen stok saat ini atau nanti inilah yang menjadi ciri khas dalam model
intertemporal yang dikembangkan oleh Clark dan Munro. Salah satu solusi dari
model Clark dan Munro adalah fenomena yang disebut sebagai most rapid approach (MRAP) atau "bang-bang approach” yang menyatakan bahwa penyesuaian ke arah tingkat eksploitasi yang optimal (biomas, tangkap dan input) harus dilakukan secepat mungkin (Gambar 5).
Dari Gambar 5 terlihat bahwa jika x* adalah kondisi optimal biomas
yang lestari, maka pada pendekatan "bang-bang", strategi yang optimal adalah melakukan eksploitasi yang maksimurn (h=hmax) pada saat x > x* (dimulai dari titik B). Sebaliknya jika x < x* (dimulai dari titik A), strategi optimal adalah tidak
melakukan eksploitasi. Melihat model ini, depresiasi sumber daya perikanan
sebenarnya akan terjadi secara cepat jika strategi pertama dilakukan. Clark dan
Munro secara implisit menyatakan bahwa deplesi akan terjadi manakala strategi
pertama dilakukan dan dimana kondisi parameter harga per satuan output jauh lebih besar dari biaya per satuan input.
Gambar 5. Pendekatan "bang-bang" optimisasi sumber daya perikanan
Secara umum dapat dikatakan bahwa keseluruhan model dasar optimisasi
pengelolaan sumber daya perikanan yang dikemukakan di atas, tidak secara x*
Stok
Waktu, t
A
h = hmax
h=0
eksplisit membahas depresiasi sumber daya perikanan. Model-model dasar di atas
melihat bahwa depresiasi terjadi manakala input yang digunakan atau output yang dihasilkan terlalu belebihan (model Gordon dan Copes). Pada model Clark dan
Munro melihat bahwa depresiasi sumber daya akan terjadi manakala penggunaan
input maupun tingkat panen tidak mengikuti trajektori optimal yang ditentukan oleh aspek intertemporal sumber daya ikan itu sendiri.
2.4. Teori Degradasi Sumber daya
Definisi degradasi agak bersifat subjektif, memiliki arti yang berbeda
tergantung pada suatu kelompok masyarakat. Misalnya, untuk sumber daya
hutan, sebagian orang mengatakan bahwa hutan yang terdegradasi adalah hutan
yang telah mengalami kerusakan sampai pada suatu point/titik dimana
penebangan kayu maupun non kayu pada periode yang akan datang menjadi
tertunda atau terhambat semuanya. Sedangkan sebagian lainnya mendefinisikan
hutan yang terdegradasi adalah suatu keadaan dimana fungsi ekologis, ekonomis
dan sosial hutan tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Oldeman (1992)
mengatakan bahwa degradasi adalah suatu proses dimana terjadi penurunan
kapasitas baik saat ini maupun masa mendatang dalam memberikan hasil.
Degradasi sumber daya dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain
karena permintaan yang tinggi terhadap jasa ekosistem akibat pesatnya
pertumbuhan ekonomi, perubahan demografis dan pilihan-pilihan individu
(individual choice), serta mekanisme pasar yang tidak menjamin keberlangsungan jasa konservasi ekosistem.
Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa
lingkungan yang sangat kaya, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang
lamun, berikut sumber daya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya.
Akan tetapi kekayaan sumber daya pesisir tersebut mulai mengalami kerusakan.
Sejak awal tahun 1990-an phenomena degradasi biogeofisik sumber daya pesisir
semakin berkembang dan meluas. Laju kerusakan sumber daya pesisir telah
mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove
Ada beberapa sumber daya perikanan yang telah dieksploitir secara
berlebihan (overfishing), termasuk udang, ikan demersal, pelagis kecil, dan ikan karang. Hal ini terjadi terutama di daerah-daerah dengan penduduk padat,
misalnya di Selat Malaka, pantai utara Pulau Jawa, Selat Bali, dan Sulawesi
Selatan. Menipisnya stok sumber daya tersebut, selain karena overfishing juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung atau tidak merusak
ekosistem dan lingkungan sehingga perkembangan sumber daya perikanan
terganggu. Penggunaan teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan.
Penggunaan teknologi penangkapan semacam ini banyak terjadi di daerah-daerah.
Teknologi penangkapan yang digunakan umumnya menyebabkan kerusakan dan
kehancuran sumber daya perikanan. Teknologi tersebut misalnya penggunaan alat
tangkap trawl, potassium cyanide, dan penggunaan bom ikan.
Dari hasil penelitian para peneliti ekonomi sumber daya dari International Center for Living Aquatic Resource Management (ICLARM) yang melakukan kajian tentang hal tersebut. Salah satu kesimpulan dari kajiannya adalah nelayan
terdorong atau terpaksa menangkap ikan dengan cara-cara merusak (destructive) karena kesalahan manajemen sumber daya perikanan (ICLARM 1992).
Selanjutnya dikatakan bahwa jika manajemen sumber daya perikanan itu tidak
dilakukan dengan baik, akhirnya akan terjadi kelebihan penangkapan ikan
(overfishing). Tangkap lebih ini dibagi dalam beberapa tipe bergantung pada tingkat keseriusannya, yaitu:
1. Recruitment overfishing, yaitu kondisi ikan-ikan muda (juvenile) yang ditangkap secara berlebihan sehingga tidak ada pertumbuhan stok ikan dewasa
yang berasal dari ikan dengan kelompok usia yang lebih muda. Dengan kata
lain, pertumbuhan stok ikan dewasa hanya terjadi melalui penambahan ukuran
berat ikan dewasa yang tersisa.
2. Biologically overfishing, yaitu kondisi penangkapan ikan yang telah mencapai tahap melebihi hasil tangkapan maksimum lestari (MSY). Hal ini berarti ikan
yang ditangkap melebihi kemampuan maksimum stok ikan untuk tumbuh
sumber daya ikan menurun secara drastis dan akhirnya membuat perikanan
berhenti secara total.
3. Economically overfishing, dimana upaya penangkapan ikan secara berlebihan melalui investasi armada penangkapan secara besar-besaran, namun hasil
tangkapan ikan yang diperoleh secara agregat hanya pada tingkat sub
optimum (lebih rendah dari tingkat maksimum yang dapat dihasilkan). Pada
kondisi seperti ini, berarti industri penangkapan ikan beroperasi melebihi
potensi maksimumnya secara ekonomi, oleh karena itu kondisi seperti tidak
lagi efisien.
4. Malthusian overfishing. Kondisinya sama seperti yang dikemukakan Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk begitu cepat, sedangkan pertumbuhan produksi
pangan untuk menghidupi penduduk sangat lambat. Dalam perikanan kondisi
ini berarti ada sedikit ikan yang tersedia di laut dan diperebutkan oleh banyak
nelayan.
Malthusian overfishing terjadi ketika pemerintah sebagai manajer sumber daya perikanan tidak mampu dan tidak berhasil menata dan mengelola kegiatan
penangkapan ikan yang dilakukan rakyatnya. Akibatnya, setiap nelayan
berkompetisi secara bebas, maka timbul daya kreasi setiap orang untuk
mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dan cepat. Daya kreasi itu diwujudkan
dengan dihasilkannya atau direkayasakannya metode dan teknik menangkap ikan
yang cepat dan efisien secara ekonomi, namun ternyata merusak dan merugikan
lingkungan. Metode dan teknik yang digunakan antara lain: bom, dinamit, racun,
aliran listrik, serta alat-alat penangkap ikan yang kontemporer bersifat merusak.
Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan, jika tidak dilakukan, orang lain
yang akan melakukannya (tragedy of common) Malthusian overfishing adalah perlombaan untuk meraih keuntungan dengan cara yang salah dan membawa
dampak kerugian bagi semua orang (Nikijuluw 2002).
Permasalahan degradasi sumber daya perikanan dan kemiskinan di
wilayah pesisir sangat kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan, degradasi
dapat terjadi akibat tangkap lebih dan kemiskinan. Namun degradasi juga dapat
menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik antara kemiskinan dan degradasi
sumber daya pesisir dan laut, yaitu: ketidakstabilan pendapatan, rendahnya akses
masyarakat dan rendahnya kontrol mereka dalam pengelolaan sumber daya laut.
Belajar dari kelemahan masyarakat tersebut maka upaya pemberdayaan harus
mengacu pada upaya mengatasi kelemahan-kelemahan pokok masyarakat pesisir
agar mereka berdaya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan
secara berkelanjutan (Hidayati 2000).
Seperti diketahui bahwa sebagian besar sumber daya pesisir dan lautan di
Indonesia telah mengalami degradasi, dimana faktor penyebabnya yang dominan
adalah karena aktivitas manusia. Namun demikian pada dasarnya masih belum
banyak dilakukan penilaian seberapa besar sebenarnya laju dari degradasi dan
depresiasi dari sumber daya pesisir dan laut ini termasuk sumber daya perikanan,
hal ini disebabkan karena memang belum ada teknik pengukuran besaran laju
degradasi/depresiasi khusus untuk sumber daya perikanan.
Model matematis untuk menghitung besaran laju degradasi sumber daya
lahan yang dilakukan oleh Amman and Durraipah (2001) dalam penelitian
mengenai "Land Tenure and Conflict Resolution: A Game Theoretic Approach in the Narok District in Kenya", adalah sebagai berikut:
φ =
t , i Avg
q qi
e
+
1
1
(2.8)
qi,tAvg = qit jika Vj dljti≤ 0 (2.9)
d q
qiAvg,t = it (2.10)
Variabel qi,t adalah komponen degradasi yang disebabkan oleh agent i dari seluas lahan tertentu. Jika output qi,t(seluas tertentu ha) lebih besar dari kemampuan daya dukung lingkungan (carrying capacity) pada waktu t, maka kehilangan efisiensi dalam bentuk faktor degradasi akan muncul. Peneliti
menggunakan fungsi logistik untuk menjelaskan hal ini, seperti persamaan di atas.
Untuk aplikasi bidang perikanan, laju degradasi Amman dan Durraipah
dimodifikasi sebagai berikut (Anna 2003) :
δ α δ
h h h %
D = − (2.11)
dimana : D = persentase degradasi =
δ
h Produksi sustainable
=
α
h Produksi aktual
Sementara koefisien degradasi dihitung berdasarkan persamaan di bawah ini :
α δ Φ
h h D
e
+ =
1 1
(2.12)
Untuk laju depresiasi pada dasarnya sama dengan laju degradasi, hanya
menggunakan parameter-parameter ekonomi, sebagai berikut :
α δ
Π Π
Φ
e D
+ =
1 1
(2.13)
Dimana : φ, = Laju depresiasi
δ
Π = Rente sustainable α
Π = Rente aktual.
2.5. Surplus Konsumen dan Surplus Produsen. Surplus Konsumen (Consumer’s Surplus)
Surplus konsumen atau Dupuit’s consumers surplus, yang pertama kali diperkenalkan oleh Dupuit tahun 1952, adalah pengukuran kesejahteraan ditingkat
konsumen yang diukur berdasarkan selisih keinginan membayar dari seseorang
dengan berapa yang sebenarnya ia bayar (Fauzi 2000a). Dengan kata lain, surplus
konsumen diartikan sebagai perbedaan antara keinginan marjinal seorang
konsumen untuk membayar (marginal willingness to pay) kepada barang dan atau jasa yang akan dibelinya dengan harga yang berlaku di pasar. Jadi surplus
konsumen merupakan ukuran tingkat kepuasan (utility) konsumen yang dapat diperoleh dari barang dan jasa dalam bentuk uang. Secara grafik konsep surplus
0 Q* Q
CS = Consumers Surplus
Gambar 6. Kurva Permintaan dan Willingness to Pay
Pada Gambar 6. terlihat ada kurva permintaan D terhadap barang Q yang
ditarik dari kiri atas ke kanan bawah dengan slope negatif. Kurva tersebut
menunjukkan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi sejumlah barang pada
setiap harga yang berbeda sepanjang sumbu P. Seluruh daerah di bawah kurva
permintaan tersebut menunjukkan keinginan membayar (willingness to pay) dari individu terhadap barang Q. Titik-titik sepanjang kurva permintaan D
menunjukkan keinginan membayar untuk setiap tambahan barang Q, atau disebut
marginal willingness to pay.
Jika keseimbangan harga di pasar adalah pada P*, maka konsumen akan
mengkonsumsi barang sebesar Q*. Walaupun konsumen ingin membayar lebih
dari P*, namun yang sebenarnya ia bayar adalah sebesar P*. Berarti ada
kelebihan keinginan membayar yang ditunjukkan oleh daerah yang di shading, yaitu sebesar P*EA. Dalam ekonomi klasik daerah ini disebut dengan surplus
konsumen (consumers surplus).
Nilai surplus konsumen dapat berubah, misalnya karena perubahan harga
barang atau peningkatan pendapatan konsumen. Secara grafik dapat dilihat pada
Gambar 7.
P* P
A
E
P
a
d
c e
0 Qo Q1 Q
Gambar 7. Pengukuran surplus konsumen
Pada harga Po konsumen akan membeli barang sebesar Qo. Keinginan membayar (WTP) konsumen adalah sebesar a + b c, namun yang benar-benar
dibayar sebesar b + c, maka surplus konsumen dicerminkan luas segitiga a.
Jika harga barang turun dari Po ke P1, maka konsumen akan membeli barang sebanyak Q1. Namun, konsumen tidak ingin membeli pada jumlah Q1,
akan tapi dia (konsumen) tetap membeli sejumlah unit yang sama seperti
sebelumnya Qo. Maka konsumen akan membayar dengan jumlah bayaran yang
lebih kecil, karena harganya turun menjadi P1. Oleh karena itu konsumen menjadi
lebih beruntung sebesar b, yang merupakan selisih antara sejumlah uang yang
dibayarkan untuk memperoleh barang Qo pada harga Po dan jumlah uang yang dibayarkan pada harga P1.
Jika konsumen menambah jumlah pembelian komoditas dari Qo menjadi
Q1, maka dia sebenarnya hanya membayar tambahan sebanyak e, namun
memperoleh nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar d + e. Oleh karenanya dengan
membeli lebih banyak (dari Qo ke Q1 ) konsumen beruntung sebesar d. Jadi
perubahan dalam surplus konsumen terjadi merupakan akibat dari penurunan
harga komoditas adalah b + d. Sedangkan total surplus konsumen dari pembelian
sebanyak Q1 pada harga P1 ditunjukkan oleh nilai sebesar a + b + d.
b Po
P1
Dalam ekonomi sumber daya, konsep surplus konsumen dapat digunakan
untuk menghitung tingkat kehilangan akibat kerusakan ekosistem. Contoh
praktisnya adalah sebagai berikut (Fauzi 2000b) :
Dimisalkan bahwa dalam kondisi lingkungan yang belum rusak,
konsumen membayar harga ikan sebesar Rp 500 per kg, dengan keinginan
membayar maksimum (maximum willingness to pay) sebesar Rp 1000 per kg. Pada tingkat harga tersebut, konsumen mampu membeli sebanyak 10 kg per bulan
atau 120 kg per tahun. Meskipun konsumen mampu membayar Rp 1000 per kg,
tapi yang sebenarnya ia bayar hanya Rp 500 per kg. Dengan demikian terjadi
surplus konsumen sebesar selisih antara keinginan membayar dengan yang
sebenarnya dia bayar. Selisih tersebut dapat dilihat pada Gambar 8. berikut yang
merupakan luas segitiga PoEoM atau 60 x 500 = Rp 30 000.
Dimisalkan sekarang bahwa, hutan mangrove sebagai tempat memijah
ikan rusak sehingga ikan/udang semakin susah ditangkap. Kondisi ini akan
menyebabkan kenaikan harga ikan karena supply yang berkurang. Katakanlah
akibat kerusakan ini menyebabkan harga ikan naik menjadi Rp 750 per kg. Pada
tingkat harga ini, konsumen hanya mampu membeli sebanyak 100 kg per tahun.
Dengan demikian surplus konsumen berkurang menjadi daerah P1E1M atau 50 x 250 = Rp 10 250. Sehingga kita bisa menghitung akibat perubahan kondisi
P
P0 = 500
M =1000
E1
D E0
P1 =750
100 120 Q
sumber daya ini mengakibatkan perubahan surplus konsumen sebesar Rp 30 000 –
Rp 10 250 = Rp 10.750 unit moneter.
Surplus Produsen (Producer’s Surplus)
Berbeda dengan pengukuran surplus konsumen, surplus produsen diukur
dari sisi manfaat dan kehilangan dari sisi produsen atau pelaku ekonomi (Fauzi
2000b). Surplus produsen adalah ukuran keuntungan yang diperoleh produsen
karena mereka beroperasi pada suatu pasar komoditas (Sugiarto et al. 2002). Surplus produsen pada dasarnya adalah surplus yang diperoleh produsen yang
merupakan selisih antara harga yang diterima oleh produsen dengan biaya yang
dikeluarkan untuk memproduksi output (Anna 2003). Identik dengan surplus
konsumen, besaran surplus produsen juga akan tergantung dari perubahan harga
dan biaya. Secara grafik surplus produsen dapat dijelaskan pada Gambar 9.
Dari Gambar 9, dapat dijelaskan bahwa surplus produsen ditunjukkan oleh
area P*EB, di atas garis supply dan di bawah garis harga. Oleh karena kurva
supply menunjukkan biaya marginal dari tiap unit barang yang diproduksi, maka
area OBEQ* adalah total biaya variabel. Area OP*EQ* adalah penerimaan kotor
(Sadoulet dan Janvry 1995).
Area P*EA adalah surplus konsumen pada kondisi awal, sementara P*EB
merupakan daerah surplus produsen pada kondisi awal. Jika tidak ada kebijakan
menyangkut harga atau output, keseimbangan, terjadi pada P* dan Q*. Jika
pemerintah kemudian melakukan kebijakan yang menyebabkan output bergeser
ke Q1 (misalnya karena pajak), maka surplus konsumen dan produsen akan
berubah. Perubahan kedua surplus tersebut menyebabkan redistribusi surplus
dari produsen dan konsumen ke pemerintah sebagai pemilik sumber daya
mewakili publik. Dengan adanya redistribusi surplus tersebut, terbentuk rente
Gambar 9. Producer’s Surplus (PS) dan Retribusinya Surplus
Dampak terhadap consumers welfare dicerminkan oleh perubahan dari consumers surplus (ΔCS) dan dampak dari producer welfare diukur dengan
perubahan producer surplus (ΔPS) (Sadoulet dan Janvry 1995). Analisa ini dapat
dipisahkan antar kelompok produsen dan konsumen jika keduanya mempunyai
share awal yang berbeda terhadap produksi dan konsumsi total dan atau mempunyai elastisitas harga yang berbeda terhadap supply dan demand. Sebagai contoh, konsumen miskin mempunyai elastisitas yang lebih tinggi terhadap
permintaan makanan karena untuk membeli makanan tersebut mereka
mengeluarkan bagian pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan konsumen
kaya. Petani kecil mempunyai elastisitas yang rendah dalam merespon supply
food crops dibanding petani besar.
2.6. Konsep Efisiensi Perikanan Tangkap
Apabila suatu ketika di suatu perairan terjadi gejala penurunan produksi
perikanan tangkap, dengan asumsi input yang digunakan sama atau lebih tinggi
dari periode sebelumnya, maka biasanya kita menduga bahwa di sana telah terjadi
overfishing, namun tidak jelas overfishing apa yang terjadi, apakah Malthusian overfishing, biological overfishing, recruitment overfishing, atau economical overfishing. Disinilah pentingnya dilakukan perhitungan kapasitas perikanan, yaitu untuk mengetahui apakah perikanan tersebut sudah efisien dalam kaitannya
P* P
A
E
D
CS
O
1
Q* Q
B
S
PS
PS
P1
Q1
C F
dengan economic overfishing. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat
dibuat suatu diagnosa terhadap permasalahan di atas, sehingga solusi kebijakan
yang akan diterapkan akan lebih tepat.
Berbagai metode telah diaplikasikan oleh para peneliti untuk mengukur
efisiensi perikanan tangkap, diantaranya dengan metode Atkinson, metode
utilitarian, metode Dalton, dan lain-lain (Simkin 1998). Metode-metode tersebut pada dasarnya lebih kepada penilaian mengenai seberapa efisien suatu kebijakan
terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ketidakmerataan
(inequality). Pendekatan ekonometrik biasa pada dasarnya tidak mampu menjadi solusi untuk memecahkan masalah efisiensi, khususnya jika yang menjadi
variabel pertimbangan memiliki multiple inputs dan output (Seiford and Thrall 1990). Penilaian terhadap kebijakan yang menyangkut efisiensi, pada dasarnya
dapat dilakukan dengan Data Envelopment Analysis (DEA), juga biasa disebut
Frontier Analysis (Charnes, Cooper, and Rhodes 1978). Teknik ini dikenal juga dengan CCR (singkatan nama depan ketiga penemunya), merupakan
pengukuran/penilaian terhadap performance untuk mengevaluasi efisiensi relatif
dari unit pengambil keputusan (Decision Making Unit, DMU) dalam suatu analisis. Sejak teknik ini diperkenalkan, sudah banyak analisis teoritis dan
empiris yang dikembangkan dan diaplikasikan pada perbankan, rumah sakit,
perpajakan, sekolah, juga sumber daya alam (Beasley 2000).
Pada prinsipnya DEA merupakan pengukuran efisiensi yang bersifat bebas
nilai (value free) karena didasarkan pada data yang tersedia tanpa harus mempertimbangkan penilaian (judgment) dari pengambil keputusan. Teknik ini didasarkan pada pemograman matematis (mathematical programming) untuk menentukan solusi optimal yang berkaitan dengan sejumlah kendala. DEA
bertujuan mengukur keragaan relatif (relative performance) dari unit analisis pada kondisi keberadaan multiple input dan output (Dyson et al. 1990, diacu dalam Fauzi dan Anna 2005).
Kelebihan DEA adalah (1) dapat mengestimasi kapasitas di bawah kendala
penerapan kebijakan tertentu, seperti pajak, Total Allowable Catch (TAC), distribusi regional atau ukuran kapal, larangan penangkapan pada waktu tertentu,
dan multiple inputs, serta tingkat input atau output yang riil maupun non-diskret, (3) dapat menentukan tingkat potensial maksimum dari effort atau variabel input secara umum dan laju utilitas optimalnya.
Dalam DEA, efisiensi diartikan sebagai target untuk mencapai efisiensi
yang maksimum, dengan kendala relatif efisiensi seluruh unit tidak boleh melebihi
100%. Secara matematis, efisiensi dalam DEA merupakan solusi dari persamaan
berikut :
∑
∑
= k kjm k i ijm i m y v y wMaxE (2.14)
Dengan kendala :
1 ≤
∑
∑
k kjm k i ijm i y v y wuntuk setiap unit ke-j
wi , vk ≥ε
Pemecahan masalah pemograman matematis di atas akan menghasilkan
nilai Em yang maksimum, sekaligus nilai bobot (w dan v ) yang mengarah ke efisiensi. Jadi, jika nilai Em = 1 artinya unit ke-m tersebut dikatakan efisien relatif terhadap unit yang lain. Sebaliknya, jika nilai Em < 1, maka unit lain lebih efisien relatif terhadap unit m, meskipun pembobotan dipilih untuk memaksimasi unit m. Salah satu kendala dari pemecahan persamaan (2.14) adalah persamaan
tersebut berbentuk fractional sehingga sulit dipecahkan melalui pemograman linear. Namun dengan melakukan linearisasi, persamaan tersebut dapat diubah
menjadi persamaan linear (linear programming), sebagai berikut :
∑
=i
ijm i
m w y
MaxE (2.15)
Dengan kendala: ϖ =
∑
kjm k kx v∑
−∑
≤ i k kjm k ijmiy v x
w 1
Dalam model DEA yang dikembangkan oleh CCR, efisiensi diukur
dengan asumsi bahwa fungsi produksi bersifat constant returns to scale (CRS). Artinya, jika input dinaikkan dua kali lipat, maka output juga meningkat secara
proporsional (dua kali lipat juga). Model ini sangat bersifat linear dan sangat
mudah diformulasikan serta dikerjakan dalam program linear. Namun, model
yang didasarkan pada constant return to scale ini tidak selalu tepat bila diaplikasi
pada aktivitas produksi yang mengalami non-constant return to scale. Beberapa
fungsi produksi, seperti produksi perikanan, bersifat decreasing returns to scale. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, model asal dari CCR ini kemudian
dikembangkan lebih lanjut oleh Banker, Charnes, and Cooper (1984) dan dikenal
dengan BCC DEA, yang memungkinkan dilakukan analisis efisiensi bagi aktivitas
ekonomi yang bersifat variable return to scale (Fauzi dan Anna 2005).
Aplikasi model DEA meliputi proses yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu :
(1) mendefinisikan DMU yang akan dianalisis, yaitu seluruh unit yang menjadi
bahan pertimbangan harus mewakili tugas sama dengan tujuan yang sama, dan
berada pada set kondisi market yang sama serta harus menggunakan input yang
sama untuk memproduksi jenis output yang sama, (2) menentukan variabel input
dan output yang akan digunakan dalam menganalisis efisiensi relatif dari DMU
yang terpilih, (3) mengaplikasikan salah satu model DEA dan menganalisis
3.
METODE
PENELITIAN
3.1. Kerangka Pendekatan Penelitian
Untuk mencapai tujuan penelitian seperti tercantum dalam Bab 1, maka
dibuatlah suatu alur fikir (road map) penelitian seperti terlihat pada Gambar 1. Alur ini mencoba melihat permasalahan pesisir dan lautan di daerah studi secara
menyeluruh (comprehensive) dan interaksi antar sumber daya yang ada di kawasan pesisir dan lautan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya ikan
(perikanan tangkap), perikanan budidaya (tambak), dan ekosistem hutan
mangrove.
Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan assessment terhadap
sumber daya-sumber daya tersebut. Untuk perikanan tangkap, penilaian
dilakukan dengan model bio-ekonomi. Dengan analisis model bio-ekonomi akan
diketahui produksi aktual dan lestari (sustainable), stok biomas, effort dan tangkapan (catch) optimal serta rente ekonomi dari sumber daya ikan. Besaran nilai-nilai di atas dipengaruhi oleh tiga parameter biofisik, yaitu pertumbuhan
intrinsic (r), carrying capacity (K), dan catch-ability coefficient (q). Ketiga parameter ini akan sangat menentukan besaran stok dan jumlah ikan yang
ditangkap serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Selain itu, juga dilakukan
analisis surplus produsen, dan analisis efisiensi relatif dan kapasitas perikanan
tangkap. Semua analisis di atas dikaitkan dengan proses rehabilitasi dan
rekonstruksi perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Secara fisik, ada keterkaitan yang jelas antara ekosistem mangrove dan
produksi ikan dari perikanan tangkap. Hal ini disebabkan karena ekosistem
mangrove merupakan tempat pemijahan (spawning ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan tempat pembesaran beberapa spesies biota laut termasuk ikan, udang, dan kepiting. Untuk melihat interaksi antara ekosistem
mangrove dan produksi perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan model
interaksi hutan mangrove dengan stok dan tangkapan ikan, yaitu dengan
produksi ikan di suatu wilayah pesisir. Disamping itu, juga dapat dihitung
biomas, tangkapan lestari, dan effort dengan masukkan variabel hutan bakau dalam model.
Selanjutnya, dilakukan penilaian (assessment) terhadap perikanan budidaya (tambak) yang meliputi, luasan, produksi dan produktivitas, rente
ekonomi, dan return to labor pada kondisi tambak sebelum terja