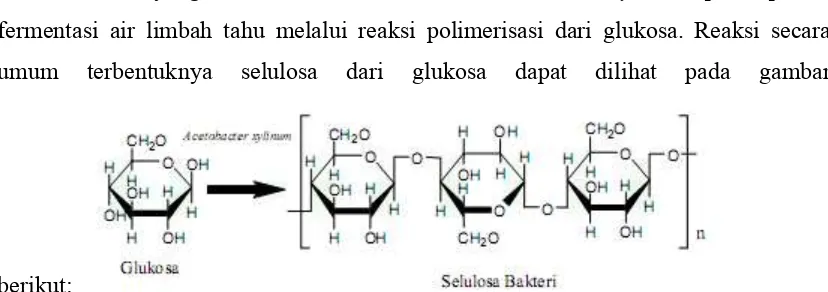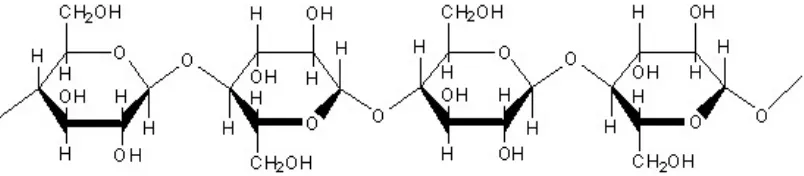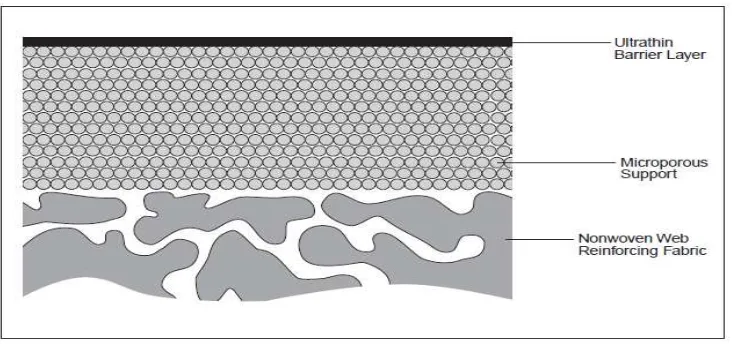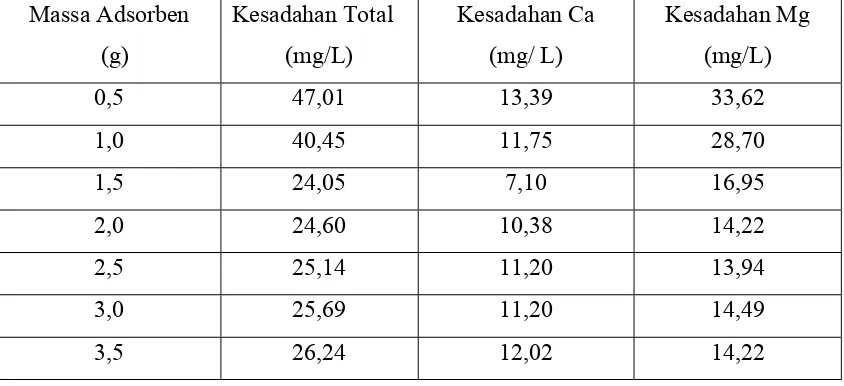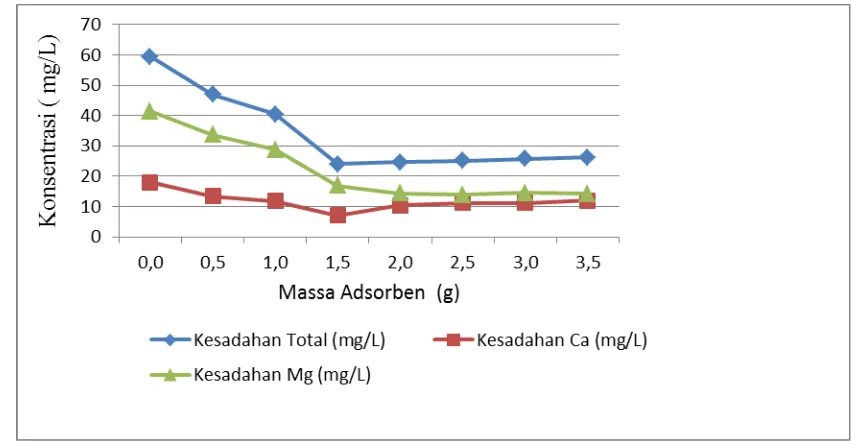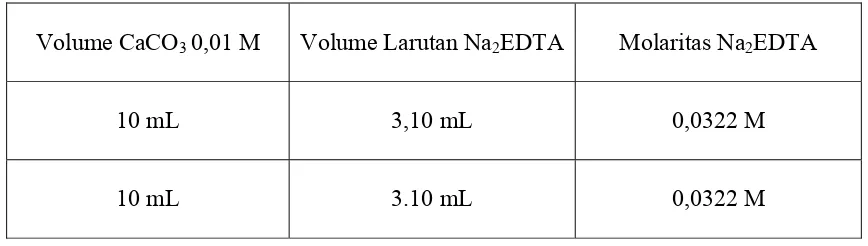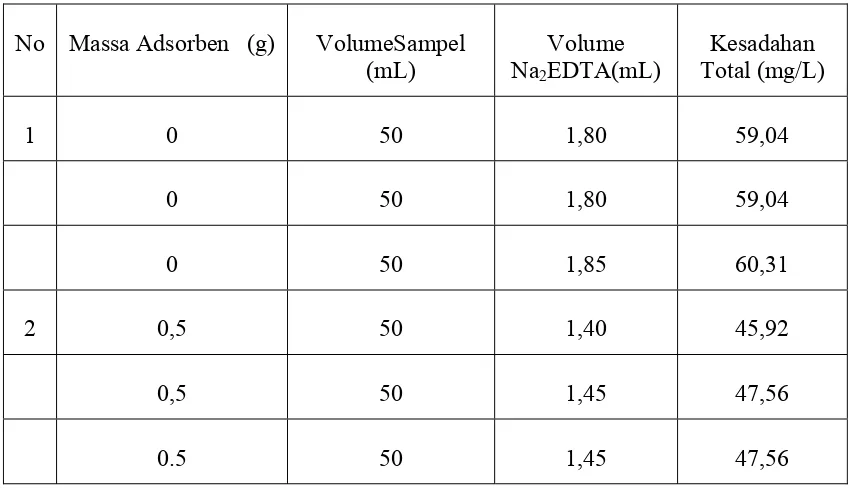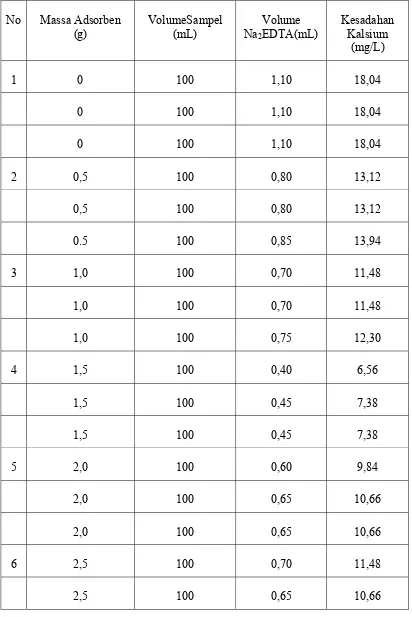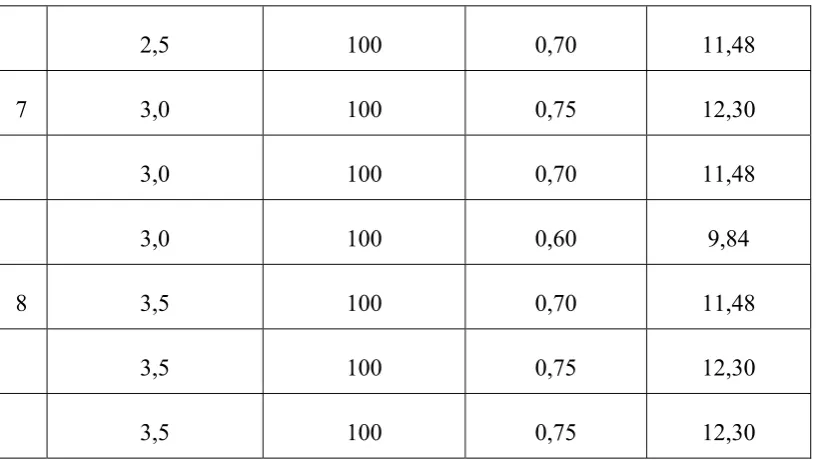STUDI PEMANFAATAN NATA DE SOYA DARI AIR LIMBAH
KEDELAI SEBAGAI ADSORBEN TERHADAP KATION
MAGNESIUM ( Mg
2+) DAN KALSIUM ( Ca
2+)
PADA AIR BAKU BOILER
DI PT SMART TBK
SKRIPSI
AZWINNATA
110822004
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
STUDI PEMANFAATAN NATA DE SOYA DARI AIR LIMBAH
KEDELAI SEBAGAI ADSORBEN TERHADAP KATION
MAGNESIUM ( Mg
2+) DAN KALSIUM ( Ca
2+)
PADA AIR BAKU BOILER
DI PT SMART TBK
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains
AZWINNATA
110822004
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013
PERSETUJUAN
Judul : STUDI PEMANFAATAN NATA DE SOYA DARI AIR LIMBAH KEDELAI SEBAGAI ADSORBEN TERHADAP KATION MAGNESIUM ( Mg2+) DAN KALSIUM ( Ca2+) PADA AIR BAKU BOILER DI PT SMART TBK
Kategori : SKRIPSI
Nama : AZWINNATA Nomor Induk Mahasiswa : 110822004
Program Studi : SARJANA (S1) KIMIA EKSTENSI Departemen : KIMIA
Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Disetujui di,
Medan, Juni 2013
Komisi Pembimbing :
Pembimbing 2 Pembimbing 1
Prof. Dr. Zul Alfian, M.Sc Drs. Chairuddin, M.Sc NIP. 195504051983031002 NIP. 195912311987011001
Diketahui/Disetujuioleh
Departemen Kimia FMIPA USU Ketua,
PERNYATAAN
STUDI PEMANFAATAN NATA DE SOYA DARI AIR LIMBAH
KEDELAI SEBAGAI ADSORBEN TERHADAP KATION
MAGNESIUM( Mg
2+) DAN KALSIUM ( Ca
2+) PADA
AIR BAKUBOILER DI PT SMART TBK
SKRIPSI
Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan-ringkasan masing-masing disebutkan sumbernya.
Medan, Juni 2013
PENGHARGAAN Bissmillahirramanirrahim,
Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya semata saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat saya untuk meraih gelar Sarjana Sains di Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.
Dengan mengucapkan rasa syukur dan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda tercinta Supranata, dengan upaya keridhoan mu dalam memberikan saya kasih sayang dan segala keperluan dalam saya bersekolah hingga sekarang. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibunda Yuslizar Br Sagala yang telah mendidik saya menjadi insan, ihsan dan islam sesuai ajaran nabi Muhammad SAW dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Abang saya Brigadir Y. Pranata yang selalu memberikan semangat, juga adik saya Azlina Sari semoga engkau juga menjadi Sarjana Sastra yang berguna bagi Nusa dan Bangsa dan Kesuksesan untuk mu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Reisya Ichwani yang sudah membantu dalam diskusi menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Drs, Chairuddin, M.Sc selaku dosen pembimbing saya untuk yang kedua kalinya, semoga Bapak diberikan Nikmat dan Berkah dari Allah SWT atas kebaikan bapak selama membimbing saya selama saya menyelesaikan tugas akhir saya pada studi Diploma III dan sekarang membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Zul Alfian, M.Sc selaku dosen pembimbing II saya yang selalu memberikan arahan dan nasihat dalam penulisan skripsi.Semoga kita semua diberikan nikmat dari Allah SWT.
Saya sangat menyadari atas kekurangan skripsi saya, karena kemampuan dan keterbatasan saya dalam pengetahuan. Oleh karena itu saya mengharapkan masukan dan saran agar skripsi saya dapat diperbaiki dan bermanfaat bagi pembaca.
Medan, Mei 2013
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan Nata De Soya dari air limbah kedelai sebagai adsorben terhadap kation Ca2+dan Mg2+ penyebab air sadah pada bahan baku air boiler di PT SMART TBK. Dalam penelitian dilakukan penentuan massa optimum dari adsorben Nata De Soya yang telah diaktivasi dengan H2SO4 1 N sebelum
THE USE OF SOYBEN WASTE WATER AS AN ADSORBENT OF
MAGNESIUM(Mg
2+) AND CALCIUM(Ca
2+) CATION
THAT CAUSED HARD WATER IN RAW
WATERBOILERS AT
PT SMART TBK
ABSTRACK
The use of Nata de Soya that prepared from soybean wastewater as an adsorbent of
magnesium(Mg2+) and calcium(Ca2+) cations that caused hard water in raw water
boilers at PT SMART TBK has been studied. Nata De Soya has been activated with 1N
H2SO4 prior to use as an adsorbent for cations magnesium(Mg2+) and calcium(Ca2+)
in raw water boilers. The result of the research demonstrated that the optimum mass
of adsorbent to adsorb Ca2+cations at 1.5 grams with adsorption capacity 60.64%,
while for the Mg2+cation optimum adsorbent mass is the mass of 2.5 grams of the
adsorption capacity of 66.34%. The study also made the process of Nata De Soya
adsorbent regeneration that optimum in adsorb Ca2+ and Mg2+ cations. From the
research that regenerated adsorption with adsorbent obtained percentage decrease
DAFTAR ISI
Halaman
Persetujuan ii
Pernyataan iii
Penghargaan iv
Abstrak v
Abstract vi
Daftar Isi viii
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii
Daftar Lampiran xiii
Bab 1 Pendahuluan
1.1. Latar belakang 1
1.2. Permasalahan 3
1.3. Batasan masalah 3 1.4. Tujuan penelitian 4 1.5. Manfaat penelitian 4 1.6. Lokasi penelitian 5 1.7. Metodologi penelitian 5
Bab 2. Tinjauan Pustaka
2.1. Air 6
2.2. Nata De Soya 7 2.2.1. Aktivasi Nata De Soya 10 2.2.2. Regenerasi Nata De Soya 11 2.2.3. Komposisi Nata De Soya 11
2.3. Adsorpsi 13
2.3.1. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Adsorpsi 16 2.4. Air Baku Boiler PT. Smart 17
2.5. Boiler 18
2.5.1. Standar Baku Air Umpan Boiler 20
Bab 3. Metodologi Penelitian
3.1. Alat dan Bahan Penelitian 21
3.1.1. Alat 21
3.1.2. Bahan 22
3.2. Prosedur penelitian 22 3.2.1. Pembuatan larutan 22
3.2.2. Pembuatan Nata De Soya 23
3.2.4. Penentuan Konsentrasi Kesadahan Ca2+ dan Mg2+ pada Sampel Air Baku Boiler Sebelum Penambahan
Adsorben Nata De Soya 24 3.2.4.1. Penentuan kesadahan Total 24 3.2.4.2. Penentuan Konsentrasi Kesadahan Ca2+ 25 3.2.4.3. Penentuan Konsentrasi Kesadahan Mg2+ 25 3.2.5. Adsorpsi Kation Ca2+ dan Mg2+ dengan Adsorben
Nata De Soya 25
3.2.6. Regenerasi Adsorben Nata De Soya yang Jenuh 25 3.2.7. Adsorpsi Kation Ca2+ dan Mg2+ dengan Adsorben
Nata De Soya yang Diregenerasi 26 3.2.8. Penentuan kadar Ca2+ dan Mg2+ dalam Adsorben
Nata De Soya 26
3.2.8.1. Penentuan Kadar Mg2+ dalam Adsorben
Nata De Soya 26
3.2.8.2. Penentuan Kadar Ca2+ dalam Adsorben
Nata De Soya 26
3.3. Bagan Penelitian 27
3.3.1. Pembuatan Nata De Soya 27
3.3.2. Aktivasi Nata De Soya 28 3.3.3. Penentuan Konsentrasi Kesadahan Ca2+ dan Mg 2+
Sebelum Penambahan Adsorben Nata De Soya 29 3.3.3.1. Penentuan kesadahan Total 29 3.3.3.2. Penentuan Konsentrasi Kesadahan Ca2+ 29 3.3.4. Adsorpsi Kation Ca2+ dan Mg2+ dengan Adsorben
Nata De Soya Teraktivasi 30 3.3.5. Regenerasi Adsorben Nata De Soya 31 3.3.6. Adsorpsi Kation Ca2+ dan Mg2+ dengan Adsorben
Nata De Soya yang Diregenerasi 32 3.3.6.1. Penentuan Kesadahan Total 32 3.3.6.2. Penentuan Kesadahan Ca2+ 32 3.3.7. Penentuan kadar Ca2+ dan Mg2+ dalam Adsorben
Nata De Soya 33
3.3.7.1. Penentuan Kadar Mg2+ dalam Adsorben
Nata De Soya 34
3.3.7.2. Penentuan Kadar Ca2+ dalam Adsorben
Nata De Soya 34
Bab 4. Hasil dan pembahasan
4.1. Hasil Penelitian 35 4.1.1. Data Penentuan Kadar Kation Kalsium dan Magnesium
pada Adsorben Nata De Soya 35
4.1.2. Persentase (%) Penurunan Optimum Konsentrasi
Kesadahan Ca2+ 37 4.1.4. Persentase (%) Penurunan Optimum Konsentrasi
Kesadahan Mg2+ 37
4.1.4. Persentase (%) Penurunan Kation Kalsium dan
Magnesium dengan Adsorben Regenerasi 38
4.2. Pembahasan 39
Bab 5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan 43
5.2. Saran 43
Daftar Pustaka 44
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Limbah Cair 9 Tabel 2.2 Standar Baku Air Umpan Boiler 20 Tabel 4.1 Data Kesadahan Megnesium dan Kalsium Sebelum Menggunakan
Adsorben Nata De Soya 35 Tabel 4.2 Data Adsorbsi Kation Magnesium dan Kalsium Sesudah
Menggunakan Adsorben Nata De Soya 35 Tabel 4.3 Data Kesadahan Megnesium dan Kalsium Sebelum Perlakuan
Dengan Adsorben Nata De Soya Regenerasi 36 Tabel 4.4 Data Adsorpsi Kesadahan Kalsium dan Magnesium dengan
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Rumus Molekul Selulosa 12 Gambar 2.2 Membran Reverse Osmosis 18 Gambar 4.1 Kurva Grafik Batang Adsorpsi Dengan Adsorben Nata De Soya
Regenerasi 40
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Larutan H2SO41 N 48
Lampiran 2. Data Standarisasi Na2EDTA dengan Larutan Pembaku
CaCO30,01 M 49
Lampiran 3. Data Penentuan Kation Kalsium dan Magnesium pada Perlakuan
Massa Adsorben 50
Lampiran 4. Data Adsorbsi dengan Penggunaan Adsorben Nata De Soya
Yang Diregenerasi 52 Lampiran 5. Foto Proses Penelitian 53
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan Nata De Soya dari air limbah kedelai sebagai adsorben terhadap kation Ca2+dan Mg2+ penyebab air sadah pada bahan baku air boiler di PT SMART TBK. Dalam penelitian dilakukan penentuan massa optimum dari adsorben Nata De Soya yang telah diaktivasi dengan H2SO4 1 N sebelum
THE USE OF SOYBEN WASTE WATER AS AN ADSORBENT OF
MAGNESIUM(Mg
2+) AND CALCIUM(Ca
2+) CATION
THAT CAUSED HARD WATER IN RAW
WATERBOILERS AT
PT SMART TBK
ABSTRACK
The use of Nata de Soya that prepared from soybean wastewater as an adsorbent of
magnesium(Mg2+) and calcium(Ca2+) cations that caused hard water in raw water
boilers at PT SMART TBK has been studied. Nata De Soya has been activated with 1N
H2SO4 prior to use as an adsorbent for cations magnesium(Mg2+) and calcium(Ca2+)
in raw water boilers. The result of the research demonstrated that the optimum mass
of adsorbent to adsorb Ca2+cations at 1.5 grams with adsorption capacity 60.64%,
while for the Mg2+cation optimum adsorbent mass is the mass of 2.5 grams of the
adsorption capacity of 66.34%. The study also made the process of Nata De Soya
adsorbent regeneration that optimum in adsorb Ca2+ and Mg2+ cations. From the
research that regenerated adsorption with adsorbent obtained percentage decrease
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Kesadahan air merupakan masalah utama yang harus dihilangkan dalam proses
pengolahan air industri. pengolahan air industri yang banyak dilakukan yaitu untuk
proses menghasilkan uap air atau steam. Air yang digunakan biasanya berasal dari air
tanah, dimana air tanah mengandung padatan terlarut yang tinggi. Magnesium dan
kalsium merupakan padatan yang mendominasi dari air sumur. Kelarutan Magnesium
dan Kalsium dalam air berbanding terbalik dengan temperatur, dimana semakin tinggi
temperatur maka semakin tidak larut mineral penyebab kesadahan dalam air. Masalah
yang ditimbulkan dari tingginya kadar kesadahan dalam air antara lain terjadinya
pembentukan kerak pada sistem perpipaan boiler yang berakibat proses perpindahan
panas kurang baik, overheating dan dapat menyebabkan pipa dan tungku boiler pecah.
(PT. Lonsum, 2008)
Berbagai metode telah diaplikasikan untuk mengurangi kadar Kalsium dan
Magnesium sebagai pembentuk kesadahan, antara lain: Presipitasi dengan bahan
kimia seperti Natrium Karbonat. Dengan penambahan Natrium Karbonat maka air
sadah tetap yang terbentuk dari garam Klorida dan Sulfat akan dapat terendapkan
menjadi kalsium karbonat. Kalsium akan mengendap sebagai Kalsium Karbonat. Sifat
dari proses pelunakan dengan cara ini cepat (1 sampai 2 jam) dapat bersamaan dengan
flokulasi, cara sederhana, efesiensi cukup tinggi, dan harga murah, namun memiliki
kekurangan yaitu penambahan bahan kimia yang banyak dapat merusak ekosistem
lingkungan hidup. Metode lain yang digunakan yaitu dengan proses penukar ion,
media yang digunakan yaitu resin. Pada saat proses pelunakan air sadah dengan resin
penukar ion, maka ion yang terlarut dalam air akan teresap kedalam resin, dan resin
dan tidak dapat bersamaan dengan proses lain, operasi rumit dan membutuhkan biaya
yang sangat mahal.
Telah dilakukan penelitian oleh Afrizal (2007) dalam pemanfaatan selulosa
bakterial Nata De Coco sebagai adsorben pada proses adsorpsi logam Cr (III). Hasil
adsorpsi yang terbaik yaitu pada konsentrasi 150 ppm dimana jumlah logam Kromium
(III) yang teradsorpsi sebesar 2,67 mg/g adsorben. Menurut Sulistiyana (2010) dalam
penelitiannya, studi pendahuluan adsorpsi kation Kalsium dan Magnesium selulosa
bakterial Nata De Coco dengan menggunakan metode Batch, dimana larutan standar
Kalsium mampu diserap oleh adsorben selulosa bakterial Nata De Coco dengan
kapasitas adsorpsi 27,466 mg/g, dari konsentrasi awal 400 mg/L, sedangkan untuk
logam magnesium kapasitas adsorpsi 18,94 mg/g dengan konsentrasi awal 300 mg/L.
Industri pengolahan tahu menghasilkan limbah air tahu yang berupa whey
tahu. Jika penanganan limbah tersebut tidak baik, limbah air tahu tersebut akan
mencemari lingkungan. Asam organik yang terkandung di dalam limbah akan
menimbulkan bau asam. Air limbah tahu juga mengandung gula,tetapi kadarnya
rendah (0,7-9%). Kandungan dalam air tahu tersebut sangat memungkinkan limbah
tersebut diolah secara fermentasi untuk membentuk Nata De Soya.
(http://elradhie91.blogspot.com201209v-behaviorurldefaultvmlo.html)
Selulosa bakteri memiliki kemurnian yang tinggi dibandingkan dari selulosa
yang berasal dari tanaman, dimana serat selulosa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
yang mengandung hemiselulosa dan lignin sulit untuk dihilangkan (Bielecki1, 2004).
Menurut Syarfi,(20007) pohon, kayu dan daun jika terdekomposisi didalam air maka
akan menyebabkan perubahan warna air menjadi coklat kemerahan karena kandungan
asam organik tersebut.
Masalah yang muncul dari penggunaan bioadsorben seperti Nata De Soya,
adalah pada kondisi jenuh maka adsorben akan dibuang menjadi limbah. Salah satu
cara untuk menanggulanginya adalah dengan proses regenerasi. Proses regenerasi
adsorben dilakukan untuk memperbaiki kembali daya adsorpsi dari adsorben. Telah
dilakukan penelitian oleh Yefrida (2008) dimana ia meregenerasi serbuk gergaji
dengan konsentrasi HCl 0,6 M. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan pemanfaatan Nata De Soya dari limbah air kedelai
teraktivasi sebagai adsorben untuk menyerap kation Magnesium dan Kalsium pada air
baku boiler dan melakukan regenerasi pada Nata De Soya yang jenuh dengan
mengaktivasi kembali dengan H2SO4 1 N.
1.2. Permasalahan
1. apakah Nata de Soya yang telah diaktivasi dapat digunakan sebagai
adsorben untuk menyerap kation Magnesium (Mg2+) dan kation Kalsium
(Ca2+) yang terdapat dalam sampel air bahan baku boiler.
2. Untuk mengetahui apakah Nata de Soya teraktivasi H2SO41N yang telah
jenuh dapat diregenerasi kembali untuk menyerap kation - kation
Magnesium (Mg2+) dan kation Kalsium (Ca2+) yang terdapat dalam sampel
air bahan baku boiler.
3. Untuk mengetahui berapa berat Nata de Soya yang mampu menyerap kation
Magnesium (Mg2+) dan kation Kalsium (Ca2+) secara optimum yang
terdapat dalam sampel air bahan baku boiler.
1.3. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada :
1. Kation pada air sadah yang ditentukan hanya kation Magnesium (Mg2+) dan
kation Kalsium (Ca2+)
2. Penentuan kandungan kation Magnesium ( Mg2+ ) dan kation Kalsium
(Ca2+) yang terdapat dalam air bahan baku boiler dilakukan sebelum dan
sesudah diadsorpsi dengan Nata de Soya yang telah diaktivasi dengan
3. Metode yang digunakan dalam penentuan kation Magnesium (Mg2+) dan
kation Kalsium (Ca2+) adalah metode titrimetri.
4. Waktu kontak antara adsorbat dengan adsorben selama 30 menit
5. Aktivasi Nata De Soya dengan H2SO4 selama 1 jam dan pada suhu kamar
tanpa pemanasan
6. Acetobacter xylinum yang digunakan dari daerah Tembung
7. Air limbah rebusan kedelai dari pembuatan tahu yang digunakan dalam
pembuatan Nata dari daerah kecamatan Karang sari
1.4. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui apakah Nata de Soya yang telah diaktivasi dapat
digunakan sebagai adsorben untuk menyerap kation Magnesium (Mg2+) dan kation
Kalsium( Ca2+) yang terdapat dalam sampel air bahan baku boiler.
2. Untuk mengetahui apakah Nata de Soya teraktivasi H2SO4 yang telah jenuh
dapat diregenerasi kembali untuk menyerap kation kation Magnesium (Mg2+) dan
kation Kalsium (Ca2+) yang terdapat dalam sampel air bahan baku boiler.
3. Untuk mengetahui berapa berat Nata de Soya yang mampu menyerap kation
Magnesium (Mg2+) dan kation Kalsium (Ca2+) secara optimum yang terdapat
dalam sampel air bahan baku boiler.
4. Untuk mengetahui apakah di dalam adsorben Nata De Soya terdapat kation
Kalsium( Ca2+) dan Magnesium (Mg2+).
1.5. Manfaat penelitian
Dari limbah cair hasil buangan air kedelai dalam pembuatan tahu diharapkan dapat
memberikan informasi sebagai adsorben penyerap kation kation Magnesium (Mg2+)
dan kation Kalsium (Ca2+) yang akan digunakan sebagai air umpan boiler.
1.6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di laboratorium ilmu dasar Universitas Sumatera Utara dan
laboratorium PT SMART TBK
1.7. Metodologi Penelitian
Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium yaitu dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana Nata de Soya yang diaktivasi dengan asam sulfat 1 N dapat
digunakan sebagai penyerap kation Kalsium (Ca2+) dan kation Magnesium (Mg2+)
pada sampel bahan baku air boiler di PT SMART TBK, kemudian untuk mengetahui
apakah Nata de Soya yang sudah jenuh sebagai penyerap kation Kalsium (Ca2+) dan
kation Magnesium (Mg2+) pada sampel bahan baku air boiler di PT SMART TBK,
dapat diregenerasi kembali. Tahap Penelitian Meliputi :
1. Pembuatan Nata de Soya dari limbah cair rebusan kedelai
2. Aktivasi Nata de Soya dengan asam sulfat 1 N
3. Penyerapan kation Kalsium (Ca2+) dan kation Magnesium (Mg2+) pada
sampel bahan baku air boiler,dan pengukuran kation Kalsium (Ca2+) dan kation
Magnesium (Mg2+) secara titimetri dimana pengukuran kation-kation tersebut
dilakukan sebelum dan sesudah penambahan adsorben Nata De Soya
4. Proses regenenerasi dari adsorben Nata de Soya yang telah jenuh dan
diaktivasi kembali dengan asam sulfat 1 N dan menggunakan nya kembali sebagai
adsorben untuk menyerap kembali kation Kalsium (Ca2+) dan kation Magnesium
(Mg2+) pada sampel bahan baku air boiler
Adapun parameter yang digunakan sebelum regenerasi Nata De Soya antara lain :
1. Variabel tetap yaitu konsentrasi kation Kalsium (Ca2+) dan kation Magnesium
2. Variabel bebas yaitu massa Nata De soya yang akan digunakan sebagai
pengadsorpsi kation Kalsium (Ca2+) dan kation Magnesium (Mg 2+) yaitu dengan
massa (0,5 ; 1,0 ; 1.5 ; 2,0 ; 2.5 ; 3,0 ; dan 3.5 g )
Setelah kondisi dari adsorben Nata de Soya jenuh dilakukan regenerasi adsorben Nata
de Soya kembali dengan cara mengaktivasi kembali Nata de Soya dengan
menggunakan H2SO4 1 N dan melakukan pengadsorpsian kembali terhadap kation
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Air
Air tawar berasal dari dua sumber yaitu air permukaan dan air tanah. Air tanah
merupakan air yang berada dibawah permukaan tanah. Kation yang mendominasi
perairan tawar adalah Kalsium dan Magnesium sedangkan pada perairan laut adalah
Sodium dan Magnesium. Kandungan Kalsium pada perairan tawar sekitar 60,9% dan
Magnesium sekitar 19,0%.
Kalsium karbonat (HCO3) merupakan senyawa yang memberikan kontribusi
besar terhadap kesadahan di perairan tawar. Senyawa ini terdapat di dalam tanah
dalam jumlah yang berlimpah sehingga kadarnya di dalam perairan tawar cukup
tinggi. Kelarutan Kalsium Karbonat menurun dengan meningkatnya suhu dan akan
meningkat dengan keberadaan Karbondioksida. Kalsium Karbonat bereaksi dengan
Karbondioksida dan akan membentuk senyawa Kalsium Bikarbonat (Ca(HCO3)2)
yang memiliki daya larut lebih tinggi dibandingkan dengan Kalsium karbonat
(CaCO3). Tingginya kadar Bikarbonat di perairan disebabkan oleh ionisasi asam
Karbonat, terutama pada perairan yang banyak mengandung Karbondioksida.
Karbondioksida diperairan bereaksi dengan basa yang terdapat pada batuan dan tanah
membentuk Bikarbonat seperti reaksi dibawah ini :
CaCO3 + CO2 + H2O Ca2+ + 2HCO3-
CaMg(CO3)2 + 2 CO2 + 2H2O Ca2+ Mg2+ + 4HCO3-
NaAlSi3O2 + CO2 + 5 H2O Na+ + HCO-3 + 2H4SiO4 + Al2SiO3.
Nilai kesadahan yang baik berkisar antara 30 – 500 mg/L CaCO3. Perairan dengan
nilai kesadahan > 40 mg/L CaCO3 disebut dengan perairan sadah, sedangkan perairan
yang paling berlimpah adalah Kalsium dan Magnesium sehingga kesadahan pada
dasarnya ditentukan oleh jumlah Kalsium dan Magnesium. Keberadaan kation yang
lain seperti Besi dan Mangan memberikan kontribusi bagi nilai kesadahan, walaupun
peranannya kecil sehingga sering diabaikan (Effendi, H. 2003).
2.2 Nata De Soya
Nata de Soya adalah biomassa yang sebagian besar terdiri dari selulosa, berbentuk
agar dan berwarna putih. Massa ini berasal dari pertumbuhan Acetobacter xylinum
pada permukaan media cair yang asam dan mengandung gula.
Nata de soya dapat dibuat dari limbah cair pengolahan tahu dan tempe. Nata
yang dibuat dari air kelapa disebut nata de Coco, dan yang dari whey tahu atau tempe
disebut nata de soya. Bentuk, warna, tekstur dan jenis nata tersebut tidak berbeda.
Pembuatan nata de soya tidak sulit dan biaya yang dibutuhkan juga tidak banyak.
Usaha pembuatan nata merupakan alternatif usaha yang cukup menjanjikan.
Fermentasi nata dilakukan melalui tahap-tahap pemeliharaan biakan murni,
pembuatan starter, fermentasi.
a) Pemeliharaan biakan murni Acetobacter xylinum
Fermentasi nata memerlukan biakan murni Acetobacter xylinum. Biakan murni ini
harus dipelihara sehingga dapat digunakan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan yaitu
proses penyimpanannya dimana biasanya disimpan pada agar miring yang terbuat
dari media Hassid dan Barker yang dimodifikasi dengan komposisis glukosa (100 g),
ekstrak khamir (2,5 g) Kalium Hidrogen Posfat (K2HPO4) 5 g Amonium sulfat (0,6 g)
Magnesium sulfat (0,2 g) agar (18 g) dan air kelapa (1 liter). Pada agar miring dengan
suhu penyimpanan 4-7 Co mikroba ini disimpan selama 3-4 minggu.
b) Pembuatan starter
Starter adalah populasi mikroba dalam jumlah kondisi fisiologis yang siap di
inokulasikan pada media fermentasi. Volume starter disesuaikan dengan volume
media fermentasi yang akan disiapkan. Dianjurkan volume yang akan digunakan tidak
c) Fermentasi
fermentasi dilakukan pada media cair yang telah di inokulasikan dengan starter.
Fermentasi berlangsung pada kondisi aerob. Fermentasi dilangsungkan sampai nata
yang terbentuk 1,0-1,5 cm. Biasanya untuk ukuran tersebut setelah 10 hari. Lapisan
nata mengandung sisa media yang sangat masam. Lapisan nata adalah massa mikroba
berkapsul dari selulosa (http:/ ristek.go.id).
Dari hasil uji balai laboratorium kesehatan semarang, (pranoto, 2009)
menyebutkan komposisi dari limbah cair kedelai pada tabel 2.1.
Tabel 2.1. Komposisi dari limbah cair
Parameter Kadar
Protein 0,42% Lemak 0,13%
Karbohidrat 0,11%
Air 98.87%
Kalsium 13,60 (ppm)
Besi 4,55 (ppm)
(http//www.scribd.com )
Selulosa yang terbentuk oleh bakteri Acetobacter xylinum pada proses
fermentasi air limbah tahu melalui reaksi polimerisasi dari glukosa. Reaksi secara
umum terbentuknya selulosa dari glukosa dapat dilihat pada gambar
Glukosa akan membentuk selulosa dengan reaksi polimerisasi melalui reaksi
kondensasi. Dalam air limbah tahu kandungan glukosa didalamnya rendah sehingga
dalam proses pembuatannya harus ditambahkan sukrosa. Sukrosa akan mengalami
hidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa.
C2H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Sukrosa glukosa fruktosa
2.2.1 Aktivasi Nata De Soya
Selulosa bakterial nata de coco dapat diaktivasi dengan menggunakan asam sulfat 1 N.
Sulistiana telah melakukan aktivasi nata dengan asam sulfat 1 N, dimana tujuannya
untuk memperpendek rantai selulosa bakterial nata de coco. Dimana pada proses
reaksi penyerapan ion Kalsium dan Magnesium pada logam standart dengan metode
batch dijelaskan bahwa reaksi yang terjadi akan menghasilkan gugus-gugus hidroksil
bebas intraseluler maupun ekstraseluler bakterial nata de coco akan berikatan dengan
logam standar. Aktivasi degradasi mekanik yaitu dengan degradasi mekanik dimana
nata de coco akan di blender sehingga memperluas permukaaan selulosa bakterial nata
de coco (Sulistiyana, 2010).
Aktivasi adalah suatu perubahan fisika dimana permukaan karbon itu menjadi
jauh lebih banyak karena hidrokarbonnya disingkirkan. Ada beberapa metode yang
dapat digunakan dalam melakukan aktivasi. Cara yang paling umum adalah perlakuan
bahan berkarbon dengan gas pengoksidasi seperti udara, uap atau karbon dioksidasi,
dan karbonisasi bahan baku dengan bahan kimia seperti seng klorida atau asam posfat.
Metode aktivasi kimia masih banyak digunakan dieropa dan negara-negara lain.
Amoco telah mengembangkan karbon aktif berbentuk serbuk yang mempunyai luas
permukaan 200 sampai 400 kali lebih besar dari jenis yang biasa.
Aktivasi dengan oksidasi gas dengan menggunakan bahan yang telah
dikarbonisasi pada suhu yang cukup tinggi. Sehingga hampir semua penyusunnya
yang dapat menguap terdekomposisi. Bahan hasil karbonisasi itu mengalami aksi gas
oksidasi, biasanya uap atau karbondioksida didalam tanur pada suhu 800-9800C.
dicampurkan dengan bahan kimia, lalu dikeringkan dan dikarbonisasi pada suhu
sampai 8500C (Austin.G.T, 1996).
Umumnya adsorben dari bahan alam diaktivasi terlebih dahulu untuk
meningkatkan kinerjanya. Aktivasi adsorben bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
dan efesiensi adsorpsi dari adsorben. Aktivasi dapat dilakukan dengan memberi
perlakuan kimia seperti direaksikan dengan asam dan basa juga dengan perlakuan
fisika seperti pemanasan dan pencucian. Biomassa seperti kulit singkong dapat dicuci
dengan asam untuk mengaktivasi selulosanya (Dewi.IR, 2005).
2.2.2 Regenerasi Nata De Soya
Regenerasi bertujuan untuk memanfaatkan bioadsorben agar tidak menjadi limbah
lingkungan kembali. Regenerasi merupakan penarikan kembali logam-logam yang
telah terikat pada gugus fungsi adsorben yang dapat dilakukan dengan penambahan
atau pencucian adsorben dengan larutan HCl, HNO3, EDTA, dan H2SO4. Regenerasi
bioadsorben merupakan faktor yang penting untuk menekan biaya proses pengolahan
limbah dan kemungkinan untuk mendapatkan logamnya kembali. Logam yang
teradsorpsi kedalam bioadsorben didesorpsi sehingga bioadsorben dapat digunakan
kembali sebagai penyerap.
Regenerasi bioadsorben merupakan pilihan terbaik bagi lingkungan dan disukai
secara ekonomi karena dapat meminimalkan penggunaan bahan baku baru,
mengurangi kebutuhan untuk proses daur ulang atau pembuangan. Telah dilakukan
pemanfaatan serbuk gergaji kayu meranti sebagai penyerap Kadmium dan kemudian
diregenerasi kembali dengan asam sulfat dan asam klorida. Dimana kapasitas
penyerapan serbuk gergaji yang diregenerasi dengan asam tersebut tidak berbeda jauh
dengan kapasitas penyerapan serbuk gergaji awal. (yefrida, 2008)
2.2.3 Komposisi Nata De Soya
Nata de soya biomassa yang terdiri dari selulosa. Dari hasil analisa gizi nata de soya
tergolong produk pangan yang bergizi terutama pada kandungan serat kasar. Data dari
dapat digunakan menjadi suatu produk bernilai. Selulosa merupakan polimer yang
paling melimpah di alam. Nama Selulosa diciptakan oleh Anselme Payen, seorang
ahli kimia fisika dan matematika Perancis. Selulosa adalah bahan utama dari tanaman
berkayu, yang memiliki keragaman aplikasi yang berkisar dari perumahan ke kertas
dan tekstil. Dapat dikatakan, selulosa adalah salah satu senyawa kimia yang paling
berpengaruh dalam sejarah budaya manusia. Biasanya selulosa disertai berbagai zat
lain, seperti lignin, di dinding sel tumbuhan matriks. Dalam spesies tertentu, seperti
kapas, selulosa terdapat dalam bentuk murni tanpa bahan tambahan dan dalam
beberapa kasus, seperti alga Valonia, selulosa hampir benar-benar dalam bentuk
kristal.(Kontturi,E.J.,2005).
Selulosa adalah bagian dari struktur material kayu dan tumbuh-tumbuhan.
Kapas adalah selulosa murni yang terkenal. Selulosa merupakan salah satu jenis
polisakarida. Dalam selulosa, molekul glukosa dalam bentuk rantai panjang tidak
bercabang yang mirip dengan amilosa. Bagaimanapun, unti-unit dari glukosa dalam
selulosa terikat pada ikatan β-1,4-ikatan glikosidik. Isomer β tidak membentuk gulungan seperti isomer α, tetapi selaras dalam baris paralel oleh ikatan hidrogen diantara kelompok hidroksil pada rantai yang berdekatan. yang mana membuat
selulosa tidak dapat larut dalam air. Ini memberikan struktur rigis ke dinding sel kayu
dan serat yang lebih tahan terhadap hidrolisis daripada pati. (Timberlake,K.C.,2008).
Gambar 2.1 Rumus Molekul Selulosa
Selulosa bakteri merupakan eksopolisakarida yang diproduksi oleh berbagai
jenis bakteri, seperti Gluconacetobacter (sebelumnya Acetobacter), Agrobacterium,
Aerobacter, Achromobacter, Azotobacter, Rhizobium, Sarcina, dan Salmonella.
oleh AJ Brown. Dia mengamati bahwa sel-sel istirahat Acetobacter memproduksi
selulosa dengan adanya oksigen dan glukosa.
Rumus molekul selulosa bakteri (C6H10O5) n sama dengan selulosa yang
berasal dari tanaman, tetapi secarafisik keduanya memiliki fitur kimia yang berbeda.
Bakteri selulosa lebih disukai daripada selulosa tanaman karena dapat diperoleh dalam
kemurnian lebih tinggi dan menunjukkan tingkat polimerisasi dan kristalinitas yang
lebih tinggi. Ia juga memiliki keuatan tarik dan kapasitas menahan air lebih tinggi
dibandingkan dengan selulosa tanaman(ChawlaP.R.et al,2008). Selulosa bakteri lebih
cocok digunakan untuk memproduksi membran audio berkualitas tinggi, kertas
berkualitas tinggi, fuel-cell, makanan hidangan penutup, material medis seperti
obat-obatan dressing luka(Czaja,N.et al.,2005).
Sebagai salah satu sumber selulosa yang dihasilkan dalam skala ilmiah,
selulosa bakteri, diproduksi secara ektraselular contohnya Acetobacter Xylinum.
Bakteri gram negatif Acetobacter Xylinum merupakan contoh selulosa sintesis dari
bakteri prokariotik. Ini ditemukan sebagai lembaran gelatin pada permukaan yang siap
dibudidayakan didalam Laboratorium sebagai sumber selulosa murni
(Aspinall,G.O.,1983). Di Jepang, matriks selulosa bakteri sebagai limbah industri
digunakan sebagai bahan pembuatan cuka tradisional (Ozawa,Y.et al.,2006).
2.3. Adsorpsi
adsorpsi adalah proses pemisahan dimana komponen tertentu dari suatu fase fluida
berpindah permukaan zat padat yang menyerap. Biasanya partikel-partikel kecil zat
penyerap ditempatkan didalam suatu hamparan tetap, dan fluida lalu dialirkan melalui
hamparan itu sampai zat padat itu mendekati jenuh dan pemisahan yang dikehendaki
tidak dapat lagi berlangsung. Kebanyakan zat pengadsorpsi atau adsorben adalah
bahan-bahan yang berpori, dan adsorpsi berlangsung terutama pada dinding-dinding
pori atau pada letak tertentu didalam partikel itu. Oleh karena pori-pori itu biasanya
sangat kecil, luas permukaan dalam menjadi beberapa orde besaran lebih besar dari
permukaan luar dan bisa sampai 2.000m2/g. Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot
komponem itu secara menyeluruh dan fluida tanpa terlalu banyak adsorpsi terhadap
komponen lain. Regenerasi adsorben dapat dilaksanakan kemudian untuk
mendapatkan adsorbat dalam bentuk terkonsentrasi. (Mccabe.W.L, 1999)
Adsorben pertama kali yaitu karbon aktif yang digunakan dalam topeng gas
dalam perang dunia I. Akan tetapi pengetahuan bahwa karbon hasil dekomposisi kayu
dapat menyingkirkan bahan-bahan berwarna dan larutan sawah sudah ada sejak abad
ke lima belas. Namun penerapan adsorben pertama kali dari arang aktif secara
komersial baru dilakukan pada tahun 1794, ketika arang kayu digunakan oleh sebuah
pabrik gula diinggris.(Austin.T.G, 1996).
Adsorpsi dari fase zat cair digunakan untuk memisahkan komponen-komponen
organik dari limbah-limbah air, ketakmurnian berwarna dari larutan gula dari minyak
nabati, dan air dari zat cair organik. Suatu contoh penting mengenai adsorpsi fase zat
cair ialah penggunaan karbon aktif untuk membersihkan zat pencemar dari limbah air.
Adsorben karbon juga digunakan untuk membersihkan zat organik runutan dari air
untuk konsumsi kota, sehingga senyawa beracun dapat dihilangkan (Mccabe,W.L,
1999).
Ditinjau dari jenis ikatan antara bahan yang akan dipisahkan dan bahan adsorpsi dapat
dibedakan menjadi dua proses yaitu adsorpsi dan absorpsi. Adsorpsi adalah
pengikatan bahan pada permukaan adsorben padat dengan cara pelekatan, absorpsi
adalah pengikatan bahan pada permukaan adsorben cair dengan cara pelarutan.
(Bernasconi.G,1995).
Proses adsorpsi pada selulosa dan lignin melibatkan gugus fungsi dari hidroksi dan
karboksilat dalam bioadsorben. Ion dalam larutan akan akan terikat pada bioadsorben
dan menggeser ion yang sama tandanya. Bila larutan ion dialirkan pada suatu
bioadsorben maka ion hidrogen adsorben bertukar dengan kation, dan ion hidroksi
akan bertukar dengan anion. (Munaf,et al.,1998).
Adsorpsi adalah suatu proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cair,
bahan yang harus dipisahkan ditarik oleh permukaan adsorben padat dan diikat oleh
Sifat selektivitas yang tinggi, proses adsorpsi sangat sesuai untuk memisahkan
bahan dengan konsentrasi yang kecil dari campuran yang mengandung bahan lain
yang berkonsentrasi tinggi.
Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang sangat besar.
Permukaan yang sangat luas ini terbentuk karena banyaknya pori yang halus pada
padatan tersebut. Biasanya luas permukaan berada dalam orde 200-100 m2/g adsorben,
dan diameter pori 0,0003-0,02 µm. Disamping luas spesifik dan diameter pori, maka
kerapatan, distribusi ukuran partikel maupun kekerasaannya merupakan data
karakteristik yang penting dari suatu adsorben. Tergantung pada tujuan
penggunaannya, adsorben dapat berupa granulat (dengan ukuran butir sebesar
beberapa mm) atau serbuk (khusus untuk adsorpsi campuran cair).
Jenis adsorpsi ada dua macam :
1. Adsorpsi Fisik ditandai dengan ciri-ciri :
- Panas adsorpsi kurang dari 40 KJ/mol
- Adsorpsi berlangsung pada suhu rendah
- Kesetimbangan adsorpsi reversible dan cepat
- Tidak ada energi aktivasi yang terlibat dalam proses ini
- Terjadi lapisan/adsorpsi multi lapis
2. Adsorpsi Kimia ditandai dengan ciri-ciri:
- Panas adsorpsi lebih besar dari ± 80 KJ/mol
- Adsorpsi berlangsung pada temperatur tinggi
- Kesetimbangan adsorpsi irreversible
- Energi Aktivasi mungkin terlibat didalam proses ini
- Terjadi adsorpsi monolapisan
(Gordon, M. Barrow, 1997)
Proses adsorpsi tergantung pada sifat zat padat yang mengadsorsi, sifat atom
molekul yang diserap, konsentrasi, temperatur dan lain lain-lain. Pada Proses adsorpsi
1. Transfer molekul-molekul zat terlarut yang teradsorpsi menuju lapisan film yang
mengelilingi adsorben.
2. Difusi zat telarut yang teradsorsi melalui lapisan film.
3. Difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui kapiler/pori dalam adsorben.
4. Adsorpsi Zat terlarut yang teradsorpsi pada dinding pori atau permukaan
adsorben.
2.3.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Adsorpsi
Proses adsorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut akan
menentukan kecepatan adsorspsi, kinetika adsorpsi serta kualitas bahan yang
diadsorpsi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses
adsorpsi.
1. Kecepatan Pengadukan (Agitasi)
Kecepatan Pengadukan berpengaruh pada kecepatan proses adsorpsi dan
kualitas bahan yang dihasilkan. Jika pengadukan terlalu lambat maka proses
akan berjalan lambat juga, tetapi jika pengadukan terlalu cepat maka akan
muncul kemungkinan struktur adsorbat mengalami kerusakan.
2. Luas Permukaan
Semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak zat yang teradsorpsi.
3. Jenis dan Karakteristik Adsorben
Jenis adsorben yang digunakan umumnya adalah karbon aktif. Ukuran partikel
dan luas permukaan karbon aktif akan menentukan tingkat dan kemampuan
adsorpsi. Ukuran partikel karbon mempengaruhi tingkat adsorpsi yaitu tingkat
adsorpsi yaitu tingkat adsorpsi naik jika ukuran partikel kecil. Oleh karena itu
adsorpsi biasanya menggunakan karbon PAC (Powder Activated Carbon)
lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan karbon granular. Kemampuan
dari adsorpsi akan meningkat jika memiliki polarisabilitas dan berat molekul
yang tinggi.
Senyawa yang terlarut memiliki gaya tarik-menarik yang kuat terhadap
pelarutnya sehingga lebih sulit diadsorpsi dibandingkan senyawa yang tidak
larut.
5. pH
Tingkat keasamaan adsorbat berpengaruh terhadap proses adsorpsi. Asam
organik lebih mudah teradsorpsi pada pH rendah, sdangkan adsorpsi untuk
senyawa basa organik lebih efektif pada suhu tinggi.
6. Temperatur
Naik turunnya tingkat adsorpsi dipengaruhi oleh temperatur. Pemanasan
adsorben akan menyebabkan pori-pori adsorben terbuka sehingga daya
serapnya meningkat, tetapi pemanasan yang terlalu tinggi juga membuat
struktur adsorben rusak sehingga daya serapnya menurun.
2.4 Air Baku Boiler Pt Smart
PT. Smart, Tbk unit Belawan memiliki beberapa unit proses pengolahan diantaranya
Refinery Plant, Fractionation Plant, Marsho Plant, Filling Plant, KCP Plant dan CBS
Plant. Semua plant proses pengolahan tersebut bertanggung jawab untuk mengolah
bahan baku menjadi produk akhir melalui proses produksi yang efektif dan efisien.
Salah satu unit yang berperan penting terhadap kelancaran proses utility dimana utility
berperan penting sebagai pemasok steam untuk kepentingan produksi setiap hari.
Water Treatment Plant bertugas mempersiapkan, menghasilkan dan
mendistrubusikan kebutuhan air bersih dan air RO (Reverse Osmosis) untuk keperluan
industri. Air yang digunakan mutu dan kualitasnya harus memenuhi standar agar tidak
menimbulkan dampak atau efek yang merugikan. Sumber air bersih berasal dari air
tanah yang diperoleh melalui sumur bor. Lokasi pengeboran air berada didaerah air
payau. Air tersebut diolah lebih lanjut dengan metode reverse osmosis menjadi air
RO. Air RO digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses produksi, bahan baku
pembuatan steam. Pada prosesnya sebelum masuk ke proses reverse osmosis air baku
kondisi jenuh resin tersebut diregenerasi dengan menggunakan natrium klorida jenuh.
Membran RO yang digunakan tersebut terdiri dari tiga lapisan, lapisan pertama
berupa lapisan penahan yang terbuat dari poliamida aromatik. Lapisan ini memiliki
fluks air tinggi dan kemampuan menyaring garam dan silika serta tahan terhadap
bahan kimia. Lapisan kedua berupa lapisan mikropori tebal yang terbuat dari
polisulfon yang berfungsi untuk membantu lapisan penahan. Lapisan ketiga berupa
polisufon yang terbuat dari nonwoven polyester yang merupakan pondasi utama
[image:33.595.124.490.313.485.2]struktur membran.
Gambar 2.2. Membran Reverse Osmosis
2.5. Boiler
Boiler adalah bejana tertutup yang terdiri atas sistem air umpan, sistem steam dan
sistem bahan bakar. Panas pembakaran dari sistem bahan bakar dialirkan ke air
sampai terbentuk air panas hingga air menghasilkan uap air atau steam. Uap air atau
steam pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan steam ke suatu
proses lainnya. Air adalah media yang digunakan oleh boiler untuk melakukan proses
penguapan disamping itu harganya juga murah dan steam dari boiler dapat digunakan
Boiler bekerja mengkonversi panas yang dihasilkan bahan bakar ke dalam
bentuk uap yang mengandung entalphy, yang kemudian digunakan untuk
menggerakkan turbin uap. Bagian-bagian boiler antara lain
a. Ruang Bakar.
b. Pensuplai Udara Pembakaran.
c. UpperDrum.
d. LowerDrum.
e. Pipa Air.
f. Superheater.
g. Penangkap Abu Pembakaran.
h. Cerobong Asap (Chimney).
i. ShootBlowing.
j. SafetyDevices
Safety devices adalah kelengkapan boiler yang harus ada untuk menjamin
keamanan dalam pengoperasiannya. Safetydevice ini terdiri atas:
SafetyValve.
SightGlass.
PressureGauge.
WaterLevelControl.
Air yang digunakan pada proses pengolahan dan air umpan boiler diperoleh
dari air sungai, air waduk, sumur bor dan sumber mata air lainnya. Kualitas air
tersebut tidak sama walaupun menggunakan sumber air sejenis, hal ini dipengaruhi
oleh lingkungan asal air tersebut. Sumber mata air sungai umumnya sudah mengalami
pencemaran oleh aktivitas penduduk dan kegiatan industri, oleh sebab itu perlu
dilakukan pemurnian. Air umpan boiler harus memenuhi spesifikasi yang telah
ditentukan agar tidak menimbulkan masalah-masalah pada pengoperasianboiler. Air
tersebut harus bebas dari mineral-mineral yang tidak diinginkan serta
Dalam deaerasi gas terlarut, seperti oksigen dan karbondioksida, dibuang
dengan pemanasan awal air umpan sebelum masuk ke boiler. Seluruh air alam
mengandung gas terlarut dalam larutannya. Gas-gas tertentu seperti karbon dioksida
dan oksigen, sangat meningkatkan korosi. Bila dipanaskan dalam sistem boiler,
Karbondioksida (CO2) dan oksigen (O2) dilepaskan sebagai gas dan bergabung dengan
air (H2O) membentuk asam karbonat (H2CO3). Penghilangan oksigen, karbondioksida
dan gas lain yang tidak dapat terembunkan dari air umpan boiler sangat penting bagi
umur peralatan boiler dan juga keamanan operasi. Asam karbonat mengkorosi logam
menurunkan umur peralatan dan pemipaan. Asam ini juga melarutkan kalsium dan
magnesium yang jika kembali ke boiler akan mengalami pengendapan dan
meyebabkan terjadinya pembentukan kerak pada boiler dan pipa. Kerak ini tidak
hanya berperan dalam penurunan umur peralatan tapi juga meningkatkan jumlah
energi yang diperlukan untuk mencapai perpindahan panas sehingga merugikan.
Air RO digunakan sebagai bahan pembuatan steam pada unit boiler, keperluan
produksi di margarine plant dan air minum karyawan. Air RO yang dihasilkan harus
sesuai dengan standar mutu air bersih yang telah ditetapkan. Proses pengolahan air
baku tersebut yaitu dimulai dengan air sumur, kemudian air sumur dilakukan
treatment untuk menghilangkan logam penyebab kesadahan. Pada proses ini disebut
dengan soft water. Setelah proses soft water kemudian air soft water tersebut diolah
kembali untuk menjadi air RO yang pelaksaanaan nya dilakukan dengan adanya
membrane filter. Air RO ini lah yang digunakan sebagai keperluan dipabrik. (Laporan
Training BMDP, 2012 )
2.5.1 Standar Baku Air Umpan Boiler
Standar baku air umpan boiler yang akan digunakan dalam proses penghasil steam
dilihat dari kapasitas tekanan boiler yang digunakan. Pt Smart Tbk menggunakan
boiler dengan tekanan 21 bar. Berdasarkan tekanan tersebut maka standar baku air
Tabel 2.2 Standar Baku Air Umpan Boiler
(PT. Lonsum 2008)
Parameter Batas Kontrol
pH 6,5-8,5
TDS (ppm) 80 Maksimum
Total Hardness (ppm) 2 maksimum
Silika (ppm) 5 maksimum
BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Alat dan Bahan 3.1.1 Alat
- Beaker glass Pyrex
- Gelas Erlenmeyer Pyrex
- Labu Ukur Pyrex
- Blender Philip
- pipet tetes
- Spatula
- Batang pengaduk
- Hotplate Cimarec
- Magnetik Stirer
- Oven Carbolite
- Kertas saring biasa
- Kertas saring whatman No 42
- Neraca Analitis Sartorius
- Desikator
- Statif dan Klem
- Buret Pyrex
- Corong
- Indikator pH
- Furnace Galenkamp
3.1.2 Bahan
- Acetobacter Xylinum
- H2SO4 ( p ) p.a (E.Merck)
- Nata De Soya
- Aquadest
- Air Baku Boiler PT Smart Tbk
- Na2EDTA p.a (E.Merck)
- Buffer pH 10 p.a (E.Merck)
- EBT p.a (E.Merck)
- Murexid
- NaOH P.a (E.Merck)
- NaCl p.a (E.Merck)
- Etanol Merck
- Aquabidest
- HCl 37 % p.a (E.Merck)
3.2 Prosedur Penelitian 3.2.1 Pembuatan Larutan
Larutan H2SO4 1 N
Sebanyak 27,17 mL H2SO4 ( p ) 98 % ( BJ = 1,84 ) diencerkan dengan aquadest sampai
volume 1 liter dalam labu takar 1000 mL.
Larutan Standart Na2EDTA 0,01 N
Sebanyak 3,723 g kristal Na2EDTA ditimbang dengan teliti dan dimasukkan kedalam
labu takar 1000 mL dan dilarutkan dengan aquadest dan diencerkan sampai garis
tanda. Larutan yang diperoleh distandarisasi dengan CaCO3 0,01 M dengan cara
dipipet sebanyak 10 mL larutan standar CaCO3 0,01 M. Dimasukkan kedalm
Ditambahkan 0,4 g indikator EBT, dan dititrasi dengan Na2EDTA 0,01 N sampai
terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi warna biru.
Larutan NaOH 1 N
Sebanyak 40 g kristal NaOH ditimbang dengan teliti dan dimasukkan kedalam labu
takar 1000 mL dan dilarutkan dengan aquadest dan diencerkan sampai garis tanda
Larutan Standar CaCO3 0,01 M
Sebanyak 1,000 g serbuk CaCO3 anhidrat dimasukkan kedalam beaker glass,
dilarutkan dengan penambahan HCl (1:1), kemudian ditambahkan 200 mL aquadest
dan didihkan untuk membuang CO2. Kemudian didinginkan dan ditambahkan 3 tetes
indikator metil merah. Ditambahkan NH4OH 3 N atau HCl (1:1) sampai larutan
berwarna jingga. Kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 1000 mL, diencerkan
dengan aquadest sampai garis tanda dan dihomogenkan.
Indikator Eriochrome Black T
Sebanyak 0,5 g eriochrome black T dicampurkan dengan 10 g NaCl kemudian digerus
sampai halus. Indikator ini disimpan didalam botol tertutup rapat.
Indikator Murexid
Sebanyak 200 mg murexid dan 100 gram NaCl dicampurkan dan digerus sampai
berukuran 40-50 mesh. Indikator ini disimpan dalam botol tertutup rapat.
3.2.2 Pembuatan Nata De Soya
Media kultur untuk produksi selulosa bakteri, setiap liter dari air limbah rebusan tahu
ditambahkan 5 g urea, dan 80 g gula pasir. Media kultur ini dimasak diatas kompor
hingga mendidih, setelah itu didinginkan hingga temperatur kamar. Keasaman dari
media diatur menjadi pH=4 dengan menambahkan CH3COOH glasial . Bibit dari
Acetobacter xylinum diinokulasi ke dalam media kultur selama 14 hari pada
3.2.3 Aktivasi Nata De Soya
Nata yang dihasilkan dipotong kecil-kecil di cuci dengan air hingga pH netral.
Selanjutnya dicuci dengan menggunakan larutan NaOH 2 % dan dibilas kembali
dengan aquadest hingga pH netral. Kemudian Nata de soya dicuci dengan etanol agar
molekul air yang terperangkap didalam pori-pori selulosa bakterial Nata de Soya tidak
kembali. Sebanyak 1 kg Nata basah diblender sampai halus lalu diaktivasi dengan
H2SO4 1 N dan distirer selama 1 jam dan dicuci dengan aquadest hingga pH netral
kemudian disaring. Nata tersebut kemudian diletakkan pada plat kaca dengan
ketebalan ± 5mm lalu dipanaskan pada suhu 950C selama 6 jam. Tujuannya untuk
mempercepat pengeringan dan menghindari pemanasan yang tidak merata. Setelah
dipanaskan Nata tersebut diblender kembali dan siap digunakan Untuk mengabsorpsi
kation Ca2+ dan Mg2+ pada sampel air baku boiler di PT SMART TBK.
3.2.4 Penentuan Konsentrasi kesadahan Ca2+ dan Mg2+ Pada Sampel air Baku Boiler Sebelum Penambahan Adsorben Nata De Soya
3.2.4.1Penentuan Kesadahan Total
Sampel air baku boiler dipipet sebanyak 50 mL dengan pipet volume, dimasukkan
kedalam erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan Buffer pH 10 kedalam erlenmeyer 250
mL sebanyak 2 mL. Ditambahkan 0,4 mg indikator Eriochrome Black T, dititrasi
dengan NaEDTA 0,01 N hingga warna merah anggur menjadi biru.
3.2.4.2Penentuan Konsentrasi Kesadahan Ca2+
Sampel air baku boiler dipipet sebanyak 100 mL dengan pipet volume. Dimasukkan
kedalam erlenmeyer 250 mL, kemudian ditambahkan 4 mL NaOH 1N dan
ditambahkan 0,2 g indikator murexid. Kemudian sampel dititrasi dengan larutan
Standart Na2EDTA 0,01 N sampai terjadi perubahan warna dari merah menjadi warna
3.2.4.3Penentuan Konsentrasi Kesadahan Mg2+
Untuk menentukan jumlah kation magnesium ( Mg2+ ) dalam sampel dengan cara :
Konsentrasi Mg2+ = ( Konsentrasi kesadahan total-Konsentrasi kation Ca2+ )
( Referensi : Standart methods for the examination of water and wastewater part
300,Determination of metal )
3.2.5 Adsorpsi kation Ca2+ dan kation Mg2+ Dengan Adsorben Nata De Soya
Sebanyak 200 mL sampel dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan
0,5 g Nata de Soya teraktivasi dengan aktivator H2SO41N. Diaduk dengan
menggunakan magnetik stirer selama 30 menit. Disaring dan filtrat nya ditentukan
kandungan Ca2+ dan Mg2+ menggunakan metode titrasi dengan larutan standart
Na2EDTA 0,01 N. Dilakukan hal yang sama untuk berat Nata De Soya 1,0 ; 1.5 ; 2,0 ;
2.5 ; 3,0 ; dan 3.5 g.
3.2.6 Regenerasi Nata De Soya yang Jenuh
Nata yang sudah jenuh yang digunakan dalam mengadsorpsi kation Kalsium dan
Magnesium dalam sampel air boiler tersebut diaktivasi kembali dengan H2SO4 1 N
dan distirer selama 1 jam kemudian disaring. Kemudian dikeringkan dengan
memanaskan Nata de soya tersebut pada suhu 950C. Nata Jenuh telah diregenerasi
dan siap digunakan.
3.2.7 Adsorpsi kation Ca2+ dan kation Mg2+ Dengan Adsorben Nata De Soya yang diregenerasi
Sebanyak 200 mL sampel dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan
0,5 g Nata de Soya yang telah diregenerasi. Diaduk dengan menggunakan magnetik
stirer selama 1jam. Disaring dan filtratnya ditentukan kandungan Ca2+ dan Mg2+
3.2.8 Penentuan Kadar Ca Dan Mg Pada Adsorben Nata De Soya
Adsorben Nata De Soya dimasukkan kedalam cawan porselen, kemudian didekstruksi
dengan menggunakan tanur pada suhu 5000C selama 4 jam. Diangkat cawan porselen
dari dalam tanur dan dimasukkan kedalam desikator, dibiarkan hingga dingin.
Ditimbang hasil dekstruksi Nata De Soya sebanyak 1 g, dimasukkan kedalam
Erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan HCl 37 % sebanyak 10 mL, dan dipanaskan
hingga mendidih. ditambahkan 150 mL aquabidest, dipanaskan larutan kembali
selama 30 menit. Diangkat larutan dan didinginkan,kemudian larutan dipindahkan
kedalam labu ukur 500 mL sambil dibilas dengan aquabidest hingga garis batas,
dihomogenkan. Disaring semua larutan dengan menggunakan kertas saring dan
corong kedalam labu Erlenmeyer.
3.2.8.1 Penentuan Kadar Mg Dalam Adsorben Nata De Soya
Filtrat hasil dekstruksi adsorben Nata De Soya dipipet sebanyak 50 mL. Dimasukkan
kedalam Erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan 2 mL buffer pH 10 kedalam Erlenmeyer,
ditambahkan 0,4 g indikator EBT. Dititrasi dengan larutan standar Na2EDTA 0,01 N
hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru.
3.2.8.2 Penentuan Kadar Ca Dalam Adsorben Nata De soya
Filtrat hasil dekstruksi adsorben Nata De Soya dipipet sebanyak 100 mL. Dimasukkan
kedalam Erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan 4 mL NaOH 0,1 N. Ditambahkan 0,2 g
indikator murexid. Dititrasi dengan larutan standar Na2EDTA 0,01 N hingga terjadi
perubahan warna dari merah menjadi warna violet. Diukur volume larutan standar
3.3 Bagan Penelitian
3.3.1 Pembuatan Nata De Soya (Imam. P, 2010)
Dimasukkan kedalam panci
Dipanaskan hinggga mendidih
Ditambahkan 5 g urea
Ditambahkan 80 g sukrosa
Diaduk hingga semua larut
Ditambahkan asam asetat
(CH3COOH) Glasial hingga pH
media kultur menjadi pH 4
Didiamkan sampai dingin hingga
temperatur menjadi 280C
Dimasukkan kedalam wadah
yang telah disterilisasi
Diinokulasikan bibit acetobacter
xylinum kedalam media kultur
Didiamkan hingga 14 hari
1 liter air limbah rebusan kedelai
Media kultur
3.3.2 Aktivasi Nata De Soya (Sulistiyana, 2010)
Dipotong kecil-kecil
Dicuci Dengan Air hingga pH 7
Dicuci dengan NaOH 2 %
Dicuci dengan aquadest hingga pH 7
Dicuci dengan etanol absolut
Diblender sebanyak 1 kg nata
basah hingga halus
Diaktivasi dengan H2SO41 N
Distirer selama 30 menit
Disaring
Dicetak pada plat kaca
dengan Ketebalan 5
mm
Dipanaskan pada suhu
95oC selama 6 jam
Diblender kembali
nata kering
Disimpandalam
desikator Nata de Soya
Filtrat
3.3.3 Penentuan kesadahan Ca2+ dan Mg2+ sebelum penambahan adsorben Nata de Soya
3.3.3.1 Penentuan kesadahan Total (Greenberg,E.A, 1981)
Dipipet sebanyak 50 mL sampel air baku boiler dengan pipet volume
Dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
Ditambahkan 2 mL buffer pH10 kedalam erlenmeyer
Ditambahkan 0,4 g indikator EBT
Dititrasi dengan Na2EDTA 0,01 N hingga terjadi perubahan warna dari
merah anggur menjadi biru
Diukur volume Na2EDTA 0,01 N yang digunakan
3.3.3.2 Penentuan kesadahan Ca2+ (Greenberg,E.A, 1981)
Dipipet sebanyak 100 mL sampel air baku boiler dengan pipet volume
Dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml
Ditambahkan 4 mL NaOH 0,1 N
Ditambahkan 0,2 g indikator murexid
Dititrasi dengan larutan standar Na2EDTA 0,01 N hingga terjadi
perubahan warna dari merah menjadi warna violet
Diukur volume larutan standar Na2EDTA 0,01 N yang digunakan Air Baku Boiler
Hasil
Air Baku Boiler
3.3.4 Adsorpsi kation Ca2+ dan Mg2+ dengan adsorben Nata de soya teraktivasi
Dimasukkan kedalam erlenmeyer
250 mL
Ditambahkan 0,5 g Nata de soya
teraktivasi
Diaduk dengan magnetik stirer
selama 30 menit
Disaring
Diukur kesadahan total dan kesadahan Ca2+ menggunakan
metode titrasi dengan larutan standar Na2EDTA 0,01 N
Dilakukan hal yang sama untuk berat adsorben Nata de Soya
1,0 ; 1.5 ; 2,0 ; 2.5 ; 3,0 ; dan 3,5 g
200 mL air baku boiler
Filtrat
Hasil
3.3.5 Regenerasi Adsorben Nata de soya
Diaktivasi dengan H2SO41 N
Distirer selama 1 jam
Dicuci dengan aquadest hingga
pH 7
Disaring
Dipanaskan pada
suhu 95oC selama
6 jam
Diblender kembali
nata kering
Disimpan dalam
desikator Nata de Soya Jenuh
Filtrat
3.3.6 Adsorpsi kation Ca2+ dan kation Mg2+ Dengan Adsorben Nata De Soya yang diregenerasi
3.3.6.1 Penentuan kesadahan Total
Dipipet sebanyak 50 mL sampel air baku boiler dengan pipet
volume
Dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
Ditambahkan 2 mL buffer pH10 kedalam erlenmeyer
Ditambahkan 0,4 g indikator EBT
Dititrasi dengan Na2EDTA 0,01 N hingga terjadi perubahan
warna dari merah anggur menjadi biru
Diukur Volume Na2EDTA yang digunakan
3.3.6.2 Penentuan kesadahan Ca2+
Dipipet sebanyak 100 mL sampel air baku boiler dengan pipet
volume
Dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
Ditambahkan 4 mL NaOH 0,1 N
Ditambahkan 0,2 g indikator murexid
Dititrasi dengan larutan standar Na2EDTA 0,01 N hingga terjadi
perubahan warna dari merah menjadi violet
Diukur volume larutan standar Na2EDTA 0,01 N
yang digunakan Air Baku Boiler
Hasil
Air Baku Boiler
3.3.7 Penentuan Kadar kation Ca2+ Dan Mg2+ Dalam Adsorben Nata De Soya (Rio.S, 2011)
Dimasukkan kedalam cawan porselen
Didekstruksi kering dengan menggunakan tanur pada
suhu 5000C Selama 4 jam.
Didinginkan didalam desikator hingga suhu kamar
Ditimbang sebanyak 1 g hasil dekstruksi Nata De Soya
Dimasukkan kedalam labu Erlenmeyer 250 mL
Ditambahkan sebanyak 10 mL HCl 37 %
Dipanaskan hingga mendidih, kemudian didinginkan,
dan ditambahkan 150 mL aquabidest, dididihkan
kembali selama 30 menit
Didinginkan larutan, kemudian dipindahkan kedalam
labu ukur 500 mL sambil dibilas dengan air aquabides
dan dihomogenkan hingga garis tanda batas.
Disaring larutan dengan menggunakan kertas saring dan
corong dimasukkan kedalam labu erlenmeyer Adsorben Nata De Soya
Abu Nata De Soya
3.3.7.1 Penentuan Kadar Mg Dalam Adsorben Nata De Soya
Dipipet Sebanyak 50 mL filtrat hasil dekstruksi
Nata De Soya
Dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 mL
Ditambahkan 2 mL buffer pH 10 kedalam
Erlenmeyer
Ditambahkan 0,4 g indikator EBT
Dititrasi dengan Na2EDTA 0,01 N hingga terjadi
perubahan warna dari merah anggur menjadi
biru
Diukur volume Na2EDTA 0,01 N yang terpakai
3.3.7.2 Penentuan kadar Ca Dalam Adsorben Nata De Soya
Dipipet Sebanyak 100 mL filtrate hasil
dekstruksi adsorben Nata De Soya
dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 mL
Ditambahkan 4 mL NaOH 0,1 N
ditambahkan 0,2 g indikator Murexid
Dititrasi dengan Na2EDTA 0,01 N hingga terjadi
perubahan warna dari merah menjadi violet
Diukur Volume Na2EDTA 0,01 N yang terpakai Filtrat Hasil Dekstruksi Nata De Soya
Hasil
Filtrat Hasil Dekstruksi Nata De Soya
BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Perlakuan titrasi terhadap sampel dalam penentuan kandungan logam Magnesium dan
Kalsium dilakukan sebanyak 3 kali perlakuan,agar data hasil pengukuran yang
diperoleh lebih tepat dan teliti. Data kesadahan Magnesium dan Kalsium sebelum
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan data kesadahan Magnesium dan Kalsium
sesudah perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.2
Tabel 4.1.Data Kesadahan Magnesium Dan Kalsium Sebelum Menggunakan Adsorben Nata De Soya
Kesadahan Total (mg/L) Kesadahan Ca (mg/L) Kesadahan Mg (mg/L)
[image:51.595.109.531.570.763.2]59,46 18,04 41.42
Tabel 4.2 Data Adsorpsi Kation Magnesium Dan Kalsium Sesudah Menggunakan Adsorben Nata De Soya
Massa Adsorben
(g)
Kesadahan Total
(mg/L)
Kesadahan Ca
(mg/ L)
Kesadahan Mg
(mg/L)
0,5 47,01 13,39 33,62
1,0 40,45 11,75 28,70
1,5 24,05 7,10 16,95
2,0 24,60 10,38 14,22
2,5 25,14 11,20 13,94
3,0 25,69 11,20 14,49
Tabel 4.3 Data Kesadahan Magnesium dan Kalsium Sebelum Perlakuan Dengan Adsorben Nata De Soya Regenerasi
Kesadahan Total (mg/L) Kesadahan Ca (mg/L) Kesadahan Magnesium
(mg/L)
73 22,21 50,79
Tabel 4.4 Data Adsorpsi Kesadahan Kalsium Dan Magnesium Dengan Adsorben Nata De Soya Regenerasi
Kesadahan Total (mg/L) Kesadahan Ca (mg/L) Kesadahan Magnesium (mg/L)
66,13 20,15 45,98
4.1.1 Data Penentuan Kadar Kation Kalsium Dan Magnesium Pada Adsorben Nata De Soya
Pada uji penentuan kadar kation Kalsium dan Magnesium dalam adsorben Nata De
Soya tidak diperoleh perubahan warna pada filtrat hasil dekstruksi pada saat
ditambahkan indikator Murexid dan EBT. Komposisi Nata De Soya tersusun atas
selulosa.Nata De soya berasal dari limbah buangan air kedelai yang komposisinya
tersusun atas gula, asam organik dan mineral dimana ketiga unsur tersebut sebagai
unsur utama pembentuk Nata De Soya.Tidak terjadinya perubahan warna pada saat
penambahan indikator murexid dan indikator EBT mengindikasikan tidak adanya
kation Kalsium dan Magnesium dalam adsorben Nata De Soya.
Dari data Adsorpsi Kation Kalsium dan Magnesium dengan menggunakan adsorben
Nata De Soya dapat ditentukan persentase Penurunan Kesadahan total dengan
Menggunakan rumus :
x100%
Maka persentase (%) penurunan konsentrasi optimum kesadahan total pada sampel air
baku boiler setelah ditambahkan adsorben Nata De Soya teraktivasi.
x 100% = 59,55 %
4.1.3. Persentase (%) Penurunan optium Konsentrasi Kation Ca2+
Dari data Adsorpsi Kation Kalsium dengan menggunakan adsorben Nata De Soya
dapat ditentukan persentase Penurunan Kesadahan total dengan Menggunakan rumus :
x 100%
Maka persentase (%) penurunan konsentrasi optimum kesadahan total pada sampel air
baku boiler setelah ditambahkan adsorben Nata De Soya teraktivasi.
x 100% = 60,64 %
4.1.4. Persentase (%) Penurunan optium Konsentrasi Kation Mg2+
Dari data Adsorpsi Kation Magnesium dengan menggunakan adsorben Nata De Soya
x
100%
Maka persentase (%) penurunan konsentrasi optimum kesadahan Magnesium pada
sampel air baku boiler setelah ditambahkan adsorben Nata De Soya teraktivasi.
x 100% = 66,34 %
4.1.5. Persentase (%) Penurunan Kation Kalsium dan Magnesium Dengan Adsorben Regenerasi
Dari data adsorpsi dengan adsorben yang diregenerasi dapat dihitung persentase (%)
penurunan kadar kation Kalsium dan Magnesium
a. Persen penurunan kesadahan total dengan penggunaan adsorben Nata De Soya
yang diregenerasi yaitu :
x 100% = 9,41%
b. Persen penurunan kation Kalsium dengan penggunaan adsorben Nata De Soya
yang diregenerasi yaitu :
x 100% = 9,27 %
c. Persen penurunan kation Magnesium dengan penggunaan adsorben Nata De Soya
x 100% = 9,47 %
4.2 Pembahasan
Penentuan kandungan kation Kalsium (Ca2+) dan Magnesium (Mg2+) pada sampel air
baku boiler dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan dengan penambahan adsorben
Nata De Soya. Pada penelitian dilakukan penentuan massa optimum adsorben Nata De
Soya dalam mengadsorpsi kation Kalsium (Ca2+) dan Magnesium (Mg2+) pada sampel
air baku boiler. Setelah didapatkan massa optimum adsorben dalam mengadsorpsi
kation Kalsium (Ca2+) dan Magnesium (Mg2+) maka ditentukan persentase (%)
penurunan optimum dari kandungan kation Kalsium (Ca2+) dan Magnesium (Mg2+) pada sampel.
Pada penelitian dilakukan kembali proses adsorpsi sampel dengan adsorben
Nata De Soya yang telah diregenerasi dengan H2SO4 1 N. Massa adsorben yang diregenerasi yaitu 1,5 gram, dimana massa 1,5 gram adalah massa optimum adsorben
dalam proses penyerapan kation Kalsium (Ca2+) dan 2,5 gram massa optimum
adsorben Nata De Soya dalam mengadsorpsi kation Magnesium (Mg2+) pada sampel. Adsorben yang diregenerasi digunakan kembali untuk mengadsorpsi kation Kalsium
(Ca2+) dan Magnesium (Mg2+), kemudian ditentukan persentase (%) penurunan kation
Kalsium (Ca2+) dan Magnesium (Mg2+) pada sampel dengan adsorben Nata De Soya yang di regenerasi. Pada proses adsorpsi dengan adsorben Nata De Soya yang
diregenerasi terjadi penurunan yang tidak begitu signifikan untuk kedua kation
tersebut. Penurunan konsentrasi kation Kalsium dengan menggunakan adsorben yang
diregenerasi sekitar 9,27 % dari Konsentrasi awal 22,21 mg/L menjadi 20,15 mg/L.
Untuk kation Magnesium dengan penggunaan adsorben Nata De Soya yang
diregenerasi terjadi penurunan sekitar 9,47 % dari konsentrasi awal 50,79 mg/L
gambar 4.2.1 Grafik Batang Adsorpsi Dengan Menggunakan Adsorben Nata De Soya
[image:56.595.108.528.186.457.2]Diregenerasi.
Gambar 4.2.1 Grafik Batang Adsorpsi Dengan Menggunakan Adsorben Nata De Soya Diregenerasi
Dari hasil penelitian didapatkan massa optimum adsorben Nata De Soya yang
paling optimum dalam penyerapan Kation Kalsium yaitu pada massa 1,5 g dimana
terjadi penurunan konsentrasi sekitar 60,64 % dari konsentrasi awal 18,04 mg/L
menjadi 7,10 mg/L. Pada kation Magnesium didapatkan massa optimum adsorben
Nata de Soya yaitu pada massa 2,5 g dimana terjadi penurunan konsentrasi sekitar
66,34 % dari konsentrasi awal 41,42 mg/L menjadi 13,94 mg/L. Grafik penurunan
dengan kenaikan massa adsorben dapat dilihat pada gambar 4.1.2 Grafik Adsorpsi
Gambar 4.1.2 Grafik Adsorpsi dengan Menggunakan Adsorben Nata De Soya
Proses aktivasi pada Nata De Soya dilakukan dengan penambahan H2SO4 1 N
dimana tujuan dari proses aktivasi ini untuk memutuskan ikatan glikosidik dari
selulosa dari Nata De Soya, dimana karena aktivasi ini akan terbentuk gugus OH
yang lebih banyak karena selulosa akan terhidrolisis menjadi D- Glukosa. Mekanisme
molekul hidrolisis dengan katalis asam pada ikatan β-1-4-glikosidik yaitu dimulai dengan sebuah proton dari asam yang berinteraksi cepat dengan oksigen dari ikatan
glikosidik yang menghubungkan dua unit D- Glukosa, sehingga membentuk ikatan
asam konjugasi. Perpecahan dari ikatan C-O dan asam konjugat pada ion karbonium
siklik kemudian pecah menjadi D glukosa bebas dan gugus karbonil yang tidak stabil,
setelah penambahan air, senyawa antara karbonium berubah menjadi D- Glukosa, dan
seiring dengan itu gugus asam kembali melepaskan H+ dan seterusnya. ( Xiang, et.al,
2003 )
Menurut Badger ( 2002 ) reaksi hidrolisis secara kimia dapat dilakukan
dengan menggunakan asam encer maupun asam pekat. Penggunaan asam encer pada
proses hidrolisis dilakukan pada temperature dan tekanan tinggi dengan waktu reaksi
yang cepat. Temperatur yang digunakan adalah mencapai 2000C. Dari data penelitian
didapatkan massa optimum adsorben Nata De Soya untuk kation Ca2+ yaitu pada
Penyerapan kation – kation tersebut dengan penggunaan adsorben Nata De Soya
Belum optimal dimana penyerapan optimum untuk kation Ca2+ sekitar 60,64 % dan
untuk Mg2+ sekitar 66,34 %. Hal ini mungkin disebabkan karena gugus-gugus OH
dan CO pada Nata De Soya yang terbentuk tidak sempurna dikarenakan pada saat
proses aktivasi dengan H2SO4 1 N pada suhu kamar