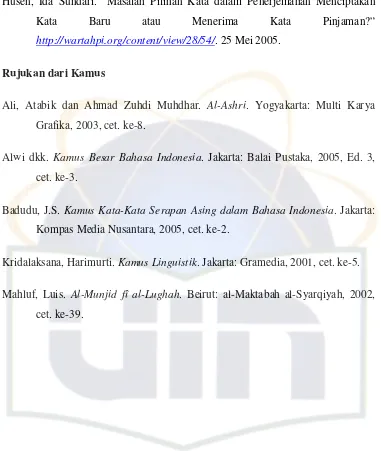DIKSI DALAM TERJEMAHAN: STUDI KRITIK
TERJEMAHAN AL-RISÂLAH AL-QUSYAIRIYYAH FÎ
ILMI AL-TASAWWUF
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sastra (S.S)
Oleh
ANNA SARASWATI
NIM : 104024000830
PROGRAM STUDI TARJAMAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
DIKSI DALAM TERJEMAHAN: STUDI KRITIK
TERJEMAHAN AL-RISÂLAH AL-QUSYAIRIYYAH FÎ
ILMI AL-TASAWWUF
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sastra (S.S)
Oleh
ANNA SARASWATI
NIM : 104024000830
PROGRAM STUDI TARJAMAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 14 Mei 2008
DIKSI DALAM TERJEMAHAN: STUDI KRITIK
TERJEMAHAN AL-RISÂLAH AL-QUSYAIRIYYAH FÎ
ILMI AL-TASAWWUF
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra (S.S)
Oleh
Anna Saraswati NIM: 104024000830
Pembimbing,
Moch. Syarif Hidayatullah, M.Hum
NIP: 150 370 229
PROGRAM STUDI TARJAMAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul DIKSI DALAM TERJEMAHAN: STUDI KRITIK
TERJEMAHAN AL-RISÂLAH AL-QUSYAIRIYYAH FÎ ILMI
AL-TASAWWUF telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 3 Juni 2008. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S) pada
Program Studi Tarjamah.
Jakarta, 3 Juni 2008
Sidang Munaqasyah
Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,
Drs. Ikhwan Azizi, MA Ahmad Syaekhuddin, M.Ag
150 265 589 150 303 001
Anggota,
Moch. Syarif Hidayatullah, M.Hum
ABSTRAK
ANNA SARASWATI
Diksi Dalam Terjemahan: Studi Kritik Terjemahan Al-Risâlah
al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf
Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu (seperti yang diharapkan). Diksi merupakan faktor utama dalam aktivitas penerjemahan. Jadi, dalam menerjemahkan, penerjemah harus teliti dalam memilih kata agar ide dan pesan penulis tersampaikan dengan baik. Diksi yang dipergunakan penerjemah harus diksi yang umum dan tidak menyalahi norma-norma umum yang berlaku. Penerjemah yang belum mahir mempergunakan bahasa akan menemukan berbagai kesulitan, karena apa yang dipikirkan atau dimaksudkan tidak akan sempurna dilahirkan kepada orang lain. Hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Sanksi yang langsung dapat diterima oleh penerjemah adalah bahwa apa yang diinginkan tidak dapat segera mendapat tanggapan dari pembaca.
Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerjemah Al-Risâlah
al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf dalam memilih diksi. Melalui data yang telah dianalisis, terdapat kata yang masih belum tepat dan belum sesuai menurut gaya bahasa. Dengan kata lain, sebagian diksi yang digunakan oleh penerjemah
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadiat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat,
hidayah, dan karunia-Nya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul
DIKSI DALAM TERJEMAHAN: STUDI KRITIK TERJEMAHAN AL-RISÂLAH
AL-QUSYAIRIYYAH FÎ ‘ILMI AL-TASAWWUF. Skripsi ini diajukan untuk
memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya
atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses
studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Abdul Chaer selaku dekan Fakultas Adab dan Humaniora.
2. Bapak Drs. Ikhwan Azizi, MA selaku ketua jurusan Tarjamah dan bapak
Ahmad Syaekhuddin, M.Ag selaku sekretaris jurusan Tarjamah yang telah
memberikan dukungan dan kemudahan sehingga segalanya dapat
terlaksana.
3. Bapak Moch. Syarif Hidayatullah, M.Hum selaku dosen pembimbing atas
ketulusan dan kesabarannya dalam membimbing Penulis dan memberikan
masukan dalam menyelesaikan skripsi, sekaligus telah memberikan
wawasan yang luas tentang dunia penerjemahan.Bapak Dr. Sukron Kamil,
MA sebagai dosen seminar skripsi yang telah memberikan banyak
4. Bapak dan ibu dosen lainnya atas curahan ilmunya selama masa studi.
5. Staf pegawai dan pengurus perpustakaan utama, perpustakaan Adab dan
Humaniora, perpustakaan pribadi Mas Tatam, dan perpustakaan pribadi
lainnya yang telah memfasilitasi buku-buku hingga Penulis terbantu dalam
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mohammad Luqman Hakiem selaku penerjemah buku Al-Risâlah
al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf di tengah-tengah kesibukannya,
beliau bersedia dihubungi via telepon dan mengirimkan profilnya lewat
e-mail.
7. Bapak dan Mama tercinta (H. Agus Salim dan Hj. Tuti Fatmawati) yang
tiada hentinya berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya, terima kasih atas
semua kasih sayang dan support yang telah diberikan selama ini. Kak
Zikri dan dek Meyla yang tak pernah lupa untuk memberikan perhatian
dan semangat kepada Penulis.
8. Kawan-kawan di Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya kawan-kawan
Tarjamah angkatan 2004 (Nay, Moena, Fiena, Nungke, Iziel, Poet, Tatam,
Erwan, Omen, dll) yang menjadi tempat bertukar pikiran bagi Penulis.
Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat
Penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab
itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa
mendatang.
Ciputat, 12 Mei 2008
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ... i
LEMBAR PERNYATAAN ... ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii
LEMBAR PENGESAHAN ... iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ... v
ABSTRAK ... ix
KATA PENGANTAR ... x
DAFTAR ISI ... xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 7
C. Tujuan Penelitian ... 7
D. Manfaat Penelitian ... 8
E. Tinjauan Pustaka ... 8
F. Landasan Teori ... 9
G. Metodologi Penelitian ... 9
H. Sistematika Penulisan ...10
BAB II KERANGKA TEORETIK A. Teori Terjemah ... 12
1. Definisi Penerjemahan ... 12
3. Metode Penerjemahan ... 19
B. Teori Diksi ... 25
1. Definisi Diksi ... 25
2. Masalah Pilihan Kata dalam Penerjemahan ... 27
3. Peranti-peranti Diksi ... 29
a. Penggunaan Kata Bersinonim ... 29
b. Penggunaan Kata Bermakna Denotasi dan Konotasi .. 32
c. Penggunaan Kata Umum dan Khusus ... 32
d. Penggunaan Kata Abstrak dan Konkret ... 33
e. Penggunaan Bentuk Idiomatis ... 34
4. Ketepatan Pilihan Kata ... 34
a. Persoalan Ketepatan Pilihan Kata ... 34
b. Persyaratan Ketepatan Pilihan Kata ... 35
5. Kesesuaian Pilihan Kata ... 37
a. Persoalan Kesesuaian Pilihan Kata ... 37
b. Persyaratan Kesesuaian Pilihan Kata ... 37
BAB III SEPUTAR RISALAH QUSYAIRIYYAH, BIOGRAFI SINGKAT DAN SEJUMLAH KARYA PENULIS DAN PENERJEMAH A. Seputar Risalah Qusyairiyyah ... 41
B. Biografi Singkat dan Sejumlah Karya Penulis ... 42
C. Biografi Singkat dan Sejumlah Karya Penerjemah ... 47
AL-QUSYAIRIYYAH FÎ ‘ILMI AL-TASAWWUF
A. Kritik Peranti-peranti Diksi ... 49
1. Penggunaan Kata Bersinonim ... 49
2. Penggunaan Kata Bermakna Denotasi dan Konotasi ... 52
3. Penggunaan Kata Umum dan Khusus ... 54
4. Penggunaan Kata Abstrak dan Konkret ... 56
5. Penggunaan Bentuk Idiomatis ... 57
B. Kritik Ketepatan Pilihan Kata ... 58
C. Kritik Kesesuaian Pilihan Kata ... 64
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 72
B. Saran ... 75
PEDOMAN TRANSLITERASI
Skripsi ini menggunakan transliterasi yang bersumber pada buku Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang diterbitkan oleh
CeQDA.
1. Padanan Aksara
Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:
No. Lambang Bunyi Transliterasi Keterangan
1 Tidak dilambangkan
2 b be
3 t te
4 ts te dan es
5 j je
6 h h dengan garis bawah
7 kh ka dan ha
8 d de
9 dz de dan zet
10 r er
11 z zet
12 s es
13 sy es dan ye
14 s es dengan garis di bawah
No. Lambang Bunyi Transliterasi Keterangan
17 z zet dengan garis di bawah
16 t te dengan garis di bawah
18 ‘ koma terbalik di atas hadap
kanan
19 gh ge dan ha
20 f ef
21 q ki
22 k ka
23 l el
24 m em
25 n en
26 w we
27 h ha
28 ` apostrof
29 y ye
2. Vokal
Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:
No. Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
2 " i kasrah
3 # u dammah
b. Vokal Rangkap
Untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:
No. Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
1
!
ai a dan i2
!
au a dan uc. Vokal panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab
dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:
No. Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
1
$!
â a dengan topi di atas2
%&"
î i dengan topi di atas3
%'#
û u dengan topi di atas3. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bahasa Indonesia terus menerus berkembang. Akhir-akhir ini, perkembangannya
itu menjadi demikian pesatnya sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi
bahasa modern, yang kaya akan kosakata dan mantap dalam stuktur. Untuk itu,
sebagai masyarakat Indonesia harus mempergunakan kosakata tersebut sesuai
dengan waktu, tempat, dan kondisi.
Jika berbicara menulis atau menerjemahkan, maka seseorang selalu
menggunakan kata. Kata tersebut dibentuk manjadi kelompok kata, klausa,
kalimat, paragraf, dan akhirnya sebuah wacana. Dengan begitu, untuk menguasai
suatu bahasa, seseorang dituntut untuk menguasai kosakata bahasa tersebut.
Walaupun demikian, penguasaan kosakata saja tidak cukup sebagai syarat untuk
menguasai bahasa tertentu. Salah satu syarat yang perlu dan mendesak dalam
berbicara, menulis, dan menerjemahkan adalah pemilihan kata.
Pemilihan kata dalam Linguistik disebut diksi. Diksi adalah pilihan kata
yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek
tertentu (seperti yang diharapkan).1
Pemakaian bahasa diatur oleh dua perangkat kaidah. Kaidah yang pertama
disebut tata bahasa, yang menentukan benar tidaknya kalimat. Kaidah yang kedua
dinamakan gaya bahasa, yang membuat bahasa yang kita gunakan menjadi baik,
indah, dan efektif. Penggunaan bentuk kata yang tepat, seperti pemilihan antara
tahu dan mengetahui, termasuk dalam cakupan tata bahasa karena pilihan yang salah berakibat kalimat menjadi salah. Sebaliknya, pemilihan antara matahari dan sang surya tergolong ke dalam cakupan gaya bahasa. Pemilihan gaya bahasa yang salah tidak berakibat kalimat menjadi salah, tetapi kalimat itu dapat
dianggap tidak tepat, tidak kena sasarannya, atau tidak indah. Kalimat yang betul
belum tentu tepat, kena, indah, atau efektif.2 Dalam penelitian ini, Penulis hanya
meneliti pemilihan kata atau diksi secara gaya bahasa.
Pilihan kata termasuk dalam ilmu semantik, yaitu ilmu yang mempelajari
makna kata. Makna kata tersebut terdapat dalam kamus. Kamus merupakan
sebuah referensi yang memuat kosakata dan disusun secara alfabetis disertai
keterangan bagaimana menggunakan kata itu. Dengan banyaknya makna dalam
kamus, kita harus memilih kata atau makna yang tepat untuk mengungkapkan
sebuah gagasan. Hal ini penting, karena tidak jarang sebuah kata dapat berubah
arti dalam ruang dan waktu yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman
dalam penggunaan.
Bahasa yang dipergunakan penulis atau penerjemah harus bahasa yang
umum dan tidak menyalahi norma-norma umum yang berlaku. Baik penulis
maupun penerjemah yang belum mahir mempergunakan bahasa akan menemukan
berbagai kesulitan, karena apa yang dipikirkan atau dimaksudkan tidak akan
sempurna dilahirkan kepada orang lain. Demikian pula dalam pergaulan umum,
jika bahasa yang dipergunakan bukan merupakan bahasa yang umum berlaku,
maka sukar pula diperoleh komunikasi yang lancar. Hal ini akan menimbulkan
kesalahpahaman. Sangsi yang langsung dapat diterima oleh pembicara, penulis,
dan penerjemah adalah bahwa apa yang diinginkan tidak dapat segera mendapat
tanggapan.
Dalam menerjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, penerjemah
harus memilih padanan kata yang sesuai dengan tuntutan konteks, sehingga hasil
terjemahannya tepat dan benar. Terkadang satu kata dalam bahasa Arab
mempunyai belasan arti. Untuk itu penerjemah harus teliti dalam memilih
padanan kata. Contoh, kata bermakna ‘banyak, sering, dan
melimpah-limpah’, dalam kalimat:
ی !
"#$%"&
Kita sering menonton TV yang menayangkan film cerita.
Pilihan diksi pada kata dalam kalimat di atas, sangat tepat diartikan ‘sering’.
Contoh lain, pada frasa
' ( ) *
, kata) *
pada frasa tersebut tidakdiartikan ‘memukul’, tetapi lebih tepatnya diatikan ‘mengocok’, karena kata yang
berdampingan dengannya bermakna ‘telur’. Jadi, frasa tersebut diartikan
‘mengocok telur’.
Penggunaan kata pada dasarnya berkisar pada dua persoalan pokok:
pertama, ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan, hal atau
barang yang akan diamanatkan. Kedua, kesesuaian atau kecocokan dalam
mempergunakan kata tersebut. Perbedaan antara ketepatan dan kesesuaian diksi
adalah dalam ketepatan, kita mempersoalkan apakah kata yang digunakan sudah
tepat, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan di antara pembicara
dan pendengar, atau antara penulis dengan pembaca. Dalam kesesuaian, kita
menyinggung perasaan orang lain.
Di bawah ini contoh pilihan kata yang kurang tepat yang terdapat dalam
buku terjemahan Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf:
(
-+",
-. / 0
1
2 3 4" 3 56 7 89 " 3 : 89 8; <
= >
< 1 6 "9< 8?( 2 3 < 1@ < "9< AB
) )
3C ( <
Beliau bersabda, “Itu bukanlah malu yang sebenarnya.Orang yang ingin malu dengan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah
swt, hendaklah menjaga pikiran dan bisikan hatinya, hendaklah ia menjaga
perutnya dan apa yang dimakannya, hendaklah ia mengingat mati dan
fitnah kubur....4
Kata
C (
di atas diterjemahkan ‘fitnah kubur’, kataC (
di atas tidaktepat dan tidak sesuai diartikan ‘fitnah’, karena dalam bahasa Indonesia kata
fitnah diartikan ‘perkataan atau pembicaraan yang sengaja disebarkan untuk
menjelek-jelekkan orang agar masyarakat mempunyai kesan yang buruk tentang
orang yang difitnah itu.’5 Dalam kamus al-Ashri
C ﺏ
bermakna ‘dicoba; diuji’.6Menurut Penulis, kata
C (
di atas lebih tepatnya diartikan ‘siksa kubur’, karenasebelumnya, kata tersebut didahului oleh kalimat hendaklah ia mengingat mati.
Jadi, arti dari
C (
tidak jauh dari kematian. Kata fitnah (kata yang dipilih oleh
3 Abul Qasim al-Qusyairy al-Naisabury, Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf (Beirut: Darul Khair, t.t.), h. 215.
4
Al-Naisabury, Risalah Qusyairiyah Induk Ilmu Tasawuf, Penerj. Mohammad Luqman Hakiem (Surabaya: Risalah Gusti, 2006), h. 252.
5J.S. Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Buku Kompas, 2005), cet. ke-2, h. 111.
penerjemah Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf), dicoba, dan diuji
merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan.
Di bawah ini contoh pilihan kata yang kurang sesuai yang terdapat dalam
buku terjemahan Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf:
E F -4" G ="9
89 H0>I - " 8ﺏ J K + ی
-
*
C
L
<
M
>
N
O
8
<
,
3
4"
<
P
(
Q$ C
#
< "
R
+
S
9
J
7))
)))))))
Al-Fudhail bin Iyadh menjelaskan, “Ada lima tanda celakaseorang manusia: Kerasnya hati, bengisnya mata, tiadanya rasa malu,
hasrat terhadap dunia, dan lamunan yang tiada terbatas.”8
Kata
+ ی
di atasditerjemahkan ‘menjelaskan’. Dalam konteks kalimat diatas, subjek sedang menyebutkan sesuatu, bukan menjelaskan. Jadi, menurut
Penulis, kata tersebut lebih sesuai diterjemahkan ‘menyebutkan’. Begitu juga
terjemahan kata
4" G
yang diterjemahkan ‘celaka’. Penggunaan kata celakakurang sesuai, karena kata celaka berkedudukan sebagai kata kerja sedangkan
pada struktur kalimat di atas lebih tepat menggunakan kata benda. Dalam kamus
al-Ashri, kata
4" G
berarti ‘kesengsaraan; kemalangan’.9 Begitu juga dalamkamus al-Munjid fî al-Lughah, kata
4" G
berarti)
EN"OF ' # UE$G
T
10yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘kesengsaraan; lawan kata kebahagiaan’.
7 Al-Naisabury, Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf, h. 217.
8 Al-Naisabury, Risalah Qusyairiyah Induk Ilmu Tasawuf, Penerj. Mohammad Luqman Hakiem, h. 255.
9
Atabik Ali, h. 1141.
Jadi, setelah merujuk beberapa kamus, menurut Penulis, kata
4" G
lebihtepat diterjemahkan ‘kesengsaraan’.
Diksi merupakan faktor utama dalam aktivitas penerjemahan. Penerjemah
harus teliti dalam memilih kata agar ide dan pesan penulis tersampaikan dengan
baik. Terkadang, penyampaian seseorang dalam menyampaikan ide yang
dimaksud mengalami kesulitan, baik dalam menulis, berkomunikasi, maupun
menerjemahkan. Hal ini disebabkan karena minimnya kosakata yang dimiliki.
Sebaliknya, ada pula seseorang yang mempergunakan kata sangat boros, namun
tidak ada isi yang tersirat di balik kata-kata itu. Inilah alasan utama Penulis
mengkritik diksi/pilihan kata dalam terjemahan agar pilihan kata dapat
tersampaikan sesuai pesan penulis dan mudah dipahami oleh para pembaca.
Sekarang ini, banyak sekali buku terjemahan di Indonesia yang telah
membuka cakrawala pemikiran kita untuk selalu berhubungan dengan bangsa lain
melalui karya mereka yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia.
Khususnya, buku terjemahan dari bahasa Arab yang sebagian besar sudah dicetak
berulang kali. Penulis menjadikan salah satu buku terjemahan tersebut sebagai
bahan kritik yang fokus membahas masalah diksi.
Buku terjemahan yang akan menjadi bahan kritik adalah buku Al-Risâlah
al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf karya Imam Al-Qusyairy al-Naisabury,
seorang sufi besar, pengarang dalam bidang tasawuf, dan ilmu-ilmu Islam. Buku
tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mohammad Luqman
Hakiem berjudul Risalah Qusyairiyah Induk Ilmu Tasawuf.
Berdasarkan latar belakang itulah, Penulis memberi judul skripsi ini
al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Pengamatan pada buku terjemahan Al-Risâlah Qusyairiyyah fî Ilmi
al-Tasawwuf memberi inspirasi kepada Penulis untuk mengangkat permasalahan
pada kajian diksi/ pilihan kata. Agar penulisan ini tidak meluas, Penulis
merumuskan masalah ini dengan bentuk pertanyaan yang akan dijawab setelah
melalui telaah mendalam. Bentuk pertanyaannya adalah:
Apakah diksi yang dipilih penerjemah buku Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî
Ilmi al-Tasawwuf sudah tepat dan sesuai secara gaya bahasa?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, Penulis memiliki tujuan
umum dalam penelitian ini, di antaranya membuktikan pentingnya memilih kata
dalam penerjemahan sehingga tidak menimbulkan kerancuan arti dan
tersampaikan apa yang diinginkan penulis buku. Selain itu, Penulis juga memiliki
tujuan inti yang secara jelas dirumuskan berikut ini:
Mengetahui akurasi kata yang dipilih oleh penerjemah buku Al-Risâlah
al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf.
D. Manfaat Penelitian
Di samping penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi kata dalam
terjemahan Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf. Penelitian ini juga
penerjemah agar dapat merujuk hasil penelitian ini guna mengetahui pilihan kata
atau diksi yang tepat dan sesuai secara gaya bahasa. Selain itu, bagi penerjemah
pemula yang ingin melakukan penerjemahan menyadari bahwa dalam
penerjemahan itu perlu diperhatikan kemahiran dalam memilih diksi yang tepat
dan sesuai agar para pembaca mudah menangkap isi atau pesan yang disampaikan
penulis.
E. Tinjauan Pustaka
Sejauh yang Penulis temukan, penelitian tentang permasalahan diksi dilakukan
oleh 5 orang, di antaranya: Umanih (2007) menganalisis diksi terhadap
terjemahan Fiqh al-Mar`ah al-Muslimah, Rachmad Joeni Akbar (2006)
menganalisis diksi terhadap Alquran terjemahan Departemen Agama surat
al-Waqi‘ah, Elang Satya Nagara (2007) menganalisis diksi pada bab puasa buku
terjemahan Fath al-Qarib, Euis Maemunah (2004) menganalisis diksi pada bab
zakat buku terjemahan Fath al-Qarib, dan Mohammad Hotib (2006) menganalisis
diksi pada terjemahan buku Bulugh al-Maram bab riba “versi A. Hassan”.
Umumnya, penelitian yang dilakukan mahasiswa Jurusan Tarjamah adalah
analisis diksi pada terjemahan Alquran dan kitab-kitab Fiqh. Sementara itu, belum
terdapat penelitian yang menganalisis atau mengkritik masalah diksi mengenai
tasawuf, seperti yang akan Penulis teliti dalam buku terjemahan Al-Risâlah
al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf.
Dalam penelitian ini, Penulis akan memakai teori Newmark dalam buku yang
disusun oleh Rochayah Machali yang berjudul Pedoman bagi Penerjemah.
Penulis juga akan menggunakan teori Eugene A. Nida. Selain itu, Penulis akan
menggunakan teori Gorys Keraf yang terdapat dalam buku Diksi dan Gaya
Bahasa. Selanjutnya, sebagai alat untuk mengkritik, Penulis akan menggunakan
teori Kunjana Rahardi dalam bukunya Seni Memilih Kata.
G. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian studi naskah
terjemahan, yaitu dengan cara menginventarisir kata-kata terkait dengan masalah
yang diteliti untuk menyingkap fakta yang ada sekaligus menemukan
masalah-masalah baru. Setelah itu, Penulis mendeskripsikan masalah-masalah tersebut sesuai
dengan data yang ada sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan penelitian.
Penulis melakukan pencarian data dengan membaca dan menelaah
berbagai kamus guna mengetahui diksi atau pilihan kata dengan tepat dan sesuai
secara gaya bahasa. Penulis mengkritik pilihan kata atau diksi yang terdapat
dalam buku terjemahan Al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî Ilmi al-Tasawwuf.
Di samping itu, Penulis juga terus berkonsultasi dengan para ahli untuk
mengetahui lebih jauh dalam memilih diksi yang tepat.
Dalam penulisan ini, Penulis juga merujuk pada sumber-sumber sekunder
berupa buku-buku tentang penerjemahan, buku mengenai semantik, kamus bahasa
Arab, bahasa Indonesia, Linguistik, ensiklopedi, internet, dan lain-lain.
Selain itu, Penulis menggunakan kajian pustaka (library research). Secara
(Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang berlaku di lingkungan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh Center of Quality Development and
Assurance (CeQDA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini disajikan dalam lima bab. Bab I merupakan bab yang memayungi
topik penelitian ini. Bab ini menjelaskan latar belakang atau alasan pemilihan
topik penelitian ini, pembatasan masalah, perumusan masalah yang berupa
pertanyaan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Bab ini
sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap bab-bab selanjutnya.
Bab II menyajikan teori penerjemahan, yang meliputi definisi, proses, dan
metode penerjemahan. Mengingat penelitian ini berorientasi pada kritik atau
penilaian, karenanya pada bab ini juga dipaparkan kerangka teori yang akan
dipakai, diantaranya, teori diksi dan perantinya, ketepatan dan kesesuaian
pemilihan kata, dan lain-lain. Bab ini akan menjadi alat kritik.
Bab III menyuguhkan hal yang terkait objek atau data penelitian ini, yaitu
kajian tentang biografi singkat Imam al-Qusyairy al-Naisabury. Bab ini akan
memperjelas penelitian.
Bab IV berupa kritik internal atau penilaian dengan menerapkan teori yang
ada pada bab II. Bab ini akan membuktikan hasil penelitian.
Bab V merupakan bab yang mengakhiri penelitian ini dengan memberikan
BAB II
KERANGKA TEORETIK
A. Teori Terjemah 1. Definisi Penerjemahan
Dalam bidang penerjemahan ditemukan banyak definisi yang disampaikan oleh
para ahli. Berbagai definisi penerjemahan tersebut sering dikutip dalam
buku-buku tentang penerjemahan.
Catford (1965) menggunakan pendekatan kebahasaan dalam melihat
kegiatan penerjemahan dan ia mendefinisikannya sebagai the replacement of
textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another
language (TL), yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ‘mengganti bahan
teks dalam bahasa sumber dengan bahan teks yang sepadan dalam bahasa
sasaran.’ Newmark (1981) juga mendefinisikan serupa, namun lebih jelas lagi,
rendering the meaning of a text into another language in the way that the author
intended the text, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ‘menerjemahkan makna
suatu teks ke dalam bahasa lain sesuai dengan yang dimaksudkan pengarang.’11
Kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) penerjemahan adalah
upaya mengganti teks bahasa sumber dengan teks yang sepadan dalam bahasa
sasaran; (2) yang diterjemahkan adalah makna yang sesuai dengan maksud
pengarang.
Di sisi lain, Eugene A. Nida dan Charles R. Taber (1969), dalam buku
mereka The Theory and Practice of Translation, memberikan definisi
penerjemahan sebagai berikut:
Translating consists in reproducing in the receptor language the closest
natural equivalent of the source language message, first in terms meaning and
secondly in terms of style.
Menerjemahkan adalah kegiatan menghasilkan kembali di dalam bahasa
penerima barang yang secara sedekat-dekatnya dan sewajarnya sepadan dengan
pesan dalam bahasa sumber, pertama-tama menyangkut maknanya dan kedua
menyangkut gayanya.
Secara lebih sederhana, menerjemahkan dapat didefinisikan sebagai
memindahkan suatu amanat dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima
(sasaran) dengan pertama-tama mengungkapkan maknanya dan kedua
mengungkapkan gaya bahasanya.12 Di sini Nida dan Taber tidak
mempermasalahkan bahasa-bahasa yang terlibat dalam penerjemahan, tetapi lebih
tertarik pada cara kerja penerjemahan, yakni mencari padanan alami yang semirip
mungkin sehingga pesan dalam BSu bisa disampaikan dalam Bsa.13 Menurut
mereka, terjemahan terbaik ialah terjemahan yang tidak berbau terjemahan.14
Menurut Benny Hoedoro Hoed, dalam bukunya Penerjemahan dan
Kebudayaan, penerjemahan adalah upaya untuk mengungkapkan (kembali) pesan
yang terkandung dalam teks suatu bahasa atau teks sumber (BSu/TSu) ke dalam
bentuk teks dalam bahasa lain atau teks sasaran (BSa/TSa).15
Dalam bukunya Translation: Applications and Research, Brislin (1976)
12 Widyamartaya, Seni Menerjemahkan (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 11. 13
Zuchridin Suryawinata dan Sugeng hariyanto, Translation: Bahasan Teori dan Penuntun Praktis Menerjemahkan (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 12.
14
Moch. Syarif Hidayatullah, Teori dan Permasalahan Penerjamahan, Diktat (Jakarta: t.pn., 2007), h. 42.
15 Benny Hoedoro Hoed, Penerjemahan dan Kebudayaan
menulis:
Translation is the general term referring to the transfer of thoughts and
ideas from one language (source) to another (target), whether the languages are
in written or oral form; whether the languages have a established orthographies
or do not have such standardization or whether one or both languages is based on
signs, as with sign languages of the deaf.
Secara bebas, definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:
Penerjemahan adalah istilah umum yang mengacu pada proses pengalihan
buah pikiran dan gagasan dari satu bahasa (sumber) ke dalam bahasa lain
(sasaran), baik dalam bentuk tulisan maupun lisan; baik kedua bahasa tersebut
telah mempunyai sistem penulisan yang telah baku maupun belum, baik salah satu
atau keduanya didasarkan pada isyarat sebagaimana bahasa isyarat orang tuna
rungu.16
Dari definisi di atas, Brislin memberi batasan pada istilah penerjemahan.
Bagi dia penerjemahan adalah pengalihan buah pikiran atau gagasan dari satu
bahasa ke dalam bahasa yang lain. Kedua bahasa ini bisa serumpun, seperti
bahasa Jawa dan Sunda, bisa dari lain rumpun, seperti bahasa Indonesia dan Arab,
atau bahkan bahasa yang sama tetapi dipakai dalam kurun waktu yang berbeda.
Definisi lain tentang penerjemahan diungkapkan oleh Mc Guire (1980),
yaitu:
Translation involves the rendering of a source language (SL) text into the
target language (TL) so as to ensure that (1) the surface meaning of the two will
be approximately similar and (2) the structure of the SL will be preserved as
16
closely as possible, but not so closely that the TL structure will be seriously
distorted.
Definisi tersebut diterjemahkan sebagai berikut:
Penerjemahan melibatkan usaha menjadikan BSu ke BSa sehingga (1)
makna keduanya menjadi hampir mirip dan (2) struktur BSa dapat dipertahankan
setepat mungkin, tetapi jangan terlalu tepat sehingga struktur BSanya menjadi
rusak.17
Definisi di atas terdapat beberapa hal yang kurang mengena. Pertama,
yang dibicarakan adalah BSu dan BSa yang sangat umum, sehingga tidak khusus
mengacu pada suatu terjemahan. Selain itu, definisi kedua mengandung
kontroversi, yaitu setepat mungkin namun jangan terlalu tepat. Dari sini kita tidak
tahu batas ketepatan yang dimaksud.
Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penerjemahan
adalah memindahkan makna yang telah diungkapkan dalam bahasa yang satu
(BSu) ke bahasa yang lain (BSa) dengan menyesuaikan kaidah kedua bahasa
tersebut.
2. Proses Penerjemahan
Menerjemahkan bukan hanya sekadar menyadur, dengan pengertian menyadur
sebagai pengungkapan kembali amanat dari suatu karya dengan meninggalkan
detail-detailnya tanpa harus mempertahankan gaya bahasanya dan tidak harus ke
dalam bahasa lain. (Pengertian menyadur tersebut disampaikan oleh Harimurti
Kridalaksana). Selain memahami definisi penerjemahan, seorang penerjemah
hendaknya mengetahui pula proses penerjemahan.18 Salah satu proses
penerjemahan yang seringkali dianut oleh banyak teoritis penerjemahan adalah
proses penerjemahan karya Nida (1975).
Nida membagi proses penerjemahan itu menjadi tiga tahap. Ketiga tahap
itu ialah:
1. Analisis
2. Pengalihan (Transfer)
3. Penyelarasan (Restructuring)19
Tahap Pertama atau Analisis
Pada tahap pertama, sebelum penerjemah menganalisis teks yang akan
diterjemahkan, ia akan dihadapkan dengan sebuah teks Bahasa Sumber (BSu),
misalnya bahasa Arab. Pada waktu seorang penerjemah menghadapi teks BSu, dia
harus memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang diterjemahkan itu. Kalau
tidak, dia tentu akan mengalami kesulitan. Misalnya seorang penerjemah yang
tidak menguasai bidang kedokteran diminta menerjemahkan teks-teks atau
materi-materi di bidang kedokteran, dia tentu akan mengalami kesulitan dalam
memahami isinya. Hal tersebut akan berakibat penerjemahannya melenceng dari
isi atau pesan teks bahasa sumbernya (BSu).
Di samping seorang penerjemah harus menguasai masalah pokok dari
materi yang diterjemahkan itu, dia harus pula menguasai BSu dengan baik sekali
dan bahkan hampir sempurna dari segi kebahasaannya. Tujuan penganalisisan dari
aspek kebahasaannya ini dimaksudkan bahwa si penerjemah harus mampu
menganalisis pola kalimatnya, struktur bahasanya, kolokasinya, idiomnya,
18
Widyamartaya, h.14. 19
peribahasanya (kalau ada), gaya bahasanya, kata-katanya, dan sebagainya.
Seorang penerjemah harus dapat menguasai segala sesuatu yang berhubungan
dengan bahasa yang digunakan dalam teks BSu, agar dia dapat memahami seluruh
isi atau maknanya.20 Untuk itu, penerjemah terlebih dahulu harus tahu bahan yang
hendak diterjemahkan itu bahasa siapa: bahasa seorang pujanggakah, seorang
noveliskah, seorang ahli hukumkah, seorang penulis iklankah, dan sebagainya.21
Di sisi lain, penerjemah juga harus menguasai (atau paling tidak banyak
mengetahui) budaya yang dilibatkan dalam BSu karena penerjemahan itu sangat
erat hubungannya dengan kebudayaan.
Tahap Kedua atau Tahap Pengalihan
Pada tahap ini, penerjemah harus mampu mencarikan padanan ke dalam BSa yang
menyangkut semua kata, frasa, klausa, kalimat, dan bahkan mencarikan padanan
untuk seluruh wacana. Pekerjaan ini tidak mudah, karena kadang-kadang terdapat
ungkapan yang sukar sekali dicarikan padanannya dalam BSa. Malahan terdapat
makna yang sama sekali tidak dapat dicarikan padanannya dalam BSa. Tetapi ada
pendapat yang mengatakan bahwa pikiran atau gagasan yang dapat diungkapkan
dalam suatu bahasa pasti juga dapat diungkapkan dalam bahasa yang lain, tentu
saja cara pengungkapannya berbeda. Tetapi harus diingat bahwa kedua ungkapan
itu (BSu dan BSa) tidak akan sama persis maknanya. Dengan demikian,
penerjemah harus berusaha mencarikan padanannya yang paling dekat, karena
setiap bahasa mempunyai sistem pengungkapan dan sistem pemaknaan yang
berbeda dengan bahasa yang lain.22 Dalam tahap ini, penerjemah harus sering
meminta bantuan orang lain.
20 Ibid., h. 6. 21
Widyamartaya, h. 16. 22
Tahap Ketiga atau Tahap Penyelarasan
Tahap ini merupakan tahap akhir, dan ini berarti bahwa tahap sebelumnya sudah
diselesaikan dengan baik. Setelah seorang penerjemah menemukan semua
padanan dalam BSa, dia harus menuangkan semua padanan itu ke dalam draft
atau rencana terjemahannya. Tentu saja hasil terjemahannya masih kasar dan
bersifat sementara serta masih memerlukan perbaikan di sana-sini. Dengan kata
lain draft itu masih memerlukan penyelarasan. Barangkali kalimat-kalimatnya
masih tampak kaku atau masih tampak seperti kalimat-kalimat yang berasal dari
kalimat-kalimat BSu. Kalimat-kalimat terjemahan tersebut masih terpengaruh
oleh bentuk bahasa sumbernya.23
Pada tahap penyerasian ini, penerjemah dapat melakukannya sendiri, atau
membiarkan orang lain melakukannya. Akan lebih baik apabila penyerasian itu
dilakukan oleh orang lain. Ada dua alasan bagi hal ini: (1) penerjemah biasanya
merasa sulit mengoreksi pekerjaannya sendiri, karena secara psikologis ia akan
beranggapan bahwa terjemahannya sudah bagus, peristilahannya sudah tepat,
bahasanya sudah cukup alamiah dan wajar, dan sebagainya; (2) penerjemahan
sebaiknya merupakan pekerjaan suatu tim. Dalam hal ini, penerjemah melulu
menerjemahkan sedangkan kegiatan penyerasian dilakukan oleh orang lain.
Apabila penerjemah sendiri ingin melakukan penyerasian, maka sebaiknya
penerjemah memberikan hasil terjemahan untuk beberapa lama, agar ia tidak ingat
lagi proses pengambilan keputusan yang dilakukannya pada waktu
menerjemahkan. Hal ini untuk menghindari pengaruh proses tersebut terhadap
tindakan penyerasian yang akan dilakukannya. Sesudah itu, barulah ia dapat
memeriksa kembali hasil terjemahan tersebut dengan pikiran yang segar.24
3. Metode Penerjemahan
Menurut Newmark, sebagaimana dikutip oleh Rochayah Machali, ada dua metode
penerjemahan, yaitu (1) metode yang memberikan penekanan terhadap bahasa
sumber (BSu); (2) metode yang memberikan penekanan terhadap bahasa sasaran
(BSa). Dalam metode jenis yang pertama, penerjemah berupaya mewujudkan
kembali dengan setepat-tepatnya makna kontekstual Tsu, meskipun dijumpai
hambatan sintaksis dan semantis pada Tsa (yakni hambatan bentuk dan makna).
Dalam metode kedua, penerjemah berupaya menghasilkan dampak yang relatif
sama dengan yang diharapkan oleh penulis asli terhadap pembaca versi BSu.25
Metode-metode yang memberikan penekanan atau lebih berorientasi
terhadap bahasa sumber antara lain:
1. Penerjemahan Kata demi Kata (Word-for-word translation)
Dalam metode penerjemahan jenis ini biasanya kata-kata TSa langsung diletakkan
di bawah versi TSu. Kata-kata dalam TSu diterjemahkan di luar konteks, dan
kata-kata yang bersifat kultural dipindahkan apa adanya. Contoh:
ﺙ
ﺙ X
$
V
<
)Y ,B
dan di sisiku tiga pulpen-pulpen.
Umumnya metode ini digunakan sebagai tahapan prapenerjemahan pada
penerjemahan teks yang sangat sukar atau untuk memahami mekanisme BSu.
Jadi, dalam proses penerjemahan, metode ini dapat terjadi pada tahap analisis atau
24
tahap awal pengalihan.
2. Penerjemahan Harfiah (Literal Translation)
Metode ini juga dapat dilakukan dalam penerjemahan awal. Kalimat-kalimat yang
panjang dan sulit diterjemahkan secara harfiah dulu untuk kemudian
disempurnakan. Dalam penerjemahan harfiah, penerjemah sudah mengubah
struktur BSu menjadi struktur BSa. Namun, kata-kata dan gaya bahasa dalam TSu
masih dipertahankan dalam TSa. Dengan sendirinya terjemahan seperti ini masih
memperlihatkan model teks dari TSu dan belum dapat dikatakan sebagai
terjemahan yang betul. Metode ini juga dipilih untuk menjaga agar jangan terjadi
kebocoran dalam mengalihkan pesan.26 Contoh:
4 N Z I
Ringan selendang.27
Metode ini dapat digunakan sebagai metode pada tahap awal pengalihan,
bukan sebagai metode yang lazim. Sebagai proses penerjemahan awal, metode ini
dapat membantu penerjemah melihat masalah yang harus diatasi.28
3. Penerjemahan Setia (Faithful Translation)
Penerjemah setia ini berupaya menghasilkan kembali makna kontekstual BSu
yang tepat. Dalam melaksanakan hal itu, penerjemah akan berhadapan dengan
kendala struktur gramatikal BSa. Dengan menggunakan metode ini, penerjemah
mentransfer kata-kata kultural dan mempertahankan tingkat ketidakwajaran
gramatikal dan leksikal (penyimpangan dari norma-norma BSu) dalam
penerjemahan. Penerjemah berupaya setia sepenuhnya terhadap tujuan dan
26
Hoed, h. 56.
27 Moch. Syarif Hidayatullah, Teknik Menerjemah Teks Arab 1, (Jakarta: Transpustaka, 2005) h. 27.
28
realisasi teks penulis BSu.29 Dalam hasil penerjemahan metode ini,
kadang-kadang terasa kaku dan seringkali asing. Contoh:
Dia (lk.) dermawan karena banyak abunya.
)+)
N"
9
%
4. Penerjemahan Semantik (Semanic Translation)
Penerjemah sangat menekankan pada penggunaan istilah, kata kunci, ataupun
ungkapan yang harus dihadirkan dalam terjemahannya.30 Perbedaan antara
penerjemahan setia (3) dan penerjemahan semantik adalah bahwa metode (3)
lebih kaku, tidak berkompromi dengan kaidah, dan lebih terikat oleh BSu
sedangkan metode (4) lebih fleksibel. Contoh seperti dalam contoh (3), namun,
dalam metode ini, hasil terjemahnnya lebih luwes.
Ia (laki-laki) adalah orang dermawan. =
N"9
%
Penerjemahan semantis harus pula mempertimbangkan unsur estetika teks
BSu dengan mengkompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran.
Metode-metode yang memberi penekanan atau lebih berorientasi terhadap
bahasa sasaran antara lain:
1. Saduran (Adaptation)
Adaptasi merupakan metode penerjemahan yang paling bebas dan paling dekat
dengan BSa. Istilah saduran dapat dimasukkan di sini asalkan penyadurannya
tidak mengorbankan hal-hal penting dalam TSu, misalnya tema, karakter, atau
alur. Biasanya metode ini dipakai dalam penerjemahan drama atau puisi. Tetapi
29
Hidayatullah, h. 15. 30
dalam penerjemahan, terjadi peralihan budaya BSu ke budaya BSa, dan teks asli
ditulis kembali serta diadaptasikan ke dalam Tsa.31
Contoh: BSu: Mumpung padhang rembulane
Mumpung jhembar kalangane
Klausa di atas dapat diadaptasi ke dalam bahasa Arab sebagai berikut:
6
V
>
B "
#
["
#
ﺏ "
$
[
#"
Selama bulan purnama bersinar.
Tidak diterjemahkan: Selama menyinari (kami) bulan purnama (kami).
(pronominal persona “kami” tidak diterjemahkan).
Versi asli BSa adalah penggambaran budaya tentang betapa pengaruh
bulan purnama di suatu suasana desa Jawa (yang mungkin temaram/gelap),
sehingga tidak hanya “padhang rembulane” (terangnya sinar bulan) saja yang
dilukiskan, tetapi juga “jembar kalangane” (luasnya lingkaran terang bulan).
Keduanya disampaikan melalui lagu/irama bunyi [e] pada akhir klausa. Demikian
pula pada penerjemahan ke dalam bahasa Arab tidak dapat menggambarkan
budaya yang serupa. Alternatif versi BSa (bahasa Arab) adalah penggambaran
netral dalam satu kalimat, dengan rima internal bunyi [na:] pada kata ana: rana:
dan badruna:. Dalam budaya masyarakat Arab, bulan purnama
[$ﺏ
/badr/ sudahmengandung makna terang bulan dengan luas lingkaran penuh.32
2. Penerjemahan Bebas (Free Translation)
Metode ini merupakan penerjemahan yang mengutamakan isi dan mengorbankan
bentuk teks BSu. Biasanya, metode ini berbentuk sebuah parafrase yang dapat
31
Machali, h. 53. 32
lebih panjang atau lebih pendek dari aslinya dan bentuk retorik (seperti alur) atau
bentuk kalimatnya sudah berubah sama sekali. Metode ini sering dipakai di
kalangan media massa.33 Contoh:
B C
>
+"
B
ﺹ
HJ
]
H^
9
8
B
ﺹ
+
N"F
3
E"
V
A"
B
M
>
O
8
Harta sumber malapetaka34
3. Penerjemahan Idiomatik (Idiomatic Translation)
Metode ini bertujuan mereproduksi pesan dalam teks BSu, tetapi sering dengan
menggunakan kesan keakraban dan ungkapan idiomatik yang tidak didapati pada
versi aslinya. Dengan demikian, banyak terjadi distorsi nuansa makna. Beberapa
pakar penerjemahan seperti Seleskovitch menyukai metode terjemahan ini, yang
dianggapnya “hidup” dan “alami (dalam arti akrab)”. Sebagai contoh adalah
penerjemahan berikut ini:
8_"V; 4J>ﺕ 4"9a J(,
Sedia payung sebelum hujan.
4. Penerjemahan Komunikatif (Communicative Translation)
Metode ini berupaya memberikan makna kontekstual BSu yang tepat sedemikian
rupa sehingga isi dan bahasanya dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca.35
Sesuai dengan namanya, metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi.
Yaitu khalayak pembaca dan tujuan penerjemahan. Melalui metode ini, sebuah
versi TSu dapat diterjemahkan menjadi beberapa versi TSa sesuai dengan
33
Machali, h. 53. 34
prinsip di atas.36 Contoh:
#
?
[
9
8
#
?
Y
ﺙ
^
9
8
Y
ﺙ
^
9
8
9
K
b
Y
Dapat diterjemahkan ke dalam beberapa versi, di antaranya:
1. Kita tumbuh dari mani, lalu segumpal darah, dan kemudian segumpal
daging (awam).
2. Kita berproses dari sperma, lalu zigot, dan kemudian embrio (terpelajar).37
Newmark memberikan komentar terhadap metode-metode di atas.
Menurutnya, hanya metode semantik dan komunikatiflah yang dapat memenuhi
tujuan utama penerjemahan, yaitu keakuratan dan keekonomisan. Pada umumnya,
masih menurut Newmark, penerjemahan semantik ditulis pada tingkat linguistik
penulis, sedangkan penerjemahan komunikatif pada tingkat linguistik pembaca.
Penerjemahan semantik digunakan untuk menerjemahkan teks-teks ekspresif,
sedangkan penerjemahan komunikatif untuk teks-teks vokatif dan informatif.38
B. Teori Diksi 1. Definisi Diksi
Dalam bahasa Indonesia, kata diksi berasal dari kata dictionary (bahasa Inggris
yang kata dasarnya diction) berarti perihal pemilihan kata. Dalam Websters (Edisi
ketiga, 1996) diction diuraikan sebagai choice of words esp with regard to
correctness, clearness, or effectiveness. Jadi, diksi membahas penggunaan kata,
36
Machali, h. 55. 37
terutama pada soal kebenaran, kejelasan, dan keefektifan.39
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang
tepat dan selaras (dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan
sehingga diperoleh efek tertentu (seperti yang diharapkan).40
Menurut Harimurti Kridalaksana, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan
lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam
karang-mengarang.41
Dalam buku Seni Menggayakan Kalimat, Widyamartaya mengutip
pendapat Gorys Keraf bahwa pilihan kata atau diksi adalah kemampuan
membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang
ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai
dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar.
Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah
besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu.42
Gorys Keraf juga menguraikan tiga kesimpulan utama mengenai diksi:
pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang
dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk
pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang
tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi; kedua,
pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat
nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk
39 Ida Bagus Putrayasa, Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika), (Bandung: Refika Aditama, 2007), cet. ke-I, h. 7.
40
Alwi dkk., h. 264. 41
Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) ed. 3.
menemukan bentuk yang sesuai (cocok) dengan situsi dan nilai rasa yang dimiliki
kelompok masyarakat pendengar; ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya
dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata
bahasa itu. Sementara itu, yang dimaksud perbendaharaan kata atau kosakata
suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa.43
Dari beberapa pendapat di atas, secara umum Penulis menyimpulkan
bahwa diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan makna atau gagasan yang
ingin disampaikan oleh pembicara, penulis, dan penerjemah. Kata-kata tersebut
harus tepat digunakan dalam situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok
masyarakat pendengar dan pembaca.
Dengan demikian, diksi yang baik dapat diketahui apabila sebuah
tulisan mampu dipahami oleh pembaca sesuai dengan tingkat keahlian di mana
tulisan itu ditujukan.
2. Masalah Pilihan Kata dalam Penerjemahan
Penerjemah harus mengalihkan pesan atau amanat, bukan mengalihbahasakan
kata per kata. Namun, pada praktiknya, dalam pengalihan pesan itu, sering
terjemahan suatu kata atau istilah menjadi kendala yang agak sulit diatasi,
demikian pula ungkapan. Terkadang kedua bahasa sedemikian berbeda sehingga
penerjemah dihadapkan pada ketidakmungkinan menerjemahkan suatu kata. Di
sinilah diperlukan kebijakan, kemampuan berbahasa Indonesia, keterampilan
menemukan kata yang tepat serta kreativitas seorang penerjemah agar teks
terjemahannya dapat berterima. Di samping itu, ia pun harus mengenali apakah
suatu kelompok kata merupakan frasa atau klausa biasa ataukah ungkapan atau
peribahasa.
Masalahnya muncul jika penerjemah tidak tahu padanan peribahasa
Indonesia atau memang dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Salah satu
solusi adalah menerjemahkan makna peribahasa itu berdasarkan kamus.
Kata-kata yang sulit dicarikan padanannya biasanya menyangkut unsur
budaya materi, religi, sosial, organisasi sosial, adat istiadat, kegiatan, prosedur,
bahasa isyarat, ekologi (Newmark: 1988: 95, seperti yang dikutip oleh Nababan,
2004). Masalahnya, terkadang padanan kata itu ada dalam bahasa Indonesia, tetapi
konotasinya berbeda. Atau sebaliknya, kata tersebut dalam teks asal memiliki
berbagai makna yang harus dipilih dengan jeli oleh penerjemah. Memang
persoalan memilih makna kata itu merupakan masalah permanen dalam
penerjemahan yang dapat membuat kesal penerjemah karena terkadang ia telah
paham betul apa yang dimaksud pengarang, tetapi mendapat kesulitan bagaimana
menuangkannya dalam bahasa Indonesia gara-gara satu kata atau istilah saja.
Contoh-contoh berikut yang menyangkut kebiasaan sehari-hari (pranata sosial,
makanan-minuman, dll.), istilah keagamaan, istilah kekerabatan, kata ganti orang,
nama diri, sebutan, gelar, kata sapaan, nama peralatan, tumbuh-tumbuhan,
bunga-bungaan, buah-buahan,dan hewan.44
Dalam pencarian padanan, kita akan dihadapkan pada beberapa kasus.
44
Kasus berikut disarikan dari website yang ditulis oleh Ida Sundari Husen,45 di
antaranya:
a. Istilah/kata yang memiliki padanan dalam bahasa Indonesia.
• Kata tersebut sebetulnya ada padanannya dalam bahasa Indonesia, namun
dengan makna yang lebih luas, misalnya dalam bahasa Inggris, kata rice yang
dapat berarti ’padi/beras/nasi’. Dalam hal ini, konteks sangat menentukan padanan
kata yang dimaksud.
• Suatu kata dari bahasa sumber dapat memiliki makna ganda dan mempunyai dua
padanan dalam bahasa Indonesia, misalnya, dalam bahasa Arab, kata maktab
dapat berarti ’meja’ atau ’kantor’. Penerjemah harus memilih yang mana yang
paling cocok dengan konteksnya.
• Banyak juga kata-kata yang sebetulnya memiliki padanan dalam bahasa
Indonesia, tetapi dengan konotasi khusus, misalnya, dalam bahasa Inggris, kata
café bermakna ’warungkopi’; kitchen bermakna ’dapur’.
Rasa rendah diri dan kebiasaan berbahasa orang Indonesia tampaknya ikut
menentukan dalam pengadopsian atau peminjaman istilah-istilah asing tersebut.
Istilah "dapur" digunakan untuk dapur tradisional yang kotor, sedangkan kalau
dapur itu bersih dan modern namanya kitchen. Dari istilah itu muncul kitchen-set
di mana-mana. Sama halnya dengan keempat istilah lain yang tersebut di atas.
Ada yang dipinjam bulat-bulat dalam bentuk aslinya, ada pula yang secara
perlahan-lahan disulap menjadi bahasa Indonesia, seperti café atau kafe.
Dalam petunjuk-petunjuk penerjemahan sering dikatakan bahwa penerjemah
harus menggunakan padanan istilah yang digunakan di Indonesia.
45
b. Istilah/kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Biasanya
terdapat dalam istilah budaya yang menyangkut adat/kebiasaan, bangunan,
tumbuhan, makanan dan minuman. Contoh, dalam bahasa Arab kata al-basyaam
tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, tetapi di kamus al-Munawwir, kata
tersebut diartikan ‘nama pohon’. Dalam hal ini, seorang penerjemah harus kreatif
untuk mencari padanan yang cocok dalam bahasa Indonesia, misalnya dengan
bertanya kepada ahli bahasa, baik sasaran, maupun sumber.
3. Peranti-peranti Diksi
a. Penggunaan Kata Bersinonim
Secara etimologi, kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma
yang berarti ‘nama’, dan syn yang berarti ‘dengan’. Maka secara harfiah kata
sinonimi berarti ‘nama lain untuk benda atau hal yang sama’. Secara semantik,
Verhaar mendefinisikan sebagai ungkapan (bisa berupa kata, frasa, atau kalimat)
yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain.46 Dikatakan
kurang lebih, karena tidak akan ada dua buah kata berlainan yang maknanya
persis sama. Yang sama sebenarnya hanya informasinya saja, sedangkan
maknanya tidak persis sama.47
Dalam buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Abdul Chaer: 2002)
juga disebutkan bahwa dalam buku-buku pelajaran bahasa sering dikatakan
sinonim adalah persamaan kata atau kata-kata yang sama maknanya. Pernyataan
ini jelas kurang tepat, sebab selain yang sama bukan maknanya, yang bersinonim
46 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. ke-3, h. 82.
pun bukan hanya kata dengan kata, tetapi juga banyak terjadi antara satuan-satuan
bahasa lainnya. Seperti dalam contoh berikut:
a. Sinonim antara morfem (bebas) dengan morfem (terikat), seperti antara
dia dengan nya, dalam kalimat “minta bantuan dia” dengan “minta
bantuannya.”
b. Sinonim antara kata dengan kata, seperti antara mati dengan meninggal.
c. Sinonim antara kata dengan frasa atau sebaliknya. Misalnya meninggal
dengan tutup usia.
d. Sinonim antara frasa dengan frasa. Misalnya, antara ayah ibu dengan
orangtua.
e. Sinonim antara kalimat dengan kalimat, seperti Adik menendang bola
dengan Bola ditendang adik.
Tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim. Misalnya
kata beras, salju, batu, kuning, dan lain-lain tidak memiliki sinonim.
Ada kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak pada bentuk
jadian. Misalnya kata benar bersinonim dengan kata betul, tetapi kata
kebenaran tidak bersinonim dengan kata kebetulan. Sebaliknya, ada
kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar, tetapi memiliki
sinonim pada bentuk jadian. Misalnya, kata jemur tidak mempunyai
sinonim tetapi kata menjemur ada sinonimnya, yaitu mengeringkan.
Kata-kata yang bersinonim ada yang dapat saling menggantikan ada pula
yang tidak.48 Contoh kata yang dapat digantikan satu sama lain: kata semua
bersinonim dengan kata seluruh, seperti dalam kalimat di bawah ini:
48
- Semua warga kota diungsikan.
- Seluruh warga kota diungsikan.
Sedangkan kata yang tidak dapat digantikan satu sama lain adalah kata melihat,
melirik, menonton, meninjau, dan mengintip. Kata melihat memiliki makna
umum; kata melirik memiliki makna melihat dengan sudut mata; kata menonton
memiliki makna melihat untuk kesenangan; kata meninjau memiliki makna
melihat dari tempat jauh; dan kata mengintip memiliki makna melihat dari atau
melalui celah sempit. Contoh dalam kalimat:
- Ia mengintip bioskop. (salah)
- Ia menonton bioskop. (benar)
Sinonim dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada
tempat tertsntu sehingga kalimat itu tidak membosankan. Dalam pemakaiannya
bentuk-bentuk kata yang bersinonim akan menghidupkan bahasa seseorang dan
mengkongkretkan bahasa seseorang sehingga kejelasan komunikasi (lewat bahasa
itu) akan terwujud. Dalam hal ini pemakai bahasa dapat memilih bentuk mana
yang paling tepat untuk dipergunakannya, sesuai dengan kebutuhan dan situasi
yang dihadapinya.49
b. Penggunaan Kata Bermakna Denotasi dan Konotasi
Makna denotasi dan konotasi dibedakan berdasarkan ada tidaknya nilai rasa dalam
sebuah kata. Kata denotasi tidak bernilai rasa, sedangkan kata konotasi memiliki
nilai rasa. Makna denotasi sering disebut makna konseptual, makna sebenarnya,
makna lugas, makna polos, makna sesungguhnya sesuai dengan faktanya.
Sedangkan konotasi itu bukanlah makna yang sebenarnya, melainkan makna
49
kiasan.50 Contoh kata kurus bermakna denotasi ‘keadaan tubuh seseorang yang
lebih kecil dari ukuran yang normal’.
Konotasi terbagi dua, yakni konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi
positif adalah makna tambahan dari makna kata sebenarnya yang bernilai rasa
tinggi, baik, sopan, santun, sakral, dan sejenisnya. Sementara itu, makna konotasi
negatif adalah makna tambahan dari makna kata sebenarnya yang bernilai rasa
rendah, kotor, jelek, dan sejenisnya.51 Contoh, kata ramping memiliki konotasi
positif, nilai rasa yang mengenakkan. Sebaliknya, kata kerempeng memiliki
konotasi negatif, nilai rasa yang tidak mengenakkan.
c. Penggunaan Kata Umum dan Khusus
Kata umum adalah sebuah kata yang mengacu kepada suatu hal atau kelompok
yang luas bidang lingkupnya.52 Kata khusus (hiponim) ialah bentuk (istilah) yang
maknanya terangkum oleh bentuk kata umum (superordinat)nya.53
Pada umumnya, untuk mencapai ketepatan pengertian, lebih baik memilih
kata khusus daripada kata umum, karena kata khusus memperlihatkan pertalian
yang khusus atau kepada obyek yang khusus, maka kesesuaian akan lebih cepat
diperoleh antara pembaca dan penulis. Misalnya, jika seorang mengatakan, “Si
Cathy, kucing Rani, mencakar adik saya,” maka, kata si Cathy tidak akan
menimbulkan salah interpretasi antara pembicara dan pendengar atau penulis dan
pembaca. Karena, si Cathy mengacu kepada obyek yang khusus, yaitu kucing
Rani yang bernama si Cathy.
50
Rahardi, h. 105.
51 Chaer, Linguistik Umum, h. 292. 52
Keraf, h. 90.
d. Penggunaan Kata Abstrak dan Konkret
Kata-kata abstrak ialah kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca/pendengar,
karena referennya berupa konsep. Konsep ialah gambaran dari obyek atau proses
yang berada di luar bahasa dan memahaminya harus menggunakan akal budi.54
Kata perdamaian, peradaban, dan lain-lain tidak dapat ditunjukkan dengan hanya
memperlihatkan sesuatu benda, gambarnya atau modelnya, namun harus
dijelaskan dengan definisi yang panjang lebar.
Kata konkret ialah kata-kata yang mudah dipahami karena referennya
dapat dilihat, didengar, dirasakan, atau diraba. Contoh, kata mobil, meja,
komputer, ayam, kucing, dan lain-lain. Kata-kata tersebut referennya dapat
ditunjukkan dengan cara melihat gambarnya.
Singkatnya, kata abstrak merupakan kata yang tidak mudah diserap oleh
pancaindra. Sebaliknya, kata konkret merupakan kata yang mudah diserap oleh
pancaindra.
e. Penggunaan Bentuk Idiomatis
Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna
unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal.55
Rahardi menuliskan dalam bukunya bahwa bentuk idiomatis sudah lekat
dan tidak dapat diceraikan. Contoh, sesuai dengan, sehubungan dengan, berharap
akan, berbicara tentang, dan lain-lain.56 Jadi, tidak cocok apabila ditulis sesuai
bagi, seharusnya sesuai dengan.
Dalam bahasa Indonesia ada dua macam bentuk idiom, yaitu idiom penuh
dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang unsur-unsurnya secara
54 Ibid., h. 83.
55 Chaer, Linguistik Umum, h. 296. 56
keseluruhan sudah merupakan satu kesatuan dengan satu makna, contoh
membanting tulang, menjual gigi, dan meja hijau. Sedang pada idiom sebagian
masih ada unsur yang memiliki makna leksikalnya sendiri. Misalnya, daftar hitam
yang berarti ‘daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai/dianggap
bersalah.’57 Untuk mengetahui makna sebuah idiom sebuah kata (frasa atau
kalimat) harus mencarinya di kamus.
4. Ketepatan Pilihan Kata
a. Persoalan Ketepatan Pilihan Kata
Ketepatan pilihan kata adalah kesanggupan sebuah kata untuk
menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau
pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau
pembicara.58 Hal ini menyangkut pula masalah makna kata dan kosakata
seseorang.
Dalam persoalan ketepatan kita bertanya apakah pilihan kata yang dipakai
sudah setepat-tepatnya, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan
antara pembicara dan pendengar, atau antara penulis dan pembaca.
Contoh, Dengan adanya kegiatan penelitian sastra diharapkan dapat
membantu menyediakan bahan-bahan guna penyusunan teori sastra Indonesia.
Suntingan: Kegiatan penelitian sastra Indonesia diharapkan dapat
membantu lahirnya teori sastra Indonesia.59
Setiap penulis harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya
untuk mencapai maksud tersebut, karena dengan begitu tidak akan menimbulkan
57 Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, h. 75. 58
Keraf, h. 87.
salah paham.
b. Persyaratan Ketepatan Pilihan Kata
Beberapa syarat berikut hendaknya diperhatikan setiap orang agar bisa mencapai
ketepatan pilihan katanya itu.
1. Membedakan secara cermat denotasi dari konotasi. Dari dua kata yang
mempunyai makna yang mirip satu sama lain ia harus menetapkan mana
yang akan dipergunakannya untuk mencapai maksudnya. Kalau hanya
pengertian dasar yang diinginkannya, maka ia harus memilih kata yang
denotatif; kalau ia menghendaki reaksi emosional tertentu, ia harus
memilih kata konotatif sesuai dengan sasaran yang akan dicapainya itu.
2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Penulis
harus berhati-hati memilih kata dari sekian sinonim yang ada untuk
menyampaikan apa yang diinginkannya, sehingga tidak timbul interpretasi
yang berlainan.
3. Membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Bila penulis sendiri
tidak mampu membedakan kata-kata yang mirip ejaannya itu, maka akan
mengakibatkan salah paham. Misalnya, bahwa-bawah, massa-masa,
karton-kartun, dan sebagainya.
4. Tidak boleh menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan
pendapat sendiri. Jika pemahaman itu belum dapat dipastikan, maka
penulis harus dapat menemukan makna yang tepat di dalam kamus.
Misalnya kata modern sering diartikan ‘canggih’. Padahal, kedua kata itu
5. Waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing, terutama kata-kata asing
yang mengandung akhiran asing tersebut, seperti kata kultur-kultural.
6. Harus dapat menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang
benar.
7. Harus dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Kata khusus lebih
tepat menggambarkan sesuatu daripada kata umum.
8. Mempergunakan kata-kata indria yang menunjukkan persepsi yang
khusus. Kata-kata tersebut merupakan pengalaman-peng