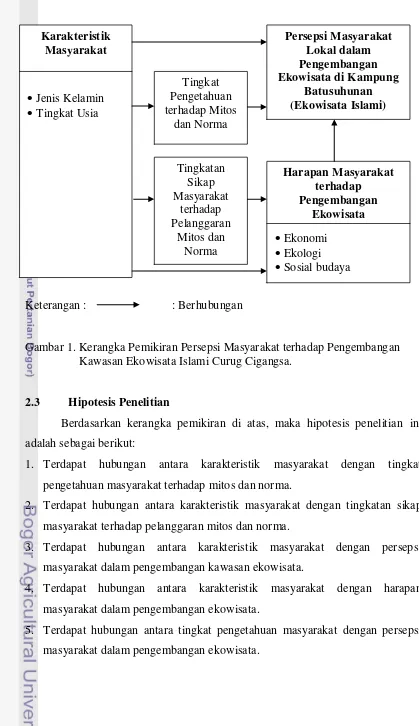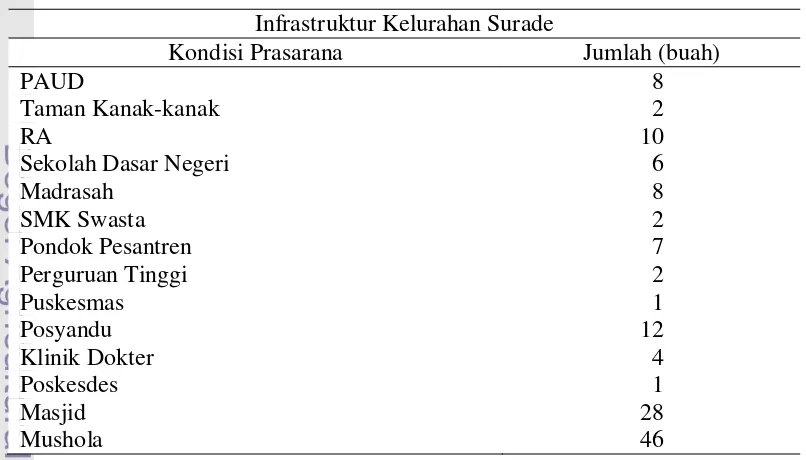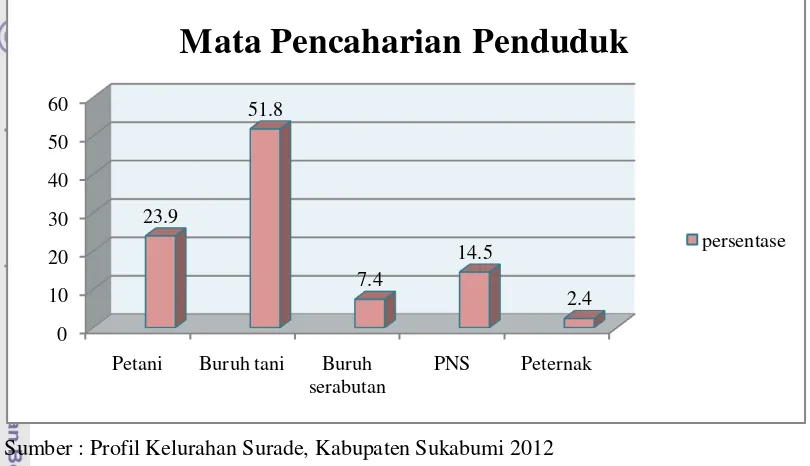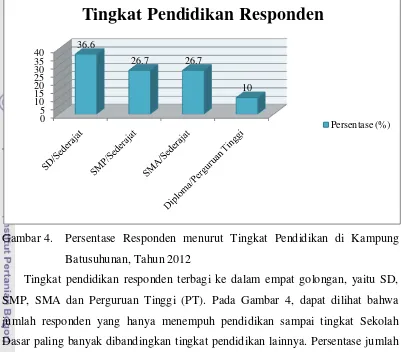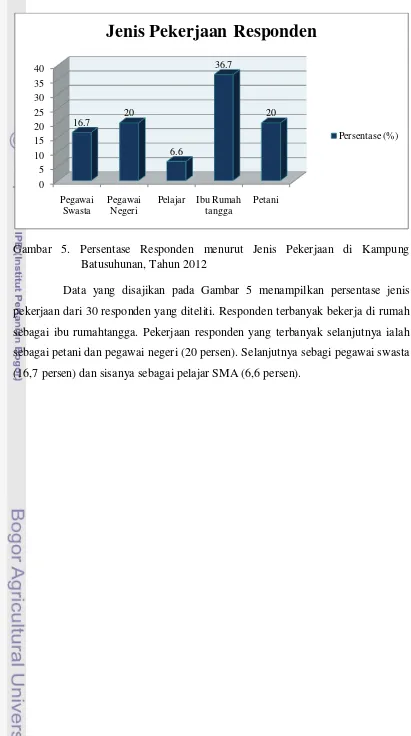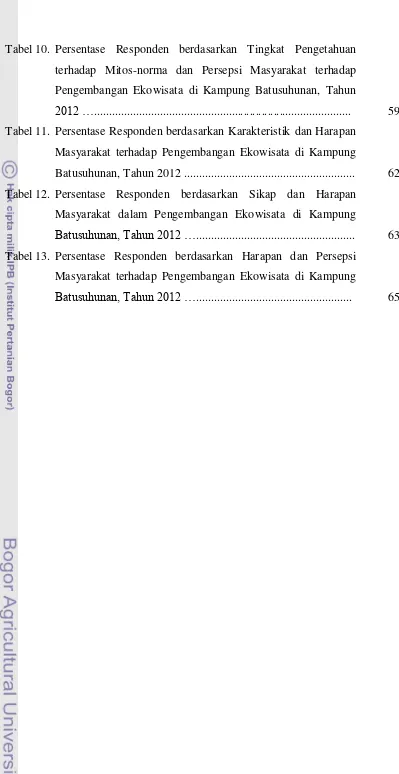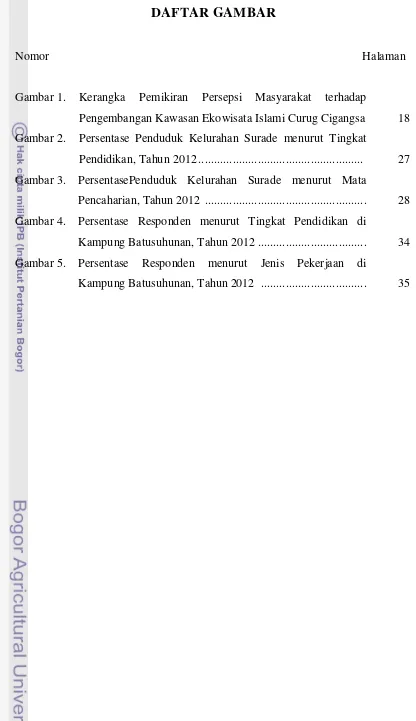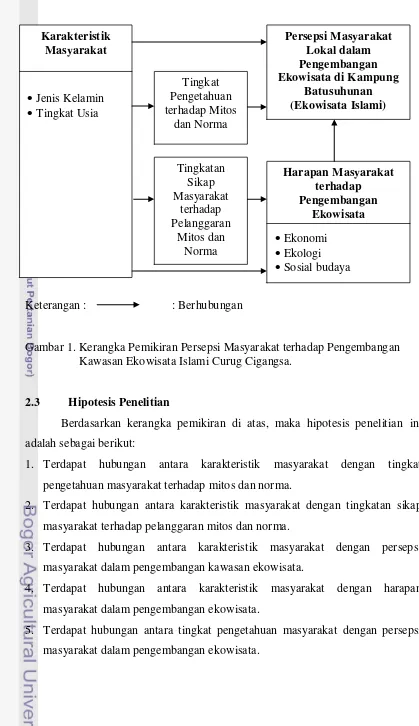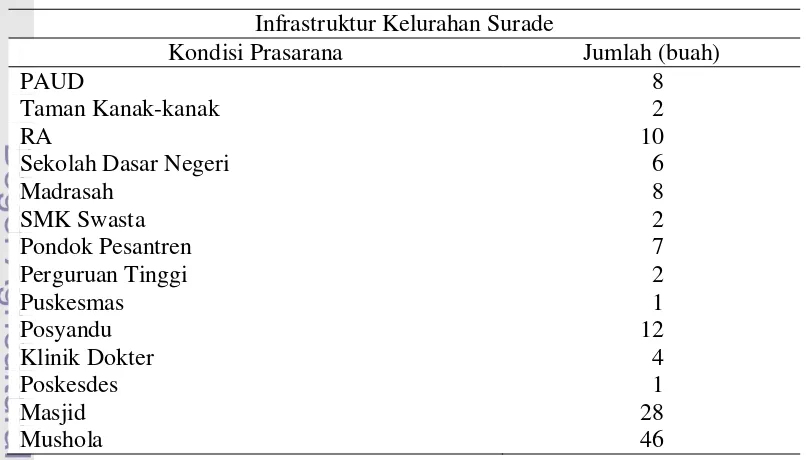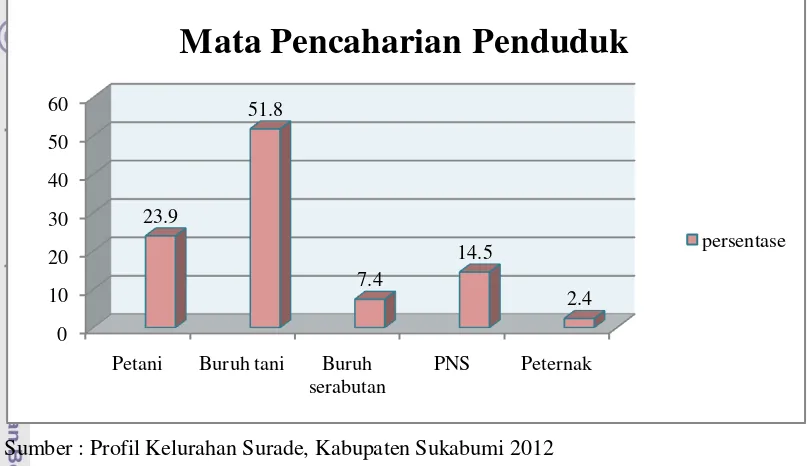ABSTRACT
Eco-tourism as one of tourism activity, that attracts attention from many participant. As a tourism activity, eco-tourism not only offering a beauty of nature but also the unique of social and cultural in some community. The research explained about the local community perception towards eco-tourism development. The research is conducted in Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. The purposes of this research are 1) to analyze level of knowledge and attitude towards myth’s and norm in Kampung Batusuhunan. That may support to protect the community from any devastating effect from tourism, 2) to analyze the local community perception in the development of “Waterfall Cigangsa Islamic Eco-tourism” area, 3) to analyze people expectations about ”Waterfall Cigangsa Islamic Eco-tourism” development. The methodology of research is based on qualitative and quantitative approaches. A quantitative data are earned from the questionnaire, while the qualitative data are earned from the open question. The results of this research showed 1) characteristic of respondent unrelated to level of knowledge and attitude towards myth’s and norm in Kampung Batusuhunan because on the best of age and sex the local people have a high level of knowledge and a firm attitudes to against the norm and myth’s, 2) the result also proved, some respondent approved to the Islamic Eco-tourism development at Kampung Batusuhunan because this idea may prevent negative effect from the ecotourism development, 3) people expectations about “Waterfall Cigangsa Islamic Eco -tourism” development mainly in economic sector because the respondents want an economic progress for the local people and Kampung Batusuhunan.
RINGKASAN
ALDILLA ADELIA Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Ekowisata Islami Curug Cigangsa (Kasus: Kampung Batusuhunan, Kelurahan
Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). Di bawah bimbingan RINA MARDIANA dan ARYA HADI DHARMAWAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mengidentifikasi serta
menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan tingkat usia terhadap tingkat
pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap mitos dan norma, persepsi
masyarakat terhadap pengembangan ekowisata, dan harapan masyarakat terhadap
pengembangan ekowisata di Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade,
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lokasi dipilih secara sengaja
(purposive) dengan pertimbangan kampung ini memiliki potensi alam berupa Curug Cigangsa yang saat ini dikembangkan sebagai kawasan “Ekowisata Islami”.
Metode yang digunakan adalah kombinasi metode kuantitatif dan
kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner untuk
mengetahui karakteristik masyarakat, hubungan tingkat pengetahuan dan sikap
terhadap mitos dan norma, persepsi masyarakat terhadap pengembangan kawasan
ekowisata, dan harapan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata. Hasil
yang didapat kemudian dipertajam melalui metode kualitatif. Metode kualitatif
menggunakan instrumen wawancara mendalam melalui pertanyaan terbuka.
Populasi dari penelitian ini adalah individu yang bermukim di Kampung
Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Jumlah responden sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan Stratified Random Sampling. Responden dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia. Pembagian golongan usia dibagi berdasarkan
Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006), yaitu golongan usia muda (18-30
tahun), golongan usia menengah (31-50) dan golongan usia tua (>51 tahun).
Jumlah pembagian responden menjadi 15 orang pria dan 15 orang wanita yang
Kampung Batusuhunan, terdapat 107 jiwa penduduk yang terbagi ke dalam 33
KK dengan jumlah pria 54 orang dan wanita 53 orang. Masyarakat Kampung
Batusuhunan umumnya merupakan masyarakat asli yang sudah secara
turun-temurun tinggal di Kampung Batusuhunan.
Penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan
masyarakat terhadap mitos dan norma dengan jenis kelamin dan tingkat usia. Data
menunjukkan bahwa baik berdasarkan jenis kelamin maupun tingkat usia,
masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mitos dan norma
yang ada serta memiliki keinginan yang kuat untuk melestarikannya. Tingkat
pengetahuan masyarakat terhadap mitos dan norma akan mempengaruhi sikap
masyarakat terhadap wisatawan yang melanggar mitos dan norma. Penelitian ini
juga menganalisis sikap masyarakat terhadap wisatawan yang melanggar mitos
dan norma berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia. Didapatkan hasil bahwa
berdasarkan jenis kelamin, pria memiliki sikap yang lebih tegas dibandingkan
wanita, sedangkan berdasarkan tingkat usia, golongan usia muda memiliki sikap
yang lebih tegas dibandingkan masyarakat dari golongan usia lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal pembentukan
ekowisata tidak semua masyarakat menyetujui ide pembentukannya. Akan tetapi,
seiring berjalannya waktu masyarakat mengikuti keputusan bersama dengan syarat konsep ekowisata yang digunakan menggunakan nama “Ekowisata Islami” dan yang mengerjakan harus masyarakat setempat. Berdasarkan data yang
diperoleh sebagian besar masyarakat Kampung Batusuhunan berpendapat bahwa
tidak akan ada kemungkinan munculnya dampak negatif dari pengembangan kawasan ini dikarenakan sudah menggunakan konsep “Ekowisata Islami”.
Penelitian ini juga menganalisis bagaimana hubungan jenis kelamin dan
tingkat usia terhadap harapan masyarakat dalam pengembangan kawasan
ekowisata. Masyarakat Kampung Batusuhunan memiliki harapan yang tinggi
dalam bidang ekonomi dibandingkan dalam bidang ekologi dan sosial budaya, hal
ini disebabkan masyarakat menginginkan adanya peningkatan pendapatan untuk
1.1 Latar Belakang
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri), dan nomos (peraturan) atau „undang-undang‟ sehingga otonomi dapat diartikan sebagai peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya
berkembang menjadi pemerintahan sendiri (Salam 2007). Menurut UU No. 32
Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Lahirnya otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan
pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
masing-masing daerah dengan keterlibatan berbagai pihak dari daerah tersebut.
Hal ini diharapkan dapat menjadikan kemampuan masyarakat daerah menjadi
semakin berkembang dan maju.
Kebijakan otonomi daerah, menuntut adanya suatu upaya dari tiap
stakeholder dan masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk membangun daerah masing-masing guna menambah pendapatan daerah. Salah satu jalan keluar yang
diambil oleh masyarakat adalah dengan menggali sumberdaya daerah yang ada
dan mengelola itu menjadi suatu sumber pendapatan daerah. Sektor pariwisata dan
ekowisata sangat cocok dijadikan sumber pendapatan daerah mengingat Indonesia
sebagai salah satu negara megabiodeversity atau memiliki berbagai keanekaragaman hayati dan didukung keindahan alamnya yang mempesona, serta
memiliki beranekaragam budaya, berpeluang sangat besar untuk mengandalkan
pariwisata alam (ekowisata) sebagai sumber pendapatan.
Pada saat ini, konsep ekowisata telah berkembang pesat. Ekowisata ini
kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari
keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata tidak dapat
dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata juga disebut sebagai
bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab. Ekowisata merupakan suatu
pengembangan, ekowisata juga menggunakan strategi konservasi, oleh karena itu
ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan
keaslian ekosistem di areal yang masih alami.
Kegiatan ekowisata tidak hanya menawarkan keindahan alam sebagai
obyek wisata, tetapi juga meliputi kehidupan masyarakat daerah sekitar.
Masyarakat lokal biasanya memiliki keunikan budaya yang dianggap dapat
menjadi sesuatu yang berpotensi untuk menarik minat wisatawan. Wisatawan
tidak saja dapat menikmati keindahan alam, tetapi juga dapat mempelajari
kehidupan masyarakat lokal yang memiliki keunikan masing-masing. Kehidupan
masyarakat lokal umumnya masih erat dengan kearifan lokal, tradisi, religi, dan
ritus-ritus kebudayaan yang kesemuanya itu menjadi daya tarik sendiri bagi
tiap-tiap daerah.
Dalam perkembangan ekowisata, akan memunculkan dampak baik negatif
maupun positif. Dampak positif yang diharapkan dari pengembangan kawasan
ekowisata adalah terpeliharanya lingkungan hidup serta dimanfaatkannya
lingkungan hidup tersebut menjadi jasa lingkungan yang memberdayakan
ekonomi lokal. Dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan ekowisata akan
memberikan pengaruh nyata bagi kemajuan masyarakat lokal. Dampak positif
yang dihasilkan biasanya terlihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat
dan kemajuan daerah tujuan ekowisata. Akan tetapi, perkembangan ekowisata
yang tidak terorganisir dengan baik, hanya akan memberikan dampak negatif baik
terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan sosial budaya komunitas lokal.
Oleh karena itu, dalam pengembangan ekowisata dibutuhkan suatu pedoman atau
prinsip yang dipegang masyarakat sebagai mekanisme untuk mereduksi dampak
negatif yang akan masuk ke dalam komunitas mereka. Pengetahuan, mitos dan
keyakinan yang dipercaya masyarakat adat lokal tentu saja memberikan pengaruh
yang sangat kuat terhadap tingkah laku dan cara hidup masyarakat. Apabila hal itu
terus dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kemungkinan
masuknya dampak negatif dari perkembangan ekowisata dapat dihindari.
Keyakinan masyarakat yang kuat akan mencegah masuknya pengaruh-pengaruh
Salah satu wilayah yang memiliki potensi sebagai kawasan ekowisata ialah
Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa
Barat. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang masuk ke dalam rencana
pengembangan prioritas di Kelurahan Surade. Surade sendiri ialah sebuah
kelurahan yang terletak di selatan Kabupaten Sukabumi. Jarak dari kota Sukabumi
menuju Surade sekitar 100 km. Kelurahan Surade merupakan kelurahan yang
paling maju dan strategis dalam mendukung visi Sukabumi Selatan di bidang
pariwisata. Kampung Batusuhunan terletak di bagian selatan Kelurahan Surade.
Kampung Batusuhunan sendiri menjadi prioritas pertama dalam rencana
pembangunan karena terdapat curug yang berpotensi untuk dijadikan kawasan
ekowisata, yang diberi nama Curug Cigangsa. Curug Cigangsa terdiri dari dua tingkat dan diperkirakan terbentuk akibat gempa yang cukup kuat sehingga
mengakibatkan longsor. Curug ini memiliki debit air yang kecil, hal ini
dikarenakan di bagian hulunya dibendung untuk keperluan irigasi. Di sekitar
lokasi ini juga terdapat sebuah batu. Batu ini oleh masyarakat setempat disebut
dengan Batu Masigit, atau Batu Masjid. Kampung Batusuhunan, selain memilki
keindahan alam yang oleh orang-orang disebut “the little Niagara” juga memiliki
keunikan sendiri yaitu masyarakatnya yang merupakan masyarakat adat dan Islam
yang sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam. Sehingga konsep ekowisata
yang ditawarkan di Kampung Batusuhunan adalah “Ekowisata Islami” yang
sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat yang masih sangat Islami.
Mengingat ekowisata di Kampung Batusuhunan ini merupakan ekowisata
yang baru saja berkembang, maka konsep ekowisata Islami ini dapat dijadikan
pedoman bagi masyarakat dan wisatawan agar dampak negatif dari ekowisata
yang biasanya muncul dapat dihindari. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan ekowisata ini tentunya menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan “Ekowisata Islami” di Kampung Batusuhunan, oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap perkembangan konsep “Ekowisata Islami” di Kampung Batusuhunan akan sangat menentukan keberlanjutan konsep ini. Persepsi masyarakat akan dibedakan
berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin.
Hal ini dikarenakan jenis kelamin dan golongan umur masyarakat akan
“Ekowisata Islami”, terhadap upaya pencegahan dampak negatif dan persepsi masyarakat terhadap kesiapan infrastruktur ekowisata.
1.2 Rumusan Masalah
Adanya otonomi daerah telah menjadikan masing-masing daerah berusaha
menambah pendapatan daerah guna memajukan daerahnya. Salah satu langkah
yang banyak ditempuh oleh pemerintah daerah antara lain dengan membuka suatu
kawasan yang awalnya hanya sebuah pemukiman biasa, menjadi kawasan
ekowisata. Ekowisata sendiri berbeda dengan pariwisata pada umumnya.
Pariwisata yang hanya mementingkan kebutuhan wisatawan tidak sesuai dengan
konsep konservasi lingkungan. Daerah tujuan ekowisata biasanya adalah daerah
yang memiliki potensi alam yang indah, juga potensi kebudayaan berupa cara
hidup atau kebiasaan hidup masyarakat yang dinilai unik.
Pengembangan suatu kawasan menjadi sebuah kawasan ekowisata telah
menjadikan kawasan tersebut mulai terbuka dengan dunia luar melalui interaksi
sosial dengan wisatawan. Masyarakat yang tadinya hidup dengan ketentuan dan
cara hidupnya masing-masing, kini mulai terpengaruh dengan dunia luar.
Pengembangan kawasan ekowisata dapat menimbulkan dampak positif maupun
negatif. Dampak positif merupakan suatu hasil yang diharapkan dan dampak
negatif merupakan suatu hal yang sebaiknya dihindari. Dampak negatif dari
kegiatan ekowisata antara lain ialah terancamnya lingkungan hidup akibat
dibangunnya sarana dan prasarana ekowisata, lunturnya kebudayaan masyarakat
dan dampak-dampak negatif lain yang nantinya hanya merugikan masyarakat
sebagai komunitas lokal yang mendiami kawasan tersebut.
Kampung Batusuhunan yang terdapat di Kelurahan Surade, Kabupaten
Sukabumi merupakan sebuah kawasan yang sedang dalam pengembangan untuk
dijadikan kawasan ekowisata. Masyarakat yang mendiami Kampung Batusuhunan
merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh pedoman dan
prinsip-prinsip Islam. Berkembangnya kawasan ini menjadi sebuah kawasan ekowisata
dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan juga
kehidupan sosial budaya masyarakat berupa pergeseran nilai-nilai tradisi yang
pedoman bagi masyarakat sekitar agar dampak negatif dari kegiatan ekowisata
dapat dihindari.
Masyarakat adat merupakan masyarakat yang memiliki norma, mitos, dan
kepercayaan sendiri. Norma, mitos dan kepercayaan itu biasanya dijadikan
pedoman dalam cara hidup masyarakat. Norma, mitos dan kepercayaan biasanya
bersifat turun-temurun dan dilestarikan oleh masyarakat adat. Seperangkat norma
dan sistem religi tersebut diharapkan dapat menjadi penyaring pengaruh dari luar
terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif dari aktivitas ekowisata
(berupa hadirnya wisatawan) yang memberikan dampak merugikan kepada
masyarakat setempat. Persepsi masyarakat setempat dan harapan masyarakat
dalam pengembangan ekowisata juga akan sangat menentukan keberlanjutan
ekowisata tersebut. Untuk itu, studi ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam
mengenai konsep “Ekowisata Islami” yang dijadikan landasan oleh masyarakat
setempat untuk mengembangkan kawasan ekowisata di Kampung Batusuhunan.
Adapun pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap mitos dan
norma di Kampung Batusuhunan dan Curug Cigangsa?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengembangan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”?
3. Bagaimana harapan masyarakat terhadap pengembangan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan
dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap mitos dan
norma di Kampung Batusuhunan dan Curug Cigangsa.
2. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap pengembangan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”.
1.4 Kegunaan Penelitian
Mengacu kepada tujuan penelitian, maka penelitian ini akan bermanfaat
bagi kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Secara khusus kegunaan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
pengetahuan serta menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji
lebih jauh mengenai konsep ekowisata dan hubungannya dengan masyarakat.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan
informasi mengenai persepsi dan harapan masyarakat adat Kampung
Batusuhunan dalam pengembangan ekowisata Curug Cigangsa.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk
semakin mempersiapkan diri terhadap kemungkinan dampak negatif yang
akan timbul dari kegiatan ekowisata melalui penguatan kearifan lokal yang
BAB II
PENDEKATAN TEORITIS
2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Ekowisata
2.1.1.1 Pengertian Ekowisata
Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata yang
mengedepankan kelestarian sumberdaya pariwisata. TIES (2002) dalam Damanik dan Weber (2006) menyatakan ekowisata dapat dipandang sebagai perjalanan
pariwisata yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan
memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata juga dapat
didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang memberikan dampak kecil
terhadap kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus meningkatkan pendapatan
masyarakat lokal melalui perluasan lapangan kerja. Hal yang sama dikemukakan
oleh Hidayati et al. (2003) yang mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke suatu lokasi dengan melakukan konservasi alam dan
menjaga kesejahteraan penduduk di sekitar lokasi wisata. Seperti yang
dikemukakan oleh Tafalas (2010), ekowisata merupakan perjalanan wisata yang
bertanggung jawab, karena selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
lokal, ekowisata juga memikirkan dan mengembangkan konservasi lingkungan.
Ekowisata dapat memberikan manfaat sebagai lapangan kerja baru yang sangat
berguna bagi kehidupan masyarakat sekitar. Damanik dan Weber (2006)
mendefinisikan ekowisata ke dalam tiga perspektif, yaitu ekowisata sebagai
produk, ekowisata sebagai pasar dan ekowisata sebagai pendekatan
pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang
berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan sebuah
perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Sebagai
pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Dengan kata lain,
ekowisata ialah suatu bentuk kegiatan wisata yang menjual keindahan alam juga
kehidupan masyarakatnya. Ekowisata memikirkan keberlanjutan lingkungan dan
secara aktif menyumbang dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat juga
Fennell (1999) dalam Hidayati et al. (2003) mendefinisikan ekowisata
sebagai kegiatan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus
pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan
tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah pada lingkungan. Ekowisata
tidak bersifat konsumtif dan berorientasi lokal (dalam hal kontrol,
manfaat/keuntungan yang dapat diambil dari skala usaha). Sedangkan Wood
(2002) dalam Hidayati et al. (2003) mendefinisikan bahwa ekowisata sebagai kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata
alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaaan dan
wisata budaya.
2.1.1.2 Prinsip dan Karakteristik Ekowisata
TIES (2000) dalam Damanik dan Weber (2006) mengidentifikasi beberapa prinsip ekowisata yang harus diikuti oleh pelaksana dan partisipator, yaitu:
a. Meminimalkan dampak negatif;
b. Membangun kesadaran serta menghormati budaya dan lingkungan;
c. Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan masyarakat sekitar;
d. Memberikan manfaat finansial secara langsung bagi konservasi;
e. Memberikan manfaat finansial bagi masyarakat setempat;
f. Menumbuhkan kepekaan sosial, lingkungan dan politik bagi masyarakat; dan
g. Mendukung hak asasi manusia dan perjanjian buruh.
Ekowisata berbeda dengan kegiatan pariwisata lainnya karena ekowisata
memiliki karakteristik yang spesifik dengan adanya kepedulian pada pelestarian
lingkungan dan pemberian manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Menurut
Hidayati et al. (2003), kegiatan ekowisata harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan seperti: (1) berbasis pada wisata alam; (2)
menekankan pada kegiatan konservasi; (3) mengacu pada pembangunan
pariwisata yang berkelanjutan; (4) berkaitan dengan kegiatan pengembangan
pendidikan; (5) mengakomodasikan budaya lokal; dan (7) memberi kontribusi
positif pada ekonomi lokal.
keberlanjutan ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan. Tujuh
prinsip tersebut, yaitu:
1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam
dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya
setempat;
2. Pendidikan konservasi lingkungan, dengan mendidik wisatawan dan
masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi;
3. Menghasilkan pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan
yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan
pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan;
4. Adanya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan;
5. Memberikan keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat;
6. Menjaga keharmonisan dengan alam; dan
7. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah
dengan daya dukung kawasan buatan.
Ekowisata sendiri adalah hal yang berbeda dengan pariwisata. Ekowisata
merupakan bagian dari konsep pariwisata. Menurut Damanik dan Weber (2006),
ekowisata memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan
pariwisata, yaitu:
1. Aktivitas wisata berkaitan dengan konservasi lingkungan;
2. Penyedia jasa wisata tidak hanya menyiapkan atraksi untuk menarik tamu,
tetapi juga menawarkan peluang bagi mereka untuk lebih menghargai
lingkungan;
3. Kegiatan wisata yang berbasis alam;
4. Organisasi perjalanan (tour operator) menunjukkan tanggung jawab finansial dalam pelestarian lingkungan hijau yang dikunjungi atau dinikmati oleh
wisatawan dan wisatawan juga melakukan kegiatan yang terkait dengan
konservasi;
5. Kegiatan wisata dilakukan tidak hanya dengan tujuan untuk menikmati
keindahan dan kekayaan alam, tetapi juga untuk mengumpulkan dana yang
akan digunakan untuk pelestarian objek daya tarik wisata (ODTW);
7. Pendapatan dari pariwisata tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan
konservasi lokal, tetapi juga untuk membantu pengembangan masyarakat
setempat secara berkelanjutan;
8. Perjalanan wisata menggunakan tekonologi sederhana yang tersedia di daerah
tujuan wisata; dan
9. Kegiatan wisata berskala kecil.
Ekowisata ialah suatu bentuk pariwisata yang memikirkan keberlanjutan
dan merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan. Dalam prakteknya,
ekowisata mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang
membedakannya dengan wisata lain. Berdasarkan UNEP (2000) dalam Damanik dan Weber (2006), prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam kegiatan ekowisata
seperti (a) secara aktif menyumbang untuk kegiatan konservasi alam dan budaya;
(b) melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan
wisata, serta memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan mereka; dan
(c) dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk
kelompok kecil.
2.1.1.3 Potensi Ekowisata dan Dampaknya
Ekowisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan.
Pengelolaan ekowisata yang baik akan menyebabkan beberapa keuntungan dalam
berbagai aspek. Akan tetapi, apabila tidak dikelola dengan benar, maka ekowisata
dapat berpotensi menimbulkan masalah atau dampak negatif terhadap kehidupan
sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.
Berdasarkan kacamata ekonomi makro, ekowisata memberikan beberapa dampak positif (Yoeti 2008), yaitu:
1. Menciptakan kesempatan berusaha;
2. Menciptakan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan
masyarakat, sebagai akibat multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar;
4. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah;
6. Mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor
ekonomi lainnya; dan
7. Memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pembayaran mengalami surplus,
dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, dan
sebaliknya.
Pengembangan ekowisata tidak saja memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan beberapa dampak negatif, antara lain (Yoeti 2008):
1. Sumber-sumber hayati menjadi rusak, yang menyebabkan Indonesia akan
kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang;
2. Pembuangan sampah sembarangan yang selain menyebabkan bau tidak sedap,
juga dapat membuat tanaman di sekitarnya mati;
3. Sering terjadi komersialisasi seni-budaya; dan
4. Terjadi demonstration effect, kepribadian anak-anak muda rusak. Cara berpakaian anak-anak sudah mendunia berkaos oblong dan bercelana
kedodoran.
Yoeti (2008) mengemukakan bahwa kegiatan ekowisata dapat
memberikan dampak pada berbagai aspek seperti sosial-budaya, ekonomi, dan
lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif dan negatif :
a. Dampak ekowisata terhadap sosial-budaya:
Kegiatan ekowisata yang menyajikan kehidupan sosial budaya masyarakat,
secara tidak langsung telah memberikan dampak bagi kehidupan sosial budaya
masyarakat sekitar tempat wisata. Dampak yang diberikan antara lain, dengan
adanya kegiatan ekowisata, masyarakat semakin melestarikan budaya dan adat
istiadat mereka. Hal ini dikarenakan budaya dan adat istiadat akan semakin
menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah mereka. Dampak tersebut
merupakan dampak yang diharapkan dari kegiatan ekowisata. Akan tetapi,
kegiatan ekowisata juga dapat memberikan dampak negatif berupa lunturnya adat
istiadat dan kebudayaan masyarakar sekitar. Hal ini dikarenakan, dengan adanya
ekowisata maka akan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap dunia luar
yang dibawa oleh para wisatawan. Hal ini dapat membuat masyarakat lokal yang
tadinya menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan mereka, menjadi mulai
tertarik dengan kebudayaan yang datang dari luar. Dampak negatif ini menjadi
mempertontonkan keindahan alam, tetapi juga mempertunjukkan kehidupan sosial
budaya masyarakat sekitar yang dianggap unik dan menarik bagi para wisatawan.
b. Dampak ekowisata terhadap ekonomi:
Ekowisata yang semakin diminati oleh para wisatawan telah memberikan
sumbangan yang besar terhadap sektor perekonomian pemerintah daerah juga
masyarakat di sekitar tempat wisata. Menurut Sedarmayanti (2005) kegiatan
ekowisata yang banyak menarik minat wisatawan telah memberikan sumbangan
devisa untuk negara dan juga telah membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sekitar. Masyarakat tidak saja mendapatkan pekerjaan, tetapi juga
dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru yang menunjang kegiatan
pariwisata.
c. Dampak ekowisata terhadap lingkungan:
Ekowisata sebagai kegiatan pariwisata yang menonjolkan kelestarian
lingkungan menjadikan kegiatan ini lebih memperhatikan kondisi lingkungan
daerah sekitar tempat wisata. Pemerintah daerah beserta aktor-aktor penunjang
pariwisata lainnya berusaha melestarikan lingkungan dengan tujuan untuk
menarik minat wisatawan. Keinginan wisatawan terhadap lingkungan hidup yang
tenang, bersih dan jauh dari polusi menjadikan ekowisata banyak dipilih orang
sebagai bentuk pariwisata yang diinginkan. Ekowisata sebagai kegiatan pariwisata
yang bertanggung jawab juga menuntut adanya keterlibatan dari wisatawan untuk
ikut melestarikan daerah yang dijadikan tujuan wisata. Konsep ekowisata secara
tidak langsung juga dapat dijadikan jalan keluar mengenai permasalahan
lingkungan yang selama ini menjadi perhatian orang banyak. Kegiatan pariwisata
yang dulu hanya memikirkan keinginan dan kepuasan wisatawan tanpa
memikirkan dampak yang dialami oleh lingkungan semakin lama semakin
ditinggalkan. Oleh karena itu, ekowisata secara tidak langsung telah memberikan
dampak positif terhadap lingkungan sekitar tempat wisata.
2.1.2 Masyarakat Adat
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut
suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh
suatu daerah dan memiliki kebudayaan sendiri yang telah ada secara
turun-temurun dinamakan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang
yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelumnya, yang berkembang di
daerah mereka dan menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas lain yang
sekarang mendiami daerah tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang
dominan dari masyarakat tetapi bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan
mewariskan tradisi leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya
sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa,
sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.
Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan dirangkum oleh
berbagai sumber menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki lima ciri yang
berbeda dengan masyarakat biasa. Karakteristik masyarakat tersebut antara lain:
(1) sekelompok orang yang membentuk masyarakat atau komunitas;
(2) memiliki lokasi yang merupakan tempat tinggal mereka;
(3) memiliki aturan dan hukum yang jelas;
(4) kondisi kultural, budaya dan ekonomi yang khas sehingga berbeda dengan
masyarakat lainnya; dan
(5) berasal dari keturunan yang sama.
Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan
wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya
merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan
kualitas produk wisata (Damanik dan Weber 2006). Masyarakat lokal juga
merupakan pemilik dari atraksi wisata yang dipertunjukkan untuk wisatawan. Air,
tanah, hutan dan lanskap merupakan sumberdaya pariwisata milik masyarakat
yang juga dikonsumsi oleh wisatawan. Masyarakat adat juga memiliki kearifan
lokal, kebudayaan, tradisi, dan sistem religi yang dapat dijadikan landasan atau
prinsip dalam perkembangan ekowisata.
2.1.3 Kearifan Lokal
Menurut Keraf (2002) kearifan lokal (tradisional) adalah semua bentuk
pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau
ekologis. Kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia,
tetapi juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang
manusia, alam, dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini
harus dibangun. Konsep kearifan lokal menurut Mitchell, et al. (2000) berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional.
Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam suatu sistem sosial
masyarakat, dapat dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari suatu
generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk, dan menuntun pola
perilaku manusia sehari-hari. Kearifan lokal yang terdapat di masyarakat biasanya
tercermin dalam norma, mitos, nilai, kebudayaan, tradisi, dan sistem religi yang
menjadi pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat adat. Berikut ini akan
dijelaskan mengenai norma dan mitos. Norma dan mitos merupakan bagian dari
kearifan lokal dikarenakan norma dan mitos merupakan sesuatu yang berasal dari
masyarakat dan dipercayai sebagai sebuah kepercayaan yang dianut bersama.
A. Norma
Norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam
suatu kelompok masyarakat. Norma akan berkembang seiring dengan
kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat dan sering disebut dengan peraturan sosial.
Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu
kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Norma
disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung
tertib sebagaimana yang diharapkan. Pelanggaran dalam norma yang berlaku
biasanya akan diberikan hukuman. Norma merupakan hasil buatan manusia
sebagai makhluk sosial. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan
petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.
Berdasarkan pendapat beberapa sosiolog dalam buku “Pengantar Sosiologi” karya Setiadi dan Kolip (2010), di dalam norma terdapat tingkatan-tingkatan yang
membedakan norma yang satu dan lainnya. Tingkatan norma tersebut antara lain:
b. Kebiasaan (folkways): suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk
yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas
dan dianggap baik dan benar;
c. Tata kelakuan (mores): sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna
melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap
anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang
suatu perbuatan; dan
d. Adat istiadat (custom): kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap
masyarakat yang memilikinya.
B. Mitos
Mitos adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk
setengah dewa yang terjadi di dunia lain dan dianggap benar-benar terjadi oleh
yang punya cerita atau para penganutnya. Mitos pada umumnya menceritakan
tentang terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi,
petualangan para dewa, kisah percintaan mereka dan sebagainya. Menurut
Armstrong (2005), mitos adalah sarana masyarakat kuno untuk menemukan
kebenaran dalam kehidupannya. Fungsi mitos sendiri adalah untuk
memperpanjang harapan manusia yang mengalami kekerasan, ketertindasan, dan
ketakutan. Mitos adalah pemandu yang dapat memberikan saran untuk bagaimana
seharusnya manusia bertindak.
Mitos akan dianggap benar apabila mitos itu dapat memberikan pengaruh
bagi masyarakat. Manusia modern sama sekali tidak dapat menghapuskan seluruh
masa lampaunya karena dia hasil produksi dari masa lampau. Manusia modern
akan menerima warisan dari masa lampau yang terus melekat dalam pikirannya,
warisan itu antara lain adalah mitos (Eliade 1963 dalam Susanto 1987). 2.1.4 Persepsi
Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang terhadap
obyek tertentu. Menurut Young (1951) persepsi merupakan aktivitas mengindera,
mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun
stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan
diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu
berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan, dan lain-lain. Di dalam proses
persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang
dapat bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang, dan sebagainya. Dengan
adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil
untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula
(Polak 1991).
DeVito (1997) mengemukakan bahwa karakteristik seseorang merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Lionberger dan
Gwin (1982) juga mengatakan bahwa karakteristik personal dapat mempengaruhi
penerimaan individu terhadap perubahan unsur. Karakteristik tersebut dapat terdiri
dari pendidikan, tempat tinggal, kedudukan, usia, dan jenis kelamin. Jenis kelamin
dan usia seseorang akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut memberikan
persepsi mengenai suatu benda atau situasi. Hal ini dikarenakan persepsi yang
diberikan antara pria dan wanita akan berbeda. Usia juga akan menentukan
persepsi seseorang. Orangtua dan anaknya akan memberikan persepsi yang
berbeda mengenai suatu benda yang sama.
2.2 Kerangka Pemikiran
Kampung Batusuhunan merupakan salah satu kampung di Kelurahan
Surade yang sedang dijadikan prioritas utama dalam pembangunan. Mengingat di
Kampung Batusuhunan terdapat potensi ekowisata berupa Curug Cigangsa dan
Batu Masigit, maka ekowisata dijadikan titik awal pembangunan di Kampung
Batusuhunan. Masyarakat sebagai pemilik kawasan dan sebagai pelaksana
kegiatan ekowisata tentu saja memiliki peran penting dalam kegiatan ekowisata.
Penelitian ini melihat hubungan karakteristik masyarakat yang terdiri dari jenis
kelamin dan tingkat usia dengan tingkat pengetahuan terhadap mitos dan norma,
tingkatan sikap masyarakat terhadap pelanggaran mitos dan norma, persepsi
masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata di Kampung Batusuhunan dan
hubungan karakteristik masyarakat dengan harapan masyarakat terhadap
Perkembangan kawasan ekowisata di Kampung Batusuhunan tentu saja
akan sangat bergantung pada persepsi masyarakat lokal yang mendiami daerah
tersebut. Sehingga persepsi masyarakat lokal terhadap pengembangan kawasan
ekowisata Curug Cigangsa menjadi faktor penting yang menentukan
perkembangan “Ekowisata Islami” yang akan dilaksanakan.
“Ekowisata Islami” merupakan ekowisata yang dalam pelaksanaannya berpedoman dengan mitos dan norma yang dibuat berdasarkan kaidah Islam. Hal
ini menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap mitos dan norma menjadi sangat penting dalam pengembangan kawasan “Ekowisata Islami”. Pada pelaksanaanya, tentu saja akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan
yang datang ke lokasi ekowisata, oleh karena itu tingkatan sikap masyarakat
terhadap pelanggaran mitos dan norma juga menjadi sangat penting.
Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan ekowisata menjadikan
masyarakat setempat memiliki harapan yang berbeda-beda terhadap
pengembangan ekowisata. Harapan masyarakat terhadap pengembangan
ekowisata dilihat berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia. Harapan masyarakat
nantinya akan berhubungan dengan persepsi masyarakat lokal dalam
pengembangan kawasan ekowisata. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada
Keterangan : : Berhubungan
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Ekowisata Islami Curug Cigangsa.
2.3 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat
pengetahuan masyarakat terhadap mitos dan norma.
2. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkatan sikap
masyarakat terhadap pelanggaran mitos dan norma.
3. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan persepsi
masyarakat dalam pengembangan kawasan ekowisata.
4. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan harapan
masyarakat dalam pengembangan ekowisata.
5. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan persepsi
masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Karakteristik
Masyarakat
Jenis Kelamin Tingkat Usia
Persepsi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Ekowisata di Kampung
6. Terdapat hubungan antara tingkatan sikap masyarakat terhadap pelanggaran
mitos dan norma dengan harapan masyarakat dalam pengembangan ekowisata.
7. Terdapat hubungan antara harapan masyarakat dengan persepsi masyarakat
dalam pengembangan ekowisata.
2.4 Definisi Operasional
Penelitian ini menggunakan beberapa istilah operasional yang digunakan
untuk mengukur berbagai peubah. Masing-masing peubah terlebih dahulu diberi
batasan sehingga dapat ditentukan indikator pengukurannya. Istilah-istilah
tersebut yaitu:
1. Untuk melihat karakteristik masyarakat, salah satunya diukur dari tingkat usia.
Tingkat Usia responden yaitu rentang waktu saat lahir sampai saat
pengambilan data, dihitung saat ulang tahun terakhir dan diukur dalam satuan
tahun, diukur dengan skala interval, dengan batasan usia : (Havighurst 1950
dalam Mugniesyah 2006)
a. Golongan usia muda : 18 tahun – 30 tahun
b. Golongan usia menengah : 31 tahun – 50 tahun c. Golongan usia tua : > 51 tahun
2. Jenis kelamin menjadi indikator karakteristik masyarakat yang dipahami
sebagai status biologis individu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan,
diukur dengan skala nominal.
3. Tingkat pengetahuan terhadap mitos dan norma, ialah kedalaman masyarakat
(responden) dalam mengetahui dan memahami mitos-mitos dan
norma-norma yang terdapat di Kampung Batusuhunan. Tingkat pengetahuan diukur
dengan menggunakan skala nominal.
Nilai : Tidak Tahu = 1, Tahu = 2 a. Rendah : skor 10-15
b. Tinggi : skor 16-20
4. Tingkatan sikap masyarakat terhadap wisatawan yang melanggar mitos dan
norma, yaitu respon berupa sikap apa yang akan dibentuk oleh masyarakat
diberlakukan di Kampung Batusuhunan. Sikap masyarakat diukur dengan
menggunakan skala ordinal.
Nilai : Diam saja = 1, Menegur = 2, Memberi Sanksi = 3 a. Rendah : skor 9-15
b. Sedang : skor 16-22
c. Tinggi : skor 23-27
5. Persepsi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata di Kampung
Batusuhunan, diukur melalui indikator pendapat masyarakat terhadap pengembangan kawasan “Ekowisata Islami” Curug Cigangsa, pendapat masyarakat terhadap kemungkinan dampak negatif, pendapat masyarakat
mengenai proporsi dampak ekowisata dan pendapat masyarakat terhadap konsep “Ekowisata Islami”.
6. Harapan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata, yaitu ekspektasi ke
masa depan yang diinginkan oleh masyarakat (responden) dari
perkembangan ekowisata di Kampung Batusuhunan, dilihat dari aspek
BAB III
PENDEKATAN LAPANGAN
1.1 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung oleh
data kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengujian hipotesis
atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian explanatory merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel
penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya
(Singarimbun dan Effendi 1989).
Data kuantitatif didapatkan melalui kuesioner kepada responden. Data
kualitatif didapatkan melalui pertanyaan terbuka kepada responden dan hasil
konsultasi atau wawancara mendalam antara peneliti dan informan.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan/hasil kuesioner yang dilakukan
melalui wawancara langsung kepada responden. Selain itu, dilakukan juga
wawancara mendalam kepada informan. Data sekunder diperoleh melalui studi
literatur yang sumbernya berasal dari berbagai arsip/dokumen-dokumen
Pemerintah Kelurahan Surade dan Kampung Batusuhunan.
3.3 Lokasi Dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di lokasi tempat dikembangkannya kawasan
ekowisata Curug Cigangsa, yaitu di Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara
sengaja (purposive) berdasarkan observasi melalui internet dan studi langsung pada tempat dengan pertimbangan:
1. Kampung Batusuhunan memiliki potensi ekologi berupa Curug Cigangsa yang
memiliki keindahan yang masih alami. Di kampung ini juga terdapat prasasti
Batu Masigit/Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat sekitar yang 100
2. Kampung Batusuhunan merupakan kampung yang lokasinya paling dekat
dengan Curug Cigangsa, sehingga kegiatan ekowisata yang dilakukan di
Curug Cigangsa akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat
Kampung Batusuhunan.
3. Kampung Batusuhunan merupakan kawasan yang menjadi prioritas pertama
dalam pembangunan wilayah Kelurahan Surade karena selama ini wilayah
Kampung Batusuhunan kurang berkembang dibandingkan dengan
kampung-kampung di Kelurahan Surade lainnya
Penelitian dilakukan selama enam bulan dengan kegiatan penelitian yang meliputi survei lokasi, penyusunan proposal skripsi, kolokium, pengambilan data lapangan, pengolahan data dan analisis data, penulisan draft skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung dengan
pendekatan kualitatif untuk memperkaya data. Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian survai yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Unit analisa
dalam penelitian ini adalah individu. Penelitian ini merupakan penelitian
eksplanatory yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi 2006).
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya
diduga. Populasi sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat Kampung
Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi. Unit analisisnya adalah
individu dikarenakan penelitian ini ingin melihat persepsi masing-masing individu
masyarakat yang dapat mewakili persepsi masyarakat Kampung Batusuhunan
secara keseluruhan. Jumlah penduduk di Kampung Batusuhunan berjumlah 107
jiwa, dengan jumlah pria sebanyak 54 jiwa, dan wanita sebanyak 53 jiwa.
Pemilihan responden dilakukan secara Stratified Random Sampling dan dibagi berdasarkan tingkatan usia dan jenis kelamin. Pembagian berdasarkan jenis
kelamin dan tingkatan usia disebabkan penelitian ini ingin melihat hubungan
antara jenis kelamin dan tingkatan usia terhadap persepsi masyarakat. Jumlah
responden yang dipilih sebanyak 30 orang dengan pembagian 15 orang wanita di
menengah dan tua. Pembagian usia ini dibagi menjadi tiga dengan mengambil
referensi menurut Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006). Pembagian jumlah responden dilakukan seimbang (15 pria dan 15 wanita) dikarenakan untuk
membandingkan persepsi responden, maka jumlah responden yang dibandingkan
sebaiknya sama rata. Pengambilan responden dilakukan dengan mengelompokkan
masyarakat Kampung Batusuhunan ke dalam tiga golongan usia, kemudian dari
tiga kelompok tersebut masing-masing diambil 5 orang pria dan 5 orang wanita.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan menggunakan
instrumen berupa kuesioner. Sebuah kuesioner berupa sekumpulan pertanyaan
yang diajukan pada responden dan informan untuk dijawab. Pertanyaan untuk
responden berupa pertanyaan tertutup yang sudah disertai jawaban pertanyaan dan
pertanyaan terbuka untuk menggali informasi data kualitatif. Selain itu juga
dilakukan wawancara dengan informan kunci. Informan kunci merupakan pihak
yang memberikan keterangan tentang diri sendiri, pihak lain dan lingkungannya.
Pemilihan informan dilakukan secara purposive, informan kunci yang dipilih adalah tokoh adat Kampung Batusuhunan.
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data hasil kuesioner dari responden diolah dengan menggunakan program
microsoft excel 2007. Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula analisis data kualitatif sebagai pendukung melalui wawancara dengan informan serta
pembicaraan dengan responden yang dilakukan melalui wawancara dengan
pertanyaan terbuka. Data ini digunakan untuk mempertajam hasil penelitian.
Data kualitatif akan diolah melalui tiga tahapan, antara lain reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2008) mendefinisikan
tahap-tahap analisis data sebagai berikut:
1. Reduksi data: merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dan mencari tema serta pola data yang diperoleh;
2. Penyajian data: menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
3. Penarikan kesimpulan yang menghasilkan temuan baru atas obyek penelitian.
Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner di lapangan yang
diperkuat dengan teknik wawancara langsung dengan responden. Pengolahan data
dilakukan dengan tabel frekuensi untuk menghitung persentase jawaban
responden yang dibuat dalam bentuk tabulasi silang untuk mengetahui hubungan
antara dua variabel yaitu untuk melihat adanya pengaruh karakteristik responden
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Surade
4.1.1 Kondisi Geografis, Topografi, dan Demografi Kelurahan Surade Secara Geografis Kelurahan Surade mempunyai luas 622,05 Ha, berada di
sebelah selatan wilayah Kabupaten Sukabumi yang secara umum terbagi dua
kategori lahan, yaitu sebelah utara dan selatan mayoritas didominasi oleh lahan
kering, perumahan dan perkotaan. Sebelah barat dan timur didominasi oleh lahan
basah pesawahan. Adapun batas-batas administrasi Kelurahan Surade adalah
sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Citanglar;
2. Sebelah timur berbatasan Desa Jagamukti;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buniwangi dan Desa Pasiripis; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadaleman.
Kelurahan Surade bertempat cukup jauh dari pusat Kabupaten Sukabumi.
Jarak tempuh perjalanan dari pusat Kabupaten adalah sepanjang 63 km.
Sedangkan jarak tempuh dari Kota Bogor adalah sepanjang 117,5 km dan jarak
tempuh dari Kota Bandung adalah sepanjang 217,5 km.
Kondisi Topografi Kelurahan Surade memiliki ketinggian 116 meter di
atas permukaan laut (dpl) dan secara umum wilayah Kelurahan Surade memiliki
ketinggian berkisar antara 15-300 meter dpl. Rata-rata suhu udara berkisar antara
150C-250C, dengan suhu rata-rata 260C. Bentuk permukaan tanah (morfologi) relatif datar di seluruh bagian kelurahan, baik di bagian utara, timur, selatan
maupun barat wilayah Kelurahan Surade.
Secara demografi, jumlah penduduk Kelurahan Surade cenderung tetap
dengan mutasi lahir, mati, pindah datang, dan pindah pergi. Jumlah penduduk
Kelurahan Surade berjumlah 9.238 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga
sebanyak 2.763 KK. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Surade sebagian
besar bekerja sebagai petani, buruh tani, sektor perdagangan dan jasa. Untuk lebih
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Kelurahan Surade menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012
Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa) Total Persentase (%)
Pria 4.630 50,1
Wanita 4.608 49,9
Total 9.238 100,0
Sumber : Profil Kelurahan, 2012
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1, jumlah penduduk Kelurahan
Surade terdiri dari 9.238 jiwa dengan jumlah pria (50,1 persen) lebih banyak dari
wanita (49,9 persen).
4.1.2 Kondisi Infrastruktur
Secara umum infrastruktur dasar di Kelurahan Surade cukup memadai.
Hal ini dibuktikan dengan tersedianya prasarana pendidikan seperti PAUD,
Taman Kanak-kanak, RA, Sekolah Dasar, Madrasah, SMK, Pondok Pesantren,
dan Perguruan Tinggi. Begitu juga dengan sarana kesehatan dan peribadatan yang
sudah tersedia dan tersebar di berbagai wilayah Kelurahan Surade. Prasarana
peribadatan yang terdapat di Kelurahan surade antara lain masjid dan mushola,
sedangkan prasarana kesehatan antara lain puskesmas, posyandu, klinik dokter,
dan poskesdes. Jumlah infrastruktur yang terdapat di Kelurahan Surade dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Infrastruktur Kelurahan Surade, Tahun 2012
Infrastruktur Kelurahan Surade
Kondisi Prasarana Jumlah (buah)
PAUD 8
Taman Kanak-kanak 2
RA 10
Sekolah Dasar Negeri 6
Madrasah 8
SMK Swasta 2
Pondok Pesantren 7
Perguruan Tinggi 2
Puskesmas 1
Posyandu 12
Klinik Dokter 4
Poskesdes 1
Masjid 28
Mushola 46
Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah infrastruktur
yang mendominasi di Kelurahan Surade adalah infrastruktur yang berhubungan
dengan agama Islam, seperti pondok pesantren, madrasah, masjid dan mushola
yang jumlahnya lebih besar dibandingkan sarana dan prasarana lainnya. Hal ini
semakin menandakan bahwa Kelurahan Surade merupakan wilayah yang
kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam.
4.1.3 Kondisi Penduduk
Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Surade apabila dilihat berdasarkan
aspek agama dikenal sebagai masyarakat Islami. Hal ini dikarenakan hampir
seratus persen penduduk Kelurahan Surade beragama Islam. Oleh karena itu, adanya konsep “Ekowisata Islami” di Curug Cigangsa menjadi suatu hal yang wajar mengingat hampir seluruh penduduk Kelurahan Surade memeluk agama
Islam. Jumlah penganut agama Islam di Kelurahan Surade berjumlah 9.233 orang
(99,9 persen), penganut agama Kristen 4 orang (0,04 persen), dan Katolik 1 orang
(0,01 persen).
Kelurahan Surade merupakan kelurahan yang cukup besar di Kabupaten
Sukabumi. Tingkat pendidikan penduduk juga tersebar mulai dari tingkat Sekolah
Dasar sampai Strata 3, dengan jumlah terbesar ialah penduduk yang menempuh
pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Rincian jumlah penduduk dengan
tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 2.
Sumber : Profil Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi 2012
Gambar 2. Persentase Penduduk Kelurahan Surade menurut Tingkat Pendidikan,
Tahun 2012
60.4 22.6
13.06 1.38
0.53 1.66 0.2 0.09
Tingkat Pendidikan Penduduk
Penduduk Kelurahan Surade memiliki mata pencaharian yang terbagi ke
dalam beberapa bidang profesi. Terdapat 1.099 orang (51,8 persen) yang bekerja
sebagai buruh tani, 508 orang (23,9 persen) sebagai petani dan sisanya (24,3
persen) tersebar sebagai buruh serabutan, PNS, dan peternak. Untuk rinciannya
dapat dilihat pada Gambar 3.
[image:31.595.111.516.194.427.2]Sumber : Profil Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi 2012
Gambar 3. Persentase Penduduk Kelurahan Surade menurut Mata Pencaharian,
Tahun 2012
Berdasarkan persentase pada Gambar 3 mata pencaharian penduduk
Kelurahan Surade mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan petani. Hal ini
mengingat kondisi alam yang sangat sesuai untuk pertanian, maka hampir
sebagian besar penduduk Kelurahan Surade berprofesi dalam bidang pertanian.
4.2 Gambaran Umum Kampung Batusuhunan
Batusuhunan merupakan nama salah satu kampung yang terdapat di
Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi. Nama Batusuhunan sudah ada sejak
jaman nenek moyang. Pemberian nama ini dikarenakan terdapat batu-batu yang
bersusun di tengah bendungan. Susunan batu ini berbentuk seperti rumah, oleh
karena itu para nenek moyang memberi nama Batusuhunan (batu yang bersusun)
untuk kampung ini. 0
10 20 30 40 50 60
Petani Buruh tani Buruh
serabutan
PNS Peternak
23.9
51.8
7.4
14.5
2.4
Mata Pencaharian Penduduk
Batusuhunan merupakan kawasan yang memiliki unsur Islam yang sangat
kuat. Masyarakat Kampung Batusuhunan yang 100 persen beragama Islam
mengatakan sering mendengar suara adzan dan suara orang sholat di dekat
bendungan. Hal ini dipercaya masyarakat sebagai pertanda bahwa di Kampung
Batusuhunan terdapat penunggu yang beragama Islam yang menjaga kampung
tersebut. Menurut informan kunci yang merupakan tokoh adat di Kampung
Batusuhunan, disana terdapat makam salah satu Wali Songo sehingga banyak
orang yang mengunjungi Kampung Batusuhunan untuk ziarah ke makam tersebut.
Berikut penuturan tokoh adat di Kampung Batusuhunan (HBY/70 tahun).
“… dari bendungan sering terdengar suara adzan dan suara orang yang sedang
sholat. Masyarakat setempat percaya bahwa Kampung Batusuhunan dilindungi oleh penunggu yang juga beragama Islam. Kami tidak keberatan dan tidak takut selama tidak ada yang diganggu. Di sini juga terdapat makam salah satu Wali Songo, oleh karena itu sejak dahulu memang sudah banyak orang yang datang ke Kampung Batusuhunan untuk berziarah …”
Kampung Batusuhunan terdapat di RW 08 Kelurahan Surade. Kampung ini
memiliki 107 jiwa penduduk yang terbagi ke dalam 33 KK dengan jumlah pria 54
jiwa (50,5 persen) dan wanita 53 jiwa (49,5 persen). Penduduk di Kampung
Batusuhunan 100 persen beragama Islam, oleh karena itu adanya konsep “Ekowisata Islami” sebagai konsep ekowisata di Curug Cigangsa sangat didukung oleh masyarakat Kampung Batusuhunan sebagai pengelola dan penanggung jawab
lokasi Curug Cigangsa tersebut. Konsep ini diharapkan dapat mencegah adanya
perubahan gaya hidup, kebudayaan dan orientasi masyarakat yang awalnya
berpedoman dengan ajaran Islam menjadi terpengaruh oleh beberapa budaya dari
luar yang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat Kampung Batusuhunan.
4.3 Gambaran Umum Curug Cigangsa
4.3.1 Sejarah Ekowisata Islami Curug Cigangsa
Curug Cigangsa merupakan salah satu kekayaan alam yang terdapat di
Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi. Curug Cigangsa terdiri dari dua tingkat dan diperkirakan terbentuk akibat gempa yang cukup kuat sehingga mengakibatkan longsor. Curug ini memiliki debit air yang
Curug Cigangsa memiliki dinding batu yang berwarna kehitaman sebagai
landasan air mengalir.
Pada awalnya Curug Cigangsa ini belum dijadikan lokasi ekowisata. Baru
pada tahun 2008 tercetus gagasan oleh pemerintah daerah untuk membuka
kawasan ini menjadi kawasan ekowisata. Hal ini tidak dapat langsung terlaksana
dikarenakan masyarakat setempat tidak setuju dengan dibukanya kawasan Curug
Cigangsa menjadi lokasi ekowisata. Masyarakat merasa apabila kawasan ini
dibuka menjadi kawasan ekowisata, maka akan banyak pengaruh dari luar yang
masuk ke lingkungan masyarakat setempat. Masyarakat juga tidak ingin apabila
kawasan Curug Cigangsa yang juga merupakan kawasan keramat menjadi rusak
akibat tingkah laku wisatawan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebiasaan
yang melekat pada diri masyarakat.
Pada tahun 2010, muncul kembali ide untuk membuka kawasan ini menjadi
kawasan ekowisata oleh PLP-BK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis
Komunitas). PLP-BK ialah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan
ditempatkan di enam kabupaten tiap provinsi. Tujuan utama pembentukan
PLP-BK ialah untuk menciptakan tatanan kehidupan dan hunian yang tertata secara
selaras, sehat, produktif, berjati diri, dan berkelanjutan. Fokus utama PLP-BK
adalah pada penguatan dan pengembangan sosial kapital melalui pengokohan
nilai-nilai universal dan kearifan lokal, penguatan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, serta membuka ruang kreativitas dan inovasi di
masyarakat untuk menciptakan sumberdaya pembangunan pemukiman. Ciri
utama PLP-BK ialah Community Based Management, yakni menangani persoalan pemukiman melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan hasil-hasil
pembangunan yang dipelihara dan dikelola oleh masyarakat setempat.
Tujuan dari PLP-BK membuka kawasan ini adalah untuk memajukan
masyarakat Kampung Batusuhunan. Setelah adanya pembicaraan yang cukup
memakan waktu lama, akhirnya masyarakat Kampung Batusuhunan setuju apabila
kawasan ini dibuka untuk umum dengan syarat jenis ekowisata yang ditawarkan adalah “Ekowisata Islami” sehingga segala tingkah laku wisatawan yang ada harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Masyarakat juga mengajukan syarat,
segala hal yang berhubungan dengan Curug Cigangsa harus dilakukan oleh
masyarakat Kampung Batusuhunan.
4.3.2 Ekowisata Islami Curug Cigangsa
Bentuk ekowisata yang ditawarkan di Curug Cigangsa merupakan bentuk
ekowisata yang sedikit lain dengan ekowisata kebanyakan. Konsep ekowisata yang ditawarkan ialah konsep “Ekowisata Islami”, sehingga segala peraturan yang terdapat di lokasi ekowisata telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam. Curug
Cigangsa sendiri memiliki pemandangan yang sangat indah dengan batu-batu
yang terbentuk alami.
Bantuan dana dari pemerintah pusat telah menjadikan jalan menuju lokasi
curug menjadi lebih mudah untuk dilewati. Jalanan yang curam kini sudah
dibangun menjadi anak-anak tangga sehingga para wisatawan tidak akan kesulitan
untuk menuju ke bawah curug. Di tengah perjalanan menuju curug juga telah
disediakan beberapa tempat untuk beristirahat, sehingga para wisatawan yang
merasa lelah dapat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.
Selain curug, di lokasi ini (bagian bawah curug) juga terdapat keunikan lain, yakni “Batu Masigit”. Batu Masigit merupakan batu-batu besar yang tersusun ke atas sehingga menyerupai masjid. Menurut kepercayaan masyarakat setempat,
Batu Masigit pada jaman dahulu digunakan oleh para Wali Songo sebagai tempat
untuk musyawarah. Hal ini yang menjadikan lokasi ini menjadi wilayah yang suci
sehingga apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kaidah-kaidah Islam
akan mendapatkan teguran dari penunggu curug (mitos). Nuansa Islami akan
terasa ketika kita memasuki jalan masuk Kampung Batusuhunan. Sebuah gapura yang bertuliskan “Kawasan Ekowisata Islami Curug Cigangsa” akan menyambut kita. Penduduk Kampung Batusuhunan ialah penganut agama Islam, oleh karena
itu hampir seluruh penduduk wanita memakai jilbab/penutup kepala yang
menambah kesan Islami di kampung tersebut.
Konsep “Ekowisata Islami Curug Cigangsa” bukanlah jenis ekowisata yang menawarkan perjalanan religius, akan tetapi jenis ekowisata yang segala peraturan
dalam pengembangan dan pelaksanaanya berpedoman pada kaidah-kaidah Islam.
di lokasi tersebut berbeda dengan lokasi ekowisata di kebanyakan tempat yang
saat ini semakin terpengaruh oleh konsep pariwisata. Walaupun belum
sepenuhnya mengikuti kaidah Islam, akan tetapi segala norma yang dibuat sudah
berpedoman pada kaidah-kaidah Islam.
4.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan menjadi Kawasan Ekowisata Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan yang baru, tentu saja
memerlukan suatu persiapan dan keterlibatan dari berbagai stakeholders. Curug Cigangsa yang pada awalnya merupakan kekayaan alam yang belum tersentuh
oleh tangan manusia dan hanya menjadi tempat wisata bagi masyarakat setempat
khususnya masyarakat Kampung Batusuhunan, kini mulai dibuka untuk
masyarakat luas dan dijadikan lokasi ekowisata.
Pengembangan Curug Cigangsa menjadi lokasi ekowisata pada awal
mulanya adalah suatu ide dari pemerintah yang dicetuskan melalui PLP-BK. Ide
ini pada awalnya tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat setempat. Setelah
perundingan selama beberapa tahun, akhirnya masyarakat Kampung Batusuhunan
setuju dengan syarat pengembangan ekowisata di Curug Cigangsa menggunakan nama “Ekowisata Islami” yang kesemua peraturannya berdasarkan pada kaidah Islam dan dalam pengembangan juga pengelolaannya harus melibatkan
masyarakat lokal.
Pada tahun 2010, setelah adanya persetujuan untuk membuka kawasan ini
menjadi kawasan ekowisata, pemerintah Kelurahan Surade mulai mengajukan
proposal dana kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan
pembangunan infrastruktur di kawasan Curug Cigangsa yang sebelumnya masih
sangat alami. Bantuan awal yang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui
PLP-BK ialah berjumlah sekitar 300 juta Rupiah. Bantuan dana ini digunakan
oleh masyarakat untuk membangun infrastruktur penunjang kawasan wisata.
Sampai saat ini, bantuan dana tersebut sudah dialokasikan untuk
membangun jalan setapak dan tangga-tangga kecil yang dapat memudahkan
wisatawan untuk mengunjungi Curug Cigangsa. Masyarakat juga membuat tiga
buah tempat bersantai dan istirahat di tiga titik kawasan Curug Cigangsa. Selain
akhir, beserta beberapa tong sampah yang disimpan di sekitar Curug Cigangsa.
Bantuan dana tersebut juga digunakan untuk membuat dua buah toilet umum dan
bangunan loket untuk pembelian tiket.
Sesuai dengan syarat yang diajukan oleh masyarakat, maka segala
kegiatan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh
masyarakat setempat. Kegiatan tersebut berupa pembangunan infrastruktur,
pembagian kerja dalam bidang ekowisata, penegakan peraturan dan hal-hal
lainnya. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan dan dukungan masyarakat
terhadap pengembangan kawasan ekowisata Curug Cigangsa. Meskipun pada
awalnya pengembangan kawasan ini menimbulkan beberapa perbedaan pendapat
antara pihak yang setuju dan tidak setuju, akan tetapi saat ini seluruh pihak yang
terlibat sama-sama mendukung pengembangan kawasan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”.
4.5 Karakteristik Responden
Karakteristik penduduk yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah
15 pria dan 15 wanita yang termasuk ke dalam salah satu dari tiga rentang usia
yang telah dibagi menurut Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006), yaitu
usia golongan muda: 18-30 tahun, usia golongan menengah : 31