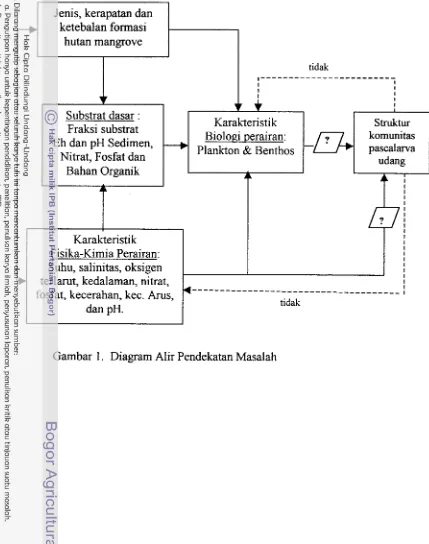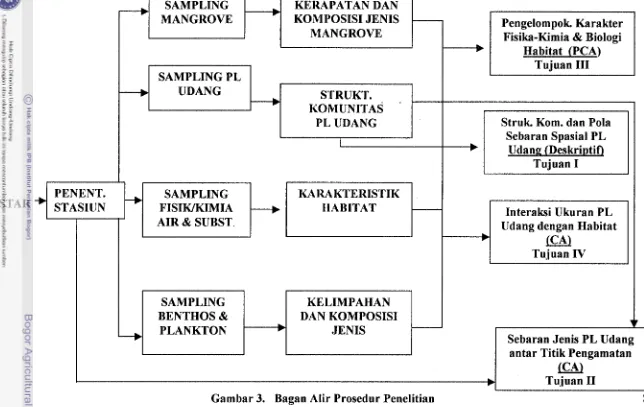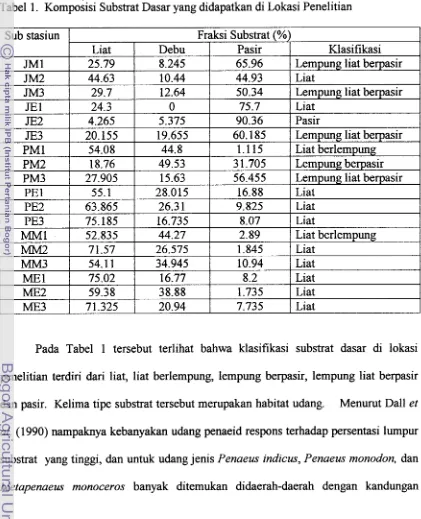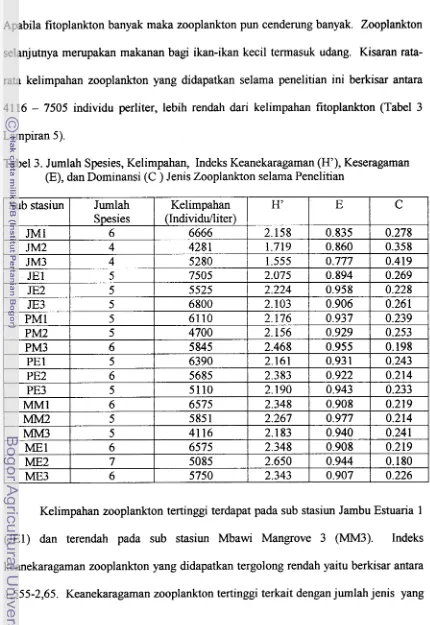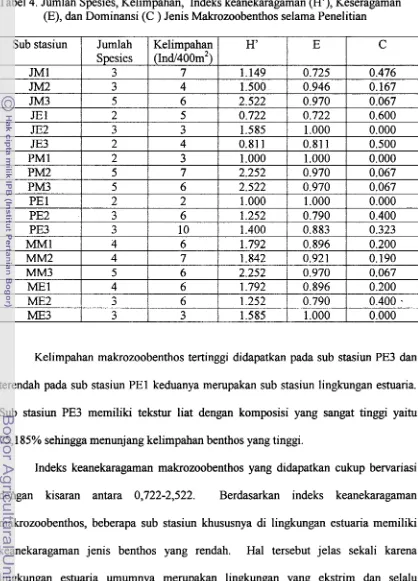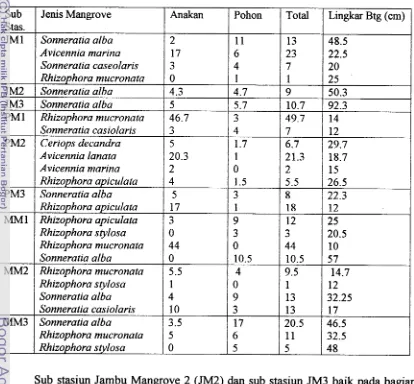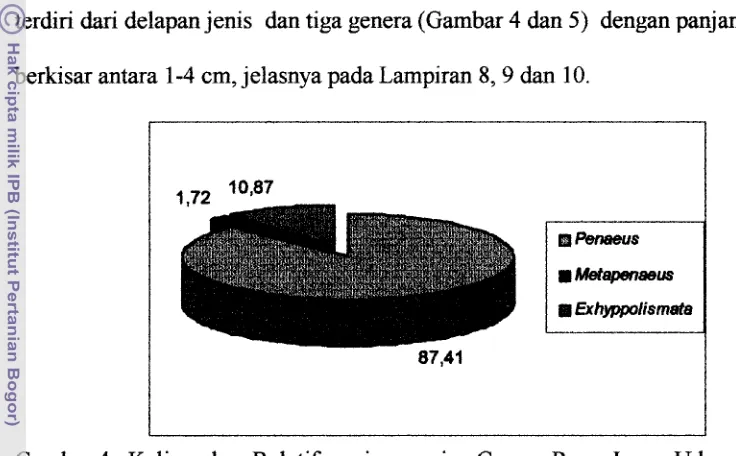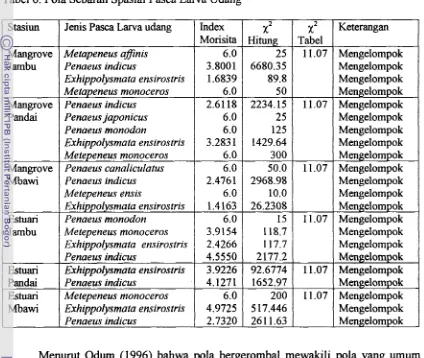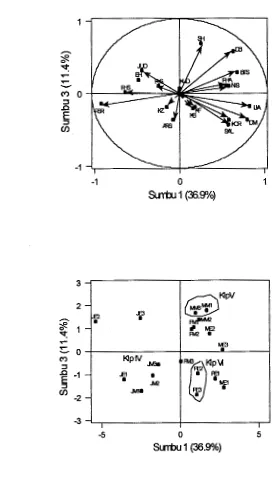STRUKTUR KOMUNITAS PASCA LARVA UDANG
HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK HABITAT
DAERAH ASUHAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DAN
ESTUARIA TELUK CEMPI
OLEH :
A R I F I N
wPROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
STRUKTUR KOMUNITAS PASCA LARVA UDANG
HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK HABITAT
DAERAH ASUHAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DAN
ESTUARIA TELUK CEMPI
A R I F I N
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Kelautan
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Tesis : Struktur Komunitas Pascalarva Udang Hubungannya dengsn Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi.
Nalna : Aria'in
Nomor Pokok : 9966.4
Program Studi : 1ln1 1 Iielautan
1. Komisi Peinbimbing
Dr.
1;
Dietriech G. ~ e n g . . KetuaMengetahui,
2. Ketua Program Stud< Ilmu Kelautan
/q$-j?l,
Dr.Ir.1-I.Ri a ffand' DEAAnggota
3. Direktur Program Pascasarjana
Dr. Ir. Mulia Purba, MS.:
SITRAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :
"Struktur Komunitas Pasca Larva Udang Hubungannya dengan Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi"
Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belwn pernah di publikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan tehh dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
PRAKATA
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan rahrnat dan nikmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tema yang &pilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2001 ini ialah pasca larva udang dan daerah asuhannya, dengan judul Struktur Komunitas Pasca larva Udang Hubungannya dengan Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi.
Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA dan Bapak Dr. Ir. H. Ridwan Affandi, DEA selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Penyandang Dana Beasiswa Pendidikan Pascasajana (BPPS) DIKTI, Bapak Bupati KDH TK. I1 Dompu yang telah memberikan bantuan dana penelitian, Ibu/Mertua, Istri dan anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga atas doa dan kasih sayangnya, adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas: Yunus, Dahlan, Nyta dan Hasni yang turut membantu dalam pengambilan data penelitian di lapangan dan
1
laboratorium.Akhirnya semoga karya ilmiah ini dapat memberikan informasi yang berarti di dalam pengelolaan sumberdaya udang di Teluk Cempi khususnya, dan dapat menarnbah khasanah informasi mengenai udang di Indonesia urnumnya.
Bogor, Pebruari 2002
ABSTRAK
ARIFIN. Struktur Komunitas Pasca Larva Udang Hubungannya dengan Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi. Dibimbing oleh DlETRlECH G. BENGEN dan RlDWAN AFFANDL.
Tingginya aktifitas pembangunan di wilayah pesisir berdampak terhadap rusaknya ekosistem pesisir yaitu ekosistem mangrove dan estuaria yang selanjutnya berdampak terhadap kehidupan organisme laut didalarnnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juli 2001 di daerah ekosistem mangrove dan estuaria Teluk Cempi Nusa Tenggara Barat.
Tujuan penelitian ini adalah
untuk
mendapatkan inforrnasi mengenai strukturkomunitas dan pola sebaran spasial pasca larva udang di daerah asuhan sekitar ekosistem mangrove dan estuaria Teluk Cempi, menentukan lokasi dan karakteristik habitat daerah asuhan tiap-tiap jenis pasca larva udang, menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang memberikan kelimpahan dan komposisi jenis pasca larva udang yang tinggi, dan menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang terkait dengan sebaran ukuran tiap jenis pasca larva udang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat delapan jenis pasca larva udang, indeks keanekaragamannya tergolong rendah, dan pola sebaran spasialnya adalah bergerombol secara tidak acak kecuali jenis A4. emxs pada stasiun Mbawi Mangrove
DAPTAR TABEL
Halam an
1. Komposisi Substrat Dasar yang didapatkan di lokasi penelitian . . . 47 2. Jumlah Spesies, Kelimpahan, Indeks Keanekaragaman (H7),
Keseragaman (E), dan Dominasi Fitoplankton . . . 49
3. Jumlah Spesies, Kelimpahan, Indeks Keanekaragarnan (H7),
Keseragaman (E), dan Dominasi Zooplankton .
.
. . ..
. . . 5 14. Jumlah Spesies, Kelimpahan, lndeks Keanekaragaman ( H ) , 53 Keseragaman (E), dan Dominasi Makrozoobenthos.. . .
.
.. . .
. . . .5. Komposisi Jenis, Kerapatan dan Lingliaran Batang Vegetasi
Mangrove . . . 5 5
6. Pola Sebaran Spasial Pasca Larva Udang . .
.
. . ..
. . . . 62DAFTAR GAMRAR
Halaman
...
Diagam Alir Pendekatan Masalah.. 7
...
Peta Lokasi Penelitian 25
...
Prosedur Penelitian dan Metode Analisis Data.. 35
Kelimpahan Relatif masing-masing Genera Pasca Larva Udang.. ... 5 8
Kelimpahan Relatif masing-inasins Jenis Pasca Larva Udang.. ... 50 Hasil Analisis Komponen Utama Parameter Perairan dan Substrat
A. Korelasi Variabel Fisika-Kimia dan Biologi perairan dan substrat pada Sumbu 1 dan 2
B. Sebaran Sub Stasiun pada Sunbu 1 dan 2 ... 7 1 Hasil Analisis Komponen Utama Parameter Perairan dan Substrat
A. Korelasi Variabel Fisika-Kimia dan Biologi perairan dan substrat pada Sumbu 1 dan 3
B. Sebaran Sub Stasiun pada sunlbu 1 dan 3 . . ... 72 Hasil Anal isis Faktorial Koresponden Sebaran Jen is Pasca Larva Udang antar sub stasiun (A) pada sumbu 1 dan 2; (B) pada sumbu 1 dan 3 ... 76
Nasil Analisis Fahqorial Koresponden Sebaran Ukuran Pasca Larva Udang dcngan Parameter Perairan (A) pada Sumbu 1 dan 2; (B) pada
...
Sunlbu 1 dan 3 79
Hasil Analisis Faktorial Koresponden Sebaran Ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Substrat (A) pada Surnbu 1 dan 2; (B) pada ...
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Alat clan Bahan yang digunakan Selama Penelitian . . .
.
..
. . . ... 90Parameter yang diukur, Unit Pengukuran dan Metode Pengukuran . . . 9 1
Kisaran dan Rataan Hasil Pengukuran Parameter Fisika-Kimia
Perairan
. . . .
. . .. .
..
. . ..
..
. . ..
..
. . . .92
Kisaran dan Rataan Hasil Pengukuran Parameter Fisika-Kimia
Substrat ... 93
Kelimpahan Plankton yang didapatkan selama Penelitian .
.
. . . 94Jenis-jenis Makrozoobenthos yang didapatkan selama Penelitian.. . . 97
Komposisi Jenis, Kerapatan dan Rata-rata Lingkaran Batang
Vegetasi Mangrove . . .
.
. . ..
. . . 99Kelimpahan Jenis Pasca Larva Udang pada setiap Sub Stasiun
Penelitian . . .
.
. . ..
. . ..
. . ..
. ..
. . . ..
. . .101
Jumlah Individu, Kelimpahan Relatif dan Panjang Karapaks Pasca
Larva Udang .
. .
. . .. . .
. . . 10 1Pasca Larva Udang yang Tertangkap selama Penelitian . . .
.
. . 102Matriks Korelasi Antar Parameter Air dan Substrat . . .
.
. . . . .. 104Akar Ciri dan Persentase Ragam pada Empat Sumbu Parameter 104 Perairan dan Substrat .. . .
.
. . .. .
. . . ...Korelasi antar Parameter Air dan Substrat pada Empat Sumbu .
. . .
..
105Kualitas Representasi (Kosinus Kuadrat) dari setiap Sub Stasiun
. . .
. . . .. 106Akar Ciri dan Persentase Ragam Sebaran Spasial Pasca Larva
Udang
. . .
. . ..
. . .. . .
. . . ..
. . ..
..
. . ..
. . 106 Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari (CA) SpasialPasca Larva Udang pada tiga Sumbu Faktorial .
.
. . .. .
. . . ... 107Akar Ciri dan Persentase Ragam pada Empat Sumbu Faktorial (CA)
ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Air .
.
. . ..
..
.. . .
..
. ..
. . . . 107Akar Ciri dan Persentase Ragam pada Empat Sulnbu Faktorial (CA)
1 8a. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif ( 2 ) dari CA Ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Perairan pada Tiga Sumbu
...
Faktorial 107
18b. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari CA Ukuran Pasca l a v a Udang dengan Parameter Substrat pada Tiga Sumbu
... Faktorial
107
... 19. Ciri-ciri Umuin Udang Fa~nili Penaeidae dan Hippolytidae 108
20. Galnbar Jenis-jenis Pasca Larva Udang yang didapatkan ... 1 1 1
2 1. Peta Sebaran Karakteristik Fisika-Kimia dan Biologi Perairan dan ... Substrat antar sub stasiun Penelitian, Hasil PCA
113
22. Peta Sebaran Jenis Pasca Larva Udang dan Jenis Mangrove menurut ...
18a. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari CA Ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Perairan pada Tiga Sumbu
... Faktorial.
107 18b. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari CA Ukuran
Pasca Larva Udang dengan Parameter Substrat pada Tiga Sumbu ... Faktorial
107 ... 19. Ciri-ciri Utnuin Udang Falnili Penaeidae dan Hippolytidae 108
20. Galnbar Jenis-jenis Pasca Larva Udang yang didapatkan ... 1 1 1
2 1. Peta Sebaran Karakteristik Fisika-Kimia dan Biologi Perairan dan Substrat antar sub stasiun Penelitian, Hasil PCA ...
113
22. Peta Sebaran Jenis Pasca Larva Udang dan Jenis Mangrove menurut ...
DAFTAR IS1
Halaman DAFTAR TABEL..
.
. . .. .
. . ..
. . .DAFTAR GAMBAR.. . . .
.
. . . DAFTAR LAMPIRAN.. . ..
. . ..
. . ..
. . ..
. . ..
. . .PENDAHULUAN . . .
Latar Belakang.. . .
Tujuan dan Kegunaan . . .
Hipotesis Penelitian.
. .
. .. .
. . .Identifikasi Masalah.. . .
.
. . ..
. . ..
. . .Pendekatan Pemecahan Masalah .
.
..
. . ..
. . ..
. . .. .
. . .TINJAUAN PUSTAKA.. . .
Taxonomi
.
.. .
. . . ..
. . ..
. . ..
. . ..
. . .Daur Hidup.. . .
Makanan . . .
.
. . ..
. . ..
. . . . . ..
. . ..
. . .. . .
. . . ..
. ..
Stock Rekruitment dan Habitat . . .Estuaria. . .
.
. . . .. .
. . .Eskosistem Mangrove .
.
. . . Potensi Hutan Mangrove.. . ..
. . .Peranan Hutan Mangrove . . . .. METODOLOGI PENELITIAN..
. . .
..
. . ..
. . ..
. . ..
. . . ..
. . . ..
.. . .
.. .
. . . ..
. .Waktu dan Tempat Penelitian.. . .
.
. . ..
Alat dan Bahan.. . . ... Prosedur Penelitian . . .
. . .
. . .Penentuan Stasiun ... . . Pengambilan Contoh Pasca Larva Udang..
. . .
.
. . .
.
. . .
. . .
. .
.. .
.
. .
Pengumpulan Data dan Prosedurnya.. . ..
. . .. .
. . ..
. . . Identifikasi Pasca Larva Udang dan Mangrove...
. . . ..
..
. . .. .
. . . Kerapatan Jenis Mangrove.. .. .
. . ..
. . ..
. . . ..
.. .
. . ..
. . . Pengarnbilan Contoh dan Identifikasiu Plankton . ..
. . ..
. . . .. Pengambilan Contoh dan Identifikasi Makrozzobenthos . . . Pengambilan Contoh Air dan Substrat . . . . ..
. . . .. Analisis Data.. . . .. . .Struktur Koinunitas Pasca Larva Udang . . .
Karakteristik Habitat . . .
Keterkaitan Pasca Larva Udang dengan Larakter Habitat . . .
HASIL DAN PEMBAHASAN.. . .
.
. . . Kondisi Fisika-Kimia Perairan dan Substrat . . .Suhu . . .
xi xii ...
X l l l
... Kecerahan ... Kekeruhan ... Kecepatan Arus ... Salinitas
Oksigen Terlarut ... ... Derajat Keasaman (pH) Air dan Substrat
Bahan Organik Total Air dan Substrat
...
Nitrat Air dan Substrat ...... Pospat Air dan Substrat
... Substrat Dasar
... Kondisi Biolog Perairan dan Substrat
... Fitoplankton ... Zooplankton ... Benthos
Vegetasi Mangrove ... ... Pasca Larva Udang
... Komposisi Jenis dan Kelimpahan
... Pola Distribusi Spasial
...
Struktur Komunitas Pasca Larva UdangKarakteristik Fisika-Kimia-Biologi Air dan Substrat Hubungannya dengan Kelimpahan clan Jumlah Jenis Pasca Larva
... Udang
Distribusi Spasial Jenis Pasca Larva Udang antar Sub
... Stasiun
Distribusi Ukuran Pasca Larva Udang Hubungannya dengan ... Parameter Air dan Sedimen
... KESIMPULAN DAN SARAN
... Kesimpulan
... Saran
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Ekosistem mangrove didefinisikan sebagai mintakat pasang surut dan mintakat
supra pasut dari pantai berlumpur, teluk, gobah dan estuaria yang didominasi oleh
fialopl~yta (tumbuhan yang hidup di air asin), yang terkait dengan anak sungai, rawa dan penggenangan, bersama dengan populasi tumbuhan dan hewan (Nybakken, 1992).
Secara ekologis ekosistem mangrove memiliki peranan yang sangat penting.
Zat hara yang diberikan oleh mangrove ke gobah-gobah sebagai detritus akan terbawa
oleh arus ke perairan pantai didekatnya dan menjadi sumber makanan jasad renik
yang merupakan mata rantai pertaina dalanl rantai makanan (Nybakken, 1997;
Bengen, 2000). Berbagai jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting dan moluska,
hidup di kawasan ini atau sangat bergantung pada keberadaan hutan mangrove dalam
melengkapi siklus hidupnya.
Khusus untuk udang cokiat Penaeus aztecus dan udang putih Yenaeus setflkrus, siklus hidupnya secara integral terkait dengan estuaria. Masa muda dari udang tersebut memanfaatkan habitat yang dangkal di estuaria, dan sebagian besar
produksi udang didukung oleh produktifitas dari daerah asuhan tersebut (Mine110 dan
Roger, 199 1). Dengan demikian, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kelimpahan
udang sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari perairan estuaria maupun hutan
mangrove, yang selanjutnya kelangsungan hidup larva maupun pasca larva udang
tersebut akan berpengaruh terhadap stok rekruitmen dan populasi udang dewasa
tersebut akan berpengaruh terhadap stok rekruitmen dan populasi udang dewasa
(Gulland dan Brian, 198 1).
Mengenai udang penaeid, meskipun taxonomi udang dewasa relatif telah
dikenal dengan baik dan kunci identifikasinya pun sudah tersedia, namun taxonomi
dari stadia awal tidak didokumentasikan. Kunci identifikasi pasca larva dan juvenil
yang tersedia masih terbatas pada jenis dan daerah geografis tertentu atau pemisahan
jenis dalam genera hanya pada level kelompok genera (Lavery dan Staples, 1990),
untuk itu perlu dimunculkan penelitian-penelitian yang terfokuskan pada larva
maupun pasca larva udang.
Tingginya pertambahan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di
wilayah pesisir bagi berbagai peruntukan, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem
pesisir khususnya hutan mangrove dan estuaria akan meningkat pula (Bengen, 2000).
Meningkatnya tekanan ini berdampak terhadap kerusakan ekosistem mangrove dan
estuaria yang selanjutnya juga berdampak terhadap kehidupan organisme di
dalamnya.
Teluk Cempi sebagai salah satu penghasil udang ekonomis penting di daerah
Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik lingkungan perairan yang spesifik karena
letaknya yang langsung berbatasan dengan Samudra India, dan wilayah pesisirnya
didukung oleh hutan mangrove yang cukup luas yaitu 749 Ha. (Anonimous, 1990).
Namun sayangnya, tingkat pengusahaan terhadap sumberdaya udang di wilayah Teluk
Cempi sudah berada pada taraf yang tinggi, estimasi produksi pada tahun 1989 sudah
Keadaan ini terjadi karena usaha penangkapan dilakukan tidak hanya terhadap udang
ukuran konsumsi melainkan juga terhadap induk udang yang siap memijah.
Usaha penangkapan terhadap induk udang sangat berpotensi untuk
mengancam populasi udang di Teluk Cempi, karena te rjadi pemutusan salah satu mata
rantai yang paling vital dalam siklus hidup udang. Keadaan tersebut akan inenjadi
lebih parah lagi apabila daerah asuhan udang di wilayah pesisir banyak mengalami
kerusakan akibat aktifitas pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan
fungsi ekologis ekosistem mangrove, seperti penebangan hutan mangrove untuk
pembuatan tambak, jalan raya maupun untuk areal pemukiman.
Perubahan habitat baik secara alami maupun oleh aktifitas manusia dapat
mempengaruhi populasi udang secara nyata. Oleh karena lokasinya di dekat daratan,
maka perannya sebagai daerah asuhan (nursery ground) lebih mudah mendapat
serangan manusia dari pada daerah pemijahan di lepas pantai. Lokasi dan
karakteristik daerah asuhan dari jenis udang yang berbeda memerlukan penggambaran
yang spesifik agar mereka bisa dilindungi (Iversen et ul., 1992).
Mengingat ha1 tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai
daerah asuhan udang di wilayah perairan ekosistem mangrove dan estuaria Teluk
Cempi terutama mengenai karakteristik biologi, fisika dan kimia yang mendukung
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
a. Mendapatkan inforrnasi mengenai struktur komunitas dan pola sebaran spasial
pasca larva udang di daerah asuhan sekitar ekosistem mangrove dan estuaria
Teluk Cempi.
b. Menentukan lokasi dan karakteristik habitat daerah asuhan tiap-tiap jenis
pasca larva udang.
c. Menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang memberikan
kelimpahan dan komposisi jenis pasca larva udang yang tinggi.
d. Menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang terkait dengan sebaran
ukuran tiap jenis pasca larva udang.
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar
pertimbangan dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk berbagai peruntukan agar
tidak merusak daerah asuhan yang memberikan kelimpahan dan komposisi jenis
pasca lava udang yang tingg. Apabila suatu saat di perairan Teluk Cempi perlu
dilakukan Restocking terhadap udang, maka informasi mengenai lokasi yang sesuai
untuk melakukan restocking telah diketahui melalui karakteristik habitat yang
memberikan kelimpahan dan komposisi jenis pasca larva udang yang tinggi.
Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memilih
karakteristik habitat untuk areal budidaya yang betul-betul sesuai dengan kehidupan
Hipotesis
Mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah :
a. Struktur komunitas pasca larva udang di Teluk Cempi sangat ditentukan oleh
karakteristik habitat daerah asuhan pada ekosistem mangrove dan estuaria.
b. Lokasi dan karakteristik habitat daerah asuhan pasca larva udang di Teluk
Cempi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem mangrove dan Estuaria.
c. Kelimpahan clan Komposisi jenis pasca larva udang yang tingg sangat
ditentukan oleh variasi karakteristik fisika, kimia, dan biologi habitat daerah
asuhan udang.
d. Sebaran ukuran tiap jenis pasca larva udang sangat ditentukan oleh
karakteristik fislka, hmia, dan biologi habitat daerah asuhan udang.
Identifikasi Masalah
Adapun pernasalahan dalam penelitian ini adalah :
Pengeksploitasian terhadap induk udang di perairan Teluk Cempi untuk
mensuplai kebutuhan induk di Hatchery akan berpengaruh terhadap stock pasca larva
udang, yang selanjutnya berpengaruh terhadap stock udang ukuran konsumsi dan
stock udang dewasa.
Sebagian dari awal daur hidup udang dihabiskan di daerah pantai dan estuaria
yang kaya akan bahan makanan yang diperlukan oleh organisme tersebut, sehingga
perubahan kondisi ekosistem tersebut akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
Perkembangan pembangunan di wilayah pesisir terutama pembukaan tambak,
pembangunan perumahan dan jalan raya, akan berpengaruh terhadap perubahan
kondisi habitat di daerah pantai terutama ekosistem hutan mangrove dan estuaria.
Perubahan kondisi habitat yang meliputi karakteristik fisika, kimia dan biologi
perairan sangat menentukan struktur komunitas organisme yang berasosiasi
dengannya.
Pendekatan Pemecahan Masalah
Banyak jenis hewan laut memanfaatkan ekosistem mangrove dan estuaria
sebagai habitat sementara untuk pemijahan, pembesaran atau untuk berlindung.
Beberapa jenis udang ekonomis penting sangat bergantung pada ekosistem
mangrove (Mcnae, 1974; Unar, 1972).
Perubahan kondisi habitat ekosistem mangrove yang meliputi komposisi jenis,
kerapatan dan ketebalan formasi ekosistem mangrove akan menentukan variasi
karakteristik fisika, kimia dan biolog perairan yang selanjutnya akan menentukan
struktur komunitas organisme yang berasosiasi dengannya.
Pengamatan perubahan kondisi habitat dapat dilakukan dengan mengukur
parameter fisika yang meliput kecerahan, kecepatan arus, fenomena pasang surut, dan
kedalaman perairan: parameter kimia (pospat, nitrat, dan pH): parameter biologi
(Plankton dan Bentos) dan parameter sedimen yang meliputi (pH, nitrat, pospat dan
Eh) di wilayah tersebut. Parameter fisika, kimia, dan biologi perairan
dan substrat selanjutnya dikaitkan dengan struktur komunitas pasca larva udang yang
Gambar 1. Diagram Alir Pendekatan Masalah Jenis, kerapatan dan
ketebalan formasi hutan mangrove
v
tidak
I - - -
I I I
I
I I I
I
Substrat dasar :
v
+
IFraksi substrat Karakteristik Struktur
Biologi perairan: komunitas
Eh dan pH SedimenY
plankton & ~~~~h~~
-
pascalarvaNitrat, Fosfat dan udang
Bahan Organik A
A
Karakteristik Fisika-Kimia Perairan: Suhu, salinitas, oksigen
A I
I I I I I I I I I I I I
1
terlarut, kedalaman, nitrat, I I [image:157.506.19.448.58.602.2]I
...
fosfat, kecerahan, kec. Arus,tidak
TINJAUAN PUSTAKA
Taxonomi Udang
FA0 mendaftar sekitar 343 jenis udang yang secara aktual ataupun potensial
merupakan jenis ekonomis penting (Holthuis, 1980). Dari jurnlah tersebut, 1 10 jenis
adalah anggota dari famili Penaeidae dan sekitar 80% merupakan hasil tangkapan
udang dunia (Dore dan Frimodt, 1987).
Menurut Fast dan James (1992) udang Penaeid merupakan anggota dari Pilum
yang terbesar dari kerajaan hewan yaitu Artlzropoda yang dicirikan oleh pertautan
anggota gerak (appendages) dan rangka luar (kutikula) yang mengalami moulting
atau ganti kulit secara periodik. Sub pilum yang besar yang hidup di air adalah
Crustacea yang memiliki 42.000 jenis dan terdiri dari 10 klas. Selanjutnya Lovett
(1 98 1) mengemukakan taxonomi udang sebagai berikut :
Pilum : Arthropods
Sub Pilum : Mandibulata
Klas : Crustacea
Sub klas : Malacostraca Super ordo : Eucarida
Or do : Decapoda
Sub ordo : Natantia
Famili : Penaeidae
Sergestid
Dore dan Frimodt (1987) menjelaskan ada 17 famili udang yang memiliki nilai
ekonomis yang berarti, namun jenis udang yang memiliki nilai ekonomis paling
penting hanya dimiliki oleh empat famili yaitu : Penaeidae, Pandalidae, Crangonidae
dan Palaemonidae. Selanjutnya dari empat famili tersebut yang paling nyata adalah
udang penaeid dan tiga famili lainnya adalah udang Caridean.
Udang dari famili Penaeidae, Sergestidae dan Luciferidae yang terdapat di
Asia Tenggara (yang tertangkap di perairan sekitar Malaysia dan Singapura) menurut
Lovett (1981) adalah meliputi : Famili : Penaeidae
Genus : Heteropenueus (1 jenis)
Solenoceru (6 jenis)
Aristacomorplta ( 1 jenis)
Penaeus (1 1 jenis)
Sicyonia (3 jenis)
Metapenaeopsis (1 0 jenis)
Parapenaeus (5 jenis)
Penaeopsis (1 jenis)
Metapenaeus (14 jenis)
Atypopenaeus (1 jenis)
Parapenaeopsis (1 1 jenis)
Farnili : Sergestidae Genus : Acetes (4 jenis) Famili : Luciferida
Genus : Lucifer (I jenis)
Menurut King (1 995) dua infra-ordo Caridea dan Penaeidea, subordo Natantia
dan ordo Decapoda memiliki jumlah jenis yang banyak dieksploitasi dan biasanya
disebut shrimp (udang berukuran kecil) dan prawn (udang berukuran besar).
Selanjutnya udang Caridea berbeda dengan udang Penaeid karena memiliki Pleuron
(yang menutup cangkang) dari segrnen abdomen kedua, dan pasangan kaki jalan
ketiga tidak memiliki capit. Tidak seperti udang penaeid, udang Caridea membawa
telur yang terbuahi diluar tubuhnya dibawah abdomen yang seringkali lebih kecil dari
telur udang penaeid.
Daur Hidup Udang
Daur hidup udang di alam terdiri dari dua fase, yaitu fase di tengah laut (laut
dalam) yang meliputi fase peneluran, dan fase perairan muara atau pantai (Toro dan
Sugiarto, 1979). Lebih lanjut dijelaskan bahwa daur hidup udang di laut dimulai pada
waktu udang dewasa memijah dan bertelur di laut. Telur yang kemudian dibuahi akan
menetas menjadi larva udang stadia nauplius, kemudian berturut-turut menjadi zoea,
mysis, dan pascalarvu yang selanjutnya bermigrasi ke daerah asuhan di wilayah
pesisir dan tumbuh di perairan tersebut hingga menjadi juvenil dan bergerak kembali
Menurut Silas (1978) pasca larva udang ditandai dengan bentuk tubuh yang
sudah menyerupai udang dewasa. Pada stadia ini udang melakukan migrasi ke arah
muara atau perairan pantai di mana salinitas relatif lebih rendah. Stadia pasca larva
dapat mencapai daerah asuhan dan tumbuh menjadi juvenil, kemudian tumbuh dewasa
dan kembali ke laut untuk melakukan pemijahan. Pasca larva akan mengalami
pergantian kulit berkali-kali tergantung jenisnya. Sebagai contoh, Penaeus
merguierzsis mengalami pergantian kulit sebanyak 14 kali, sedangkan Penaeus
monodon dan Metapenaeus monocerus mengalami 12 kali pergantian kulit. Selama
4-5 hari pertama, pasca larva cenderung lnasih bersifat planktonik, selanjutnya kadang
berenang atau berdiam di dasar perairan.
Pada stadia pascalarva, udang akan berrnigrasi memasuki daerah estuaria
dimana salinitas lebih rendah dan juga merupakan area yang baik untuk daerah
asuhan. Mekanisme perpindahan pascalarva memasuki daerah asuhan seperti yang
diteliti oleh Hughes (1968) adalah berhubungan dengan salinitas. Pada penurunan
salinitas 2-3 '1, pascalarva udang akan turun dari kolom air dan membatasi
aktifitasnya di sekitar dasar perairan sebagai proses aklimatisasi terhadap salinitas
permukaan yang lebih rendah. Pada saat pasang naik, pasca larva akan naik ke
permukaan air dan terbawa a m pasang memasuki estuaria atau daerah pesisir.
Khusus untuk udang coklat Penaeus uztecus dan udang putih Penaeus
setgerus menurut Minello dan Roger (1991) siklus hidupnya secara integral terkait
dengan estuaria. Masa muda dari udang tersebut memanfaatkan habitat yang dangkal
daerah asuhan tersebut. Dengan demikian, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
kelimpahan udang sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari perairan estuaria maupun
hutan mangrove, yang selanjutnya kelangsungan hidup larva maupun pasca larva
udang tersebut akan berpengaruh terhadap stok rekruitmen dan populasi udang
dewasa (Gulland dan Brian, 1 98 1 ).
Pada awal stadia nauplius dan mysis, udang terdapat sebagai plankton di
daerah neritik, tetapi pada akhirnya larva terkonsentrasi disekitar mulut estuaria dan
lagun (Longhurst dan Daniel, 1987), mereka masuk ke wilayah tersebut pada saat
pasang tinggi. Pada beberapa kasus, mereka menggunakan migrasi vertikal antara
permukaan dan dasar, bergerak ke atas menuju estuaria (Rothlisberg, 1982;
Orsi,1986). Selanjutnya menurut Longhurst dan Daniel (1987) larva sangat cepat
menempel di antara vegetasi di air dangkal dan bergerak secara progresif ke perairan
lagun yang dalam, dirnana mereka berkembang, dan mereka kembali ke laut terjadi
pada saat aliran air tawar yang masuk banyak, dan biasanya setelah 3-6 bulan mereka
berada di tempat tersebut.
Beberapa jenis udang memiliki daur hidup yang bervariasi; beberapa
diantaranya senang menempati air dalam dekat pinggir cekungan (shelf), ada juga
jenis yang hldup di pantai tetapi tidak memasuki estuaria sebagai juvenil, dan
beberapa udang dewasa maupun juvenil lainnya terdapat secara khusus di perairan
estuaria. Jenis pantai yang larvanya tidak memasuki estuaria menurut para ahli
merupakan jenis yang khusus dan ha1 itu terjadi biasanya apabila habitat estuaria tidak
Makanan Udang
Udang Penaeid diketahui memakan beragam makanan dan digambarkan
sebagai Omnivorous scavengers (Dall, 1968). Opportunistic omnivorous (Ruello,
1973; Cockcroft dan McLachan, 1986; dan King, 1995), pemakan detritus (Dall,
1968), Karnivora (Hunter dan Feller, 1987), dan merupakan predator (Marte, 1980;
Leber, 1985; Wessenberg dan Hill, 1987). Sedangkan pasca larva dan juvenil yang
epibentik keduanya memakan material hewan dan tumbuhan terrnasuk mikroalga,
gumpalan detritus, makrofita, foraminifera, nematoda, kopepoda, tanaid, larva
molluska dan larva brachyura (Chong dan Sasekumar, 1981; Gleason dan Wellington,
1988).
Udang penaeid yang menghuni mangrove dan rawa garam, tampaknya
menggunakan sumber karbon dari makrofita atau detritus yang berasal dari makrofita
dan mikroba heterotropik yang berasosiasi dengannya. Juga, bagian yang penting dari
karbon dalam biomassa udang berasal dari mikroalga planktonik (Gleason dan
Wellington, 1988), alga epipit (Fry, 1984), atau alga benthik (Stoner dan Zimmerman, 1988) studi tersebut merupakan bukti bahwa mikroalga maupun organisme makanan
pada mikroalga dapat menjadi sumber utama nutrisi udang penaeid yang hidup di
habitat pantai.
Dall(1968) dalam Dall et al. (1990) tidak menemukan perbedaan yang berarti dalam pemilihan makanan diantara E. esculentus, P. merguiensis, P. plebejus, M
jaringan hewan hanya sekitar 22 % frekwensi kejadiannya (kurang memakan hewan) dan lebih banyak material tumbuhan (21%) daripada yang dimakan oleh P. monodon
yaitu masing-masing 4 1 % jaringan hewan dan 1 1 % material turnbuhan.
Liao (1969) dalam Dall et al. (19990) mendapatkan bahwa P. Japonicus
sangat jelas memilih kerang yang dipotong pendek dan cacing polychaeta dari pada
daging ikan. Selanjutnya Balsubramanian et al. (1979) dalam Dall et at. (1990) menyatakan bahwa meskipun udang telah diakui sebagai hewan scavenger, mereka
nampaknya tidak menyukai makanan mati. Metapeneus dubsoni lebih menyukai organisme yang terbunuh masih segar dan hidup dari pada material hewan yang
hancur dan sudah mati.
Dall et a/. (1990) menetapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan udang Penaeid merubah kebiasaan makanannya, yaitu faktor-faktor fisiologs seperti urnur,
jenis kelamin dan stadia moulting; faktor-faktor spasial seperti habitat dan
ketersediaan makanan; dan faktor-faktor dengan suatu komponen temporal termasuk
waktu siang atau malam, musim dan pasang surut. beberapa dari faktor-faktor
tersebut saling terkait, sebagai contoh sebagaiman udang tumbuh mereka umumnya
merubah habitat. Sebagai akibatnya surnber utama dari variasi adalah sering tidak
mudah diidentifikasi.
Stock Rekruitmen dan habitat Udang
Rekruitmen stok menunjukan variasi yang sangat besar dari tahun ke tahun
Rekruitmen yang aktual pada suatu tahun tertentu ditentukan oleh kondisi lingkungan
dalam tahun tersebut. Oleh karena itu hubungan stok rekruitmen dengan kondisi
lingkungan (cuaca, suplai bahan makanan, pembangunan kawasan pantai dan
sebagainya) adalah jauh lebih baik untuk dipelajari (Gulland dan Brian, 1981).
Keberadaan dari lingkungan dapat menyebabkan bias pendugaan hubungan
stok dan rekruitrnen. Ukuran stok udang dewasa sangat ditentukan oleh kesuksesan
musim pemijahan sebelumnya yang dibatasi oleh intensitas penangkapan antara
rekruitrnen dan musim pemijahan. Stok pemijahan yang banyak akan te rjadi selama
periode dimana kondisi-kondisi lingkungan umurnnya bagus yang akan meningkatkan
stok rekruitmen. Sebaliknya kondisi lingkungan yang buruk akan memberikan jumlah
pemijahan yang kecil yang juga mempengaruhi rendahnya rekruitmen. Suatu
penelitian yang dilakukan di Teluk Karpentaria dan dimana saja, rekruitmen adalah
sangat kuat dipengaruhi oleh curah hujan. Selanjutnya hubungan antara stok dan
rekruitmen sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan pantai (seperti
pembangunan perurnahan, jalan raya, penebangan hutan mangrove, dan sebagainya)
yang memberikan dampak yang nyata dan tidak dapat berbalik terhadap rekruitrnen
(Gulland dan Brian, 198 1 ).
Udang genus Penaeus, terdapat di daerah tropis dan subtropis dari lintang
40% hingga 40"s. Daerah penyebaran dan habitat dari delapan jenis yang terseleksi,
baik juvenil maupun udang dewasa telah diketahui dengan baik. Udang dewasa
lepas pantai, sementara udang muda umumnya terdapat di habitat pantai yang
terlindung (Fast dan James, 1992).
Perubahan habitat baik secara alarni maupun oleh aktifitas manusia dapat
mempengaruhi populasi udang secara nyata (Gulland dan Brian, 198 1 ). Karena lokasinya di estuaria, daerah asuhan (nursery ground) umumnya lebih mudah
mendapat serangan dari manusia dari pada daerah pemijahan di lepas pantai.
Pola kepadatan juvenil udang di estuaria tampaknya menjadi penting sebagai
indikator nilai habitat. Di Teluk Mobile, Losch (1965) melaporkan bahwa udang
coklat kecil berasosiasi dengan vegetasi dibawah permukaan air (Ruppia dan
Vallisneria) dan habitat udang putih didapatkan pada dasar yang tidak bervegetasi
dengan banyak jumlah detritus organik. Selanjutnya Stokes (1974) melaporkan
bahwa udang putih lebih sering ditemukan pada dasar yang tidak bervegetasi di dekat
Laguna Medre, Texas dan udang coklat ditemukan di dasar yang tidak bervegetasi
dan di padang lamun.
Menurut Minello dan Roger (1991) bahwa pola kepadatan, tidak selalu
menggambarkan nilai dari habitat estuaria. Hewan dapat melakukan pengelompokan
dalam habitat yang seQkit makanan atau nilai sederhana yang terlindung karena pola
arus atau karena kekuatan selektif secara evolusioner yang sinkroni atau kesamaannya
tidak terlalu lama. Sebaliknya, habitat yang relatif tidak tercemar dapat secara
langsung menyediakan makanan bagi organisme iitau berperan sebagai jalur migrasi.
informasi yaitu bagaimana fungsi habitat mengatur pertumbuhan dan kelangsungan
hidup udang.
Kebanyakan daerah asuhan telah dikenali dengan baik. Meskipun banyak
yang telah dipelajari mengenai habitat udang muda, lingkungan spesifik yang
diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan setiap kelompok umur adalah
perlu untuk diidentifikasi melalui analisis dan interpretasi data biologs dan
hidrografis yang terkait (Iversen et al., 1993). Inforrnasi ini akan diperlukan untuk
evaluasi pengaruh gangguan alami dan aktifitas manusia terhadap kuantitas dan
kualitas habitat udang di estuaria dan terhadap produksi udang selanjutnya.
Menurut Iversen et a/. (1993) meskipun kerusakan habitat asuhan dapat
diperbaiki dan ditingkatkan melalui teknik-teknik manajemen air dan penanaman
kembali turnbuhan rawa, mangrove dan padang lamun, namun studi perlu dilakukan
untuk menentukan apakah perbaikan habitat mendukung produksi udang seperti
halnya habitat alami yang tidak rusak, dan membentuk suatu habitat yang betul-betul
berfungsi.
Banyak studi yang dilakukan terhadap stok udang menunjukan hubungan yang
jelas antara jumlah udang yang memijah dan kelimpahan rekruitmen selanjutnya
terhadap perikanan (Iversen et al., 1993). Kelimpahan rekruitrnen tidak seluruhnya
bergantung pada kondisi lingkungan sperti yang sebelumnya drpikirkan. Suatu stok
udang dapat over penangkapan apabila terjadi penangkapan lebih terhadap jumlah
induk yang memijah. Studi kuantitaif perlu dilakukan untuk menegakan relatif
rekruitmen berikutnya. Pemahaman dan penggunaan hubungan tersebut dapat
mengarah ke prediksi yang lebih baik dari hasil tangkapan tahunan dan menyediakan
manajemen yang efektif dan lebih praktis.
Untuk mendapatkan suatu ukuran kesuksesan pemijahan yang berkaitan
dengan indeks kelimpahan stok, indeks kelimpahan juvenil awal udang harus
diperoleh melalui sampling pada daerah asuhan (Iversen et al., 1993). Studi juga
diperlukan untuk mengevaluasi pengaruh stok udang dewasa yang potensial untuk memijah dan menghasilkan udang muda. Pada daerah geografis tertentu dimana stok
induk yang memijah telah berkurang dengan sangat serius karena overfishing dan atau
karena kondisi lingkungan secara temporal, udang dewasa dapat dilepaskan ke
estuaria dan perairan pantai untuk memperbanyak jurnlah kejadian udang yang akan
memijah secara alami atau melakukan restocking pasca larva atau udang muda .
Hal tersebut merupakan suatu ha1 yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan
rekruitmen atau untuk memperbaiki kembali populasi udang.
Estuaria
Kata estuaria berasal dari bahasa Latin yaitu aestus, yang berarti pasang (naik
turun) dan kata sifat aestuarium yang berarti yang disebabkan oleh pasang naik dan
pasang surut. Kebanyakan orang mengetahui estuaria sebagai suatu wilayah dimana
sungai bertemu dengan teluk kecil (inlet) laut. Selanjutnya Fairbridge (1980)
mendefenisikan estuaria sebagai suatu jalur masuk air laut kedalam sungai sejauh
batas atas pasang naik, biasanya dapat dibagi kedalam tiga wilayah yaitu (a) estuaria
terbuka; (b) estuaria bagan tengah, daerah percarnpuran yang kuat air tawar dengan
air asin; (c) estuaria sebelah atas atau estuaria fluvial, dicirikan oleh air tawar tetapi
merupakan subjek dari aksi pasang surut harian.
Menurut Sumich (1992) estuaria pada daerah pantai dimana saja di dunia
adalah suatu daerah dimana secara ekologis sangat kritis yang inendukung beragam
komunitas biologis dan berperan sebagai daerah istirahat, daerah mencari makan dan
daerah asuhan berbagai jenis biota laut. Kebanyakan estuaria telah mengalami
pembahan akibat aktifitas manusia. Pembahan tersebut telah mempengaruhi
produktifitas, keragaman spesies, dan kualitas air.
Estuaria di daerah tropis Australia menurut Blaber et al. (1989) dalam Sheaves (1992) merupakan habitat yang beragam, meliputi hutan mangrove, padang lamun,
dataran lurnpur dan saluran-saluran air terbuka, yang kesemuanya mungkin berbeda
dalam ha1 kedalaman, heterogenitas struktur, tipe substrat clan terpapar oleh pasang
SUN^.
Ekosistem Mangrove
Asal kata "mangrove" tidak diketahui dengan jelas dan terdapat banyak
pendapat mengenai asal usul katanya. Macnae (1968) menyebutkan kata mangrove
sebagai perpaduan antara bahasa Portugs yaitu Mangue dan bahasa Inggns yaitu
grove. Sementara Mastaller (1997) menyatakan bahwa kata mangrove berasal dari
bahasa Melayu kuno yaitu mangi-mangi yang digunakan untuk menerangkan marga
Tomlinson (1986) dan Wightman (1989) mendefenisikan mangrove baik
sebagai tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas.
Mangrove juga didefenisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di
pantai daerah tropis dan sub tropis yang terlindung (Saenger et a / . , 1983).
Adanya persitiwa pasang surut yang berpengaruh langsung pada komunitas
mangrove menyebabkan komunitas ini umumnya didominasi oleh jenis-jenis pohon
yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh pada
perairan payau. Frekwensi serta volume air tawar dan air laut yang bercampur sangat
berpengaruh terhadap kondisi kimia-fisika perairan hutan mangrove. Faktor
lingkungan yang sangat mempengaruhi komunitas mangrove menurut Nybakken
(1992) yaitu: salinitas, suhu, pH, oksigen terlarut, arus, kekeruhan dan substrat dasar.
Menurut Darsidi (1986), ciri-ciri hutan mangrove adalah ; (1) Tidak
terpengaruh iklim; (2) Terpengaruh pasang surut; (3) Tanah tergenang ait laut, tanah
lumpur atau pasir, terutama tanah liat; (4) Hutan tidak mempunyai struktur tajuk; (5)
Pohon dapat mempunyai tinggi 30 meter; (6) Jenis-jenis pohon mulai dari laut ke
darat adalah Rhizoplzora, Avicennia, Sonneratia, Xylocarpus, Lunznitzera, Bruguiera
dan Nypa fruticans; (7). Tumbuhan bawah yaitu : Acrostrchu~n aureurn, Acanthus il~clfolius, A. ebracteatus. Hutan mangrove sering disebut juga sebagai hutan payau
karena turnbuh di dasar payau, sedangkan hutan mangrove yang didominasi oleh jenis
Ekosistem mangrove merupakan subjek dari berbagai aktivitas pembangunan
seperti akuakultur, pertanian, kehutanan dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Lebih dari 50% hutan mangrove dunia telah berubah (World Resources Institute, 1996
dalam Ronnback et al., 1999), dan untuk wilayah Asia-Pasifik laju kerusakan hutan mangrove adalah 1% per tahun (Ong, 1995 dalam Ronnback et al., 1999). Hutan mangrove awalnya menempati sekitar 75% teluk-teluk kecil dan pantai tropis
(Farnsworth dan Ellison, 1997 dalam Ronnback et al., 1999), tetapi sekarang ini mereka tinggal sekitar 25% dari garis pantai tropis di dunia (World Resources
Institute, 1996 dalam Ronnback et al., 1999). Alasan utama dibelakang kerusakan hutan mangrove adalah ketidakrnampuan untuk menilai sumberdaya alam dan peran
ekologis yang dibangkitkan oleh sistem tersebut (Saenger et al., 1983; Hamilton dan Snedaker, 1984; Hamilton et al., 1989).
Potensi Hutan Mangrove.
Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang
(81.000 Krn) dan sebagian besar ditumbuhi oleh hutan mangrove (Satari
dkk,
1986dalam Darsidi, 1986). Selanjutnya menurut Darsidi (1986), potensi hutan mangrove
dapat ditinjau dari dua aspek yaitu potensi ekologis dan potensi ekonomi.
Potensi ekologis lebih ditekankan pada kemampuan hutan mangrove dalam
mendukung eksistensi lingkungan (sebagai hutan air asin, penahan angin, penahan
gempuran ombak, pengendali banjir dan tempat persembunyian, mencari makan
Sedangkan potensi ekonomi ditunjukan dengan kemampuan hutan mangrove
dalam menyediakan produk yang dapat diukur dengan uang. Salah satu produk dari
hutan mangrove yang secara ekonomi potensial dan dapat langsung dimanfaatkan
yaitu kayu.
Kesesuaian perairan Teluk Cempi bagi kehidupan udang didukung oleh
keberadaan hutan mangrove di kecamatan Dompu dan Hu'u dengan luas masing-
masing sekitar 682 Ha dan 67 Ha (Anonimous, 1990).
Peranan Hutan Mangrove
Menurut Tomascik et al. (1997) bahwa diseluruh kepulauan Indonesia, hutan mangrove memainkan peran vital dalam pembangunan sosial ekonomi komunitas
pantai. Ekosistem mangrove memiliki sejumlah fungsi penting, seperti sebagai
penahan fisik dari serangan badai gelombang, merupakan ekosistem produktif yang
mengirim energi dan bahan organik ke sistem yang berdekatan yang selanjutnya
dapat mendukung perikanan udang dan ikan ekonomis penting di pantai.
Lebih lanjut dinyatakan oleh Tomascik et al. (1997) bahwa peran h t i s dari
ekosistem mangrove berkaitan dengan tingginya laju produktifitas primer mereka.
Biomassa bahan organik yang berasal dari akar, dan daun membentuk jaring-jaring
makanan yang kompleks yang meliputi berbagai jenis hewan yang tidak bertulang
belakang seperti krustasea dan moluska, juga ikan, mamalia, reptil dan burung.
Sejumlah jenis udang ekonomis penting seperti Penaeus monodon dan P. indicus
Menurut Ronnback (1999) mangrove menyediakan kisaran pelayanan
ekologis yang luas seperti perlindungan dari badai dan banjir pasang, mencegah erosi
garis pantai dan mempertahankan keanekaragaman biologs (biodiversity).
Siklus hidup dari udang (Penaeus merguiensis) erat sekali berasosiasi dengan
mangrove (Tomascik et al., 1997). Di Indonesia menurut Martosubroto dan Naamin
(1977) didapatkan korelasi yang erat (r = 0,89) antara total area hutan mangrove dan
hasil tangkapan udang ekonomis di lepas pantai. Hubungan yang positif tersebut
kemungkinan disebabkan karena : (1) mangrove rnerupakan sumber penting dari
detritus dan nutrien yang merupakan sumber bahan bakar dalam rantai makanan di
dekat pantai; dan (2) mangrove berperan sebagai daerah asuhan dan daerah mencari
makanan b a g beberapa jenis biota laut.
Mangrove merupakan daerah asuhan penting bagi banyak jenis udang clan
kepiting ekonomis penting di seluruh daerah tropis (Macnae, 1974; Dall et a/., 1990).
Dalam pengertian nilai per unit hasil tangkapan dan total nilai dari hasil tangkapan,
udang penaeid merupakan surnberdaya yang paling penting di antara perikanan pantai
di seluruh dunia (Dall et al., 1990). Banyak jenis udang palaemonid juga berasosiasi
dengan mangrove termasuk udang raksasa air tawar ekonomis penting
Macrobrachium rosenbergii (Macnae, 1974; Matthes dan Kapetsky, 1988; Singh et
METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Tempat
Penelitian ini telah dilakukan selama lima bulan mulai bulan Maret hingga Juli
2001, di sekitar perairan hutan mangrove dan estuaria Teluk Cempi Dompu, Nusa
Tenggara Barat. Peta Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.
Alat dan Bahan
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : botol sampel,
kantong plastik, meteran plastik, sieve net, oven, kompas, secop, jaring sodo (sero
ukuran mata jaring 0,3 mm), thermometer, salinometer, kertas pH, layang-layang arus,
stop wach, seichi disk, DO meter, pisaulgunting, es box, mikroskop/makroskop, buku
identifikasi udang, plankton, makrozoobenthos dan mangrove, serta alat tulis menulis.
Sedangkan bahan-bahan yang digunakan terdiri dari : Formalin 40%, contoh
dahan, daun dan ranting mangrove; contoh pasca larva udang, plankton dan benthos;
dan contoh air serta substrat (lengkapnya pada Lampiran 1).
Prosedur Penelitian
Penentuan Stasiun Penelitian
Stasiun penelitian dipusatkan di sekitar ekosistem mangrove dan estuaria
Mbawi, Pandai dan Jambu yang ditentukan berdasarkan pengamatan visual terhadap
penyebaran vegetasi mangrove baik jenis maupun kerapatannya, serta karakteristik
khusus yang terdapat pada stasiun-stasiun tersebut juga aktifitas pembangunan di
Dengan demikian ditetapkan enam stasiun pengamatan, yaitu : Stasiun 1, merupakan daerah Ekosistem Mangrove Mbawi (Kondisi masih bagus); Stasiun 2, merupakan daerah estuaria sungai Mbawi; Stasiun 3 merupakan daerah ekosistem mangrove
Pandai (kondisi sedang); Stasiun 4 merupakan daerah estuaria sungai Pandai; Stasiun
5 merupakan daerah ekosistem mangrove Jambu (tergolong kondisi kurang bagus),
Stasiun 6 merupakan daerah estuaria sungai Jambu.
Pada setiap stasiun ditetapkan masing-masing 2-3 substasiun (sebagai
ulangan). Pengambilan sampel air, sedimen, bentos, plankton dan pasca larva udang,
hlakukan secara periodik selaina 1 bulan dengan selang waktu pengamatan sekitar 2
minggu.
Pengambilan Contoh Pasca Larva Udang
Pengarnbilan contoh pasca larva udang dilakukan pada tiap sub stasiun
pengamatan dengan menggunakan jaring seser (sero) berbentuk segi tiga ukuran lm x
lm x 1
m
dengan ukuran mata jaring 0,3 mm, dengan jalan menyeser ditengah-tengah vegetasi mangrove (pada alur sungailcreack) dan estuaria sepanjang jarak 50 meter.Pengumpulan Parameter Air dan Sedimen serta Prosedur Pelaksanaannya.
Adapun data yang dikumpulkan beserta alat, metode dan tempat pengumpulan data tersebut disajikan pada Lampiran 2.
Identifikasi Pasca Larva Udang dan Mangrove
Untuk keperluan identifikasi, maka sampeI pasca larva udang diawetkan
tersebut di bawa ke laboratorium untuk diidentifikasi dengan berpedoman pada buku
identifikasi udang menurut Dore dan Frimodt (1987) dan Smith (1977).
Sedangkan untuk mangrove, jenis yang tidak diketahui dilapangan di potong
dahan, dam, bunga dan buahnya selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk di
identifikasi dengan berpedoman pada Bengen (2000) dan Noor. Dkk., (1999).
Kerapatan Jenis Mangrove
Untuk memperoleh data kerapatan jenis mangrove maka dilakukan sampling
pada tiap stasiun dengan menggunakan "belt transect" yang ditempatkan tegak lurus
garis pantai. Di sepanjang transek dibuat petak pengamatan berukuran 10 m x 10 m
untuk data vegetasi mangrove yang masuk kategori pohon (diameter di atas 10 cm),
kemudian dalam petak pengamatan 10 m x 10 m tersebut dibuat lagi petak pengamatan berukuran 5 m x 5 m, untuk data vegetasi mangrove yang masuk kategori
anakanhelia (diameter antara 2 - 10 cm). Vegetasi mangrove pada tiap petak
pengamatan diidentifikasi, diukur diameternya kemudian jumlah individunya dihitung
untuk setiap kategori.
Pengambilan Contoh dan Identifikasi Plankton
Pengambilan contoh plankton dilakukan dengan menggunakan plankton net
nomor 25 untuk mengambil sampel fitoplankton dan zooplankton pada setiap stasiun
Pengambilan Contoh dan Identifikasi Makrozoobenthos
Pengambilan contoh makrozoobenthos dilakukan dengan menggunakan sekop,
sampel substrat diambil hingga kedalaman 20 cm, ukuran lebar 20 cm dan panjang 20
cm pada setiap stasiun yang telah ditentukan dan dilakukan secara acak. Sarnpel
tersebut di ayak dengan rnenggunakan sieve net untuk mendapatkan makrozoobenthos
(ukuran >1,0 mm). Makrozoobenthos yang didapatkan tersebut diawetkan dengan
formalin, selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi.
Kualitas Air dan Substrat.
Pengukuran kualitas air dan subtsrat dilakukan secara acak (pada posisi
pengarnbilan contoh udang) di tiap stasiun pengainatan, dengan pengulangan
sebanyak tiga kali. Pengambilan contoh substrat dilakukan secara acak pada alur
pengambilan contoh udang dengan menggunakan pipa PVC diameter 10 cm dengan
panjang 60 cm. Pipa PVC tersebut dibenamkan kedalam substrat dasar sedalam 15-30
cm Contoh substrat tersebut dimasukan kedalam kantong plastik berlabel untuk
selanjutnya dibawa ke laboratoriurn untuk dianalisa fraksi substratnya.
Analisis Data.
Kelimpahan Pasca Larva Udang.
Untuk menganalisa kelimpahan pasca larva udang digunakan rumus :
Ni=
A
Dimana : Ni = kelimpahan pasca larva udang jenis ke- I (1ndividu/m2)
Cni = Jurnlah individu dari jenis I
Pola Distribusi Kelimpahan Pasca Larva Udang.
Pola distribusi kelimpahan pasca larva udang pada setiap sub stasiun dianalisi
berdasarkan indeks penyebaran Morisita, yang pengukurannya berdasarkan rumus :
Dirnana : Id = Indeks penyebaran Morisita
n = jumlah sub stasiun pengamatan
C
X = Jumlah total individu dalam total n sub stasiun pengamatanC
x2
= Kuadrat jumlah individu per sub stasiun untuk total n sub stasiun.Dengan knteria pola distribusi adalah sebagai berikut : Jika nilai Id = 1,O maka distribusi acak
Jika nilai Id = 0 maka distribusi normal
Jika nilai Id = n maka distribusi bergerombol
Keanekaragaman Jenis Pasca Larva Udang
Keanekaragaman menggambarkan kekayaan dan sebaran kelimpahan jenis
dalam suatu komunitas. Untuk menyatakan keanekaragaman jenis dalam suatu
komunitas, maka salah satu cara yang paling urnurn untuk penelitian ekologis kelautan adalah dengan menggunakan indeks kekayaan jenisl keragaman (richness) Shannon-
Wiener yang diturunkan dari teori informasi dan bertujuan untuk mengukur
keteraturan atau ketidakteraturan (Krebs, 1989):
S
Dimana : H' = Indeks Shannon-Wiener
Pi = Peluang kepentingan untuk tiap jenis = ni/N
S = Jumlah jenis
Nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener berkisar antara 0
-
cx, dengan kriteriasebagai berikut :
H'< 3,2 : keanekaragaman populasi kecil
3,2 < H' < 9,9 : keanekaragaman populasi sedang
H' 2 9,9 : keanekaragaman populasi besar
Keseragaman Jenis
Keseragaman jenis yaitu komposisi tiap jenis yang terdapat dalam komunitas
(Krebs, 1989). Keseragaman jenis tersebut didapat dengan membandingkan indeks
keanekaragaman dengan nilai maksimumnya, dengan persamaan dibawah ini :
E = H'I Hmax
Dimana : E = Indeks keseragaman jenis
H' = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener
H max = Log 2 S = Indeks keanekaragamam maksimum
S = Jumlah jenis
Dominasi Jenis
Indeks dominasi jenis digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jenis
organisme yang mendominasi suatu koinunitas pada tiap habitat. Sebab dalam
dalam menentukan alam dan gawai pada komunitas tersebut. Hanya ada sedikit jenis
saja yang merupakan pengendali utama (Odum, 1996). Dominasi jenis diperoleh
menurut indeks dominasi Simpson dengan rumus sebagai berikut :
C = 2 (ni/N12
Dimana : C = Indeks dominasi Simpson
ni = Nilai kepentingan untuk tiap jenis
N = Total nilai kepentingan
Nilai indeks dominasi Simpson berkisar antara 0 - 1, dengan knteria sebagai berikut: C =
-
0, berarti komunitas tidak ada jenis yang mendominasi ataukomunitas dalam keadaan stabil
C =
-
1, berarti ada dominasi dari jenis tertentu atau komunitas dalamkeadaan tidak stabil.
Karakteristik Habitat
Kerapatan dan Ketebalan Formasi Mangrove
Kerapatan suatu jenis mangrove adalah total individu jenis tersebut yang
terdapat dalarn suatu unit area yang di ukur, dengan menggunakan rumus :
A
Dimana : Ki = Kerapatan Mangrove jenis ke-i.
C
ni = Jurnlah individu dari jenis ke-i.Sedangkan untuk ketebalan mangrove dihitung dengan jalan menarik transek
garis tegak lurus garis pantai pada bagan pinggir dan tengah dibelakang setiap stasiun
pengamatan, kemudian dihitung rata-rata ketebalannya.
Pengelompokan Karakteristik Habitat
Untuk melihat pengelompokkan karakteristik habitat antar sub stasiun
pengamatan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis stastistik
multivariabel yang didasarkan pada Analisis Komponen Utama (Principal Component
Analysis, PCA) menurut Legendre & Legendre (1983);