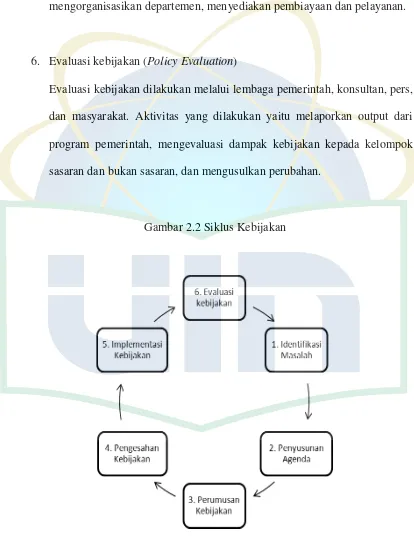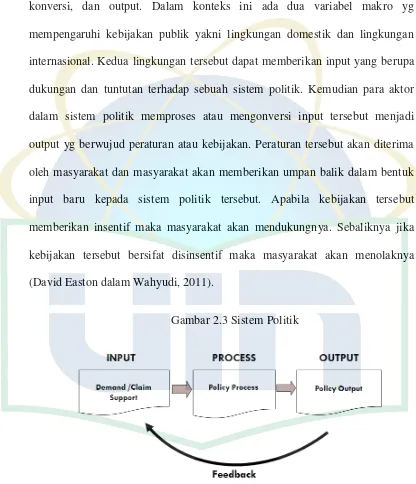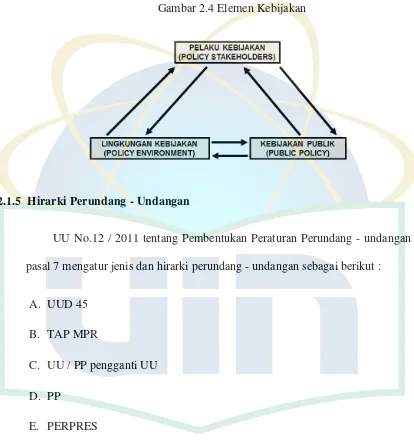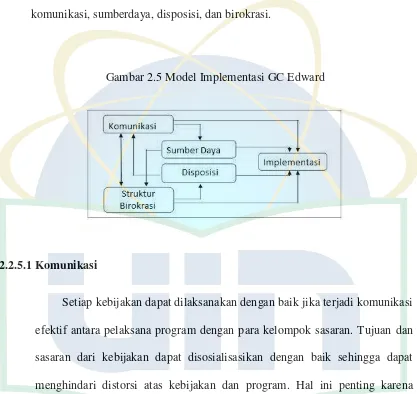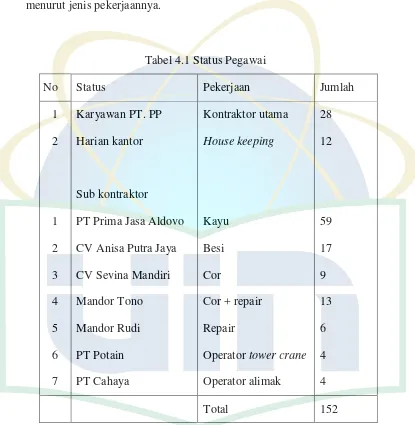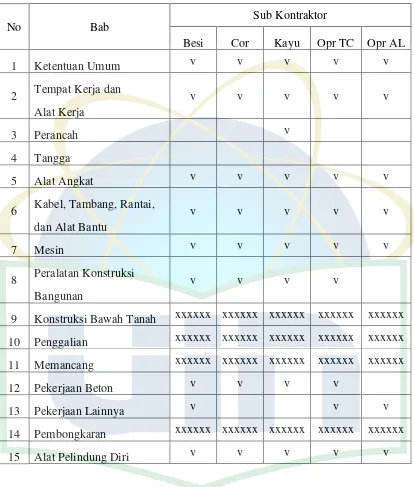ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI GC EDWARD PADA
PENERAPAN PERMENAKERTRANS NO.PER.01/MEN/1980
TENTANG K3 KONSTRUKSI BANGUNAN PADA PROYEK
APARTEMEN DAN HOTEL DI KEMANG JAKARTA SELATAN
TAHUN 2013
SKRIPSI
OLEH:
Rizqy Unggul Permadi
NIM: 108101000018
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
v
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
PUBLIC HEALTH STUDY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Thesis, Juli 2014
Rizqy Unggul Permadi, NIM : 108101000018
ANALYSIS GC EDWARD IMPLEMENTATION MODEL ON THE APLICATION PERMENAKERTRANS NO.PER.01/MEN/1980 ABOUT CONSTRUCTION OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF THE PROJECT APARTMENTS AND HOTEL IN KEMANG SOUTH JAKARTA YEAR 2013
xvi + 157 pages, 13 tables, 8 pictures
This study aims to look how the implementation of one of the government’s policy in the field of occupational safety which is Permenakertrans No.1 / 1980 about construction occupational health and safety on the apartments and hotel development projects in the works by PT PP in Kemang, South Jakarta . This study uses a model approach that saw GC Edward model policy implementation based on four basic subtances namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.
This study uses qualitative research methods. The information used comes from the informant interviews, field observations, and projects data related to work safety. Informants in this study was divided into 2 parts : 4 people who represent the main contractor and 5 people who represent sub-contarctor. Each informant has duties and responsibilities are different from each other.
vi
In each subtance based on GC Edward model the are problems resulting from the implementation of Permenakertrans No.1 / 1980 about construction occupational health and safety on the building construction is not going well. Problems are that there are not competent workers to work, recruitment of workers only based ages not skill, workers commitment to implement occupational safety is still lacking, the application of strict punishment is not done, and there are still many information related work safety and standard operational procedures that have not been socialized to workers.
Recommendation are given to company that repair worker recuitment system, the provision of safety training to workers specifically according to the type of work, the application of punishment was more emphasized, and dissemination of standard operating procedures for workers overall.
Keywords : Policy, Implementation, Construction
vii
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Skripsi, Juli 2014
Rizqy Unggul Permadi, NIM : 108101000018
ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI GC EDWARD PADA PENERAPAN PERMENAKERTRANS NO.PER.01/MEN/1980 TENTANG K3 KONSTRUKSI BANGUNAN PADA PROYEK APARTEMEN DAN HOTEL DI KEMANG JAKARTA SELATAN
TAHUN 2013
xvi + 157 halaman, 13 tabel, 8 gambar
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan salah satu kebijakan pemerintah di bidang keselamatan kerja yaitu Permenakertans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan pada proyek pembangunan apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT PP di Kemang, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan model GC Edward yang melihat implementasi kebijakan berdasarkan 4 substansi dasar yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Metode penelitian bersifat kualitatif. Informasi yang digunakan bersumber dari wawancara terhadap informan, observasi di lapangan, dan data - data proyek yang terkait dengan keselamatan kerja. Informan dalam penelitian terbagi menjadi 2 bagian yaitu 4 orang yang mewakili kontraktor utama dan 5 pekerja sub kontraktor. Setiap informan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda - beda antara satu dan lainnya.
viii
Pada masing - masing substansi berdasarkan model GC Edward terdapat permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan dari Permenakertans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan tidak berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut antara lain masih adanya pekerja yang belum kompeten untuk bekerja, rekrutmen pekerja hanya berdasarkan umur bukan keahlian, komitmen pekerja untuk melaksanakan peraturan keselamatan kerja masih kurang, penerapan hukuman tidak tegas dilakukan, dan masih banyaknya informasi terkait keselamatan kerja dan standar operasional prosedur yang belum disosialisasikan kepada pekerja.
Rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan yaitu perbaikan sistem rekrutmen pekerja, pemberian pelatihan keselamatan kerja kepada pekerja secara spesifik menurut jenis pekerjaan, penerapan hukuman dipertegas, dan sosialisasi standar operasional prosedur menyeluruh kepada pekerja.
Kata kunci : Kebijakan, Implementasi, Konstruksi
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT karena atas rahmat dan
karunia - Nya yang telah memberikan banyak kemudahan kepada saya mulai dari
pengajuan surat izin lapangan, selama penugasan, sampai selesainya laporan skripsi
ini. Tak terkira banyaknya rasa syukur yang dapat hamba panjatkan ke hadiratmu.
Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi,
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saya mengucapkan terima kasih kepada orang - orang yang telah membantu
dalam proses penyusunan laporan skripsi ini. Untuk hal tersebut saya mengharapkan
saran dan kritik guna memperbaiki laporan skripsi ini sehingga dapat lebih sempurna.
Saya mengucapkan terima kasih kepada :
1. Kedua orang tua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan penuh baik
moril maupun materiil.
2. Ibu Febrianti selaku Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN
Jakarta.
3. Bapak Arif Sumantri selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan
x
4. Ibu Riastuti Kusuma Wardhani selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan masukan dan bimbingan selama penyusunan laporan skripsi ini
hingga selesai.
5. Bapak Mulyono dan Bapak Dadan selaku HSE officer proyek Kemang yang
telah banyak membantu saya saat proses pengerjaan skripsi di lapangan.
6. Seluruh informan pekerja proyek Kemang yaitu pekerja kayu, besi, cor, house
keeping, operator tower crane, dan alimak yang telah memberikan informasi
yang saya butuhkan selama proses pengerjaan skripsi di lapangan dan berbagi
pengalaman kerja kepada saya.
7. Seluruh dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah membimbing
dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya selama proses
perkuliahan.
8. Teman - teman Kesmas 2008 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya satu
per satu. Semoga semua perjuangan kita selama perkuliahan dapat menjadi
kenangan untuk kita semua.
9. Serta segenap pihak yang telah banyak berperan aktif membantu pelaksanaan
skripsi dan dalam menyelesaikan laporan skripsi ini yang tidak saya sebutkan
secara keseluruhan.
Dengan memanjatkan doa kepada ALLAH SWT, saya berharap semua
kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan kebahagaiaan dunia dan akhirat, dan
xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Rizqy Unggul Permadi
TTL : Lamongan 15 April 1989
Alamat : Jl. Jamhur I No.108 Rt 04/01 Cinere, Depok
Agama : Islam
Gol. Darah : A
No. Telp : 0856 48563175
RIWAYAT PENDIDIKAN
1995 – 2001 SD Jetis VI - Lamongan
2001– 2004 SMP Negeri 12 - Jakarta
2004– 2007 SMA Negeri 6 - Jakarta
2008 – sekarang S1 – Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
xii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERNYATAAN……….………. i
LEMBAR PERSETUJUAN... ii
ABSTRAK……….……… x
KATA PENGANTAR……….……….... ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP…….………....……… xi
DAFTAR ISI.……….... xii
DAFTAR TABEL………..………... xviii
DAFTAR GAMBAR………... xix
BAB I PENDAHULUAN……….……… 1
1.1Latar Belakang………. 1
1.2Rumusan Masalah……….... 8
1.3Pertanyaan Penelitian ……….. 8
1.4Tujuan Penelitian………... 9
1.4.1Tujuan Umum ……….... 9
1.4.2Tujuan Khusus………... 9
xiii
1.5.1Manfaat Aplikatif………... 10
1.6 Ruang Lingkup ………... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA………...………. 12
2.1Kebijakan K3 Konstruksi………...………...………….... 12
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik………... 12
2.1.2 Proses Kebijakan Publik... 16
2.1.3 Kebijakan Publik dan Hukum... 19
2.1.4 Elemen Kebijakan... 20
2.1.5 Hirarki Perundang - undangan ... 21
2.1.6 Kebijakan Kesehatan ... 22
2.1.7 Jasa Konstruksi... 23
2.1.8 Kebijakan Publik K3 Konstruksi Bangunan... 25
2.1.9 Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan ... 28
2.2Implementasi Kebijakan………... 29
2.2.1 Model Implementasi Van Horn dan Van Meter……….. 34
2.2.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle………. 35
2.2.3 Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier…… 36
2.2.4 Model Implementasi G.Shabir Chema dan Dennis Rondinelli... 37
2.2.5 Model Implementasi GC Edward………...……... 39
2.2.5.1Komunikasi ………... 39
xiv
2.2.5.1.2 Kejelasan………..………... 41
2.2.5.1.3 Konsistensi………..……….. 41
2.2.5.2Disposisi……….………. 41
2.2.5.2.1 Pengangkatan Birokrasi……… 42
2.2.5.2.2 Insentif……….. 42
2.2.5.3Sumber Daya………….………... 43
2.2.5.3.1 Staf……… 43
2.2.5.3.2 Informasi……… 43
2.2.5.3.3 Wewenang………. 44
2.2.5.3.4 Fasilitas………... 44
2.2.5.4Struktur Birokrasi……….…...……… 45
2.2.5.4.1 Standar Operasional Prosedur……… 45
2.2.5.4.2 Fragmentasi………... 46
2.3Kerangka Teori………... 47
BAB III KERANGKA PIKIR ……...………...... 49
3.1Kerangka Pikir….………... 49
3.2Definisi Istilah………... 50
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN………... 57
4.1Jenis Penelitian……….57
4.2Waktu dan Tempat Penelitian………... 57
xv
4.4Instrumen Penelitian……… 62
4.5Jenis Data………...………... 63
4.6Teknik Pengumpulan Data………. 64
4.7Pengolahan Data………. 65
4.8Analisis Data……….. 66
4.9Keabsahan Data………... 67
BAB V HASIL... 68
5.1 Karakteristik Informan... 68
5.2 Implementasi Kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang K3 Konstruksi Bangunan ... 69
5.3 Analisis Model GC Edward... 73
5.3.1 Komunikasi... 73
5.3.1.1 Transmisi... 73
5.3.1.2 Kejelasan... 79
5.3.1.3 Konsistensi... 83
5.3.2 Disposisi... 84
5.3.2.1 Komitmen... 84
5.3.2.2 Insentif... 85
5.3.3 Sumber Daya... 89
5.3.3.1 Staf... 89
5.3.3.2 Informasi... 93
xvi
5.3.3.4 Fasilitas... 100
5.3.3.5 Anggaran... 102
5.3.4 Struktur Birokrasi... 103
5.3.4.1 Standar Operasional Prosedur... 103
5.3.4.2 Fragmentasi... 108
BAB VI PEMBAHASAN ... 114
6.1 Keterbatasan Penelitian... 114
6.2 Implementasi Kebijakan Permenakertrans No.1 /1980 Tentang K3 Konstruksi Bangunan... 115
6.3 Analisis Model GC Edward... 119
6.3.1 Komunikasi... 119
6.3.1.1 Transmisi... 119
6.3.1.2 Kejelasan... 122
6.3.1.3 Konsistensi... 124
6.3.2 Disposisi... 126
6.3.2.1 Komitmen... 126
6.3.2.2 Insentif... 128
6.3.3 Sumber Daya... 131
6.3.3.1 Staf... 131
6.3.3.2 Informasi... 134
6.3.3.3 Wewenang... 136
xvii
6.3.3.5 Anggaran... 139
6.3.4 Struktur Birokrasi... 140
6.3.4.1 Standar Operasional Prosedur... 140
6.3.4.2 Fragmentasi... 142
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 145
7.1 Kesimpulan... 145
7.2 Saran... 148
DAFTAR PUSTAKA ... 151
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Status Pegawai……….. 59
Tabel 4.2 Matriks Informan Kontraktor...……….. 60
Tabel 4.3 Matriks Informan Subkontraktor... 61
Tabel 5.1 Karakteristik Informan……….. 68
Tabel 5.2 Implementasi Permenakertrans No.1 / 1980 ... 69
Tabel 5.3 Pelatihan K3 Umum ... 77
Tabel 5.4 Pelatihan K3 Khusus ... ... 78
Tabel 5.5 Kompetensi Informan ... 82
Tabel 5.6 Kewenangan HSE Pusat dan HSE Proyek ... 96
Tabel 5.7 Kewenangan Quality Control ... 98
Tabel 5.8 Kewenangan Pekerja Lapangan ... 99
Tabel 5.9 SOP Pekerjaan... 105
xix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kebijakan Publik Sebagai Bentuk Nyata Ideologi………....15
Gambar 2.2 Siklus Kebijakan………... 18
Gambar 2.3 Sistem Politik……… 20
Gambar 2.4 Elemen Kebijakan………. 21
Gambar 2.5 Model Implementasi GC Edward………. 39
Gambar 3.1 Kerangka Pikir ...……….. 49
Gambar 5.1 Struktur Organisasi Proyek ... 109
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Kebijakan merupakan apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau
tidak dilakukan (Dye dalam Wibawa, 1994). Sedangkan kebijakan publik adalah
kebijakan - kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah
dan pejabat - pejabatnya (Anderson dalam Wibawa, 1994). Kebijakan kesehatan
didefinisikan sebagai suatu bentuk arah utama dalam suatu pemerintahan negara
berupa kebijakan politik guna menjalankan program - program pembangunannya,
secara khusus di sektor kesehatan (Walt dalam Massie, 2009). Oleh karena itu,
sebagai aktor penting maka pemerintah adalah pihak yang menentukan kebijakan
negara termasuk kebijakan kesehatan yang meliputi perlindungan tenaga kerja.
Isu global mengenai upaya perlindungan tenaga kerja sudah dimulai sejak
International Labour Organization ( ILO ) mulai didirikan pada tahun 1919 untuk
mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya
dapat dicapai melalui keadilan sosial. Lalu pada tahun 1944 para pendiri ILO
menerapkan deklarasi Philadelphia yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah
komoditas dan menetapkan hak asasi manusia dan hak ekonomi kepada kaum
pekerja. Kemajuan besar dicapai ILO pada tahun 1998 dengan diadakannya
Konferensi Perburuhan Internasional yang mengadopsi deklarasi ILO tentang
2
membahas mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja. Hingga saat ini ILO
telah membantu banyak negara melalui upaya - upaya pembuatan kebijakan
mengenai hak serikat pekerja dalam memperoleh demokrasi dan perlindungan
tenaga kerja (ILO, 2007).
Pada tingkat nasional kewajiban untuk melindungi keselamatan dan
kesehatan pekerja telah diatur dalam undang - undang dan peraturan keselamatan
dan kesehatan kerja yang menjamin perlindungan pekerja terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia. Selain itu juga mengatur dengan jelas tentang hak dan
kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat - syarat keselamatan
kerja serta sistem manajemen K3 (Modjo, 2007).
Upaya perlindungan tenaga kerja sudah dimulai saat sebelum Indonesia
mendapatkan kemerdekaannya yaitu dengan dibuatnya Veiligheidsreglement
tahun 1910 disusul Verordening Stoom Ordonnantie tahun 1930. Lalu setelah
Indonesia merdeka dibuatnya landasan undang - undang dasar 1945. Pasal 27 ayat
2 berbunyi “ Tiap - tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini dijadikan landasan utama dalam
pembuatan kebijakan - kebijakan selanjutnya seperti undang - undang No.1 tahun
1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur tentang kewajiban pimpinan
tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja, UU No.23
tahun 1992 tentang kesehatan pasal 23 tentang kesehatan kerja menekankan
pentingnya kesehatan kerja agar pekerja dapat bekerja secara sehat dan
3
ketenagakerjaan paragraf 5 pasal 86 dan 87 tentang keselamatan dan kesehatan
kerja harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan lainnya yang
berlaku. Pada pasal 35 dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan
perlindungan kepada tenaga kerjanya mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan
kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Sebagai penjabaran dan
kelengkapan Undang - undang, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah
dan kementerian tenaga kerja dan kementrian kesehatan juga mengeluarkan
kebijakan untuk memudahkan pelaksanaan K3 di tempat kerja. Hingga saat ini
sudah puluhan aturan hukum dibuat mengenai keselamatan kerja.
Dengan banyaknya kebijakan yang sudah dibuat dalam upaya
melindungi tenaga kerja tidak menjamin kecelakaan kerja tidak akan terjadi.
Sampai saat ini kecelakaan kerja masih saja sering terjadi dari tahun ke tahun.
Secara global, ILO mencatat bahwa setiap tahunnya kurang lebih terjadi 337 juta
kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak kurang dari 2,3 juta nyawa melayang.
Dilihat dari dampak ekonomi USD 1,25 Trilyun atau 4% dari Global Gross
Domestic Product (GDP) dialokasikan utuk biaya dari kehilangan waktu kerja
akibat kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja, kompensasi untuk para
pekerja, terhentinya produksi, dan biaya pengobatan pekerja (ILO, 2012).
Secara nasional, data yang didapat dari Jamsostek menunjukkan bahwa
pada tahun 2011 terjadi 99.491 kecelakaan kerja. Total klaim yang telah dibayar
sekitar Rp 504,3 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 yang
sebesar 98.711 kecelakaan kerja dengan total klaim yang dibayar Rp 401,237
4
kerja di Indonesia pada tahun 2009 terdapat 88.492 kasus kecelakaan kerja . Pada
kesempatan terpisah Dirut Jamsostek juga menyatakan bahwa selama 34 tahun
sejak PT Jamsostek beroperasi hingga kini, terjadi 1.883.200 kasus kecelakaan
kerja dengan total klaim yang harus dibayarkan sebanyak Rp 3,46 triliun. Dari
jumlah tersebut sektor yang mencatat persentase tertinggi adalah sektor konstruksi
sebesar 32 % (Pikiran rakyat, 2012).
Pada 2009 tercatat pekerja di sektor jasa konstruksi ada 5% atau sekitar
4,5 juta pekerja dengan kecelakaan kerja yang beragam. Hingga November 2009
pelaksanaan program jasa konstruksi secara nasional telah terdaftar menjadi
peserta jamsostek sebanyak 93.103 perusahaan dengan sekitar 4.362.224 orang
tenaga kerja (Poskota, 2010).
Data yang disampaikan oleh menteri tenaga kerja Muhaimin Iskandar
menyatakan sampai dengan September 2012 angka kecelakaan kerja berada pada
kisaran 80.000 kejadian (Detik finance, 2012). Pusat Pembinaan Penyelenggaraan
Konstruksi menilai pentingnya pemahaman mengenai pengadaan barang atau jasa
pemerintah di bidang konstruksi menyusul tingginya kasus kecelakaan pekerja
konstruksi yang bermunculan dengan rata - rata 7 orang meninggal per hari
(Industri bisnis, 2013) .
Kebijakan mengenai penyelenggaraan K3 pada pekerjaan konstruksi
tergambar pada UU No.18 / 1999 tentang jasa konstruksi yang mengamanatkan
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang
5
kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib
penyelenggaraan konstruksi.
Kebijakan K3 yang menyangkut dengan kegiatan konstruksi lainnya yaitu
Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan. Peraturan ini bisa
dibilang merupakan induk penting pelaksanaan K3 pada kegiatan konstruksi di
Indonesia karena memuat banyak hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan
kostruksi yaitu tempat kerja, peralatan kerja, mesin, perancah, tangga, alat angkat,
penggalian, pemancangan, beton, APD, dan apapun yang berkaitan dengan
konstruksi. Sudah 33 tahun berlalu namun peraturan ini masih dipakai sebagai
bagian dari persyaratan legal yang harus dipenuhi perusahaan konstruksi dalam
menjalankan kegiatannya dan belum direvisi hingga saat ini. Peraturan ini juga
lebih bersifat aplikatif di lapangan dibandingkan peraturan pemerintah lainnya di
bidang konstruksi.
Implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang
dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Implementasi kebijakan
mencakup tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok,
publik maupun privat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang
telah ditentukan terlebih dahulu. Ini meliputi baik usaha - usaha sesaat untuk
menstransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha yang
berkelanjutan untuk mencapai perubahan - perubahan besar dan kecil yang
diamanatkan oleh keputusan - keputusan kebijakan (Van Horn dan Van Meter
6
agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang
(Nugroho, 2008).
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh
beberapa variabel antara lain komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan
disposisi. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah -
perintah dan arahan - arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang
diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Disposisi yaitu kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.
Struktur birokrasi yaitu kelembagaan perusahaan dalam mensukseskan
implementasi kebijakan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari luar perusahaan
(GC Edward dalam Sahuri, 2012).
PT. PP ( Pembangunan Perumahan ) merupakan salah satu perusahaan
BUMN konstruksi terbersar di Indonesia. Saat ini PT. PP sedang menggarap salah
satu proyek di Kemang, Jakarta Selatan berupa apartemen dan hotel. Proyek yg
ini sudah berjalan dari tahun 2012. Menurut studi pendahuluan yang dilakukan
pada Februari 2013 tercatat pada laporan kecelakaan sudah terjadi 5 kecelakaan
kerja hingga saat ini dengan rincian 4 kecelakaan terjadi pada tahun 2012 dan 1
kecelakaan kerja pada Januari 2013. Menurut penanggung jawab K3 proyek,
kecelakaan kerja yang dilaporkan belum tentu sebenarnya yang terjadi karena di
lapangan banyak pekerja yang menyembunyikan atau tidak melaporkan
kecelakaan kerja yang sifatnya hanya cedera ringan sehingga bisa jadi jumlah
kecelakaan kerja yang terjadi jumlahnya bisa mencapai puluhan. Selain itu juga
7
Diakui pula oleh penanggung jawab K3 proyek bahwa karakteristik
kegiatan konstruksi yang berbeda dengan sektor lainnya sehingga kecelakaan
kerja pada sektor ini mustahil dapat mencapai zero accident. Karakteristik yang
dimaksud misalnya banyak melibatkan tenaga kerja kasar yang berpendidikan
relatif rendah, intensitas kerja tinggi dibuktikan dengan akhir pekan yang tetap
melakukan kegiatan operasinya, peralatan kerja yang beragam jenis, teknologi,
dan kapasitasnya, dan juga mobilisasi peralatan dan material yang tinggi.
Hasil observasi yang dilakukan peneliti saat studi pendahuluan juga
menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran - pelanggaran terkait aturan K3 antara
lain masih banyak bahan - bahan berserakan di lokasi kerja dan masih banyak
pekerja yang menggunakan APD seenaknya bahkan masih ada saja yang tidak
mau menggunakan.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai gambaran implementasi kebijakan Permenakertrans No.1 /
1980 tentang K3 konstruksi bangunan pada proyek hotel dan apartemen yang
sedang digarap PT. PP di Kemang, Jakarta Selatan. Penelitian ini akan melihat
bagaimana analisa model GC Edward pada penerapan kebijakan K3 pada proyek
tersebut dan juga untuk mengetahui hambatan dan problem yg muncul dalam
proses implementasi berdasarkan model implementasi kebijakan GC Edward
yaitu dengan melihat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
8
1.2Rumusan Masalah
PT. PP ( Pembangunan Perumahan ) saat ini sedang menggarap salah satu
proyek di Kemang, Jakarta Selatan berupa apartemen dan hotel. Proyek yg ini
sudah berjalan dari tahun 2012. Menurut studi pendahuluan yang dilakukan pada
Februari 2013 tercatat pada laporan kecelakaan sudah terjadi 5 kecelakaan kerja
dengan rincian 4 kecelakaan terjadi pada tahun 2012 dan 1 kecelakaan kerja pada
Januari 2013. Menurut penanggung jawab K3 proyek ini, kecelakaan kerja yang
dilaporkan belum tentu sebenarnya yang terjadi karena di lapangan banyak
pekerja yang tidak melaporkan kecelakaan kerja yang sifatnya cedera ringan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran - pelanggaran
terkait aturan K3 antara lain masih banyak bahan - bahan berserakan di lokasi
kerja dan masih banyak pekerja yang menggunakan APD seenaknya bahkan
masih ada saja yang tidak mau menggunakan.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan
Penelitian ini untuk melihat bagaimana analisa model GC Edward pada penerapan
kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan pada
proyek apartemen dan hotel yang sedang digarap PT PP di Kemang, Jakarta
Selatan.
1.3 Pertanyaan Penelitian
Bagaimana analisa model GC Edward pada penerapan kebijakan
9
proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan
Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan ?
1.4 Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum
Diketahuinya implementasi penerapan kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980
tentang K3 konstruksi bangunan pada lokasi proyek apartemen dan hotel yang
sedang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan
dengan pendekatan analisis kebijakan model GC Edward.
1.4.2 Tujuan Khusus
1. Diketahuinya gambaran tentang komunikasi terhadap penerapan kebijakan
Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di lokasi
proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan
Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.
2. Diketahuinya gambaran tentang disposisi terhadap penerapan kebijakan
Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di lokasi
proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan
Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.
3. Diketahuinya gambaran tentang sumber daya terhadap penerapan kebijakan
Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di lokasi
proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan
10
4. Diketahuinya gambaran tentang struktur birokrasi terhadap implementasi
kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di
lokasi proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT
Pembangunan Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.
1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Aplikatif
1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
dalam menentukan perencanaan kegiatan K3 sehubungan dengan kegiatan
konstruksi di lokasi proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan
PT Pembangunan Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.
2. Bagi fakultas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam
pengembangan kurikulum program studi Kesehatan Masyarakat
khususnya pada konsentrasi K3.
3. Bagi pihak Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya sehubungan
dengan permasalahan K3 konstruksi di Indonesia.
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan
perbandingan ataupun data dalam penelitian studi implementasi kebijakan
Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di
11
1.6 Ruang Lingkup
Penelitian ini dilakukana pada bulan mei 2013 dengan perkiraan jumlah
hari ± 30 hari bertempat di lokasi proyek Kemang Village Residence, Jakarta
Selatan. PT. PP sebagai salah satu kontraktor menggarap pembangunan beberapa
apartemen dan hotel pada proyek tersebut.
Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti itu sendiri. Triangulasi data dilakukan
berdasarkan teknik yaitu observasi, wawancara, dan telaah dokumen dan juga
berdasarkan sumber yaitu informan dari pekerja kontraktor dan pekerja
subkontraktor. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana proses
implementasi yang dilakukan di lapangan. Bantuan dari pihak lain atau
penghubung diperlukan saat proses wawancara mendalam dengan informan
sebagai sumber data primer. Data juga diperoleh dengan melakukan telaah
dokumen perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Permenakertrans No.1 /
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kebijakan K3 Konstruksi
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik
Menurut Jones dalam Wahyudi (2011), kata kebijakan sering digunakan
dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum,
proposal, patokan dan maksud besar tertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikan
kebijakan adalah keputusan tetap yg dicikan oleh konsistensi dan pengulangan
tingkah laku dari mereka yg membuat dan dari mereka yg mematuhi keputusan
tersebut.
Secara etiologi publik berasal dari bahasa yunani yakni pubes berarti
kedewasaan secara picik, emosional maupun intelektual. Dalam bahasa yunani
istilah publik sering dipadankan dengan kata common yang bermakna hubungan
antar individu. Oleh karena itu publik sering dikonsepsikan sebagai suatu ruang
yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu diatur atau diintervensi oleh
pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama (Namawi
dalam Wahyudi, 2011).
Menurut menurut Thomas R Dye dalam Wibawa (1994), kebijakan publik
diartikan sebagai “whatever governments choose to do or not to do” (pilihan
13
menurut Andersondalam Zaeni (2006): “A purposive course of action followed
by an actor or set of actors in deadling with a problem or a matter of
concern”(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti
dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu). Selanjutnya Harold D Laswell dan
Abraham Kaplan dalam Yulisetyaningtyas (2008) mengatakan bahwa
kebijakan publik sebagai “a projected program of goals, values and practices“
(suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).
Amara Raksasataya dalam Wisakti (2008) menyebutkan bahwa kebijaksanaan
adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata
dari taktik atau strategi.
Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan
publik menurut Anderson dalam Susilowaty (2007) adalah :
1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan
14
3. Kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa
bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat
negarif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan
sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang -
undangan yang bersifat memaksa atau otoritatif.
Kebijakan publik juga berarti serangkaian instruksi dari para pembuat
keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam
konteks ini, kebijakan publik dapat dilihat dalam tiga lingkungan kebijakan,
yaitu : (1) perumusan kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan dan (3) penilaian
kebijakan atau evaluasi. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan
pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari perumusan,
pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. (Nakamura dan Smallwood dalam
Yulisetyaningtyas, 2008). Lebih jauh lagi kebijakan publik dapat ditetapkan
secara jelas dalam peraturan - peraturan, perundang - undangan, atau dalam
bentuk pidato pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program
-program dan tindakan - tindakan yang dilakukan pemerintah (Islamy, 1997).
Kebijakan publik menentukan bentuk kehidupan bangsa dan negara.
Negara dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya mempunyai respon
15
kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya pemerintah untuk mengatur
kehidupan bersama yang disebut sebagai bangsa dan negara. Kebijakan publik
pada akhirnya merupakan bentuk paling nyata dari ideologi suatu negara.
(Nugroho, 2008)
Gambar 2.1 Kebijakan Publik Bentuk Nyata Ideologi
Ideologi adalah keyakinan politik negara berdaulat. Ideologi diturunkan
menjadi politik kebangsaan apapun bentuknya baik demokrasi atau non
demokrasi. Lalu diturunkan lagi menjadi kebijakan publik. Politik yang paling
unggul sekalipun tidak ada gunanya jika tidak mampu membangun kebijakan -
kebijakan publik yang juga unggul.
Ideologi
Sistem
Politik
16
2.1.2 Proses Kebijakan Publik
Proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas
yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para
ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah
kebijakan publik. Untuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian
mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy
process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles).
Thomas R. Dye dalam Wahyudi (2011) menjabarkan proses kebijakan
publik sebagai berikut :
1. Identifikasi masalah kebijakan (Identification of Policy Problem)
Dapat dilakukan melalui identifikasi apa yg menjadi tuntutan atas tindakan
pemerintah. Aktivitas yang dilakukan yaitu publikasi masalah sosial dan
mengekspresikan tuntutan akan tindakan dari pemerintah. Peserta yang
terlibat antara lain media massa, kelompok kepentingan, inisiatif
masyarakat, maupun opini publik.
2. Penyusunan agenda (Agenda Setting)
Merupakan aktivitas yg memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan
media massa atas keputusan apa yg akan diputuskan terhadap masalah
publik tertentu. Aktivitas yang dilakukan yaitu menentukan mengenai
17
dibahas oleh pemerintah. Peserta yang terlibat antara lain kaum elit
termasuk presiden kongres, kandidat untuk jabatan publik tertentu, maupun
dewan negara.
3. Perumusan kebijakan (Policy Formulation)
Merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan
penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan,
kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga
legislatif. Aktivitas yang dilakukan adalah pengembangan proposal
kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah. Peserta yang
terlibat antara lain presiden, lembaga eksekutif, komite kongres, dan
kelompok kepentingan.
4. Pengesahan kebijakan (Legitimating of Policy)
Pengesahan kebijakan dilakukan melalui tindakan politik oleh partai
politis, kelompok penekan, presiden, dan kongres. Aktivitas yang
dilakukan yaitu memilih proposal, mengembangkan dukungan untuk
proposal terpilih, menetapkannya menjadi peraturan hukum, dan
memutuskan konstitusionalnya. Peserta yang terlibat antara lain kelompok
18
5. Implementasi kebijakan (Policy Implementation)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, atau
aktivitas agen eksekutif yg terorganisasi. Aktivitas yang dilakukan yaitu
mengorganisasikan departemen, menyediakan pembiayaan dan pelayanan.
6. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)
Evaluasi kebijakan dilakukan melalui lembaga pemerintah, konsultan, pers,
dan masyarakat. Aktivitas yang dilakukan yaitu melaporkan output dari
program pemerintah, mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok
sasaran dan bukan sasaran, dan mengusulkan perubahan.
19
2.1.3 Kebijakan Publik dan Hukum
Hukum publik merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Hukum
publik memberikan wadah legal bagi negara untuk mencapai tujuan yang
dibawa oleh kebijakan publik tersebut dan untuk membatasi kekuasaan negara
karena prinsip negara modern adalah negara dengan kekuasaan tidak tak
terbatas.
Setiap kebijakan publik yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal
dan berlaku mengikat kehidupan bersama, maka pada saat itu pula kebijakan
publik berubah menjadi hukum. Berarti hukum merupakan wujud dari
kebijakan publik, tapi kebijakan publik tidak identik dengan hukum.
Hukum publik merupakan formalisasi dan legalisasi dari kebijakan
publik. Tanpa proses formalisasi dan legalisasi tersebut kebijakan publik
menjadi tidak berdaya untuk dilaksanakan. Namun tidak semua kebijakan
publik memerlukan kodifikasi formal dan legal dalam bentuk hukum publik
karena tetap ada kebijakan yang dapat dilaksanakan secara efektif tanpa
memerlukan bentuk formal legal yaitu kebijakan yang mengandalkan sanksi
politik dan sanksi sosial. Jadi tujuan hukum adalah untuk membuat kebijakan
publik dapat dilaksanakan dan untuk membatasi kekuasaan pembuat dan
20
2.1.4 Elemen Kebijakan
Kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem yg terdiri dari input,
konversi, dan output. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yg
mempengaruhi kebijakan publik yakni lingkungan domestik dan lingkungan
internasional. Kedua lingkungan tersebut dapat memberikan input yang berupa
dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor
dalam sistem politik memproses atau mengonversi input tersebut menjadi
output yg berwujud peraturan atau kebijakan. Peraturan tersebut akan diterima
oleh masyarakat dan masyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk
input baru kepada sistem politik tersebut. Apabila kebijakan tersebut
memberikan insentif maka masyarakat akan mendukungnya. Sebaliknya jika
kebijakan tersebut bersifat disinsentif maka masyarakat akan menolaknya
(David Easton dalam Wahyudi, 2011).
Gambar 2.3 Sistem Politik
Lingkungan kebijakan seperti gejolak politik pada suatu negara akan
21
memasukkannya kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan
kebijakan publik untuk memecahkan masalah - masalah yg bersangkutan.
Gambar 2.4 Elemen Kebijakan
2.1.5 Hirarki Perundang - Undangan
UU No.12 / 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
pasal 7 mengatur jenis dan hirarki perundang - undangan sebagai berikut :
A. UUD 45
B. TAP MPR
C. UU / PP pengganti UU
D. PP
E. PERPRES
F. PERDA provinsi
22
Kesemuanya merupakan bentuk kebijakan publik yang terkodifikasi
secara legal. Di samping itu, kekuatan hukum Peraturan Perundang - undangan
sesuai dengan hirarki tersebut. Artinya peraturan di bawah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan pada hirarki di atasnya.
Dalam pemahaman kontinentalis, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar yaitu
ketujuh peraturan di atas.
2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah. Kebijakan ini dapat
berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur,
peraturan bupati, ataupun surat keputusan bersama / SKB antar menteri.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah yang mengatur pelaksanaan
kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya berupa peraturan yang
dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, atau walikota.
Namun ada beberapa kebijakan yang sifatnya messo atau makro dapat
diimplementasikan langsung dan itu bukan merupakan kekeliruan.
2.1.6 Kebijakan Kesehatan
Kebijakan kesehatan didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang
berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan
23
Kebijakan - kebijakan kesehatan dibuat oleh pemerintah dan swasta. Kebijakan
merupakan produk pemerintah walaupun pelayanan kesehatan cenderung
dilakukan oleh swasta, dikontrakkan atau melalui kemitraan, kebijakannya
disiapkan oleh pemerintah dimana keputusannya mempertimbangkan aspek
politik. (Walt dalam Massie, 2009).
Kebijakan kesehatan berpihak pada hal - hal yang dianggap penting dalam
suatu institusi dan masyarakat, bertujuan jangka panjang untuk mencapai
sasaran, menyediakan rekomendasi yang praktis untuk keputusan - keputusan
penting (WHO dalam Massie, 2009).
Kebijakan kesehatan terefleksi dalam beberapa bentuk hukum tertulis
misalnya undang - undang, peraturan pemerintah, rencana strategis, program
kesehatan, dan sebagainya.
2.1.7 Jasa Konstruksi
Menurut Undang - undang tentang Jasa konstruksi, "Jasa Konstruksi"
adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi
pengawasan pekerjaan konstruksi. "Pekerjaan Konstruksi" adalah
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta
24
Dari pengertian dalam UU No.18 / 1999 Tentang Jasa Konstruksi tersebut
maka dalam masyarakat terbentuklah "Usaha Jasa Konstruksi", yaitu usaha
tentang jasa di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang
semuanya disebut penyedia jasa.
Proyek Konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu
kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian
kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek
menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam
rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dengan banyaknya pihak yang terlibat
dalam proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga
dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup
tinggi (Ervianto, 2007).
Bidang konstruksi perlu mendapat perhatian dikarenakan lokasi pekerjaan
proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung resiko cukup
besar sehingga dapat dikatakan bahwa industri konstruksi terbilang paling
rentan terhadap kecelakaan kerja. Hal tersebut karena bidang konstruksi
merupakan satu bidang produksi yang memerlukan kapasitas tenaga kerja dan
tenaga mesin yang sangat besar, bahaya yang sering ditimbulkan umumnya
dikarenakan faktor fisik, yaitu : terlindas dan terbentur yang disebabkan oleh
terjatuh dari ketinggian, kejatuhan barang dari atas atau barang roboh. Hal
tersebut juga didukung oleh prilaku kerja yang tidak aman. Selain kurangnya
25
dilakukan pemilik usaha sering tidak mencukupi (IOSH, 2007). Oleh karena itu
perlu adanya peraturan terkait keselamatan kerja bidang konstruksi.
2.1.8 Kebijakan Publik K3 Konstruksi Bangunan
Dalam mengisi cita - cita pembangunan nasional maka perlu dilakukan
program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan
agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari
perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dalam
pertumbuhan ekonomi negara. Sektor konstruksi sangat dibutuhkan negara
dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian nasional oleh karena itu
sudah selayaknya pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan guna
mengatur dan memberdayakan jasa konstruksi nasional.
Menyadari akan hal tersebut maka sudah selayaknya kehadiran undang -
undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi sangat dibutuhkan guna
mengatur dan memberdayakan jasa konstruksi nasional. Hal inilah yang
menyebabkan pemerintah berinisiatif menyusun konsep awal Undang - Undang
Jasa Konstruksi pada tahun 1988 dan selanjutnya bersama asosiasi jasa
konstruksi secara berkesinambungan meneruskan konsep awal Rancangan
Undang - Undang Jasa Kontruksi yang selanjutnya diubah dan disempurnakan
hingga akhirnya dapat dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan selesai pada
26
Pada UU No.18 / 1999 Tentang Jasa Kontruksi pasal 23 ayat 2 dijelaskan
bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan
tentang keamanan, keselamatan dan keselamatan kerja, perlindungan tenaga
kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kemudian pada pasal 24 ditambahkan
bahwa penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat
menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai
dengan masing - masing tahapan pekerjaan konstruksi. Sub penyedia jasa
tersebut juga harus memenuhi kewajiban - kewajibannya kepada penyedia jasa.
Pada UU No.13 / 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 35 dijelaskan
bahwa pemberi kerja wajib memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya
mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik
tenaga kerja. Diperjelas lagi pada bab X paragraf 5 tentang keselamatan dan
kesehatan kerja bahwa perlindungan kepada tenaga kerja harus dilaksanakan
sesuai peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku. Masih pada UU
yang sama pada pasal 65 dijelaskan bahwa penyerahan sebagian pekerjaan ke
perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang
dibuat secara tertulis yang mencakup perlindungan kerja.
Terlihat bahwa penyedia jasa wajib memenuhi ketentuan K3 dan
perlindungan terhadap tenaga kerjanya sehingga sub penyedia juga wajib
memenuhi ketentuan K3 dan perlindungan tenaga kerja sebagai tanggung
jawabnya terhadap penyedia jasa sesuai dengan Perundang - undangan yang
27
hubungan komplementer dengan peraturan Perundang - undangan terkait K3
agar bisa melakukan kegiatan produksinya.
Menimbang bahwa kenyataan menunjukkan banyak terjadi kecelakaan
akibat belum ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja
menyeluruh pada pekerjaan konstruksi bangunan dan dengan semakin
meningkatnya pembangunan dengan penggunaan teknologi modern dan juga
sebagai pelaksanaan Undang - Undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan
kerja maka diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja pada pekerjaan Konstruksi Bangunan. Peraturan Perundang -
Undangan yang dimaksud contohnya seperti :
1. Permenakertrans No.1 / MEN / 1980 Tentang K3 Pada Konstruksi
Bangunan.
2. SKB Menteri Pekerjaan Umun dan Menteri Tenaga Kerja No.174 / Men /
1986 No.104 / KPTS / 1986 Tentang K3 Pada Tempat Kegiatan
Konstruksi.
3. Permenaker No.1 / MEN / 1989 Tentang Kualifikasi dan Syarat - syarat
Operator Keran Angkat.
4. Permenakertrans No.2 / MEN / 1982 Tentang Kualifikasi Juru Las.
5. Kepmenaker No.51 / MEN / 1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor
Fisika di Tempat Kerja.
6. Permen PU No.9 / Per / 2008 Tentang SMK3 Kontruksi Bidang Pekerjaan
28
2.1.9 Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan
Peraturan perundang - undangan Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang
K3 Pada Konstruksi Bangunan (selanjutnya disebut peraturan) dibuat pada
masanya berdasarkan ideologi Pancasila. Sistem politik yang berkembang
pada masa pembuatan peraturan ini adalah demokrasi pancasila. Demokrasi
Pancasila mempunyai bentuk operasional pada tingkat politis dalam bentuk
pembangunan. Peraturan ini dibuat untuk mengakomodir kegiatan
pelaksanaan pembangunan yang sangat pesat sebagai bagian dari program
kerja Presiden ke - 2 RI yaitu Presiden Soeharto yang pada jaman itu disebut
dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA).
Peraturan ini merupakan bentuk kebijakan publik yang terkodifikasi
secara legal dan formal. Pembuatan peraturan ini melibatkan ahli hukum dan
ahli yang menguasai masalah berkaitan terutama teknik dan K3. Peraturan ini
bersifat messo yang dibuat di bawah departemen tenaga kerja dan transmigrasi
pada masanya dan dapat diimplementasikan.
Peraturan ini bisa dibilang merupakan induk penting pelaksanaan K3
pada kegiatan konstruksi di Indonesia karena memuat banyak hal yang harus
diperhatikan dalam kegiatan konstruksi yaitu tentang tempat kerja dan alat
kerja, perancah, tangga dan tangga rumah, alat angkat, kabel baja, tambang,
rantai, peralatan bantu, mesin, peralatan konstruksi bangunan, konstruksi di
bawah tanah, penggalian, pekerjaan memancang, pekerjaan beton,
pembongkaran, dan pekerjaan lainnya, serta penggunaan perlengkapan
29
Sudah 33 tahun berlalu namun peraturan ini masih dipakai sebagai
bagian dari persyaratan legal yang harus dipenuhi perusahaan konstruksi
dalam menjalankan kegiatannya dan belum direvisi hingga saat ini. Peraturan
ini juga lebih bersifat aplikatif di lapangan dibandingkan peraturan pemerintah
lainnya di bidang konstruksi.
Secara regulator pembuatan peraturan ini berada di bawah Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh
perusahaan konstruksi sebagai operator dalam menjalankan proyeknya
termasuk juga sub kontraktor yang ikut bekerja pada proyek tersebut dengan
tujuan agar seluruh pekerja dan pengunjung yang berada di lokasi proyek
dapat terhindar dari resiko terkena kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2.2 Implementasi Kebijakan
Menurut Grindle dalam Zaeni (2006) “Implementasi kebijakan pada
dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan
menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan
mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Konteks kebijakan ini meliputi
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor - aktor yang telibat.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2008). Untuk
30
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau
melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Kebijakan publik selalu mengandung setidak - tidaknya tiga komponen
dasar yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran
tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan
birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek.
Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana
diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau
bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja
kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa,
1994).
Menurut Irfan Islamy (1997) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan olehseorang pelaku
atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Untuk
melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi
kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh
arah yang telah diprogramkan itu benar - benar memuaskan. Akhirnya pada
tingakatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa
perubahan yang dapat diukur dalam masalah - masalah besar yang menjadi
sasaran program.
Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan - catatan elit saja jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Artinya, implementasi kebijakan
31
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah
harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan - badan administrasi
maupun agen - agen pemerintah di tingkat bawah (Winarno, 2005).
Namun sebaik apapun program tanpa ada implementasi mustahil sasaran
dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Implementasi berarti penerapan
pelaksanaan karena itu implementasi kebijakan berupa program merupakan
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam pelaksanakan
program, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berhubungan
dengan mekanisme penjabaran keputusan - keputusan politik ke dalam prosedur -
prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih menyangkut masalah
konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle
dalam Hadi, 2012).
Dalam konteks kebijakan publik, selain pemerintah selaku decision maker,
juga terdapat para stakeholder kebijakan. Pemangku kepentingan di sini adalah
individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan terhadap suatu
kebijakan. Stakeholder kebijakan ini bisa berupa aktor yang terlibat dalam
perumusan dan implementasi kebijakan, para penerima manfaat maupun para
korban yang dirugikan oleh suatu kebijakan publik (Suharto dalam Anshori,
2011).
Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif,
dengan konsekuensi lebih melakukan retrospeksi dari pada prospeksi dengan
tujuan ganda, yaitu memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang
-32
faktor yang dapat diubah supaya diperoleh pencapaian hasil secara lebih baik,
utnuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara
implementasi lain (Wibawa dalam Zaeny, 2006).
Implementasi sebagai sebuah output berorientasi pada penyelesaian
masalah langsung dengan mewaspadai kemungkinan terjadinya dampak berantai
dari pilihan pelaksanaan satu kebijakan (Henry dalam Wahyudi, 2011). Ini terjadi
karena pilihan terhadap satu kebijakan tidak didasari oleh satu rasionalitas
tunggal. Pilihan ini bersifat jamak yg meliputi :
1. Rasionalitas teknis
Berhubungan dengan efektivitas dalam memecahkan masalah.
2. Rasionalitas ekonomi
Berhubungan dengan efisiensi pencapaian tujuan yg ditetapkan.
3. Rasionalitas legal
Berhubungan dengan kesesuaian perundang – undangan dan pertimbangan
hukum.
4. Rasionalitas sosial
Berhubungan dengan kapasitas meningkatkan institusi sosial yg penting
seperti menumbuhkan masyarakat madani.
5. Rasionalitas substanstif
Berusaha untuk mensinergikan seluruh rasionalitas yg disebutkan
33
Ada 3 (tiga) level sehubungan dengan proses perubahan kelembagaan yaitu
level kebijakan, level organisasional, dan level operasional. Dalam suatu negara
demokrasi adanya level kebijakan ini selalu ditandai dengan adanya badan
legislatif dan badan hukum. Sementara adanya level organisasional ditandai
dengan adanya badan eksekutif. Pada level ini, biasanya keputusan - keputusan
mengenai tata kehidupan yang diharapkan senantiasa dimusyawarahkan dan
dirumuskan. Pada tahap implementasinya, aspirasi semacam ini akan tercapai
sejalan dengan perkembangan lembaga dan perkembangan peraturan dari
perundang-undangan itu sendiri (Bromley dalam Susilawaty, 2007).
Proses implementasi kebijaksanaan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan
dasar yang dapat dijabarkan dalam bentuk UU, perintah, keputusan, dsb agar
tujuan dan sasaran dapat tercapai sehinggan nantinya dampaknya dapat dipakai
untuk melakukan perbaikan kebijaksanaan itu sendiri ( Mazmanian dan Sabatier
dalam Indriarti, 2003).
Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994) mengemukakan bahwa
implementasi kebijakan mencakup tindakan - tindakan yang dilakukan oleh
individu atau kelompok, publik maupun privat yang diarahkan kepada
pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Ini meliputi
baik usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah
operasional, maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar
dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan - keputusan kebijakan.
Pendekatan pengembangan kesehatan oleh pembuat kebijakan biasanya
34
informasi yang relevan. Apabila pada implementasi tidak mencapai apa yang
diharapkan kesalahan seringkali bukan pada kebijakan itu melainkan pada faktor
politik atau manajemen implementasi yang tidak mendukung atau sedikitnya
sumber daya pendukung yang tersedia ( Juma dan Clarke, 1995 dalam Massie,
2009).
2. 2.1 Model Implementasi Van Horn dan Van Meter
Van Horn dan Van Meter dalam Hadi (2012) menyatakan bahwa proses
implementasi kebijakan terdiri dari 6 faktor :
1. Standar dan sasaran kebijakan
Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran yang jelas
dan terukur sehingga ketentuannya dapat terwujud. Ukuran standar dan
tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor - faktor yang
menentukan hasil kerja maka identifikasi indikator - indikator hasil kerja
merupakan hal yang penting dalam analisis karena indikator ini menilai
sejauh mana standar dan tujuan keseluruhan kebijakan.
2. Sumber daya
Terdiri dari SDM, material, dan metode yang memudahkan administrasi.
3. Komunikasi antar organisasi
Sebagai perwujudan dari program kebijakan perlu hubungan yang baik
antar instansi terkait yauitu dukungan komunikasi dan koordinasi.
35
dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan
bertindak dengan cara yang konsisten.
4. Karakteristik agen pelaksana
Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal
harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen - agen pelaksananya.
5. Disposisi
Merupakan respon terhadap kebijakan dan kondisi.
6. Lingkungan kondisi sosial ekonomi politik
Sejauh mana kelompok kepentingan memberi dukungan dan bagaimana
opini publik yang terbentuk di lingkungan.
2.2.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle
Merilee S Grindle dalam Irwan (2009) menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan berdasarkan 2 variabel besar yaitu isi (konten) dan lingkungan
(konteks).
1. Isi
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
( Interest Affected ).
2. Jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran ( Type of Benefit ).
3. Sejauh mana perubahan yag diinginkan dari kebijakan ( Content of
Change Envision ).
36
5. Implementor kompeten dan kapabel ( Program Implementer ).
6. Sumber daya pendukung program telah memadai ( Resources Committed ).
2. Lingkungan
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga / institusi.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
2.2.3 Model Implementasi Damien Mazmanian dan Paul Sabatier
Mazmanian dan Sabatier dalam Arief (2012) menjelaskan bahwa ada 3
variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan :
1. Karakteristik Masalah ( Tractibility of the Problems )
Mencakup kesulitan permasalahan yang dihadapi, kemajemukan kelompok
sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, cakupan
perubahan prilaku, kelompok sasaran yang dikehendaki dan diharapkan.
2. Karakteristik Kebijakan ( Ability of Statue to Structure Implementation )
Mencakup kejelasan isi kebijakan, dukungan teoritis, alokasi sumber daya
finansial, keterikatan dan dukungan berbagai institusi, kejelasan dan
37
3. Variabel Lingkungan ( Non Statutory Variables Affecting Implementation )
Mencakup sosial ekonomi kelompok sasaran, kemajuan teknologi,
dukungan public, sikap kelompok pemilih, komitmen, dan keterampilan
implementor.
2.2.4 Model Implementasi G. Shabbir Chema dan Dennis Rondinelli
G. Sahbbir Chema dan Dennis Rondinelli dalam Purwitasari (2011)
menjelaskan bahwa ada 4 variabel besar yang mempengaruhi implementasi
kebijakan :
1. Kondisi Lingkungan
- Sistem politik
- Struktur pembiayaan
- Karakteristik struktur politik lokal
- Kendala sumber daya
- Sosio kultural
- Derajat keterlibatan pada penerima program
- Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup
2. Hubungan antar organisasi
- Kejelasan dan konsistensi sasaran program
- Pembagian fungsi antar instansi yang pantas
- Standarisasi prosedur, perencanaan, anggaran, implementasi, dan evaluasi
38
- Efektivitas jejaring untuk mendukung program
3. Sumber daya
- Kontrol terhadap sumber daya
- Keseimbangan antara pembagian anggaran dan program kegiatan
- Ketepatan alokasi anggaran
- Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran
- Dukungan pemimpin pusat
- Dukungan pemimpin lokal
- Komitmen birokrasi
4. Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
- Keterampilan tekinis, manajerial, dan politis
- Kemampuan mengkoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan
keputusan
- Dukungan dan sumber daya politik instansi
- Sifat komunikasi internal
- Hubungan yang baik antar instansi dengan kelompok sasaran
- Kualitas pimpinan instansi yang bersangkutan
- Komitmen petugas terhadap program
39
2.2.5 Model Implementasi Kebijakan GC Edward
Seorang pakar kebijakan publik bernama GC Edward dalam teorinya
menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan berdasarkan 4 faktor yaitu
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi.
Gambar 2.5 Model Implementasi GC Edward
2.2.5.1Komunikasi
Setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi
efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan
sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat
menghindari distorsi atas kebijakan dan program. Hal ini penting karena
semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan
mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan
kebijakan seluruhnya.
Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan
40
dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian,
penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan
mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media
komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada
kelompok sasaran akan sangat berperan (Edward dalam Winarno, 2005).
Ada 3 indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu
transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2.2.5.1.1 Transmisi
Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan
implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam
penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian atau
miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang
harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan
terdistorsi di tengah jalan (Edward dalam Agustino, 2006).
Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan
dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik
pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi