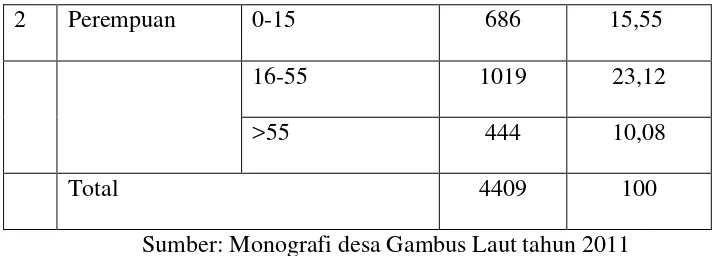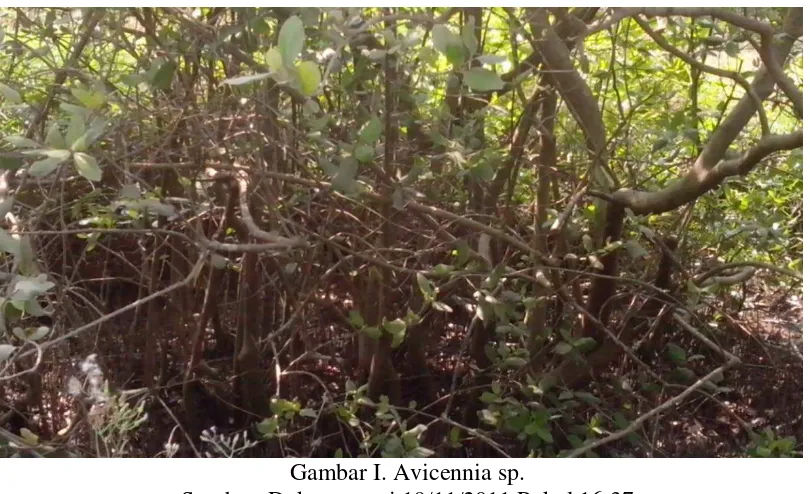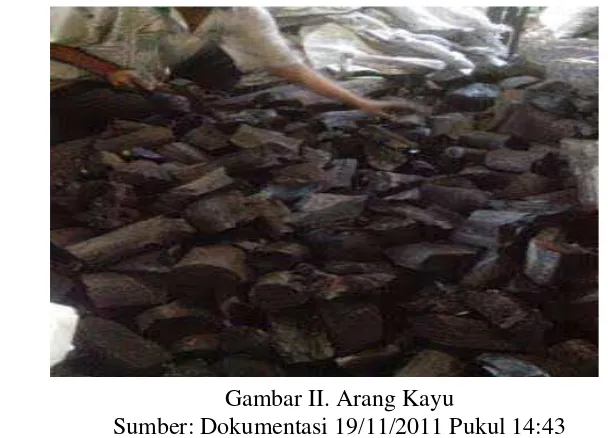Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan
Sumberdaya Kayu Mangrove
di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Dalam Bidang Antropologi Oleh:
Rabithah Adawiyah
070905037
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Halaman Persetujuan
Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan
Oleh:
Nama : Rabithah Adawiyah NIM : 070905037
Departemen : Antropologi
Judul : Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh,
Kab. Batu Bara.
Medan, 25 April 2014
Dosen Pembimbing Ketua Departemen
Dr. R. Hamdani Harahap, M.si
NIP. 19640227198903 1 003 NIP. 19621220198903 1 005 Dr. Fikarwin Zuska
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PERNYATAAN ORIGINALITAS
Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan
Sumber Daya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut,
Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara
SKRIPSI
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulias diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian terbukti lain atau tidak seperti yang saya nyatakan di sini, saya bersedia diproses secara hukum dan siap menanggalkan gelar kesarjanaan saya.
Medan, 25 April 2014
ABSTRAK
Rabithah Adawiyah 2014, judul skripsi: Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, 100 halaman, 6 tabel, 5 gambar, 18 daftar pustaka serta lampiran.
Skripsi ini mendeskripsikan : Strategi adaptasi pembuat arang dalam memanfaatkan sumberdaya kayu mangrove. Penelitian ini berlokasi di Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Kajian ini menjelaskan tentang adaptasi yang dilakukan masyarakat khususnya pembuat arang dalam menghadapi perubahan lingkungannya dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang pada awalnya pemanfaatan sumberdaya alam bersifat bebas dan terbuka namun berubah menjadi tertutup dan dilarang untuk pemanfaatannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakan dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan dilingkungannya untuk bertahan hidup. Perubahan lingkungan yang dimaksud dengan adanya pengeksploitasi hutan mangrove dari yang bersifat terbuka dan bebas menjadi tertutup dan diawasi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara serta observasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci sebanyak 3 orang. Wawancara tak berstruktur namun fokus digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan biasa. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pembuat arang, dari proses mencari kayu, membuat arang, pengepakan hingga pendistribusian. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui strategi adaptasi apa saja yang dilakukan para pembuat arang dalam menghadapi pengeksploitasian sumberdaya alam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pola-pola berfikir dalam masyarakat khususnya pembuat arang dalam membuat keputusan untuk bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan para pembuat arang dalam bertahan hidup sangat beragam. Setelah muncul larangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yaitu hutan mangrove maka mereka mencari cara lain untuk bertahan hidup. Tetap bertahan dalam memproduksi arang adalah pilihan dari sebagian pembuat arang. namun, itu saja tidak cukup bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup karena produksi arang yang dilakukan tidak lagi seperti dulu. Kemudian para pembuat arang mulai mencari kegiatan lain sebagai usaha untuk dapat bertahan hidup, sebagiam orang memilih berkebun cabai menjadi salah satu pilihan untuk bertahan hidup, ada juga yang menanam coklat sebagai penghasilan sampingan mereka untuk dapat bertahan hidup, dan ada juga yang mengambil membuat arang bakau dengan cara mengganti jenis kayu yang digunakan untuk produksi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillahirabbil’alamin.
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu
Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara” ini dengan baik.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah (Nazmi Athar) dan Mama (Fauziah) yang telah mencurahkan segala doa, perhatian, kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, serta dukungan yang tidak pernah terputus kepada penulis, serta kedua abang penulis yaitu Muhammad Yazid S.Hut dan Ismail Tarmidzi Amd terima kasih untuk dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang terucap dan tak terucap.
Antropologi dan kepada Bapak Agustrisno, MSP selaku Sekretaris Departemen Antropologi yang sering menunjukkan kepeduliannya terhadap mahasiswa dengan menanyakan mengenai apa dan bagaimana dengan skripsi yang ingin dibuat.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Savitri M.Hum selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan perhatian dalam menyelesaikan segala urusan akademis selama masa perkuliahan . Kepada seluruh staf pengajar Departemen Antopologi FISIP USU yang telah memberikan begitu banyak ilmu, wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis selama proses belajar ini berlangsung. Serta Kak Nurhayati selaku staf administrasi Departemen Antropologi dan Kak Sofiana yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakek dan Nenek yang telah bersedia memberikan tempat tinggal bagi penulis selama di lokasi penelitian, untuk yayuk terima kasih sudah menemani selama di lokasi penelitian, untuk Pak Mujani dan Ibu Jumikem terima kasih keripik pisang dan degannya. Bang Sutris dan Kak Wati terimakasih atas kebaikan dan informasi yang telah diberikan. Bang Budi dan Hasan terima kasih informasi dan jasa kendaraannya yang bersedia mengantar kemana-mana. Pak Sutimin dan Ibu Sani, Bang Sapri dan Kak Tuti, Hendra, dan Arif terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan.
Zulfan Amd, dan Oppa terima kasih telah mendukung dan menyemangati penulis, untuk Abangda Fauzi S.Pd terima kasih telah menjadi inspirasi buat penulis.
Serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2007, Indriani S.Sos, Septian Hadavi Lubis S.Sos, Rendy Arsami S.Sos, Khairil Fikri S.Sos, Hendra Alpino S.Sos, dan teman-teman seperjuangan yang terkhusus Tino, Tata, Jonathan, Perlaungan, Tya. Untuk teman-teman lainnya yang tidak penulis cantumkan, terima kasih atas hari-hari indah selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga penulis berikan untuk Bang Dani, Bang Andri, dan Bang Tasvin atas canda tawa selama kebersamaan di kampus dan di luar kampus, serta segala bantuan dari semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.
RIWAYAT HIDUP
Rabithah Adawiyah, akrab dipanggil Bitah, lahir pada tanggal 23 Juli 1989 di Tanjung Gading. Anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Nazmi Athar dan Fauziah.
Pendidikan Taman Kanak-kanak dimulai pada umur 5 tahun. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di Tanjung Gading pada SD Negeri 016397 Kec. Air Putih, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Putih, dan dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Mitra Inalum dan selesai tahun 2007 pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan spesifikasi ilmu Antropologi.
Pengalaman organisasi yang pernah penulis ikuti adalah kegiatan SIAGA I yang diselenggarakan oleh Musholla As-Siyasah FISIP USU. Penulis juga menjadi anggota muda HMI Komisariat FISIP USU. Penulis juga pernah mengikuti Dialog Budaya oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh sebagai peserta. Penulis juga pernah menjadi Koordinator Sie Dana dalam Kegiatan Inisiasi 2009.
KATA PENGANTAR
Skripsi ini merupakan hasil tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Judul skripsi ini adalah Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu Mangrove di
Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara.
Sebagian besar skripsi ini berisi deskripsi tentang kehidupan pembuat arang yang didasarkan pada pengamatan dan wawancara penulis mengenai adaptasi lingkungan yang ada di Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Secara sistematis, kajian tentang adaptasi masyarakat dalam menghadapi larangan dari pemerintah untuk memanfaatkan sumberdaya kayu mangrove yang notabene adalah bahan baku dalam pembuatan arang. Pandangan Masyarakat terhadap hutan mangrove dan manfaat hutan mangrove tersebut bagi masyarakat khususnya pembuat arang. Proses pembahasan mengenai bagaimana budaya korporasi itu dapat dipahami oleh karyawan atau staf dapat ditemukan dalam bab III dari skripsi ini.
Pada bab IV dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana para pembuat arang mengkonstruksi pikiran mereka untuk melakukan adaptasi di terhadap perubahan lingkungan. Kebijakan pemerintah yang mengeksploitasi hutan mangrove dan sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggarnya.
pemerintah terhadap pelarangan pemanfaatan hutan mangrove walaupun dalan hati mereka merasa hal itu tidak adil, sehingga mereka mencari cara untuk dapat bertahan hidup dengan melakukan strategi-strategi adaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi tata bahasa dan isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan koreksi, saran maupun kritik dari para pembaca yang bersifat membangun menyempurnakan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Amin Ya Rabbal’Alamin.
Medan, April 2014
DAFTAR ISI
Halaman Persetujuan ... i
PERNYATAAN ORIGINALITAS ... ii
ABSTRAK ... iii
UCAPAN TERIMA KASIH ... iv
RIWAYAT HIDUP ... vii
KATA PENGANTAR ... viii
DAFTAR ISI ... x
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xiv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Tinjauan Pustaka ... 9
1.3 Rumusan Masalah ... 16
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 16
1.5 Metode Penelitian ... 17
1.5.1 Tipe penelitian ... 17
1.5.2 Teknik pengumpulan data ... 17
1.6 Pengalaman Di Lapangan ... 24
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 28
2.1. Gambaran Lokasi ... 28
2.1.1. Lokasi dan Luas Desa Gambus Laut ... 28
2.1.2. Sejarah Desa ... 29
2.1.3. Letak Geografis dan Lingkungan Alam ... 30
2.1.4. Keadaan Penduduk ... 30
2.1.4. Keadaan Flora dan Fauna ... 32
2.2. Pola Pemukiman Penduduk dan Sarana Desa ... 33
2.2.1. Pola Pemukiman ... 33
2.2.2. Sarana Ekonomi Desa ... 34
2.2.3. Sarana Pendidikan ... 35
2.2.4. Sarana Ibadah ... 36
2.2.5. Sarana Kesehatan ... 37
2.2.6. Sarana Komunikasi ... 37
2.2.7. Sarana Rekreasi dan Hiburan ... 38
2.2.9. Hubungan Sosial dan Organisasi Sosial ... 39
2.3. Sejarah Pembuatan Arang ... 40
2.4 Kondisi Hutan Mangrove ... 42
2.5 Tumbuhan Mangrove ... 43
2.6 Arang ... 47
2.7 Tungku arang ... 48
2.8 Kriteria Kayu ... 48
2.9 Proses Pembuatan Arang... 49
2.9.1 Lokasi ... 49
2.9.2 Cara pengambilannya ... 50
2.9.3 Proses pengolahan kayu menjadi arang. ... 50
2.9.4 Sistem Pengolahan ... 52
2.9.5 Distributor ... 52
2.9.4 Limbah ... 53
BAB III ARANG ... 54
3.1 Pengertian arang dan manfaatnya. ... 54
Bahan Bakar Metalurgi ... 54
Memasak Bahan Bakar ... 55
Industri Bahan Bakar... 55
Otomotif Bahan Bakar ... 56
3.2 Macam-macam Arang ... 56
3.2.1 Arang Kayu ... 56
3.2.2 Arang Serbuk Gergaji ... 57
3.2.3 Arang Sekam Padi ... 57
3.2.4 Arang Tempurung Kelapa ... 58
3.2.5 Arang Serasah ... 59
3.2.6 Briket Arang ... 59
3.2.7 Arang Kulit Buah Mahoni ... 60
3.3 Sejarah Awal Pembuatan Arang Di Desa Gambus Laut ... 61
3.4 Profil Keluarga ... 63
3.4.1 Bapak Mujani ... 63
3.4.2 Bang Sutris ... 65
3.4.3 Bapak Sutimin ... 68
3.5 Pendapatan ... 69
3.5.2 Bang Sutris ... 71
3.5.3 Pak Sutimin ... 71
BAB IV STRATEGI EKONOMI ... 73
4.1 Pandangan Masyarakat tentang Hutan Mangrove ... 73
4.1.1 Hutan Mangrove sebagai tumbuhan pinggir pantai. ... 74
4.1.2 Hutan Mangrove sebagai penghambat ombak air pasang ... 74
4.1.3 Hutan Mangrove sebagai sumber daya alam yang menguntungkan ... 74
4.2 Pandangan Masyarakat tentang Pembuat Arang ... 74
4.3 Strategi Adaptasi ... 75
4.3.1 Penggantian Jenis Kayu ... 79
4.3.2 Berkebun Cabai ... 79
4.3.3 Usaha-usaha lainnya... 80
4.4 Kebijakan Pemerintah ... 80
4.2 Proses Penangkapan ... 81
4.3 Sanksi-sanksi ... 82
BAB V KESIMPULAN ... 84
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Halaman
1 Kondisi Hutan Mangrove di Desa Gambus Laut 8
2 Data Informan 20
3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 30
4 Jumlah Penduduk di Desa Gambus Laut 31
5 Mata Pencaharian Penduduk 34
DAFTAR GAMBAR
Gambar Judul Halaman
1 Avicennia sp 50
2 Arang Kayu 57
3 Arang Sekam Padi 58
4 5
Arang Tempurung Kelapa Arang Briket
ABSTRAK
Rabithah Adawiyah 2014, judul skripsi: Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, 100 halaman, 6 tabel, 5 gambar, 18 daftar pustaka serta lampiran.
Skripsi ini mendeskripsikan : Strategi adaptasi pembuat arang dalam memanfaatkan sumberdaya kayu mangrove. Penelitian ini berlokasi di Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Kajian ini menjelaskan tentang adaptasi yang dilakukan masyarakat khususnya pembuat arang dalam menghadapi perubahan lingkungannya dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang pada awalnya pemanfaatan sumberdaya alam bersifat bebas dan terbuka namun berubah menjadi tertutup dan dilarang untuk pemanfaatannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakan dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan dilingkungannya untuk bertahan hidup. Perubahan lingkungan yang dimaksud dengan adanya pengeksploitasi hutan mangrove dari yang bersifat terbuka dan bebas menjadi tertutup dan diawasi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara serta observasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci sebanyak 3 orang. Wawancara tak berstruktur namun fokus digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan biasa. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pembuat arang, dari proses mencari kayu, membuat arang, pengepakan hingga pendistribusian. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui strategi adaptasi apa saja yang dilakukan para pembuat arang dalam menghadapi pengeksploitasian sumberdaya alam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pola-pola berfikir dalam masyarakat khususnya pembuat arang dalam membuat keputusan untuk bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan para pembuat arang dalam bertahan hidup sangat beragam. Setelah muncul larangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yaitu hutan mangrove maka mereka mencari cara lain untuk bertahan hidup. Tetap bertahan dalam memproduksi arang adalah pilihan dari sebagian pembuat arang. namun, itu saja tidak cukup bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup karena produksi arang yang dilakukan tidak lagi seperti dulu. Kemudian para pembuat arang mulai mencari kegiatan lain sebagai usaha untuk dapat bertahan hidup, sebagiam orang memilih berkebun cabai menjadi salah satu pilihan untuk bertahan hidup, ada juga yang menanam coklat sebagai penghasilan sampingan mereka untuk dapat bertahan hidup, dan ada juga yang mengambil membuat arang bakau dengan cara mengganti jenis kayu yang digunakan untuk produksi.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangWilayah pesisir merupakan sumber daya potensial di Indonsia, yang
merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini
sangat besar didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km (Dahuri
R, Rais Y, Putra S, G, Sitepu, M.J, 2001). Garis pantai yang panjang menyimpan
potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan
non hayati. Potensi hayati adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup, antara lain hewan dan tumbuhan, misalnya perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang. Potensi non hayati adalah sumber daya alam yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi tetapi tidak hidup, misalnya tanah, udara, mineral dan bahan tambang serta pariwisata.
Sumber daya alam di wilayah pesisir terdapat berbagai macam ekosistem.
Ekosistem pesisir laut merupakan sumber daya alam yang produktif sebagai
penyedia energi bagi kehidupan komunitas di dalamnya. Sumber daya alam pesisir
laut umumnya berupa aneka makhluk hidup yang dapat digunakan untuk kebutuhan
rumah tangga, ataupun dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bertahan hidup.
Semua sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pesisir pantai
untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan suatu insting dari manusia sebagai makhluk
yang memiliki akal dan pikiran.
Ekosistem pesisir laut mempunyai potensi sebagai sumber bahan pangan,
menunjukkan bahwa ekosistem pesisir dan laut merupakan aset yang tak ternilai
harganya di masa yang akan datang. Ekosistem pesisir laut meliputi estuaria, hutan
mangrove, padang lamun, terumbu karang, ekosistem pantai dan ekosistem
pulau-pulau kecil. Komponen-komponen yang menyusun ekosistem pesisir laut tersebut
perlu dijaga dan dilestarikan karena menyimpan sumber keanekaragaman hayati dan
plasma nutfah. Salah satu komponen ekosistem pesisir dan laut adalah hutan
mangrove.
Di Indonesia, hutan mangrove atau hutan bakau kurang lebih seluas 4,2 juta
ha.1
MANFAAT HUTAN MANGROVE
Hutan mangrove adalah hutan yang terdiri dari pohon-pohon besar dan
tumbuhan perdu. Vegatasi mangrove merupakan tumbuhan halofit (hidup dengan
adanya pengaruh garam), yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Faktor
ekologis yang menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove adalah frekuensi air
laut tergenang secara tetap, endapan lumpur atau pasir, dan percampuran antara air
laut dengan air sungai di muara. Dengan kondisi yang spesifik ini, hutan mangrove
berperan penting dalam stabilitas ekosistem pantai pesisir.
Secara garis besar manfaat hutan mangrove dapat dibagi dalam dua bagian :
1. Fungsi ekonomis, yang terdiri atas :
a. Hasil berupa kayu (kayu konstruksi, kayu bakar, arang, serpihan kayu untuk
bubur kayu, tiang/pancang)
b. Hasil bukan kayu
• Hasil hutan ikutan (non kayu)
1
• Lahan (Ecotourisme dan lahan budidaya)
2. Fungsi ekologi, yang terdiri atas berbagai fungsi perlindungan lingkungan
ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, diantaranya:
a. Sebagai proteksi dan abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang.
b. Pengendalian instrusi air laut
c. Habitat berbagai jenis fauna
d. Sebagai tempat mencari, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan
udang
e. Pembangunan lahan melalui proses sedimentasi
f. Pengontrol penyakit malaria
g. Memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air)
Pemanfaatan hutan mangrove yang tidak seimbang mengakibatkan luasannya
semakin menurun. Kondisi ini tentunya mengancam kelangsungan hidup manusia.
Hutan mangrove merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial dan mendukung
bagi kelangsungan hidup manusia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan
(ekologi).
Rusaknya hutan mangrove diakibatkan oleh penebangan dalam skala besar.
Tingginya interaksi manusia yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove
menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan tingginya kerusakan kawasan
hutan mangrove. Intensitas interaksi manusia dengan kawasan hutan mangrove yang
begitu tinggi pada dasarnya juga dipengaruhi oleh fakor lain dan salah satu fakor
pendorongnya adalah tuntutan ekonomi.
Masyarakat di sekitar pesisir pantai memanfaatkan hutan mangrove yang
hidup. Hutan mangrove yang kayunya banyak memiliki kegunaan untuk masyarakat
menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memanfaatkannya demi melangsungkan
hidup. Seperti halnya di Desa Gambus Laut yang terletak di Kabupaten Batubara,
masyarakat menggunakan kayu bakau untuk dijadikan arang yang kemudian dapat
mereka jual dan bernilai ekonomi untuk kelangsungan hidup mereka. Namun,
pengolahan kayu bakau tersebut tidaklah diikuti dengan pelestarian kembali oleh
masyarakat. Karena menurut pengetahuan masyarakat sekitar khususnya pembuat
arang, kayu bakau yang telah dipotong akarnya akan kembali memunculkan tunas
baru, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat tidak melestarikan kembali
hutan mangrove.
Dari wawancara dengan Bapak Mujani ( 64 Tahun) yang mengatakan bahwa
dahulu daerah Desa Gambus Laut ini dikelilingi oleh pohon bakau. Sekitar 30 Tahun
yang lalu tanah di Desa Gambus Laut ini masih didominasi oleh rawa-rawa yang
ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau, sehingga mau seberapa banyak pun kayu
tersebut diambil tidak pernah habis. Oleh karena itu mereka merasa tidak perlu
melakukan pelestarian terhadap pohon bakau tersebut. Dahulu ada tiga kepala
keluarga yang bekerja sebagai pembuat arang. Mereka masing-masing memiliki satu
tungku yang mempunyai kapasitas 300 kg kayu bakau. Pada awalnya pekerjaan
membuat arang ini merupakan pekerjaan pokok mereka. Akan tetapi setelah
mempunyai anak, mereka mengalami pertambahan kebutuhan ekonomi, selain
membeli pangan untuk kehidupan sehari-hari mereka juga harus membiayai sekolah
anak mereka. Sehingga Pak Mujani mulai berkebun, menanam pisang dan coklat.
Jenis hutan mangrove yang yang terdapat di pesisir pantai timur adalah jenis
Rhizophora sp2
Kayu dari hutan-hutan mangrove dipanen terutama 90% untuk produksi
arang, misalnya di Sumatera (Boon 1936)
yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat arang, dan jenis
Avicennia sp. Arang pada masa dahulu sebuah komoditi yang sangat terkenal karena
fungsinya sebagai salah satu sumber energi yang cukup bagus dan ramah lingkungan
namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi arang lambat laun
ditinggalkan dan beralih ke minyak bumi, batubara (bahan bakar fosil) dan listrik
karena dianggap lebih praktis. Arang bakau memiliki kualitas yang baik setelah
arang kayu oak dari Jepang dan arang onshyu dari Cina. Pengusahaan arang
mangrove di Indonesia sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu.
3
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, lahan kosong yang terdapat di Desa
Gambus Laut ini mulai dijual oleh para pemiliknya. Dikarenakan para pengusaha
perkebunan yang ingin membuka lahan di daerah ini. Mulyono mengatakan bahwa
pihak perkebunan berani membayar dengan nilai yang tinggi atas tanah mereka, . Salah seorang masyarakat di Desa
Gambus Laut Mulyono (25 Tahun) mengatakan bahwa beberapa orang
masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pembuat arang, dengan menggunakan
kayu bakau yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Para pembuat arang yang terdapat
di Desa Gambus Laut bukanlah para produsen arang yang utama, atau yang
produksinya terus menerus dilakukan. Usaha yang mereka punya masih dalam
bentuk tradisional yang hanya dapat menghasilkan sedikit arang.
2
Jenis Rhizophoraceae merupakan kayu bakar berkualitas baik karena menghasilkan panas yang tinggi dan awet. Sumber: Departemen kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II. 2010.
3
sehingga mereka banyak yang menjual tanahnya kepada pihak perkebunan. Lahan
kosong yang tadinya rawa yang penuh dengan tumbuhan bakau sekarang sudah
disulap oleh pihak perkebunan menjadi ladang sawit. Sehingga para pembuat arang
mulai kesulitan untuk mencari bahan baku membuat arang. Para pembuat arang
kemudian pergi ke pesisir pantai karena tumbuhan bakau di pesisir pantai masih
banyak. Bapak Mujani mengatakan dahulu dia tidak mengambil bakau di pesisir,
tetapi semenjak lahan kosong tempat dia biasa mengambil kayu bakau mulai
ditimbun dan ditanami bibit sawit maka mereka mulai pergi ke pesisir untuk
mengambil kayu bakau.
Pada awal menjadi pembuat arang Bapak Mujani hanya memiliki satu
tungku4
Pada tahun 1990 sudah dikeluarkan keppres No. 32 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung, yang terdapat pada pasal 26 yang berbunyi:
, setelah anak-anaknya dewasa Bapak Mujani mulai membangun satu tungku
lagi untuk anaknya. Begitu juga dengan keluarga yang lain, sehingga ada sekitar
enam tungku di Desa Gambus Laut. dan bahan baku yang diambil adalah dari pesisir
pantai. Bapak Mujani dan pembuat arang lainnya tidak pernah mempelajari
bagaimana penanaman kembali pohon bakau. Disamping minimnya pendidikan
mereka, pemerintah juga tidak pernah memberikan pengarahan terhadap mereka para
pembuat arang yang merupakan pengguna bakau. Sehingga lama kelamaan hutan
bakau di pesisir Desa Gambus Laut mulai menipis dan rusak.
“Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau dan tempat perkembangbiakannya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.”
4
Pada pasal berikutnya di jelaskan batas kawasan hutan bakau, pada pasal 27
yang berbunyi:
“Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.”
Pada tahun disahkannya Keputusan Presiden ini kawasan pesisir khususnya
hutan bakau di desa Gambus Laut dalam keadaan baik. Para pembuat arang
menggunakan kayu bakau untuk diproses lebih lanjut menjadi arang dan hal ini
merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat tersebut. Sejak lama mereka
sudah bergelut dalam bidang pembuatan arang ini hingga sekarang. Gudang arang
yang terdapat di daerah Gambus Laut ini 8 tungku dan saat ini yang aktif sekitar 6
tungku.
Akan tetapi, pemanfaatan kayu bakau yang terus-menerus dilakukan sebagian
masyarakat menyebabkan wilayah hutan bakau di desa Gambus Laut ini menjadi
rusak, sehingga wilayah ini menjadi kawasa konservasi. Data tentang kondisi hutan
menyatakan bahwa keadaan hutan mangrove di desa Gambus Laut ternyata lebih
banyak luas hutan yang rusak.
Kondisi Hutan Mangrove di desa Gambus Laut
No Kondisi Luas (ha)
1. Luas hutan yang kondisinya baik 180
2. Luas hutan yang kondisinya rusak 281
3, Luas hutan produksi yang sudah siap diambil
hasilnya
-
Pada tahun 2007 muncul Undang-undang Republik Indonesia No. 27 tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 35 pada Bab
Larangan yang menjelaskan bahwa:
“Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menebang mangrove dikawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.”5
Dari wawancara dengan salah seorang pegawai di Departemen Kehutanan
Sumatera Utara, Bapak Ernest (31 Tahun) mengatakan bahwa wilayah pesisir di desa
Gambus Laut ini termasuk dalam kawasan konservasi. Adanya pemetaan terhadap
wilayah pesisir sebagai wilayah konservasi membuat masyarakat tidak dapat lagi
menggunakan kayu bakau. Tuntutan untuk bertahan hidup membuat manusia akan
mencari cara untuk dapat hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
Dengan adanya larangan pengambilan bakau oleh pemerintah, dan juga keberadaan
perusahaan di areal lokasi yang dulunya menjadi situs pengambilan bakau oleh para
pembuat arang, menyebabkan munculnya permasalahan kehidupan (ekonomi) bagi
para pembuat arang ini.
Akses untuk pengambilan kayu bakau mulai ditutup. Pembuat arang menjadi
kesulitan untuk mendapatkan kayu bakau. Pembuat arang di Desa Gambus Laut di
satu sisi harus terus melanjutkan hidup dengan membuat arang, tapi di sisi lain
adanya tekanan dari pemerintah kepada mereka, yaitu penangkapan yang dilakukan
polisi hutan ketika pembuat arang mengambil arang di pesisir pantai. Pembuat arang
yang terlihat mengambil arang di pesisir pantai akan ditangkap dan diinapkan
dikantor dinas kehutanan selama dua sampai tiga hari.
5
1.2 Tinjauan Pustaka
Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan rapat serta memiliki jenis
pohon yang selalu berdaun. Keadaan lingkungan di mana hutan mangrove tumbuh,
mempunyai faktor-faktor yang ekstrim seperti salinitas air tanah dan tanahnya
tergenang air terus menerus. Meskipun mangrove toleran terhadap tanah bergaram
(halophytes), namun mangrove lebih bersifat facultative daripada bersifat obligative
karena dapat tumbuh dengan baik di air tawar.
Flora mangrove terdiri atas pohon, epipit, liana, alga, bakteri dan fungi.
Menurut Hutching dan Saenger (1987) di Indonesia tercatat ada 202 jenis tumbuhan
mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis liana, 44 janis herba
tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku6
Hasil hutan mangrove non kayu ini sampai dengan sekarang belum banyak
dikembangkan di Indonesia. Padahal apabila dikaji dengan baik, potensi sumberdaya
hutan mangrove non kayu di Indonesia sangat besar dan dapat medukung
pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan. Salah satunya adalah sumberdaya
mangrove sebagai salah satu makanan alternatif. Mangrove memiliki kegunaan yang
baik sebagai bahan bangunan, dan kayu bakar. Sebagai kayu bakar, secara tradisional . Dari sekian banyak jenis mangrove di
Indonesia, jenis mangrove yang banyak ditemukan antara lain adalah jenis api-api
(Avicennia sp), bakau (Rhizophora sp), tancang (Bruguiera sp), dan bogem atau
pedada (Sonneratia sp), merupakan tumbuhan mangrove utama yang banyak
dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang
menangkap, menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya.
6
masyarakat biasanya memakai jenis Xylocarpus sp (Nirih atau Nyirih), dan terutama
sebagai bahan pembuat arang biasanya dipakai Rhizophora sp. Oleh karena itu,
keberadaan dan kelestarian hutan mangrove sangatlah penting untuk kesejahteraan
manusia.
Manusia adalah makhluk budaya yang akan menggunakan kebudayaannya
dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan
adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makluk soaial,
yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara
selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang
dihadapi. Dalam pengertian ini kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau
pegangan yang kegunaan operasional dalam hal manusia mengadaptasi diri
menghadapi lingkungan tertentu (fisik/alam, sosial, dan kebudayaan) untuk mereka
dapat tetap melangsungkan kehidupannya (Harahap: 1996).
Spradley mendefenisikan kebudayaan sebagai sebuah sistem pengetahuan
yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk
menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus menyusun strategi
perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka (Spadley;1997).
Spradley (1997) menjelaskan lebih lanjut bahwa kebudayaan berada dalam
pikiran (mind) manusia yang didapatkan dengan proses belajar dan menggunakan
budaya tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Proses belajar tersebut menghasilkan
pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari pengalaman-pengalaman individu atau
masyarakat yang pada akhirnya fenomena tersebut terorganisasi di dalam pikiran
mendeskripsikan pola yang ada dalam pikiran manusia itu adalah khas, yaitu melalui
metode folk taxonomi7
Apapun yang dihasilkan oleh setiap manusia baik yang bersifat nyata seperti
artefak maupun yang bersifat abstrak seperti pengetahuan yang ada dalam pikiran
seseorang sudah tergolong kepada hakekat karya manusia yang merupakan bagian
dari kebudayaan. Erat kaitannya dengan hal tersebut adaptasi dalam cara hidup juga
merupakan bagian dari kebudayaan serta pengalaman yang di dapat dalam setiap
rentetan kehidupan yang dijalani manusia. .
Dalam rangka adaptasi manusia terhadap lingkungannya, Cohen (1968)
mengatakan bahwa adaptasi adalah salah satu proses yang dilakukan oleh
sekelompok masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam lingkungan
tempat hidupnya dan mendayagunakan untuk tujuan-tujuan produktif juga
mempertahankan kelangsungan hidupnya (Harahap: 1996).
Penelitian adaptasi masyarakat dengan lingkungan telah banyak diteliti oleh
para ahli, Julian Steward yang menjelaskan hubungan timbal balik yang terjadi
antara kebudayaan dan lingkungan mengenai penelaahan sudut adaptasi. Steward
meneliti tentang adaptasi masyarakat primitive yang dilakukan pada masyarakat
berburu dan meramu Shoshone di Great Basin, Amerika Utara. Ia menjelaskan
aspek-aspek tertentu dari kebudayaan Shoshone menurut ketersediaan sumberdaya
dalam lingkungan hidup semi-gurun yang tandus. Ia menjelaskan bahwa kasus
kepadatan penduduk, organisasi berbentuk kumpulan kecil beberapa keluarga yang
7
sangat tersebar dan pola menetap berubah-ubah pada teritori terbatas serta kurang
kekuasaan pemimpin yang permanen semuanya tercermin pada ketidakmampuan
teknologi Shoshone untuk mengekstraksi bahan makanan dalam jumlah banyak dan
stabil dari sumber daya yang tersedia secara sporadic dan tersebar pada lingkungan
yang gersang. Steward memandang dinamika organisasi sosial budaya sebagai hasil
dari proses adaptasi manusia dan lingkungannya (Harahap, 1997: 8). Manusia yang
sedang dalam keadaan mempertahankan hidup akan dengan segera melakukan
aktifitas yang dapat dilakukannya untuk bertahanhidup, aktifitas tersebut tidak
dilakukannya sendiri, melainkan dengan lingkungannya dan membentuk kelompok
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Selanjutnya penelitian oleh Cliffort Geertz tentang aktifitas adaptasi petani
Indonesia Luar. Di Indonesia Luar (Sumatera) berkembang sistem ladang atau
pertanian berpindah. Pertanian ladang atau Swidden8
8
Sistem pertanian ladang adalah suatu sistem dimana petani menebas sebidang lahan di hutan, membiarkan vegetasi mongering dan kemudian dibakar sebelum ditanami dengan tanaman palawija.
sebagaimana disebut
antropolog, merupakan ladang yang setelah sekali panen, umumnya dua kali,
kesuburan tanah berkurang maka tersebut lahan akan ditinggalkan, kemudian
mencari bidang lahan baru di hutan yang kemudian akan dibersihkan. Lahan yang
ditinggalkan secara perlahan akan kembali subur dalam 10-15 tahun kemudian, maka
lahan itu bisa dibersihkan atau diusahakan kembali. Peladangan berpindah
merupakan satu adaptasi pertanian yang efektif pada lapisan tanah yang kurang subur
di daerah hutan basah tropis, dimana sebagian besar nutrein yang ada tersimpan pada
vegetasi (Harahap, 1997: 9).
Konsep strategi adaptasi lain yaitu yang dikemukakan oleh A. Terry Rambo
(1983) dalam ilmu ekologi manusia. Menurut Rambo, dalam kasus masyarakat
manusia, adaptasi yang diterapkan adalah hasil seleksi alam pada tingkat kebudayaan
atau sistem sosial yang berasal dari keputusan-keputusan dari individu atau
kelompok. Keputusan yang dihasilkan adalah mengenai strategi berinteraksi yang
menguntungkan dengan lingkungannya. Individu-individu atau kelompok membuat
pilihan-pilihan mengenai eksploitasi sumberdaya yang tersedia pada saat ia
memenuhi tuntutan hidup atau mengatasi ancaman-ancaman lingkungan. Dalam
studi antropologi, adaptasi sering dilihat sebagai cara mempertahankan kondisi
keberadaan kehidupan dalam menghadapi perubahan. Individu atau kelompok akan
membuat pilihan, jika menguntungkan maka pilihan tersebut akan dipakai. (Nita
Savitri, 1998, hal:15)
Sama seperti penelitian di atas, penelitian yang diajukan peneliti juga
mengenai adaptasi manusia terhadap lingkungannya (lingkungan hidup9
Adaptasi budaya tidak bisa dilihat sebagai suatu yang statis yang dicapai pada
saat permulaan sejarah suatu kebudayaan dan kemudian dipertahankan tidak berubah
sampai kapanpun. Sebaliknya, hubungan antara manusia dan alam merupakan satu ), lebih
spesifik lagi yaitu strategi adaptasi yang dilakukan oleh para pembuat arang. Sumber
daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal manusia yang biasa
dapat diakses secara bebas kini tidak dapat lagi dimanfaatkan atau digunakan untuk
kepentingan hidup manusia, sehingga manusia akan mencari cara untuk dapat
memanfaatkan sumberdaya alam yang ada demi mensejahterakan hidupnya.
9
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
hubungan yang dinamis dimana keduanya terus-menerus beradaptasi dan beradaptasi
ulang sebagai bentuk perubahan menanggapi pengaruh dari yang lain.10
Heddy Shri Ahimsa Putra dalam bukunya Ekonomi Moral, Rasional dan
Politik dalam Industri Kecil di Jawa mengatakan:
“Adaptasi bukan hanya sekedar persoalan bagaimana mendapatkan
makanan dari suatu kawasan tertentu, tetapi juga mencakup persoalan
transformasi sumber-sumber daya lokal dengan mengikuti model dan
patokan-patokan, standard konsumsi manusia yang umum, serta biaya
dan harga atau mode-mode produksi di tingkat nasional.”
Pengertian adaptasi ini menjadi sangat luas bahkan dapat dikatakan
mencakup hampir seluruh pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Proses adaptasi manusia merupakan suatu bentuk kebudayaan, sehingga dapat
disimpulkan bahwa seluruh perilaku manusia merupakan kebudayaan. Setiap
perilaku kemudian dapat kita pandang sebagai suatu upaya untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai atau masalah yang
dihadapi dapat diatasi.
John W. Bennett (1969) membedakan antara adaptive behavior (perilaku
adaptif) dengan adaptive strategies (siasat-siasat adaptif) dan adaptive processes
(proses-proses adaptif). Bagi Bennett hanya perilaku yang berkenaan dengan
pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah saja yang dapat dikatakan adaptif, dan
lebih khususnya lagi adalah perilaku untuk mengatasi kendala-kendala yang sulit,
yang meliputi keterbatasan atau kelangkaan sumber daya guna mencapai
tujuan-tujuan atau mewujudkan harapan-harapan yang diinginkan. Siasat-siasat adaptif
berada pada tingkat yang disadari oleh yang menjalankannya, pelaku dapat
10
merumuskan atau menyatakan siasat-siasat tersebut, berbeda dengan proses adaptif
yang merupakan pernyataan formulasi dari pengamat atau peneliti. (Heddy Shri
Ahimsa-Putra, 2003: 10). Pencapaian tujuan dan harapan yang dimaksudkan adalah
tujuan dan harapan untuk dapat melangsungkan kehidupan dalam upaya bertahan
hidup dengan lingkungan sekitar.
Heddy Shri Ahimsa mengganti konsep adaptif menjadi adaptasi, sebab
konsep adaptasi tidak menuntut pembuktian apakah suatu perilaku adaptif atau tidak.
Setiap perilaku kemudian dapat kita pandang sebagai suatu upaya untuk
menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan agar tujuan yang diinginkan dapat
tercapai atau masalah yang dihadapi dapat diatasi.
Selanjutnya Bennett (1969) mengatakan, perilaku adaptasi mencakup
pengambilan berbagai keputusan, atau lebih khusus lagi pemilihan atas sejumlah
alternative. Perilaku adaptasi adalah perilaku yang ditujukan untuk mengatasi
masalah yang dihadapi atau untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Strategi
adaptasi dapat didefenisikan sebagai pola-pola yaitu perilaku atau tindakan berbagai
usaha yang direncanakan oleh manusia untuk dapat memenuhi syarat minimal yang
dibutuhkannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi
(Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2003: 12).
Sebagaimana telah dikatakan oleh Bennett di atas, maka secara sederhana
strategi adaptasi dapat di defenisikan sebagai pola-pola berbagai usaha yang
direncanakan oleh manusia untuk dapat memenuhi syarat minimal yang
dibutuhkannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di
tempat tersebut. Seperti halnya para pembuat arang yang terdapat di Desa Gambus
berbagai usaha untuk memanfaatkan sumberdaya alam demi mencapai tujuannya.
Tujuan untuk dapat bertahan hidup dalam masalah-masalah yang ada disekitar
mereka dan bagaimana cara mereka menyiasati ataupun beradaptasi dalam
menghadapi masalah-masalah yang ada di lingkungan hidup mereka.
1.3 Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana
masyarakat, khususnya para pembuat arang, menghadapi keterbatasan dalam
mengakses sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan mereka, terutama
sumber daya bakau yang digunakan sebagai bahan pembuatan arang.
Untuk lebih memudahkan dalam memahami permasalahan yang menjadi
fokus dalam penelitian ini, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam beberapa
pertanyaan penelitian, sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove terkait
dengan kegiatan pembuatan arang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat, khususnya para pembuat arang, terkait dengan
adanya larangan dari pemerintah dalam mengakses sumber daya kayu bakau?
3. Lantas, bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh para pembuat arang
tersebut?
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan
masyarakat dalam usaha untuk mempertahankan hidupnya, dan untuk mengetahui
bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat disekitar
Manfaat penelitian ini adalah secara praktis, yaitu yang nantinya hasil
penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan memberi
kontribusi yang berharga dalam memperluas wawasan pembaca, mahasiswa, para
praktisi (LSM) atau pembuat kebijakan bahwa masyarakat pesisir itu menggunakan
sumberdaya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya.
Manfaat secara akademis, untuk menambah kepustakaan pada bidang
Antropologi, yaitu pada bidang masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Tipe penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berusaha
mengumpulkan data kualitatif sebanyak mungkin yang merupakan data utama untuk
menggambarkan permasalahan yang akan dibahas nantinya. Untuk mencapai sasaran
yang dituju yaitu mengungkap pengetahuan para pembuat arang desa Gambus Laut,
Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara tentang lingkungan hidup dan siasat para pembuat
arang untuk bertahan hidup maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut.
1.5.2 Teknik pengumpulan data
a. Lapangan
o Informan
Wawancara dilakukan dengan informan. Informan yang lazimnya dikenal ada
tiga jenis, yaitu: informan pangkal, informan pokok atau informan kunci, dan
informan biasa. Informan pangkal, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan luas
penjelasan tersebut maka peneliti telah menentukan informan pangkal meliputi
kepala desa, aparat pemerintah dinas kehutanan, dan dinas kelautan dan perairan.
- Bapak Kepala Desa di Desa Gambus Laut.
- Bapak Ernest, S.Hut (31 Tahun) merupakan Staff di Departement Kehutanan
Sumatera Utara.
- Bapak Aditya (25 Tahun) merupakan Pegawai di Dinas Kelautan dan
Perairan Batu Bara.
Data yang telah diperoleh dari informan pangkal meliputi kondisi desa, dan keadaan
lingkungan di sekitar pesisir Desa Gambus Laut.
Informan pokok atau informan kunci, yaitu orang yang mempunyai keahlian
mengenai suatu masalah yang ada dalam masyarakat tersebut dan yang menjadi
perhatian penelitian, seperti para pembuat arang, pekerja di gudang arang dan para
penjual kayu.
- Bapak Mujani (64 Tahun) merupakan Pembuat arang.
- Bu Sani (50 Tahun) merupakan pembuat arang.
- Bang Sutris (31 Tahun) merupakan pembuat arang.
- Bang Sapri (30 Tahun) merupakan pembuat arang.
- Kak Tuti
- Kak Wati
- Hasan (23 Tahun) merupakan pembuat arang.
Data yang telah diperoleh dari informan pokok tentang strategi adaptasi yang
Informan biasa, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai sesuatu
masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi bukan ahlinya, seperti
masyarakat yang ada di sekitar gudang arang.
- Mulyono (25 Tahun) merupakan pekerja pabrik, dahulunya pernah bekerja
bersama bapak Sutimin.
- Nenek Ngatiem merupakan warga kampung Desa Gambus Laut.
- Kakek merupakan warga kampung Desa Gambus Laut.
- Hendra (23) penjual kayu
- Arif ( 20 Tahun) anak pembuat arang
Jenis Informan Individu Informasi yang di dapat
Pangkal Kepala Desa
Departement
Kehutanan
Dinas Kelautan dan
Peraian
- Sejarah desa, data desa, batas-batas
desa, dan data kependudukan.
- Undang-undang tentang Pengelolahan
Kawasan Hutan Lindung.
- Informasi tentang kondisi pesisir di Desa
Gambus Laut
Kunci Pak Mujani
Bang Sutris
Ibu Sani/Pak
Sutimin
- Sejarah pembuatan arang, cara membuat
arang, strategi adaptasi.
- Proses pembuatan arang, cara
mendapatkan kayu, strategi adaptasi.
- Cara mendapatkan kayu, proses
pembuatan arang,
Nenek Ngatiem dan
Kakek
Hendra
Arif
arang, lokasi pengambilan kayu.
- Tentang aktifitas masyarakat sekitar.
- Lokasi pengambilan kayu, hambatan
dalam mengambil kayu, dan tentang
para penjaga pantai.
- Lokasi pengambilan kayu, dan tentang
penjaga pesisir pantai.
Data yang diperoleh dari informan biasa adalah tentang siapa-siapa saja yang bisa
ditemui peneliti untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian.
o Wawancara
Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan untuk memperoleh data
mengenai pandangan-pandangan Pembuat Arang di Desa Gambus Laut, Kec. Lima
Puluh, Kab. Batu Bara tentang hutan mangrove dan larangan dari pemerintah dalam
mengakses sumber daya kayu bakau serta siasat mereka dalam bertahan hidup.
Saat itu saya datang ke Desa Gambus Laut ini untuk melihat keadaan desa.
Observasi awal saya sebelum saya tinggal di Desa Gambus Laut. Kemudian
Mulyono membawa saya ke lokasi dapur arang. Wawancara pertama kali saya
lakukan dengan Ibu Sani, dia adalah informan pertama saya. Wawancara dengan Ibu
Sani sewaktu saya pertama kali datang ke Desa Gambus Laut. Saya melihat Bu Sani
sedang memilah-milah kayu yang akan dibuat menjadi arang. Dia bersama suami dan
dua orang anak laki-lakinya. Suami Bu Sani bernama Pak Sutimin. Ibu Sani agak
dia berfikir saya adalah wartawan yang mau mengambil berita tentang pembuatan
arang dan masalah larangan pengambilan kayu bakau lalu saya memperkenalkan diri
dan menjelaskan bahwa saya bukan wartawan, barulah pembicaraan dimulai dengan
santai.
Pertanyaan dimulai dari asalmuasal pembuatan arang. Dari mana mereka
mempelajari pembuatan arang ini. Lalu pertanyaan berlanjut kepada cara
pengambilan kayu. Bu Sani mengatakan bahwa dia dan suaminya tidak mengambil
kayu sendiri. Mereka membeli kayu-kayu itu dari penjual kayu langganan mereka.
Satu sampan berisi kayu dihargai sebesar sepuluh ribu rupiah. Bu Sani mengatakan
kadang dia membeli sampai dua sampan berisi kayu. Dan terkadang hanya satu
sampan saja. Tungku yang dimilikinya berkapasitas 200 kg. Proses Pembelian kayu
tidak menggunakan sistem timbang berat, tapi hanya dengan sistem satu sampan,
ntah berapa kilo isi kayu di sampan itu harganya tetap sepuluh ribu rupiah. Jika
persediaan kayunya masih ada Bu Sani hanya membeli satu sampan saja. Namun,
jika persediaan kayunya tinggal sedikit maka dia akan segera membeli kayu kembali.
Tidak seperti suaminya Bu Sani adalah orang yang ramah. Itulah wawancara singkat
saya dengan Bu Sani, karena hari sudah sore saya memutuskan untuk melanjutkan
wawancara dilain waktu. Setelah mengambil beberapa foto saya pun pamit pulang.
Kedatangan saya yang kedua kalinya di Desa Gambus Laut, saya kembali
medatangi Bu Sani. Hanya wawancara singkat tentang proses pembuatan tungku
arang lalu Bu Sani menyuruh saya untuk mendatangi Pak Mujani yang merupakan
pembuat arang juga. Rumah Pak Mujani tidak begitu jauh dari rumah Bu Sani.
Kemudian saya bertemu dengan keluarga Pak Mujani. Sama seperti Bu Sani.
menganggap saya adalah orang asing. Awal perjumpaan saya saat itu adalah dengan
Kak Tuti, Kak Tuti adalah Istri Bang Sapri yang merupakan anak dari Pak Mujani.
Saat itu Pak Mujani sedang tidak ada dirumah, jadi saya memutuskan untuk
mewawancarai anaknya saja. Bang Sapri merupakan pembuat arang, saat itu Kak
Tuti sedang menjaga tungku arangnya yang sedang dalam proses pemasakan.
Kemudian saya bertanya tentang proses pemasakan arang. Bang Sapri mengatakan
proses pemasakan arang tidak boleh ditinggal, karena selama proses pemasakan api
tidak boleh mati, jika api mati maka kayu tidak akan menjadi arang malahan kayu
akan menjadi abu. Oleh karena itu, Bang Sapri dan Kak Tuti selalu bergantian untuk
menjaga api bakaran arang.
Wawancara mendalam saya terapkan kepada keluarga Pak Mujani. Pak
Mujani mempunyai lima orang anak laki-laki yang bekerja sebagai pembuat arang,
dari keluarga Pak Mujani saya banyak mendapatkan informasi tentang kehidupan
pembuat arang di Desa Gambus Laut. Keluarga Pak Mujani sangat terbuka, terutama
istrinya Ibu Jumikem. Ibu Jumikem sangat senang didatangi oleh orang, apalagi jika
yang datang adalah anak gadis, itu dikarenakan dia tidak mempunyai anak
perempuan. Jadi jika dia melihat ada anak gadis yang datang dia langsung keluar dan
mendatanginya.
Bang Sapri mengatakan susah saat ini untuk mencari kayu bakau, karena
mereka musti kejar-kejaran dengan aparat pemerintahan yaitu polisi hutan. Karena
jika ketahuan mereka akan ditangkap dan disuruh membayar denda. Walaupun
kemudian mereka dilepaskan kembali, tapi adanya denda tersebut sangat
memberatkan mereka. Dan lagi aparat pemerintah yang katanya adalah polisi hutan
gunakan untuk membuat arang. hal itu terjadi dua atau tiga bulan sekali. dan saat
mereka datang, mereka juga meminta uang kepada pembuat arang.
Sedikit keterangan diatas adalah kronologis dari jalannya wawancara
mendalam yang telah saya laksanakan. Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan
data mengenai bagaimana strategi yang dilakukan pembuat arang dalam menghadapi
permasalahan yang terjadi akibat larangan penganbilan kayu bakau yang dibuat oleh
pemerintah.
o Observasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung untuk
memperoleh gambaran selengkapnya mengenai pengolahan/pemanfaatan sumber
daya alam kayu mangrove menjadi arang oleh para pembuat arang di desa Gambus
Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Pengamatan yang dilakukan peneliti terkait
dengan kegiatan para pembuat arang dan kehidupan sehari-hari mereka yang
merupakan cerminan dari strategi beradaptasi. Melihat bagaimana cara pembuat
arang menyusun kayu-kayu di dalam tungku kemudian membongkar tungku yang
telah selesai dimasak. Bagaimana keadaan rumah mereka dan apa-apa saja yang
mereka lakukan selain membuat arang.
o Studi Dokumentasi
Untuk melengkapi data yang diperoleh di lapangan, peneliti akan mencari
data yang terkait dengan masalah penelitian berupa buku-buku, jurnal, tesis, laporan
penelitian, skripsi, majalah, surat kabar dan tulisan-tulisan lainnya termasuk tulisan
dari media elektronik yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk menambah
pemahaman penulis terhadap pemasalahan yang akan diteliti. Penggunaan data-data
ini adalah untuk mendukung data yang didapat dari lapangan.
o Data Visual
Gambar visual yang dihasilkan sebagai bukti yang dapat dilihat oleh semua
orang, dan sebagai data pelengkap yang paling akhir.
b. Analisis Data
Data yang di peroleh dari lapangan dianalisi secara kualitatif. Data yang
dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara akan disusun sesuai dengan
kategori perilaku, siasat (pengetahuan), dan proses. Kemudian dilakukan
penganalisaan hubungan dari setiap bagian yang telah disusun untuk memudahkan
saat mendeskripsikannya. Setelah ini akan dianalisa kategori-kategori tersebut secara
mendalam sesuai data yang dibutuhkan.
1.6 Pengalaman Di Lapangan
Kunjungan pertama saya pada pertengahan tahun 2011, saat itu saya datang
hanya untuk observasi awal. Saya pergi ke kantor Kepala Desa Gambus Laut untuk
meminta ijin penelitian, saat itu saya tidak bertemu dengan siapa-siapa karena
seluruh pegawai sedang istrahat, kemudian ada salah seorang penduduk yang datang
dan bertanya kepada saya apa yang saya lakukan di kantor itu, setelah saya
kepala desa. Saat itu langsung saya hubungi dan ternyata rumah sektretaris tidak jauh
dari kantor kepala desa. Ibu itu pun segera membuka kantor dan memberikan
data-data yang saya butuhkan.
Kunjungan kedua saya untuk melihat lokasi pembuatan arang, saat itu
Mulyono membawa saya ke tempat Bu Sani dan Pak Sutimin. Tatapan mereka agak
tidak mengenakkan saat melihat saya. Saat saya menghampirinya, dia langsung
berbicara bahasa jawa kepada Mulyono. Dalam bahasa jawa dia bertanya kepada
Mulyono saya ini siapa dan mau apa datang ke tempat dapur arangnya. Lalu
mulyono menjelaskan dengan bahasa jawa juga bahwa saya hanya seorang
mahasiswa dan hanya ingin belajar. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu
Sani, ternyata awalnya dia berfikir saya adalah wartawan. Sebab dia bilang
sebelumnya pernah wartawan datang dan mengambil gambar kegiatan mereka. Tidak
seperti Bu Sani yang mulai mencair dalam suasana perbincangan suami bu Sani yaitu
Pak Sutimin tidak terlalu memberikan respon yang baik. Dia lebih banyak diam dan
sesekali memperhatikan saya. Kendalanya adalah mereka masih menggunakan
bahasa Jawa untuk berkomunikasi, sehingga saya kurang mengetahui apa yang
mereka katakan, Mulyono lah yang menjadi translater saya.
Kunjungan penelitian berikutnya saya menginap tiga hari dirumah salah
seorang warga, namanya Nenek Ngatiem dan Kakek Tukimin dan anak bungsunya
bernama yayuk. Nenek dan Kakek sangat baik dan ramah, dan setelah saya tinggal
disitu baru saya mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai sanitasi yang baik.
Mereka masih menggunakan jamban, semua rumah di dusun ini masih menggunakan
jamban, termasuk rumah Kepala Desa. Kebetulan rumah Kepala Desan terletak di
untuk mengunjungi Bu Sani, lalu Bu Sani menyarankan saya untuk ke tempat Pak
Mujani, di sana saya bertemu dengan Bang Supri, Hasan, Kak Tuti, Kak Wati dan Bu
Jumikem, sambutan mereka sangat baik tetapi saya hanya sebentar saja karena sudah
sore. Malamnya saya berniat pergi ke rumah Kepala Desa untuk melapor bahwa saya
tinggal di dusun itu untuk beberapa hari, tetapi ternyata Kakek sudah lebih dulu
melapor kepada Kepala Desa. Keesokan harinya saya langsung menuju kerumah Bu
Jumikem dan disana saya bertemu dengan Pak Mujani, Bang Budi dan Bang Sutris
yang merupakan anak Bu Jumikem dan Pak Mujani. Bu Jumikem langsung membuat
keripik pisang untuk teman mengobrol, pisang itu hasil dari kebunnya, dan tidak
tanggung-tanggung Bu Jumikem juga menyuruh anaknya memanjat pohon kelapa
untuk mengambil “degan”. Ibu Jumikem sangat baik dan ramah, kami juga di ajak
makan siang di rumahnya tapi kami sudah janji sama nenek untuk makan siang
dirumah. Sorenya saya membantu Bang Sutris dan Kak Wati membongkar tungku
arangnya. Saat membongkar arang banyak yang membantu, Hasan dan Arif juga ikut
membantu memasukkan arang ke goni, keseluruhan arang ada enam goni. Keesokan
paginya saya kembali ke rumah Bu Jumikem, saat itu bu Jumikem sedang mencuci
jadi saya ke rumah Kak Wati untuk mengobrol sedikit dengannya sebelum saya
kembali ke Medan. Setelah lama mengobrol dengan kak Wati saya kembali ke rumah
Ibu Jumikem untuk berpamitan karena akan pulang ke Medan.
Saya sempat membiarkan data penelitian ini selama sebulan. Data penelitian
saya berupa foto-foto yang ada di handphone hilang, dikarenakan handphonenya
dicuri orang, tidak tau kenapa saya menjadi malas untuk mengerjakan skripsi ini.
Sampai beberapa bulan saya diamkan. Kemudian saya mendapat pekerjaan, saya
sanggup. Satu tahun berlalu dan saya masih bekerja dan memdiamkan data-data
penelian saya. Kemudian di satu kesempatan saya datang ke Desa Gambus Laut lagi
untuk mengambil data-data peneliat yang hilang berupa foto-foto, dan saya kembali
me-refresh kembali data-data penelitian saya. Saya pergi kerumah Ibu Jumikem,
ternyata Ibu Jumikem sedang pergi ke Perdagangan tempat saudaranya yang sedang
pesta jadi saya pergi ke rumah kak Wati, saya mengobrol dengan kak Wati dan Bang
Sutris, kebetulan ada Bang Budi, Hasan dan Arif. Lalu kami mengobrol di pondok
yang ada di rumah Bu Jumikem.
Setelah kembali ke Medan saya mulai mengerjakan skripsi ini, namun karena
sambil bekerja saya tidak dapat fokus dengan skripsi ini. Saya kebanyakan
mendiamkan skripsi ini dari pada mengerjakannya, dan akhirnya skripsi ini tidur
selama setahun lagi sampai akhirnya di saat terakhir masa kuliah, saya memutuskan
untuk berhenti dari pekerjaan saya karena saya tidak dapat fokus dengan dengan
skripsi ini jika masih bekerja. Akhirnya saya kembali fokus ke skripsi ini, lalu saya
kembali ke lapangan untuk mengambil data-data kembali sebagai tambahan data-data
BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
2.1. Gambaran LokasiKabupaten Batu Bara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 Kecamatan serta 100 Desa/Kelurahan Definitif.
Wilayah Kabupaten Batu Bara di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Asahan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.
Sebagian besar kecamatan yang terdapat di kabupaten batu bara berada di pesisir pantai timur. Ibu kota kabupaten yaitu kecamatan lima puluh yang merupakan kecamatan terbesar di kabupaten batubara ini terletak di pesisir pantai timur juga, sehingga tidak heran jika wilayah ini merupakan wilayah pesisir yang banyak menghasilkan produksi pantai.
2.1.1. Lokasi dan Luas Desa Gambus Laut
Berdasarkan data tahun 2011, luas desa Gambus Laut adalah 1430 ha, terdiri dari pemukiman penduduk 448 ha, hutan mangrove 461 ha, sawah 321 ha, pekarangan dan lain-lain 200 ha. Desa Gambus Laut terbagi atas wilayah administrasi pemerintahan yang lebih kecil yang dinamakan dusun, dan masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dan dipilih oleh warga dusun yang disyahkan oleh Kepala Desa Gambus Laut. Di desa Gambus Laut terdapat 8 dusun, setiap dusun memiliki nama, dusun 1 adalah titi payung, dusun 2 adalah pematang panai, dusun 3 adalah kampung lima, dusun 4 adalah kampung mesjid, dusun 5 sungai megang, dusun 6 dan dusun 7 adalah pemetang segenap, dan dusun 8 adalah sei kuba.
2.1.2. Sejarah Desa
Desa Gambus laut pada awalnya merupakan bagian dari Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan pada tahun 1993. Desa Perupuk di mekarkan menjadi dua Desa,. Desa Perupuk sebagai Desa Induk dan Desa Gambus Laut sebagai Desa Pemekaran.
2.1.3. Letak Geografis dan Lingkungan Alam
Secara administratif batas-batas desa Gambus Laut adalah, -Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
-Sebelah selatan berbatasan dengan desa Lau kuk Bulan
-Sebelah barat berbatasan dengan desa Suka Ramai/Kuala Indah -Sebelah timur berbatasan dengan desa Perupuk
Desa gambus Laut merupakan wilayah pesisir dan terletak di dataran rendah dengan tetinggian di atas permukaan laut sebesar 0,5 m. Kondisi geografis dan rendahnya permukaan tanah menyebabkan desa Gambus Laut di pengaruhi oleh pasang surut air laut, beberapa rumah di desa Gambus Laut ini terutama pemukiman warga yang terletak di pinggiran sungai saat air pasang besar maka akan terendam air sampai ketinggian 50 cm. Pasang surutnya air dapat terjadi siang dan malam. Curah hujan rata-rata 16 mm setiap tahun dan suhu udara rata-rata 36 derajat C setiap tahun. 2.1.4. Keadaan Penduduk
Berdasarkan monografi desa pada tahun 2011 penduduk desa Gambus Laut berjumlah 4.409 jiwa atau 1.198 kepala keluarga (KK), yang terdiri atas 2.260 jiwa laki-laki (51,26%) dan 2.149 jiwa wanita (48,74%). Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3
No Jenis Kelamin Kelompok Umur Jumlah %
1 Laki-laki 0-15 513 11,63
16-55 1126 25,53
2 Perempuan 0-15 686 15,55
16-55 1019 23,12
>55 444 10,08
Total 4409 100
Sumber: Monografi desa Gambus Laut tahun 2011
Penduduk tersebar di 8 dusun yang kepadatannya berbeda antara satu dusun dengan dusun lainnya. Menurut data dari kantor kepala desa Gambus Laut penduduk yang sangat padat adalah dusun VII dengan jumlah penduduk 1.091 jiwa. Dusun yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk rendah adalah dusun I dengan jumlah penduduk 420 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4
No Dusun Jumlah KK Jumlah
1 I 113 KK 420 jiwa
2 II 130 KK 451 jiwa
3 III 128 KK 439 jiwa
4 IV 132 KK 473 jiwa
5 V 144 KK 537 jiwa
6 VI 136 KK 484 jiwa
7 VII 278 KK 1091 jiwa
8 VIII 137 KK 514 jiwa
Total 1198 KK 4409 jiwa Sumber: Monografi desa Gambus Laut tahun 2011
suku yang di desa Gambus Laut yaitu suku jawa, aceh, banjar dan batak toba. Keberagaman suku ini akibat migrasi.
Berdasarkan agama, mayoritas penduduk desa Gambus Laut beragama Islam dengan jumlah 4.252 jiwa (96,44%), sedangkan yang beragama lain adalah: beragama Kristen Protestan 106 jiwa (2,40%), dan beragama Kristen Katolik 51 jiwa (1,16%).
Tingkat pendidikan penduduk desa relatif tinggi, tidak tamat SD 225 jiwa (5,13%), tamat SD 1353 jiwa (30,68%), tamat SLTP 1.169 jiwa (26,51%), tamat SLTA 1146 jiwa (25,99%). Sedangkan penduduk yang menamatkan perguruan tinggi 63 jiwa (1,425%). Jumlah penduduk yang belum bersekolah sebanyak 453 jiwa (10,27%).
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di desa Gambus Laut tergolong berpendidikan cukup tinggi. Hal ini didorong oleh fasilitas pendidikan di desa Gambus Laut yang memadai. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini, sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama.
2.1.4. Keadaan Flora dan Fauna
Jenis tumbuhan yang terdapat di desa Gambus Laut cukup beragam walaupun desa ini terletak di daerah pesisir pantai. Tumbuhan yang terdapat di daerah ini antara lain: kelapa, kelapa sawit, rumbia, cemara, pohon bakau (mangrove), dan nipah. Beberapa jenis tumbuhan palawija juga dapat timbuh di desa ini antara lain: jagung, padi, cabai, dan kacang-kacangan.
Dan ada juga hewan peliharaan penduduk seperti kambing, lembu, bebek, entok, dan ayam. Hewan peliharaan ini selain untuk dikonsumsi sendiri juga dijual sebagai penambah penghasilan rumahtangga. Jenis hewan peliharaan lain yang tidak untuk dikonsumsi adalah ikan lele, kucing dan burung perkutut.
2.2. Pola Pemukiman Penduduk dan Sarana Desa
2.2.1. Pola Pemukiman
Pola pemukiman penduduk di desa Gambus Laut tidak terlalu padat. Hal ini terlihat dari masih terdapat tanah kosong yang ditanami sawit dan cabai oleh penduduk. Jenis rumah di desa Gambus Laut ini berupa rumah permanen, semi permanen dan non permanen. Rumah-rumah yang dibangun tergantung dari keadaan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah.
Rumah permanen yaitu rumah yang berlantaikan kramik atau semen dan berdindingkan semen, atap rumah dari seng bergelombang dan ada juga rumah yang sudah menggunakan seng multiroof. Rumah semi permanen yaitu rumah yang didasarnya adalah semen dan berdindingkan setengah tepas dan setengah semen, atap rumah terbuat dari tepas yaitu anyaman daun nipah. sedangkan rumah non permanen yaitu rumah yang berdinding anyaman bambu dan atap dari anyaman daun nipah, sedangkan lantainya ada yang sudah di semen dan ada juga yang masih berlantaikan tanah.
rumah. Rata-rata penduduk desa Gambus Laut kurang memperhatikan sanitasi. Penduduk desa Gambus Laut masih menggunakan jamban sebagai WC mereka, dengan mengorek lubang seluas 6x4meter dan di dalam kolam tersebut hidup beberapa ekor lele. Berbeda dengan rumah penduduk yang ada di dekat sungai, mereka membuat jamban di pinggir sungai, mereka tidak lagi membuat kolam.
Aliran listrik masuk di desa ini sekitar tahun 1992, waktu itu Perusahaan Listrik Negara melakukan program masuk listrik gratis. Sedangkan untuk sarana air minum mereka mengambil sumber air sumur bor yang diberikan oleh Perusahaan INALUM. Pada umumnya sumber air di desa Gambus Laut adalah air sumur, baik itu sumur bor atau sumur dangkal.
2.2.2. Sarana Ekonomi Desa
Kondisi desa Gambus Laut yang terletak di dataran rendah tidak membuat sarana ekonomi di desa ini terbatas. Penduduk desa Gambus Laut sangat beruntung karena memiliki tekstur tanah yang dapat diolah menjadi tanah pertanian untuk menanam padi dan palawija. Selain kekayaan alam lautnya, masyarakat juga punya kekayaan alam daratan.
Tabel 5
No Mata Pencaharian Jumlah %
1 Nelayan 896 62,70
2 Petani 232 16,23
3 Buruh Tani 128 8,95
4 Pedagang 86 6,10
5 Tukang Batu 5 0,34
6 Penjahit 5 0,34
7 Pegawai Negeri 46 3,21
8 Perangkat Desa 11 0,76
9 Pengrajin 2 0,13
10 Industri Kecil 8 0,55
11 Buruh Industri 10 0,69
Total 1429 100
Sumber: Monografi desa Gambus Laut tahun 2011 2.2.3. Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan di desa Gambus Laut ini kurang memadai. Di desa Gambus Laut ini hanya terdapat 2 gedung SD Inpres, dan 6 Gedung PAUD. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 6
No Sekolah Unit Murid Guru
1 PAUD 6 127 8