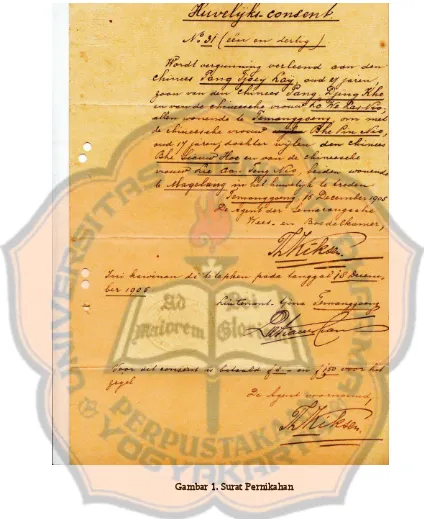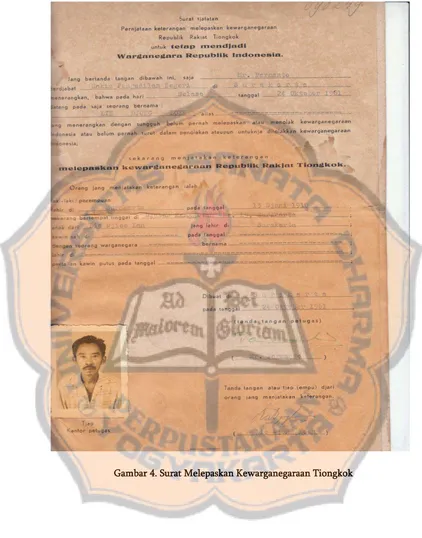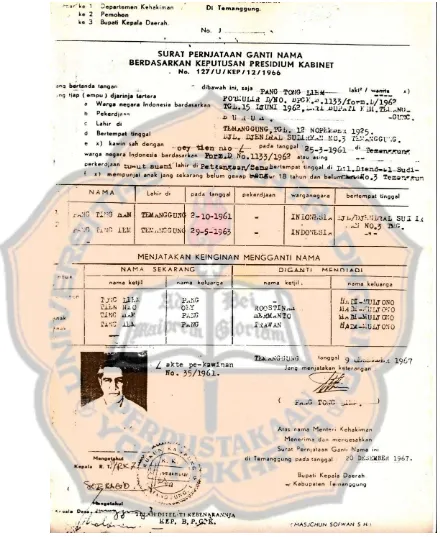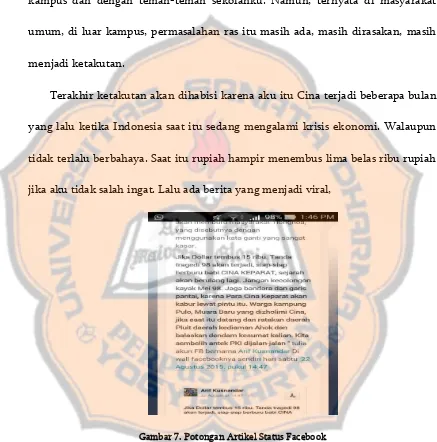viii
Abstrak
Menjadi orang keturunan Cina adalah menjadi orang yang istimewa di Indonesia ini. Banyak pengalaman yang begitu berbeda kami rasakan walaupun kami sama-sama warga negara Indonesia, mulai dari berbagai kerusuhan anticina, sampai berbagai undang-undang yang bersifat diskriminatif. Keistimewaan ini membuat saya ingin melihat bagaimana pengalaman rasisme sebagai orang keturunan Cina di Indonesia. Kebutuhan untuk memaknai apa yang dialami dan bagaimana pengalaman sebagai peneliti tidak dibungkam atas nama jarak dan objektivitas membuat saya menggunakan metode penelitian dan penulisan autoetnografi. Metode yang menggunakan pengalaman pribadi dari penulisnya sebagai sumber data dari penelitian. Pengalaman rasisme yang saya ceritakan dalam tulisan ini akan saya analisa menggunakan teori dari Frantz Fanon. Dari data ditemukan bahwa adanya kecenderungan saya untuk menolak kecinaan saya yang membuat saya menjadi Liyan dan berusaha menjadi yang standar yaitu Jawa. Usaha yang pada akhirnya gagal dan menuntut negosiasi terus menerus.
ix
Abstract
Being a Chinese descent means become a distinctive people in Indonesia. Although we are the citizens of the same nation, we have a lot of differences in the way we experienced what have been happened; from anti-china riots to discriminative regulations. This distinctness urged me to look into my own racism experiences as a Chinese descent. As a researcher as well, the need to make sense of what I have experienced and how to conduct the research out of silenced experiences in the name of proper distance and objectivity, made me decide to use auto ethnography research and writing method: a method that uses the researcher’s personal experiences as a source of research data. My racism experiences narrated in this writing was analyzed using Frantz Fanon theory. From this research, I found that there was a tendency to refuse my “chineseness” – which converted me become Other – and efforts to become standard i.e. Javanese. Those efforts eventually failed, and required continuous negotiations.
Cilik-cilik Cina, Suk Gedhe Arep Dadi Apa?
Sebuah Studi Autoetnografi Mengenai Pengalaman Rasisme
T
ESISUntuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M. Hum)
di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Oleh:
Anne Shakka Ariyani H. NIM: 136322013
MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
i
Cilik-cilik Cina, Suk Gedhe Arep Dadi Apa?
Sebuah Studi Autoetnografi Mengenai Pengalaman Rasisme
T
ESISUntuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M. Hum)
di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Oleh:
Anne Shakka Ariyani H.
NIM: 136322013
MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
vi
yang sudah saya kejar seumur hidup ini, saya ingin berterima kasih pada begitu
banyak pihak yang menemani saya selama proses ini.
Jelas, kepada Tuhan dan keluarga saya untuk kesempatannya sehingga di
tengah banyaknya keterbatasan, saya boleh dan bisa melanjutkan sekolah saya.
Terima kasih untuk banyaknya ‗kebetulan‘ sehingga saya bisa belajar di tempat
istimewa ini.
Terima kasih untuk semua dosen yang memberikan kepercayaan,
kesempatan, dan bimbingan. Dipercayai oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian
untuk melakukan banyak hal itu adalah pembelajaran yang mengubah hidup.
Terima kasih terutama untuk Mbak Katrin Bandel yang sudah menjadi dosen
pembimbing yang menemani saya di setiap prosesnya, yang sudah dengan ikhlas
dan sabar membaca kisah yang sama berulang kali. Terima kasih untuk Rama
Banar dan Bapak St. Sunardi untuk setiap saran dan masukan yang berguna baik
untuk penulisan saya, maupun selama proses belajar saya di IRB selama ini.
Mbak Desi, Mbak Dita, Pak Mul, dan Mbak Marni, menyenangkan untuk
bisa banyak bekerja sama dan untuk semua bantuan dalam yang sudah diberikan
dalam proses belajar saya di IRB. Terima kasih.
Terima kasih khusus untuk teman seperjuangan yang sudah berjalan bersama
vii
mengajari, menemani, menyediakan waktu untuk saya tangisi, dan berkali-kali
menyelamatkan saya.
Untuk semua teman IRB yang sudah menjadi teman berdiskusi, teman yang
saling mendukung, dan terima kasih sudah menjadi pelanggan ―Panda, Pedagang
Perantara Anda!‖ yang membuat saya bisa lebih mudah bertahan hidup. Teman
-teman 2013, -teman -teman Jangkrik! Mas Noel, Mas Adit, Hans, Idud, Vina, Si
Tong, Cahyi, dan Padmi. Teman-teman belajar bersama di PusDep Mbak Vini,
Gogor, Pita, Kak Umar, dan semua teman lain yang tidak dapat saya sebutkan
satu demi satu.
Terakhir untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan di sini, yang
membuat saya melanjutkan studi ini, yang membuat saya bisa menjalani proses
penulisan ini sampai akhir.
viii
Abstrak
Menjadi orang keturunan Cina adalah menjadi orang yang istimewa di Indonesia ini. Banyak pengalaman yang begitu berbeda kami rasakan walaupun kami sama-sama warga negara Indonesia, mulai dari berbagai kerusuhan anticina, sampai berbagai undang-undang yang bersifat diskriminatif. Keistimewaan ini membuat saya ingin melihat bagaimana pengalaman rasisme sebagai orang keturunan Cina di Indonesia. Kebutuhan untuk memaknai apa yang dialami dan bagaimana pengalaman sebagai peneliti tidak dibungkam atas nama jarak dan objektivitas membuat saya menggunakan metode penelitian dan penulisan autoetnografi. Metode yang menggunakan pengalaman pribadi dari penulisnya sebagai sumber data dari penelitian. Pengalaman rasisme yang saya ceritakan dalam tulisan ini akan saya analisa menggunakan teori dari Frantz Fanon. Dari data ditemukan bahwa adanya kecenderungan saya untuk menolak kecinaan saya yang membuat saya menjadi Liyan dan berusaha menjadi yang standar yaitu Jawa. Usaha yang pada akhirnya gagal dan menuntut negosiasi terus menerus.
ix
Abstract
Being a Chinese descent means being distinctive people in Indonesia. Although we are the citizens of the same nation, we have a lot of differences things differently; from anti-china riots to discriminative regulations. This distinctness urged me to look into my own racism experiences as a Chinese descent. In order to make sense of things I have been through as a researcher without being silenced for the sake of proper distance and objectivity, I applied autoethnography research and writing method. Autoetnography is a method that
uses the researcher‘s personal experiences as the source of research data. Racism experiences narrated in this writing are analyzed by using Frantz Fanon‘s theory. From this research, I found that there a tendency to reject my ―chineseness‖ – which converted me into the Other–and to attempt to become what I perceive as the standard, which is Javanese. Those efforts eventually failed, and required continuous negotiations.
1
Bab I
Pendahuluan
A.Latar Belakang
Terlahir di tengah keluarga berketurunan Cina dan memiliki mata sipit ini
sebagai efeknya, membuat perjalanan hidup saya ini memiliki liku-likunya
tersendiri. Bukan hanya sekadar saya tidak sama dengan teman-teman
sepermainan dalam hal fisik, tetapi juga banyak hal lain yang pada akhirnya
saya sadari saya lakukan dengan cara yang berbeda pula. Kesadaran akan
perbedaan tersebut tidak terbentuk begitu saja pada diri saya. Kesadaran,
pemahaman, dan pengalaman akan kecinaan yang ternyata menuntut
negosisasi terus menerus dalam diri saya. Negosiasi itu pada akhirnya saya
bawa ke dalam penelitian yang saya lakukan untuk meluluskan saya dari
perkuliahan tingkat S1 di bidang Psikologi. Saya berusaha memahami dan
mereduksi kecemasan dan kegelisahan saya sebagai orang Cina dengan cara
mengolahnya secara intelektual.
Bagi saya menjadi Cina bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Rasanya
banyak batasan-batasan yang tidak dapat saya lampaui karena ada kata ―Cina‖
yang dilekatkan dalam diri saya. Kata yang pada awalnya tidak saya mengerti
apa maksudnya. Kata yang akhirnya mau tidak mau saya adopsi menjadi salah
2 Kata yang sedikit banyak membawa rentetan mengenai apa yang boleh dan
tidak boleh saya lakukan, apa yang bisa dan tidak bisa saya lakukan. Kata yang
begitu ingin saya lepas tetapi tidak dapat karena kata itu menggurat dalam
pada diri saya dan mengalir di dalam darah.
Keinginan memahami dan melepas inilah yang membuat saya pada
akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai ―Identitas
Warga Keturunan Cina di Jawa Tengah‖1. Suatu usaha yang masih jauh dari
sempurna untuk belajar dan memahami bagaimana melakukan suatu
penelitian dan penulisan akademis. Penelitian yang pada awalnya saya
lakukan karena saya menemukan adanya perbedaan pandangan dan
pemahaman mengenai apa itu Cina dan apa itu Jawa di dalam keluarga saya
dan di lingkungan pergaulan saya yang didominasi oleh orang-orang yang
bukan keturunan Cina.
Saya mendapatkan adanya pembedaan yang memang dilakukan oleh
orang-orang Cina, termasuk keluarga saya sebagai orang-orang yang saya
temui, dengan orang-orang Jawa di sekitar kami. Relasi yang tidak mungkin
kami hindari sebagai kelompok minoritas untuk bertemu dengan orang-orang
mayoritas. Di kepala saya waktu itu, saya berpikiran bahwa tidak aneh jika
orang-orang Cina itu didiskriminasikan karena kami sendiri juga membedakan
1 Anne Shakka, 2012, Identitas Warga Keturunan Cina di Jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas
3 diri dengan orang-orang di sekitar kami. Dari situ saya sudah tidak berdiri di
pihak orang-orang Cina. Bagi saya, kelompok orang Cina sudah menjadi
―mereka‖, saya hanya dipaksa berada di dalamnya.
Penelitian berlangsung. Saya saat itu melakukan wawancara dengan
kedua orangtua saya mengenai kisah hidup dan pengalaman mereka sebagai
orang keturunan Cina. Ada tiga orang narasumber yang membantu saya
dengan kisah hidup mereka kala itu, Mamah saya, Papah, dan seorang teman
dari Papah saya. Dari penelitian tersebut, saya menemukan bahwa sebagai
orang keturunan Cina mereka bergulat dengan banyak hal. Ada
tegangan-tegangan yang sulit untuk didamaikan. Di satu sisi, mereka merasa sebagai
bagian yang menyatu dengan orang-orang di sekitar mereka, di sisi lain,
mereka tetap berbeda. Ada keinginan untuk bertahan tetap berbeda, sekaligus
ada keinginan untuk melenyapkan perbedaan itu. Juga ada perasaan terancam
terus-menerus yang membuat mereka melakukan segala cara untuk merasa
aman dan mengamankan keluarga mereka dari berbagai aspek.
Di sisi lain, saya juga berproses untuk menemukan diri. Saya menemukan
bahwa banyak ketakutan yang saya bawa dalam diri saya adalah ketakutan dan
kekhawatiran yang dibawa oleh orangtua sebagai orang Cina yang terus
menerus merasa terancam. Ada suatu ketidakpercayaan diri dan perasaan
4 orang Cina. Temuan-temuan bagi saya kala itu menjelaskan banyak hal, tetapi
tidak dapat saya bahasakan dalam skripsi saya. Temuan yang terasa ada, tetapi
tidak terlihat dengan jelas. Suara saya sebagai peneliti terpaksa harus
dibungkam atas nama jarak dan objektivitas.
Sebagai seorang keturunan Cina yang terlahir di akhir tahun delapan
puluhan dan tumbuh besar di era sembilan puluhan, saya tidak terlalu banyak
bertemu dengan diskriminasi rasial sebagaimana yang orangtua saya alami.
Saya tidak mengalami kerusuhan yang membahayakan hidup saya secara
langsung selama ini. Secara kasat mata, hidup saya damai dan tenteram.
Namun tetap saja ada yang terasa tidak benar dan mengganjal dalam
perjalanan hidup saya sehari-hari. Suatu perasaan akan adanya perbedaan
yang pada akhirnya menubuh dan membentuk cara saya berpikir dan
berperilaku. Suatu keadaan yang memengaruhi pilihan dan keputusan yang
saya ambil.
Di sinilah pada akhirnya saya memilih untuk melakukan penelitian ini.
Suatu penelitian yang ingin mencoba menjelaskan bagaimana pengalaman
rasisme yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang
keturunan Cina. Bukan suatu pengalaman akan kekerasan atau perbedaan
perlakuan yang masif, melainkan mengenai pengalaman-pengalaman kecil
5 dapat terlepas dari banyak wacana besar yang melingkupi dan memang tidak
bisa dihindari.
Berangkat dari tujuan ingin menjelaskan bagaimana pengalaman rasisme
ini, saya memutuskan untuk menggunakan metode yang terbilang masih
cukup baru untuk dilakukan dalam penelitian di Indonesia, metode
autoetnografi. Di Program Ilmu dan Religi dan Budaya Universitas Sanata
Dharma, metode ini baru dilakukan oleh Kurniasih dalam penelitiannya
―Jilbab Sebagai Lokus Pengolahan Diri: Sebuah Analisa Otoetnografi‖.
Pemilihan metode ini saya lakukan dengan pertimbangan karena pengalaman
dari diri sendirilah yang ingin saya maknai dan bahasakan. Saya berharap
metode ini menyediakan perangkat itu. Suatu metode yang memungkinkan
saya sebagai penulis lebih memahami lingkungan dan situasi budaya melalui
pengalaman hidup saya (Chang, 2008; Wall, 2008).2
Pemilihan ini juga saya lakukan dengan melihat ada penelitian mengenai
pengalaman rasisme yang juga menggunakan metode serupa walaupun tidak
menggunakan istilah autoetnografi. Dua di antaranya yang saya temukan
adalah tulisan dari Frantz Fanon dalam ―White Skin Black Masks‖ yang
menceritakan pengalaman diskriminasi rasial yang dialaminya sebagai seorang
2 Heewon Chang, 2008. Autoethography as Method. California: Left Coast Press, Inc. & Sarah
6 kulit hitam di Prancis. Bertemu Fanon membuat saya merasakan bahwa apa
yang saya alami itu bukan pengalaman diri saya sendiri saja. Kami sama-sama
merasakan bagaimana menjadi liyan dan bagaimana itu memengaruhi kami
sebagai individu. Saya jadi merasa heran kenapa saya begitu terlambat
mengenal Frantz Fanon, padahal orang ini berbicara mengenai psikologi dan
dominasi kolonial, sesuatu yang sangat relevan dengan keadaan Indonesia
sebagai negara bekas jajahan. Tulisan lain adalah karya Ien Ang dalam ―On
Not Speaking Chinese‖ yang merupakan suatu kumpulan artikel dari penulis
dalam bentuk tulisan semi-autobiographical (2001: vii) mengenai
pengalamannya sebagai seorang keturunan Cina diaspora dalam kehidupannya
sebagai seorang akademisi dan mengalami benturan-benturan dengan berbagai
budaya. Kedua buku ini akan saya bahas dan jelaskan lebih lanjut pada bagian
lain bab ini.
Perjalanan saya untuk memahami kecinaan ini juga membawa pada isu
yang pernah muncul mengenai orang Cina yang ada di Indonesia atau
mungkin suatu isu yang memang muncul dan dialami pada orang Cina
diaspora, resinicization atau pencinaan kembali. Usaha di mana orang-orang
Cina diaspora mencoba untuk menemukan kembali identitasnya sebagai orang
Cina atau menemukan kembali identitas budayanya. Usaha yang mulai marak
7 beberapa tahun terakhir. Saya masih berusaha memahami apa tujuan dari
usaha melakukan pencinaan kembali ini dan sejujurnya, tidak dapat saya
temukan manfaatnya. Dalam tulisan ini saya nanti juga akan secara khusus
membahas mengenai gerakan pencinaan kembali ini dalam posisi saya sebagai
orang Cina yang ingin mengkritisi hal tersebut.
Pada bab-bab selanjutnya saya akan berbicara mengenai bagaimana
wacana Cina yang tumbuh dan berkembang di Indonesia melalui pengalaman
rasial yang saya alami.
Tulisan ini saya harapkan bisa menjadi suatu alternatif dari
penelitian-penelitian mengenai orang keturunan Cina di Indonesia secara umum,
bagaimana pengalaman rasisme yang saya alami ini bisa untuk
menggambarkan akibat psikologis kepada individu yang menjadi liyan dalam
masyarakat.
B. Tema Penelitian
Pengalaman rasisme tidaklah selalu merupakan suatu pengalaman yang
menyisihkan atau suatu pengalaman akan kekerasan dan genosida pada suatu
kelompok ras. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengalaman
rasisme pada kehidupan sehari-hari saya sebagai orang keturunan Cina di
8 C.Rumusan Masalah
Perjalanan untuk mengenali dan memahami pengalaman rasisme sebagai
keturunan Cina membuat saya ingin mempertanyakan kembali bagaimana
pengalaman rasial dengan perangkat yang baru saya kenal ini, autoetnografi.
Hal tersebut ini membuat saya mengajukan kedua pertanyaan ini:
1. Bagaimana posisi dan relevansi metode autoetnografi dalam penelitian
kajian budaya?
2. Bagaimana pengalaman rasisme yang terjadi pada orang keturunan Cina di
Indonesia ini bisa ditemukan, direfleksikan, dan dimaknai dengan metode
autoetnografi?
D.Tujuan Penelitian
1. Untuk memahami bagaimana wacana kecinaan itu memengaruhi
pandangan dan pemikiran masyarakat di dalamnya serta bagaimana
wacana itu dimaknai dalam kehidupan sehari-hari
2. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman rasisme itu dirasakan dan
9 E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini berfokus pada penggunaan metode autoetnografi sebagai
suatu metode penelitian dalam kajian budaya secara khusus dan pada
penelitian ilmu sosial secara lebih luas. Diharapkan penelitian ini bisa
memberikan wacana baru dalam penggunaan metode penelitian ini dalam
bidang penelitian ilmu sosial. Di sisi lain, penelitian ini mengangkat tema
mengenai pengalaman rasial sebagai seorang keturunan Cina di Indonesia.
Penelitian dan pemaknaan pengalaman keseharian ini diharapkan
memberikan suatu warna lain dalam kajian dan narasi besar mengenai orang
keturunan Cina yang ada di Indonesia.
F. Tinjauan Pustaka
Banyaknya wacana dan penelitian yang selama ini saya baca mengenai
orang Cina di Indonesia sering kali tidak menggambarkan diri saya secara
utuh, padahal saya merasa secara kategori operasional, saya termasuk di
dalamnya. Penelitian mengenai orang Cina di Indonesia banyak yang
menceritakan mengenai bagaimana orang-orang Cina pasca Orde Baru mulai
merayakan kembali kecinaan yang mereka miliki atau mengadopsi identitas
10 pandang peneliti sebagai seorang yang berada di luar dari kelompok yang
diteliti.
Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penelitian yang
terkait dengan tema penelitian yang saya teliti. Pemilihan penelitian ini
meliputi penelitian mengenai objek formal yang akan saya teliti yaitu tentang
kecinaan, mengenai pengalaman rasisme, dan penelitian sejenis yang
menggunakan metode autoetnografi atau yang berbicara mengenai
pengalaman rasisme yang dialami oleh penulisnya.
1. White Skin Black Masks
Salah satu tulisan yang membahas rasisme dengan berangkat dari
pengalaman penulisanya sendiri adalah buku dari Frantz Fanon ini yaitu
Black Skin White Masks. Ia berbicara tentang pengalamannya sebagai
orang kulit hitam dalam berelasi dengan dunia kulit putih. Tulisan ini
pertama terbit dalam bahasa Prancis pada tahun 1952. Dalam pengantarnya,
Fanon menjelaskan bahwa buku ini sebenarnya sudah selesai ditulisnya tiga
tahun sebelumnya, tetapi tidak dapat langsung diterbitkan karena rasisme
masih menjadi isu yang sensitif kala itu. Buku ini sendiri terbit ketika
Fanon merasa lingkungan di sekitarnya sudah lebih menerima isi dari
tulisannya ini.3.
3 Saya sendiri menggunakan White Skin Black Masks ini dengan versi terjemahan bahasa Inggris
11 Buku ini sendiri sebenarnya merupakan analisis psikoanalisa dari
Fanon mengenai kondisi psikologis orang kulit hitam (lelaki) sebagai subjek
kolonial. Secara khusus dia menggunakan pengalaman pribadinya sebagai
data dalam analisanya. Fanon membagi bukunya dalam delapan bab. Pada
tiap babnya dia membahas berbagai macam aspek yang menurutnya
dipengaruhi oleh kondisi diskriminasi ras yang diterima oleh orang kulit
hitam di dunia barat, dalam kasus buku ini adalah di Prancis.
Fanon sebagai seorang yang mendapatkan beasiswa dalam bidang
kedokteran dan psikiatri memfokuskan tulisan dan analisisnya pada
bagaimana kondisi diskriminasi yang dialami oleh subjek kolonial ini
memengaruhi mereka dalam berperilaku, berbahasa, dan dalam bagaimana
mereka memandang diri mereka sendiri dan Liyan—dalam hal ini adalah
orang kulit putih. Dalam dunia kolonial, dikenal pandangan yang
menyatakan bahwa orang kulit hitam itu merupakan seorang yang
dianggap bodoh, primitif, liar, dan terbelakang. Bahkan Fanon juga
menyatakan bahwa ada anggapan bahwa orang kulit hitam dianggap
sebagai hasil evolusi manusia yang kurang sempurna. Orang-orang kulit
putih memerlakukan mereka secara berbeda. Mereka diperlakukan seperti
12 anak kecil atau orang bodoh, tetapi mereka kadang juga dipandang sebagai
monster—sampai membuat seorang anak kecil menangis karena takut
dimakan oleh orang kulit hitam.
Pertemuan dengan Liyan dan kondisi seperti itulah yang digambarkan
Fanon terjadi dalam dirinya dan orang-orang kulit hitam lainnya yang
berada di dunia Barat. Relasi yang kemudian mengubah cara pandang
mereka memandang kehitaman mereka, dan memandang dunia di
sekitarnya. Relasi ini, bagi Fanon, juga mengubah relasi orang kulit hitam
dengan sesama kulit hitam sendiri. Mereka yang sudah mengenyam
pendidikan Barat dan berbicara dengan bahasa orang Barat, seringkali tidak
lagi memahami atau tidak mau lagi memahami budaya asli mereka yang
mereka tinggalkan. Tulisan Fanon ini juga berfokus pada kerusakan
psikologis yang disebabkan oleh kolonialisme, bagaimana kolonialisme
berpengaruh pada pembentukan subjek seseorang baik itu dari sisi korban
maupun dari orang yang melakukan kolonisasi.
Menurut saya, buku Fanon ini akan memberi saya perangkat bahasa
untuk berbicara mengenai bagaimana pengalaman terdiskriminasi akan
membentuk dan memengaruhi kondisi psikologis seseorang dan bagaimana
pengalaman itu direproduksi juga dalam keluarga orang-orang yang
13 Cina di Indonesia, teori Fanon ini tidak akan dapat ditempatkan dengan
tepat karena kompleksitas posisi orang Cina itu sendiri.
2. On Not Speaking Chinese
Buku ini ditulis oleh Ien Ang, seorang Indonesia keturunan Cina yang
lahir di Indonesia dan pada tahun 1967 pindah ke Belanda. Ia menjadi
seorang akademisi dalam bidang kajian budaya dan akhirnya pindah dan
menjadi warga negara Australia. Buku ini menekankan pada posisi Ang
sebagai seorang Cina yang diaspora. Seorang Cina yang tinggal di Barat.
Permasalahan yang dia angkat adalah permasalahan yang didapatnya dari
pengalaman hidupnya. Ia selalu merasa tidak asing dengan keberadaan
dirinya. Sebagai seorang dengan fisik Cina di Barat, dia merasa berbeda dari
orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan ketika ia berada di Taiwan,
yang pada dasarnya orang-orangnya memiliki ciri fisik yang sama dengan
dirinya, ia tetap merasa berbeda karena dia tidak dapat berbahasa Cina.
Konsep teoretis yang dipakainya dalam penelusuran ini adalah hibriditas.
Ang mengkritik konsep asimilasi dan multikulturalisme yang menurutnya
tidak tepat dalam menggambarkan relasi antar ras yang terjadi.
Buku ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama berjudul,
―Beyond Asia: deconstructing diaspora‖, bagian kedua, ―Beyond the West:
14
living hybridities.‖ Permasalahan yang banyak diangkat adalah pertemuan
antara dia sebagai seorang wanita Asia dengan dominasi Barat atau orang
kulit putih. Secara khusus dia membahas posisinya sebagai perempuan Asia
adalah pada tulisannya yang berjudul ―I‘m feminist but…: ‗other‘ women
and postnational identities‖ (Ang, 2001: 177).
Ien Ang juga secara khusus membahas mengenai Cina di Indonesia dari
tahun 1960-an sampai ke era 2000-an pada bab 3 yang berjudul, ―Indonesia
On My Mind, Diaspora, the Internet and the struggle for hybridity.‖ Di sini
Ang banyak membahas mengenai hibriditas dan diaspora. Hal ini
terpengaruh dari keadaannya sebagai seorang migran di Belanda. Dia
sendiri mempertanyakan apakah ia seorang Cina diaspora ataukah seorang
Indonesia diaspora.
Lebih lanjut dia mengkritisi mengenai wacana yang sudah diterima
begitu saja mengenai Cina di Indonesia. Seperti pandangan bahwa orang
Cina yang mendominasi kekayaan dan kesejahteraan di Indonesia. Sesuatu
yang tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan, tetapi juga tidak benar begitu
saja. Kecinaan di Indonesia tidak lagi menjadi suatu penanda ras atau ciri
fisik saja, melainkan menjadi suatu identitas ekonomi.
Ang kemudian menganalisis persoalan kecinaan yang ada di Indonesia
15 pembauran dilakukan sebagai suatu strategi untuk membaur dengan
lingkungannya. Hal ini terutama dilakukan oleh orang keturunan Cina
yang tidak cukup kaya untuk berpindah negara. Hibriditas sebagai suatu
strategi yang perlu untuk dilakukan sebagai suatu negosiasi atas
marginalisasi yang terjadi.
Buku ini juga membantu saya dalam melihat permasalahan kecinaan
yang ada di Indonesia dari perspektif kajian budaya dan kajian
pascakolonial. Selain itu, dalam buku ini Ien Ang menggunakan metode
penulisan yang sejalan dengan metode yang saya gunakan yaitu
semi-autobiografi.
Sebagai seorang keturunan Cina yang sudah lama meninggalkan
Indonesia, Ang memandang negara ini dalam posisinya yang sudah bukan
lagi menjadi orang Indonesia. Di sini saya akan memiliki posisi pandang
yang berbeda sebagai orang keturunan Cina yang tumbuh dan besar di
Indonesia.
Dalam penelitian ini saya akan membahas mengenai pengalaman
rasisme yang terjadi pada orang keturunan Cina yang ada di Indonesia.
Pada penelitian sejenis teori yang sering saya jumpai adalah negosiasi yang
dilakukan orang keturunan cina tentang kecinaan mereka, bagaimana
16 Dalam buku tersebut Ang banyak berbicara mengenai teori identitas
dari Homi Bhabha dan mengkritik praktik asimilasi yang banyak digunakan
untuk menghadapi perbedaan budaya. Mengutip Zygmunt Bauman, Ang
menyatakan bahwa asimilasi tidak akan pernah benar-benar berhasil
karena asimilasi yang dipahami sebagai ―membuat menjadi sama‖ tidak
akan bisa terjadi. Subjek yang diasimilasi hanya akan menjadi subjek yang
tidak benar-benar nyata, bahkan dicontohkan di sini bahwa subjek
non-Barat yang paling non-Barat sekalipun tidak akan pernah benar-benar menjadi
Barat (Ang, 2005:9).
3. Penelitian Mengenai Orang Cina Indonesia Pasca Orde Baru
Identitas dan kondisi orang-orang keturunan Cina yang ada di
Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru menjadi suatu persoalan yang cukup
banyak dibicarakan. Di sini saya akan membahas beberapa di antaranya,
yaitu Setelah Air Mata Kering karya I. Wibowo (2010), Identitas Tionghoa
Pasca Soeharto tulisan Chang-Yau Hoon (2012), dan Identitas Hibrid Orang
Cina dari Darwin Darmawan (2014). Ketiga buku ini merupakan hasil
kajian yang membahas mengenai pengalaman orang Cina pasca Orde Baru,
sejalan dengan apa yang akan saya bahas. Selain itu pembahasan ini juga
membantu saya untuk menempatkan di mana posisi penelitian saya sendiri
17
Setelah Air Mata Kering adalah kumpulan tulisan yang
menggambarkan bagaimana kondisi orang Cina setelah runtuhnya Orde
Baru. Dalam buku ini dibahas mengenai geliat orang Cina di Indonesia
dalam menanggapi kebebasan yang diperoleh. Tulisan-tulisan ini tidak
lepas dari sejarah orang Cina di Indonesia yang berada di posisi tertindas
dan bagaimana perubahan mulai dirasakan dan diusahakan untuk terjadi.
Sebagai contoh adalah bagaimana mulai bermunculan usaha untuk
menunjukkan rasa nasionalisme orang Cina di Indonesia. Mulai munculnya
partai dan organisasi politik yang didirikan untuk mewadahi aspirasi
orang-orang keturunan Cina di Indonesia. Usaha lain seperti mulai menuliskan
sejarah atau biografi orang-orang Cina yang berperan selama masa
kemerdekaan Indonesia seperti Oey Tjoy Tat, seorang menteri negara pada
masa pemerintahan Soekarno. Buku ini juga membahas mengenai
bagaimana perkembangan dari agama Buddha dan Kong Hu Chu yang pada
masa Orde Baru sempat mengalami tekanan yang luar biasa.
Kedua buku berikutnya secara khusus membahas mengenai identitas
orang Cina di masa reformasi ini. Reformasi di sini menjadi suatu penanda
penting bagi orang Cina di Indonesia pada khususnya karena runtuhnya
rezim lama yang dianggap begitu represif bagi orang-orang Cina.
18 orang keturunan Cina di Indonesia mulai menunjukkan dirinya kembali
sebagai orang keturunan Cina. Hal ini terlihat dengan mulai dipelajarinya
kembali bahasa Mandarin, tumbuhnya organisasi baik organisasi
masyarakat maupun organisasi politik yang menunjukkan kecinaan mereka,
atau dapat dikatakan mulai ada usaha untuk melakukan pencinaan kembali
atau resinifikasi pada masyarakat keturunan Cina yang menjadi subjek
penelitian Hoon.
Sedangkan pada Darwin Darmawan secara khusus membahas
mengenai bagaimana identitas hibrid dari orang Cina di Gereja GKI
Perniagaan, Jakarta. Penelitian ini merupakan suatu penelitian dalam area
kajian budaya dan kajian Pascakolonial dengan menggunakan teori dari
Homi Bhabha mengenai hibriditas dan ruang ketiga yang digunakan
sebagai strategi negosiasi identitas bagi orang keturunan Cina. Dalam buku
ini dikatakan bahwa Kekristenan menjadi suatu identitas atau ruang ketiga
yang menegosiasikan aspek kecinaan dan keindonesiaan yang selama ini
dianggap berada dalam posisi yang berlawanan. Di sini Darmawan sudah
mencoba membongkar berbagai wacana yang tertanam dalam pemikiran
kita mengenai kecinaan, seperti pandangan akan adanya eksklusifitas dari
19 Ketiga buku ini saya gunakan untuk memberi saya gambaran yang
cukup luas mengenai bagaimana kondisi orang keturunan Cina yang ada di
Indonesia pasca Orde Baru. Bidang apa saja yang mengalami perubahan dan
pembebasan, geliat apa saja dan di mana saja yang terjadi sejak kebebasan
itu diberikan dan diundang-undangkan. Undang-undang represif apa saja
yang dicabut dan digantikan dengan undang-undang yang lebih ramah
Cina.
Apa yang tidak saya temukan dari beberapa penelitian di atas adalah
bagaimana pengalaman keseharian orang keturunan Cina dalam menemui
diskriminasi dan rasisme dan bagaimana pengalaman itu dimaknai dan
direfleksikan kembali. Bagaimana sebenarnya keadaan orang-orang Cina
yang sehari-harinya membuka toko. Apakah pengeluaran Keppres tentang
penggantian penggunaan istilah Cina dengan Tionghoa4 akan memengaruhi
mereka, misalnya. Apakah undang-undang tersebut memperbaiki
perlakuan yang mereka dapatkan, atau memengaruhi pandangan mereka
akan diri mereka sendiri?
Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menempatkan diri untuk
melihat bagaimana orang keturunan Cina dalam keseharian mereka.
4 Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Surat
20 Apakah pergantian rezim yang terjadi dan wacana-wacana yang ada di
Indonesia ini juga memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka? Apakah
perubahan itu juga dirasakan dan terjadi pembentukan makna ulang akan
diri mereka sebagai orang keturunan Cina?
G.Kerangka Teoretis
Remembering Fanon is a process of intense discovery and disorientation. Remembering is never a quiet act of introspection or retrospection. It is a painful re-membering, a putting together of the dismembered past to make sense of the trauma of the present. It is such a memory of the history of race and racism, colonialism and the question of cultural identity, that Fanon reveals with greater profundity and poetry than any other writer.
(Mengingat Fanon adalah suatu proses yang sangat emosional akan pengungkapan diri dan keadaan kehilangan arah. Mengingat bukan hanya suatu tindakan melakukan instrospeksi maupun restropeksi. Ini adalah suatu tidakan yang menyakitkan untuk mengumpulkan dan menyusun kembali masa lalu yang terpecah untuk memahami trauma yang ada di saat ini. Mengingat Fanon adalah berbicara tentang memori sejarah mengenai ras dan rasisme, kolonialisme, dan pertanyaan akan suatu identitas kultural, suatu yang diungkapkan oleh Fanon dengan suatu cara yang lebih mendalam dan lebih puitis daripada yang pernah dituliskan oleh penulis lain.)
(Homi K. Bhabha5.)6
Bagi Fanon, ras dan rasisme bukanlah suatu konsep yang dipahami dengan
berbagai definisi yang ditemukan dalam buku. Ras dan rasisme bukanlah suatu
teori untuk dimengerti dan dipahami. Bagi Fanon, ras dan rasisme adalah
pengalaman yang dia cecap dan rasakan dalam kehidupan sehari-harinya sebagi
5 Kata pengantar untuk edisi 1986, Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition
(Bhabha, 1986: xxxv)
6 Semua terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dilakukan oleh saya sendiri kecuali
21 seorang Martinique yang tinggal di Prancis. Kehitamannya adalah konsep ras
yang dia pahami ketika dia akhirnya dihadapkan terus menerus dengan
Liyannya, para kulit putih. Atau mungkin lebih tepatnya dirinya yang adalah
―yang lain‖. Rasisme adalah apa yang dia alami, dan perlakuan yang dia terima
setiap harinya sebagai seorang berkulit hitam dalam dunia berkulit putih. Sesuatu
yang tidak melulu masuk akal, tetapi diterima seakan-akan itu kebenaran dan
direproduksi terus menerus.
―Lihat ada Negro! Mama, ada Negro! Mama, lihat ada Negro. Aku takut!‖
Takut! Takut! Sekarang mereka mulai takut kepadaku. Aku ingin bunuh diri karena tertawa, namun tawa sama sekali bukan masalahnya. Aku
tidak tahan lagi karena aku tahu ada legenda, kisah, dan sejarah… Aku
bertanggung jawab, tidak hanya pada raga ini, namun juga pada ras, dan
leluhurku.‖7
Rasisme bagi Fanon di sini menjadi suatu pengalaman yang berulang kali
menegaskan kehitamannya. Suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya dari
dirinya dan juga selalu terkait dengan seluruh ras dan leluhurnya. Suatu keadaan,
jika tidak mau dibilang beban, yang tidak mengada begitu saja tetapi juga
membawa serta kisah-kisahnya, legenda, dan sejarah, baik yang terjadi dalam
kenyataan yang dialaminya setiap harinya, maupun yang terjadi pada tataran
bahasa dan wacana yang tidak terlihat namun bertumbuh di dalam pikiran.
7 Frantz Fanon, 2016, Black Skin, White Masks Kolonialisme, Rasisme, dan Psikologi Kulit Hitam
22 1. Ras dan Rasisme
Kata ras atau ‗race‘ sendiri, pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris
pada tahun 1508 dalam puisi William Dunbar. Pada awalnya kata ini
menunjukkan suatu kata yang didenotasikan dengan kelas manusia atau
benda. Baru pada abad akhir abad ke 18, kata ras bermakna menjadi suatu
kategori yang membedakan manusia dalam karakteristik fisik berdasarkan
keturunan/etnik/suku (Ashcroft, Griffiths et al., 1998: 199). Dalam dunia
imperialisme dan kolonialisme, ras ini digunakan sebagai suatu kategori untuk
menegaskan hierarki yang didasari pada segi fisik untuk melegitimasikan
penjajahan atau penguasaan dari ras yang dianggap lebih unggul (kulit putih)
terhadap ras yang dianggap inferior (kulit berwarna).
Konsep perbedaan berdasarkan fisik atau ideologi-ideologi mengenai
perbedaan ras ini kemudian semakin tumbuh dan dilegitimasi dengan
dimasukkannya ideologi-ideologi ini dalam wacana sains. Dalam segi sains ini
ciri-ciri fisik atau biologis kemudian dikaitkan dengan ciri-ciri psikologis atau
intelektual. Hal ini juga dijelaskan Ania Loomba dengan mengacu pada buku
John Burke, The Wild Man‘s Pedigree (Loomba, 2003: 151). Di situ Loomba
mencontohkan adanya kategorisasi manusia seperti manusia liar dengan ciri
berkaki empat, bisu, dan berambut lebat; orang Amerika adalah orang dengan
23 oleh adat; orang Asia adalah orang dengan kulit kehitaman, mata hitam, keras,
angkuh, tamak, dan diatur oleh pikiran (governed by opinion). Di situ
ditunjukkan juga bahwa orang Eropa yang memiliki ciri psikologis yang
unggul seperti optimis, lembut, cerdas, cerdik, dan diatur oleh hukum
(Loomba, 2003: 115).
Wacana semacam inilah yang kemudian dibawa dan disebarkan dalam
dunia kolonialisme untuk membenarkan penguasaan dari orang-orang Eropa
atas orang dari ras lainnya. Bahkan di sini orang Eropa berpendapat bahwa
orang-orang dari suku atau ras lain itu merupakan ras yang lebih primitif
sehingga perlu untuk diperadabkan atau dibimbing menjadi ‗orang dewasa‘.
Pemisahan berdasarkan ras ini jugalah yang digunakan oleh pihak
Belanda dalam melanggengkan dominasi dan kekuasaannya di Hindia
Belanda. Belanda kala itu menerapkan sistem politik apartheid. Mereka
membagi sistem masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga golongan:
masyarakat Eropa, masyarakat timur asing (vreemde oosterlingen), yang
termasuk di dalamnya orang Cina, India, dan Arab, dan yang ketiga adalah
golongan pribumi. Onghokham dalam bukunya Anti Cina, Kapitalisme Cina,
dan Gerakan Cina. Sejarah Etnis Cina di Indonesia menjelaskan lebih lanjut
bahwa dalam golongan pribumi sendiri masih dibagi-bagi berdasarkan
24 Pembagian ini dapat kita lihat di Jakarta saat ini di mana bisa kita temukan
Kampung Ambon, Kampung Melayu, Pecinan, dan lain sebagainya
(Onghokham, 2008: 4).
Jika kita menilik lebih jauh dari pembagian yang dilakukan oleh sistem
kolonial ini, tidaklah murni pembagian berdasarkan ras atau ciri fisik. Kembali
pada kategorisasi yang dimunculkan oleh Linnaeus dalam Ania Loomba
(Loomba, 2003: 115), sains Barat hanya membagi ras menjadi lima kategori
yaitu manusia liar, Amerika (penduduk asli Amerika), Eropa, Asiatik, dan
Afrika, sehingga Cina, Melayu, Arab, dan India, merupakan satu rumpun ras
Asiatik. Pembagian yang pada akhirnya merupakan suatu konstruksi dan
pemisahan yang dilakukan kolonial demi kemudahan dan keuntungan
mereka. Pembagian yang menegaskan stereotipe-stereotipe untuk memastikan
masing-masing kelompok berada pada tempatnya masing-masing dan tidak
bersatu untuk melawan kolonialisme.
Pembatasan dan pembedaan secara rasial ini juga diikuti dengan
pembatasan cara berpakaian, seperti orang Cina yang tidak boleh berpakaian
dengan cara orang Eropa ataupun penduduk pribumi. Hal ini didasari oleh
kecurigaan Belanda yang berlebihan akan keberadaan orang Cina di Hindia
Belanda kala itu (Onghokham, 2008: 171). Sampai pada tahun 1910, lelaki
25 Cina. Saat ada seorang Cina yang ingin memotong kucirnya dan ingin
berpakaian secara Eropa, orang tersebut harus membuat petisi dan meminta
izin kepada Gubernur Jenderal (Onghokham, 2008: 4). Pemisahan berdasarkan
ras yang juga dilakukan oleh Belanda adalah dengan mengeluarkan peraturan
untuk membatasi tempat tinggal atau pemukiman orang-orang Cina. Seperti di
Batavia, mereka tinggal di satu kawasan, yaitu Glodok. Jika mereka ingin
berpergian atau keluar dari kampung tersebut, mereka harus memiliki pas
jalan atau izin untuk melintas.
Peraturan atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak
Belanda ini, terutama kepada orang-orang Cina adalah karena meletusnya
perang atau pemberontakan yang dikenal dengan periode perang ―Wolanda
-Cina‖, perang yang terjadi antara VOC dan orang-orang Cina dengan
dukungan dari penguasa-penguasa lokal dan kerajaan Mataram (Lombard,
1996b; Onghokham, 2008; Daradjadi, 2013). Pemberontakan ini sendiri dipicu
oleh VOC yang melakukan pembantaian besar-besaran pada orang Cina di
Batavia pada 9 dan 10 Oktober 1740 (Lombard, 1996b; Daradjadi, 2013).
Pembantaian orang-orang Cina atau yang dikenal dengan de Chineezen
Grootemoord ini memakan korban sampai 10.000 orang Cina di Batavia.
26 genap lima juta jiwa8. Pembantaian yang juga ditandai oleh Onghokham
sebagai kerusuhan anticina pertama dalam sejarah nusantara (Onghokham,
2008: 114). Di satu sisi, keberadaan perang ini dapat menandai adanya
kerjasama atau persatuan antara orang-orang Cina dengan orang-orang lokal,
dalam kasus ini adalah orang-orang Jawa atau kerajaan Mataram. Tetapi di sisi
lain, pembantaian yang dilakukan oleh VOC ini juga mengawali keterpisahan
antara orang keturunan Cina dan pribumi dengan politik apartheid yang
dilakukan Belanda kemudian.
Perbedaan yang tidak hanya sekadar berdasarkan perbedaan secara fisik
atau secara budaya saja. Pembedaan yang kemudian terjadi adalah pembedaan
yang menimbulkan adanya hierarki dalam relasi di masyarakat. Salah satu
penandanya adalah adanya perbedaan hak dan perlakuan dalam hukum
kolonial antara orang Cina dan orang Pribumi. Seperti adanya hak yang
diberikan kepada orang-orang Cina untuk mengelola beberapa sektor
perekonomian yang strategis seperti mengelola rumah gadai dan perdagangan
candu. Adanya ketimpangan hukum dan berbagai kebijakan kolonial ini yang
membuat dinamika masyarakat menjadi tertahan dan menyebabkan adanya
minoritas (Onghokham, 2005: 82).
8 Iwan Santosa dalam Catatan Editor: Perang Terbesar Melawan VOC, Modal Sosial Membangun
27 Dalam perjalanannya kemudian, orang-orang keturunan Cina juga tidak
mengalami keadaan yang lebih baik, bahkan bisa dibilang lebih buruk
dibandingkan pada era kolonial. Orang-orang keturunan Cina ini ditempatkan
pada posisi yang dilematis oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh
pihak-pihak yang berkuasa dan merasa memiliki hak atas orang-orang keturunan
Cina ini. Seperti adanya kebijakan dari pihak Cina yang menyatakan bahwa
semua orang keturunan Cina adalah warga negara Cina. Keadaan tersebut
memposisikan orang keturunan Cina memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini
berbuntut adanya kesulitan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia
dan pandangan akan orang Cina sebagai entitas yang asing terus menerus.
Bahkan jika makhluk asing ini sudah tinggal dan menetap di tempat itu selama
lebih dari tiga generasi. Masih banyak ejekan-ejekan yang menyuruh
orang-orang keturunan Cina ini untuk pulang ke negaranya. Negara yang mana?
Ditempatkan sebagai liyan terus menerus ini membuat tidak adanya
ikatan atau perasaan sebagai satu pihak antara orang keturunan Cina dengan
orang-orang pribumi di sekitarnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang
membuat orang-orang keturunan Cina mudah menjadi korban ketika ada
kerusuhan atau ketika situasi politik memanas. Dapat kita lihat sejarahnya,
sejak tahun 1740, lalu tahun 1965 di mana orang keturunan Cina dikaitkan
28 yang terjadi tidak pandang bulu. Lalu kerusuhan pada tahun 1981 di Solo yang
merembet ke beberapa tempat, dan yang terakhir adalah rangkaian kerusuhan
di tahun 1997-1998.
Beberapa dari kejadian tersebut pada mulanya tidak ada korelasinya
dengan orang keturunan Cina. Salah satunya adalah kerusuhan di Situbondo
yang terjadi pada 10 Oktober 1996 di mana pada awalnya terjadi penistaan
agama oleh seorang anak pesantren yang disidangkan dan menimbulkan
kemarahan massa (Purdey, 2006: 40-42). Kemarahan tersebut berlanjut
dengan pengerusakan yang menyerang rumah-rumah orang keturunan Cina.
Ada yang juga disebabkan oleh perselisihan antara orang keturunan Cina
dengan tetangga atau pekerjanya dan hal itu berakibat pada kerusuhan yang
melanda seluruh kota. Di sini saya melihat bahwa jika kamu bukan orang
keturunan Cina kamu boleh marah, atau menyatakan ketidaksenanganmu
kepada orang lain, tetapi hal itu tidak boleh dinyatakan jika kamu merupakan
seorang keturunan Cina. Sedikit salah langkah akibatnya bisa terjadi
pembakaran.
Pasca reformasi memang terjadi perubahan pada kondisi orang keturunan
Cina di Indoenesia. Pemerintahan dan keadaan menjadi lebih ramah.
Undang-undang yang mendiskriminasi orang Cina dicabut, banyak hal menjadi
29 dan butuh waktu, secara garis besar, saya sendiri merasakan adanya perbedaan
dalam perlakuan yang saya terima jika dibandingkan dengan saat saya masih
anak-anak dulu. Saya tidak perlu merasakan kesulitan yang Papah saya
rasakan ketika mengurus berbagai dokumen.
Dalam kondisi seperti inilah kehidupan kami jalani. Kehidupan yang
membawa sejarah panjang migrasi, pembantaian, dan diskriminasi. Kehidupan
yang juga membawa kekayaan, dan hak-hak istimewa sebagai warga negara
kelas atas. Kehidupan yang mulai bergeser menjadi kehidupan yang lebih baik
dan bahkan mulai dirayakan dengan meriah di setiap Imlek oleh hampir
semua orang Indonesia. Bahkan seorang keturunan Cina saat ini sudah bisa
bermimpi menjadi Presiden, sesuatu yang tidak mungkin terjadi 20 tahun
yang lalu.
Masyarakat luas pun mengalami kehidupan yang sama dari sisi yang
berbeda. Mereka memandang orang-orang keturunan Cina ini sebagai
makhluk asing yang entah bagaimana menjadi sukses dan kaya. Bahkan
mungkin menjadi orang paling kaya di lingkungannya. Seseorang yang
dianggap merampas sumber penghidupan yang seharusnya menjadi hak
mereka. Dan dari hal-hal tersebutlah rasisme yang saya alami ini terbentuk
30 2. Respon Psikologis
Mendefinisikan apa yang dituliskan Fanon dalam bukunya Black Skin,
White Masks bukanlah hal yang mudah saya lakukan. Pada awalnya saya
hanya melihat adanya kesamaan dari apa yang dituliskan Fanon dengan
pengalaman yang saya alami dan rasakan sebagai orang keturunan Cina.
Bagaimana pengalaman dipandang berbeda dari orang-orang di sekitar, diejek
mengenai sesuatu yang tidak bisa kita ubah begitu saja, warna kulit atau
bentuk mata. Bagaimana ketakutan dan usaha untuk berusaha menjadi sama
dengan orang-orang di sekitar, usaha yang pada akhirnya tetap gagal karena
penampilan yang memang tidak bisa diubah dengan mudah. Hal lain adalah
bagaimana pengalaman menjadi yang lain ini juga membentuk bagaimana
pandangan kami, saya dan Fanon, mengenai diri kami ini. Dalam tulisan ini
saya akan mengacu pada tulisan Fanon secara khusus yaitu Black Skin, White
Masks. Tulisan ini yang secara khusus berbicara mengenai psikologi dari
rasisme dan dominasi kolonial dengan didukung beberapa tulisan sekunder
lainnya.
Pengalaman kehitaman Fanon terjadi ketika dia hidup sebagai orang kulit
hitam yang berada di Perancis. Dia sebagai tentara yang membela Prancis
dalam peperangan, dia yang merupakan seorang Pskiater, dengan pendidikan
31 adanya perlakuan yang berbeda karena warna kulitnya. Perbedaan yang tidak
setara karena ada relasi kuasa di situ di mana Putih tetap menjadi standar dari
dirinya yang Hitam. Fanon selalu dilihat dari kehitamannya. Hitam sebagai
liyan, putih sebagai standar.
Menjadi kulit hitam di antara kulit hitam dan hitam di antara putih,
adalah suatu pengalaman yang berbeda. Tubuhnya menjadi sangat hadir dan
sangat disadari. Yang dilihat dan yang dipikirkan orang kulit putih itu yang
berlaku sampai orang kulit hitam juga dipaksa melihat dengan mata kulit
putih.
Pada orang kulit hitam sendiri, mereka memandang diri mereka sendiri
sebagaimana orang kulit putih memandang mereka. Hal ini menimbulkan
adanya persepsi dalam diri kulit hitam bahwa dirinya merupakan seorang
yang masih terbelakang, bahwa dirinya itu memang budak, dan berbeda
dengan orang-orang kulit putih. Sedangkan kulit putih sendiri diposisikan
sebagai standar yang harus dicapai. Hal ini menyebabkan adanya
kecenderungan untuk melakukan proses ―memutihkan‖ diri atau
―menghindari kehitaman‖ (Gordon, 2015: 40).
Proses untuk menjadi putih ini dilakukan dengan berbagai cara. Orang
kulit hitam akan berusaha melakukan hal-hal yang dilakukan kulit putih agar
32 pakaian yang dipakai kulit putih, mereka akan berbicara dengan bahasa yang
digunakan orang kulit putih.
―Waiterrr? Bwing me a dwink of beerrr!‖ (Fanon, 1952: 5). Fanon
menunjukkan bagaimana orang kulit hitam berusaha menghancurkan
stereotipe pada dirinya yang dipandang tidak bisa mengucapkan huruf ‗r‘
dengan baik dengan menonjolkan caranya mengucapkan walaupun pada
akhirnya tidak juga diucapkan dengan benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
ada pandangan psikologis yang dipercayai bahwa dunia ini akan terbuka
ketika batasan-batasan disingkirkan. (Fanon, 1952: 5)
Proses atau usaha yang dilakukan untuk memutihkan diri ini juga
dilakukan dengan mencari pasangan dari orang kulit putih atau menghasrati
orang kulit putih. Hal ini dicontohkan Fanon dari sebuah novel I Am a
Martinician Woman, yang ditulis oleh Mayotte Capecia (Fanon, 1952: 25).
Dalam buku itu, sebagaimana yang dijelaskan Fanon, menceritakan tentang
seorang wanita kulit hitam yang ingin menjadi putih. Dia mencintai orang
kulit putih tanpa syarat. Lelaki itu adalah pangerannya. Dia tidak
menginginkan atau meminta sesuatu apapun. Wanita ini hanya menginginkan
sedikit warna putih dalam hidupnya (Fanon, 1952: 25).
Bagi Fanon, wanita dalam kisah tersebut mencintai lelaki kulit putih
33 Capecia sebagaimana yang diimajinasikan dalam tulisannya di sini
mengungkapkan bahwa sebagai wanita kulit berwarna dia menginginkan
tidak hanya warna putih melainkan juga adanya hasrat untuk diinginkan.
Ketika wanita tersebut menyadari bahwa menjadi putih adalah hal yang dia
inginkan, maka diinginkan oleh seorang kulit putih menjadi hal yang paling
diinginkan (Gordon, 2015).
Ada dua tipe wanita yang diceritakan Fanon dalam pembahasannya
mengenai wanita kulit berwarna dengan pria kulit putih. Wanita kulit hitam
dan wanita campuran atau mulatresee. Wanita kulit hitam hanya memiliki
satu kemungkinan, menjadi putih. Sedangkan yang kedua tidak hanya
menginginkan menjadi kulit putih tetapi juga menghindari agar dirinya tidak
lagi terperosok menjadi hitam (Gordon, 2015: 40).
Setiap usaha yang dilakukan orang kulit hitam itu dilakukan untuk
membuat dirinya menjadi putih. Hingga suatu saat dia merasa dirinya adalah
seorang kulit putih sampai dia bertemu dengan masyarakat atau liyan kulit
putih yang menjadi cermin dari dirinya. Pertemuannya dengan liyan ini akan
membuatnya terpaksa untuk menyadari bahwa dirinya tetap kulit hitam. ―Ini
dokter yang kulit hitam, dia adalah seorang profesor kulit hitam.‖ Atau
dengan kata lain, walaupun berkulit hitam dia merupakan seorang dokter, ia
34 juga mengalami adanya pembedaan yang diterimanya karena posisinya dan
pendidikannya di antara teman-temannya yang berkulit putih. Dia menjadi
sama dengan kulit putih karena dia dianggap berbeda dengan orang-orang
kulit hitam lainnya. ―I am slave not to the ―idea‖ others have to me, but my
appearance (Fanon, 1952: 95). Apapun yang orang kulit hitam lakukan,
penampilannya itu akan selalu menjadi penanda dirinya, dan hal itu yang
menentukan bagaimana dirinya dipandang dan diperlakukan oleh orang lain.
Usaha dan kegagalan terus-menerus inilah yang menjadi pengalaman
keseharian orang kulit hitam. Lingkaran yang membentuk identitas dan
bagaimana seorang kulit hitam memandang dirinya. Sesuatu yang membentuk
identitas kulit hitamnya. Identitas yang tidak pernah menjadi suatu produk
yang jadi atau selesai, identitas selalu merupakan proses problematik akan
akses terhadap suatu imaji akan keutuhan (Bhabha, 1986: xxx).
3. Nativisme, Négritude, dan Resinifikasi
Dalam suatu komunitas atau negara yang pernah mengalami kolonisasi,
seringkali ditemukan adanya kecenderungan munculnya nativisme. Nativisme
sendiri adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya keinginan atau gerakan
untuk menemukan atau memunculkan kembali kebudayaan asli atau
kebudayaan sebelum kolonialisme terjadi (Ashcroft, Griffiths et al., 1998: 159).
35 yang ada sebelum kolonialisme terjadi, dan bahwa budaya yang ―asli‖ tersebut
bisa diraih kembali. Hal ini dimunculkan untuk mengatasi atau melampaui
kolonialisme yang seringkali mendiskriminasikan atau merendahkan
orang-orang yang dikoloni, sebagai contohnya yang terjadi pada orang-orang-orang-orang kulit
hitam.
Salah satu gerakan yang muncul untuk melawan kolonialisme yang terjadi
pada orang kulit hitam adalah gerakan yang dikenal dengan Négritude.
Gerakan ini pada awalnya dimunculkan oleh para intelektual Afrika dan
Caribia yang berada di Paris seperti Leopold Sedar Senghor dan Aime Césaire
pada sekitar era perang dunia kedua (Ashcroft, Griffiths et al., 1998: 161).
Négritude sendiri adalah suatu gerakan orang-orang kulit hitam yang muncul
melalui tulisannya yang membawa semangat untuk memperbaiki gambaran
orang kulit hitam dengan mengekspresikan atau mengafirmasi kehitaman
(Gordon, 2015: 53). Dalam gerakan ini muncul kecenderungan untuk
merayakan kehitaman yang selama ini berada dalam posisi inferior
dibandingkan dengan kulit putih.
Frantz Fanon sendiri mengenal gerakan ini dari saudara dan juga gurunya
Aime Césaire, ia mengadopsi gerakan ini ketika mendukung Aime Césaire
dalam pemilihan sebagai walikota Fort-de-France dari partai komunis
36 untuk merehabilitasi posisi orang-orang kulit hitam. Usaha yang dilakukan
dengan menggali kembali sejarah orang kulit hitam yang bercerita tentang
riwayat orang-oang kulit hitam yang terpelajar. Kisah-kisah yang
membuktikan bahwa orang kulit hitam bukanlah makhluk primitif atau
setengah manusia, ras kulit hitam yang sudah memiliki sejarah panjang sejak
dua ribu tahun yang lalu (Fanon, 2016: 101).
Pengakuan akan keberadaan yang diungkapkan dalam gerakan Négritude
ini pada akhirnya tidak membawa Fanon ke sampai pada posisi yang dia
inginkan. Keberadaannya sebagai orang kulit hitam tidak bisa terlepas dari
orang kulit putih, dan hanya menemukan kekosongan.
―Without a black past, without a black future, it was imposibble for me to
live my blackness. Not yet white, no longer completely black, I was damned. (Tanpa masa lalu hitam, tanpa masa depan hitam, mustahil bagiku untuk melalui kehitamanku. Belum putih, tidak lagi sepenuhnya
hitam, aku terkutuk.‖ (Fanon, 1952: 117)
Négritude, sebagai suatu gerakan, bisa menjadi gerakan yang ―rasis‖
karena mengafirmasi superioritas atas kulit putih, atau menjadi suatu gerakan
antirasis ketika menolak kekuasaan kulit putih dan antirasis terhadap kulit
hitam (Gordon, 2015: 52). Pandangan esensialis akan adanya suatu identitas
hitam juga menjadi dasar dari munculnya gerakan ini, walaupun dalam
retorika yang diajukan identitas kehitaman tersebut dibicarakan secara positif
37 Gerakan serupa juga cenderung muncul pada orang-orang Cina di
Indonesia, resinifikasi atau gerakan pencinaan kembali. Gerakan di mana
orang-orang Cina mulai memunculkan ciri identitas kecinaan atau
menceritakan kembali jasa-jasa orang keturunan Cina bagi negara Indonesia.
Seperti yang ditemukan dalam penelitian Hoon (2012) yang menemukan
bahwa orang-orang keturunan Cina pasca Orde Baru mulai kembali
mempelajari bahasa Cina, kembali berorientasi ke negara Cina sebagai pilihan
alternatif tempat tinggal atau pendidikan, membentuk organisasi
kemasyarakatan atau partai Tionghoa atau yang berbasis marga, serta
munculnya kembali media baik cetak maupun televisi yang berbahasa Cina
(Wibowo and (ed.), 2010).
Munculnya gerakan ini bisa dianggap sebagai reaksi dari terbebasnya
orang-orang keturunan Cina dari rezim Orde Baru yang sangat menekan dan
membatasi gerakan orang-orang Cina. Misalnya, Didi Kwartanda dalam
bukunya pengantarnya dalam buku Geger Pacinan menyatakan bahwa ada
penghilangan sejarah mengenai peran orang Cina dalam perang melawan
penjajah dalam materi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia
(Kwartanada, 2013: xiv).
Saya dalam penelitian ini akan mencoba memandang dan merefleksikan
38 apa saja yang dilakukan seorang keturunan Cina dalam prosesnya bernegosiasi
dalam menghadapi liyannya, atau dalam prosesnya menjadi liyan. Bagaimana
saya mencoba keluar dari kecinaan yang saya alami, bagaimana hal itu, tentu
saja gagal, karena penampilan yang tidak dapat saya lepaskan, bagaimana
kegagalan terus menerus itu membentuk pandangan saya akan diri dan
kecinaan saya. Kemudian, apakah saya dapat keluar dari lingkaran ini?
H.Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian autoetnografi yang akan melihat
bagaimana pengalaman sehari-hari saya dalam mengalami rasisme. Memilih
untuk menggunakan metode ini bukanlah suatu yang tanpa polemik. Ada
banyak kritik dan ketidaksetujuan dalam penggunaan metode ini untuk suatu
penelitian. Salah satunya adalah kritik yang diajukan oleh Sara Delamont
dalam tulisannya yang berjudul Arguments againts Auto-Ethnography9 yang
dengan cukup keras melakukan kritik terhadap metode penelitian
autoetnografi. Ia menggunakan kata yang keras yaitu ‗lazy‘, malas. Delamont
menyatakan bahwa pada dasarnya metode penelitian ini adalah suatu metode
9 Artikel dari Sara Delamont ini adalah tulisan yang pernah dipresentasikan pada European
Sociological Association conference; ‗Advance in Qualitative Research Practice‘ pada September 2006. Tulisan ini juga diterbitkan kembali di Qualiti (halaman 2-4), suatu terbitan mengenai penelitian kualitatif dari Cardiff University pada 4 Februari 2007. Artikel saya unduh pada Kamis, 12 Maret 2015 dari http://www.cardiff.ac.uk
39 penelitian yang malas, baik secara harafiah maupun secara intelektual
(Delamont, 2007: 2).
Lalu mengapa saya bersikeras untuk menggunakan metode ini? Carolyn
Ellis menjelaskan bahwa metode autoetnografi adalah suatu metode yang
secara sistematis melihat pada pengalaman pribadi dari penulis. Metode ini
berfokus pada sensasi fisik, pikiran, dan emosi dari penulis. Instrospeksi dan
mengingat kembali pengalaman emosional digunakan sebagai suatu metode
untuk memahami kembali pengalaman hidup yang sudah terjadi (Ellis, 2004:
xvii). Dalam penelitian ini saya ingin melihat bagaimana rasisme yang saya
alami memengaruhi diri saya secara psikologis dan bagaimana saya memaknai
hal tersebut. Metode autoetnografi ini akan memungkinkan melihat
pengalaman saya sendiri dan lebih memudahkan saya dalam menarasikan
pengalaman yang saya miliki. Pembahasan lebih menyeluruh mengenai
metode autoetnografi ini akan saya bahas pada Bab II.
Selain mengingat kembali bagaimana pengalaman yang pernah saya
sendiri alami, saya akan menggunakan dokumentasi yang saya miliki seperti
catatan harian, dokumen-dokumen, dan foto-foto mengenai kehidupan saya
atau keluarga saya. Data pengalaman hidup ini juga akan saya perbandingkan
atau untuk memastikan pengalaman yang saya alami dengan mewawancara
40 kembali data wawancara kedua orangtua saya mengenai pengalaman hidup
mereka sebagai orang keturunan Cina yang pernah saya gunakan dalam skripsi
saya.
Selain untuk memvalidasi pengalaman sendiri, wawancara juga dilakukan
untuk mencari tahu bagaimana pandangan orang-orang mengenai orang
keturunan Cina di Indonesia baik dari persepsi orang Cina itu sendiri maupun
dari pandangan orang noncina. Wawancara yang terjadi ini tidak saya lakukan
secara formal dengan membuat daftar pertanyaan tertentu. Wawancara atau
percakapan-percakapan yang terjadi merupakan diskusi mengenai kecinaan
yang mereka pahami. Seperti bagaimana pandangan kami tentang orang Cina,
atau bagaimana pengalaman kami terkait dengan kecinaan, misalnya
pengalaman rasisme yang dialami atau pengalaman berteman dengan orang
keturunan Cina, wacana atau stereotipe mengenai orang Cina yang tersebar di
masyarakat. Sumber data lain selain data pengalaman dan data wawancara
adalah data pustaka seperti mengenai sejarah dan kebijakan pemerintah
mengenai warga keturunan Cina yang ada di Indonesia.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa orang Cina di Indonesia bukanlah
suatu kelompok yang homogen. Perbedaan lokasi dan status ekonomi
merupakan suatu faktor yang akan memengaruhi bagaimana pengalaman dan
41
Tionghoa di Indonesia10 menemukan dalam penelitiannya bahwa di level kelas
sosial yang tinggi, orang-orang Cina tidak mengalami permasalahan rasisme.
Mereka bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang pribumi. Dari
pernyataan ini dan mengacu pada pernyataan Ien Ang mengenai kelas orang
Cina yang bergulat dalam masyarakat adalah orang keturunan Cina dari kelas
menengah bawah, saya kemudian mengevaluasi posisi di mana saya berdiri
secara kelas.
Kesadaran akan kelas dalam suatu penelitian etnografi ini juga dilakukan
oleh Paul Willis, dalam imajinasi etnografis.11 Dalam penelitian etnografi yang
dilakukan oleh Willis, basis material menjadi salah satu dasar di mana
pengalaman sehari-hari terjadi. Kelas ini akan menentukan bagaimana
lingkungan sosial seseorang, bagaimana dia berelasi dengan lingkungannya,
pendidikan seperti apa yang akan didapatkannya, dan bagaimana hal itu
dimaknai dalam konteks kelasnya.
Dari sini saya berpendapat bahwa memastikan posisi kelas adalah hal yang
penting untuk memberikan konteks pada pengalaman rasisme akan
dibicarakan. Saya melihat posisi kelas saya dari gaya hidup yang saya jalani
dan dari pendidikan saya sebagai mahasiswa pascasarjana yang menjadikan
saya berada di posisi kelas menengah. Walaupun hal ini juga bisa
10 (Tan, 2008), hlm. 172
42 dipertanyakan kembali dengan standar seperti apa saya menempatkan diri
saya. Posisi ini menentukan pendidikan yang saya dapatkan, tempat tinggal,
dan lingkungan pergaulan. Sesuatu yang pastinya akan sangat berbeda jika
misalnya saya berasal dari kelas atas atau kelas bawah.
Lebih lanjut pemahaman akan kelas dan bagaimana hal itu dimaknai akan
membawa saya pada penarikan kesimpulan lebih lanjut dengan melihat
bagaimana pengalaman yang saya alami itu dipengaruhi dan memengaruhi
lingkungan yang lebih luas. Ada hubungan saling memengaruhi antara suatu
struktur sosial dan identitas atau pembentukan budaya dalam diri seseorang.
Struktur sosial ini tidak hanya terletak di luar diri, melainkan juga ada di
dalam diri. Struktur inilah yang terkait erat dengan ideologi, ideologi yang
hadir karena diadopsi, dipertarungkan, dijelaskan, serta ideologi yang ditolak
(Willis, 2000: xvi). Metode analisis data ini akan membantu saya memahami
bagaimana suatu budaya atau ideologi yang ada di dalam masyarakat itu diolah
di dalam diri, baik itu diterima maupun ditolak. Dalam penelitian ini ideologi
yang akan dilihat adalah mengenai keturunan Cina yang ada di Indonesia,
seperti apakah ideologi yang terbentuk di dalam masyarakat dan bagaimana
43 I. Skema Penulisan
Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab secara keseluruhan:
Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang
penelitian ini, rumusan masalah, kajian pustaka, kajian teori yang digunakan,
dan metode yang digunakan secara singkat.
Bab II akan membahas mengenai metode autoetnografi secara lebih
mendalam. Bagaimana perkembangan dan posisi metode tersebut dalam
penelitian ilmu sosial secara umum dan bagaimana metode tersebut bisa
digunakan dalam penelitian kajian budaya.
Bab III akan berbicara mengenai bagaimana pengalaman saya sebagai
seorang keturunan Cina dengan metode autoetnografi yang sudah dibahas
sebelumnya.
Bab IV merupakan kesimpulan dan refleksi dari proses yang sudah