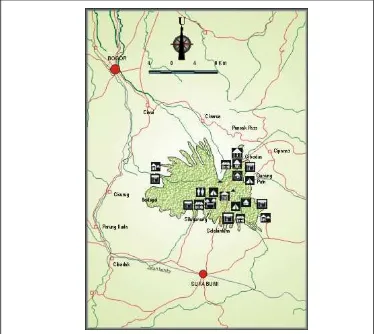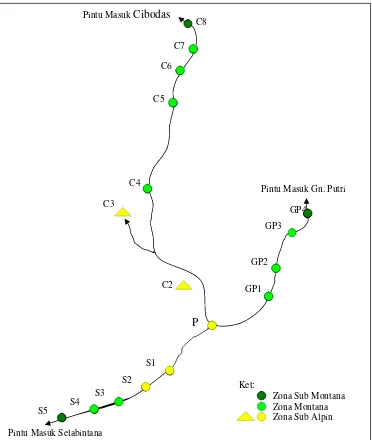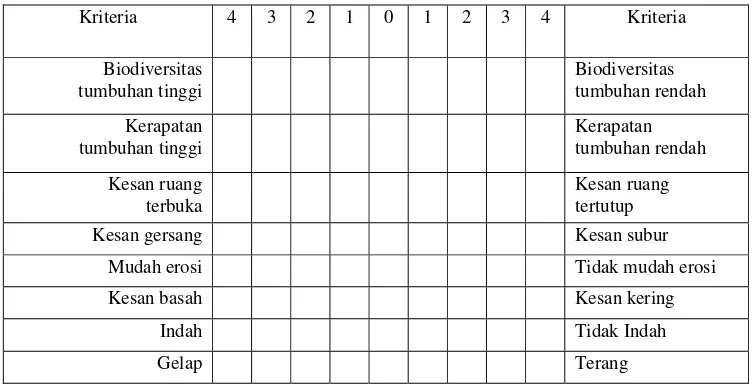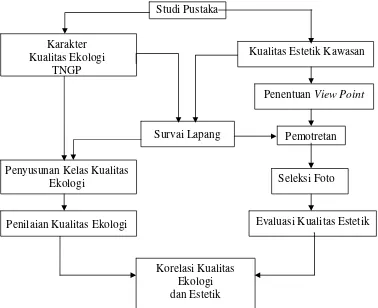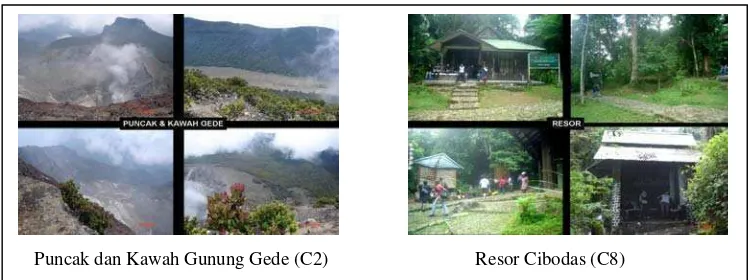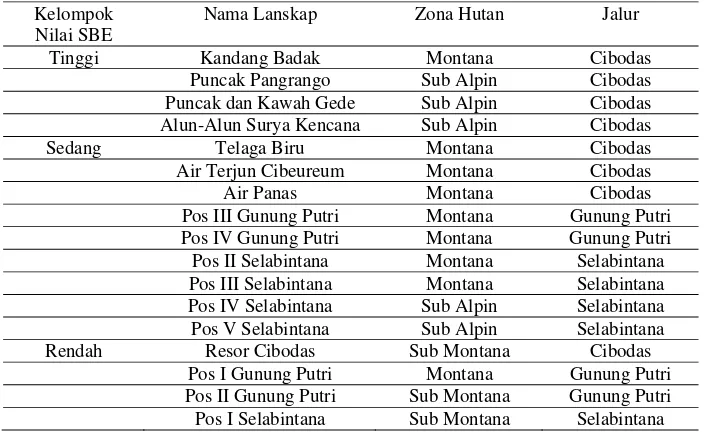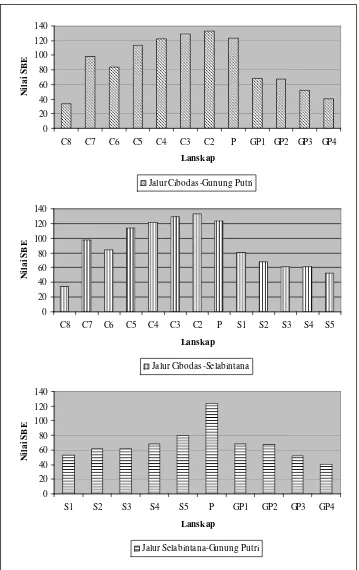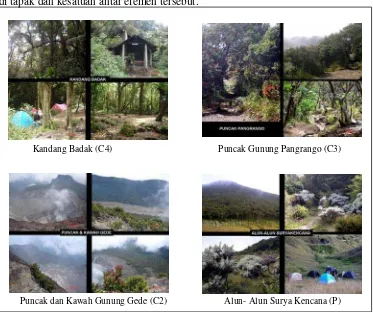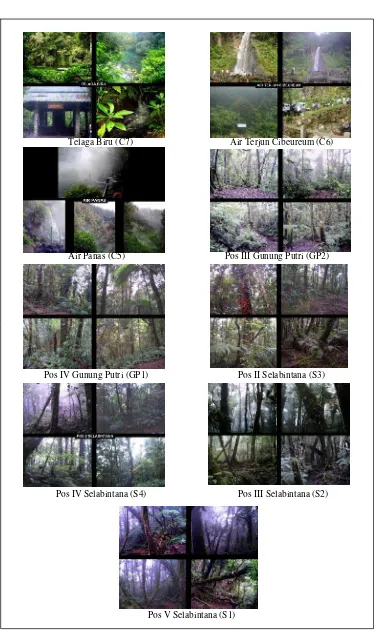TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO
Oleh
DIDIK YULIANTO
A34202008
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP
FAKULTAS PERTANIAN
INSTIT UT PERTANIAN BOGOR
DIDIK YULIANTO. Studi Kualitas Estetika dan Ekologi pada jalur Wisata Alam Taman Nasional Gede Pangrango. (Dibimbing oleh ANDI GUNAWAN dan AKHMAD ARIFIN HADI).
Taman Nasional Gede Pangrango merupakan kawasan dengan beragam tujuan, antara lain untuk konservasi dan rekreasi. Di dalam kawasan ini terdapat tiga jalur wisata alam, yaitu: jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana. Untuk mengetahui kondisi kualitas ekologi dan estetik pada ketiga jalur itu, maka dilakukan penelitian terhadap ketiganya.
Penelitian ini dimulai dengan studi pustaka untuk identifikasi karakter kualitas ekologi dan penentuan titik-titik lanskap di sepanjang jalur wisata alam TNGP. Hasil studi pustaka berupa karakteristik kualitas ekologi yang terdiri dari tujuh variabel, yaitu: biodiversitas, kerapatan, penutupan lahan, kesuburan, tingkat erosi, kelembaban, dan intensitas penyinaran. Sedangkan jumlah titik pengamatan ada 17 buah, terdiri dari 8 pos di jalur Cibodas, 4 pos di jalur Gunung Putri, dan 5 pos di jalur Selabintana. Kemmudian dilakukan pengambilan data sekunder dan data primer di lapangan. Data sekunder berupa kondisi umum lokasi, sedangkan data primer berupa data pengamatan karakteristik kualitas estetik dan ekologi, serta foto dari 17 pos.
Foto-foto lanskap TNGP dipresentasikan kepada responden dalam bentuk slide yang ditayangkan dengan program Microsoft Office Power Point 2003, dimana responden adalah mahasiswa Arsitektur Lanskap semester 6 yang berjumlah 46 orang. Hasil penilaian responden berupa data kualitatif untuk penduga nilai keindahan dan kualitas ekologi lanskap pada setiap pos. Data tersebut dianalisis dengan metode Scenic Beauty Estimation untuk penduga nilai keindahan dan Semantic Differential untuk penduga kualitas ekologi (Daniel dan Boster, 1976).
34.22), dengan demikian lanskap ini merupakan lanskap yang paling tidak disukai, karena terdapat bangunan di tapak yang membuat pemandangan menjadi kurang alami dan unik. Menurut hasil analisis pada ketiga jalur dapat diketahui bahwa rata-rata nilai keindahan lanskap di jalur Cibodas lebih tinggi dari kedua jalur lainnya. Penyebaran nilai keindahan mempunyai pola tertentu yang mengikuti pola ketinggian letak pos pada ketiga jalur, yaitu bertambahnya nilai keindahan seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat.
Pengamatan lebih lanjut adalah analisis karakteristik kualitas estetik pada kelompok keindahan lanskap tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil pengamatan ini dapat diketahui bahwa karakteristik yang meningkatkan nilai keindahan lanskap adalah dominasi tipe lanskap, keteraturan vegetasi yang tumbuh, dan variasi bentuk, tekstur, dan warna yang tinggi. Sedangkan karakteristik yang dapat mengurangi nilai keindahan adalah bentuk penggunaan lahan yang tidak alami, serta vegetasi yang terlalu rapat dan kurang teratur. Analsis terhadap kualitas ekologi menunjukkan bahwa kondisi ekologi pada jalur wisata alam TNGP relatif masih bagus, yang dicirikan oleh biodiversitas, kerapatan, penutupan lahan, dan kesuburan yang tinggi. Selanjutnya, hasil analisis korelasi antara karakteristik estetik dan ekologi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara keduanya.
TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO
Skripsi sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian
pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
Oleh
DIDIK YULIANTO
A34202008
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP
FAKULTAS PERTANIAN
INSTIUT PERTANIAN BOGOR
GEDE PANGRANGO
Nama
: Didik Yulianto
NRP
: A34202008
Program Studi
: Arsitektur Lanskap
Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Ir. Andi Gunawan, MSc.
Akhmad Arifin Hadi, SP
NIP. 131 681 404
NIP. 132 310 805
Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian
Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M.Agr.
NIP. 130 422 698
Penulis dilahirkan di Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 1984. Penulis meupakan anak ketiga dari enam
bersaudara dari Bapak Ramto Sunarto dan Ibu Sumarsih Ramto Sunarto.
Tahun 1996 penulis lulus dari SD Kragilan II Gantiwarno, kemudian pada
tahun 1999 penulis menyelesaikan studi di SLTPN II Klaten, Klaten. Selanjutnya
penulis lulus dari SMUN I Klaten, Klaten pada tahun 2002.
Tahun 2002 penulis diterima di IPB melalui jalur USMI. Penulis diterima
sebagai mahasiswa Program Studi Arsitektur Lanskap, Departemen Arsitektur
Lanskap, Fakultas Pertanian.
Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat,
hidayah dan karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan.
Terdorong oleh
keinginan untuk memahami arti penting kelestarian alam bagi kehidupan, dengan
jalan mempelajari adanya hubungan yang selaras antara keindahan dengan
keseimbangan lingkungan, maka penulis melakukan penelitian ini. Topik
penilitian ini adalah persepsi kualitas ekologi dengan kualitas estetik pada suatu
lanskap wisata alam. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasinal Gede
Pangrango (TNGP) yaitu pada jalur wisata alam Cibodas, Gunung Putri, dan
Selabintana.
Penulis menyampaikan terimakasih kepada Dr. Ir. Andi Gunawan MSc
dan Akhmad Arifin Hadi SP atas bimbingan dan pengarahannya selama kegiatan
penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada
staf TNGP, staff departemen Arsitektur Lanskap dan semua pihak atas segala
bantuannnya selama pelaksanaan penelitian. Kepada kedua orang tua, keluarga,
dan Wieke Oktaviani yang telah memberikan dukungan yang tulus baik moril
maupun materiil, penulis mengucapkan terimakasih.
Akhirnya, semoga hasil penelitian ini berguna bagi yang memerlukan.
Bogor, Agustus 2006
PENDAHULUAN ... 1
Latar Belakang ... 1
Tujuan ... 2
Kegunaan ... 2
TINJAUAN PUSTAKA ... 3
Taman Nasional ... 3
Tujuan dan Pengelolaan Taman Nasional ... 3
Zona Taman Nasional ... 4
Zona Pemanfaatan ... 5
Rekreasi ... 6
Dampak Rekreasi ... 6
Etika Lingkungan dan Konsep Wisata Berkelanjutan ... 8
Ekoturisme ... 8
Potensi Suplai Rekreasi ... 10
Transportasi dan Pelayanan ... 10
Informasi dan Promosi ... 11
Atraksi ... 12
Ekologi Lanskap ... 13
Pendekatan Ekologi dan Kualitas Ekologi ... 15
Persepsi ... 16
Estetika Lingkungan ... 16
Kualitas Estetika ... 17
Elemen Pengalaman Estetik ... 18
Evaluasi Kualitas Estetik ... 19
Metode Pendugaan Nilai Keindahan ... 19
Evaluasi Lanskap dengan Menggunakan Model SBE ... 20
METODOLOGI ... 22
Tempat dan Waktu Penelitian ... 22
Metode Penelitian ... 22
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30
Kondisi Umum Lokasi ... 30
Evaluasi Kualitas Estetik ... 34
Kecenderungan Nilai Estetik pada Tiga Alternatif Jalur ... 37
Karakteristik Kualitas Estetik ... 39
Evaluasi Karakteristik Kualitas Ekologi pada Jalur Wisata Alam TNGP ... 45
Korelasi Kualitas Ekologi dan Estetik ... 50
Potensi Rekreasi ... 51
KESIMPULAN DAN SARAN ... 46
Kesimpulan ... 46
Saran ... 47
DAFTAR PUSTAKA ... 48
Nomor Halaman
Tabel 1. Tabel Kuesioner Semantic Differntial ... 27
Tabel 2. Hubungan Kelompok Keindahan Lanskap dengan
Zona Hutan dan Jalur ... 35
Tabel 3. Karakteristik Kualitas Ekologi pada Tiga Kelompok
Nomor Halaman
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Taman Nasional Gede-Pangrango ... 8
Gambar 2. Jalur Wisata Alam TNGP ... 19
Gambar 3. Bagan Alur Pelaksanaan Studi ... 13
Gambar 4. Lanskap dengan Nilai Keindahan Tertinggi dan Terendah ... 34
Gambar 5. Nilai SBE pada Tiga Jalur Wisata Alam ... 36
Gambar 6. Kecenderungan Nilai Keindahan pada Tiga Alternatif Jalur ... 38
Gambar 7. Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Tinggi ... 41
Gambar 8. Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Sedang ... 42
Gambar 9. Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Rendah ... 44
Gambar 10. Grafik Nilai Tengah Penilaian Variabel Ekologi untuk Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Tinggi ... 47
Gambar 11. Grafik Nilai Tengah Penilaian Variabel Ekologi untuk Kelompok Lanskap dengan Kualitas Keindahan Sedang ... 48
Nomor Halaman
1. Format Kuesioner SBE ... 56
2. Format Kuesioner Semantic Differential ... 57
3. Foto-Foto Lanskap dan Hasil Perhitungan SBE ... 58
4. Hasil Perhitungan SBE ... 60
5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Nilai SBE ... 65
6. Hasil Uji Beda Nilai Keindahan pada Tiga Jalur ... 66
Latar Belakang
Pelestarian alam merupakan upaya penting dalam memelihara
keberlanjutan sumberdaya alam. Jaminan keberlanjutan alam menjadi inti dari
konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan
alam yang menekankan pada asas manfaat jangka panjang. Pemanfaatan alam
bukan menjadi milik generasi sekarang, tetapi juga menjadi milik generasi
mendatang, sehingga sumberdaya alam harus tetap lestari. Untuk itu setiap bentuk
pemanfaatan alam harus berpegang pada asas pelestarian, tidak terkecuali pada
taman nasional (Soemarwoto, 1991; Turner et al. 2001).
Pemanfaatan taman nasional sebagai tempat pariwisata dan rekreasi
menjadi salah satu tanggapan atas kebutuhan masyarakat terhadap pariwisata dan
rekreasi. Taman nasional menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat, karena
kondisinya yang masih alami dan mempunyai pemandangan yang indah. Sebagai
tempat wisata yang masih alami dan pemandangannya indah, taman nasional
sesuai dengan kecenderungan minat masyarakat dewasa ini, di mana mereka lebih
menyukai kegiatan wisata atau rekreasi ke tempat yang alami dan indah
(Lindberg, 1993).
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) adalah salah satu
tempat rekreasi untuk masyarakat luas. Lokasinya berada di Propinsi Jawa Barat,
dan termasuk dalam tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur,
dan Kabupaten Sukabumi (Haris, 2001). Taman nasional ini menjadi salah satu
tempat rekreasi pilihan bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di
kota-kota di dekat TNGP. Kegiatan rekreasi alam oleh pengunjung TNGP antara
lain pendakian gunung dan berkemah. Kegiatan pendakian gunung menjadi
pilihan para pengunjung karena dapat memberikan suatu pengalaman berbeda dari
bentuk kegiatan rekreasi alam lainnya. Pengunjung menyukai kegiatan ini karena
tantangannya, pemandangan yang indah di sepanjang jalur, dan manfaat pelajaran
Potensi kegiatan rekreasi alam yang dapat ditawarkan pada setiap tempat
berbeda, karena karakteristik masing-masing tempat berbeda termasuk dalam hal
ekologi dan kualitas visualnya. Karakter ekologi dan kualitas visual yang unik
dapat memberi nilai tambah dan daya tarik tersendiri dari suatu kawasan, karena
menjanjikan suatu pengalaman yang berbeda pula bagi pengunjung. Taman
Nasional Gede Pangrango memiliki karakteristik kawasan yang unik, baik dari
segi ekologi maupun kualitas visualnya. Kedua faktor ini menentukan penilaian
potensi penyediaan rekreasi pada taman nasional. Penilaian ini sejalan dengan
konsep lanskap ekologis sekaligus estetik yang sesuai dengan isu pembangunan
yang berkelanjutan. Hal yang ingin dicapai darinya sangat jelas, yaitu
terwujudnya keselarasan kepentingan manusia dengan kelestarian alam. Menurut
Thorne dan Huang (1990) dasar konsep ini adalah evaluasi pola spasial tapak serta
pengaruhnya terhadap integritas ekologi lanskap dan daya tarik estetik. Lebih
lanjut dijelaskan dua langkah pokok penerapan konsep tersebut adalah evaluasi
kualitas lingkungan, yaitu: kualitas lingkungan fisik, bentuk teknologi dan
budidaya, serta evaluasi daya tarik estetik, yaitu: penilaian oleh indera manusia,
arti simbolik tapak, dan nilai positif emosional tapak.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mempelajari karakteristik
kualitas estetik dan kualitas ekologi serta hubungan antara keduanya pada jalur
wisata alam Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP).
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak
yang terkait dalam pengembangan dan pengelolaan tapak. Dan sebagai
Taman Nasional
Taman nasional merupakan kawasan dengan ekosistem yang masih asli
dan fungsi utamanya untuk pelestarian alam. Secara umum taman nasional
dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya,
pariwisata, dan rekreasi. Untuk mendukung berbagai kegiatan pemanfaatan
tersebut dan menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan, maka pengelolaan
taman nasional harus berdasarkan sistem zonasi (Undang-Undang RI No. 5 tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem).
Tujuan dan Pengelolaan Taman Nasional
Pemanfaatan taman nasional harus dengan pengelolaan yang baik dan
jelas. Menurut Miller (1978) tujuan yang harus dijadikan pedoman dalam
pengelolaan taman nasional adalah :
1. Untuk memelihara unit-unit biotik utama untuk melestarikan fungsinya
dalam ekosistem
2. Untuk menjaga keanekaragaman hayati dan hukum lingkungan
3. Untuk melindungi kekayaan sumberdaya plasma nutfah
4. Untuk memelihara obyek, struktur dan tapak peninggalan atau warisan
kebudayaan
5. Untuk melindungi panorama alam yang indah
6. Untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pemantauan
lingkungan di dalam areal alamiah
7. Untuk menyediakan fasilitas kegiatan rekreasi dan wisata
8. Untuk mendukung pembangunan atau pengembangan daerah pedesaan dan
penggunaan lahan marginal secara rasional
9. Untuk memelihara produksi dan kelestarian daerah aliran sungai
10. Untuk mengendalikan erosi dan pengendapan serta melindungi investasi
Tujuan pengelolaan taman nasional dapat dicapai jika dalam
pelaksanaannya digunakan sebuah sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan
taman nasional perlu menggunakan sistem pengaturan ruang pemanfaatan yang
jelas dan tidak tumpang tindih. Pengaturan ruang ini perlu dilakukan di dalam
kawasan, karena bentuk pemanfaatan dan fungsi taman nasional tidak hanya satu
jenis, contohnya konservasi dan rekreasi. Kegiatan konservasi dan rekreasi
mempunyai bentuk dan sifat kegiatan yang berbeda, selain itu hasil dan dampak
dari kedua jenis pemanfaatan ini juga berbeda. Kedua bentuk pemanfaatan ini
mempunyai cara pengelolaan yang berbeda, sehingga antara ruang konservasi dan
rekreasi harus mempunyai batas yang jelas. Untuk penetapan batas–batas ruang
kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sitem zonasi (MacKinnon, 1993).
Zona Taman Nasional
Menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pengelolaan kawasan taman nasional
menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan cara pengaturan kegiatan
yang berdasarkan pada pembagian ruang. Pada umumnya kawasan taman nasional
terbagi dalam beberapa zona, yaitu:
1. Zona Inti
Zona inti merupakan zona dengan persyaratan yang ketat. Manusia dapat
melakukan kegiatan di dalam zona inti, tetapi kegiatan tersebut tidak boleh
menyebabkan perubahan apapun pada ekosistem kawasan. Bentuk kegiatan
yang dapat dilakukan adalah kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, dan kegiatan penunjang budi daya.
2. Zona Pemanfaatan
Zona pemanfaatan merupakan zona yang mempunyai bentuk kegiatan paling
luas. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam zona pemanfaatan adalah
kegiatan pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pendidikan, pemulihan jenis tumbuhan dan satwa asli, dan
kegiatan penunjang budi daya. Selain itu pembangunan sarana pariwisata alam
3. Zona khusus
Zona khusus adalah zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan. Zona khusus
biasanya memiliki kondisi dan fungsi yang khas. Zona khusus dapat berupa
zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, dan zona rehabilitasi.
Zona Pemanfaatan
Berdasarkan intensitas pemanfaatannya, maka zona pemanfaatan
dibedakan ke dalam zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan terbatas.
Zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan terbatas mempunyai perbedaan
pada bentuk dan arah pengembangan wisatanya, terutama dalam pembangunan
fasilitas untuk pengunjung. Fasilitas yang dibangun di dalam zona pemanfaatan
intensif dapat bersifat permanen, sedang fasilitas di dalam zona pemanfaatan
terbatas bersifat nonpermanen. Fasilitas permanen yang dapat dibangun di dalam
zona pemanfaatan intensif seperti bangunan administratif, pelayanan umum,
tempat parkir, kantor staf, instalasi pekerjaan umum, shelter, kantin, bumi
perkemahan, dan fasilitas khusus lainnya. Sedangkan pengadaan fasilitas rekreasi
di dalam zona pemanfaatan terbatas diupayakan seminimal mungkin, contoh
tempat MCK tidak permanen (Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990).
Penetapan setiap zona harus berdasarkan pada kriteria tertentu yang sesuai
dengan fungsi dan tujuannya. Menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990
kriteria penetapan zona pemanfaatan adalah:
1. Mempunyai obyek wisata yang menarik dan mempunyai potensi untuk
menjadi pusat kegiatan pariwisata alam.
2. Mempunyai kondisi lingkungan yang memungkinkan pembangunan
sarana dan prasarana pengunjung.
3. Memiliki topografi lahan yang relatif datar dan mempunyai jenis tanah
yang tidak tahan erosi.
4. Memiliki penutupan vegetasi tidak terlalu rapat dan ruang yang cukup
terbuka.
Rekreasi
Rekreasi merupakan salah bentuk aktivitas manusia untuk mengisi waktu
luangnya. Manusia melakukan rekreasi untuk menghilangkan beban pikiran
akibat tekanan dan rutinitas pekerjaannya. Rekreasi dapat memulihkan kondisi
mental dan fisik yang lelah, serta memberikan kepuasan rasa senang bagi manusia
(Brockman, 1979; Soekotjo, 1980; Soemarwoto, 1991). Minat masyarakat
terhadap rekreasi mulai meningkat sejak awal tahun 90-an, terutama minat
terhadap obyek wisata alam. Latar belakang fenomena tersebut adalah
meningkatnya tekanan hidup karena rutinitas kerja dan beban aktivitas yang berat,
sehingga mereka membutuhkan akivitas yang dapat mengembalikan semangat
kerjanya (Lindberg, 1993).
Berdasarkan tempatnya, Mercer (1981) menggolongkan rekreasi menjadi
dua, yaitu rekreasi di tempat tertutup dan rekreasi di tempat terbuka. Lebih lanjut
dinyatakan bahwa rekreasi di tempat terbuka lebih baik karena dapat diperoleh
pengalaman yang khas, baru dan berbeda. Brockman (1979) mengemukakan
kelebihan rekreasi di alam terbuka adalah pengalaman yang lebih baik bagi fisik
dan mental manusia, karena untuk melakukan rekreasi di alam terbuka manusia
harus mempunyai kesehatan fisik, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan.
Bentuk kegiatan rekreasi di alam terbuka adalah memancing, berburu, mendaki
gunung, berkuda, piknik, dan berkemah.
Pilihan bentuk kegiatan rekreasi yang akan dilakukan manusia tergantung
pada latar belakang ketersediaan kesempatan, kesesuaian dengan kondisi pelaku,
serta kemampuan fisik dan intelektual. Bentuk kegiatan rekreasi dapat bersifat
fisik, intelektual, estetik, emosi, atau kombinasinya. Karena latar belakang dan
sifat yang berbeda, maka bentuk kegiatan rekreasi menjadi spesifik bagi setiap
individu, dimana pilihan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya
(Brockman, 1979).
Dampak Kegiatan Rekreasi
Pembangunan sektor wisata dewasa ini terus meningkat dan membuka
kesempatan baru dalam lapangan kerja. Kemajuan ini memberikan hasil yang
negatif bagi lingkungan dan manusia. Menurut Gunn (1997) dampak negatif
tersebut adalah:
1. Terjadinya pencemaran lingkungan di lokasi wisata, sehingga
menyebabkan degradasi sumber daya alam.
2. Tergesernya budaya masyarakat lokal yang diakibatkan oleh desakan
budaya luar dari wisatawan.
3. Timbulnya biaya ekonomi tambahan yang diakibatkan oleh tindakan
pengembangan wisata yang tidak sesuai kemampuan sumber daya alam.
4. Bentuk tata guna lahan menjadi tidak terpadu, sebagai akibat dari
pembangunan wisata tidak memperhatikan peraturan tata guna lahan.
5. Kualitas sumber daya tapak berkurang, karena pengembangan bentuk
kegiatan wisata, atraksi, fasilitas pelayanan yang tidak sesuai dengan
kondisi tapak.
6. Kerusakan kualitas tapak yang diakibatkan oleh tindakan cut and fill pada
terhadap bentuk lahan yang asli dan introduksi spesies tanaman dan hewan
yang baru. Tindakan tersebut meningkatkan resiko bahaya erosi dan
hilangnya spesies asli di tapak.
Dampak negatif dari kegiatan rekreasi secara garis besar disebabkan oleh
dua faktor, yaitu faktor pengelola dan faktor pengunjung. Pertama, faktor yang
berasal dari pengelola antara lain: 1) Kegiatan pengembangan tapak yang tidak
sesuai dengan daya dukung dan kemampuan tapak, contoh ukuran tapak yang
tidak sebanding dengan jumlah dan intensitas pengunjung, 2) Kegiatan
pengelolaan yang tidak optimal, contoh manajemen pengelolaan sampah yang
tidak tepat. Kedua, faktor yang berasal dari pengunjung antara lain: 1) Tindakan
vandalisme, 2) Tindakan membuang sampah sembarangan, 3) Pencemaran air
oleh bahan-bahan kimia dari pasta gigi dan sabun yang berasal dari pengunjung.
Etika Lingkungan dan Konsep Wisata Berkelanjutan
Menurut Gunn (1997) etika lingkungan merupakan turunan dari etika
tapak. Etika lingkungan merupakan pernyataan tentang penghargaan dan
pengakuan terhadap hak hidup tumbuhan, binatang, dan seluruh isi alam. Lebih
lanjut dinyatakan bahwa tumbuhan, binatang, dan alam mempunyai hak yang
setara dengan manusia.
Konsep wisata berkelanjutan merupakan jawaban atas permasalahan yang
terjadi dalam pembangunan wisata. Konsep wisata berkelanjutan mengikuti
konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga mempunyai prinsip dasar yang
sama. Prinsip dasar yang dipegang adalah pembangunan yang ramah lingkungan,
yaitu dengan tercapainya keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial dan
lingkungan. Syarat untuk suksesnya pembangunan berkelanjutan adalah integrasi
serta kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Langkah
pertama untuk menciptakan integritas dan kerjasama ketiga pelaku pembangunan
tersebut adalah pemahaman dan penanaman makna dasar serta tujuan utama dari
konsep pembangunan berkelanjutan (Gunn, 1997; Lindberg, 2001).
Menurut Gunn (1997) dimensi yang harus diperhatikan dalam
pembangunan wisata berkelanjutan ada tiga, yaitu: 1) Jenis wisata harus sesuai
dengan kondisi sumber daya tapak, 2) Ketersediaan sumber daya yang
menentukan tingkat dan arah pembangunan wisata, dan 3) Perbandingan antara
jumlah kunjungan nyata ke tapak dengan jumlah kunjungan yang potensial.
Ekoturisme
Bentuk pariwisata yang sesuai dengan konsep sadar dan ramah lingkungan
adalah ekoturisme. Karena bentuk pariwisata ini mampu menanggapi respon
adanya dampak negatif dari kegiatan pariwisata komersial dan massal selama ini.
Dengan demikian kehadiran ekoturisme merupakan jawaban atas kepentingan
terhadap pelestarian sumber daya alam dan adanya permintaan terhadap wisata
Menurut Gunn (1997) hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam
ekoturisme adalah:
1. Pengalaman, penghargaan, pemahaman terhadap sumber daya alam
2. Perolehan pengalaman yang berasal dari lingkungan dan penghargaan
terhadap lingkungan
3. Penggunaan fasilitas pelayanan dan pendukung yang ramah lingkungan
4. Memberikan kontribusi langsung bagi pembangunan ekonomi lokal
Ketertarikan masyarakat terhadap ekoturisme dilatarbelakangi oleh
beberapa alasan, dimana alasan tersebut bervariasi antar individu. Kesamaan
alasan dapat ditemukan pada bentuk kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai.
Menurut Gunn (1997) bentuk kegiatan dan tujuan pengunjung dalam ekoturisme
adalah:
1. Mengetahui tempat baru atau mendapatkan pengalaman yang baru
2. Mendapatkan pengalaman hidup di alam bebas
3. Mendapatkan suasana tempat rekreasi yang tenang
4. Melakukan aktivitas di tapak seperti berkemah, hiking
5. Melakukan kegiatan wisata air seperti memancing, olahraga arung jeram,
berenang, dan bersampan
6. Melihat atraksi budaya lokal
7. Mempelajari atau mengamati alam dan budaya masyarakat lokal secara
langsung
8. Melihat dan mengenal kehidupan alam bebas seperti kegiatan mengamati
kehidupan burung, orang hutan, dan kera
9. Menikmati pemandangan yang indah atau alami seperti laut, pantai, danau,
pegunungan dan air terjun
10. Menyalurkan hobi fotografi
Potensi Suplai Rekreasi
Potensi suplai rekreasi adalah peluang pengembangan suatu tapak untuk
penyediaan kegiatan rekreasi. Pengembangan suatu tapak menjadi tempat rekreasi
harus memperhitungkan dua hal, yaitu: 1) kondisi permintaan masyarakat
terhadap kebutuhan wisata, dan 2) Penawaran jasa wisata yang tersedia.
(Lindberg, 1993; Gunn, 1997). Lebih lanjut Gunn (1997) mengemukakan bahwa
penawaran dan permintaan dalam wisata mempunyai hubungan yang dinamis dan
saling berpengaruh, dimana perubahan pada jumlah permintaan akan
mempengaruhi jumlah penawaran.
Menurut Gunn (1997) komponen yang membentuk penawaran ada lima,
yaitu : atraksi, pelayanan, transportasi, informasi, dan promosi. Karakteristik dan
kondisi komponen penawaran tersebut berbeda pada setiap tempat. Perbedaan
tersebut disebabkan perbedaan kondisi sumber daya alam, fisik lokasi, dan sosial
budaya masyarakatnya.
Transportasi dan Pelayanan
Transportasi merupakan penghubung antara pengunjung dengan lokasi
wisata. Pengembangan bidang trasnportasi perlu memperhatikan masalah jaringan
jalan dan sarana transportasi, yaitu yang mampu mendukung kelancaran dan
kenyamanan pengunjung. Menurut Gunn (1997) pengembangan transportasi yang
seimbang harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:
1. Kemampuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat
2. Mengutamakan kelancaraan aksesibilitas
3. Keseimbangan antara penggunaan lahan untuk pembangunan sarana
transportasi dengan penggunaan lahan yang lain
4. Menggunakan pendekatan matematika dalam perhitungan kapasitas lalu
lintas jalan, untuk mengetahui perkiraan batas jumlah maksimum dan
minimum kendaraan yang melewati jalan
5. Membuat rancangan hirarki jalan untuk jalur pejalan kaki, sepeda, motor,
6. Memperhatikan fungsi sosial dan aktifitas lain yang ada di dekat jalur
transportasi
7. Penyediaan area parkir kendaraan
8. Pembuatan rancangan harus berdasarkan skala manusia
9. Pembangunan sarana transportasi mampu menambah nilai estetik
Pelayanan dan fasilitas yang baik akan meningkatkan daya tarik tempat
wisata. Pengembangan jenis pelayanan dan fasilitasnya harus memperhatikan
kondisi dan karakteristik setempat. Selain itu kegiatan pengembangan pelayanan
dan fasilitas harus menjaga keserasian dengan kondisi eksisting (Gunn, 1997).
Lebih lanjut Gunn (1997) menyatakan bahwa penyediaan bentuk pelayanan dan
fasilitas dapat dilakukan oleh pengelola resmi tempat wisata, pemerintah, atau
swasta. Pengelola resmi umumnya menyediakan pelayanan dan fasilitas yang
bersifat umum, contoh: tempat informasi, lapangan parkir, tempat pendaftaran dan
tempat ibadah. Sedangkan penyediaan layanan rumah makan, tempat belanja
suvenir dan makanan, atau penginapan biasanya dilakukan oleh swasta.
Informasi dan Promosi
Harapan pengunjung saat mengunjungi tempat wisata adalah ingin
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, karena itu mereka membutuhkan
informasi yang cukup tentang tempat wisata sebelum mereka mengunjunginya.
Informasi yang cukup juga membantu calon pengunjung menetapkan pilihan
tempat dan waktu kunjungan yang tepat. Menurut Gunn (1997) informasi penting
yang harus disampaikan ke masyarakat atau calon pengunjung antara lain:
1. Letak tempat wisata
2. Jenis atraksi dan bentuk kegiatan yang ditawarkan
3. Jenis pelayanan dan fasilitas pendukung yang tersedia
4. Alternatif rute jalan menuju tempat wisata dan perkiraan biaya perjalanan
Promosi merupakan bagian upaya penyampaian informasi ke masyarakat
yang berupa gambaran tentang tempat wisata. Bentuk dan strategi promosi secara
adalah bentuk promosi yang sengaja dilakukan oleh pengelola. Media promosi
resmi umumnya berupa media periklanan, yaitu media massa dan media
elektronik. Selain itu pengelola dapat mempromosikan tempat wisatanya melalui
jaringan informasi yang melibatkan kerjasama dengan penyedia jasa hotel atau
restoran. Sedangkan bentuk promosi tidak resmi merupakan akibat tidak langsung
dari tingkat kepuasan pengunjung. Pengunjung akan menceritakan
pengalamannya ke orang lain, sehingga orang lain menjadi tertarik untuk
berkunjung ke tempat wisata tersebut. Jadi promosi tidak langsung adalah
promosi yang berasal dari upaya pengelola dalam menciptakan citra baik ke
pengunjung (Gunn, 1997).
Atraksi
Menurut Gunn (1997) atraksi merupakan inti dari wisata. Atraksi
merupakan bentuk kegiatan atau suasana tapak yang menjadi daya tarik utama
tempat wisata. Atraksi wisata dapat dikelompokkan dalam dua kelompok umum,
yaitu touring circuit dan longer stay. Touring circuit adalah pengunjung menikmati atraksi selama perjalanan dan dalam waktu pendek, sehingga
pengunjung tidak perlu menginap. Contoh touring circuit adalah wisata pantai,
pemandangan pegunungan, dan air terjun. Sedangkan longer stay adalah
pengunjung menikmati atraksi dalam waktu lama, sehingga pengunjung perlu
menginap, contoh wisata budaya.
Bentuk atraksi yang ditampilkan tergantung potensi lingkungan dan sosial
budaya, karena adanya perbedaan karakteristik lingkungan dan sosial budaya yang
dimiliki setiap tempat wisata. Karakteristik lingkungan ditentukan oleh jenis
vegetasi, bentuk kehidupan alami di tapak, kualitas air, bentuk topografi tapak,
dan iklim. Sedangkan karakteristik sosial budaya tergantung karakteristik
masyarakat pendukung tapak (Gunn, 1997). Lebih lanjut Gunn (1997)
menyatakan bahwa kekayaan fisik lingkungan, kekayaan alam dan budaya, serta
kualitas merupakan unsur esensial yang mendukung kenyamanan pengunjung,
Fungsi taman nasional sebagai tempat rekreasi dapat menjadi alternatif
bagi masyarakat dalam memilih tempat rekreasi. Kondisi taman nasional yang
masih alami sesuai dengan minat masyarakat dewasa ini, karena perkembangan
permintaan masyarakat terhadap rekreasi mengarah pada obyek wisata yang masih
alami. Latar belakang terjadinya peningkatan minat terhadap obyek wisata alam
adalah ketertarikan masyarakat terhadap keindahan alam dan kondisi
lingkungannya yang masih alami. Masyarakat berharap mendapatkan kepuasan
fisik dan mental dengan melihat keindahan alam (Lindberg, 1993).
Penyediaan rekreasi harus mempertimbangkan dampak dari kegiatan
pengunjung. Pengetahuan tentang dampak yang mungkin timbul dan upaya
pengelola untuk meminimalisir dampak dapat menjamin kualitas lingkungan dan
keindahan obyek rekreasi (Gold, 1980; Lindberg, 1993). Lebih lanjut dinyatakan
bahwa dalam pengembangan tapak untuk rekreasi diperlukan pendekatan yang
tepat, agar kegiatan rekreasi sesuai dengan kemampuan tapak. Alat pendekatan
yang sesuai dengan tujuan pemeliharaan kualitas keindahan dan lingkungan
adalah pendekatan ekologi lanskap. Orientasi utama pendekatan ekologi lanskap
adalah perlindungan kualitas visual lanskap dan ekologi.
Ekologi Lanskap
Kegiatan pembangunan menyebabkan perubahan pola ruang dan
perubahan hubungan antar elemen dalam ruang. Perubahan pada pola ruang akan
berakibat pada perubahan proses ekologi di dalamnya. Perubahan proses ekologi
dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa kondisi
lingkungan yang seimbang dan lestari. Sedangkan dampak negatif berupa
kerusakan lingkungan (Merriam, 1994; Turner et al. 2001).
Ekologi lanskap memberikan suatu konsep, teori, dan metode baru dalam
memahami interaksi yang dinamis dalam ekosistem berdasarkan pola ruang.
Pemahaman proses ekologi di dalam tapak dapat membantu pengambilan
keputusan pembangunan yang tepat. Dengan demikian hasil yang diharapkan dari
kegiatan pembangunan berupa hasil yang positif (Thorne dan Huang,1990;
Prinsip utama dalam ekologi lanskap adalah integritas ruang dan proses
ekologi di dalamnya. Keterkaitan antar ruang merupakan implikasi logis dari
proses ekologi, karena proses ekologi dalam suatu tapak tidak dapat terlepas dari
lingkungan sekitarnya. Jalinan proses ekologi antar tapak terjadi melalui aliran
massa dan energi. Aliran massa dan energi terjadi dalam bentuk perpindahan
unsur-unsur atau mineral melalui gerakan air, udara, dan gravitasi (Thorne dan
Huang, 1990; Merriam, 1994; Turner et al. 2001)
Skala pembangunan lanskap mempunyai selang yang lebar. Contoh
pembangunan lanskap berskala kecil adalah lanskap rumah, sedang yang berskala
besar adalah lanskap wilayah kota, taman nasional, dan hutan. Semakin besar
skala pembangunan lanskap berarti semakin kompleks proses ekologi di
dalamnya, sehingga hal ini memerlukan pedoman yang tepat dalam
pelaksanaannya. Menurut Merriam (1994) terdapat tiga pedoman dasar dalam
skala pembangunan lanskap yang besar, yaitu:
1. Komposisi lanskap yang menjadi sumber daya dan pembentuk tapak serta
mempengaruhi lingkungan di dalam tapak. Sumber daya atau habitat yang
penting harus mendapat perhatian utama. Jenis sumber daya yang penting
adalah sumber daya yang mempengaruhi keberadaan spesies di dalam
tapak. Jika sumber daya atau habitat ini rusak maka berakibat pada
hilangnya spesies tertentu.
2. Pola ruang harus mendukung proses ekologi di dalam tapak. Pola ruang
harus memperhatikan bentuk dan ukuran ruang. Elemen pengaturan pola
ruang adalah perimeter ruang, rasio ruang, dan jarak antar ruang yang
membatasi spesies dengan perilaku berbeda. Pembatasan dan pengaturan
jarak antar ruang dapat mencegah persaingan antar spesies dalam mencari
makan dan berkembang biak.
3. Upaya antisipasi terhadap bentuk gangguan yang potensial di masa depan.
Gangguan tersebut dapat berupa gangguan manusia, pencemaran
Pendekatan Ekologi dan Kualitas Ekologi
Menurut Gold (1980) pendekatan ekologi merupakan penilaian
karakteristik ekologi melalui serangkaian analisis terhadap faktor-fakor ekologi
serta hubungan di antara faktor-faktor tersebut. Penjelasan tentang kondisi setiap
faktor dan hubungan di antaranya dapat digunakan untuk penjelasan kondisi
ekologinya. Secara umum faktor-faktor ekologi tersebut terbagi dalam tiga-
sumber daya tapak yang paling dasar, yaitu:
1. Lingkungan atmosfer yang terdiri dari udara, uap air, dan mikroorganisme.
2. Lingkungan air yang terdiri dari air, tumbuhan, binatang, mikroorganisme,
dan habitat.
3. Lingkungan tanah yang terdiri dari tanah, tumbuhan, binatang,
mikroorganisme dan habitat.
Udara, air, tanah, tumbuhan dan hewan merupakan komponen proses
ekologi di alam. Dalam proses di alam dijelaskan bahwa udara berhubungan
dengan metabolisme tumbuhan dan isolasi. Sedang air mempunyai peran yang
penting dalam proses metabolisme tumbuhan dan hewan untuk proses respirasi
dan regulasi. Lebih jauh tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme berperan dalam
siklus rantai makanan, di mana siklus ini merupakan wujud dari aliran massa dan
energi (Gold, 1980; Wirakusumah, 2003). Lebih lanjut Wirakusumah (2003)
menyatakan bahwa aliran massa dan energi berada dalam kondisi seimbang jika
tidak ada kelas dalam mata rantai makanan yang terganggu. Dalam kondisi
demikian dapat dinyatakan bahwa kualitas ekologinya bagus, karena terjadi
keseimbangan distribusi massa dan energi.
Kualitas ekologi adalah derajat penilaian yang menggambarkan status
keadaan lingkungan di suatu tapak Status keadaan lingkungan disebut baik jika
nilai kualitasnya tinggi dan sebaliknya. Penilaian kualitas ekologi suatu tapak
memerlukan indikator yang berasal dari komponen ekologi. Komponen ekologi
merupakan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif atau dijelaskan secara
kualitatif. Komponen tersebut adalah siklus energi, kestabilan lingkungan abiotik,
daya lenting lingkungan, suksesi ekologi, biodiversitas, nilai unik tapak, dan
Persepsi
Persepsi merupakan suatu gambaran, pengertian, serta interpretasi
seseorang terhadap suatu obyek, terutama bagaimana orang menghubungkan
informasi yang diperolehnya dengan diri dan lingkungan dimana dia berada.
Bentuk persepsi tersebut berbeda pada setiap orang, karena pengaruh latar
belakang intelektual, pengalaman emosional, pergaulan, dan sikap seseorang.
Sedangkan, kedalaman persepsi akan sebanding dengan kedalaman intelektual
dan semakin banyaknya pengalaman emosional yang dialami seseorang (Eckbo,
1964). Lebih lanjut Porteous (1977) menambahkan bahwa persepsi akan
menentukan tindakan seseorang terhadap lingkungannya.
Bentuk obyek yang diamati seseorang salah satunya adalah lanskap,
dimana seseorang akan melakukan persepsi terhadap lanskap yang sudah
diamatinya (Nasar, 1988). Lebih lanjut dinyatakan bahwa persepsi seseorang
terhadap kualitas suatu lanskap ditentukan oleh interaksi yang kuat antara variabel
lanskap dan pengetahuan seseorang terhadap lanskap tersebut. Hasilnya berupa
penilaian yang bagus atau tidak bagus. Tingkat penilaian tersebut tergantung pada
kepuasan perasaan seseorang terhadap lanskap tersebut.
Estetika Lingkungan
Lingkungan merupakan wadah bagi manusia untuk beraktifitas dan
berinteraksi dengan sesama manusia dan alam beserta isinya. Manusia selalu
melakukan persepsi dan interpretasi terhadap lingkungannya. Proses persepsi dan
interpretasi merupakan rangkaian tindakan manusia sebagai upaya mendapatkan
gambaran dari lingkungannya, sehingga manusia dapat menetapkan tindakan
selanjutnya terhadap lingkungan tersebut. Arah dan bentuk tindakan manusia
terhadap lingkungannya dapat berupa hal-hal yang positif atau negatif, dimana
pilihan tindakan tersebut sangat bergantung dari hasil persepsi dan interpretasi
sebelumnya. Tindakan yang positif seperti pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya alam dengan bijaksana merupakan hasil pemahaman yang benar terhadap
lingkungannya, sebaliknya tindakan negatif seperti perusakan dan pemborosan
terhadap sumber daya alam merupakan hasil pemahaman yang salah terhadap
dan interpretasi yang benar, sehingga manusia dapat menetapkan tindakan yang
benar dalam mengelola lingkungannya (Foster, 1982).
Estetika adalah sesuatu yang dirasakan oleh manusia sebagai hasil
hubungan yang harmonis dari semua elemen, baik itu elemen pada suatu obyek,
ruang maupun kegiatan. Estetika berkaitan erat dengan penilaian secara visual,
karena penampilan suatu obyek otomatis dinilai dari penampakkan visualnya
(Simonds, 1983; Nasar, 1988). Selanjutnya Heath (1988) menambahkan bahwa
manusia pada umumnya menyukai keindahan. Untuk itu manusia senantiasa
menjadikan lingkungannya tetap indah. Salah satu upaya yang dilakukan manusia
adalah perlindungan terhadap kualitas keindahan lingkungan.
Kualitas Estetika
Nilai estetik suatu tempat atau lanskap merupakan dimensi penting dalam
pengamatan ekologi dan kekuatan nilai estetik telah menjadi aspek utama dalam
tindakan konservasi. Perumusan kebijakan tentang estetik juga membawa pada
pemahaman yang baik atas masalah lingkungan. Sebagai contoh pemandangan
pegunungan yang masih alami dengan hutan yang gundul dimana tidak hanya
nilai estetiknya berbeda, tetapi kondisi ekologi keduanya juga berbeda. Nilai
estetik dapat menjadi salah satu alat ukur lingkungan, karena indera manusia
mampu menangkap dan membedakan kondisi lingkungan di sekitarnya melalui
indera penglihatan, pendengaran atau penciuman (Foster, 1982).
Penilaian terhadap kualitas estetik lingkungan menjadi alat yang relevan
dalam lingkup pengamatan lanskap alami maupun nonalami. Meskipun kualitas
estetik merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dimakan, tetapi dapat
memberikan kepuasan secara mental bagi manusia. Pemenuhan terhadap kepuasan
estetik merupakan puncak dari kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia
tidak hanya menghendaki kepuasan secara fisik, tetapi yang lebih utama adalah
kepuasan mental atau jiwa. Keindahan lingkungan sebagai salah satu alat
pemenuhan kebutuhan estetik perlu dipelajari dan dibuat metode penilaiannya,
sehingga lingkungan dapat dikelola dengan baik agar kualitas estetiknya dapat
Elemen Pengalaman Estetik
Kualitas estetik tapak akan menentukan pengalaman estetik pengguna
tapak tersebut. Inti pembentuk kualitas estetik adalah integritas elemen fisik dan
visual tapak. Elemen fisik tapak berupa bentuk lahan, tata guna lahan, mosaik
vegetasi, badan air. Sedangkan elemen visual berupa bentuk, ruang, skala, warna,
pola, komposisi dan hubungan antar elemen fisik (Gold, 1980; Foster, 1982).
Berikut ini penjelasan dari masing-masing elemen tapak:
1. Bentuk lahan merupakan tulang punggung dalam lanskap, dan secara
visual merupakan hasil gabungan dari bentuk lahan yang cembung dan
cekung. Karakteristik bentuk lahan adalah kontur (skyline silhouettes),
skala dan jarak pengulangan elemen, dan variasi permukaan (warna dan
penutupan vegetasi). Selain itu bentuk lahan yang khas seperti lembah dan
ngarai mempengaruhi bentuk ruang di tapak.
2. Mosaik vegetasi menentukan pola utama dari variasi visual permukaan
lanskap. Perbedaan bentuk fisik vegetasi, warna, teksur, skala, bentuk pola
utama, batas tepi, dan perubahan fisik karena musim merupakan unsur
dasar dari mosaik vegetasi.
3. Badan air merupakan elemen yang spesial dan langka dalam lanskap yang
alami. Keberadaannya tidak hanya menambah nilai estetik tapak, tetapi
juga menjadi pendukung kehidupan di sekitarnya. Dalam suatu lanskap,
badan air dapat menjadi pemandangan yang berdiri sendiri atau dapat juga
membentuk kesatuan pemandangan dengan vegetasi serta bentuk lahan di
dekatnya.
Menurut Foster (1982) pengamatan terhadap elemen tapak dapat melalui
pengamatan peta atau analisis laporan tertulis atau representasi grafis berupa foto,
diagram, dan sketsa. Bentuk hasil pengamatan visual terhadap elemen tapak dapat
dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: 1) Elemen yang berupa area seperti
danau, petak lahan sawah, petak kebun teh, dan petak hutan pinus; 2) Elemen
yang berupa koridor seperti sungai, jalan raya, dan jalan setapak. Lebih lanjut
dinyatakan bahwa pengamatan visual dapat memberikan hasil yang baik dan
skalanya. Hasil pengamatan setiap unit memberikan gambaran kondisi yang
berbeda. Kondisi setiap unit biasanya bergantung pada karakteristik spasial serta
hubungan antara bentuk lahan, vegetasi, dan badan air di dalam unit tersebut.
Evaluasi Kualitas Estetik
Evaluasi kualitas estetik merupakan penilaian terhadap nilai keindahan
suatu lanskap. Evaluasi kualitas estetik dapat menggunakan tiga kriteria estetika,
yaitu kesatuan, variasi , dan kontras. Pertama, kesatuan adalah kualitas total
elemen yang terlihat menyatu dan harmonis. Dalam lanskap, kesatuan merupakan
ekspresi dari tipe komposisi lanskap. Salah satu tipe komposisi lanskap adalah
pemandangan yang dominan, contohnya pemandangan puncak gunung yang
terlihat menonjol dari lanskap sekitarnya. Kedua, variasi adalah banyaknya jenis
elemen dalam tapak dan hubungan antar elemen yang berbeda. Variasi atau
kekayaan sumber daya adalah dua hal yang dipandang penting oleh ahli biologi
dan seniman, karena variasi yang besar sama artinya dengan kualitas tapak yang
tinggi. Tetapi diperlukan juga kesatuan elemen disamping variasi elemen untuk
tercapainya kualitas tapak yang tinggi. Contoh variasi elemen dalam lanskap
adalah jenis pohon deciduous tumbuh di antara pohon berdaun jarum. Ketiga,
kontras adalah perbedaan antar elemen yang terlihat menonjol tetapi tetap
harmonis. Kontras dapat berupa perbedaan warna, tekstur, atau bentuk elemen
(Foster, 1982).
Metode Pendugaan Nilai Keindahan
Menurut Daniel dan Boster (1976) metode pendugaan nilai keindahan
merupakan alat pendekatan dalam penilaian kualitas estetik tapak atau lanskap
tertentu. Terdapat tiga metode umum dalam pendugaan nilai keindahan, yaitu:
1. Pengamatan deskriptif adalah bentuk metode yang digunakan secara
eketensif dalam representasi dan evaluasi kualitas lanskap. Hasil penilaian
kualitas keindahan digambarkan dalam karakter yang relevan dengan
lanskap, seperti rasa hangat, nyaman, keanekaragaman elemen, dan
harmonis. Penyajian hasil dapat berupa angka, dimana setiap karakter
karakter dijumlahkan. Nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh
karakter merupakan gambaran kualitas lanskap yang diamati.
2. Survei dan kuisioner adalah bentuk metode yang sudah digunakan secara
luas, dan hasil penilaian kualitas lanskap berdasarkan preferensi terhadap
setiap sampel. Preferensi yang tinggi terhadap sampel tertentu
menunjukkan nilai keindahan sampel tersebut juga tinggi.
3. Evaluasi persepsi pilihan adalah metode penilaian kualias lanskap yang
berdasarkan pendapat pengamat yang dipandang relevan. Penilaian
dilakukan tidak secara langsung di tapak, tetapi dengan foto atau slide
yang diambil dari tapak dan dianggap sesuai dengan kondisi tapak.
Masing-masing metode di atas mempunyai bentuk khusus untuk
penerapan secara praktis di lapangan. Salah satu metode khusus penilaian kualitas
keindahan adalah metode SBE (Scenic Beauty Estimation). Konsep yang
mendasari metode ini adalah keindahan merupakan hasil interaksi manusia dengan
alam, yaitu sebagai bentuk persepsi terhadap pemandangan lanskap melalui indera
penglihatannya (Daniel dan Boster, 1976).
Evaluasi Lanskap dengan Menggunakan Model SBE
Konsep yang mendasari metode ini adalah keindahan merupakan hasil
interaksi manusia dengan alam, yaitu sebagai bentuk persepsi terhadap
pemandangan lanskap melalui indera penglihatannya. Tahap pelaksanaan metode
SBE adalah pengambilan foto lanskap, penyajian foto dalam bentuk slide, dan
evaluasi penilaian kualitas keindahan. Tahap pertama, pengambilan foto
dilakukan secara acak pada sudut pandang 10 sampai 3600, dimana pemilihan
sudut pandang harus mewakili kondisi lanskap. Level pengambilan foto juga
harus sama dengan level mata manusia yang berdiri pada posisi normal. Tahap
kedua, foto setiap lanskap disusun sesuai kelompok lanskap, lalu dipresentasikan dalam bentuk slide. Penyusunan foto antar lanskap dibuat acak, sedangkan foto
untuk lanskap yang sama disusun dalam satu kelompok. Penilaian terhadap slide
dilakukan oleh pengamat. Pengamat dapat berupa individu atau kelompok. Selain
pengarahan harus bersifat netral dan tidak berpengaruh pada penilaian yang akan
dilakukan pengamat. Presentasi harus dilakukan sekali dan penilaian pengamat
berkisar pada nilai 0 (sangat jelek) dan 9 (sangat indah). Tahap ketiga, hasil
penilaian pengamat untuk setiap lanskap dikumpulkan dan diurutkan dari nilai
terkecil sampai tertinggi. Selanjutnya dilakukan analisis nilai keindahan secara
statistik deskriptif. Nilai keindahan yang diperoleh dapat dijadikan representasi
Waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP)
yang terletak di Propinsi Jawa Barat. Pengamatan secara langsung dilakukan di
tiga jalur wisata alam pada kawasan TNGP. Waktu penelitian dimulai dari bulan
[image:33.612.132.506.224.558.2]Februari 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Taman Nasional Gede-Pangrango
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode survai untuk pengumpulan data
ekologis dan pengambilan foto lanskap. Pengolahan data foto dengan
menggunakan metode Scenic Beauty Estimation (SBE), yang bertujuan untuk
menilai kualitas estetik lanskapnya. Sedangkan pengolahan data ekologi
menggunakan metode Semantic Differential (SD). Hasil pengolahan data ekologi
dan estetik dianalisis lebih lanjut dengan uji statistik, sehingga dapat diketahui
hubungan antara kualitas ekologi dan estetik tapak. Secara umum penelitian ini
dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan mencakup kegiatan studi pustaka, penentuan karakter kualitas
ekologi kawasan TNGP, dan penentuan titik pemotretan untuk penilaian
kualitas estetik kawasan.
2. Tahap Pegumpulan Data
Tahap pengumpulan data mencakup kegiatan pengumpulan data sekunder,
pengamatan karakter ekologi secara langsung di tapak, dan pengambilan foto
vantage point pada setiap pos. 3. Tahap pengolahan data
Tahap pengolahan data merupakan tahap penilaian kualitas ekologi, penilaian
kualitas estetika, uji multikolinearitas, dan korelasi karakter ekologi dengan
estetika.
Tahap Persiapan
Tahap kegiatan ini dimulai dengan studi pustaka. Hasil studi
pustaka berupa identifikasi karakter kualitas ekologi dan titik pemotretan di
sepanjang jalur wisata alam TNGP. Menurut Thompson dan Stainer (1997)
karakter kualitas ekologi berupa variabel-variabel ekologi, yaitu keanekaragaman
hayati, kerapatan vegetasi, tingkat penutupan, kesuburan tanah, kepekaan terhadap
erosi, tingkat kelembaban, dan intensitas cahaya. Variabel-variabel tersebut
dianggap sebagai indikator penilaian kualitas ekologi. Sedangkan yang menjadi
variabel estetik adalah nilai keindahan lanskap. Analisis kualitas ekologi juga
didukung dengan data sekunder dari masing-masing karakter ekologi.
Pengamatan kualitas ekologi dan estetika dilakukan pada titik lanskap
tertentu di sepanjang jalur wisata alam. Titik lanskap yang dipilih adalah pos-pos
perhentian sementara pengunjung saat melakukan kegiatan pendakian. Pada
pos-pos tersebut peluang pengunjung untuk menikmati pemandangan dan kondisi
pada tiga jalur pendakian utama di kawasan TNGP (Gambar 2). Ketiga jalur
tersebut adalah jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana. Pada
jalur Cibodas dipilih delapan pos pengamatan, yaitu: Resor (C8), Telaga Biru
(C7), Curug Cibeureum (C6), Air Panas (C5), Kandang Badak (C4), Puncak
Pangrango (C3), Puncak dan Kawah Gede (C2), dan Alun-Alun Surya Kencana
(P). Pada jalur Gunung Putri dipilih empat pos pengamatan, yaitu: pos 1 (C4), pos
2 (C3), pos 3 (C2), dan pos 4 (C1). Dan di jalur Selabintana dipilih lima pos
[image:35.612.135.507.246.686.2]pengamatan, yaitu: pos 1 (C5), pos 2 (C4), pos 3 (C3), pos 4 (C2), dan pos 5(C1).
Gambar 2. Jalur Wisata Alam TNGP
S1
S3
S5 S4
Pintu Masuk Selabintana
C7
C6
C5
C4
C8
GP4
GP3
P
GP2
GP1 C2
C3
Pintu Masuk Cibodas
Pintu Masuk Gn. Putri
S2 Ket:
Zona Sub Montana
Zona Montana
Tahap Pengumpulan Data
Kegiatan pada tahap pengumpulan data adalah pengamatan karakter
ekologi dan kegiatan pengambilan foto pada setiap pos, serta pengumpulan data
sekunder tapak. Pengamatan karakter ekologi dilakukan secara kualitatif.
Pengamatan secara kualitatif merupakan pengamatan atas perbandingan kondisi
relatif karakter ekologi antar pos. Kegiatan selanjutnya adalah pengambilan foto
lanskap di pos dengan kamera digital. Pemotretan dilakukan dengan sudut
pandangan manusia pada posisi normal. Selain itu pemotretan diarahkan pada
view yang mewakili karakter lanskap pos. Pengambilan foto dilakukan pada pagi hari cerah sekitar pukul 10.00-14.00 WIB, agar diperoleh kualitas foto yang
bagus. Pada setiap pos diambil beberapa foto kemudian diseleksi berdasarkan
kualitas warna dan keterwakilan karakter lanskap.
Data sekunder karakter ekologi berasal dari literatur pustaka di
perpustakaan TNGP dan perpustakaan IPB. Literatur pustaka berupa hasil
penelitian di kawasan TNGP yang sudah dilakukan sebelumnya. Data karakter
ekologi berupa data iklim, hidrologi, geologi, topografi, vegetasi, dan satwa.
Selain itu diambil data tentang kondisi umum lokasi berupa letak, aksesibilitas,
luas, dan status kawasan.
Tahap Pengolahan Data
Hasil pemotretan lanskap dipresentasikan dalam bentuk slide foto
berwarna yang kemudian dinilai oleh responden. Responden adalah mahasiswa
Program Studi Arsitektur Lanskap yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang
berjumlah 46 orang. Para responden dikumpulkan dalam satu ruang kemudian
dilakukan presentasi slide dengan program Microsoft Office Power Point 2003.
Penayangan kelompok slide dilakukan dua kali, di mana kelompok slide pertama
untuk penilaian tingkat keindahan lanskap dan kelompok slide kedua untuk
penilaian kualitas karakter ekologi.
Penayangan kelompok slide pertama dilakukan dalam waktu 8 detik untuk
setiap lanskap secara urut berdasarkan letak ketinggian pos dari rendah ke tinggi.
Responden memberikan skor 1 (terendah) sampai 10 (tertinggi) untuk setiap slide
mendekati 1 dianggap lanskap yang tidak indah dan skor mendekati 10 dianggap
lanskap yang indah (Daniel dan Boster, 1976).
Penayangan kelompok slide kedua dilakukan selama kurang lebih 1 menit.
Waktu yang dibutuhkan lebih lama, karena jumlah variabel ekologi yang harus
dinilai responden lebih banyak dari pada variabel penilaian kelompok slide
pertama. Selanjutnya, responden memberikan skor 0 (netral) jika kualitasnya
[image:37.612.131.509.253.447.2]sedang, atau skor 4 (sangat tinggi) jika karakter ekologinya kuat (tabel 1).
Tabel 1. Tabel Kuesioner Semantic Differential
Kriteria 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Kriteria
Biodiversitas tumbuhan tinggi
Biodiversitas tumbuhan rendah
Kerapatan tumbuhan tinggi
Kerapatan tumbuhan rendah
Kesan ruang terbuka
Kesan ruang tertutup
Kesan gersang Kesan subur
Mudah erosi Tidak mudah erosi
Kesan basah Kesan kering
Indah Tidak Indah
Gelap Terang
Pengolahan data hasil kuesioner terbagi dalam tiga tahap, yaitu:
pengolahan data ekologi, pengolahan data estetik, dan analisis korelasi kualitas
ekologi dan estetik. Bentuk pengolahan masing-masing tahap adalah:
1. Pengolahan data penilaian karakter ekologi dengan metode SD
Metode SD merupakan metode penilaian dengan menggunakan kata sifat yang
saling berlawanan (adjective bipolar) untuk menggambarkan kondisi setiap
karakter ekologi. Hasil penilaian responden dikelompokkan sesuai karakter
ekologinya, lalu ditabulasikan dalam satuan persen untuk pengukuran
keragamannya. Selanjutnya skor penilaian diberi bobot nilai 1-9 dari kiri ke
kanan. Setelah pembobotan, nilai dari seluruh responden dijumlahkan
kemudian dibagi dengan jumlah responden, sehingga didapatkan nilai rataan
untuk setiap karakter ekologi. Rataan bobot nilai yang diperoleh diplotkan
ekologi. Nilai rataan tersebut juga menjadi dasar pengelompokkan karakter
ekologi yang berpengaruh kuat pada lanskap setiap pos.
2. Penilaian kualitas keindahan dengan metode SBE
Langkah pertama yang dilakukan adalah pengelompokkan data kuesioner
estetik setiap pos berdasarkan skala penilaian dari 1 sampai 10. Selanjutnya
setiap pos dihitung jumlah frekuensi, frekuensi kumulatif, peluang kumulatif
dan nilai z untuk setiap peringkat dari skor penilaian yang didapat (Daniel dan
Boster, 1976). Formulasi SBE yang digunakan dalam perhitungan adalah:
SBEx =
[
Zlx−Zls]
×100Dimana SBEx = Nilai pendugaan keindahan pemandangan lanskap ke-x
Zlx = Nilai rata-rata z lanskap ke-x
Zls = Nilai rata-rata z lanskap yang digunakan sebagai standar
Nilai Z diformulasikan sebagai :
Z =
σ μ
−
x
σ2
merupakan ukuran pemusatan nilai tengah
σ 2
=
N xi
∑
( −μ)Nilai N adalah banyaknya populasi. Selang kepercayaan untuk μ;s diketahui,
bila x adalah nilai tengah contoh berukuran n yang diambil dari suatu populasi
dan ragam σ 2 diketahui maka selang kepercayaan (1-α) x 100% adalah:
x – z
N
σ
α/2 < μ < x + z
N
σ
α/2
Hasil nilai SBE digunakan untuk pengelompokkan tingkat keindahan dengan
menggunakan sebaran normal. Tingkat keindahan lanskap dikelompokkan ke
dalam tinggi, sedang dan rendah. Kelompok lanskap yang mempunyai nilai
keindahan tinggi adalah pos yang mempunyai nilai SBE lebih tinggi dari
kuartil ketiga (Q3). Kelompok lanskap bernilai sedang adalah pos yang
Sedangkan pos yang mempunyai nilai SBE kurang dari kuartil pertama (Q1)
termasuk dalam kelompok lanskap yang rendah.
3. Analisis korelasi kualitas ekologi dan estetik
Analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai karakter
kualitas ekologi terhadap nilai keindahan lanskap. Analisis korelasi ini
menggunakan program SPSS 10.0 pada Windows. Analisis korelasi yang
digunakan adalah analisis korelasi Person, karena dapat mengukur hubungan
dua variabel yang bersifat linier, dimana data berbentuk kuantitatif dan
berdistribusi normal. Hasil korelasi dapat bersifat netral, positif, atau negatif.
Jika nilai korelasinya bersifat positif, maka peningkatan suatu variabel akan
menyebabkan kenaikan variabel yang lain, demikian pula sebaliknya. Bila
nilai korelasi nol, maka tidak ada hubungan linier antara variabel yang satu
dengan variabel lainnya (Walpole, 1995). Hasil penilaian kualitas estetik,
variabel ekologi, hubungan antara kualitas ekologi dan estetik, dan data
sekunder ekologi digunakan untuk analisis potensi ekologi tapak bagi
pengembangan rekreasi di tapak. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas
terhadap karakter kualitas ekologi. Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan
Alur Pelaksanaan Studi
Studi dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan. Rangkaian tahap
kegiatan tersebut disusun dalam bentuk alur pelaksanaan studi. Bagan alur
[image:40.612.132.510.163.471.2]pelaksanaannya dibuat sebagai berikut:
Gambar 3. Bagan Alur Pelaksanaan Studi Studi Pustaka
Karakter Kualitas Ekologi
TNGP
Kualitas Estetik Kawasan
Korelasi Kualitas Ekologi dan Estetik Penyusunan Kelas Kualitas
Ekologi
Penilaian Kualitas Ekologi
Pemotretan Survai Lapang
Seleksi Foto
Kondisi Umum Lokasi
Letak , Luas dan Aksesibilitas. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango (TNGP) secara geografis terletak di titik 106051’-107002’ BT dan
6041’-6051’ LS. Kawasan ini terbagi ke dalam tiga wilayah administratif, yaitu
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Kawasan TNGP
mempunyai luas 15 196 Ha terdiri dari zona inti seluas 14 379.5 Ha, zona rimba
seluas 651.5 Ha dan zona pemanfaatan seluas 275 Ha (Haris, 2001).
Kawasan TNGP berbatasan langsung dengan hutan produksi perum
Perhutani, PT Perkebunan Nusantara XII, dan tanah milik masyarakat.
Aksesibilitas ke dalam kawasan ini mudah, karena kawasan ini dikelilingi jalan
raya propinsi penghubung kota Bogor-Cianjur dan kota Bogor–Sukabumi-
Cianjur. Kondisi sarana jalan dari jalan raya propinsi ke arah pintu gerbang cukup
bagus dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Jumlah pintu gerbang
utama untuk masuk ke dalam kawasan tersebut ada tiga, yaitu pintu gerbang
Cibodas, pintu gerbang Gunung Putri, dan pintu gerbang Selabintana (Haris,
2001).
Topografi dan Geologi. Menurut Haris (2001) topografi kawasan ini
bervariasi, terdiri dari lahan datar, dataran tinggi, dan bukit sedang sampai terjal.
Ketinggian kawasan ini berada pada 1000-3019 m dpl dan puncaknya merupakan
daerah tertinggi di Propinsi Jawa Barat. Gunung Gede Pangrango termasuk dalam
rangkaian jalur gunung berapi dari pulau Sumatera sampai Nusa Tenggara.
Geologi kawasan ini berupa batuan vulkanik seperti andesit, tuff, basalt,
lava breksi, breksi mekanik dan proklastik. Jenis tanahnya adalah:
1. Tanah regosol dan litosol terdapat pada lereng pegunungan yang lebih
tinggi dan berasal dari lava dan batuan hasil kegiatan gunung berapi. Jenis
tanah seperti ini sangat peka terhadap erosi.
2. Tanah asosiasi andosol dan regosol terdapat pada lereng gunung yang
lebih rendah dan agak peka terhadap erosi. Jenis ini mengalami pelapukan
3. Tanah latosol coklat terdapat pada lereng paling bawah. Tanah ini
mengandung liat dan lapisan subsoilnya gembur, mudah ditembus air,
serta lapisan bawahnya yang mudah melapuk. Tanah seperti ini sangat
subur dan dominan, serta agak peka terhadap erosi.
Iklim dan Hidrologi. Iklim di kawasan ini berdasarkan klasifikasi
Schmidt dan Fergusson termasuk tipe iklim A, dengan nilai Q berkisar antara
11.30%-33.30%. Suhu udara berkisar antara 100-180 C. Kelembaban relatif
sepanjang tahun berkisar dari 80%-90%. Daerah ini termasuk daerah terbasah di
pulau Jawa dengan rata-rata curah hujan tahunan 3 000-4 200 mm. Bulan basah
terjadi pada bulan Oktober–Mei, dengan rata-rata curah hujan bulanan 200 mm.
Bulan kering biasanya terjadi pada bulan Juni-September dengan rata-rata curah
hujan bulanan kurang dari 100 mm (Haris, 2001).
Kawasan Gunung Gede Pangrango memiliki banyak sumber air. Sumber
air tersebut mengalir dan bersatu membentuk sungai-sungai besar di sekitar
kawasan tersebut. Terdapat 60 aliran sungai besar dan kecil, yang berhulu di
Gunung Gede dan Pangrango. Dua puluh sungai mengalir ke Kabupaten Cianjur,
23 sungai mengalir ke Kabupaten Sukabumi, dan 17 sungai mengalir ke
Kabupaten Bogor. Pada lereng Utara Gunung Gede beberapa aliran sungai kecil
bersatu membentuk air terjun besar Cibeureum. Aliran dari air terjun besar
Cibeureum mengalir ke rawa Gayonngong dan ke Telaga Biru. Disamping
Cibeureum, terdapat juga beberapa air terjun lain yang pada akhirnya bersatu
dalam aliran sungai Cipanas dan sungai Citarum yang mengalir ke arah Utara
menuju laut Jawa. Di lereng Selatan Gunung Gede Pangrango aliran-aliran sungai
bersatu membentuk sungai Cimandiri di Sukabumi yang bermuara di Pelabuhan
Ratu. Aliran-aliran air di lereng Barat laut Gunung Pangrango mengalir ke sungai
Cisarua dan Cinegara yang merupakan sumber air bagi sungai Ciliwung dan Kali
Angke yang bermuara di teluk Jakarta (Haris, 2001).
Vegetasi. Jenis vegetasi di kawasan taman nasional sangat
beranekaragam. Secara umum jenis vegetasi tersebut dapat di bagi dalam tiga
zona hutan (Haris, 2001). Urutan ketinggian dari ketiga zona hutan tersebut adalah
zona hutan Perum Perhutani, zona hutan Montana, dan zona hutan Sub Alpin.
1. Hutan Sub Montana
Zona ini dapat dikategorikan ke dalam hutan sub montana. Zona ini
merupakan batas terluar taman nasional. Hutan di kawasan ini berupa hutan
produksi monokultur dari jenis rasamala (Altingia excelsa). Pengelolaan hutan ini
dilakukan oleh Perum Perhutani. Hutan ini ditandai dengan tiga lapisan tajuk.
Lapisan tajuk teratas didominasi oleh jenis Rasamala (Altingia excelsa). Tinggi
tajuk teratas jenis tumbuhan ini dapat mencapai 60 m. Jenis lainnya yang
menonjol berturut-turut adalah Saninten (Castanopsis argentea), dan Antidesma
tentandrum. Lapisan tajuk kedua berupa jenis perdu dan semak diantaranya Ardisia fulginosa, Dichera febrifuga, randanus laizrox, Pinanga sp dan Lapotea stimulans. Pada lapisan tajuk ketiga terdapat berbagai jenis tumbuhan bawah, epifit, dan lumut antara lain Begonia, paku-pakuan, anggrek dan Lumut Merah
(Sphagnum gedeanum).
2. Hutan Montana
Zona ini dicirikan oleh adanya dominasi pohon bertajuk besar. Pohon pada
lapisan atas mempunyai pertumbuhan yang jarang. Sedangkan lapisan tajuk
tumbuhan bawah mempunyai pertumbuhan yang rapat. Lapisan tajuk tumbuhan
bawah ini berupa semak rendah, sedang dan tinggi. Jenis tumbuhan yang mudah
dikenal yaitu Puspa (Schima walichii), tumbuhan berdaun jarum (Dacrycarpus
imbricatus dan Podocarpus neriifolius), Jamuju (Podocarpus imbricatus), Rasamala (Altingia excelsa), dan Kiracun (Macropanax dispernum). Untuk jenis
tumbuhan bawah berupa paku-pakuan, epifit, seperti Dendrobium sp, Arundina
sp, Cymbiddum- spp dan Calanthe spp. 3. Hutan Sub Alpin
Zona ini merupakan zona hutan teratas pada taman nasional. Ciri yang
menonjol adalah keanekaragaman tumbuhannya semakin berkurang seiring
dengan bertambahnya ketinggian tempat. Kerapatan tumbuhan pada zona ini
sangat tinggi. Lapisan tajuk pada zona ini terdiri dari satu lapis dan didominasi
oleh pohon-pohon pendek, antara lain Cantigi Gunung (Vaccinium
varingiaefolium), Rhododendron resutum, dan Myrsine avenis. Jenis tumbuhan lain yang mudah ditemukan adalah lumut. Tumbuhan lumut banyak terdapat pada
batang pohon adalah lumut janggut. Di daerah puncak terdapat jenis tumbuhan
yang khas, yaitu Edelweis Jawa (Anaphalis javanica) yang sangat terkenal di
kalangan pecinta alam, karena bunganya terlihat tidak pernah layu.
Taman nasional TNGP memiliki beberapa flora endemik yang langka dan
beberapa tanaman introduksi. Jenis tumbuhan endemik dan langka antara lain
anggrek Liparis bilobulata, Malaxis sagittata, Pachicentria varingiaefolia, dan Corrybas mucronatus, sedangkan tanaman yang diintroduksi antara lain Dendrobium jecobsoni, Agathis loranthifolia, Pinus merkusii dan Maesopsis emini. Tanaman introduksi tersebut sengaja dimasukkan oleh para peneliti ke dalam kawasan (Riatmo, 1989).
Satwa. Kawasan TNGP mempunyai beberapa jenis satwa, baik dari jenis
primata, mamalia, burung, dan bermacam satwa kecil. Beberapa jenis satwa di
kawasan TNGP sudah tergolong langka (Riatmo, 1989). Jenis satwa langka antara
lain:
1. Jenis primata seperti Gibbon Jawa (Hylobates moloch) dan Surili Jawa
(Dresbytis aygula),
2. Jenis mamalia seperti macan tutul (Panthera pardus), anjing hutan (Cuon
alpinus), dan trenggiling (Manis javanica),
3. Jenis burung seperti alap-alap (Accipiter soloensis), betet (Lanios scaeh),
dan kutilang (Pycnonotus aurigaster).
Jenis satwa yang populasinya masih banyak antara lain:
1. Jenis primata seperi kera ekor panjang (Macaca fascicularis) dan Lutung
(Presbytis cristata),
2. Jenis mamalia besar seperti kancil (Tragulus javanicus), babi hutan (Sus
schrofa), dan muncak (Muntiacus muntjak),
3. Jenis mamalia kecil seperti sigung (Mydaus javanensis), kucing hutan
(Felix bengalensis), tikus hutan (Rattus lepturus), dan bajing terbang
Evaluasi Kualitas Estetika pada
Jalur Wisata Alam TNGP
Jalur wisata alam TNGP mempunyai tiga pintu masuk, yaitu pintu masuk
Cibodas, Gunung Putri, dan Selabintana (Gambar 5). Pada jalur wisata alam
tersebut terdapat pos-pos peristirahatan sementara, dimana pengunjung biasanya
berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, dan sambil melihat pemandangan alam.
Pada pos peristirahatan tersebut dilakukan pengamatan karakteristik kualitas
ekologi dan estetiknya. Jumlah pos peristirahatan yang diamati ada 17 buah pos
yang berada di sepanjang jalur wisata alam dari ketiga pintu masuk kawasan
TNGP.
Penilaian kualitas estetika pada jalur wisata alam dengan menggunakan
analisis SBE dari penilaian responden terhadap tingkat keindahan lanskap 17 pos
melalui presentasi foto. Responden adalah mahasiswa Program Studi Arsitektur
Lanskap angkatan 40 yang duduk di semester enam, terdiri atas laki-laki dan
perempuan yang berjumlah 46 orang. Hasil analisis SBE pada tujuh belas lanskap
pos di jalur wisata alam TNGP mempunyai nilai SBE berkisar 34.22 hingga
133.26 (Lampiran 4). Lanskap yang mempunyai nilai keindahan tertinggi adalah
lanskap Puncak dan Kawah Gede (Nilai SBE = 133.26), yang artinya lanskap ini
merupakan lanskap yang paling banyak diminati, karena memiliki obyek
pemandangan yang unik berupa kawah. Sedangkan lanskap yang mempunyai nilai
SBE terendah adalah lanskap Resor Cibodas (Nilai SBE = 34.22), dengan
demikian lanskap ini merupakan lanskap yang paling tidak disukai, karena
terdapat bangunan di tapak yang membuat pemandangan menjadi kurang alami
dan unik.
[image:45.612.132.509.547.687.2]Puncak dan Kawah Gunung Gede (C2) Resor Cibodas (C8)
Ketujuh belas lanskap pada jalur wisata alam TNGP dapat dikelompokkan