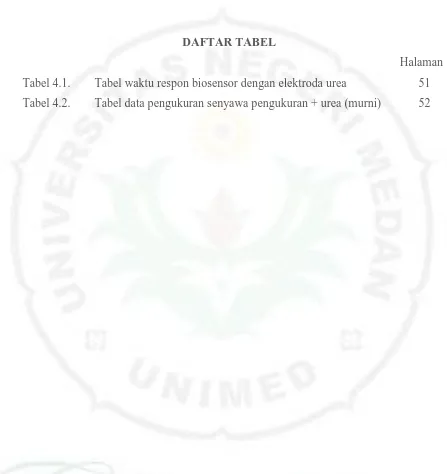IMMOBILISASI E NZIM URE ASE UNTUK PEMBUAT AN SE NSOR KIMIA DALAM PENE NTUAN URE A
Oleh: Debby Tamba NIM.4123210006 Program Studi Kimia
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sain
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
iii
IMMOBILISASI E NZIM URE ASE UNTUK PEMBUAT AN SE NSOR KIMIA DALAM PENE NTUAN URE A
Debby Tamba (4123210006)
ABSTRAK
Pembuatan biosensor urea untuk analisis urea secara potensiomeri melalui immobilisasi enzim urease telah dilakukan. Imobilisasi urease ini dibantu dengan matriks polivinil alkohol (PVA) menjadi membran yang terlapis pada kawat wolfram yang digunakan untuk mendeteksi urea secara potensiometri dengan elektroda pembanding Ag/AgCl. Penelitian didahului dengan uji respon urea pada elektroda dengan variasi pencelupan 1x-5x kemudian penentuan larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer, konsentrasi larutan elektrolit, jenis larutan buffer dan pengaruh senyawa pengganggu. Pengukuran urea memiliki respon yang lebih baik pada larutan buffer Natrium Asetat 0,001 M dan pH 7. Membran elektroda dibuat dari 0,0504 gram PVA dan 6 mg enzim urease dan dilekatkan pada kawat wolfram dengan variasi satu kali (1x) hingga lima kali (5x) pencelupan. Setelah imobilisasi, membran larut dalam air pada proses pengujian sehingga elektroda membran dicoating pada campuran 0,5044 gram PVC, 0,0120 gram KTpClPB dan 10 mL tetrahidrofuran (THF) dan melekat pada wolfram. Elektroda urea digunakan untuk analisis urea standar. Pengukuran potensial urea terbaik terdapat pada larutan buffer Natrium asetat 0,001 M, pH larutan 7 menggunakan elektroda dengan variasi 1x pencelupan. Hasil pengukuran menunjukkan, elektroda dengan variasi 1x pencelupaan memiliki linearitas yang terbaik dengan Faktor Nernst yang tinggi. Faktor Nernst 9,44 linear pada konsentrasi 10-3Mhingga 10-5M. Elektroda urea variasi dua kali (1x) pencelupan merupakan elektroda urea terbaik pada pengembangan biosensor urea ini dan memiliki rata-rata waktu respon 258 sekon.
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan
tepat waktu. Penyelesaian skripsi dengan judul “Immobilisasi Enzim Urease Untuk
Pembuatan Sensor Kimia dalam Penentuan Urea”.
Banyak pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dari awal
pembuatan proposal penelitian, melaksanakan penelitian dan penyususan laporan
dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Bapak Drs. Kawan Sihombing, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, Bapak
Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc, Ph.D , Ibu Dr. Ida Duma Riris, M.Si , dan
Bapak Drs. Marudut Sinaga, M.Si selaku dosen penguji skripsi, yang telah mereview,
memberikan arahan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis lebih terarah
dalam pembuatan proposal penelitian, melaksanakan penelitian hingga penyelesaian
laporan dalam bentuk skripsi ini.
2. Bapak Alm.Drs. Rahmat Nauli, M.si selaku dosen pembimbing akademik
penulis, Bapak Agus Kembaren selaku Ketua Jurusan Kimia, seluruh Dosen Jurusan
Kimia yang telah mendidik penulis, dan seluruh staf/laboran Jurusan Kimia terkhusus
Bang Nizam dan Bang Daniel yang sudah membantu selama penelitian.
3. Yang terkasih, keluarga penulis Ayahanda Henry Tamba, SE dan Ibunda
Hosianna Sembiring, Kak Melsandy Tamba, Am.Keb, dan Kedua Adik Heryanty
Tamba dan George Andre Tamba. Kekasih Andie Sahat Simanjuntak, Amd.,Rad.
Terimakasih atas segala nasehat dan dukungan baik moril dan materi sehingga
penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Drs. Abdul Hakim, M.Si yang sudah membantu penulis dalam penelitian.
Krystin Tarihoran, Ira Dwi yana, Beril Sardina br.Ginting, partner dan teman
v
5. Kimia Nondik 2012 yang menjadi teman baik dan seperjuangan penulis selama
kuliah hingga lulus terutama sahabat terbaik Lia Febrina. Terimakasih sudah menjadi
teman suka duka selama kurang lebih empat tahun kuliah di Kimia Unimed.
6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan belum disebutkan satu persatu.
Penulis telah berupaya dengan maksimal untuk menyelesaikan penelitian hingga
skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis masih memiliki banyak kekurangan.
Penulis berharap pembaca memberikan saran yang mendukung perbaikan skripsi ini
dan semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus
dibidang kimia. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.
Medan, Juli 2016
Penulis,
Debby Tamba
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN i
RIWAYAT HIDUP ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Batasan Masalah 5
1.3. Rumusan Masalah 6
1.4. Tujuan Penelitian 6
1.5. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. Urea 7
2.1.1. Metabolisme Nitrogen 8
2.1.2. Alur Nitrogen Asam Amino: Siklus Urea 9
2.1.3. Siklus Urea 12
2.1.4. Fungsi siklus urea selama puasa 13
2.2. Enzim Urease 15
2.3. Biosensor 16
2.4. Potensiometri 18
2.4.1. Elektroda Pembanding 20
2.4.2. Elektroda Indikator 22
2.5. Polivinil Alkohol (PVA) 25
vii
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.2. Alat dan Bahan 29
3.3. Prosedur Penelitian 29
3.3.1. Pembuatan Larutan 29
3.3.2. Pembuatan Elektroda Urea dengan Immobilisasi Urease
pada Kawat Wolfram 31
3.3.3. Uji Respon Elektroda Kerja Terhadap Urea 31
3.3.4. Optimalisasi Elektroda Urea 32
3.3.5. Penentuan Sensitivitas, Waktu Respon dan Jangkauan
Pengukuran 35
3.4. Diagram Alir 35
3.4.1. Diagram Alir Pembuatan Elektroda dengan Imobilisasi
Enzim Urease pada Kawat Wolfram 35
3.4.2. Diagram Alir Uji Respon Elektroda Kerja Terhadap Urea 36
3.4.3 Diagram Alir Optimasi Elektroda Kerja 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
4.1. Uji Respon Elektroda Kerja Terhadap Urea 40
4.2. Optimalisasi elektroda Urea 42
4.2.1. Penentuan pH Optimum Larutan Buffer 42
4.2.2. Penentuan Konsentrasi Buffer Optimum 45
4.3. Optimalisasi Larutan Elektrolit 47
4.4. Penentuan Jenis Larutan Buffer 48
4.5. Penentuan Sensitivitas, Waktu Respon dan Jangkauan Pengukuran 50
4.5.1. Sensitivitas Biosensor 50
4.5.2. Jangkauan Pengukuran 51
4.5.3 Waktu Respon Biosensor 51
viii
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53
5.1. Kesimpulan 53
5.2. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55
ix
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Struktur Urea 7
Gambar 2.2. Ringkasan metabolisme asam amino 9
Gambar 2.3. Sumber nitrogen untuk sintesis urea 10
Gambar 2.4. Peran berbagai jaringan dalam metabolisme asam amino dalam
keadaan kenyang 11
Gambar 2.5. Peran berbagai jaringan dalam metabolisme asam amino
selama puasa 12
Gambar 2.6. Siklus urea 13
Gambar 2.7. Perubahan alanin menjadi glukosa pada manusia 14
Gambar 2.8. Struktur Inti Enzim Urease 16
Gambar2.9. Skema Biosensor secara umum 17
Gambar 2.10. Elektroda Kalomel 21
Gambar 2.11. Elektroda Perak/Perak Klorida 21
Gambar 2.12. Alur E sebagaifungsi–log a pada metode potensiometri 23
Gambar 2.13. Penentuan limit deteksi berdasarkan ekstrapolasi titik temu
alur linear dan garis singgung alur non linear 24
Gambar 2.14. Struktur Monomer PVA 25
Gambar 3.1. Desain Elektroda Urea 31
Gambar 3.2. Desain Pengukuran Potensial 32
Gambar 3.3. Diagram Alir Pembuatan Elektroda dengan Imobilisasi Enzim
Urease pada Kawat Wolfram 36
Gambar 3.4. Diagram Alir Uji Respon Elektroda KerjaTerhadap Urea 36
Gambar 3.5. Diagram Alir Penentuan pH Optimum Larutan Buffer 37
Gambar3.6. Diagram AlirPenentuanKonsentrasi OptimumLarutan Buffer 37
Gambar3.7. Diagram Alir Penentuan Jenis Buffer yang Digunakan
Untuk Elektroda Sensor Urea 38
x
Gambar 3.9. Diagram Alir Pengaruh Senyawa Pengganggu 39
Gambar 4.1. Kurva Standar Hubungan Log Konsentrasi Urea dengan
Potensial pada lima Elektroda Urea 40
Gambar 4.2. kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea elektroda
urea variasi 1x pencelupan 41
Gambar 4.3. Kurva Potensial Urea Standar pada pH Larutan Uji yang Berbeda
pada larutan Buffer Trisma HCl 43
Gambar 4.4. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada
Buffer Trisma HCl pH 6,5 44
Gambar 4.5. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada
buffer Natrium Asetat dengan berbagai variasi pH 44
Gambar 4.6. kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada
buffer Natrium Asetat pH 7 45
Gambar 4.7. Kurva log konsentrasi buffer trisma HCl terhadap potensial urea 46
Gambar 4.8. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada
buffer Natrium Asetat dengan berbagai variasi konsentrasi 46
Gambar 4.9. Kurva log konsentrasi larutan elektrolit KCl terhadap potensial
urea KCl 47
Gambar 4.10. Kurva log urea pada larutan elektrolit KCl optimum
0,005 M 48
Gambar 4.11. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada
buffer Trisma HCl 49
Gambar 4.12. Kurva log konsentrasi urea terhadap potensial urea pada
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4.1. Tabel waktu respon biosensor dengan elektroda urea 51
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Data dan Kurva Hasil Analisa Potensial Urea pada uji respon
elektroda urea, Kondisi pH, konsentrasi dan jenis Berbeda
serta konsentrasi KCl yang berbeda 58
Lampiran 2. Sensitivitas, waktu respon dan jangkauan pengukuran dan
senyawa pengganggu 65
1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Urea adalah senyawa kimia yang dapat terbentuk secara biologis dalam tubuh
makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan (Khairi, 2003). Dalam
tubuh manusia pembentukan urea terjadi sebagai produk akhir dari metabolisme
protein yang menghasilkan urea. Senyawa ini digunakan dalam pembentukan
asam-asam amino sebagai unsur-unsur protein yang berguna bagi tubuh. Kadar
urea pada tubuh manusia memiliki batas yang telah ditetapkan yaitu 1,8 – 4,0
mg/L pada darah (Khairi, 2005).
Asam amino, yang dihasilkan dari pencernaan protein makanan, diserap
melalui sel epitel usus dan masuk ke dalam darah. Berbagai sel mengambil asam
amino ini yang kemudian masuk menjadi simpanan di dalam sel. Asam amino
tersebut digunakan untuk membentuk protein dan senyawa lain yang mengandung
nitrogen, atau dioksidasi untuk menghasilkan energi. Hati adalah tempat utama
oksidasi asam amino. Sebelum rangka karbon pada asam amino dioksidasi,
nitrogen terlebih dahulu harus dikeluarkan. Nitrogen asam amino membentuk
amonia, yang bersifat toksik bagi tubuh. Di hati, amonia dan gugus amonia dari
asam amino diubah menjadi urea, yang bersifat nontoksik, larut dalam air, dan
mudah dikeluarkan melalui urin. Perubahan nitrogen asam amino menjadi urea
terutama berlangsung di hati. Urea terbentuk dalam siklus urea dari NH4+, CO2
dan ATP bereaksi menghasilkan karbamoil fosfat, yang akan bereaksi dengan
ornitin untuk membentuk sitrulin. Aspartat kemudian bereaksi dengan sitrulin
membentuk argininosuksinat, yang membebaskan fumarat dan membentuk
arginin. Akhirnya arginin diuraikan oleh arginase untuk membebaskan urea dan
membentuk kembali ornitin (Marks, dkk. 2000).
Untuk kepentingan diagnosis dalam bidang kesehatan, dilakukan penentuan
kadar urea pada serum atau urin. Pada umumnya penentuan urea dilakukan
2
spektrofotometri dan juga secara elektrokimia yang disebut dengan
biosensor.Pengembangan biosensor saat ini merupakan salah satu penelitian yang
sedang berkembang dalam berbagai bidang, salah satunya dibidang kimia analitik.
Sensor adalah perangkat yang menggabungkan elemen pengakuan dengan
transduser sinyal. Sensor kimia dapat didefenisikan sebagai alat untuk
mengubah bentuk informasi kimia antara suatu konsentrasi kimia kedalam bentuk
signal. Perangkat sensor kimia adalah sebuah alat yang mengubah informasi kimia
mulai dari konsentrasi komponen menjadi sinyal analitik. Dalam bidang kimia,
sensor dikembangkan secara elektrokimia, dimana elektroda digunakan sebagai
elemen transduksi, mewakili turunan penting dari sensor kimia (Wahab dan
Nafie, 2014).
Biosensor pertama kali diperkenalkan ditahun 1962 oleh Clark dan Lyons,
yang telah mengimobilisasi enzim glukosa oksidase (GOD) dengan membran
semipermeabel dialisis pada permukaan elektroda oksigen dengan tujuan untuk
menghitung langsung konsentrasi sampel secara amperometri. Mereka
memaparkan bagaimana membuat sensor elektrokimia (pH, polarografi,
potensiometri, atau konduktometri) lebih baik dengan menggunakan enzim pada
tranduser sebagai membran yang diselipkan. Perangkat biosensor terdiri dari
Bioreseptor yaitu komponen biologis yang terimobilisasi (contohnya enzim,
DNA) dan transduser yang mengubah sinyal kimia hasil dari interaksi analit
dengan bioreseptor kedalam suatu alat elektronik (contohnya potensiostat)
(Koyun, dkk, 2010).
Secara spektrofotometri, kadar urea ditentukan dengan metode kolorimetri
menggunakan spektrofotmeter. Pengukurannya didasarkan pada reaksi enzimatik
urease yang spesifik teradap urea dengan dietilmonoksim. Reaksi ini
menghasilkan larutan kuning dan ditentukan absorbansinya (Khairi, 2003).
Sedangkan secara elektrokimia (potensiometri) penentuan urea dilakukan
berdasarkan reaksi antara urea dengan urease membentuk ammonium hidroksida.
Urease diimobilisasi/diikat pada permukaan kawat logam dan digunakan juga
elektroda referensi dimana keduanya adalah untuk menentukan potensial dari
3
untuk menghasilkan ion amonium, hidroksida dan karbondioksida. Reaksi
enzimasi tersebut menghasilkan ion yang berasal dari hasil reaksi substrat,
kemudian dapat dideteksi dengan elektroda secara potensiometri (Situmorang,
2010). Persamaan reaksi enzimasi tersebut adalah sebagai berikut:
Didalam pengembangan biosensor urea secara potensiometri, hal yang
menjadi parameter utama adalah bagaimana teknik imobilisasi urease yang baik
pada elektroda agar diperoleh waktu respon yang cepat dan sensitivitas yang
tinggi terhadap urea. Dengan itu biosensor tersebut akan mampu menentukan urea
pada sampel biologis dengan optimum (Gupta, dkk, 2010).
Enzim terimobilisasi merupakan enzim yang dilekatkan pada permukaan
suatu bahan tidak larut dengan menggunakan suatu matriks atau membran. Enzim
terimobilisasi ini akan lebih tahan terhadap perubahan pH dan suhu. Karena telah
dilekatkan, sistem imobilisasi ini akan membuat enzim tetap berada pada tempat
tertentu (Wikipedia, 2015). Secara elektrokimia, potensiometri misalnya
imobilisasi enzim pada elektroda ini bertujuan agar elektroda yang dibuat dapat
digunakan berulang kali dan enzim urease yang digunakan tetap berada disekitar
elektroda kerja.
Imobilisasi enzim urease yang relevan pada suatu permukaan elektroda
merupakan salah satu langkah penting. Kualitas ataupun kemampuan biosensor
yang dibuat dengan imobilisasi enzim ini sangat dipengaruhi oleh teknik
imobilisasi dan pemilihan matriks yang digunakan (Fauziah, 2012). Terdapat
beberapa metode imobilisasi yang telah diketahui baik digunakan. Beberapa
metode tersebut adalah metode adsorpsi, cross linking, entrapment,
microencapsulation, dan covalen attachment. Metode-metode tersebut adalah
metode terbaik yang sudah digunakan dalam pengembangan biosensor saat ini
(Koyun, dkk, 2012).
Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan beberapa jenis material
4
Begun Fauziah (2012) dalam penelitiannya Optimasi Biosensor Urea dengan
mengimobilisasi urease menggunakan membran Polianilin (PAn). Imobilisasi
Urease dalam matrik PAn ini memiliki waktu respon biosensor 20 menit dengan
stabilitasnya sampai 7 hari. Sensitivitas yang dihasilkan yaitu 0,0445.
Mulyasuryani, A dkk (2010) menggunakan membran kitosan sebagai matriks
untuk mengimobilisasi urease dan dengan menggunakan H3O+ sebagai eketroda
tranduser. Dalam penenlitian itu diperoleh faktor nernst pada uji respon biosensor
secara potensiometri 28,47 mV/decade, waktu respon 280 sekon (4 menit 40
sekon) dan range konsentrasi sekitar 0,1 hingga 6,0 ppm. Urease tersebut
diimobilisasi pada membran kitosan yang telah dilarutkan dengan asam asetat
dengan pH 4.
Selain menggunakan membran kitosan dan PAn, beberapa penelitian
sebelumnya juga menggunakan polimer PVC dan Glutaraldehid sebagai matriks
untuk imobilisasi urease. Khairi (2003) melaporkan penggunaan PVC sebagai
matriks untuk mengimobilisasi urease secara entrapmen pada kawat tembaga
(tranduser), diperoleh sensitivitas 47,8 mV/dekade dengan waktu respon 135
sekon dan stabilitasnya 14 hari. Hasil ini lebih baik daripada menggunakan
membran kitosan seperti yg dilaporkan oleh Mulyasuryani, A, dkk. Penelitian
tersebut dilakukan dengan metode potensiometri secara selektif ion.
Selain PVC dan Glutaraldehida yang telah banyak diteliti sebagai matriks,
polimer PVA juga telah digunakan sebagai matriks pada pengembangan
biosensor. Menurut Jha, dkk (2007) telah menggunakan PVA sebagai matriks
untuk imobilisasi urease untuk menentukan kadar urea darah blood urea nitogen
(BUN). Sensor tersebut bekerja pada 1-1000 mM urea dan waktu respon 120
sekon. biosensor tersebut menunjukkan korelasi yang baik dengan reagen metode
BUN komersial yang menggunakan analiser kimiawi klinis. PVA adalah salah
satu polimer yang berfungsi sebagai perekat yang baik tetapi masih jarang
digunakan/diteliti sebagai matriks untuk imobilisasi urease pada pengembangan
biosensor urea. PVA larut dalam air, sehingga harus dilakukan iradiasi pada
5
gamma). Iradiasi PVA ini juga dapat dilakukan dengan microwave dengan daya
8-15 W.
Pemilihan matriks ini sangat penting karena berhubungan dengan stabilitas.
Matriks dapat berupa polimer atau gel. Untuk menghasilkan matriks dengan
keterulangan pemakaian yang tinggi, maka sangat baik menggunakan polimer
melalui teknik elektropolimerisasi karena akan menghasilkan lapisan yang
homogen dan merata. Elektroda yang digunakan sebagai tranduser berbeda-beda
tetapi memiliki fungsi yang sama. Elektroda ammonia, elektroda oksigen, dan
elektoda logam yang meliputi tembaga, antimoni, iridium, wolfram (tungsten),
dan PAn semikonduktor. Elektroda tersebut telah digunakan untuk pengembangan
biosensor pestisida, glukosa, kolesterol dan urea (Emr dan Yacynych, 1995).
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut
biosensor urea melalui imobilisasi urease dengan matriks polimer PVA (polyvinil
alcohol), dan elektroda Wolfram dipilih sebagai transduser. Imobilisasi urease
dengan PVA dilekatkan pada pada permukaan Wolfram. Dengan penggunaan
matriks dan elektroda tersebut diharapkan dapat mengembangkan biosensor urea
yang lebih baik untuk penentuan urea. Peneliti mengangkat judul
“I mmobilis asi En zi m Ur eas e Un tuk Pembuatan Sen sor Ki mia Dalam Pen en tuan Urea” untuk penelitian ini.
1.2. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada:
1. Teknik immobilisasi enzim urease untuk pembuatan biosensor urea dalam
deteksi potensiometri pada elektroda wolfram menggunakan matriks polimer
polivinil alkohol (PVA)
2. Kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai enzim urease
sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri meliputi jenis
larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer, larutan elektrolit
dan senyawa pengganggu.
3. Uji aktivitas enzim meliputi sensitivitas, waktu respon dan jangkauan
6
1.3. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana teknik yang baik untuk mengimmobilisasi enzim urease di dalam
matriks polimer polivinil alkohol (PVA) pada kawat wolfram untuk
membuat biosensor urea dalam deteksi potensiometri.
2. Bagaimana kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai
enzim urease sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri
meliputi jenis larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer,
larutan elektrolit dan senyawa pengganggu.
3. Bagaimana menguji aktivitas enzim yang meliputi sensitivitas, waktu respon
dan jangkauan pengukuran.
1.4.Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menentukan teknik yang baik untuk mengimmobilisasi enzim di dalam
matriks polimer polivinil alkohol (PVA) pada kawat wolfram untuk
membuat biosensor urea dalam deteksi potensiometri.
2. Menentukan kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai
enzim urease sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri
meliputi jenis larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer,
larutan elektrolit dan senyawa pengganggu.
3. Menentukan sensitivitas, waktu respon dan jangkauan pengukuran.
1.5.Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui teknik yang baik untuk mengimmobilisasi enzim urease di dalam
matriks polimer polivinil alkohol (PVA) pada kawat wolfram untuk
membuat biosensor urea dalam deteksi potensiometri.
2. Mengetahui Kondisi optimum elektroda wolfram yang telah diimmobilisai
enzim urease sebagai biosensor pada analisis urea secara potensiometri
meliputi jenis larutan buffer, pH larutan buffer, konsentrasi larutan buffer,
larutan elektrolit dan senyawa pengganggu.
3. Mengetahui aktivitas enzim yang meliputi sensitivitas, waktu respon dan
53 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah
diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Teknik Immobilisasi urease dengan menggunakan matriks polivinil alkohol
(PVA) harus dilekatkan kembali dengan larutan polivinil klorida (PVC),
plastisiser KTPClPB dan Tetrahidrofuran agar tidak mudah larut dalam
pengukuran dan dapat digunakan berulang kali, karena pengeringan elektroda
urea menggunakan microwave tidak berhasil
2. Elektroda urea terbaik yang dihasilkan pada saat uji respon yaitu elektroda
urea dengan variasi satu kali pencelupan dan diperoleh faktor Nernst sebesar
16,03 dan koefisien korelasi 0,896 dan jangkauan pengukuran 10-5 M hingga
10-3 M mV/dekade.
3. Pengukuran urea standar dengan biosensor urea optimum pada kondisi
larutan buffer trisma pH 6,5 dan buffer asetat pH 7 dan pada konsentrasi
0,001 M dan konsentrasi optimum larutan KCl yaitu 0,005 M.
4. Besarnya sensitivitas ditunjukkan oleh harga Faktor Nernst biosensor tersebut
dan Faktor Nernst merupakan slope dari persamaan regresi kurva kalibrasi.
Diperoleh faktor Nernstnya adalah 9,44 mV/dekade dan linearitas (r) sebesar
0,529. Elektroda urea pada penenlitian ini memiliki jangkauan pengukuran
54
5.2. Saran
Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan:
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai komposisi membran untuk
elektroda urea dan bagaimana cara agar membran elektroda hasil imobilisasi
urease menggunakan polivinil alkohol tidak larut larut pada larutan pada saat
pengukuran.
2. Sebaiknya konsentrasi urea yang diukur memiliki rentang yang luas agar
dapat diperoleh batas deteksi elektroda urea.
3. Perlu dilakukan penentuan stabilitas biosensor dan aplikasi biosensor urea
pada sampel klinis terkontrol, agar diketahui kualitas biosensor urea
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai senyawa pengganggu terhadap
55
DAFTAR PUSTAKA
Day, R A, dan Underwood, A L., (2002), Analsis Kimia Kuantitatif Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta
Dahliani, R. A., (1995), Pengaruh Hemodialisis Terhadap Kadar Ureum pada Penderita Gagal Ginjal di Bagian Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung
Emr, SA, And Yacynyh, A.M., (1995), Use of Polymer Film in Amperometric Biosensors, Electroaanalysis, 7: 913-923
Fauziyah, B., (2012), Optimasi Parameter Analitik Biosensor Urea Berbasis Imobilisasi Urease dalam Membran Polianilin, Saintis Vol. 1 No 1 2012
Gupta B, dkk., (2010),Urea Biosensor based on Conducting Polymer Transducer, Biosensors, Pier Andrea Serra, India, Intech
Jha, K., Topkar, A., dan D’Souza, S F., (2008), Development of Potentiometric Urea Biosensor based on Urease Ommobilized in PVA-PAA Composite Matrix for Estimation of Blood Urea Nitrogen (BUN), Journal of Biochem and Biophys Methods70 (2008) 1145-1150
Khairi., (2003), Pembuatan Biosensor Urea dengan Transduser Tembaga, Jurnal Sains Kimia Vol 7 No 2 2003: 40-43
Khairi., (2005), Perbandingan Metode Potensiometri Menggunakan Biosensor Urea dengan Metode Spektrofotometri untuk Penentuan Urea, Jurnal Sain KimiaVol. 9 No 2 Hal; 68-72
Koyun, A, Ahlatcioglu, E., dan Ipek, Y, K., (2001), Biosensors and Their Principle, In Tech, Turky
Marks, Dawn B., Marks, Allan D., dan Smith, Colleen M., (2000), Biokimia Kedokteran Dasar : Sebuah Pendekatan Klinis, EGC, Jakarta
Mulyasuryani, A., Roosdiana, A., dan Srihardyastuti, A., (2010), The Potentiometric Urea Biosensor Using Chitosan Membrane. Indo J Chem 2010, 10 (2), 162-166
Rahim, A F., (2013), Modifikasi Elektroda Amonia dengan Ekstrak Enzim Urease dari Kedelai Hitam sebagai Biosensor Urea secara Potensiometri., Skripsi, FST, Unair, Surabaya
56
Situmorang, M., (2010), Kimia Analitik Lanjut dan Instrumentasi, FMIPA UNIMED, Medan
Situmorang, M; S, P Maulim; Nurwahyuni, I; (2008), Rancang Bangun Biosensor Elektrokimia Sebagai Instrumen Analisis Untuk Kontrol Kualitas Makanan dan Minuman, Laporan Penelitian Hibah Bersaing perguruan Tinggi, Universitas Negeri Medan
Wahab, W A, dan Nafie, L N., (2014), Metode Pemisahan dan Pengukuran 2 (Elektrometri dan Spektrofotometri), FMIPA UNHAS, Makasar