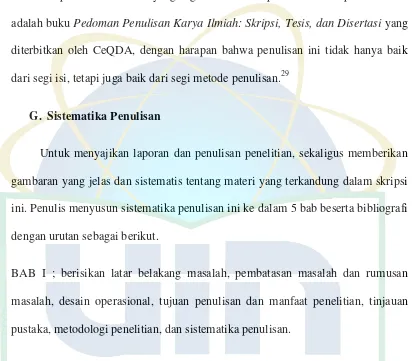TRADISI INTELEKTUAL HMI CABANG CIPUTAT 1960-1998
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora
untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana (S1) Humaniora
Mughni Labib 109022000011
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
v
Abstract
Mughni Labib 109022000011
The title of this thesis is HMI Ciputat Intellectual Tradition 1960-1998. Author tries to make a descriptive explanation about intellectual tradition that constructed by Cak Nur (Nurcholish Madjid) as the pioner of renewal idea at that time university student environment. Afterwards it was continued by the next generations. Author aims to convey about how does the spirit, the pattern of activist-intellectual cadres formation that was existed in previous time in order to enhance intellectual spirit which has begun descending among activists. This thesis is written by descriptive-qualitative research methods with socio-political and cultural approach to find out the chronology of events, processes and influential factors to the formation of intellectual tradition in HMI Ciputat environment. This research was using data collection techniques such as library research and interview to history figures for a valid data. The main problem in this thesis is different intellectual tradition pattern that has constructed by Cak Nur and next generations. As the result of this thesis, it showed that the different intellectual tradition pattern was caused by socio-political condition either at national level, or local and university, besides pop culture is also giving big influences to student movement. It can be concluded that the intellectual formation in HMI Ciputat was based on the spirit or enthusiasm to continue the intellectualization conducted by Cak Nur that gave the effect as a single fighter by the next generations. Through high level of spirit or enthusiasm of intellectual process (reading, discussion and writing) and mutual support among cadres turn the formation intellectual run well. It added
with research and political activities that create cadres of HMI Ciputat to be ‘mature’ and the
tradition should be reinstated by the rising generation in order to produce useful intellectual figures.
vi
Abstrak
Mughni Labib 109022000011
Skripsi ini berjudul ”Tradisi Intelektual HMI Cabang Ciputat 1960-1998”. Penulis mencoba mendeskripsikan tradisi intelektual yang dibangun oleh Cak Nur (Nurcholish Madjid) sebagai pelopor gagasan pembaharuan di kalangan mahasiswa saat itu. Kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Tujuan dari penulis adalah ingin menyampaikan bagaimana semangat, pola perkaderan aktivis-intelektual yang ada pada zaman sebelumnya guna meningkatkan semangat intelektual yang sudah mulai kendur di kalangan aktivis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosio-politik dan budaya untuk mengetahui kronologi peristiwa, proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya tradisi intelektual di lingkungan HMI Cabang Ciputat. Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara (interview) kepada para tokoh pelaku sejarah guna mendapatkan data yang valid. Masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah, bahwa tradisi intelektual yang dibangun oleh Cak Nur, diteruskan oleh generasi selanjutnya dalam bentuk atau pola dan wadah yang berbeda. Hasil dari temuan masalah tersebut perbedaan pola tradisi intelektual disebabkan oleh kondisi sosial-politik di tingkat nasional, maupun di tingkat lokal ataupun kampus, ditambah lagi dengan hedonisme dan pragmatisme pelan-pelan memberi pengaruh yang sangat besar dalam gerakan mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa perkaderan intelektual di HMI Cabang Ciputat didasari dari semangat ingin melanjutkan intelektualisasi yang dilakukan oleh Cak Nur yang terkesansingle fighter oleh generasi-generasi selanjutnya. Semangat tinggi dalam proses intelektual (membaca, diskusi dan menulis) serta semangat saling mendorong di antara sesama kader menghidupkan perkaderan intelektual. Ditambah dengan kegiatan-kegiatan penelitian serta
aktivitas politik membuat kader HMI Cabang Ciputat “matang” dan tradisi tersebut yang seharusnya kembali dihidupkan oleh generasi saat ini agar rahim intelektual HMI Cabang Ciputat terus menghasilkan tokoh-tokoh intelektual yang banyak bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
vii
Daftar Lampiran
Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan Ahmas Uci Sanusi Ketua Umum HMI Cabang Ciputat periode 1981-1982
Lampiran 2 : Hasil wawancara dengan Dr. Didin Syafrudin Ketua Umum HMI Cabang Ciputat periode 1984-1985
Lampiran 3 : Hasil wawancara dengan Prof. Amsal Bahtiar Sekretaris Umum HMI Cabang Ciputat periode 1985-1986
Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Saiful Mujani, P. hd. pelopor kelompok studi FORMACI.
Lampiran 5 : Hasil wawancara dengan Aris Budiono Ketua Umum HMI Cabang Ciputat periode 1990-1991
Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Sukron Kamil, MA. Ketua umum HMI Cabang Ciputat periode 1995-1996
Lampiran 7 : Hasil wawancara dengan Prof. Oman Fathurahman, Ketua Umum HMI Komisariat Adab periode 1992-1993
Lampiran 8 : Hasil wawancara dengan Dr. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si. anggota DPR RI periode 2009-2014, Aktivis BEM 1997, Aktivis FORMACI.
Lampiran 9 : Hasil bincang-bincang dengan Dra. Tati Hartimah, MA Ketua Umum KOHATI (Korps HMI Wati) periode 1980an.
viii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan kasih dan sayang-Nya, semoga rahmat dan hidayah-Nya selalu tercurah kepada kita semua, amin. Shalawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat, semoga kita sebagai ummatnya mendapat pertolongannya kelak, amin.
Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan mencapai gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah adalah membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Dalam rangka itulah penulis menyusun skripsi ini dengan judul : “TRADISI INTELEKTUAL HMI CABANG CIPUTAT
1960-1998“.
ix
Dalam rangka menelusuri jejak-jejak perkaderan intelektual yang ada di HMI, khususnya HMI Cabang Ciputat yang terkenal dengan penghasil para cendekiawan muslim, seperti Nurcholish Madjid, Atho Mudzhar, Fachry Ali, Azyumardi Azra, Komarudin Hidayat, Bahtiar Effendy dan lain-lain. Penting bagi kita untuk mempelajari proses yang mereka alami sampai mereka mapan dalam keilmuan dan menghasilkan karya yang memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia Islam di Indonesia bahkan di dunia. Untuk itu penting rupanya untuk kita mempelajari, memahami dan mengamalkan prosesnya sehingga kita bisa mengikuti jejak intelektual mereka.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak penulis temui rintangan dan hambatan. Sungguh pun begitu Alhamdulillah atas kerja keras semangat dan dukungan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungn moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa kendala yang berarti.
1. Prof. Dr. Sukron Kamil, MA, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. H. Nurhasan, MA, selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam dan
Shalikatus Sa’diyah, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Sejarah dan
x
3. Kepada dosen pembimbing Dr. H. Abdul Wahid Hasyim, MA dan Dra. Hj. Tati Hartimah, MA, yang dengan sabar dan penuh dedikasi tinggi selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan materi skripsi ini.
4. Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Adab dan Humaniora, kepada Ketua jurusan dan sekertaris serta dosen-dosen jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang memberikan sumbangsih ilmu dan pengalamannya, Pembimbing Akademik Drs H. M. Ma’ruf Misbah, MA, yang selalu bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk bertanya dan meminta solusi atas beberapa kendala yang penulis hadapi.
5. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
ix
7. Kepada Bang Eko Arisandi, S. Pd. yang telah memberikan referensi dan arahan kepada penulis untuk menemui tokoh-tokoh dengan kompetensi mumpuni dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para Kakanda/ Yunda alumni HMI atau Korps Alumni HMI (KAHMI) yang menjadi narasumber yang merupakan para pelaku sejarah sebagai sumber-sumber primer terkait penulisan skripsi ini.
9. Kepada para senior Sejarah dan Kebudayaan Islam, para senior BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Adab dan Humaniora periode 2012-2013, kanda dan yunda HMI Komisariat Adab dan Humaniora, teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Indonesian Youth, kawan-kawan di KPU (Komisi Pemilihan Umum) UIN 2013, kawan-kawan di DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) UIN 2013-2014 serta kawan-kawan seperjuangan angkatan 2009, Akhmad Yusuf, Tutur Ahsanil Mustofa, Itsna Ruhillah, Septy Tantri, Ahmad Fauzan Baihaqi, M. Kholik Bahrudin, Budi Rachmatsyah Pangabean, Rahmat Hidayatullah, Angga Maulana, Ali Nurdin, Hani Humairoh, Meilani, Aida Kusnadi, Nia R. Febrina, Ilham Muharam, Rivqi Muraham Dani, Acit, dan Amalia Rachmadanty yang tak hentinya memberikan dukungan, semangat, do’a dan tawa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam hangatnya ikatan keluarga.
x
yang menjadikan ini sebagai bahan bacaan mereka dan dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi.
Jakarta , 31 Maret 2015
xi
DAFTAR ISI
Halaman Judul ... i
Lembar Pengesahan ... ii
Lembar Pernyataan ... iv
Abstrak ... v
Daftar Lampiran ... vii
Kata Pengantar ... viii
Daftar Isi ... xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah ... 9
C. Desain Operasional ... 11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 16
E. Tinjauan Pustaka ... 16
F. Metode Penelitian ... 18
G. Sistematika Penulisan ... 20
BAB II SEJARAH SOSIAL CIPUTAT DAN IAIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA A. Sejarah Sosial Ciputat dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ... 22
BAB III HMI CABANG CIPUTAT DALAM LINTASAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA A. Berdirinya HMI Cabang Ciputat ... 30
xii
C. Nilai-nilai Dasar Perjuangan warisan Intelektual Cak Nur ... 42
BAB IV PERKEMBANGAN TRADISI INTELEKTUAL HMI
CABANG CIPUTAT
A. Cak Nur sebagai Tonggak Pewaris Tradisi Intelektual di HMI (1963-1975)... 48 B. Komunitas Intelektual (Intellectual Community)
(1975-1985)…... ... 58 C. Tradisi Intelektual pada masa Kelompok Studi (1986-1998)... .. 70 D. Relasi Tradisi Intelektual HMI Cabang Ciputat dengan
Intelektual Mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ... .. 78
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN ... 93 B. SARAN ... 96
DAFTAR PUSTAKA... 97
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lembaga pendidikan tinggi sudah ada pada saat pendudukan Jepang atas Indonesia, seperti STI (Sekolah Tinggi Islam) yang didirikan di Jakarta pada 8 Juli 1945, yang dipindahkan ke Yogyakarta pada 10 April 1946 karena pada saat itu Jakarta diduduki kembali oleh tentara Belanda dan Ibukota Negara sementara dipindahkan ke Yogyakarta. Selain STI ada juga BPTGM (Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada) yang didirikan pada 17 Februari 1946 dan inilah cikal bakal UGM (Universitas Gajah Mada).
Lembaga pendidikan sangat penting perannya dalam pembentukan intelektual dan moral mahasiswa sebagai penerus bangsa. Selain itu karena kondisi Indonesia yang sedang mengalami tekanan dari Luar yaitu Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 dan juga ada beberapa tekanan yang terjadi dari dalam seperti pemberontakan PKI di Madiun atau “Madiun Affair” pada September 1948.1 Untuk itu diperlukan mahasiswa yang memiliki intelektualitas yang tinggi serta moral yang baik untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Di Yogyakarta pada saat itu telah terdapat organisasi mahasiswa yang berideologi sosialis atau gerakan “newleft”2, yang muncul sebagai akibat
1
Prof. Agussalim Sitompul,Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975, (Jakarta: Misaka Galiza, 2008),h. 27-28
2
2
penjajahan Belanda yang membawa westernisasi, sekulerisasi terhadap pola pikir mahasiswa. Di antaranya organisasi itu adalah PMY (Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta), dan SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) di Surakarta.3 Organisasi-organisasi tersebut terseret dalam arus pemikiran sosialis, karena tidak memiliki dasar pemikiran Islam yang kuat. Padahal bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam, tetapi malah tidak memiliki organisasi mahasiswa yang berideologi Islam. Kemudian mayoritas umat Islam hanya terjebak pada hal-hal mitos.
Beberapa faktor yang disebutkan di atas menyebabkan mahasiswa STI seperti Lafran Pane mempunyai kegelisahan dan keinginan untuk menciptakan pola pikir generasi muda yang cerdas dan beriman, cerdas akal dan cerdas hati, sebagai langkah pasti memperjuangkan umat Islam, serta meninggikan semangat Nasionalisme Indonesia dengan mendirikan organisasi Mahasiswa Islam bernama Himpunan Mahasiswa Islam (yang kemudian disebut HMI) pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H yang bertepatan dengan 5 Februari 1947 di salah satu ruang kuliah STI, di Yogyakarta bersama teman-teman sekelasnya anatar lain, Asmin Nasution, Anton Timur Jailani, Dahlan Husein, Yusdi Ghozali, Kartono, Maisaroh Hilal, Suwali, Mansyur, M. Anwar, Tayeb Razak, Toha Mashudi, A. Dahlan Ranuwiharjo, dan lain-lain.4
Perjuangan secara pemikiran dilakukan seperti yang tercantum dalam konstitusi HMI yang diputuskan dalam kongres pertama di Yogyakarta tanggal 30 November 1947 yang terdapat pada tujuan HMI dalam pasal IV Anggaran Dasar disebutkan:
3
Op.Cit, h. 9 4
3
1. Menegakkan dan mengembangkan Agama Islam.
2. Mempertinggi derajat Rakyat dan Negara Republik Indonesia.5
Konstitusi (AD/ART) HMI dirumuskan dan disepakati dalam kongres pada tingkatan PB HMI. Dalam tujuan pertama yang telah dirumuskan HMI jelas terlihat bahwa kader HMI berusaha dibentuk sebagai kader umat dan kader bangsa.
Selanjutnya HMI memasuki fase pengukuhan di mana mendapat banyak reaksi dari organisasi-organisasi di luar HMI yang berasaskan sosialis. Namun, HMI dapat mengatasinya dengan baik. Selanjutnya HMI mengalami fase perjuangan fisik. Tahun 1947-1949 HMI mambantu tentara Indonesia dalam mengusir Belanda dalam Agresi Militer Belanda 1 dan 2 serta pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. HMI tergabung dalam CM (Corps Mahasiswa) berjuang secara fisik bersama mahasiswa dari organisasi lainnya, ditandai dengan pembentukan perwakilan-perwakilan dari setiap daerah.di bawah pimpinan Ahmad Tirtosudiro.6
Kemudian perjalanan HMI bukan tanpa tantangan, setelah berdirinya HMI kemudian memasuki fase konsolidasi. Terutama pembentukan cabang-cabang diberbagai daerah. Sebagai gambaran pada kongres pertama 1947 terdapat 4 cabang. Kemudian setelah kongres kedua tahun 1951 bertambah menjadi 5 cabang. Ketika kongres dilaksanakan di Jakarta, jumlah cabang bertambah menjadi 8. Saat kongres keempat di Bandung pada tahun 1955 jumlah cabang menjadi 12, dan pada kongres kelima di Medan 1957 jumlah cabang menjadi 19.
5Ibid
, h. 30
6Ibid
4
Kongres keenam di Makassar jumlah cabang bertambah menjadi 23. Lonjakan jumlah cabang meroket saat kongres HMI ketujuh di Jakarta yakni menjadi 42 cabang.7 Jumlah Cabang HMI meningkat menjadi 90 cabang saat kongres Solo pada tahun 1966.8 Dari segi kuantitas cabang, periode 1963-1966 menunjukkan kenaikan yang signifikan.
Agussalim Sitompul mencatat fase-fase sejarah HMI, yakni: pertama, fase pengukuhan, 5 Februari – 30 November 1947, yaitu ketika hadirnya HMI memperoleh reaksi dari berbagai pihak, namun dapat diatasi dengan baik. Kedua, Perjuangan Besenjata (fisik) 1947-1949. Ketiga, fase pertumbuhan dan pembangunan HMI 1950 – 1963. Pada fase pembangunan ini HMI berkembang cukup pesat. Terjadi perkembangan di dalam tujuan HMI termaktub dalam konstitusi yang berbunyi “Ikut mengusahakan terbentuknya manusia akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam.” Perkembangan tujuan ini disahkan
dalam kongres ke-4 HMI di Bandung pada 15 Oktober 1955. Selain itu, tercatat terdapat 41 jumlah cabang yang mengikuti kongres ke-7 tahun 1963 di Jakarta ini.9 Keempat, fase tantangan I 1963 – 1965. Kelima, fase kebangkitan HMI sebagai pelopor Orde Baru dan Angkatan 1966, 1966-1968. Dan keenam, fase Pembangunan 1969 – 1970.10 Pada fase tantangan I, HMI menghadapi upaya pembubaran oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dihadapi HMI dengan strategi PKI (Pengamanan, Konsolidasi, dan Integrasi). Di zaman Orde Baru
7
Pada kongres tersebut HMI komisariat Ciputat yang tadinya berada di bawah Cabang Jakarta Raya sudah menjadi Cabang sendiri.
8
M. Alfan Alfian,HMI 1963-1966; Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara, (Jakarta: Kompas Media Nusantara 2013) h. 1
9
Op.Cit, h.118, 131
10
5
(1966–1998), zaman ini dibagi ke dalam fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan angkatan 66 (1966 – 1968), fase partisipasi HMI dalam pembangunan (1969 – 2010), dan fase pergolakan dan pembaruan pemikiran (1970-1998) yang ”gong”-nya dilakukan Nurcholish Madjid (Ketua Umum PB HMI ketika itu) dengan menyampaikan pidatonya dengan topik
”Keharusan Pembaruan Pemikiran dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat”
tahun 1970 di Taman Ismail Marzuki. Pada zaman Reformasi (1998 – 2014). Zaman ini dibagi dalam fase reformasi (1998–2000) dan fase tantangan II (2000
– 2014). Dalam fase tantangan II HMI dituntut dapat terus eksis meskipun alumninya banyak tertimpa musibah dan HMI digerogoti berbagai macam permasalahan termasuk konflik internal yang ditingkat PB HMI sempat menimbulkan dua kali dualisme kepemimpinan.
Seiring dengan berjalannya waktu HMI menjadi organisasi mahasiswa yang besar. Dengan banyaknya cabang di seluruh Indonesia, jumlah kader dan alumni HMI yang tersebar di segala profesi, baik di lingkungan pemerintahan ataupun juga di tengah-tengah masyarakat, menjadi bukti sahih eksistensi HMI hingga saat ini sebagai organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia.
HMI organisasi mahasiswa Islam yang di dalamnya terdapat pola pelatihan/pendidikan yang nantinya akan membentuk karakter mahasiswa Islam yang akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Bab III pasal 4 Tujuan HMI.11 Dengan jenjang perkaderan yang semakin sistematis dan terorganisir, seperti
11
6
tahap pertama setelah perekruitan adalah Maperca (Masa Perkenalan Calon Anggota Baru), yang kemudian dilanjutkan dengan basic training (Latihan Kader 1), Intermmadiate Training (Latihan Kader 2), dan Advance Training (Latihan Kader 3), diharapkan alumni-alumni HMI ini dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya di masyarakat luas ataupun untuk nusa bangsa dan agamanya.
HMI masih dapat eksis, survive dan yang lebih penting lagi masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial – politik di Indonesia ini. Semua itu tidak lepas dari perjuangan para kader HMI pada setiap zamannya yang mampu menjalankan dan memainkan peran dalam dinamika sosial – politik di Indonesia yang diwarnai dengan kompetisi politik dan ideologi yang kental. Kemudian juga posisi HMI yang merupakan organisasi mahasiswa yang bersifat independen, tetap dihitung sebagai kekuatan sosial–politik yang penting.12
Para pemimpin HMI juga melakukan tugas dan fungsinya dalam mengelola organisasi HMI yang juga mengalami pertumbuhan yang pesat secara nasional. Kemudian juga HMI mampu merespon dan berpengaruh dalam dunia kemahasiswaan di kampus-kampus, hubungan HMI dengan politik (elite-elite birokrasi), hubungan dengan para tokoh organisasi kemahasiswaan serta organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dan juga hubungan dan pengaruh HMI di internal umat Islam dan segmen kebangsaan lainnya. Yang paling penting adalah karakter independensi HMI yang dihadapkan pada hiruk-pikuk kompetisi ideologi politik, khususnya dalam menghadapi kekuatan politik komunis. Dalam sejarah HMI yang begitu panjang dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan di
12
7
atas membuat HMI masih survive dan menjadi organisasi mahasiswa tertua dan terbesar se-Indonesia.
HMI sepanjang sejarahnya memiliki tradisi intelektual untuk menjaga kualitas kadernya ataupun dalam proses perkaderan itu sendiri. Sehingga kemampuan intelektual kader HMI tetap terjaga, sebagai usaha menjaga proses terbentuknya manusia Akademis, Pencipta, Pengabdi yang bernafaskan Islam,13 yang disahkan dalam kongres ke-4 HMI di Bandung yang menjadi formulasi dan sampai saat ini menjadi jiwa dari tujuan HMI.
Berbicara tentang tradisi intelektual di HMI tidak bisa kita pungkiri Nurcholish Madjid yang kemudian secara akrab dipanggil Cak Nur menjadi salah satu tokoh yang paling berperan dalam mengembangkan tradisi intelektual tersebut baik di HMI tingkat Nasional ataupun yang lebih khususnya pada HMI Cabang Ciputat. Dengan pemikiran pembaharuannya, Cak Nur berhasil mengubah paradigma umat Islam di Indonesia dari kejumudan yang melandanya. Umat Islam hanya berorientasi pada fiqh saja, seakan-akan Islam hanya fiqh sebagai ajaran utamanya. Saling berdebat yang tidak membawa banyak manfaat bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun banyak yang menentangnya namun lambat laun berhasil mengubah paradigma yang kolot dan jumud tersebut. Dengan kemampuan intelektualnya tersebut, Cak Nur mencoba membentuk suatu tradisi intelektual, diawali dari kawan-kawan HMI Cabang Ciputat sampai membentuk sebuah komunitas intelektual di HMI Cabang Ciputat yang saat ini berhasil membentuk tokoh-tokoh tingkat Nasional ataupun Internasional, dari tradisi intelektual yang ditumbuh kembangkan dan ditularkan oleh Nurcholish Madjid.
13
8
HMI Cabang Ciputat berdiri diawali sebuah komisariat Ciputat yang berinduk pada HMI Cabang Jakarta Raya pada tahun 1960. Dengan AM Fatwa, yang memiliki inisiatif untuk mendirikan HMI di Ciputat. Bersama teman-temannya Abu Bakar, Salim Umar, dan Komaruddin bersepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai ketua umum HMI komisariat Ciputat. Empat serangkai ini yang dengan semangat merekruit anggota-anggota baru HMI, sehingga pada tahun berikutnya. Setelah banyak anggota yang mengikuti MAPRAM14 yaitu Masa Perkenalan Anggota HMI Cabang Jakarta Raya, maka pada tahun berikutnya status HMI komisariat Ciputat ditingkatkan menjadi HMI Cabang Ciputat dan dilantik oleh Ismail Hasan Metareum (alm) sebagai Ketua Umum HMI PB.15
HMI Cabang Ciputat berdiri pada akhir rezim Orde Lama yang sangat kental dengan politik ideologi. Islam, Komunis dan Nasionalis menjadi ideologi yang sangat kuat di rezim Orde Lama tersebut. Dari politik aliran yang kental saat itu, sepertinya gesekan yang sangat terlihat terjadi antara Islam dan Komunis. Dengan propaganda yang dilancarkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dan organisasi—organisasiunderbouw yang sangat gencar untuk membubarkan HMI. Isu yang diangkat dalam propaganda tersebut adalah HMI adalah organisasi underbouw dari Masyumi16, HMI Anti Manipol Usdek, dan kontra revolusi. PB HMI dengan segala upayanya mendekatkan diri dengan pemerintah yang dikenal “adaptasi nasional” dengan tujuan agar HMI tidak jadi dibubarkan, ternyata
14
Saat itu MAPRAM adalah pelatihan awal untuk menjadi anggota HMI dan hanya bisa dilakukan oleh lembaga setingkat Cabang saja. Lihat Moh. Salim Umar, Kenangan Indah di Ciputat, dalam Membingkai Perkaderan Intelektual, Setengah Abad HMI Cabang Ciputat, ed. Rusydy Zakaria dkk, (Ciputat: HMI Cabang Ciputat, Presidium KAHMI Ciputat, UIN Jakarta Press & AM FATWA CENTER 2012), h. 24-25.
15
AM Fatwa, Op.Cit, h. 7
16
9
usaha-usaha yang dilakukan oleh PB HMI menuai kecaman dari banyak Cabang
di Indonesia. karena PB HMI dianggap “menjilat” pemerintah. Dalam kondisi
politik yang tidak stabil ini HMI Cabang Ciputat berdiri. Secara otomatis selain melaksanakan perkaderan aktivitas kader HMI Cabang Ciputat saat itu tentu dengan aktivitas politik seperti demonstrasi. Tetapi, menariknya HMI Cabang Ciputat saat dipimpin oleh Cak Nur malah lebih mengembangkan kemampuan intelektual. Dan tradisi intelektual yang dibangun oleh Cak Nur ini menginspirasi dan memotivasi kader-kader dibawahnya untuk meneruskannya.
Ini yang membuat saya tertarik menulis tentang HMI Cabang Ciputat karena dengan sejarah panjang dan besarnya dapat melahirkan tokoh-tokoh yang luar-biasa dalam pemikiran, menghasilkan banyak teknokrat, politisi, dan para pemikir. Ini menarik dibahas karena tradisi intelektual yang dibuat Cak Nur tersebut membuahkan hasil. Untuk itu tulisan ini berjudul “Tradisi Intelektual HMI
Cabang Ciputat 1960-1998”
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
HMI merupakan organisasi mahasiswa yang berorientasi kepada nilai-nilai ke-Islaman, kemudian kader–kader HMI adalah mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sesuai tujuannya didirikannya “untuk menciptakan
tenaga professional di lingkungan Departemen Agama” sebagian besar dari
10
selain Agama Islam, seperti ilmu sosial, politik, filsafat, bahkan ekonomi. Ini menjadi menarik untuk dibahas.
HMI Cabang Ciputat berdiri dalam satu kondisi politik yang tidak stabil pada rezim Orde Lama. Sehingga HMI Cabang Ciputat tentu ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik seperti demonstrasi. Tetapi HMI Cabang Ciputat malah memiliki suatu tradisi intelektual yang baik. Dan terus berkembang pada generasi-generasi kader HMI selanjutnya.
Bahwa sepanjang perkembangan tradisi intelektual yang menghasilkan banyak tokoh dari rahim intelektual Ciputat ternyata melalui proses dan pola yang berbeda-beda meskipun sama-sama terinspirasi dan termotivasi oleh Cak Nur. Tradisi intelektual mengalami perkembangan yang sangat menarik untuk diteliti.
2. Pembatasan Masalah
Agar kajian dalam skripsi ini fokus, maka perlu diadakan pembatasan
masalah terkait judul penulisan penenelitian “Tradisi Intelektual HMI Cabang
11
3. Perumusan Masalah
Adapun perumusan penelitian masalah dapat dibaca dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana muncul dan berkembangnya tradisi intelektual HMI Cabang Ciputat?
2. Mengapa kader HMI Cabang Ciputat memiliki kemampuan intelektual di luar bidang-bidang ilmu Agama?
Pertanyaan-pertanyaan di atas akan penulis jawab dalam uraian-uraian dan analisis yang didasarkan pada sumber-sumber yang penulis gunakan.
C. Desain Operasional
Dalam sub-bab ini akan menjelaskan pengertian Tradisi Intelektual. Dalam penjelasan secara umum yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Tradisi adalah Adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.17 Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Intelektual berasal dari kata intelek yang berarti kemampuan seseorang untuk mengetahui atau menerima pengetahuan. Makin berkembang intelek seseorang, makin besar kemampuannya untuk berfikir secara rasional dan intelegen. Berfikir secara rasional berarti berfikir dengan nalar atau akal sehat dan tidak terpengaruh perasaan. Sedang berfikir secara intelegen berarti mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki secara tepat untuk menghadapi situasi baru. Sedangkan intelektual berarti cerdas,
17
12
berakal, berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, mempunyai kecerdasan tinggi, menyangkut pemikiran dan pemahaman.18
Menurut pemikiran Ali Syari’ati setiap nabi adalah intelektual dalam
pengertian yang sebenarnya atau pemikir yang tercerahkan. Mereka berasal dari kelompok miskin yang tertindas oleh sistem kapitalistik dan despolitik pada zamannya.19 Nabi Muhammad tidak dilahirkan dari golongan Kapitalis (mala) atau penguasa (mutraf), tetapi dari kalangan jelata, kelas kaum tertindas (mustad’afin). Nabi Musa adalah manusia penggembala, Nabi Syu’aib dan Nabi
Hud adalah guru miskin dan Nabi Ibrahim adalah seorang tukang batu. Para nabi dari kalangan miskin tersebut hadir dalam konteks sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat yang beragam. Namun demikian, dasar-dasar dan misi mereka memiliki persamaan, yaitu menyuarakan kebenaran, membangun keadilan sosial bagi seluruh kaumnya, serta perjuangan melawan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap kaum miskin.20 Nabi Adam dilahirkan untuk memberantas kebatilan dan kebodohan. Nabi Nuh memimpin kaumnya yang lemah untuk menentang para perampas. Nabi Hud dan pengikutnya berjuang menyadarkan penguasa yang otokratik. Nabi Saleh dan kaumnya berjuang untuk menegakkan egalitarianisme sosial. Nabi Ibrahim dengan segenap kesabarannya berjuang melawan penguasa yang kejam sekaligus penyebar pengingkaran terhadap Tuhan. Nabi Yusuf adalah cerminan kaum yang terpingggirkan dan mengalami
diskriminasi. Nabi Syu’aib berjuang membebaskan kaumnya dari ketimpangan
18
Dendi Sugono dkk,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi IV, (Jakarta: Gramedia 1998) h. 541
19
Hariqo Wibawa Satria,Lafran Pane; Jejak Hayat dan Pemikirannya, (Jakarta: Penerbit Lingkar 2010) h. 114
20
13
ekonomi. Nabi Musa adalah pembebas para budak. Nabi Isa adalah pemimpin
kaum mustad’afin dalam menegakkan kebenaran. Dan Nabi Muhammad terlahir
kelas bawah, mengalami hidup di tengah masyarakat yang timpang, dan akhirnya memimpin umatnya menegakkan keadilan dan persamaan universal.21
Berdasarkan penjelasan di atas penulis berkeyakinan bahwa apapun istilahnya dan dalam peradaban apa pun diproklamirkan mengenai orang-orang yang kompetensi keilmuannya didedikasikan untuk mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan pada hakikatnya adalah sama. Titik tekan yang membedakan ada pada karya perubahan apa yang mampu dihasilkan. Singkatnya, banyaknya pengertian tentang intelektual bukanlah sebuah problem asalkan tidak menyempitkan maknanya. Sementara itu Pramoedya AnantaToer berusaha mendefinisikan kaum intelektual dengan rincian-rincian tugas yang harus diembannya sesuai dengan tanah tempat ia berada. Pram menjelaskan bahwa kaum intelektual bukan sekedar bagian dari bangsanya, melainkan ia adalah nurani bangsanya, karena bukan saja dalam dirinya terdapat gudang ilmu dan pengetahuan, terutama pengalaman kebangsaannya. Dengan isi gudangnya, ia dapat memilih yang baik dan yang terbaik untuk dikembangkan. Sehingga ia memiliki dasar dan alasan paling kuat untuk menjadi tegas dalam memutuskannya atau tidak.22 Sedangkan menurut Ahmad W. Pratikno intelektual (Cendekiawan) adalah
“Orang yang kerena pendidikannya baik formal, informal, maupun nonformal mempunyai perilaku cendekia, yang tercermin dalam kemampuannya menatap, menafsirkan, dan merespon lingkungan sekitarnya dengan sifat kritis, kreatif, objektif, analitis dan bertanggung jawab. Karena
21
Sarbini,Ibid, h. 84-85
22
14
sifat-sifat tersebut menjadikan cendekiawan memiliki wawasan dan pandangan yang luas, yang tidak dibatasi ruang dan waktu.”23
Untuk itu dalam hubungannya dengan HMI, yang merupakan organisasi mahasiswa yang berazaskan Islam, penggunaan kata intelektual muslim sangat relevan bagi para kadernya. Untuk itu M. Dawan Raharjo membagi cendekiawan muslim menjadi ke dalam tiga tipe. Pertama adalah ulama-cendekiawan yaitu cendekiawan yang berbasis pada pendidikan agama, dan pengetahuan umum mereka bisa diperoleh melalui proses otodidak, atau memang menjalani pendidikan umum lanjutan. Kedua, adalah cendekiawan-ulama yaitu, cendekiawan yang berbasis pada pendidikan umum, dan pengetahuan agama mereka biasanya diperoleh dari pendidikan keluarga yang mendalam, pendidikan agama tingkat menengah atau otodidak. Ketiga, adalah tipe cendekiawan yang berbasis pada pendidikan umum, tetapi pengetahuan agama mereka relative minim dibandingkan kedua tipe cendekiawan di atas. Walaupun pengetahuan agama mereka minim tetapi mereka memiliki kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan diri sebagai cendekiawan dengan akhlak islami dan komitmen perjuangan yang tinggi untuk mengembangkan Islam dan kemusliman bagi diri sendiri maupun orang lain, baik di bidang yang berkaitan dengan agama ataupun perubahan sosial pada umumnya.24 Untuk itu satu-satunya ukuran pasti yang dipakai dalam karya intelektual, baik intelektual barat maupun intelektual muslim adalah keabsolutan moral yang harus dipegang yaitu keadilan, kebenaran, dan akal. Ketiga hal ini akan muncul dalam tiga karakter utama yaitu: seimbang, lepas
23
Ahmad W. Pratikno, “Anatomi CendekiawanMuslim, Potret Indonesia” dalam Amien Rais
(ed.), Islam di Indonesia,(Jakarta: Rajawali, 1986) h. 3.
24
15
dari kepentingan, dan rasional.25 Untuk itu diperlukan suatu rekayasa pengorganisasian, pendidikan dan perjuangan agar nilai-nilai tersebut dapat diamalkan oleh para Intelektual Muslim.
Mengacu kembali pada Tradisi Intelektual khususnya intelektual muslim di HMI Cabang Ciputat yang menjadi tolak ukur dari pembahasan skripsi ini dapat dianalogikan seperti ini. Dalam pengertian tradisi intelektual Cak Nur dianggap sebagai nenek moyang yang melahirkan sebuah adat atau kebiasaan yang dianggap baik dan benar yang dapat mendukung proses terbentuknya kemampuan seorang intelektual muslim beserta moral-moral yang harus dimiliki, yang ditularkan Cak Nur kepada generasi penerusnya sebagai penopang perkaderan intelektual HMI Cabang Ciputat yang masih dijalankan hingga saat ini. Walaupun saat ini dapat dikatakan hasilnya tidak sebaik generasi awal setelah Cak Nur yang terkena langsung pengaruh dan semangat dari pemikiran Cak Nur. Namun, setidaknya semangat Cak Nur akan terus hidup bersamaan dengan berjalannya perkaderan di HMI Cabang Ciputat pada khususnya atau bahkan HMI se-Indonesia pada umumnya karena di dalam Materi Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI terdapat buah pemikiran Cak Nur yang akan terus hidup.
25
16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian skripsi ini bertujuan pertama, untuk mengetahui apa yang dilakukan HMI cabang Ciputat dalam menumbuhkembangkan intelektual kader
HMI.Kedua,bagaimana perkembangan tradisi intelektual HMI Cabang Ciputat.
Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Dapat memberikan wawasan yang luas tentang sejarah perjuangan HMI Cabang Ciputat yang terkenal dengan tradisi intelektualnya. 2. Memberikan manfaat bagi penulis dan para pencinta studi penelitian
sejarah dalam rangka pengembangan sejarah Islam umumnya dan khususnya tentang studi perkembangan mahasiswa Islam di Indonesia. 3. Menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan
4. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian skripsi ini, buku yang menjadi inspirasi untuk menulis penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi Intelektual HMI Cabang Ciputat
17
di HMI Cabang Ciputat. Walaupun buku ini merupakan kumpulan cerita-cerita dari pada Alumni HMI (KAHMI), namun cerita-cerita ini merupakan pengalaman langsung yang mereka gambarkan dalam buku tersebut, sehingga dapat terlihat jelas bagaimana dahulu perjuangan para KAHMI dalam berproses sebagai aktivis HMI. Mereka bukan hanya sibuk sebagai aktivis HMI yang sangat kritis terhadap pemerintahan tetapi mereka juga aktivis kampus yang sangat menonjol dalam hampir seluruh kegiatan keilmuan atau perkuliahan.
Kemampuan intelektual aktivis HMI Cabang Ciputat periode 60, 70 sampai 80-an bisa dibilang periode emas HMI Cabang Ciputat. Selain nama besar Cak Nur yang menjadi pelopor perkaderan intelektual HMI Cabang Ciputat, banyak nama yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari aktivis HMI Cabang Ciputat yang pada hari ini berhasil dengan segala macam profesinya adalah hasil dari sebuah proses perjuangan mereka sebagai aktivis HMI Cabang Ciputat.
Kemudian dari Skripsi Maria Ulfa, Jurusan SKI 2005, yang berjudul
Sejarah Berdirinya KOHATI HMI Cabang Ciputat, dan gerakan intelektualnya.
Menggambarkan tentang sejarah berdirinya organisasi perempuan di HMI Cabang Ciputat dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual mahasiswa IAIN Jakarta. Fokus kajian dari skripsi tersebut lebih kepada gerakan perempuan muslim dalam upaya pengembangan intelektual.
18
F. Metode Penelitian
Laporan Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-politik dan budaya serta metode yang digunakan adalah metode historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau26. Poin-poin penting yang akan ditulis dipaparkan sesuai dengan bentuk, kejadian, suasana pada masanya. Adapun faktor analisa pada faktor-faktor politik menjadi faktor pendukung.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah (historiografi). Oleh karena itu, upaya merekonstruksi masa lampau dari obyek yang diteliti itu ditempuh melalui metode sejarah dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencoba mendeskripsikan tradisi intelektual HMI Cabang Ciputat. Dengan demikian penelitian sejarah mencangkup:
1. Heuruistik atau teknik mencari, mengumpulkan data atau sumber (Dokumen),27. Maka dalam hal ini, penulis mengumpulan data-data sebagai bahan penulisan dan melakukan penelitian kepustakaan (Library
Research) dengan merujuk kepada sumber-sumber yang berhubungan
dengan tema dalam skripsi ini, bisa seperti buku-buku, majalah, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis mencari sumber di Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, dan beberapa toko buku yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Meminjam buku koleksi senior di HMI salah satunya
26
Louis Gottschalk,Mengerti Sejarah. terj: Nugroho Notosusanto(Jakarta: UI Press.1983), h. 32.
27
19
perpustakaan pribadi milik kanda Eko Arisandi, kemudian perpustakaan pribadi Ibu Tati Hartimah dan koleksi pribadi yang berhubungan dengan tema sebagai sumber, baik itu sumber primer seperti tulisan-tulisan Fachry Ali sebagai pelaku sejarah ataupun sekunder. Selain itu penulis juga melakukan wawancara (interview) kepada para tokoh pelaku sejarah terkait seperti alumni-alumni HMI dari Ibu Tati Hartimah, Ahmad Sanusi, Amsal Bahtiar, Didin Syafrudin, Saiful Mujani, Oman Fathurahman, Sukron Kamil, Aris Budiono, dan TB Ace Hasan Syadzily merupakan para aktivis HMI yang menjaga tradisi intelektual yang dibanggun oleh Cak Nur.
2. Tahap selanjutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber, di mana semua sumber-sumber telah terkumpul, baik berupa buku-buku, majalah, dan hasil wawancara. Maka penulis melakukan kritik dan uji terhadapnya untuk mengindentivikasi keabsahannya tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik eksteren dengan cara membandingkan tulisan-tulisan dari satu penulis dengan penulis yang lain. Selanjutnya keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang di telusuri melalui kritik interen.
20
4. Fase terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan28. Tahap ini adalah rangkaian dari keseluruhan dari teknik metode pembahasan.
Adapun sumber acuan yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah bukuPedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang diterbitkan oleh CeQDA, dengan harapan bahwa penulisan ini tidak hanya baik dari segi isi, tetapi juga baik dari segi metode penulisan.29
G. Sistematika Penulisan
Untuk menyajikan laporan dan penulisan penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam skripsi ini. Penulis menyusun sistematika penulisan ini ke dalam 5 bab beserta bibliografi dengan urutan sebagai berikut.
BAB I ; berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, desain operasional, tujuan penulisan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II ; merupakan bab inti pertama yang membahas tentang profil Ciputat dengan lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
BAB III ; merupakan bab inti kedua yang akan membahas HMI Cabang Ciputat, dari sejarah berdirinya, dan bagaimana tradisi intelektual terbentuk.
28
Ibid. h. 76. 29
21
BAB IV ; merupakan bab inti ketiga yang akan membahas perkembangan tradisi intelektual di HMI Cabang Ciputat dari periode 1960–1998.
BAB II
SEJARAH SOSIAL CIPUTAT DAN IAIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
Ciputat tahun 1960 adalah sebuah desa kecil yang posisinya ada di selatan kota Jakarta. Meskipun jaraknya cukup dekat dari Jakarta, namun hanya ada kendaraan
umum “oplet” untuk menuju ke Ciputat.1 Di sebelah Utara Ciputat berbatasan
langsung dengan Jakarta. Sebelah Selatan Ciputat berbatasan dengan daerah, Depok, dan Parung, Bogor. Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Wilayah Administrasi Jakarta Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Cisauk dan Pagedangan.
Dengan kondisi geografis Ciputat yang sangat strategis, sangat dekat dengan Jakarta sebagai Ibu kota Negara, maka itu sangat wajar jika Ciputat sangat maju dalam perkembangan ekonomi dan pendidikan. Pada tahun 1950 dikeluarkan PP No. 34 tahun 1950 tentang perguruan tinggi Islam Negeri di bawah Departemen Agama guna mencetak pegawai dan guru yang berkualitas di lingkungan Departemen Agama di seluruh Indonesia dan dengan PP tersebut didirikanlah ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) pada 1 Juni 1957.2ADIA inilah cikal bakal dari IAIN dan UIN.
Kemudian pada tahun 1964 Soekarno telah memberikan tanah seluas 200 hektare untuk pembangunan kampus UI di Ciputat setelah melihat Ciputat dari udara.
1
A.M. Fatwa, Catatan Awal Berdirinya…., dalam Rusydy Zakaria, dkk, ed., Membingkai
Perkaderan Intelektual, (Ciputat: HMI Cabang Ciputat, Presidium KAHMI Ciputat, UIN Jakarta Press dan AM FATWA Center, 2012) h. 7
2
Namun tanah yang dibebaskan baru 8,5 hektar dan di lapangan ternyata kurang dari 6 hektar wilayah yang bisa dibangun untuk menjadi kampus UI. Pada 28 September 1965 Presiden Soekarno meletakkan batu pertama dan menandatangani prasasti pembangunan kampus UI. Namun pembangunan kampus UI tidak pernah terlaksana karena dua hari setelah itu terjadi G30S/PKI. Lahan yang diperuntukkan menjadi kampus UI kini telah menjadi komplek dosen UI.3 Ini bukti bahwa Ciputat dahulu sangat strategis sehingga sempat direncanakan untuk pembangunan kampus UI dan pembangunan kampus ADIA (saat ini UIN).
Saat berdirinya HMI komisariat Ciputat berinduk pada Cabang Jakarta Raya, Ciputat merupakan sebuah kecamatan, di bawah Kabupaten Banten dan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ketiga setelah pendiriannya, HMI komisariat Ciputat meningkatkan statusnya menjadi Cabang mengingat sangat jauhnya posisi komisariat Ciputat dengan Cabang Jakarta Raya dan mulai banyaknya mahasiswa yang mengikuti pelatihan kader di HMI komisariat Ciputat, maka ditingkatkanlah HMI Komisariat Ciputat, menjadi HMI Cabang Ciputat.4Sebelum membahas HMI Cabang Ciputat kita harus mengetahui demografi wilayah tempat HMI Cabang Ciputat berdiri.
Ciputat merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Banten, di propinsi Jawa Barat. Ciputat merupakan daerah strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, karena itu Ciputat sering dianggap bagian dari Jakarta Selatan. Termasuk
3
Azwil Nazir, Sejarah Komplek Dosen UI di Ciputat, diakses tanggal 02 Februari 2014
http://Azwilnazir.com/2014/02/02/1482 4
A.M. Fatwa,Catatan Awal Berdirinya…., dalam Rusydy Zakaria, dkk, ed., Membingkai
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kendatipun berdomisili di Ciputat tetapi secara administratif berada di DKI Jakarta.
Ciputat tahun 1960-an pada waktu HMI komisariat Ciputat, Cabang Jakarta Raya didirikan, masih merupakan daerah yang cukup sepi. Walaupun letaknya tidak begitu jauh dengan Jakarta, tetapi akses kendaraan umum dari Jakarta menuju Ciputat atau sebaliknya tidak begitu baik. Kendaraan umum dari Jakarta menuju Ciputat hanya ada dari Kebayoran Lama, itupun tidak banyak kendarannya.5 Penduduk di Ciputat semakin berkembang dan bertambah banyak dikarenakan adanya lembaga pendidikan tinggi yang berdiri di sana, yaitu ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) pada tahun 1957 yang kemudian menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta. IAIN ini yang menjadi salah satu faktor semakin banyak dan berkembangnya penduduk di Ciputat disebabkan mahasiswa yang mengampu pendidikan di IAIN semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun.
Status ADIA berubah menjadi IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960 dengan Peraturan Pemerintah No. 11 yang menggabungkan PTAIN dan ADIA dengan nama baru IAIN (Institut Agama Islam Negeri) yang berpusat di Yogyakarta dan Prof. Mr. R.H. A. Soenarjo ditunjuk sebagai Rektor, dibantu oleh Prof. T.M. Hasby
Ash-Shiddieqy sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Dr. Muchtar Yahya sebagai Dekan
Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Yogyakarta. Sementara itu kampus yang berkedudukan di Jakarta menjadi Fakultas Tarbiyah dengan Prof. Dr. Mahmud Yunus
sebagai dekannya dan Fakultas Adab dengan Prof. Bustomi A. Gani sebagai dekannya.6
Dalam perkembangannya, pemusatan IAIN yang hanya ada di dua kota tidak dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat di seluruh negeri untuk belajar agama Islam. Menanggapi aspirasi yang berkembang, pada tahun 1960, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) melalui TAP-nya merekomendasikan IAIN untuk dikembangkan di beberapa daerah. Dalam waktu 3 tahun untuk menanggapi aspirasi dari masyarakat Indonesia, dikembangkan IAIN menjadi 18 fakultas yang tersebar di seluruh negeri. Fakultas Tarbiyah didirikan di Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Banda Aceh. Fakultas Adab didirikan di Jakarta dan Yogyakarta.
Fakultas Ushuluddin didirikan di Yogyakarta dan Jakarta. Fakultas Syari’ah didirikan
di Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Serang, dan Ujung Pandang.
Dalam perkembangan IAIN yang pesat, Departemen Agama mengeluarkan keputusan penting No. 49 tahun 1963 tentang peningkatan IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta menjadi lembaga independen. Sejak saat itu IAIN Yogyakarta menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkoordinasi seluruh fakultas di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara IAIN Jakarta mengkoordinasi fakultas di Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera. Perkembangan kampus IAIN tersebut tidak
6
6
dibarengi dengan kendaraan umum menuju Ciputat masih cukup sulit. Sampai pertengahan tahun 1970-an hanya ada bus Gamadi, Ajiwirya, dan mobil swif yang arahnya dari Blok M menuju Ciputat. Bahkan aktivis HMI saat itu jika mengikuti kajian di luar Ciputat, untuk berangkat dan pulang menggunakan mobil bak terbuka.7
Dalam upaya peningkatan mutu dan menampung permintaan masyarakat untuk pendidikan tinggi agama Islam, cabang-cabang IAIN di beberapa tempat ditingkatkan menjadi IAIN yang terpisah dan mandiri. Peraturan Pemerintah No. 27, tanggal 5 Desember 1963. Berdasarkan keputusan tersebut, IAIN Jakarta menjadi mandiri, hal yang sama terjadi juga pap IAIN ar-Raniry Banda Aceh pada tahun yang sama, IAIN Raden Fatah Palembang pada 22 Oktober 1964, IAIN Antasari di Kalimantan Selatan pada 22 November 1964, IAIN Sunan Ampel di Surabaya pada 6 Juli 1965, IAIN Alaudin Ujung Pandang pada 28 Oktober 1965, IAIN Imam Bonjol Padang pada 21 November 1966, dan IAIN Sultan Taha Saefudin di Jambi pada tahun 1967.8
Pada masa Orde Baru Pemerintah tidak melakukan kebijakan baru apapun, hanya meneruskan kebijakan—kebijakan lama pada masa Orde Lama. Karena pada awal Orde Baru pada 1967–1971 Kementerian Agama masih dipimpin oleh Saifudin Zuhri dan KH. Mohammad Dachlan dari Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga secara otomatis tidak ada juga perkembangan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selain bertambahnya mahasiswa.
7
Wawancara pribadi dengan Tati Hartimah, Ketua Umum KOHATI Cabang Ciputat periode 1978-1979, Cirendeu, 14 Agustus 2014
8
27
Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Harun Nasution (1973–1984), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikenal luas sebagai kampus pembaharu. Hal ini disebabkan karena Harun Nasution banyak mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam pemikiran Islam dengan menekankan pada Islam rasional. Harun Nasution mengadakan perubahan kurikulum IAIN yang salah satunya memasukkan matakuliah filsafat dan menyelenggarakan Program Pascasarjana (PPs). PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini merupakan PPs pertama di lingkungan IAIN di seluruh Indonesia. PPs ini mengawali perkuliahan pada tanggal 1 September 1982. Setelah peresmian pada 30 Agustus 1982.9 Selain itu untuk memperkuat pemikiran pembaharuan Islam, Harun Nasution melakukan kuliah umum setiap dua minggu sekali dan dia sebagai pemberi materinya.
Di IAIN Jakarta pada periode 1973 – 1978 tercatat beberapa orang telah dikirim untuk melanjutkan ke luar negeri antara lain: ke Australia 6 orang, Inggris 2 orang, Mesir 7 orang, Sudan 2 orang, Kanada 9 orang, Singapura 1 orang, dan Belanda 8 orang. Sebelumnya tidak pernah ada kebijakan di Departemen Agama yang seperti itu. Pada periode ini Departemen Agama dipimpin oleh Mukti Ali.10 Ini memberikan kesempatan pada kader-kader terbaik HMI dan mahasiswa terbaik IAIN untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Seperti yang didapat oleh M. Atho Mudzhar, Mulyadi Kartanegara, Azyumardi Azra, Komarudin Hidayat, Bachtiar Effendy, Saiful Mujani, Fuad Jabali, Alimun Hanif, Oman Fathurahman dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Program ini dilakukan untuk meningkatkan
9
Tim Penyusun,Buku Pedoman Akademik tahun 2010, (Ciputat: UIN Jakarta 2010), h. 8 10
28
mutu IAIN di Indonesia. Namun, program ini sempat vakum sampai beberapa tahun dengan alasan yang tidak begitu jelas. Sampai pada akhir 1985, semenjak Departemen Agama dipimpin oleh Munawir Sjazali, kebijakan ini dilanjutkan secara formal. Oleh Munawir program ini merupakan salah-satu pilot project yang menjadi prioritas progam kerjanya.11
Perkembangan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selain dipengaruhi oleh Rektor yang menjadi pimpinannya, tetapi juga sangat bergantung pada kebijakan dari Departemen Agama. Karena IAIN di bawah naungan Departemen Agama. Sejak diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1988, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, Fakultas
Ushuluddin, Fakultas Syari’ah dan Fakultas Dakwah.12
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama ini hanya ada fakultas agama dan jurusan-jurusan tentang agama. Perkembangan paling besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ketika tahun 1998 saat Azyumardi Azra menjadi Rektor. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjadi simbol umat Islam dan kemajuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan sosial-kegamaan. Perlu upaya untuk mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, lembaga ini mulai mengembangkan diridengan konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas. Langkah ini dimulai dengan dibukanya jurusan Psikologi, Pendidikan Matematika, Ekonomi, dan Perbankan Islam pada tahun 1998. Ini adalah langkah awal perubahan IAIN menjadi UIN
11
Ibid, h. 25 12
29
(Universitas Negeri Islam).13 Pada periode ini 1998 Ciputat sudah menjadi daerah yang cukup ramai. Dengan akses kendaraan umum yang cukup mudah. Sehingga semakin banyak calon mahasiswa yang ingin berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
13
BAB III
HMI CABANG CIPUTAT
A. Dinamika Awal Berdirinya HMI Cabang Ciputat
Bisa dikatakan tradisi intelektual di HMI Cabang Ciputat dimulai oleh Cak Nur, meskipun pendirian HMI Cabang Ciputat adalah atas inisiatif A.M. Fatwa, Abu Bakar, Salim Umar, dan Komarudin. Sebelum berkuliah di ADIA Jakarta A.M. Fatwa pernah mengikuti dan aktif dalam PII di dearah, dari ketua Cabang Sumbawa Besar, dan ketua Wilayah Nusa Tenggara.1Selain itu, sebelum A.M. Fatwa kuliah di ADIA, dia juga sempat berkuliah di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta dan telah
mengikuti “perkaderan” HMI di Cabang Jakarta. Dengan pengalaman besentuhan
langsung dengan HMI, A.M. Fatwa berinisiatif mendirikan komisariat Ciputat pada tahun 1960 saat ADIA berkembang menjadi IAIN di bawah naungan Departemen Agama dan statusnya menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri).2Abu Bakar dipilih sebagai Ketua Umum, Moh. Salim Umar sebagai ketua I, dan A.M. Fatwa sebagai ketua II HMI komisariat Ciputat yang dilantik oleh Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Alwi Al-Djahwasyi.3
1
A.M. Fatwa, Catatan Awal Berdirinya dan Dinamika Aktivis HMI Cabang Ciputat, dalam Rusydy Zakaria dkk, ed.,Membingkai Perkaderan Intelektual, Setengah Abad HMI Cabang Ciputat, (Ciputat: HMI Cabang Ciputat, Presidium KAHMI Ciputat, UIN Jakarta Press, AM Fatwa Center, 2012) h. 3. Pada saat itu setiap alumni PII dari semasa sekolah sebagai pelajar, saat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, otomatis akan dengan sendirinya untuk mengikuti atau bergabung dengan HMI, mengkuti hasil dari Muktamar Muslimin Indonesia yang ke-2 yang berlangsung di Yogyakarta pada 20-25 Desember 1949. Pada saat itu juga kondisi Umat Muslim masih bersatu padu sehingga hasil kongres atau muktamar umat Muslim Indonesia masih dijalankan dengan baik.
2
IAIN Jakarta sendiri tadinya adalah cabang dari IAIN Yogyakarta, namun pada akhirnya menjadi pusat sendiri dan terlepas dari IAIN Yogyakarta.
3
Setahun kemudian pada tahun 1961 setelah memiliki anggota yang cukup banyak, pengurus komisariat Ciputat memiliki keinginan untuk meningkatkan statusnya menjadi HMI Cabang Ciputat. Inisiatif itu diambil karena masalah jauhnya komisariat Ciputat dengan Cabang Jakarta. Maka dilakukan Rapat Anggota sekaligus pemilihan pengurus Cabang melalui formatur. Dalam pemilihan tersebut, kembali terpilih 3 orang formatur yaitu, Abu Bakar, Moh. Salim Umar dan A.M. Fatwa masing-masing secara berurutan sebagai ketua umum, ketua I dan ketua II, HMI Cabang Ciputat. Setelah dilakukan timbang-terima jabatan dari Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Alwi Al-Djahwasyi, dan pengurus HMI Cabang Ciputat dilantik oleh Norsal (Ketua Umum PB HMI periode 1960-1963).4 Pada awal berdirinya HMI Cabang Ciputat memiliki beberapa komisariat yang merupakan fakultas-fakultas di
lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu: Tarbiyah, Syari’ah, Adab dan
Ushuludin.
Sebelumnya saat menjadi komisariat Ciputat, untuk menjadi anggota HMI harus mengikuti MAPRAM yaitu Masa Perkenalan Anggota HMI di Cabang Jakarta. Setelah memiliki banyak kader, HMI komisariat Ciputat meningkatkan status menjadi HMI Cabang Ciputat dan menyelenggarakan MAPRAM HMI sendiri, dan makin bertambah banyaklah anggota HMI Cabang Ciputat. Kegiatan HMI Cabang Ciputat selanjutnya ialah mengirimkan beberapa anggotanya mengikuti Basic Training pada cabang-cabang HMI di kota lain, seperti Cabang Jakarta, Cabang Bandung, Cabang Yogyakarta, dan lain-lain. Kemudian juga menyelenggarakan Basic Training sendiri
4Ibid
yang diikuti pula oleh cabang-cabang lain.5 Saat itu Basic Training adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh setingkat Cabang, dan dalam lingkup nasional (saat ini seperti LK II Intermadate Training).
Pada kepengurusan periode 1962 – 1963 terpilihlah Moh. Salim Umar sebagai Ketua Umum, A.M. Fatwa sebagai ketua I, Sokamakarya sebagai ketua II, dan Nurcholish Madjid sebagai sekretaris umum. Inilah awal mulanya Nurcholish Madjid ikut bergabung dalam kepengurusan HMI, walaupun pada mulanya mendapat banyak tolakan, karena Nurcholish Madjid belum pernah menjadi pengurus komisariat.6
Saat awal berdirinya HMI Cabang Ciputat bukan tanpa halang rintang, situasi tingkat Nasional yang sedang bergejolak, PB HMI mendapat tekanan dari CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi underbow PKI, memulai gerakan “mengganyang HMI”. Aksi pertama tekanan yang dilakukan CGMI pada tahun 1962, dalam kongres PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) yang merupakan wadah dari organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia, CGMI berhasil melakukan propaganda dan mengeluarkan HMI dalam kongres tersebut. Keadaan tersebut menggambarkan posisi PB HMI yang lemah ditingkat nasional. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh CGMI, HMI adalah anak partai terlarang Masyumi, anti Manipol USDEK (Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifestasi Politik/ Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang oleh Presiden
5
Moh. Salim Umar, Kenangan Indah di Ciputat, dalam Membingkai Perkaderan Intelektual, Setengah Abad HMI Cabang Ciputat, ed. Rusydy Zakaria dkk, h. 25.
6
Soekarno dijadikan haluan Republik Indonesia.)7, organisasi kontra-revolusi dan lain-lain. Tuntutan-tuntutan itu tidak hanya meraka lancarkan dalam forum-forum pertemuan kemahasiswaan seperti pada sidang MMI (Majelis Mahasiswa Indonesia), tetapi juga dalam rapat-rapat terbuka, bahkan dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi. Hampir setiap hari, surat kabar yang mereka miliki (Harian Rakyat dan Bintang Timur) memuat berita-berita besar tuntutan pembubaran HMI.8
Pada 17 Oktober 1963 Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Syarif Hidayatullah melakukan demonstrasi yang dimotori oleh Salim Umar sebagai Sekretaris Dewan Mahasiswa IAIN Jakarta dan Ahmad Mudzakkir (alm.) sebagai Ketua Dewan Mahasiswa IAIN Jakarta. Posisi Salim Umar yang ketika itu menjadi Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, membuat banyak kader HMI Cabang Ciputat itu melakukan demonstrasi. Demonstrasi bersumber dari ketidakpuasan mahasiswa terhadap dominasi golongan tertentu di lingkungan Departemen Agama dan IAIN. Saat itu menteri agama dijabat oleh KH. Saefudin Zuhri, sedangkan rektor IAIN Jakarta dijabat oleh Prof. Drs. H. Soenardjo. Peristiwa yang sama juga terjadi satu pekan sebelumnya di IAIN Yogyakarta bahkan sampai menggagalkan Sidang Senat Terbuka. Dalam demonstrasi di Ciputat para mahasiswa menyatakan ketidaksenangannya terhadap pola yang serba NU (Nahdatul Ulama) di lingkungan IAIN. Departemen Agama sangat didominasi oleh NU. Hampir semua posisi penting
7
Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 1947–1975, (Jakarta: Misaka Galiza, 2008) h. 38
8
4
dan menentukan kebijakan-kebijakan Departemen Agama dipegang oleh NU. Dominasi ini melebar ke IAIN. Bahkan Departemen Agama merubah struktur pimpinan akademis seperti rektor, dekan sampai ke staf administratif.9 Kejadian ini dimotori oleh HMI dikarenakan saat itu belum ada organisasi mahasiswa yang berafilias non-NU selain HMI.10
Demonstrasi di IAIN Yogyakarta dan Ciputat ini menjadi masalah penting di awal kepengurusan PB HMI periode 1963 – 1966 di bawah kepemimpinan Sulastomo, merasa bertindak cepat dan tegas. Peristiwa ini dinilai sangat tidak menguntungkan, baik dari segi kepentingan nasional maupun kepentingan umat. Dari kepentingan nasional, PB HMI merasa perlu menggalang kekuatan-kekuatan serta pemersatu umat. Tampaknya tidak mungkin, serangan yang gencar dilakukan oleh CGMI dan PKI pada saat itu dihadapi tanpa adanya dukungan seluruh umat Islam khususnya dan kekuatan-kekuatan antikomunis lain pada umumnya. Dalam keadaan seperti ini, peranan Partai NU sangat penting selain bagian Islam dan kekuatan anti-komunis, NU juga saat itu masuk dalam pemerintahan Soekarno. Atas dasar pertimbangan inilah dalam rangka kepentingan nasional, PB HMI mengeluarkan kebijakan untuk memberi sanksi kedua peristiwa yang terjadi di Yogyakarta dan Ciputat tersebut. Selanjutnya, PB HMI memutuskan pengurus HMI Cabang Yogyakarta yang baru terpilih tidak disahkan dan kepengurusan yang lama diperpanjang masa jabatannya. Sedangkan pengurus HMI Cabang Ciputat dibekukan
9
Fuad Jabali & Jamhari, IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003), h. 16
10
dan ditunjuklah Syarifudin Harahap, atas nama PB HMI sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, kepengurusan HMI Cabang Ciputat sejak saat itu diambil alih oleh PB HMI sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
Di Ciputat sendiri peristiwa 1963 ini menimbulkan trauma psikologis bagi kader-kader HMI. Karena dalam peristiwa ini terdapat kader-kader HMI yang ditangkap dan mendekam di penjara, termasuk para dosen yang dianggap mendukung peristiwa itu. Beberapa aktivis HMI sperti, AM. Fatwa, Salim Umar, Ali Husen, Jalaluddin Suyuti, Syaifudin Faturusi dan kawan-kawan yang lain ikut mendekam di penjara akibat tindakan represif aparat dengan tuduhan kontra revolusi dan merongrong kewibawaan Presiden Pimpinan Besar Revolusi. Pembekuan HMI Cabang Ciputat sendiri berdampak pula pada seluruh proses perkaderan HMI di Ciputat yang lumpuh total dalam waktu yang cukup lama. Kader-kader HMI khawatir menjadi korban penangkapan, sehingga seolah-olah HMI menjadi organisasi yang menakutkan bagi mahasiswa selain kader HMI. Keadaan ini menjadi hal yang tidak mudah untuk menghidupkan kembali perkaderan di Ciputat. Terutama bagi M. Salim Umar yang saat itu menjabat sebagai ketua umum, bahkan dia sendiri sempat dipaksa mundur dari jabatannya. Baru setelah keadaan membaik, didorong kader-kader yang lebih muda seperti Nurcholish Madjid dan Musthoha, perkaderan di HMI Cabang Ciputat mulai berdenyut kembali pada periode berikutnya.
6
Nurcholish Madjid terpilih menjadi Ketua Umum HMI Cabang Ciputat untuk periode 1964-1965.11Cak Nur inilah yang mengawali perkaderan intelektual di HMI Cabang Ciputat. Karyanya yang sangat penting pada fase ini adalah risalah kecil berjudul
Dasar-Dasar Islamisme yang menjadi materi pelatihan dalam training-training HMI
saat itu. Dalam membuat karyanya itu Cak Nur terinspirasi materi yang dibawakan
oleh Mar’ie Muhammad dari buku Islam dan Sosialisme karya H.O. S.
Cokroaminoto.12Materinya yang Cak Nur buat yang berjudulDasar-dasar Islamisme
awalnya sering dibawakan di HMI Cabang Ciputat saja. Materi yang Cak Nur bawakan terdengar oleh Ketua Badko13 (Badan Koordinasi) Jawa Barat Ahmad Nurhani dan meminta Cak Nur membawakan materinya ke seluruh pelatihan yang dilakukan cabang-cabang HMI se-Jawa Barat. Aktivitasnya memberi ceramah di Badko se-Jawa Barat terdengar oleh Pengurus Besar HMI yang ketika itu Ketua Umumnya Sulastomo. Akhirnya Cak Nur ditarik dalam kepengurusan di PB HMI dengan tugas untuk memberikan ceramah tentang materinya tersebut.14
Sebelum menjadi Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, Cak Nur sudah sering muncul dalam forum-forum nasional sebagai juru bicara HMI Cabang Ciputat, salah
11
Menurut Fachry Ali yang terpenting bukanlah mengenai jabatan-jabatan yang diemban oleh Nurcholish Madjid, saat sebagai Ketua Umum Cabang HMI, Ketua Badko HMI Jawa Barat atau saat menjabat sebagai Kteua Umum PB HMI selama dua periode, tetapi yang terpenting adalah HMI Cabang Ciputat telah memberi wadah pertama bagi kreasi intelektual Nurcholish Madjid untuk diwariskan. Lihat Fachry Ali Prolog;Lima Puluh Tahun HMI Cabang Ciputat; sebuah Narasi tentang Warisan Intelektual, h. xxvi
12
Ahmad Gaus AF, Api Islam Nurcholish Madjid, Jalan Hidup Seorang Visioner, (Jakarta: Kompas, 2010) h. 38
13
Badan Koordinasi (Badko) adalah badan pembantu Pengurus Besar. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang di bawah koordinasinya. Masa Jabatan Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar. Lihat Anggaran Rumah Tangga HMI BAB II Struktur Organisasi, Bagian V. Badrudduja, Arridho Sugiarto, Modul LK I basic training HMI Cabang Ciputat, (Ciputat: HMI Cabang Ciputat, 2011) h. 46
14
satunya saat ketika kongres HMI ke-7 di Masjid Agung al-Azhar, yang diselenggarakan pada tanggal 8-14 September 1963. Saat itu, PB HMI melakukan kebijakan adaptasi nasional sebagai usaha menyelamatkan HMI dari ancaman isu pembubaran HMI. Pro-kontra muncul dari cabang-cabang utusan Kongres. Cak Nur atas nama HMI Cabang Ciputat menyampaikan pandangan yang menentang keras kebijakan adaptasi nasional yang dilakukan oleh PB HMI. Nurcholish langsung mendapat teguran secara lisan dari para senior HMI Cabang Ciputat saat itu seperti A.M. Fatwa.
Dengan aktivitasnya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, sekaligus bagian dari PB HMI yang bertugas memberikan ceramah tentang materinya yang berjudul Dasar-dasar Islamisme hampir di seluruh Cabang di Indonesia, Cak Nur menjadi terkenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan dalam Islam. proses inilah yang membuat Cak Nur kemudian terpilih sebagai ketua umum PB HMI selama dua periode berturut-turut (1966-1969 dan 1969-1971). Pada fase ini Nurcholish tercatat antara lain merumuskan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai naskah ideologis yang sampai sekarang masih dipakai pada setiap pelatihan di HMI. Pada saat memimpin PB HMI Nurcholish Madjid sering melontarkan ide-ide pembaharuan dalam berbagai tulisannya seperti “Modernisasi ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi”, “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”
dan lain-lain. Meskipun terjadi pro-kontra, namun ide-ide pembaharuannya mencatatkan namanya sebagai “kader intelektual”15 dalam HMI. Diakui atau tidak,
15
8
prestasi dan ketokohan Nurcholish Madjid tak terelakan kemudian membangun citra baik bagi HMI Cabang Ciputat sebagai perkaderan intelektual yang membedakan dengan cabang-cabang lain.16
Terlepas dari berbagai penafsiran lainnya, perkembangan tradisi intelektual di lingkungan HMI Cabang Ciputat yang kian lama kian ajeg ini merupakan respon dari generasi selanjutnya terhadap tradisi intelektual yang dilakukan Cak Nur di Ciputat. Pada fase awal perkembangan tradisi intelektual ini, tokoh yang paling langsung menorehkan pengaruhnya adalah M. Dawam Raharjo yang memberikan kesempatan perkembangan intelektual sehingga kader-kader HMI Cabang Ciputat terbawa dalam berbagai intellectual events tingkat internasional.17
B. Kualitas Insan Cita HMI
Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Begitu pula
dengan HMI. HMI memiliki tujuan “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi
yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.” Sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar HMI pasal IV yang disahkan dalam kongres ke-9 di Malang pada tanggal 3–10 Mei
16
Pengalaman ini didapat hampir rata-rata kader HMI Cabang Ciputat yang sedang berkunjung ke HMI cabang lain, semisal dalam mengikuti LK 2. Kader-kader Ciputat terkesan masih dihormati oleh cabang-cabang lain se-Indonesia. Kader-kader HMI Cabang Ciputat akan heran, karena kader-kader HMI dari cabang lain sangat antusias bertanya tentang Cabang Ciputat, atau bahkan terkesan kagum dengan Cabang Ciputat. Hal ini tak lain karena karya-karya alumninya serta banyak tokoh Nasional berasalan dari HMI Cabang Ciputat.
17
Fachry Ali, “Intelektual, Pengaruh Pemikiran dan Lingkungannya” pengantar dalam