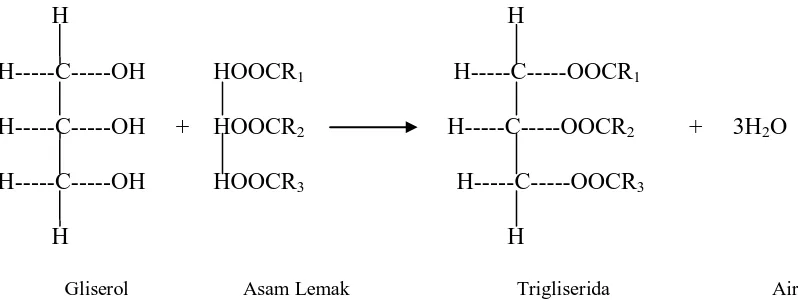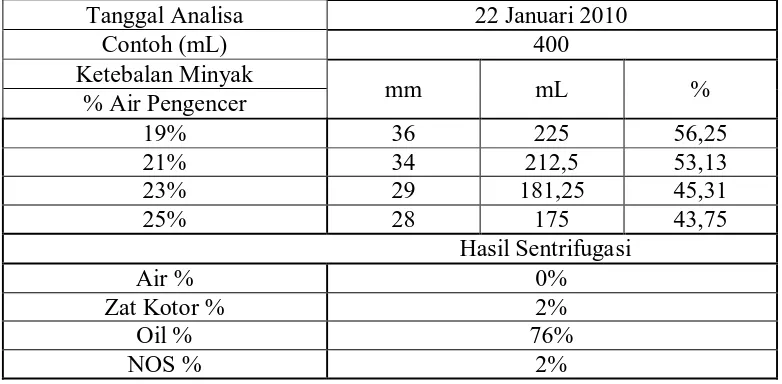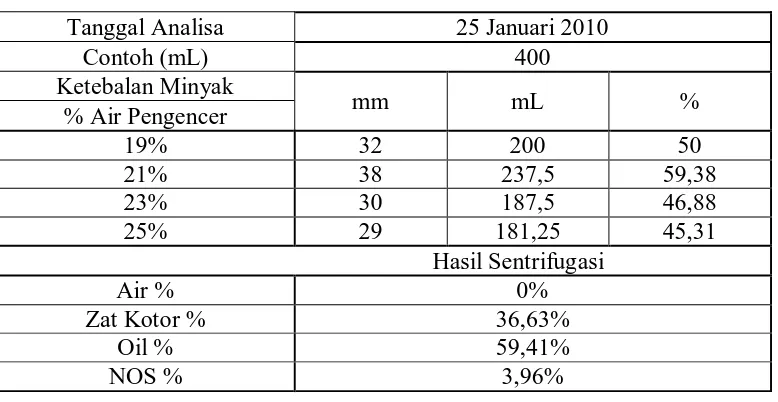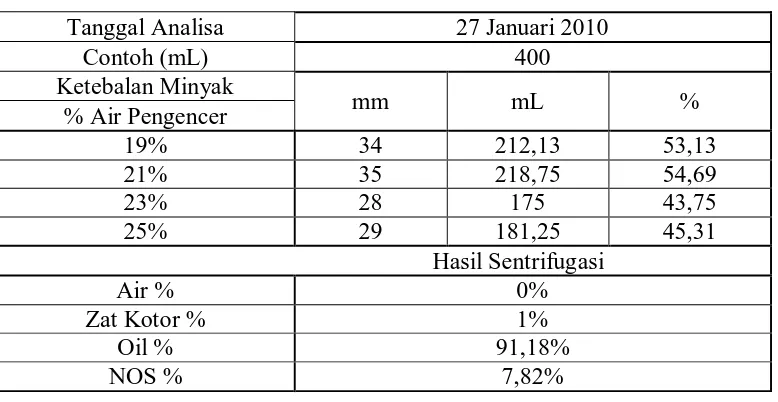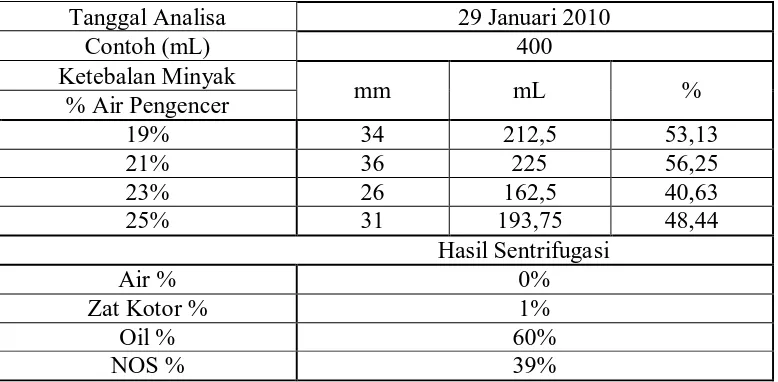PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH AIR PENGENCER
TERHADAP EFISIENSI PEMISAHAN MINYAK DARI CAIRAN
PADA STASIUN PRESSAN DI PTP NUSANTARA IV PULU RAJA
KARYA ILMIAH
FITRI JUNIAWATI
072409042
DEPARTEMEN KIMIA
PROGRAM STUDI D3 KIMIA INDUSTRI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
ii
PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH AIR PENGENCER
TERHADAP EFISIENSI PEMISAHAN MINYAK DARI
CAIRAN PADA STASIUN PRESSAN DI PTP NUSANTARA IV
PULU RAJA
KARYA ILMIAH
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Ahli Madya
FITRI JUNIAWATI
072409042
DEPARTEMEN KIMIA
PROGRAM STUDI D3 KIMIA INDUSTRI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
PERSETUJUAN
Judul : PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH AIR PENGENCER TERHADAP PEMISAHAN MINYAK DARI CAIRAN PADA STASIUN PRESSAN DI PTP NUSANTARA IV PULU RAJA
Kategori : TUGAS AKHIR
Nama : FITRI JUNIAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 072409042
Program Studi : D3 KIMIA INDUSTRI
Departemen : KIMIA
iv
PERNYATAAN
PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH AIR PENGENCER TERHADAP EFISIENSI PEMISAHAN MINYAK DARI CAIRAN PADA STASIUN
PRESSAN DI PTP NUSANTARA IV PULU RAJA
KARYA ILMIAH
Saya mengakui bahwa karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali
beberapa kutipan dan ringkasan masing – masing disebutkan sumbernya.
Medan, Mei 2010
FITRI JUNIAWATI
PENGHARGAAN
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi-rabbil’alamin penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kasih saying-Nya
kepada kita semua serta salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai
salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada program Diploma 3 Kimia
Industri di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera
Utara.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini jauh dari kata
kesempurnaan karena keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan, pengetahuan
dan waktu, tetapi penulis ini berharap karya ilmiah ini dapat berguna bagi penulis dan
semua pihak yang membaca karya ilmiah ini khususnya serta lingkungan Universitas
Sumatera Utara pada umumnya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik
dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.
Selama penulisan karya ilmiah ini penulis banyak mendapatkan doa dan
dukungan, bantuan dan petunjuk dari dari semua pihak, maka pada kesempatan ini
dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima
kasih yang sebesar-besarnya :
1. Kedua orangtua saya yang telah banyak memberikan dukungan baik moril
maupun materil serta kasih sayang dan kesabaran yang begitu banyak kepada
saya.
vi
3. Dosen Pembimbing saya Dr.Marpongahtun, M.Sc. yang telah sabar selama
membimbing saya dan memberikan banyak kritikan dan saran yang
membangun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Kepala Laboratorium Pak Ginting dan seluruh staf yang ada di Lab di PTP
Nusantara IV Pulu Raja yang banyak memberikan saran dan masukan serta
memperbolehkan menganalisa sampai memperoleh data untuk melengkapi
karya ilmiah ini.
5. Kepada Kepala Dinas Pengolahan, Bapak Sakry yang telah memberikan
saran dalam menentukan judul karya ilmiah ini dan seluruh staf yang ada di
kantor ISO dan di kantor Administrasi.
6. Ibu kos saya yang telah mengizinkan saya tinggal dan memberikan fasilitas
selama saya PKL disana.
7. Teman-teman PKL saya, Mira dan Reni
8. Teman-teman satu angkatan 2007 di Kimia Industri yang telah memberikan
dukungan dan bantuan selama menyelesaikan karya ilmiah ini.
Hanya doa yang dapat penulis sampaikan kepada Allah SWT.
Mudah-mudahan kebaikan yang diterima penulis dari semua pihak yang telah membantu,
kiranya Allah SWT dapat membalas kebaikan tersebut. Penulis dengan segala
kemampuan berusaha menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Apabila
ada kekurangan, kesalahan, kritik dan saran penulis terima dengan senang hati.
Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan berharap semoga
tulisan ini bermanfaat bagi yang membacanya.
Medan, April 2010
Penulis
ABSTRAK
viii
THE INFLUENCE OF DILLUTION WATER ADDITION TO OIL SEPARATION EFFECIENCY THE LIQUID FROM PRESSING STATION IN
PTP NUSANTARA IV PULU RAJA
ABSTRACT
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
2.1. Sejarah dan Penyebaran Kelapa Sawit 5
2.2. Klasifikasi Kelapa Sawit 7
2.2.1. Berdasarkan Tebal-Tipisnya Cangkang 8
2.2.2. Berdasarkan Warna Buah 9
2.3. Minyak Sawit 9
2.4. Pengolahan Minyak Kelapa Sawit 11
2.5. Proses Pengambilan Minyak Kelapa Sawit (Ekstraksi) 13
2.5.1. Rendering 14
2.5.1.1. Wet Rendering 14
2.5.1.2. Dry Rendering 14
2.5.2. Mechanical Expression 15
2.6. Air Pengencer ( Dilution Water ) 15
3.2.1. Pelaksanaan Pengambilan Contoh 19
3.2.2. Pelaksanaan Sentrifugasi Sampel 19
3.2.3. Pelaksanaan Percobaan di Laboratorium 19
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 21
4.1. Hasil 21
4.2. Perhitungan 25
x
4.2.2. Mengukur Ketebalan Minyak 26
4.3. Pembahasan 26
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 28
5.1. Kesimpulan 28
5.2. Saran 29
DAFTAR PUSTAKA 30
DAFTAR LAMPIRAN 31
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4.1. Data Jumlah Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) 21
Pada Tanggal 22 Januari 2010
Tabel 4.2. Data Jumlah Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) 22
Pada Tanggal 25 Januari 2010
Tabel 4.3. Data Jumlah Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) 22
Pada Tanggal 26 Januari 2010
Tabel 4.4. Data Jumlah Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) 23
Pada Tanggal 27 Januari 2010
Tabel 4.5. Data Jumlah Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) 23
Pada Tanggal 28 Januari 2010
Tabel 4.6. Data Jumlah Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) 24
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Reaksi Pembentukan Trigliserida 10
ABSTRAK
viii
THE INFLUENCE OF DILLUTION WATER ADDITION TO OIL SEPARATION EFFECIENCY THE LIQUID FROM PRESSING STATION IN
PTP NUSANTARA IV PULU RAJA
ABSTRACT
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tanaman kelapa sawit (Elaeis Quinensis Jacq) menghasilkan buah yang disebut
Tandan Buah Segar (TBS). Setelah diolah, TBS akan menghasilkan minyak. Minyak
yang berasal dari kelapa sawit terdiri atas dua macam. Pertama, minyak yang berasal
dari daging buah (mesocarp) yang dihasilkan melalui perebusan dan pemerasan
(press). Minyak jenis ini dikenal sebagai minyak sawit kasar atau crude palm oil
(CPO). Kedua, minyak yang berasal dari inti sawit, dikenal sebagai minyak inti sawit
atau palm kernel oil (PKO).
Pengolahan kelapa sawit merupakan proses untuk memperoleh minyak dan
kernel dari buah kelapa sawit, melalui proses perebusan, pemipilan, pelumatan,
pemgempaan, pemisahan, pengeringan, dan penimbunan. Pengolahan kelapa sawit
yang dilakukan secara mekanis dan fisika dapat berperan dengan baik jika tersedia
bahan baku yang sesuai dan kinerja pabrik yang baik.
Prosedur pengolahan kelapa sawit adalah uraian tentang proses dan
mekanisme pengolahan pada setiap penggal atau unit alat pengolahan sejak buah
diterima di pabrik sampai dihasilkan minyak sawit kasar yang memenuhi mutu
xiv
Buah terdiri dari pericarp, cangkang dan inti. Pada pericarp ditemukan minyak
sawit yang didominasi “palmitat”, sedangkan pada inti sawit ditemukan “laurat”.
Oleh sebab itu pada proses pengolahan kedua jenis sumber ini perlu dipisahkan, yaitu
pertama-tama memisahkan daging buah yang mengandung minyak. Proses ini
berlangsung di stasiun pengempaan dengan menggunakan alat yang dinamakan screw
press.
Selama proses pengempaan, ada air yang ditambahkan dalam adonan yaitu air
pengencer. Air pengencer yang di berikan pada alat screw press tergantung pada jenis
alat. Pemberian air pengencer dilakukan dengan cara menyiram cake dalam pressan
dari atas bagian tengah dan di chute screw press. Jumlah air pengencer yang diberikan
tergantung pada suhu air pengencer, semakin tinggi suhu air pengencer maka jumlah
air yang diberikan semakin sedikit.
Pengenceran bertujuan untuk mengencerkan minyak sehingga pemisahan pasir
dan serat-serat yang terdapat dalam minyak dapat berjalan dengan baik. Pengenceran
berlangsung dengan baik bila suhu air pengencer 90o-98oC. Suhu air pengencer sangat
mempengaruhi proses pemisahan minyak dari zat kotor, Non Oil Solid (NOS), lumpur
dan air yang terkandung dalam daging buah. Air pengencer yang diberikan kedalam
cairan bermanfaat untuk menurunkan viskositas cairan sehinggga zat yang memiliki
BJ > 1,0 kg/m2 akan mudah mengendap sedangkan zat yang memiliki BJ < 1,0 kg/m2
akan mengapung, selain itu juga untuk mempermudah pemisahan fraksi yang terdapat
dalam cairan minyak berdasarkan polaritas dan untuk memecahkan emulsi minyak
yang dalam bentuk butiran halus yang sering melekat dengan NOS serta berperan
Jumlah air pengencer yang digunakan sangat bervariasi antara satu Pabrik
Kelapa Sawit (PKS) dengan PKS yang lainnya. Jumlah air pengencer yang digunakan
yaitu sebanding dengan crude oil yang keluar dari screw press. Jumlah air yang
digunakan berpengaruh terhadap retention time (waktu retensi) dalam Continous
Settling Tank (CST) yang sangat penting artinya dalam efisiensi pemisahan minyak
dan kualitas minyak. Jumlah air pengencer yang dianjurkan adalah sebanding dengan
jumlah minyak yang terdapat dalam cairan yaitu harus sesuai dengan norma yang
ditetapkan oleh setiap PKS ( Naibaho, PM., 1996).
Berdasarkan hal diatas, penulis ingin melakukan pembahasan mengenai
“PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH AIR PENGENCER TERHADAP
EFISIENSI PEMISAHAN MINYAK DARI CAIRAN PADA STASIUN PRESSAN
DI PTP NUSANTARA IV PULU RAJA”.
1.2. Permasalahan
Proses CPO di pabrik PTP Nusantara IV Pulu Raja, Kisaran melalui beberapa tahapan
proses, salah satu proses tersebut yaitu proses pemisahan minyak pertama kali dari
adonan di stasiun pengepressan. Permasalahan yang terdapat di sini yaitu:
1. Berapa kandungan NOS, Minyak, Air dan Kotoran dalam hasil pressan.
2. Bagaimana proses penambahan air pengencer di screw press dan apa
pengaruh penambahan air pengencer terhadap efisiensi pemisahan minyak.
3. Berapa norma atau parameter spesifikasi dari suhu dan jumlah air
xvi
1.3.Tujuan
1. Untuk mengetahui kandungan hasil pressan yang meliputi NOS, Minyak, Air
dan Kotoran.
2. Untuk mengetahui pengaruh air pengencer pada proses pengepressan terhadap
efisiensi pemisahan minyak.
3. Untuk mengetahui norma atau parameter spesifikasi jumlah air pengencer
yang sesuai digunakan di PTP Nusantara IV Pulu Raja, Kisaran.
1.4.Manfaat
1. Memberitahukan kandungan hasil pressan yang meliputi NOS, Minyak, Air
dan Kotoran.
2. Untuk mengetahui jumlah air pengencer yang digunakan agar efisiensi
pengutipan minyak pada proses pengepressan dapat terjadi semaksimal
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sejarah dan Penyebaran Kelapa Sawit
Kelapa sawit ( E. guineensis Jacq) diusahakan secara komersil di Afrika, Amerika
Selatan, Asia Tenggara, Pasifik Selatan serta beberapa daerah lain dengan skala lebih
kecil. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika dan Amerika Selatan, tepatnya
Brasilia. Di Brasilia, tanaman ini ditemukan secara liar atau setengah liar di sepanjang
tepi sungai.
Kelapa sawit Afrika telah berhasil didomestikasikan di Afrika Barat pada
sekitar abad ke-16 dan ke-17 atau jauh pada periode sebelumnya. Senyawa kimia yang
serupa dengan minyak sawit telah ditemukan pada makam orang Mesir pada tahun
3000 SM.
Perkembangan industri kelapa sawit telah dipaparkan secara jelas oleh Hartley
(1988). Ekspor minyak dan inti sawit dari Afrika dimulai pada abad ke-19. Pada saat
itu, sumber minyak hanya berasal dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh liar dan
minyak masih diekstrksi dengan cara sederhana dan tidak efisien. Dari
gerombol-gerombol kelapa sawit yang tumbuh liar ini akhirnya berkembang menjadi
perkebunan rakyat. Perkebunan besar yang pertama mulai berkembang di Sumatera
dan Malaysia pada awal abad ke-19, kemudian diikuti oleh Congo Belgia (sekarang
xviii
Kelapa sawit pertama kali diintroduksikan ke Indonesia oleh pemerintah
kolonial Belanda pada tahun 1848, tepatnya di Kebun Raya Bogor (s’Lands
Plantentuin Buitenzorg). Dengan mendatangkan empat batang bibit kelapa sawit dari
Mauritius dan Amsterdam (masing-masing mengirimkan dua batang). Satu dari
keempat tanaman tersebut saat ini masih hidup di Kebun Raya Bogor yang tinggi
pokoknya telah mencapai lebih dari 20 m. Tanaman kelapa sawit di Kebun Raya
Bogor ini dianggap sebagai nenek moyang tanaman kelapa sawit di Asia Tenggara
( Tim Penulis PS. 1997 ).
Awal mulanya, tanaman kelapa sawit sekedar berperan sebagai tanaman hias
langka di Kebun Raya Bogor dan sebagai tanaman penghias jalanan atau pekarangan.
Itu terjadi mulai tahun 1848 hingga beberapa puluh tahun sesudahnya baru
dibudidayakan secara komersil dalam bentuk perkebunan yaitu padan tahun1911. Jadi
kelahiran perkebunannya membutuhkan waktu sekitar 63 tahun.
Pada saat ini, perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan
dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri oleochemical.
Produk minyak sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak
2.2. Klasifikasi Kelapa Sawit
Klasifikasi dan penyebaran kelapa sawit merupakan dasar untuk memahami tanaman
tersebut. Dalam dunia botani, semua tumbuhan diklasifikasikan untuk memudahkan
dalam identifikasi secara ilmiah. Metode pemberian nama ilmiah (Latin) ini
dikembangkan oleh Carolus Linneaeus. Tanaman kelapa sawit diklarifikasikan
sebagai berikut :
Divisi : Embryophyta Siphonagama
Kelas : Angiospermae
Ordo : Monocotyledonae
Famili : Arecaceae (dahulu disebut Palmae)
Subfamili : Cocoideae
Genus : Elaeis
Spesies :
1. Elaeis guineensis Jacq.(kelapa sawit Afrika)
2. Elaeis melanococca atau Corozo oleifera (kelapa sawit
Amerika Latin)
3. Elaeis odora
Varietas/tipe : Digolongkan berdasarkan :
1. Tebal tipisnya cangkang (endocarp) : dikenal ada tiga
xx
2. Warna buah : dikenal tiga tipe yaitu Nigrescens, Virescens,
dan Albescens ( Pahan, I., 2008 ).
2.2.1. Berdasarkan Tebal-Tipisnya Cangkang
Berdasarkan tebal-tipisnya cangkang, dikenal tipe-tipe kelapa sawit sebagai berikut :
a. Tipe Dura; tipe ini memiliki cirri-ciri daging buah (mesocarp) tipis, cangkang
(endocarp) tebal (2-8 mm), inti (endosperm) besar dan tidak terdapat cincin
serabut. Persentase daging buah 35%-60% dengan rendemen minyak
17%-18%. Adapun tipe Deli Dura adalah tipe Dura yang berasal dari Kebun Raya
Bogor (aslinya dari Afrika yang dimasukkan tahun 1848), kemudian
dikembangkan di Deli yaitu daerah sekitar Medan. Dewasa ini tipe Deli Dura
banyak digunakan dalam kegiatan pemuliaan kelapa sawit.
b. Tipe Psifera; tipe ini memilki ciri-ciri daging buahnya tebal, tidak mempunyai
cangkang, tetapi terdapat cincin serabut yang mengelilingi inti. Intinya kecil
sekali bila dibandingkan dengan tipe Dura ataupun Tenera. Perbandingan
daging buah terhadap buahnya tinggi dan kandungan minyaknya tinggi.
Bunga kelapa sawit tipe Psifera biasanya steril. Kelapa sawit tipe ini hanya
dipakai sebagai “pohon bapak” dalam persilangan dengan tipe Dura/Deli
Dura.
c. Tipe Tenera; tipe ini merupakan hasil silang antara tipe Dura dan Psifera. Sifat
tipe Tenera merupakan kombinasi sifat khas dari kedua induknya. Tipe ini
mempunyai tebal cangkang 0,5 - 4 mm, mempunyai cincin serabut walaupun
tidak sebanyak seperti Psifera, sedangkan intinya kecil. Perbandingan daging
yang terbentuk tiap tahun lebih banyak daripada tipe Dura, tetapi ukurannya
lebih kecil.
2.2.2. Berdasarkan Warna Buah
Berdasarkan warna buah, tipe-tipe kelapa sawit dibedakan sebagai berikut :
a. Tipe Nigrescens; tipe ini meiliki ciri-ciri buah mentah berwarna ungu (iolet)
sampai hitam, sedangkan pangkalnya agak pucat. Setelah buah matang, warna
buah berubah menjadi merah-kuning. Tipe ini banyak dijumpai dimana-mana.
b. Tipe Virescens; tipe ini memiliki ciri-ciri buah mentah berwarna hijau. Setelah
matang, buah menjadi merah-kuning (orange) tetapi bagian ujungnya tetap
kehijau-hijauan. Tipe ini sudah jarang dijumpai di lapangan.
c. Tipe Albascens; tipe ini memiliki ciri-ciri buah muda berwarna kuning pucat,
sedangkan buah masak berwarna kuning tua karena mengandung sedikit
karoten. Ujung buah berwarna ungu kehitam-hitaman. Tipe ini suda h sulit
dijumpai dan kurang disukai untuk dibudidayakan (Setyamidjaja, D., 2006).
2.3. Minyak Sawit
Sebagai minyak dan lemak, minyak sawit adalah suatu trigliserida yaitu senyawa
gliserol dengan asam lemak. Sesuai dengan bentuk bangun rantai asam lemaknya,
minyak sawit termasuk golongan minyak asam oleat-linoleat. Minyak sawit berwarna
merah jingga karena kandungan karotenoida (terutama β-karotena), berkonsentrasi
xxii
kadar Asam Lemak Bebas (ALB) nya) dan dalam keadaan segar, minyak sawit
mempunyai bau dan rasa yang cukup enak.
Minyak sawit terdiri atas berbagai trigliserida dengan rantai asam lemak yang
berbeda-beda. Berikut reaksi pembentukan trigliserida ditunjukkan pada gambar 2.1.
H H
Gambar 2.1. Reaksi Pembentukan Trigliserida
Komponen utama minyak sawit adalah asam palmitat dan asam oleat. Selain
mengandung karotenoida 500-700 ppm (diantaranya β-karotena 54,4%) juga
mengandung tokoferol 500-800 ppm. Kedua zat tak tersabunkan tersebut hanya 0,3%
dari minyak sawit. Kadar tokoferol tersebut tergantung pada kehati-hatian perlakuan
dalam pengolahan (minyak yang berkadar ALB tinggi biasanya tokoferolnya lebih
rendah).
Trigliserida minyak sawit hanya mengandung sedikit ikatan asam lemak
tak jenuh dan juga mengandung tokoferol sehingga agak tahan terhadap oksidasi
2.4. Pengolahan Minyak Kelapa Sawit
Pengolahan kelapa sawit merupakan proses untuk memperolah minyak dan kernel dari
buah kelapa sawit, melalui proses perebusan, pemipilan, pengempaan, pemisahan,
pengeringan, dan penimbunan. Pengolahan kelapa sawit yang dilakukan secara
mekanis dan fisik dapat berperan dengan baik jika tersedia bahan baku yang sesuai
dan kinerja pabrik yang baik. Untuk mengendalikan proses pengolahan diperlukan
pengetahuan dan penguasaan terhadap proses pengolahan dan kemampuan untuk
mengoperasikan serta mendiagnosis suatu penyimpangan.
Prosedur pengolahan kelapa sawit adalah uraian tentang proses dam
mekanisme pengolahan pada setiap penggal atau unit alat pengolahan sejak buah
diterima di pabrik, sampai dihasilkan minyak sawit Crude Palm Oil (CPO) dan kernel
yang memenuhi mutu dengan efisiensi teknis dan ekonomis (Pardamean, M., 2008).
Disini saya memulai pembahasan proses pengolahan minyak kelapa sawit
hanya pada stasiun kempa saja secara mendalam. Karena pada pada stasiun ini, kelapa
sawit diperas (diekstraksi) pertama kali untuk mendapatkan minyaknya dengan
penambahan air pengencer untuk mengeluarkan minyak dari daging buah.
Kempa yang populer yang telah sering digunakan dipabrik-pabrik adalah
kempa ulir (screw press) yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Kempa ini berfungsi
ganda yaitu merajang buah yang belum dilumatkan pada digester dan memeras
minyak, sehingga cake bebas minyak. Untuk mengefisiensikan proses ekstraksi
xxiv
Pengaturan tekanan pressan dilakukan hati-hati, karena perlakuan yang salah
dapat menyebabkan persentase kehilangan minyak yang tinggi atau persentase biji
yang pecah tinggi.
Tujuan pengempaan adalah memeras minyak sebanyak mungkin dari massa
remasan sehingga kehilangan minyak juga semakin sedikit. Untuk ini umumnya telah
dipakai kempa ulir ganda. Karena kempa ulir adalah yang paling sesuai untuk buah
Tenera. Massa yang keluar dari digester diperas dalam screw press pada tekanan cone
30-50 Bar menggunakan air pengencer yang bersuhu 90-98oC sebanyak 15-20% TBS.
Untuk menurunkan viskositas minyak, penambahan air dapat pula dilakukan di oil
gutter ( Pardamean, M., 2008).
Gambar 2.2. Alat Pressan (screw press)
Fungsi screw press adalah :
1). Memeras cairan yang terdapat dari bahan buah dan memisahkannya dari inti
serta serabut buah.
2). Melumatkan kembali buah yang belum sempat dilumatkan di dalam digester
(alat pelumat) agar pengambilan minyak berjalan sempurna dan pada adonan
3). Cairan yang keluar dari pressan mengandung bahan-bahan seperti : minyak,
air, NOS, kotoran, serabut halus, bubur daging buah, lumpur tanah, pasir
halus dan pasir kasar.
Dengan demikian masih banyak bahan yang bukan minyak terkandung dalam
bahan-bahan-bahan yang keluar dari alat kempa sehingga perlu dimurnikn lebih lanjut
dalam proses klarifikasi. Pengambilan cairan minyak menjadi kurang efektif apabila
di screw press terjadi :
1). Silinder press tersumbat akibat jarang dikosongkan.
2). Air panas (air pengencer) diberikan pada adonan tidak cukup.
3). Tekanan screw press dibawah ketentuan.
4). Buah yang tidak matang direbus.
5). Fraksi buah yang berbeda-beda dan juga jenis buah yang berbeda.
6). Screw press yang telah aus (Karim, A., 2001).
2.5. Proses Pengambilan Minyak Kelapa Sawit (Ekstraksi)
Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari bahan yang
diduga mengandung minyak atau lemak. Adapun cara ekstraksi ini ada
bermacam-macam, tapi yang di bahan disini hanya dua macam yaitu : rendering (wet rendering
xxvi
2.5.1. Rendering
Rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang diduga
mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang tinggi. Pada semua cara
rendering, penggunaan panas adalah suatu hal yang spesifik, yang bertujuan untuk
menggumpalkan protein pada dinding sel bahan dan untuk memecahkan dinding sel
tersebut sehingga mudah ditembus oleh minyak atau lemak yang terkandung
didalammya. Menurut pengerjaanya, rendering dibagi dalam dua cara yaitu : wet
rendering dan dry rendering.
2.5.1.1.Wet Rendering
Wet rendering adalah proses rendering dengan penambahan sejumlah air selama
berlangsungnya proses tersebut. Cara ini dikerjakan pada ketel yang terbuka atau
tertutup dengan menggunakan temperature yang tinggi serta tekanan 40-60 pound
tekanan uap (40-60 psi). Bahan yang akan diekstraksi ditempatkan pada ketel yang
dilengkapi dengan alat pengaduk, kemudian air ditambahkan dan campuran tersebut
dipanaskan perlahan-lahan sampai suhu 50oC sambil diaduk. Minyak yang terekstraksi
akan naik ke atas dan kemudian dipisahkan.
2.5.1.2. Dry Rendering
Dry rendering adalah cara rendering tanpa penambahan air selama proses
berlangsung. Dry rendering dilakukan dalam ketel yang terbuka dan dilengkapi
atau lemak dimasukkan ke dalam ketel tanpa penambahan air. Bahan tadi dipanasi
sambil diaduk. Pemanasan dilakukan pada suhu 220oF-230oF (105oC-110oC).
2.5.2. Mechanical Expression
Pengepresan mekanik merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak, terutama
untuk bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk memisahkan
minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi (30-70%). Pada pengepressan
mekanis ini diperlukan perlakuan pendahuluan sebelum minyak atau lemak
dipisahkan dari bijinya. Perlakuan pendahuluan tersebut mencakup pembuatan serpih,
perajangan dan penggilingan serta tempering (pemasakan) (Ketaren, S., 1986).
2.6. Air Pengencer (Dilution Water)
Pada pembahasan diatas, banyak dijumpai kata air pengencer. Apakah sebenarnya air
pengencer dan apa fungsi air pengencer dalam pengutipan minyak di stasiun
pengepressan. Berikut akan dijelaskan mengenai air pengencer.
Air pengencer adalah air panas yang disiramkan ke daging buah yang telah
lumat agar kandungan minyak yang ada di daging buah keluar. Air pengencer yang di
berikan pada alat screw press tergantung pada jenis alat. Pemberian air pengencer
dilakukan dengan cara menyiram cake dalam pressan dari atas bagian tengah dan atau
di chute screw press. Jumlah air pengencer yang diberikan tergantung pada daging
xxviii
terhadap kandungan air cake. Kandungan air cake yang tinggi dapat menyebabkan
proses :
1) Pemecahan cake yang lebih sulit dalam CBC (Cake Breaker Conveyor). Hal
ini sering menyebabkan beban CBC yang terlalu berat.
2) Semakin tinggi kandungan air ampas maka kalor bakarnya akan semakin
menurun yang dapat memeperkecil kapasitas dan efisiensi boiler.
3) Pemeraman biji yang berkadar air yang tinggi dalam silo biji akan lebih dan
dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekistraksi biji yang lebih rendah.
4) Penurunan kapasitas screw press akibat bertambahnya kandungan air dan
kecepatan gerak cake dalam worm.
Jumlah air pengencer yang diberikan, menurut hasil percobaan pada
beberapa alat screw press yaitu 50-70% terhadap kandungan minyak dalam adonan
tersebut, misalnya jika rendemen minyak 22% dengan kapasitas screw press 10
tonTBS/jam maka air yang disemprotkan sebagai air pengencer sebanyak 1,1-1,65 m3.
Pengenceran bertujuan untuk pengenceran minyak sehingga pemisahan
pasir dan serat-serat yang terdapat dalam minyak dapat berjalan dengan baik.
Pengenceran berlangsung dengan baik bila suhu air pengencer 90-98oC. Jumlah air
pengencer yang dianjurkan yaitu sebanding dengan crude oil yang keluar dari screw
press.
Berdasarkan uraian sebelumnya maka jumlah air pengencer yang
digunakan adalah 320 liter/ton TBS setara dengan 9600 liter/jam untuk PKS 30 ton
Pemakaian air pengencer yang terlalu banyak akan menyebabkan
penurunan kualitas unit pengolahan PKS terutama pada alat klarifikasi. Pemberian air
pengencer tergantung pada disain unit pengolahan dan kandungan NOS yang dapat
xxx
BAB 3
BAHAN DAN METODE
3.1. Alat dan Bahan
3.1.1. Alat
- Ember
- Termometer 200oC
- Beakerglass
- Gelas ukur 100 ml
- Hot plate
- Stigma (jangka sorong)
- Alat sentrifugasi
3.1.2. Bahan
- Cairan dari talang kempa (oil gutter)
3.2. Prosedur Percobaan
3.2.1. Pelaksanaan pengambilan contoh
– Ditutup kran air panas untuk pengencer pada kempa dan talang minyak (oil
gutter) selama kurang lebih 10 menit ( sampai cairan dari kempa ke vibro
separator dianggap tidak ada bertambah air).
3.2.2. Pelaksanaa sentrifugasi sampel
– Dimasukkan sampel ke dalam alat sentrifugasi sebanyak 10 mL.
– Disentrifugasi selama 10 menit.
– Dihiitung kadar minyak, air, zat pengotor dan NOS yang terpisah.
3.2.3. Pelaksanaan percobaan di Laboratorium
– Disediakan Beakerglass kapasitas 400 mL sebanyak 4 buah.
– Contoh dipanaskan dan diaduk hingga merata kemudian dimasukkan ke
dalam Beakerglass yang telah tersedia masing−masing sebanyak 400 mL
dan diberi nomor I s/d IV.
– Perbandingan penambahan air pengencer sebagai berikut :
Beakerglass I : 19% (76 mL air panas)
Beakerglass II : 21% (84 mL air panas)
Beakerglass III : 23% (92 mL air panas)
Beakerglass IV : 25% (100 mL air panas)
– Dipanaskan di atas Hot Plate (elektro thermal), kondisikan temperatur
xxxii
– Diamati ketebalan minyak dari masing−masing B eakerglass dengan cara
mengukur ketebalan minyak dengan alat ukur (milimeter) dan dicatat,
kemudian dihitung menjadi mililiter.
– Temperatur tetap dipertahankan dan pengamatan tetap dilanjutkan sampai
BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh data penambahan air pengencer
terhadap pemisahan minyak dari cairan yang ada di stasiun presaan di PTPN IV
Kelapa Sawit Pulu Raja, hasil analisis pada tanggal 22 -29 Januari 2010 yang
masing-masing ditunjukkan pada tabel 4.1. sampai tabel 4.6.
Tabel 4.1. Data Jumlah Penambahan Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) Pada Tanggal 22 Januari 2010
Tanggal Analisa 22 Januari 2010
xxxiv
Tabel 4.2. Data Jumlah Penambahan Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) Pada Tanggal 25 Januari 2010
Tanggal Analisa 25 Januari 2010
Contoh (mL) 400
Tabel 4.3. Data Jumlah Penambahan Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) Pada Tanggal 26 Januari 2010
Tanggal Analisa 26 Januari 2010
Tabel 4.4. Data Jumlah Penambahan Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) Pada Tanggal 27 Januari 2010
Tanggal Analisa 27 Januari 2010
Contoh (mL) 400
Tabel 4.5. Data Jumlah Penambahan Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) Pada Tanggal 28 Januari 2010
Tanggal Analisa 28 Januari 2010
xxxvi
Tabel 4.6. Data Jumlah Penambahan Air Pengencer (%) dan Ketebalan Minyak (mm) Pada Tanggal 29 Januari 2010
Tanggal Analisa 29 Januari 2010
Contoh (mL) 400
Ketebalan Minyak
mm mL %
% Air Pengencer
19% 34 212,5 53,13
21% 36 225 56,25
23% 26 162,5 40,63
25% 31 193,75 48,44
Hasil Sentrifugasi
Air % 0%
Zat Kotor % 1%
Oil % 60%
4.2. Perhitungan
4.2.1. Sentrifugasi contoh
- Menghitung kadar minyak,air, zat pengotor, NOS
xxxviii
4.2.2. Mengukur ketebalan minyak
Tebal minyak yang terpisah = 36 ml (data tabel 4.1.)
Karena 1 mm = 6,26 mL, maka:
36 mm x 6,25 mL = 225 mL
Kemudian hasil dari mL dirubah ke persen (%) menjadi 56,25%
Begitu selanjutnya untuk data tabel 4.2. sampai tabel 4.6.
4.3. Pembahasan
Dari analisa data tabel diatas, diperoleh hubungan antara jumlah air pengencer
dengan efisiensi ketebalan minyak. Penggunaan air pengencer sebanyak mungkin
menimbulkan efisiensi kehilangan minyak semakin kecil, tetapi disamping itu perlu
diperhatikan efek yang ditimbulkannya. Kadar air dalam minyak akan tinggi apabila
jumlah air pengencer yang digunakan terlalu banyak seperti pada penambahan air
pengencer sebanyak 22%-25% pada data tabel diatas sehingga ketebalan minyak yang
didapat hanya sedikit. Hal ini menimbulkan kesulitan pada proses selanjutnya karena
waktu tinggal minyak di tangki pemisah akan sedikit dimana minyak banyak terikut
dengan sludge.
Maka penggunaan air pengencer yang efisiensi menurut hasil pengolahan dan
analisa di laboratorium adalah pada penambahan 19%-21%. Menurut spesifikasi
yang diolah pada saat itu dan juga jam kerja pengolahan yang ada disana. Karena
apabila TBS yang diolah hanya sedikit maka tidak ada penambahan air pengencer
karena minimal TBS yang diolah 700 ton/jam kerja pengolahan. Maksudnya adalah
bahwa kapasitas olah di sana adalah 30 ton/jam, sedangkan jam kerja pengolahan
adalah 12 jam, maka minimal TBS yang harus disediakan adalah 700 ton/jam kerja
pengolahan sehingga bisa ditambahkan jumlah air pengencer sebanyak 19%-21%. Jika
penggunaan air pengencer yang digunakan sebanyak 22%-25%, menurut tabel diatas
minyak yang dihasilkan ketebalnnya tidak maksimal karena minyak telah banyak
mengandung air sehingga akan sulit diproses pada stasiun selanjutnya.
Keberhasilan efisiensi ekstraksi minyak pada stasiun pengempaan tidak hanya
dipengaruhi oleh penggunaan optimal dari air pengencer. Faktor lainnya adalah suhu
air pengencer tidak melebihi dari yang ditentukan yaitu 90o-98oC dan tekanan pressan
yang digunakan tidak melebihi dari 40-50 Bar sesuai dengan standart pengolahan
xl
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
1. Hasil analisa laboratorium dari tanggal 22-29 Januari 2010 telah diketahui
rata-rata hasil kandungan dari cairan yang keluar dari pressan yaitu :
- Air : 0%
- Zat kotor : 7,60%
- Oil (Minyak) : 77,46%
- NOS : 11,61%
2. Dengan penambahan air pengencer yang sesuai maka minyak yang
dihasilkan dapat membentuk ketebalan yang maksimal.
3. Norma/ Parameter Spesifikasi air pengencer di PTP Nusantara IV Pulu Raja
5.2. Saran
1. Pada proses penambahan air pengencer di stasiun pressan diharapkan
menggunakan alat pengukur air sehingga pemisahan minyak dari cairan lebih
efisien.
2. Screw press yang digunakan sebaiknya diperiksa dan dibersihkan dari
sisa-sisa ampas setiap seminggu sekali agar pisau-pisau yang ada di dalamya
tidak aus dan bekerja dengan baik.
xlii
DAFTAR PUSTAKA
Ketaren, S. 1986. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Cetakan Pertama. Jakarta : UI-Press.
Mangoensoekarjo, S. 2003. Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
Naibaho, PM. 1996. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Medan : Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
Pahan, I. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Cetakan Kelima. Jakarta : Penebar Swadaya.
Pardamean, M. 2008. Panduan Lengkap Pengolahan Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit.Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Agro Media Pustaka.
Setyamidjaja, D. 2006. Kelapa Sawit, Teknik Budidaya, Panen Dan Pengolahan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
LAMPIRAN
Lampiran. Norma / parameter Spesifikasi Angka Kerja Pengolahan
No Uraian Norma
1. Tekanan rebusan (kg/cm2) 2,8-3,0 kg/cm2
2. Lama direbus 80-100 menit
3. Sistem Rebusan 3 puncak
4. Holding time 45-50 menit
5. Tekanan Kerja Pressing 40-50 BAR
6. Suhu Kerja Stasiun Klarifikasi 95-98 oC
9. Pemakaian air pengencer di pengempaan (%TBS) 19%-21%
10. Pemakaian air vibrating screen (%TBS) 28
11. Kebutuhan air tiap ton TBS (m3) 1,5