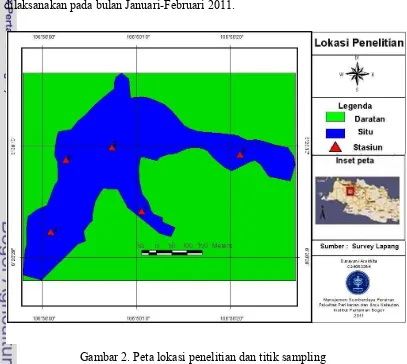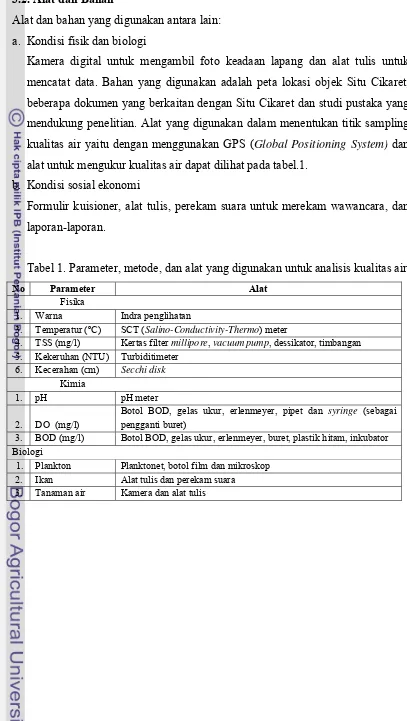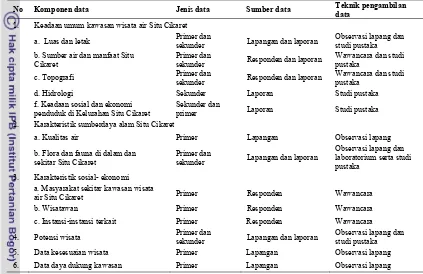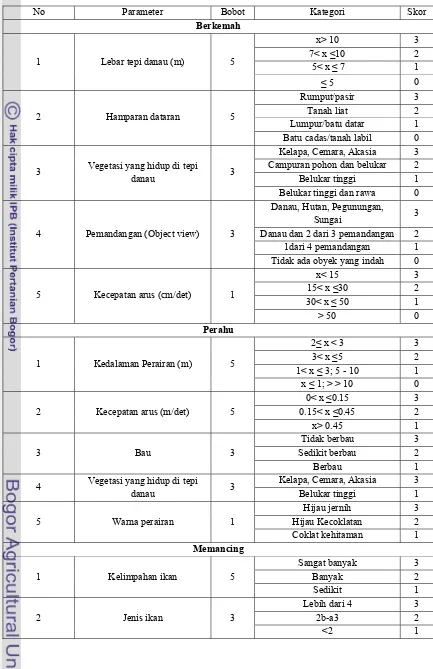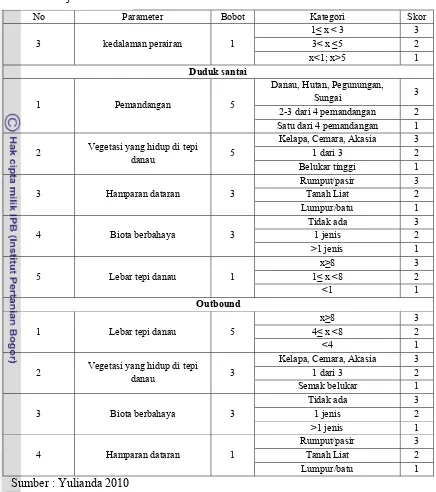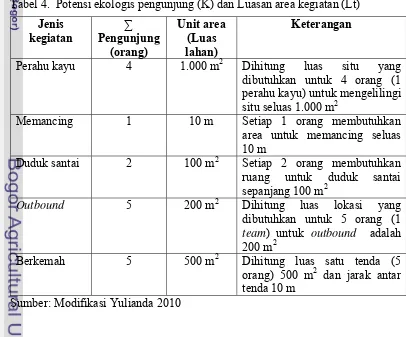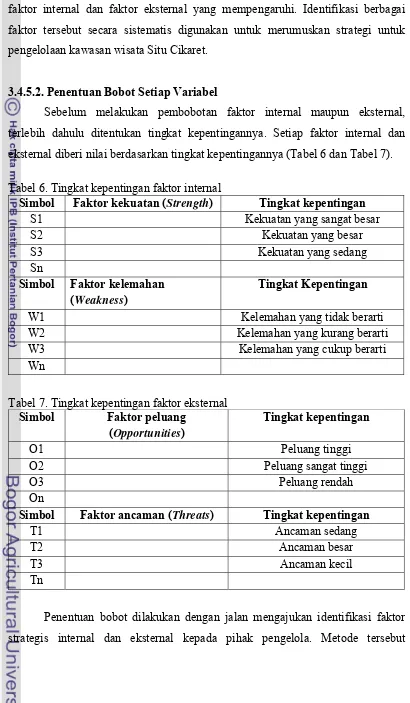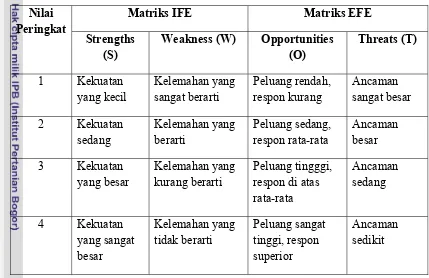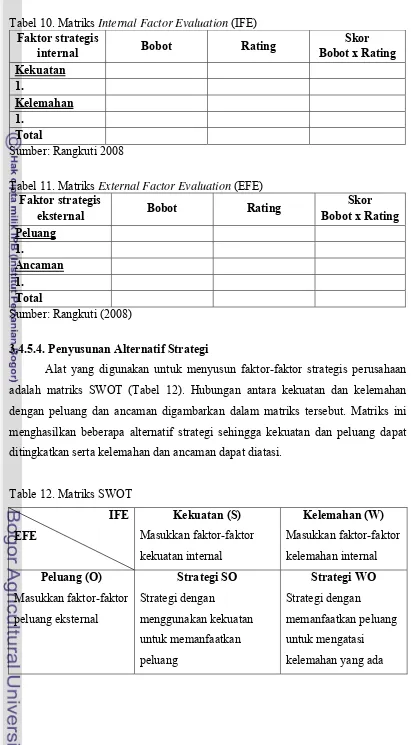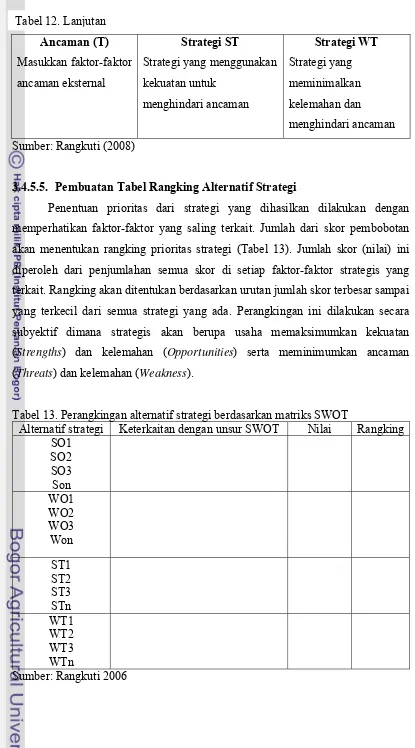i
KAJIAN SUMBERDAYA PERAIRAN SITU CIKARET UNTUK
PENGEMBANGAN WISATA DI KELURAHAN CIKARET
KECAMATAN CIBINONG, BOGOR
DARAYANI ARADHITA
SKRIPSI
DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
iii
RINGKASAN
Darayani Aradhita. C24063364. Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata Di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor. Dibawah bimbingan Agustinus M. Samosir dan Fredinan Yulianda.
Situ Cikaret merupakan satu dari 96 situ yang ada di Kabupaten Bogor dengan luas 10.53 hektar dan potensial untuk pengembangan wisata. Wisata merupakan segala kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan maksud menikmati atraksi alam dan budaya. Ekowisata merupakan pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan konservasi untuk pengembangan wisata, sehingga wisata dengan konsep ekowisata akan menjaga berlangsungnya proses ekologi yang tetap mendukung sistem kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin kelestarian spesies dan ekosistem. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu ditinjau permasalahan yang terjadi di Situ Cikaret, baik masalah internal maupun eksternal kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Situ Cikaret, dan menyusun rencana alternatif strategi pengelolaan kawasan Situ Cikaret untuk kegiatan wisata perairan secara berkelanjutan.
Penelitian dilakukan di Situ Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui survey pendahuluan pada bulan Desember 2010 dan pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2011. Pengkajian kawasan untuk kegiatan wisata dilakukan dengan analisis Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) sehingga setiap kegiatan wisata yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan peruntukannya, analisis Daya Dukung Kawasan (DDK) untuk mengetahui jumlah maksimum pengunjung yang dapat ditampung oleh kawasan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia, dan analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) untuk memperoleh alternatif strategi pengelolaan yang diprioritaskan.
Situ Cikaret memiliki potensi bentang alam (pemandangan), potensi sumberdaya habitat (vegetasi tepi situ, potensi air terkait kuantitas dan kualitas air), dan potensi sumberdaya ikan. Permasalahan yang terdapat di kawasan perairan Situ Cikaret yaitu permasalahan ekologis dan pengelolaan kawasan. Permasalahan ekologis terdiri atas sumberdaya habitat yang tidak terawat, sedimentasi, pencemaran limbah (limbah domestik, pertanian dan perikanan). Permasalahan pengelolaan yaitu belum adanya lembaga yang berwenang penuh dalam pengelolaan kawasan Situ Cikaret sebagai tempat wisata, sarana dan prasarana wisata belum memadai, tata ruang kawasan yang kurang terencana, serta dampak dari aktivitas wisatawan terhadap keseimbangan dan keutuhan kawasan. Berdasarkan analisis IKW, diperoleh lima jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangakan di kawasan Situ Cikaret yaitu berperahu, memancing, duduk santai, berkemah dan
outbound. Kelima jenis kegiatan tersebut menyebar pada sembilan titik yang terdapat di kawasan perairan Situ Cikaret. Analisis DDK menunjukan nilai daya dukung kawasan sebesar 449 orang/hari. Dari analisis SWOT diperoleh tiga alternatif strategi pengelolaan kawasan Situ Cikaret yang diprioritaskan yaitu (1) Pengoptimalan potensi sumberdaya kawasan untuk kegiatan wisata berdasarkan analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan. (2) Perlu adanya lembaga yang berwenang penuh dalam pengelolaan dan pengembangan potensi sumberdaya kawasan Situ Cikaret sebagai tempat wisata. (3) Pihak pengelola membuat rancangan pola pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Situ Cikaret yang tidak bertentangan dengan kesesuaian dan daya dukung kawasan.
iv
KAJIAN SUMBERDAYA PERAIRAN SITU CIKARET UNTUK
PENGEMBANGAN WISATA DI KELURAHAN CIKARET
KECAMATAN CIBINONG, BOGOR
DARAYANI ARADHITA C24063364
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
ii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI
DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor
adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi.
Bogor, September 2011
v
PENGESAHAN SKRIPSI
Judul : Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret
Kecamatan Cibinong, Bogor Nama : Darayani Aradhita
NIM : C24063364
Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan
Menyetujui:
Pembimbing I, Pembimbing II,
Ir. Agustinus M. Samosir, M. Phil Dr.Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc
NIP. 1961 1211 198703 1 003 NIP 19630731 198803 1 002
Mengetahui:
Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc NIP 19660728 199103 1 002
vi
PRAKATA
Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Kajian Sumberdaya Perairan Situ Cikaret Untuk Pengembangan Wisata di Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong, Bogor”; disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Januari-Februari 2011, dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ir. Agustinus M Samosir, M.Phil selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dalam pemberian bimbingan, masukkan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk berbagai pihak.
Bogor, September 2011
Penulis
vii
UCAPAN
TERIMA KASIH
Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ir. Agustinus M Samosir, M.Phil dan Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku dosen pembimbing I dan II atas bimbingan, a r a h a n , ma s u k a n , d a n n a s e h a t yang telah diberikan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si sebagai dosen pembimbing akademik atas segala bimbingannya selama masa studi di Insitut Pertanian Bogor.
3. Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS dan Ir. Gatot Yulianto, M.Si selaku wakil komisi pendidikan program S1 dan dosen penguji tamu dalam sidang skripsi atas saran,
nasehat, dan perbaikan yang diberikan.
4. Keluarga tercinta; Ayahanda E d i S a n y o t o d a n E k o S u p r i a t n o , Ibunda Sri Yuliani dan Retno Yuli Astuti, suami tersayang Oki Hidayat, dan saudara-saudara terbaik Diah Ayu Stella Mediana, Dewi Aryani dan Resti Pratiwi atas doa, dukungan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis. 5. Staf Tata Usaha MSP (Mbak Widar dan Mbak Maria) atas bantuan,
kesabaran dan perhatiannya selama masa studi di Institut Pertanian Bogor. 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor beserta staff atas
segala bantuan selama penelitian berlangsung.
7. Team Kepompong (Zewita Maria, Fitriana Intan Putri, Mishbahudin Dhiya’ul Haq, Dwi Wahloyo, Ageriyanto), keluarga besar MSP 43, 44, dan 45 atas kebersamaan, bantuan, motivasi dan dukungannya.
viii
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Padang, pada tanggal 16 Agustus 1988 dari pasangan Bapak Edi Sanyoto dan Ibu Sri Yuliani. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan formal ditempuh di TK. Adhiyaksa Kupang (1994), SD Muhammadiyah I Kupang (2000), SLTPN 1 Kupang (2003) dan SMAN 1 Kupang (2006). Pada tahun 2006, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Setelah melewati tahap Tingkat Persiapan Bersama (TPB) selama satu tahun, penulis diterima pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif di organisasi kemahasiswaan organisasi Ikatan Keluarga Muslim TPB (IKMT) tahun 2006/2007, Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER) tahun 2007-2009, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tahun 2007/2008, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Insitut Pertanian Bogor tahun 2008-2010. Penulis juga berkesempatan menjadi Asisten Mata Kuliah Ekologi Perairan (2007/2008 dan 2009/2010) dan Asisten Pelajaran Agama Islam (2007-2009).
ix
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Situ ... 6
3.3.1. Metode pengambilan dan pengumpulan data ... 19
3.3.2. Metode pengambilan responden ... 20
x
4.5. Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan bagi Kegiatan Ekowisata ... 87
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan ... 90
5.2.Saran ... 91
DAFTAR PUSTAKA ... 92
xi
DAFTAR TABEL
Halaman 1. Parameter, metode, dan alat yang digunakan untuk analisis
kualitas air... ... 18
2. Jenis data yang dibutuhkan ... 19
3. Parameter kesesuaian sumberdaya untuk wisata danau ... 23
4. Potensi ekologis pengunjung (K) dan Luasan area kegiatan (Lt) ... 25
5. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata ... 26
6. Tingkat kepentingan faktor internal ... 28
7. Tingkat kepentingan faktor eksternal ... 28
8. Penilaian bobot faktor strategi internal dan eksternal ... 29
9. Skala penilaian peringkat untuk Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) ... 30
10. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) ... 31
11. Matriks External Factor Evaluation (EFE) ... 31
12. Matriks SWOT ... 31
13. Perangking alternatif strategi berdasarkan matriks SWOT ... 32
14. Kelimpahan fitoplankton di perairan Situ Cikaret... 37
15. Kelimpahan zooplankton di perairan Situ Cikaret ... 38
16. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di perairan Situ Cikaret ... 39
17. Kualitas air Situ Cikaret ... 41
18. Indeks kesesuaian wisata (IKW) di Situ Cikaret ... 74
xii
14. Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan responden di kawasan wisata Situ Cikaret ... 55
22. Permasalahan yang ada di kawasan Situ Cikaret berdasarkan presepsi masyarakat ... 64
23. Tingkat kepedulian responden terhadap kelestarian Situ Cikaret ... 65
24. Presentase tingkat kesadaran responden terhadap kebersihan Situ Cikaret ... 66
25. Presepsi responden tentang pengelolaan kawasan Situ Cikaret ... 67
xiii
27. Potensi Situ Cikaret yang dapat dikembangkan ... 68 28. Kegiatan Wisata yang dapat di kembangkan di kawasan
Situ Cikaret ... 69 29. Pendapat responden tentang hal yang harus dibenahi dari kawasan
Situ Cikaret ... 71 30. Dampak positif kegiatan wisata di Situ Cikaret berdasarkan
presepsi masyarakat ... 72 31. Dampak negatif dari alih fungsi kawasan sebagai tempat wisata
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Sarana dan prasarana di sekitar Situ Cikaret ... 96
2. Vegetasi tepi Situ Cikaret ... 98
3. Stasiun pengamatan kualitas air ... 99
4. Peta kontur kedalaman Situ Cikaret ... 100
5. Perhitungan indeks kesesuaian wisata ... 101
6. Peta kesesuaian wisata ... 108
7. Peta daya dukung kawasan ... 109
8. Lokasi kesesuaian wisata Situ Cikaret ... 110
9. Penentuan analisis strategi pengelolaan kawasan untuk wisata ... 112
10. Matriks SWOT ... 114
11. Perangkingan alternatif strategi ... 115
21. Kuisioner wawancara ... 117
1.1. Latar Belakang
Situ merupakan salah satu ekosistem perairan tergenang yang umumnya berair tawar dan berukuran relatif kecil. Situ dapat terbentuk secara alami yaitu karena kondisi topografi yang mungkin terperangkapnya sejumlah air. Sumber air lahan tersebut dapat berasal dari mata air yang terdapat didalamnya, dari masuknya air sungai dan atau limpasan air permukaan/hujan (surface run-off). Situ ini juga dapat terbentuk akibat kegiatan alamiah, seperti bencana alam, kegiatan vulkanik maupun tektonik. Keberadaan air di dalam lahan tergenang dapat bersifat permanen maupun sementara (Suryadiputra 2005).
Situ Cikaret adalah satu dari 96 situ yang ada di Kabupaten Bogor, memiliki luas 29.5 ha berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor pada tahun 1989/1990, sementara hasil pengukuran selanjutnya pada tahun 1992 luas perairan situ yaitu 10.53 ha (Suwignyo et al. 1993). Lokasi Situ Cikaret melintasi 2 (dua) desa, yaitu Kampung Curug Desa Pekansari dan Kampung Cikaret Desa Harapan Jaya, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kelurahan Cikaret ini memiliki batas wilayah meliputi Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kuda, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Batu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyaharja (Pemerintah Kabupaten Bogor 2010).
Karakteristik potensi sumberdaya Situ Cikaret dapat dikembangkan sebagai objek wisata situ. Namun, pengembangan wisata situ ini dapat dikatakan belum optimal sebagai suatu objek wisata situ. Hal ini diduga karena kurangnya peran pemerintah dalam pengembangan wilayah ini serta pemanfaatan utamanya sebagai sumber air bagi daratan sekitarnya, belum adanya promosi daerah, sehingga menyebabkan kunjungan wisatawan ke Situ Cikaret cenderung tidak tinggi karena cakupannya hanya sekitar wilayah kabupaten saja dan belum mendapat penanganan yang optimal dalam upaya pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan untuk kegiatan wisatsa serta belum ada kegiatan konservasi kawasan ini yang berguna meningkatkan kelestariannya.
Kajian mengenai potensi sumberdaya Situ Cikaret ini juga perlu dilakukan agar potensi sumberdaya Situ Cikaret dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan sesuai untuk dijadikan objek wisata situ. Potensi wisata di Situ Cikaret ini diharapkan dapat dioptimalkan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan di situ tersebut.
1.2. Perumusan Masalah
Pengelolaan Situ Cikaret berdasarkan fungsi utama situ yaitu untuk kegiatan pengairan yang secara teknis sebagai penampung air dan secara ekologis adalah peresap air. Pemanfaatan perairan situ untuk kegiatan lainnya (perikanan dan pariwisata) adalah kegiatan tambahan yang berprioritaskan sekunder. Pengelolaan perairan situ harus senantiasa memperhatikan koordinasi pemanfaatan agar tidak terjadi tumpang tindih (konflik kepentingan). Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip pelestarian perairan situ yaitu menjaga kebersihan situ.
Beberapa permasalahan untuk pengembangan wisata Situ Cikaret, antara lain :
1. Pendangkalan dan penyempitan perairan situ yang terus berlanjut akibat kegiatan manusia yang dilakukan baik di situ maupun di daratan sekelilingnya.
2. Kuantitas dan kualitas air perairan situ telah menurun sebagai akibat adanya limpasan limbah cair maupun padat dari daerah pertanian, pemukiman dan industri di daerah hulunya.
3. Belum adanya upaya pengelolaan yang khusus terhadap Situ Cikaret dari instansi terkait terhadap permasalahan yang ada.
4. Belum optimalnya upaya pengembangan kawasan Situ Cikaret sebagai objek wisata.
Gambar 1. Kerangka pendekatan studi
Strategi Pengelolaan Kawasan Perairan Situ Cikaret Identifikasi Potensi
Analisis Kesesuaian Wisata
Analisis SWOT
Analisis Dayadukung Kawasan
Pemerintah Daerah
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
1. Mengkaji potensi sumberdaya dan permasalahan yang ada di kawasan Situ Cikaret.
2. Menyusun rencana alternatif strategi pengelolaan kawasan Situ Cikaret untuk kegiatan wisata perairan secara berkelanjutan.
1.4. Manfaat Penelitian
II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Situ
2.1.1. Definisi Situ
Menurut Puspita et al. (2005) situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, sumber airnya berasal dari mata air, air hujan, dan/atau limpasan air permukaan. Situ alami dan buatan memiliki perbedaan utama yang terletak pada proses pembentukannya. Situ buatan yaitu situ yang berasal dari dibendungnya suatu cekungan (basin), sedangkan situ alami yaitu situ yang terbentuk secara alami karena kondisi topografi yang memungkinkan terperangkapnya sejumlah air.
Situ dapat terbentuk secara alami yaitu karena kondisi topografi yang mungkin terperangkapnya sejumlah air. Sumber air lahan tersebut dapat berasal dari mata air yang terdapat didalamnya, dari masuknya air sungai dan atau limpasan air permukaan/hujan (surface run-off). Situ ini juga dapat terbentuk akibat kegiatan alamiah, seperti bencana alam, kegiatan vulkanik maupun tektonik. Keberadaan air di dalam lahan tergenang dapat bersifat permanen maupun sementara. Pada musim kemarau panjang (misalnya: selama berlangsungnya fenomena el-nino), beberapa situ dapat mengalami kekeringan secara total dan berubah fungsi menjadi suatu lapangan terbuka yang terkadang dimanfaatkan penduduk sekitarnya untuk melakukan kegiatan bercocok tanam atau bahkan sebagai fasilitas lapangan bola (Suryadiputra 2005).
2.1.2. Nilai dan Manfaat Situ
Ekosistem situ memiliki berbagai nilai dan manfaat bagi berbagai makhluk hidup. Nilai dan manfaat tersebut antara lain (Puspita et al. 2005):
a. Nilai ekologis situ
1. Pengaturan fungsi hidrologis
Keberadaan situ sangat erat kaitannya dengan air dan siklus hidrologis di bumi. Secara alami, situ merupakan cekungan yang dapat menampung air tanah dan limpasan air permukaan. Dengan demikian keberadaan situ dapat mencegah terjadinya bencana banjir pada musim penghujan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Situ juga dapat mencegah meluasnya intrusi air laut ke daratan karena situ merupakan pemasok air bagi kantung-kantung air lain seperti sungai, rawa dan sawah. 2. Habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan
Ekosistem situ merupakan tempat hidup, mencari makan dan berkembang biak berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Bahkan beberapa jenis diantaranya merupakan jenis hewan dan tumbuhan yang endemik dan dilindungi. Salah satu contoh adalah Situ Gunung Putri yang ditumbuhi sejenis rumput alang-alang yang merupakan habitat hidup sejenis angsa liar berwarna hitam (Database Situ-Situ Jabotabek, WI-PI in Puspita et al. 2005).
3. Menjaga sistem dan proses-proses alami
Keberadaan ekosistem situ dapat menjaga kelangsungan sistem dan proses-proses ekologi, geomorfologi dan geologi yang terjadi di alam. Sebagai contoh, daratan banjir di sekitar situ banyak dijadikan lahan pertanian karena tanahnya subur. Kesuburan ini disebabkan adanya proses penambahan unsur hara dari hasil sedimentasi. Situ juga secara tidak langsung berperan sebagai penghasil oksigen melalui berbagai jenis fitoplankton yang hidup di dalamnya.
b. Nilai ekonomis situ 1. Penghasil energi
yang digunakan untuk pembangkit listrik adalah Situ Tando Kracak di Kecamatan Leuwiliang Bogor, yang dikelola oleh PLN (Bapedalda Kabupaten DT II Bogor, 1999 in Puspita el al. 2005).
2. Sumber air
Situ yang merupakan penampung air hujan dan limpasan air permukaan dapat dijadikan sumber air bagi masyarakat setempat baik untuk kebutuhan air minum, pengairan sawah (irigasi), maupun peternakan.
3. Penghasil berbagai jenis sumberdaya alam bernilai ekonomis.
Ekosistem situ kaya akan berbagai jenis sumberdaya alam (hewan ataupun tumbuhan) bernilai ekonomis, baik yang bersifat liar maupun yang dibudidayakan. Selain itu, situ juga berperan sebagai sumber plasma nutfah. Ikan, udang dan katak merupakan merupakan beberapa jenis hewan bernilai ekonomis yang dapat ditemukan di situ. Berbagai jenis tumbuhan air yang hidup di situ ada yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan ada juga yang dapat dijadikan bahan makanan bagi manusia dan ternak. Selain itu, tumbuhan kayu yang hidup di sekitar ekosistem situ juga dapat dijadikan bahan bangunan ataupun arang.
4. Sarana wisata dan olah raga
Situ dengan pemandangan alam yang indah menjadi salah satu potensi bagi kegiatan wisata. Selain itu perairan situ yang relatif luas juga dapat dijadikan areal kegiatan olahraga air seperti memancing, dayung dan ski air. Contoh situ yang telah dikembangkan menjadi sarana rekreasi dan olahraga air antara lain Situ Gunung Putri dan Situ Cigudeg di Bogor. c. Nilai sosial dan budaya situ.
memiliki nilai sejarah daerah Betawi yang unik (Kompas 2 Juni 2001 in Puspita et al. 2005).
Menurut Ubaidillah et al. (2003) situ merupakan salah satu sumberdaya yang potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Namun dalam perkembangannya, situ-situ menghadapi permasalahan yang sangat kompleks yang mencakup permasalahan aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek hidrologis, aspek tata ruang dan aspek sosial kemasyarakatan.
1. Aspek kelembagaan
Permasalahan aspek kelembagaan antara lain meliputi:
a. Belum adanya keberpihakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam upaya konservasi situ.
b. Belum adanya pembagian tugas pengelolaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c. Kurangnya keterpaduan pelaksanaan program pengelolaan situ.
d. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan kelembagaan pemanfaatan situ. e. Lemahnya kampanye publik tentang manfaat dan fungsi situ, baik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 2. Aspek hukum
Permasalahan aspek hukum antara lain meliputi:
a. Kekosongan hukum sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah.
b. Belum adanya legalitas penguasaan atas situ. c. Belum adanya jaminan kepastian hukum. d. Lemahnya penegak hukum.
3. Aspek fisik hidrologis
Permasalahan aspek fisik hidrologis antara lain meliputi: a. Menurunnya kualitas perairan.
b. Pendangkalan.
c. Penutupan perairan oleh gulma. d. Longsor lahan.
4. Aspek tata ruang
Permasalahan aspek tata ruang antara lain meliputi:
a. Tidak terkendalinya perubahan tata guna lahan atau alih fungsi situ. b. Tidak jelasnya batas daerah penguasaan situ.
c. Belum adanaya rencana detail kawasan dan rencana teknis kawasan. 5. Aspek sosial kemasyarakatan.
Permasalahan aspek sosial kemasyarakatan antara lain meliputi:
a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat situ. b. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan situ.
c. Pemanfaatan situ oleh masyarakat yang tidak memperhatikan keberlanjutan fungsi situ.
2.2. Faktor Pembatas Perairan Situ
Faktor pembatas bagi perairan tawar menurut Odum (1971) adalah suhu, kekeruhan dan debit arus. Parameter fisika yang dianalisis antara lain : suhu, kecerahan, dan warna perairan. Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam satu hari, sirkulasi udara, penutupan awan dan aliran serta kedalaman dari badan air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisik, kimia dan biologi badan air. Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20o-30oC (Effendi 2003).
Kecerahan air tergantung pada warna dan kekeruhan. Nilai kecerahan sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuspensi, serta ketelitian orang yang melakukan pengukuran. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang berupa plankton dan mikroorganisme lain (APHA 1976; Davis & Cornwell 1991 in Effendi 2003).
adanya bahan organik dan bahan anorganik; karena keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam (misalnya besi dan mangan), serta bahan-bahan lain (Effendi 2003).
Parameter kimia yang dianalisis antara lain: DO, BOD, dan pH. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO) adalah gas oksigen terlarut dalam air. Oksigen yang terlarut dalam air berasal dari fotosintesis oleh fitoplankton atau tumbuhan air dan difusi udara (APHA 1992 in Effendi 2003). Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (Biochemical Oxygen Demand/BOD) merupakan gambaran secara tak langsung kadar bahan organik adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroba aerob untuk mengoksidasi bahan organik menjadi karbondioksida dan air (Davis & Cornwell 1991 in Effendi 2003). Dengan kata lain BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerob yang terdapat pada botol BOD yang diinkubasi pada suhu sekitar 200 selama 5 hari dalam keadaan tanpa cahaya (Boyd 1988 in Effendi 2003).
Tebbut (1992) in Effendi (2003) menyatakan bahwa pH hanya menggambarkan ion hidrogen. Mackereth et al. (1989) in Effendi (2003) berpendapat bahwa pH juga berkaitan erat dengan karbondioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin sedikit kadar karbondioksida bebas. Larutan asam (pH rendah) bersifat korosif. Nilai pH dapat menunjukkan kualitas perairan sebagai lingkungan hidup, walaupun perairan itu tergantung pula dari berbagai faktor lain. Parameter biologi yang dianalisis adalah kesuburan suatu perairan situ dengan melihat kelimpahan plankton dan biota yang hidup di kawasan perairan.
2.3.Ruang Lingkup Pariwisata dan Ekowisata 2.3.1.Pariwisata
Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk
melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain (Damanik 2006).
Pariwisata dapat juga diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk
sementara waktu, diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan
maksud bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi,melainkan untuk
sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia.
Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata
(Yulianda 2007).
Dalam UU No 9 tahun 1990 (Damanik 2006 in Rahmawati 2009), beberapaistilah yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata antara lain :
1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan
daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk
pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di
bidang tersebut.
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata.
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa
pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata,
usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
6. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau
disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
Menurut Munasef (1995) in Sulaksmi (2007), kegiatan pariwisata terdiri
dari tiga unsur, diantaranya :
1. Manusia (man) yang merupakan orang yang melakukan perjalanan dengan
maksud menikmati keindahan dari suatu tempat (alam).
2. Ruang (space) yang merupakan daerah atau ruang lingkup tempat melakukan
perjalanan.
3. Waktu (time) yang merupakan waktu yang digunakan selama dalam perjalanan
dan tinggal di daerah tujuan wisata.
Kelly (1996) in Sulaksmi (2007) menyatakan klasifikasi bentuk wisata
yang dikembangkan berdasarkan pada bentuk utama atraksi atau daya tariknya
lain : ekowisata (ecotourism), wisata alam (nature tourism), wisata petualangan
(adventure tourism), wisata berdasarkan waktu (gateway and stay) dan wisata
budaya (cultural tourism).
Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yaitu (Soemarwoto 2004 in Sari 2009):
1. Terpeliharanya proses ekologi yang esensial 2. Tersedianya sumberdaya yang cukup
3. Lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai
2.3.2. Ekowisata
Istilah ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh Hector Cebalos-Lascurian pada tahun 1983 yang mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan ke daerah-daerah yang lingkungan alamnya masih asli atau relatif masih sedikit sekali terganggu untuk tujuan mempelajari, mengagumi dan bersenang-senang sambil menikmati pemandangan dengan berbagai tanaman dan hewan liar serta mengamati budaya setempat (Fennel 2005). Goodwinn (1996) in Fennel (2005), menyatakan bahwa ekowisata adalah wisata alam yang berdampak rendah yang berkonstribusi langsung pada pemeliharaan spesies dan habitat baik secara langsung melalui konservasi dan/atau secara tidak langsung melalui penyediaan pendapatan bagi masyarakat lokal dan melindungi wilayah warisan satwa sebagai sumber pendapatan. Sedangkan Clark (1996), menyatakan bahwa ekowisata merupakan kontrol pembangunan yang diperlukan berdasarkan daya dukung untuk menjamin sumberdaya alam agar tidak dimanfaatkan berlebihan oleh pengunjung. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat
menciptakan industri pariwisata (Eplerwood 1999 in Fandeli 2000).
Sumberdaya ekowisata terdiri atas sumberdaya alam dan sumberdaya
manusia yang dapat diintegrasikan menjadi komponen terpadu bagi pemanfaatan
wisata. Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat diklasifikasikan menjadi
tiga kelompok yaitu (Fandeli 2000 in Yulianda 2007) :
a. Wisata alam (nature tourism), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada
b. Wisata budaya (cultural tourism), merupakan wisata dengan kekayaan budaya
sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan.
c. Ekowisata (Ecotourism, green tourism atau alternative tourism), merupakan
wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan
perlindungan sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan.
2.4. Konsep dan Prinsip Pengembangan Ekowisata
Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis wisatawan (Fandeli & Muchlison 2000).
Dalam kaitannya dengan ekowisata, From (2004) in Damanik dan Weber
(2006) menyusun tiga konsep dasar tentang ekowisata yaitu sebagai berikut :
Pertama, perjalanan outdoor dan di kawasan alam yang tidak menimbulkan
kerusakan lingkungan. Kedua, wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas
yang diciptakan dan dikelola oleh masyarakat kawasan wisata. Ketiga, perjalanan
wisata ini menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal.
Pemilihan ekowisata sebagai konsep pengembangan dari wisata air didasarkan pada lima unsur utama (Yoeti 2000 in Agustin 2007), yaitu:
1. Ekowisata sangat bergantung pada kualitas sumberdaya alam khususnya perairan, peninggalan sejarah dan budaya.
2. Melibatkan masyarakat.
3. Ekowisata air meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam dan perairan itu sendiri, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya.
4. Tumbuhnya pasar ekowisata air di tingkat nasional dan internasional. 5. Ekowisata air sebagai sarana mewujudkan ekonomi berkelanjutan.
Menurut The Ecotourism Society (Eplerwood 1999 in Fandeli 2000), menyebutkan ada delapan prinsip dalam kegiatan ekowisata yaitu:
1) Mencegah dan menanggulangi dari aktivitas wisatawan yang mengganggu terhadap alam dan budaya
2) Pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan conservation tax dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan
meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.
3) Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam.
4) Meningkatkan penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
5) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif.
6) Menjaga daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.
7) Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonize dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat. 8) Meningkatkan devisa buat pemerintah. Apabila suatu kawasan pelestarian
2.5. Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan
Dalam pariwisata kesesuiaan mencakup kesesuiaan sumberdaya atau potensi yang dikaitkan dengan luas areal bagi setiap peruntukan wisata. Setiap kegiatan wisata mempunyai persyaratan sumberdaya dan lingkungan yang sesuai dengan wisata yang dikembangkan (Yulianda 2007).
Daya dukung lingkungan pada area wisata adalah jumlah individu maksimum yang dapat diakomodir pada suatu area dengan tidak mempengaruhi/merusak lingkungan yang ada dan dapat memberikan suatu kepuasan bagi pengunjung, juga bagi masyarakat setempat (Libosada 1998 in Maryadi 2003). Untuk menghindari kerusakan lingkungan akibat tidak sesuainya antara jumlah pengunjung persatuan luas per satuan waktu,perlu dilakukan suatu analisis daya dukung (carrying capacity analysis) dalam suatu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan wisata.
Daya dukung lingkungan pariwisata dipengaruhui oleh dua faktor utama, yaitu tujuan wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata. Sedangkan daya dukung badan air yang digunakan untuk pariwisata dipengaruhi oleh luas dan volume badan air serta pergerakan air (Soemarwoto 2004).
Faktor bofisik yang mempengaruhi daya dukung lingkungan bukan hanya faktor alamiah, melainkan juga faktor yang berasal dari perbuatan manusia. Daya dukung lingkungan tidak hanya cukup dilihat dari sarana dan pelayanan wisatawan, melainkan juga harus mempertimbangkan kemampuan lingkungan untuk mendukung sarana itu. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perencanaan pariwisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan akan menurunkan kualitas lingkungan, serta merusak ekosistem yang digunakan sebagai objek pariwisata, hal ini akan menghambat bahkan menghentikan perkembangan pariwisata tersebut (Soemarwoto 2004).
III.
METODE PENELITIAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Situ Cikaret Kelurahan Cikaret, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelurahan Cikaret ini memiliki batas
wilayah meliputi Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kuda, Sebelah
Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya, Sebelah Barat berbatasan dengan
Desa Kota Batu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyaharja. Situ
Cikaret memiliki luas perairan sebesar 10.53 ha yang dikelilingi oleh jalan lingkar
dan dam pembatas perairan.
Waktu penelitian pendahuluan dilaksanakan pada bulan Desember 2010
untuk mengetahui kondisi awal daerah penelitian dan mempersiapkan
perlengkapan untuk pengambilan data. Pengumpulan data primer dan sekunder
dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2011.
3.2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan antara lain:
a. Kondisi fisik dan biologi
Kamera digital untuk mengambil foto keadaan lapang dan alat tulis untuk
mencatat data. Bahan yang digunakan adalah peta lokasi objek Situ Cikaret,
beberapa dokumen yang berkaitan dengan Situ Cikaret dan studi pustaka yang
mendukung penelitian. Alat yang digunakan dalam menentukan titik sampling
kualitas air yaitu dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) dan
alat untuk mengukur kualitas air dapat dilihat pada tabel.1.
b. Kondisi sosial ekonomi
Formulir kuisioner, alat tulis, perekam suara untuk merekam wawancara, dan
laporan-laporan.
Tabel 1. Parameter, metode, dan alat yang digunakan untuk analisis kualitas air
No Parameter Alat
Fisika
1. Warna Indra penglihatan
3. Temperatur (ºC) SCT (Salino-Conductivity-Thermo) meter
4. TSS (mg/l) Kertas filter millipore, vacuum pump, dessikator, timbangan
5. Kekeruhan (NTU) Turbiditimeter
6. Kecerahan (cm) Secchi disk
Kimia
1. pH pH meter
2. DO (mg/l)
Botol BOD, gelas ukur, erlenmeyer, pipet dan syringe (sebagai
pengganti buret)
3. BOD (mg/l) Botol BOD, gelas ukur, erlenmeyer, buret, plastik hitam, inkubator
Biologi
1. Plankton Planktonet, botol film dan mikroskop
2. Ikan Alat tulis dan perekam suara
3.3. Jenis Pengumpulan Data
Komponen, jenis, sumber, dan cara pengambilan data yang diperlukan
dalam penelelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jenis data yang dibutuhkan
No Komponen data Jenis data Sumber data Teknik pengambilan data
1. Keadaan umum kawasan wisata air Situ Cikaret
a. Luas dan letak Primer dan
sekunder Lapangan dan laporan
Observasi lapang dan studi pustaka b. Sumber air dan manfaat Situ
Cikaret
Primer dan
sekunder Responden dan laporan
Wawancara dan studi pustaka
c. Topografi Primer dan sekunder Responden dan laporan Wawancara dan studi pustaka
d. Hidrologi Sekunder Laporan Studi pustaka f. Keadaan sosial dan ekonomi
penduduk di Kelurahan Situ Cikaret
Sekunder dan
primer Laporan Studi pustaka
2. Karakteristik sumberdaya alam Situ Cikaret
a. Kualitas air Primer Lapangan Observasi lapang
b. Flora dan fauna di dalam dan sekitar Situ Cikaret
Primer dan
sekunder Lapangan dan laporan
Observasi lapang dan laboratorium serta studi pustaka
3. Karakteristik sosial- ekonomi a. Masyarakat sekitar kawasan wisata
air Situ Cikaret Primer Responden Wawancara
b. Wisatawan Primer Responden Wawancara
c. Instansi-instansi terkait Primer Responden Wawancara
4. Potensi wisata Primer dan
sekunder Lapangan dan laporan
Observasi lapang dan studi pustaka
5. Data kesesuaian wisata Primer Lapangan Observasi lapang
6. Data daya dukung kawasan Primer Lapangan Observasi lapang
3.3.1. Metode pengambilan dan pengumpulan data
Pengambilan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung dan
wawancara berbagai pihak yang terkait dengan tujuan penelitian dengan
menggunakan alat bantu kuisioner. Data primer yang dibutuhkan meliputi:
a. Data mengenai sejarah kawasan Situ Cikaret, permasalahan-permasalahan
yang terjadi dalam pengelolaan.
b. Karakteristik kawasan wisata seperti potensi sumberdaya alam yang dimiliki
oleh objek wisata Situ Cikaret meliputi keindahan alamnya, vegetasi yang
tumbuh di sekitar Situ Cikaret, kondisi perairannya, keanekaragaman jenis
ikan dan plankton yang hidup di dalamnya.
c. Karakteristik pengunjung seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,
pendapatan, intensitas kunjungan, daerah asal, persepsi dan apresiasi terhadap
d. Tanggapan dari masyarakat mengenai kawasan wisata air Situ Cikaret.
e. Keadaan topografi dengan jarak sekitar 50 m dari kawasan wisata Situ
Cikaret.
Pengumpulan data kualitas air dilakukan pada lima titik lokasi yang
diperkirakan dapat mewakili keadaan kawasan wisata Situ Cikaret, yaitu satu titik
pada dua inlet, dua titik ditengah Situ Cikaret, dan satu titik pada satu outlet.
Pengambilan air contoh dilakukan pada bagian permukaan perairan.
Parameter kualitas air yang diamati adalah warna, temperatur, kecerahan,
kekeruhan, TSS, DO, BOD, pH, dan plankton. Pengambilan data ikan diperoleh
dengan cara wawancara terhadap 30 orang masyarakat yang sedang memancing
dan menjala ikan di Situ Cikaret serta pihak pengelola kawasan situ.
Metode pengambilan data sosial-ekonomi yaitu dengan cara wawancara dan
penyebaran kuesioner terhadap 30 orang pengunjung dan 30 orang masyarakat.
Untuk data sekunder dilakukan pengumpulan data yang berasal dari studi pustaka,
laporan, hasil penelitian, dan data penunjang lainnya yang berkaitan dengan
masalah yang dikaji diperoleh dari:
a. Perpustakaan Institut Pertanian Bogor
b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong
c. Instansi-instansi terkait
d. Internet
3.3.2. Metode pengambilan responden
Metode pengambilan sampel terhadap pengunjung dan masyarakat sekitar
dilakukan dengan menggunakan metode accidental sampling dan purposive
sampling. Tehnik accident sampling yaitu proses pengambilan sampel dilakukan
tanpa perencanaan, dari responden yang pertama kali dijumpai dapat dipilih dan
langsung diwawancarai, sedangkan metode purposive sampling yaitu anggota
populasi dipilih untuk memenuhi tambahan tertentu mengandalkan logika atas
kaidah-kaidah yang yang berlaku yang disadari semata-mata dari judgement
peneliti yaitu sampel yang diambil diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang
diajukan, digunakan untuk situasi dimana persepsi orang pada sesuatu sudah
Masyarakat sekitar kawasan situ yang dijadikan responden sebanyak 30
orang ditambah dengan 30 orang pengunjung, hal ini berdasarkan pertimbangan
kemampuan responden dalam memahami dan menjawab kuesioner yang diajukan.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengisian
kuesioner sebagai data pokok. Data-data yang sudah dikumpulkan dianalisa
dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga bisa ditentukan altematif strategi
dalam upaya pengelolaan Situ Cikaret secara berkelanjutan.
3.4. Metode Analisis Data 3.4.1. Kualitas air
Kualitas air Situ Cikaret dibandingkan dengan baku mutu kualitas air
menurut PP No.82 tahun 2001 kelas 2 dan literatur-literatur lain yang mendukung
penelitian.
3.4.2. Kelimpahan plankton
Pencacahan organisme plankton dilakukan dengan menggunakan metode
sensus. Menurut Greenberg et al. (1980) jumlah individu plankton per liter air
dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
a
N = Jumlah total fitoplankton (ind/l)
n = Jumlah rataan individu yang teramati (ind)
u = Ulangan (3)
Vt = Volume air tersaring (30 ml)
Vcg = Volume air dibawah coverglass ( 1 ml)
Aa = Luas satu lapang pandang (20x50 mm2)
Acg = Luas coverglass/SRC (20x50mm2)
3.4.3. Analisis potensi dan kesesuaian
Analisis potensi dalam penelitian ini mencakup sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia yang berada di dalam maupun di luar atau sekitar Situ
air, tumbuhan air, flora dan fauna yang terdapat di sekitar Situ Cikaret. Potensi
sumberdaya manusia mencakup masyarakat sekitar kawasan Situ Cikaret,
pengunjung dan instansi yang terkait seperti Kelurahan, Dinas Pariwisata, Dinas
Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Kegiatan wisata yang akan dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan
potensi sumberdaya alam dan peruntukannya. Setiap kegiatan wisata mempunyai
persyaratan sumberdaya dan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan wisata yang
dikembangkan. Persamaan yang digunakan untuk kesesuaian wisata adalah
(Yulianda 2007):
∑
= (Ni/Nmaks)x100%)
IKW
Keterangan :
IKW = Indeks Kesesuaian Wisata
Ni = Nilai parameter ke-i (Bobot x Skor)
Nmax = Nilai maksimum dari suatu kategori wisata.
Nilai parameter ke-i (Ni) merupakan hasil perkalian antara bobot dan skor
lokasi penelitian dari suatu parameter. Nilai maksimum dari suatu kategori wisata
(Nmaks) merupakan hasil perkalian antara bobot dan skor maksimum dari suatu
parameter. Parameter, bobot dan skor yang dimaksud dapat dilihat pada matriks
kesesuaian. Matriks kesesuaian wisata yang digunakan berdasarkan matriks
kesesuaian menurut Yulianda (2007) yang telah dimodifikasi. Matriks ini dibuat
berdasarkan hasil studi pustaka dan subjektifitas dari pakar yang ahli dalam
bidangnya.
Kesesuaian lahan untuk wisata perairan tawar bagian danau dapat dibagi
wisata kategorinya menjadi berkemah, perahu karet, memancing, duduk santai,
outbound dan berendam di air panas. Kesesuaian wisata danau
mempertimbangkan masing-masing parameter yang berbeda dalam kategori
Tabel 3. Parameter kesesuaian sumberdaya untuk wisata danau
No Parameter Bobot Kategori Skor
Berkemah
Lumpur/batu datar 1
Batu cadas/tanah labil 0
3 Vegetasi yang hidup di tepi
danau 3
Kelapa, Cemara, Akasia 3
Campuran pohon dan belukar 2
Belukar tinggi 1
Belukar tinggi dan rawa 0
4 Pemandangan (Object view) 3
Danau, Hutan, Pegunungan,
Sungai 3
Danau dan 2 dari 3 pemandangan 2
1dari 4 pemandangan 1
Tidak ada obyek yang indah 0
Kelapa, Cemara, Akasia 3
Belukar tinggi 1
5 Warna perairan 1
Hijau jernih 3
Hijau Kecoklatan 2
Coklat kehitaman 1
No Parameter Bobot Kategori Skor
3 kedalaman perairan 1
Satu dari 4 pemandangan 1
2 Vegetasi yang hidup di tepi
danau 5
Kelapa, Cemara, Akasia 3
1 dari 3 2
2 Vegetasi yang hidup di tepi
danau 3
Kelapa, Cemara, Akasia 3
1 dari 3 2
Sumber : Yulianda 2010 Keterangan:
Nilai maksimum = 51 (perahu karet), 51 (berkemah), 27 (Memancing), 51 (duduk santai), 36 (outbound).
Analisis daya dukung ditujukan pada pengelolaan kawasan wisata Situ
Cikaret dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada secara lestari.
Metode yang digunakan untuk menghitung daya dukung pengembangan
ekowisata alam yaitu dengan menggunakan konsep Daya Dukung Kawasan. Daya
Dukung Kawasan (DDK) adalah jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik
dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa
menimbulkan gangguan pada alam dan manusia.
Perhitungan DDK dalam bentuk rumus (Yulianda 2007) dapat dituliskan
sebagai berikut :
DDK = K x Lp/Lt x Wt/Wp
Dimana:
DDK = Daya Dukung Kawasan
K = Potensi ekologis pengunjung per satuan unit area Lp = Luas area atau panjang area yang dapat dimanfaatkan
Lt = Unit area untuk kategori tertentu (sepeda air, memancing, duduk santai, outbond, pengambilan gambar untuk foto)
Wt = Waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari
Wp = Waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu (sepeda air, memancing, duduk santai, outbond, pengambilan gambar untuk foto)
Tabel 4. Potensi ekologis pengunjung (K) dan Luasan area kegiatan (Lt)
Jenis
dibutuhkan untuk 4 orang (1 perahu kayu) untuk mengelilingi situ seluas 1.000 m2
Memancing 1 10 m Setiap 1 orang membutuhkan
area untuk memancing seluas 10 m
Duduk santai 2 100 m2 Setiap 2 orang membutuhkan
ruang untuk duduk santai sepanjang 100 m2
Outbound 5 200 m2 Dihitung luas lokasi yang
dibutuhkan untuk 5 orang (1
team) untuk outbound adalah 200 m2
Berkemah 5 500 m2 Dihitung luas satu tenda (5
orang) 500 m2 dan jarak antar tenda 10 m
Potensi ekologis pengunjung (K) ditentukan oleh kondisi sumberdaya dan
jenis kegiatan yang akan dikembangkan. Panjang dan luas area wisata Situ Cikaret
(Lp) yang dapat digunakan oleh pengunjung mempertimbangkan kemampuan
alam mentolerir pengunjung sehingga keaslian alam tetap terjaga.
Daya dukung kawasan disesuaikan dengan karakteristik sumberdaya dan
peruntukannya, misalnya daya dukung wisata bermain air ditentukan panjang dan
luas area (Lt) yang diperuntukkan untuk sepeda air dan kondisi aimya. Kebutuhan
manusia akan ruang diasumsikan dengan keperluan ruang horizontal untuk dapat
bergerak bebas dan tidak merasa terganggu oleh keberadaan manusia (pengunjung
lainnya). Untuk wisata bermain air diasumsikan setiap orang membutuhkan 625
m2.
Waktu kegiatan pengunjung (Wp) dihitung berdasarkan lamanya waktu
yang dihabiskan oleh pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata. Kegiatan
wisata dapat diperjelas lagi berdasarkan kegiatan yang dilakukan atau kegiatan
yang dapat dikembangkan misalnya mengelilingi situ dengan sepeda air,
memancing, duduk santai, outbound, pengambilan gambar untuk foto dan
shooting. Waktu pengunjung diperhitungkan dengan waktu yang disediakan untuk
kawasan (Wt). Waktu kawasan adalah lama waktu areal dibuka dalam satu hari,
dan rata-rata kerja sekitar 8 jam (08.00 - 16.00) WIB.
Tabel 5. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata
No Kegiatan Waktu yang dibutuhkan
Wp-(jam)
Total waktu 1 hari Wt-(jam)
Sumber: Yulianda 2010
3.4.5. Analisis SWOT
Analisis yang digunakan untuk strategi pengelolaan adalah analisis SWOT
yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi
kondisi sebuah objek wisata secara sistematik dengan membandingkan faktor
internal Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weaknesses) dengan faktor
eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (threats). Metoda analisis data
yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data
secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan
faktor eksternal, sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan dengan
pembobotan dan pemberian rating.
Dari analisis SWOT ini akan dihasilkan matriks SWOT. Matriks ini dapat
menghasilkan empat strategi kemungkinan alternatif. Keempat strategi tersebut
adalah:
1. SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan
memanfaatkan peluang sebesar-besarnya
2. ST, yaitu strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi
ancaman
3. WO, yaitu strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada
dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
4. WT, yaitu strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan
berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman
Kerangka kerja dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT adalah sebagai
berikut :
a. Analisis Penilaian Faktor Internal dan Faktor Eksternal
b. Penentuan Bobot Setiap Variabel
c. Penentuan Peringkat (Rating)
d. Penyusunan Alternatif Strategi
e. Pembuatan Tabel Rangking Alternatif Strategi
3.4.5.1. Analisis penilaian faktor internal dan eksternal
Penilaian faktor internal (IFE) adalah untuk mengetahui sejauh mana
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan cara mendaftarkan semua kekuatan
dan kelemahan serta memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
hubungan antara area-area tersebut. Sedangkan penilaian faktor eksternal (EFE)
adalah untuk mengetahui sejauh mana ancaman dan peluang yang dimiliki dengan
Hal tersebut dilakukan dengan mengevaluasi dan identifikasi terhadap
faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Identifikasi berbagai
faktor tersebut secara sistematis digunakan untuk merumuskan strategi untuk
pengelolaan kawasan wisata Situ Cikaret.
3.4.5.2. Penentuan Bobot Setiap Variabel
Sebelum melakukan pembobotan faktor internal maupun eksternal,
terlebih dahulu ditentukan tingkat kepentingannya. Setiap faktor internal dan
eksternal diberi nilai berdasarkan tingkat kepentingannya (Tabel 6 dan Tabel 7).
Tabel 6. Tingkat kepentingan faktor internal
Simbol Faktor kekuatan (Strength) Tingkat kepentingan
S1 Kekuatan yang sangat besar
S2 Kekuatan yang besar
S3 Kekuatan yang sedang
Sn
Simbol Faktor kelemahan (Weakness)
Tingkat Kepentingan
W1 Kelemahan yang tidak berarti
W2 Kelemahan yang kurang berarti
W3 Kelemahan yang cukup berarti
Wn
Tabel 7. Tingkat kepentingan faktor eksternal
Simbol Faktor peluang
(Opportunities)
Tingkat kepentingan
O1 Peluang tinggi
O2 Peluang sangat tinggi
O3 Peluang rendah
On
Simbol Faktor ancaman (Threats) Tingkat kepentingan
T1 Ancaman sedang
T2 Ancaman besar
T3 Ancaman kecil
Tn
Penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor
digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor penentu
internal dan eksternal (Tabel 8).
Menurut David (2006) penentuan bobot setiap variabel menggunakan
skala 1, 2, 3, dan 4 yaitu :
1 : Jika indikator faktor horizontal kurang penting daripada indikator faktor
vertikal
2 : Jika indikator faktor horizontal sama penting dengan indikator faktor vertikal
3 : Jika indikator faktor horizontal lebih penting daripada indikator faktor vertical
4 : Jika indikator faktor horizontal sangat penting daripada indikator faktor
internal
Tabel 8. Penilaian Bobot Faktor Strategi Internal dan Eksternal
Faktor Strategis Internal/Eksternal
A B C D E Total
A B C D …. Total
Sumber : Kinnear & Taylor (1991) in Nancy (2007)
Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan niali setiap variabel
terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus (Kinnear
& Taylor 1991 in Nancy 2007) :
Keterangan :
ai = bobot variabel ke-i
xi = nilai variabel ke-i
i = 1, 2, 3,.….n
3.4.5.3. Penentuan peringkat (rating)
Pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi objek diukur dengan
menggunakan nilai peringkat dengan skala 1-4 terhadap masing-masing faktor
strategis yang dimiliki objek wisata Situ Cikaret (Tabel 9).
Tabel 9. Skala penilaian peringkat untuk Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE)
Nilai Peringkat
Matriks IFE Matriks EFE
Strengths (S)
Weakness (W) Opportunities (O)
Nilai dari pembobotan dikalikan dengan peringkat pada setiap faktor dan
semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk memperoleh total skor
pembobotan. Total skor pembobotan berkisar antara 1-4 dengan rata-rata 2.5. Jika
total skor pembobotan IFE dibawah 2.5 maka dapat dinyatakan bahwa kondisi
internal lemah, sedangkan jika berada diatas 2.5 maka dinyatakan bahwa kondisi
internal kuat. Demikian juga total pembobotan EFE jika dibawah 2.5 menyatakan
bahwa kondisi eksternal lemah dan jika diatas 2.5 menyatakan bahwa kondisi
eksternal kuat (David 2006). Matriks IFE dan matriks EFE dapat dilihat pada
Tabel 10. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)
Faktor strategis
internal Bobot Rating
Skor
Tabel 11. Matriks External Factor Evaluation (EFE)
Faktor strategis
eksternal Bobot Rating
Skor
3.4.5.4. Penyusunan Alternatif Strategi
Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan
adalah matriks SWOT (Tabel 12). Hubungan antara kekuatan dan kelemahan
dengan peluang dan ancaman digambarkan dalam matriks tersebut. Matriks ini
menghasilkan beberapa alternatif strategi sehingga kekuatan dan peluang dapat
ditingkatkan serta kelemahan dan ancaman dapat diatasi.
Table 12. Matriks SWOT
3.4.5.5. Pembuatan Tabel Rangking Alternatif Strategi
Penentuan prioritas dari strategi yang dihasilkan dilakukan dengan
memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait. Jumlah dari skor pembobotan
akan menentukan rangking prioritas strategi (Tabel 13). Jumlah skor (nilai) ini
diperoleh dari penjumlahan semua skor di setiap faktor-faktor strategis yang
terkait. Rangking akan ditentukan berdasarkan urutan jumlah skor terbesar sampai
yang terkecil dari semua strategi yang ada. Perangkingan ini dilakukan secara
subyektif dimana strategis akan berupa usaha memaksimumkan kekuatan
(Strengths) dan kelemahan (Opportunities) serta meminimumkan ancaman
(Threats) dan kelemahan (Weakness).
Tabel 13. Perangkingan alternatif strategi berdasarkan matriks SWOT
Alternatif strategi Keterkaitan dengan unsur SWOT Nilai Rangking SO1
4.
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Situ Cikaret
Situ Cikaret merupakan salah satu dari 96 situ yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Secara geografis terletak pada 6o28’ LS dan 106o50’ BT sedangkan secara administrasif, Situ Cikaret berada di Jalan Raya Cikaret dan berada pada tiga desa, yaitu Desa Pekansari, Desa Tengah, dan Desa Harapan Jaya yang termasuk Kelurahan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kelurahan Cikaret memiliki batas wilayah meliputi Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Kuda, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Jaya, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Batu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyaharja (Gambar 3).
Gambar 3. Peta Kawasan Situ Cikaret Sumber : (www.google earth.com)
Sehingga instansi pengelola yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan sumberdaya kawasan Situ Cikaret adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, hal ini dikarenakan Situ Cikaret merupakan anak sungai dari sungai lintas provinsi yaitu Sungai Ciliwung. Namun, dikarenakan letak Sungai Cikaret berada di Kabupaten Bogor, maka Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang dalam hal ini yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor yang berperan dalam operasi dan pemeliharaan Situ Cikaret terkait pemanfaatannya sebagai sarana irigasi. Sedangkan untuk pemanfaatan yang telah ada saat ini terkait dengan objek wisata di Situ Cikaret dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti pemeliharaan fasilitas hiburan dan pengadaan warung makan. Untuk pengadaan sarana kebersihan, taman Situ Cikaret, papan informasi, dan gazebo atau tempat duduk santai dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.
Situ Cikaret terletak pada ketinggian 125 m dari permukaan laut dengan topografi berbentuk cekungan, serta memiliki kemiringan lahan 8%-25%. Jenis tanah yang terdapat di Situ Cikaret dan sekitarnya adalah tanah latosol. Pada perairan ini terdapat banyak teluk-teluk yang ditutupi oleh tumbuhan air. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson, wilayah Kecamatan Cibinong termasuk tipe iklim A yang bersifat basah. Arah angin, sebagian besar berasal dari selatan dengan kecepatan 4-6 m per detik. Temperatur rata-rata antara 25.30-26.30 C dengan kelembaban udara antara 67.90%-85.68% (Bappeda 1994). Situ Cikaret mendapatkan pasokan air dari Sungai Playangan dan Sungai Kebantenan. Sedangkan outlet Situ Cikaret adalah Sungai Tambakan dan Sungai Cikaret.
4.1.1. Sumber air dan manfaatnya
terjadi sedimentasi atau pengendapan lumpur, kemudian akan terbentuk daratan yang tidak stabil dan berpotensi menimbulkan penyuburan berlebih (eutrofikasi). Sebagian besar perairan situ yang berada di Desa Pekansari dan Desa Tengah telah berubah menjadi persawahan atau kolam ikan. Sebagian lagi telah ditimbun dalam rangka pengembangan Desa Tengah menjadi Ibu Kota Kabupaten Bogor. Perairan situ yang masih terbuka adalah bagian hilir dekat bendungan di Desa Harapan Jaya.
Situ Cikaret dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan perikanan (budidaya dan penangkapan), pertanian sebagai sarana pengairan sawah seluas 300 ha di daerah hilir, pengendali banjir, kawasan berdagang, pariwisata, sarana latihan olahraga air, tempat latihan TNI, dan latihan tim SAR. Bentuk pemanfaatan kegiatan perikanannya yaitu sebagai lahan usaha perikanan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap peralatan yang dipergunakan adalah alat statis berupa jaring insang dan pancing rawai, sedangkan untuk perikanan budidaya yaitu dengan membangun kolam-kolam dan patok-patok sebagai rumah ikan di tepian situ.
4.2. Sarana dan Prasarana yang telah ada di Kawasan Situ Cikaret
Sarana dan prasarana umum yang terdapat dikawasan Situ Cikaret ini sudah cukup banyak namun belum termanfaatkan dengan optimal terutama sarana kebersihan lingkungan seperti bak pengolahan limbah, tong sampah dan kebersihan Situ Cikaret itu sendiri. Sarana dan prasarana yang sudah dimiliki antara lain warung makan, jalan setapak, mushala, gazebo atau sarana duduk santai, fasilitas bermain, tong sampah, taman situ cikaret dan papan informasi (Lampiran 1).
4.3. Sumberdaya Kawasan Situ Cikaret
4.3.1. Sumberdaya Hayati 4.3.1.1. Fitoplankton
Tabel 14. Kelimpahan fitoplankton di perairan Situ Cikaret
1 Actinastrum hantzchii 2202 1761 881 2453 2705
2 Coelastrum 0 6668 0 4907 0
3 Closterium 0 0 2202 692 2139
4 Mougeotia 1636 692 440 1007 0
5 Scenedesmus 315 0 126 252 377
6 Botryococcus 1573 35291 75490 14154 87065
Cyanophyceae
Total 7675 58503 99647 27450 107006
4.3.1.2. Zooplankton
Zooplankton memiliki peran penting dalam suatu ekosistem karena menjadi konsumen tingkat satu dalam rantai makanan suatu ekosistem perairan. Jumlah kelas dan genus zooplankton yang dijumpai di Situ Cikaret relatif sedikit, yaitu terdiri atas tiga kelas (6 genus) dengan kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 4 yaitu 2768 ind/l. Kisaran kelimpahan zooplankton pada stasiun 1 sampai stasiun 5 di perairan Situ Cikaret berturut-turut adalah 377-944 ind/l, 126-944 ind/l, 189-629 ind/l, 126-944 ind/l, dan 189-944 ind/l. (Tabel 15). Kelimpahan zooplankton secara umum berkisar antara 126-994 ind/l dan didominasi oleh genus
Cephalodella (kelas Rotifera). Ketersediaan zooplakton di perairan diharapkan
ikan-ikan plankton feeder, dengan memanfaatkan keberadaan zooplankton sebagai pakan alami.
Tabel 15. Kelimpahan zooplankton di perairan Situ Cikaret
No Genus
Total 2328 2265 2579 2768 2642
4.3.1.3. Komunitas Ikan
Ketersediaan sumber daya alam di kawasan wisata Situ Cikaret khususnya ketersediaan ikan, sekarang sudah semakin berkurang. Hal ini dapat dirasakan bagi masyarakat sekitar yang biasanya menjala dan memancing di sekitar kawasan Situ Cikaret dengan jumlah tangkapan yang semakin menurun, namun pihak pengelola yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah pada event-event tertentu biasanya melakukan penebaran beberapa jenis ikan di perairan Situ Cikaret. Tujuannya dilakukan penebaran ikan tersebut selain untuk menarik minat wisatawan yang akan melakukan kegiatan memancing, juga dapat menambah ketersediaan ikan yang berada di kawasan Situ Cikaret, tetapi perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan perairan dengan mengetahui daya dukung perairan sehingga tidak mengganggu ekosistem perairan tersebut.
jenis ikan tersebut dapat menghambat perkembangan jenis ikan lainnya. Oleh sebab itu pengurangan jumlah ikan karnivora diperairan perlu dilakukan (Tabel 16).
Tabel 16. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di Situ Cikaret
No Jenis Ikan
10 Belida (Notopterus sp.) V 11
4.3.1.4. Tumbuhan air
Eceng gondok memiliki kemampuan menyerap logam berat, dan dapat tumbuh dengan cepat pada danau dan waduk sehingga dalam waktu yang singkat dapat mengurangi oksigen, mengurangi fitoplankton dan zooplankton serta menyerap air sehingga dapat terjadi proses pendangkalan, sedangkan tumbuhan hydrilla merupakan tumbuhan liar yang mempunyai daya penyebaran yang sangat cepat dan secara signifikan dapat mengurangi tanaman air serta keanekaragaman hayati hewan. Tumbuhan hydrilla juga dapat mempengaruhi ukuran ikan dan tingkat populasi di mana ikan predator tidak dapat berburu efektif dalam perairan yang terdapat banyak hydrilla, selain itu juga dapat mempengaruhi kegiatan rekreasi, memperlambat saluran irigasi dan menciptakan air tergenang yang berkembang biak nyamuk. Padatan atau serasahnya bahkan dapat menyebabkan banjir, mengubah kualitas air dengan menurunkan kadar oksigen, peningkatan pH dan suhu air (Gambar 4).
Gambar 4. Jenis tumbuhan air yang terdapat di Situ Cikaret Sumber foto : Dokumentasi pribadi
4.3.1.5. Vegetasi tepi situ
Situ Cikaret merupakan kawasan perairan yang dikelilingi oleh kawasan perhutanan, perkantoran, dan jalan raya. Bagian barat Situ Cikaret dikelilingi oleh jalan raya, pepohonan, dan rerumputan, sedangkan bagian utara yaitu pepohonan, semak-semak dan kawasan perkantoran, bagian timur merupakan kawasan perhutanan dengan dominasi pohon kelapa, pohon pinus, semak-semak, dan rumput liar. Bagian selatan Situ Cikaret didominasi oleh semak-semak, perkebunan dan terdapat kawasan warung makan (Lampiran 2).
Eichhornia crassipes
4.3.2. Sumberdaya Air
Sumberdaya air merupakan salah satu bagian situ yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di suatu perairan. Kualitas sumberdaya air suatu perairan dapat dilihat dari beberapa parameter antara lain parameter fisika yang mencakup warna, suhu, kecerahan, kekeruhan, dan TSS. Parameter kimia yang diamati adalah pH, DO, dan BOD (Tabel 17).
Pengambilan contoh air dilakukan pada tanggal 20 Januari 2011 pada pukul 09.00 hinggal pukul 10.30 dengan kondisi cuaca mendung pada kedalaman perairan 0-30 cm dari permukaan. Pengambilan contoh air dilakukan diberbagai tempat dengan prinsip keterwakilan dan berdasarkan pada karakteristik yang dimiliki perairan. Untuk parameter fisika-kimia-biologi diambil di lima stasiun. Stasiun 1 yaitu perairan kawasan perikanan, dekat dengan kegiatan pertanian dan perkebunan, stasiun 2 yaitu dibagian tengah perairan, stasiun 3 inlet dari Sungai Playangan, stasiun 4 yaitu inlet dari Sungai Kebantenan, stasiun 5 yaitu outlet dan dekat dengan warung-warung makan (Lampiran 3).
Keterangan : p yaitu permukaan
* yaitu batas maksimum yang diperbolehkan pada baku mutu PP No.82 tahun 2001 klas 2.
** yaitu batas minimum yang diperbolehkan. Sumber : Data primer, 2011 (diolah)
4.3.2.1. Parameter fisika a. Warna
Warna perairan Situ Cikaret yang diamati secara visual berdasarkan indra penglihatan pada umumnya berwarna hijau kecoklatan (Tabel 17). Warna perairan sendiri dapat mempengaruhi estetika dan menunjukkan keberadaan plankton diperairan. Warna kecoklatan diperairan diduga karena adanya bahan organik, bahan anorganik, keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam yang terkandung didalamnya (Effendi 2003). Selain itu, perairan tersebut juga berpotensi mengalami kekeruhan yang tinggi. Kekeruhan yang terjadi dapat membatasi masuknya sumber cahaya, sehingga fitoplankton tidak dapat berfotosintesis. Warna perairan hijau kecokelatan yang mendominasi di stasiun 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan pada stasiun 3 perairan berwarna hijau kehitaman, hal ini diduga karena perairan telah terkontaminasi dengan limbah pabrik botol yang terdapat di dekat Situ Cikaret dan juga terdapat oksida mangan pada perairan sehingga menyebabkan air berwarna kecoklatan atau kehitaman (Effendi 2003).
b. Suhu