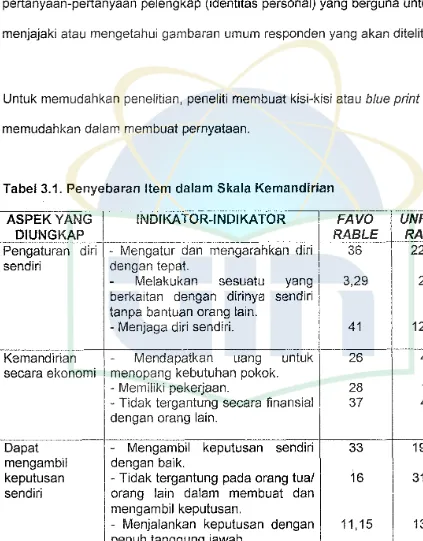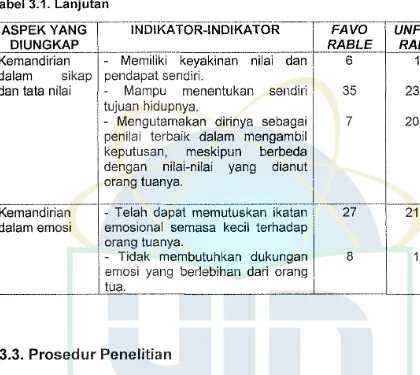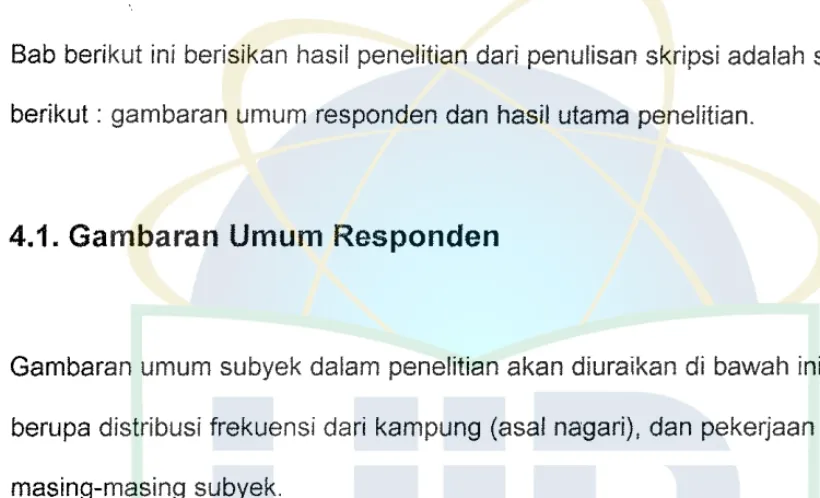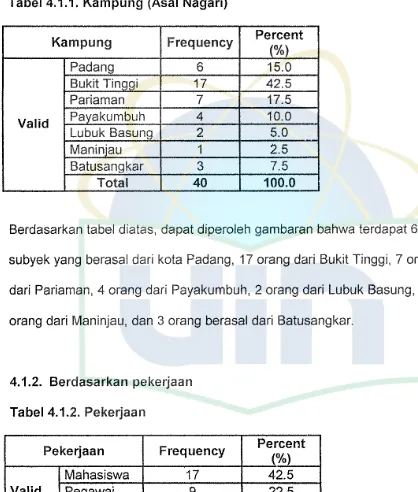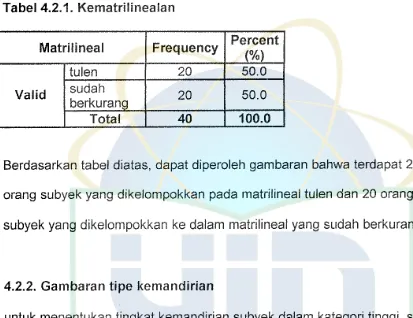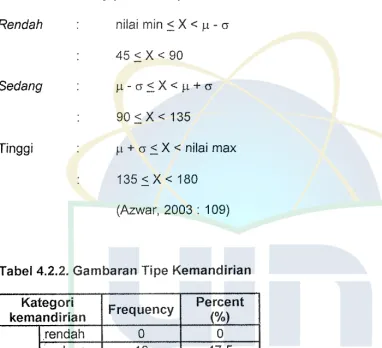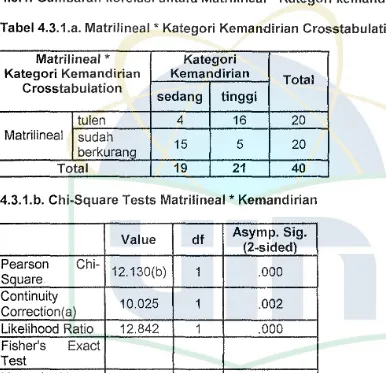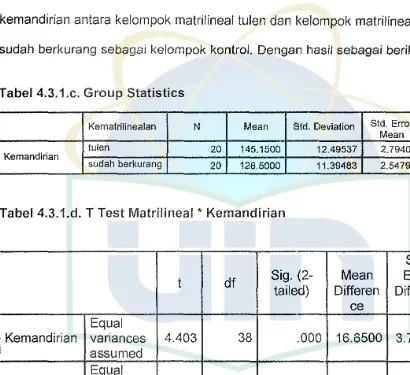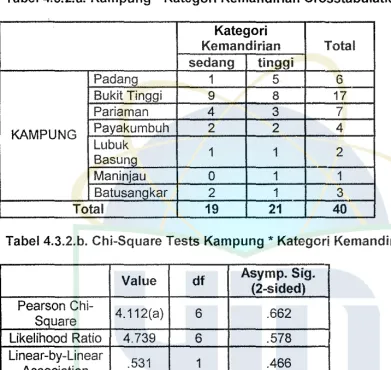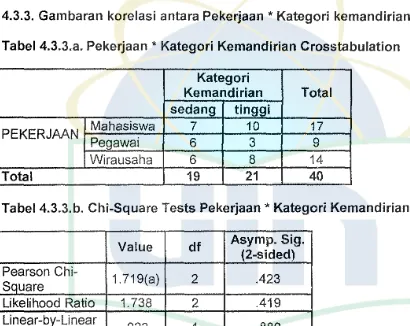SUDAH
DI SCAN
PENGARUH SISTEM MATRILINEAL TERHADAP
KEMANDIRIAN LAKl-LAKI MINANGKABAU
Oleh:
RADHIYA BUST AN
NIM : 100070020161Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
memperoleh
gelar Sarjana Psikologi
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
TERHADAP KEMANDIRIAN LAKl-LAKI MINANGKABAU telah diujikan
dalam sidang munaqasycih Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif
Hid2yatullah Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2004. Skripsi ini telah diterima
sehagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1
(S 1) pad a Fakultas Psikologi.
Ora. n・エエ|セ@ rtati, M.Si
NIP. セUP@ セ@ 938
\
'
Penguji I
セ@
Dr. Lily Surayya Ekaputri
Sidang Munaqasyah
Anggota
Jakarta, 30 Agustus 2004
Sekret
Abdul Rahman Sh
NIP. 150
l)3
224Ora. N Hartati, M.Si
NIP. 1 \ 15 938
_/'//'
Q/t,a/uw·.>MJtb<Ihhr.r//1,
kehendakNyalah segala sesuatu bisa terjadi, atas ridhaNya juga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Kesejahteraan, keselamatan, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang sepanjang hidupnya telah
memikirkan umatnya agar mereka selamat dunia dan akt1irat. Allahumma
Sha/Ii Wassalim 'Alaihi. Selain Allah dan Rasulnya, penulis juga ingin menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :
1. Papaku Bustanuddin Agus dan Mamaku Rosnida R yang sangat kusayangi, terima kasih telah sangat berjasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dan telah memberikan dukungan yang sangat besar baik lahir maupun bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Yang terhormat lbu Ora. Hj. Netty Hartati, M.Si, selaku dekan Fakultas
Psikologi UIN Syarif Hidayatullah dan sekaligus sebagai pembimbing I
dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat lbu Ora. Zahrotun Nihayah, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Psikologi UIN, terima kasih atas semuanya Bu ... 4. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman Shaleh, M.Si, sebagai
pembimbing II yang dengan sabar telah banyak memberikan
bimbingan-bimbingan kepada penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat lbu Ora. Agustiyawati, M. Phil, sne, selaku dosen Pembimbing Akademik kelas B angkatan 2000, Ors. Asep Haerul Gani, Psi, sebagai dosen seminar, terima kasih telah mau meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk dan saran kepada penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Psikologi yang telah mengajar dan staff
administrasi Fakultas Psikologi yang telah membantu menyelesaikan segala keperluan yang berkaitan dengan skripsi ini dengan baik.
7. Kakak-kakaku tercinta Nefi dan Nefa, serta adik-adikku tersayang Milla dan Fani, terima kasih karena telah menjadi semangat bagi penulis.
8. lbunda Afniwati dan Om Arifin, Pak In dan Tante Yuni, Pak Eri dan Tante Des, Uni Lili dan Om Man, yang telah memberikan dukungan dan perhatian yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Faiz .... , makasih ya telah memberikan support kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta angkatan 2000 Fakultas Psikologi UIN, khususnya Eci, Emi, Rita, Fitri, Adi, Hamdan, serta Kak Bowo, yang telah banyak membantu, memberikan informasi dan rneleburkan kecemasan penulis dalam menghadapi kesulitan menyelesaikan skripsi ini.
12.Adik-adikku di kosan, Nova dan Opi yang selalu setia mengingatkan penulis untuk terus bersemangat.
13. Pak Syaf dan !bu, senior-seniorku; Da Buja, Da Jhon, Da lrwandi, Da Busman, Da Andi, Da UI, Da Budi, Da lean, Da Yulius, Da Pita, Da Ud, Da Hafiz, Da Mursal, Da Zul, Mamak Edwil dan Mamak Aja, teman-temanku; Yenti, Mini, Delvi, Nini, Ria, Elza, dan Ummul serta adikku Pepen yang selalu setia menemani, dan seluruh anggota KMM Ciputat maupun KMM Jaya yang telah memberikan masukan-masukan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan tentunya terima kasih juga atas kesediaannya untuk menjadi responden dalam penelitian ini.
14. Perpustakaan Psikologi UIN, Perpustakaan Pusat UIN, Perpustakaan Fakultas Psikologi dan Antropologi UI, dan PDll-LIPI, yang telah memberikan banyak sumbangan ilmu bagi penulis
15. Serta seluruh pihak yang membantu dan menyediakan sarana dan prasarana kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Demikianlah rasa syukur dan terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dan berperan aktif serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan tidak mengurangi segala hormat, maka demi kebaikan serta kemajuan selanjutnya penulis mohon saran serta masukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun
bagi siapa saja yang dapat dan sempat membacanya. Amiin Ya Rabbal
'Alamin ...
Jakarta, Agustus 2004
Penulis,
(C) Radhiya Bustan
(D) Pengaruh Sistem Matrilineal Terhadap Kemandirian Laki-laki
Minangkabau
(E) xv + 76 halaman
(F) Minangkabau adalah salah satu etnis yang terdapat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di propinsi Sumatera Barat. Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama dalam masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal adalah garis keturunan, yang menelusuri garis keturunan, perempuan (anak perempuan, anak dari anak perempuan) (Keesing, 1975). Sebagai akibat dari sistem matrilineal itu, posisi laki-laki seolah-olah menjadi lemah, karena dalam sistem ini pembagian harta pusaka, sawah ladang dan tempat tinggal, didominasi oleh perempuan.
Bahkan dalam pembuatan keputusan yang vital bagi anak keturunan dalam kaum pun perempuan tetap memiliki posisi kewenangan dan kekuasaan (Tanner& Thomas, 1985).
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem matrilineal berpengaruh terhadap kemandirian laki-laki Minangkabau. Dalam penelitian ini akan dilihat apakah nantinya terdapat hubungan dan perbedaan antara kemandirian laki-laki Minangkabau yang masih memegang matrilineal tulen dengan kernandirian laki-laki
Minangkabau yang sudah terpengaruh oleh budaya lain, seperti pengaruh dari sistem patrilineal, dan pengaruh lainnya.
Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada akhir bulan Juli 2004. Populasi pada penelitian ini adalah laki-laki Minangkabau (matrilineal) yang sedang
dan pernah menjalani pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang berusia 18-40 tahun (dewasa dini). Dimana sampel untuk penelitian ini berjumlah 70 orang, dengan rincian 30 orang untuk penelitian tahap pertama (try out skala) dan 40 orang untuk penelitian tahap kedua. Berdasakan analisa hasil kuesioner, dari 40 orang responden penelitian tahap kedua ini terdiri dari 20 orang yang matrilineal tulen dan 20 orang matrilineal yang sudah berkurang.
Melalui teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan cara
incindental sampling disebarkan instrumen penelitian berupa angket
hasil pilot study dengan reliabilitas 0,959 pada skaia kemandirian.
Analisa data menggunakan uji Chi Square dengan a= 0,05 dan df
=
1,Dari hasil analisa statistik ditemukan: terdapat hubungan atau pengaruh antara sistem matrilineal dengan tingkat kemandirian. Berdasarkan perbandingan Chi Square uji dan label, diperoleh
keputusan bahwa Chi Square hitung/Koreksi Yates> Chi Square tabel (10,025 > 3,84), maka Ho ditolak. Sedangkan untuk melihat perbedaan
mean dari kedua variabel ini dilakukan dengan uji t (T test).
Berdasarkan perbandingan t hitung dan label, dapat diambil keputusan bahwa t hitung > t label (4.403 > 1,68), maka Ho ditolak, berarti bahwa ada pengaruh sistem matrilineal terhadap l<emandirian laki-laki
Minangkabau. Kemudian juga terdapat beberapa analisis terhadap data pendukung, dengan hasil sebagai berikut: (1) Tidak ada
hubungan antara kampung/asal nagari dengan tingkat kemandirian. (2) Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan tingkat kemandirian. (3) Tidak ada hubungan antara kampung/asal nagari dengan tingkat kematrilinealan. (4)Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kematrilinealan seseorang.
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lebih lanjut dari skripsi Nurkesuma. Dimana penelitian ini mendukung hasil penelitiannya yang berjudul Nilai Kemandirian dalam Pola Kekerabatan Matrilineal dan ldentitas Sosial Perempuan Minangkabau. Dengan hasil penelitiannya
bahwa: 0
Nilai kemandirian dapat digunakan sebagai peramal terhadap identitas sosial dan sebaliknya identitas sosial dapat dijadikan sebagai peramal bagi kemandirian" (Skripsi Fakultas Psikologi Depok, 1995). Sementara dalam skripsi ini identitas sosial tersebut adalah sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangl<abau. Terbukti bahwa sistem tersebut memberikan pengaruh terhadap kemandirian laki-laki Minangkabau. Hal ini juga berkaitan dengan pendapat Tajfel (1982) bahwa jika seseorang memiliki identitas sosial maka ia akan
menggunakan nilai-nilai kelompok tersebut sebagai patokan dalam bertingkah laku. Zavalloni dan Louis-Guerin (1977) juga mengatakan bahwa representasi antar kelompok yang menggambarkan elemen-elemen identitas social didasari salah satunya oleh nilai yang terkait dalam kelompok-kelompok tersebut.
Untuk penelitian lebih lanjut dapat diteliti mengenai "Seberapa besar masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal?" dan "Apakah terjadi pergeseran sistem matrilineal di Minangkabau menuju sistem patrilineal dewasa ini?". Kemudian juga diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbesar jumlah sampel penelitian, serta mengadakan perbandingan dengan kelompok masyarakat patrilineal. Metode observasi dan wawancara juga dapat dilakukan untuk lebih memperdalam hasil penelitian.
HALAMAN PERSEMBAHAN ... 1v
KATA PENGANTAR. . ... ... ... . ... . . ... v
ABSTRAK ... . .. vii
DAFTAR ISi. ... ix
DAFTAR TABEL.. XI BAB 1 BAB 2 BAB 3 PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2. ldentifikasi Masalah ... ... .. . ... ... .. ... ... ... 11
1.3. 1.4. 1.5. 1.2.1. Pembatasan Masalah ... . 11
1.2.2. Perumusan Masalah ... . 14
Tujuan Penelitian ... . . ... 14
Manfaat Penelitian ... 15
Sistematika Penulisan ... .. . .... 16
KAJIAN PUST AKA ... 17
2.1. Kajian Teori... ... ... ... .... ... 17
2.1.1. Minangkabau... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 17
a. Dasar Budaya Minangkabau... 18
b. Sistem Kekerabatan Matrilineal... ... ... ... 22
c. Kecenderungan Merantau... ... . 31
2.1.2. Kemandirian ... . 33
2.1.3. Penelitian Terdahulu ... . . ... 38
2.2. Kerangka Berfikir ... .
2.3. Hipotesa ..
METODOLOGI PENELITIAN ... .
3.1. Subyek Penelitian ...
39 42
43
3.2. lnstrumen Penelitian... 45
3.3. Prosedur Penelitian... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... .. 50
3.4. Analisa Statistik... . . . . . . . . . . . . . 52
BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 55
4.1. Gamba ran Umum Responden ... 55
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian ... 57
4.3. Analisis dan lnterpretasi Hasil Penelitian... .. . .. 60
BAB 5 KESIMPULAN, DISKUSI, DAN SARAN ... 72
5.1. Kesimpulan... .. . . .. . . . .. . . .. . . . ... ... .. . . .. . . .. 72
5.2. Diskusi ... 73
5.3. Saran ... 75
Tabe14.1.1.
Tabel 4.1.2.
Tabel 4.2.1.
Tabel 4.2.2.
Tabel 4.3.1.a.
Tabel 4.3.1.b.
Tabel 4.3.1.c.
Tabel 4.3.1.d.
Tabel 4.3.2.a.
Tabel 4.3.2.b.
Tabel 4.3.3.a.
Tabel 4.3.3.b.
Tabel 4.3.4.a.
Tabel 4.3.4.b.
Tabel 4.3.5.a.
Tabel 4.3.5.b.
Gambaran Responden Berdasarkan Kampung/Asal Nagari
Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan
Gambaran Kematrilinealan
Gambaran Tipe Kemandirian
Matrilineal * Kategori Kemandirian Crosstabulation
Chi-Square Test Matrilineal * Kategori Kemandirian
Group Statistics
T-Test Matrilineal * Kemandirian
Kampung * Kategori Kemandirian Crosstabulation
Chi-Square Tests Kampung * Kategori Kemandirian
Pekerjaan * Kategori Kemandirian Crosstabulation
Chi-Square Tests Pekerjaan * Kategori Kemandirian
Kampung * Matrilineal Crosstabulation
Chi-Square Tests Kampung * Matrilineal
Pekerjaan * Matrilineal Crosstabulation
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
"Minangkabau" dapat diartikan dengan bermacam-macam pengertian, antara
lain : Adat Minangkabau, kerajaan Minangkabau, bahasa Minagkabau,
kebudayaan Minangkabau dan suku Minangkabau atau etnis Minangkabau,
dengan arti yang lebih luas dari itu. Penamaan nama Minangkabau dalam
tambo, kaba dan cerita rakyat banyak dihubungkan dengan kisah akan
keberanian dan kehebatan nenek moyang orang Minangkabau, seperti
keberhasilan mereka mengalahkan kerbau Majapahit melalui strateginya
mengadu kerbau kecil yang sudah di pasang tanduk besi dengan kerbau
besar yang dibawa pasukan Majapahit.
lnformasi ilmiah yang bisa dipercaya adalah sejarah Minangkabau dari
Joustra (dalam Amir, 1977 : 7) dalam bukunya "Minangkabau, Overzicht Van
Land, Geschiedenes en Volk", asal mula nama daeratl ini, yaitu "
Minangkabau" pun berada dalam kegelapan". Keterangan-keterangan yang
paling banyak mengandung kemungkinan kebenaran, adalah dari
"Phinangkhabu"yang berarti "tanah asal". Sedangkan perkataan lain:
"Menang Kerbau" atau ·'Mainang" yang berarti "mengembalakan kerbau" ini
adalah keterangan orang banyak saja (Amir, 1977: 7).
2
Daerah asal dari masyarakat yang berkebudayaan Minangkabau adalah
daerah propinsi Sumatra Baral sekarang ini dan sekitarnya. Luas daerah
yang didiami orang Minangkabau melebihi daerah Sumatera Baral.
Kabupaten Bengkalis, sebagian daerah Kerinci dan kabupaten di bagian
Bengkulu sebelah Utara (dari Ombak nan badabua, durian ditakuak rajo, si
Kilang Aie Bangih). Terlepas dari daerah asal ini, pendukung kebudayaan
Minangkabau juga tersebar di beberapa tempat di Sumatra dan juga di
Malaya, yaitu di Negeri Sembilan.
Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak iama dalam masyarakat
Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal
merupakan salah satu tipe sistem keturunan unilineal (rnenarik keturunan
melalui satu garis tunggal). Tipe sistem unilineal lain adalah sistem patrilineal,
seperti yang diamalkan orang Balak.
Matrilineal adalah garis keturunan, yang menelusuri garis keturunan,
perempuan (anak perempuan, anak dari anal< perempuan) (Keesing, 1975).
lemah, karena dalam sistem ini pembagian harta pusaka, sawah ladang dan
tempat tinggal, didominasi oleh perempuan. Perempuan diberi hak
menggarap atau menggunakan harta tersebut. Mamak (saudara laki-laki dari
ibu) berkewajiban menjaga harta pusaka itu dari rongrongan pihak lain dan
membagi hak penggarapan itu secara adil antara saudara perempuan atau
kemenakan perempuannya. Kekuasaan mamak pada praktiknya tidak untuk
memiliki, tetapi menjaga dan mengatur hak penggunaan atau penggarapan
harta pusaka tersebut. Sementara ia juga sebagai suami di rumah istrinya
atau ayah dari anak-anaknya.
Laki-laki sebagai suami disebut "urang sumando". Julukan urang sumando ini
berarti ia sebagai tamu di rumah istri dan anak- anaknya, tidak berkuasa
memiliki dan menentukan keputusan. la diumpamakan "abu diatas tunggul ",
mudah ditiup dan terbang. Bila terjadi perceraian, ia keluar dari rumahnya
dengan baju yang melekat di tubuhnya.
Dalam sistem matrilineal, anak-anak yang dilahirkan para ibu termasuk suku
(clan) ibunya atau suku saudara-saudara ibunya, sementara ayah termasuk
suku ibunya pula. Apabila ibu bersuku Caniago, misalnya, maka seluruh
anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan termasuk suku Caniago,
4
dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Seorang ayah berada di
luar keluarga anak dan istrinya.
Dalam artikelnya mengenai perempuan Minangkabau, J.C. Prindiville (1980)
berpendapat bahwa laki-laki boleh jadi memiliki tempat istimewa sebagai
perwakilan keluarga dan di dalam kehidupan sosial yang lebih luas sebagai
akibat status, pengaruh, dan tanggung jawab sebagai rnamak dan penghulu.
Akan tetapi laki-laki itu sendiri di dalam kelompok matrilineal isterinya hanya.
periferal dalam kewenangan.
Pendapat lain dikemukakan oleh Tanner&Thomas (1985), menurut mereka
perempuan tetap memiliki posisi kewenangan dan kekuasaan, terutama
dalam pembuatan keputusan yang vital bagi anak keturunan kaum itu.
Seperti dalam perkawinan, kematian serta pembagian harts pusaka.
Walaupun laki-laki menjadi mamak dan penghulu dikatakan sebagai
pimpinan dalam kaum, akan tetapi sesungguhnya sejauh itu terkait dengan
penggunaan tanah, rumah serta perlengkapan-perlengkapan adat termasuk
titel pemegang kewenangan yang sesungguhnya adalah terletak pada
perempuan senior dalam kaum itu. Suatu keputusan tidak dapat diambil
kecuali melalui persetujuan dan mufakat dengannya. Bila ia masih hidup
kedudukannya di alas mamak dan penghulu. Bila ia meninggal maka
Dengan cepat dan lancarnya persinggungan antar budaya yang berbeda
seperti dewasa ini, masyarakat matrilineal, termasuk Minangkabau penuh
dengan kontroversi-kontroversi struktural. Di antaranya adalah timbulnya
perebutan alegiansi (kesetiaan dan tanggung jawab) seorang laki- laki.
Kepada siapakah seorang laki- laki dewasa harus setia dan bertanggung
jawab? Kepada kelompok payung-nya (khusunya ibu, saudara perempuan
dan kemenakan- nya) atau kepada isteri dan anak- anaknya sendiri? Dalam
istilah teknis antropologi hal ini disebut perebutan alegiansi seorang laki- laki
antara keluarga matrilineal melawan keluarga batih. Secara adat, seorang
laki- laki adalah milik payungnya, karena itu dia harus bertanggung jawab dan
setia terhadap keluarga matrilineal-nya dalam segala hal. Sementara itu isteri
dan anak- anaknya mempunyai pula mamak sendiri yang akan melindungi
mereka.
Perebutan alegiansi yang paling dahsyat di Minangkabau biasanya adalah
.,...-11{\--l'v)
antara ibu\. dan isteri. Sang ibu merasa memiliki anak laki- lakinya baik secara
adat maupun secara biologis. Sebaliknya secara psikologis sang isteri dan
anak- anak juga merasa memiliki suami dan bapaknya. Namun hak
psikologis ini dinafikkan dalam adat Minangkabau. Di pihak laki- laki pun
terjadi semacam pembelahan jiwa, antara setia dan bertanggung jawab
6
Kontroversi berikutnya adalah tentang pendidikan dan rasa kasih terhadap
anak. Karena seorang laki- laki adalah milik keluarga matrilinealnya, maka dia
hanya bertanggung jawab terhadap ibu, saudara perempuan, dan
kamanakannya. Ada/ah kewajiban seorang mamak untuk mendidik dan
menyayangi kamanakan-nya. Setiap anak mempunyai mamak yang menjadi
ayah sosial-nya. Betapa gelisah dan kontroversialnya jiwa mereka ketika
dewasa, karena mereka mempunyai ayah sosial yang berbeda dari ayah
bio/ogis (Marzali, 2003).
Sebagai akibat dari perebutan alegiansi dan tidak jelasnya penanggung
jawab atas diri anak laki-laki Minang, maka mereka dikenal sebagai bangsa
perantau, bangsa pedagang.
Merantau bagi orang Minang, terutama bagi kaum prianya, mempunyai
makna tersendiri dalam arti dapat meningkatkan status dan harga diri
seseorang dalam masyarakat (kalau ia berhasil dalam perantauannya). O/eh
karena itu, merantau bagi orang Minangkabau umumnya dilatarbelakangi
oleh keinginan untuk meningkatkan harga diri atau status di berbagai bidang
kehidupan seperti bidang sosial-ekonomi, pengetahuan atau pendidikan, dan
Merantau juga dapat dilihat sebagai proses menuju kemandirian dan
kedewasaan dan sebagai kewajiban sosial yang dipikulkan ke bahu laki-laki
untuk meninggalkan kampung halamannya mencari harta kekayaan atau
menuntut ilmu pengetahuan, dan mencari pengalaman hidup (Nairn, 1979).
Sehingga dengan merantau laki-laki Minangkabau menjadi lebih mandiri
dalam berbagai hal, seperti membuat mereka mampu untuk mengatur diri
sendiri, kemandirian secara ekonomi, dapat mengambil keputusan sendiri,
terlibat dalam kegiatan di luar rumah, kemandirian dalam sikap dan tata nilai,
serta kemandirian dalam emosi, dan mereka sudah tidal< terikat lagi dengan
sistem matrilineal yang membuat mereka tidak memperoleh banyak
kesempatan dalam berbagai hal.
Dengan berlatar belakang hal tersebut diatas, dimana kita melihat bahwa
dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan
matrilineal, anak laki-lakinya tidak mempunyai hak milik di kampung, karena
semua harta pusaka diturunkan kepada anak perempuan. Dia hanya
bertugas membantu saudara perempuan atau ibu. Bahkan untuk tidurpun
harus pergi ke surau. Dalam hal penggunaan tanah, rumah, serta
perlengkapan-perlengkapan adat termasuk title pemegang kewenangan yang
berperan adalah perempuan senior dalam kaum, suatu keputusan tidak dapat
8
Di kampung baguno balun, hanya berstatus "pembantu" atau "pengurus"
harta saudara perempuan dan kemanakannya. Kalau yang sudah
berkeluarga merantau karena tidak tahan tinggal di rurnah gadang
bersama-sama dengan pambayan-pambayan (suami adik atau kakak istri yang lain)
karena mertua sering membanding-bandingkan dengan menantunya yang
lain yang banyak pambaoannya pulang untuk mertua dan anak istrinya.
Karena mereka merasa mengalami hambatan-hambatan untuk berkembang,
maka laki-laki Minangkabau menjadi lebih kreatif, diwujudkannya dengan
merantau. Merantau menjadikan orang lebih mandiri.
Dalam T riandis ( 1995) disebutkan bahwa mereka yang tidak mudah konform
pada kelompoknya dan mampu mempertahankan privasi dan otonomi
mereka, maka ekspresi dirinya tidak mudah 'diseragamkan' oleh kelompok
dan memungkinkan mereka untuk bebas mengekspresikan diri. Dalam hal ini,
penolakan yang terjadi dalam diri laki-laki Minangkabau terhadap sistem
matrilineal yang mereka anggap menghambat mereka untuk lebih
berkembang dan berbagai kontroversi-kontroversi sosiai lainnya yang
terdapat dalam sistem matrilineal ini, merupakan suatu perwujudan diri
mereka untuk lebih kreatif dan mandiri agar dapat melepaskan diri dari sistem
Secara tradisional, merantau harus dilakukan tanpa membawa modal yang
diperlukan. Mereka merantau hanya diberi bekal sehelai kain sarung dan tiket
kapal oleh kaum dan saudara ayahnya yang mau membantu. Bekal lain
hanya pandai mengaji dan seni bela diri yang dinamakan ilmu silek (silat).
Namun demikian, tradisi seperti itu sekarang sudah mulai berubah. Mamak
sudah tidak sepenuhnya bertanggung jawab, bahkan tidak lagi bertanggung
jawab. Dia sudah memperhatikan anak istrinya, "anak dipangku, kemanakan
dibimbiang". Apakah sifat kemandirian itu masih ada dengan perubahan
struktur keluarga yang makin ke patrilineal ini? Ataukah kenyataan
sebaliknya, anak laki-laki Minang sekarang lebih tergantung kepada
keluarganya karena bapak dan mamak sama-sama memperhatikan?
Berkaitan dengan itu, menarik kiranya meneliti apakah berbagai kontroversi
dalam sistem kekerabatan matrilineal ini mempunyai dampak terhadap
kemandirian laki-lakinya, karena menyebabkan orang Minang gelisah
mencari bentuk- bentuk struktur yang stabil. Sebagian menemukan struktur
tersebut dengan cara beristeri orang lain, sebagian lain dalam bentuk punya
toko besar dan kaya raya di rantau orang, adapula dalam bentuk menjadi
10
Struktur masyarakat Minangkabau yang penuh kontroversi ini adalah sebagai
akibat dari adat matrilineal Minangkabau yang berhadapan atau dipengaruhi
oleh struktur patrilineal dan pergaulannya dengan suku lain. Apakah
kontroversi struktural ini akan berimbas balik terhadap personaliti dan
temperamen manusia Minang, khususnya laki- laki Minang? Kontroversi
membuat mereka gelisah dan mencari struktur yang mapan dan stabil.
Apakah hal ini juga akan membuat laki-laki Minang menjadi lebih mandiri
atau sebaliknya makin tergantung kepada bantuan orang lain
(komunitasnya)? Laki-laki Minang yang sudah berkeluarga apakah makin
mandiri atau lebih tidak bertanggung jawab karena peran ganda sebagai
"ayah biologis" dan "ayah sosial" tersebut?
Di masyarakat matrilineal yang demikian, masyarakat atau budaya setempat
mendorong anak kemenakannya khususnya yang iaki-laki untuk mandiri,
seperti menyuruh merantau dulu. Para antropolog mengungkapkan
masyarakat matrilineal ditemukan di masyarakat primitif. Anak-anak
masyarakat primitif memang lebih cepat mandiri dari anak orang modern.
Kemandirian ini juga mendapat perhatian masyarakat maju dewasa ini.
Orang Baral dan Jepang sekarang tidak suka meninggalkan harta yang
banyak buat anaknya. Yang penting mereka tinggalkan adalah rasa percaya
1.2. ldentifikasi
Masalah
1.2.1. Pembatasan masalah
Matrilineal disini difokuskan pada pengertian matrilineal menurut Kato (1982)
dengan ciri- ciri nya sebagai berikut :
1. Keturunan dihitung berdasarkan garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu.
4. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isteri.
5. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakan
perempuannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara
perempuan.
Penelitian ini untuk membuktikan apakah sistem matrilineal berpengaruh atau
tidak terhadap kemandirian laki-laki Minangkabau. Maka subyek penelitian
laki-laki Minangkabau dibagi ke dalam 2 kelompok;
a. Matrilineal kuatltulen : apabila subyek tersebut masih menjalani semua
ciri-ciri matrilineal diatas. Dengan kata lain, subyek pada tingkat ini
adalah subyek yang dibesarkan dalam suasana matrilineal.
b. Matrilinea/ yang sudah berkurang. Subyek ini sudah tidak dibesarkan
matrilineal sepenuhnya. Subyek pada kelompok ini adalah untuk
memperoleh data kontol.
12
Subyek penelitian ini juga dibatasi pada laki-laki Minangkabau yang ada di
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alasan peneliti membatasinya adalah karena
keluarga besar UIN diasumsikan mempunyai pengetahuan agama yang lebih
dari pada yang di perguruan tinggi umum. Dengan pengetahuan agama yang
lebih akan menunjang mereka untuk lebih mengenal dan menjalankan adat
Minangkabau dengan bail<, karena orang Minang mempunyai falsafah adat
basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah.
Laki- laki Minang disini dibatasi pada laki- laki dewasa ( berumur 18 - 40
tahun/ dewasa dini ) yang telah mempunyai tanggung jawab ekonomi minimal
terhadap dirinya sendiri. Alasan peneliti memilih responden pada masa
dewasa dini karena masa dewasa dini adalah masa pencarian kemantapan
dan masa reproduktif (Hurlock, 1980 : 272), sehingga diasumsikan mereka
yang pada usia dewasa dini akan mengalami proses kemandirian yang
berarti, karena banyak tindakan dan minat yang terbawa dari masa remaja
dulu yang perlu disesuaikan dengan peran sebagai orang dewasa, sehingga
Kemandirian yang akan diteliti disini adalah kemandirian dengan
indikator-indikator sebagai berikut (berdasarkan hasi! penelitian dari Frank (1988),
serta bentuk-bentuk kemandirian yang dikemukakan oleh Douvan & Adelson
(1966) dan Hoffman (1984):
a. Pengaturan diri sendiri.
Kemandirian dapat dilihat dari kemampuan individu untuk dapat mengatur
dan mengarahkan dirinya dengan tepat serta dapat menjaga diri sendiri.
lndividu yang memiliki self govermance yang baik biasanya merasa dirinya
sudah dewasa dan cukup matang, dapat bertindak secara cepat, melakukan
sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain serta
memiliki pengaturan diri yang baik.
b. Kemandirian secara ekonomi
Merupakan kemampuan seseorang mendapatkan uang untuk menopang
kebutuhan pokoknya, memiliki pekerjaan, tidak tergantung secara finansial
dengan orang lain, dapat menghasilkan uang sendiri serta tidak menerima
bantuan dalam hal keuangan.
c. Dapat mengambil keputusan sendiri
lndividu yang mandiri digambarkan sebagai individu yang mampu mengambil
keputusan sendiri dengan baik, tidak tergantung pada orang tua atau orang
lain dalam membuat dan mengambil keputusan serta dapat menjalankan
14
d. Terlibat dalam kegiatan di luar rumah
Seorang dikatakan mandiri apabila ia telah dapat tinggal terpisah dari orang
tua atau kampung halamannya, misalnya pada waktu mereka menuntut ilmu,
ataupun bekerja di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Dalam
masyarakat Minangkabau diistilahkan dengan 'merantau'.
e. Kemandirian dalam sikap dan tata nilai
Dalam sikapnya, orang yang mandiri mampu menjadi individu yang unik yaitu
memiliki keyakinan, nilai dan pendapat sendiri.
f. Kemandirian dalam emosi
Tidak lagi membutuhkan dukungan emosi yang berlebihan dari orang tua dan
lingkungannya.
1.2.2. Perumusan masalah
• Apakah sistem matrilineal berpengaruh terhadap kernandirian laki- laki
Minangkabau?
1. 3. Tujuan
Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas tujuan yang hendak
dicapai melalui penelitian ini adalah untuk dapat melihat apakah ada
khususnya sistem kekerabatan matrilineal dengan kemandirian laki-laki
Minangkabau.
1.4. Manfaat penelitian
Mengingat begitu urgennya bahasan tersebut, peneliti berfikir penelitian ini
cukup penting untuk psikologi, dan dapat memberikan sumbangan untuk
memperkaya psikologi sosial dan lintas budaya khususnya. Untuk pendidikan
dan pembangunan masyarakat dapat diambil manfaatnya agar menciptakan
pemuda-pemuda yang mandiri. Pada sistem pendidikan, penelitian ini juga
bermanfaat sebagai wacana keilmuan untuk mengkaji tentang aspek-aspek
kemandirian dan pendidikan watak percaya diri, ulet, clan mampu
16
1.5. Sistematika penulisan
BABI
BAB II
BAB Ill
BAB IV
BABV
: Pada Bab Pendahuluan ini dikemukakan mengenai latar
belakang masalah, identifikasi masalah yang terdiri dari
pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang berisi
deskripsi garis besar penelitian ini.
: Bab Kajian Pustaka, menjelaskan kajian teori dan kerangka
berpikir dalam penelitian ini yaitu mengenai matrilineal dan
kemandirian, serta penelitian terdahulu. Dan dikemukakan pula
hipotesa dalam penelitian ini.
: Bab Metodologi penelitian, dengan sub bab yang pertama
adalah subyek penelitian, yang terdiri dari; karakteristik subyek,
populasi, jumlah subyek, dan teknik pengambilan sampel. Sub
bab berikutnya adalah instrumen penelitian, prosedur penelitian,
dan analisa statistik.
: Bab Hasil Penelitian, yang terdiri dari sub bab; gambaran
umum responden, deskripsi hasil penelitian, serta analisis dan
interpretasi hasil penelitian.
2.1. Kajian teori
2.1.1. Minangkabau
BAB2
KAJIAN PUSTAKA
Banyak pendapat yang mengemukakan asal mula narna Minangkabau,
antara lain mengatakan bahwa kata minang berasal dari nama besi runcing
yang dipasang di ujung hidung anak kerbau. Pendapat lain mengatakan
bahwa asalnya dari kata mainang kabau, yang artinya memelihara kerbau.
Nama Minangkabau yang tertua dalam catatan sejarah ditemui dalam
Nagarakertagama yang ditulis pada tahun 1365 oleh Prapanca, pujangga
Majapahit. Ven der Tuuk mengatakan asal kata Minangkabau berasal dari
kata phinang khabu yang artinya tanah asal. Dr. Muh. Hussein Nainar
mengatakan bahwa asalnya dari menon khabu yang artinya tanah mulia.
Dalam buku Sumatera Tengah, yang diterbitkan Jawatan Penerangan
Sumatera Tengah, dikemukakan juga bahwa kata itu berasal dari bahasa Sri
Lanka mau angka bahu, yang artinya memerintah. Pendapat yang terakhir
mengatakan berasal dar·i kata minanga tamwan, minanga menjadi minang,
tamwan berubah menjadi kabau. Kata itu ditemukan pada prasasti
Kedudukan Bukit (Navis, 1984: 53).
Orang Minangkabau (orang Minang) menyebut daerahnya dengan a/am
Minangkabau. Penamaan "Alam Minangkabau" menunjukkan bahwa orang
Minang sangat tergantung dengan alam. Bukti keterikatan orang Minang
dengan a lam diungkap dalam filosofi : "a/am takambang jadi guru". Alam
terkembang seperti kita tahu, bukanlah sesuatu yang liar dan tak beraturan,
tetapi sebaliknya, sangat teratur dan tunduk kepada hukum-hukum alam.
Filosofi berguru kepada alam bagi orang Minang menjadikan ia dapat
mendayagunakan hukum alam (sunnatullah) sebagai sumber belajar untuk
menata kehidupannya. Dengan masuknya Islam, maka semua ini tinggal
menyesuaikan, karena hukum alam itu ternyata adalah sunnatullah.
Ada tiga ciri utama yang selalu melekat pada etnis Minang : Pertama,
kepenganutan yang kuat terhadap Islam dengan falsafah adat basandi
Syara', Syara' basandi Kitabullah; kedua, kepatuhan tert1adap sistem
Matrilineal; ketiga, kecenderungan kuat untuk merantau (Azra, 1988).
a. Dasar budaya minangkabau
Ada enam prinsip utama adat Minangkabau yang secara tradisional dianggap
1. Yang melahirkan anak dan yang punya anak ada!ah perempuan
(ibulmande ). Prinsip ini nampaknya berlaku universal.
19
2. Yang punya kuasa dan wewenang terhadap kaurn perempuan dan
anak-anak adalah laki-laki. lni nampaknya juga merupakan prinsip yang
universal. Di rnana- rnana di dunia kita melihat kekuasaan berada di
tangan laki- laki.
3. Keturunan ditarik melalui garis perempuan. Yang dimaksud dengan
"keturunan" disini adalah sama dengan "descent" dalam bahasa
lnggris. Garis keturunan ini sering disimbolkan dengan "darah", bahwa
"keturunan" disalurkan melalui "darah". Bagi orang Minangkabau
"darah" diturunkan rnelalui ibu. Prinsip adat ini disebut dengan istilah
matrilineal. Sebenarnya, secara biologis Orang Minang rnengakui
mengalirnya "darah" bapak ke dalam tubuh anak. Pengakuan ini
dibuktikan dengan sebutan "bako" terhadap keluarga bapak. Bako
artinya asal atau benih asal. Dengan demikian bapak adalah benih asal
dari seorang anak. Narnun pengakuan ini tidak diikuti dengan
pengakuan sosial. Sehingga akhirnya orang Minang "percaya" bahwa
hanya darah ibu-lah yang mengalir ke dalarn tubuh seorang anak.
4. Anggota kelompok-keturunan (suku, payuang, paruik, dst) diangkat atau
direkrut melalui garis perempuan. Fungsi utama dari prinsip ketiga
diatas adalah untuk mendukung prinsip adat keempat ini. Pada Orang
Kalau kelompok ibunya adalah Caniago, maka anak itu otomatis
menjadi kelompok Caniago. Dia berada di luar kelompok bapaknya.
Bahkan minta pindah ke kelompok bapaknya pun tidak boleh.
5. Pewarisan harta pusaka, rumah gadang, gelar, kedudukan, dan
kekuasaan politik dilaksanakan melalui garis perempuan. lni adalah
fungsi penting kedua dari prinsip adat ketiga. Bahwa dalam kehidupan
masyarakat perlu tata tertib politik. Di Minangkabau, dengan adanya
prinsip adat ketiga, bahwa "keturunan ditarik melalui garis perempuan",
maka pewarisan tahta politik dan harta ekonomis ini-pun diselaraskan
dengan prinsip tersebut. Yang mewarisi tanah pusaka dan rumah
gadang adalah anak- anak perempuan. Yang mewarisi kedudukan dan
gelar penghulu adalah kemenakan laki- laki, atau anak saudara
perempuan.
6. Perkawinan eksogami-kelompok (eksogami suku, payuang, atau paruik)
adalah satu keharusan. lni artinya seseorang tidak boleh kawin di
dalam kelompok. Sesama anggota kelompok adalah bersaudara, atau
berdunsanak, karena darah keturunannya sama (Marzali, 2003).
Adat Minangkabau pada hakikatnya adalah ajaran budi, dan budi pekerti,
berada pada pelatihan filsafat budi (ethical philosophy), yang tujuannya
adalah untuk menata perilaku-sosial maupun individual agar sesuai dengan
kepercayaan yang bersifat theologik-eskatalogik (Ketuhanan dan alam
akhirat) yang semuanya berpuncak pada ke-Esaan dan ke-Mahakuasaan
Allah.
21
Ajaran adat yang bersifat penghalusan budi bersintesis dengan ajaran Islam
yang bersifat lebih penghalusan budi (Akhlaqul Karimah), tetapi yang
sekarang dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah SWT serta
Muhammad Rasulullah SAW panutan utama akan kehalusan budi itu. Dalam
proses pengintegrasian dan sintesis dari kedua sumber budaya ini kata
sepakat akhirnya dibuhul dengan perjanjian Bukit Marapalam, tertuang dalam
adigium:
"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (adat mesti didasarkan
pada agama, agama (Islam) berdasarkan Kitabullah (al-Qur'an).
Kata adat berasal dari bahasa Sangsekerta, dibentuk dari kata "a" dan "data".
"Dato" artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. Jadi "adal" pada hakikatnya
adalah segala sesuatu yang bersifat tidak kebendaan (Salmadanis dan
Samad, 2003 : 25).
Bukti kuatnya penyesuaian adat dan syarak itu adalah adanya pusaka tinggi
beberapa kasus tertentu menurut sepanjang adat, menurut aturan adat
Minangkabau jatuhnya kepada kemanakan. Begitu pula halnya ada pusaka
rendah, yaitu hasil usaha yang dilakukan oleh satu keluarga boleh dimiliki
oleh anak-anaknya sesuai menurut hukum Islam.
Dengan status dan hirarkinya yang demikian maka secara prinsip tidak
mungkin ada benturan antara adat dan syarak, yang di atasnya adalah
al-Qur'an kalimatul 'u/ya. Maka al-Qur'an dengan sendirinya adalah konstitusi
tertinggi bagi budaya dan masyarakat adat Minangkabau.
b. Sistem kekerabatan matrilineal
Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama dalam masyarakat
Minangkabau adalah sistem kekerabatan matri!ineal yang mengatur garis
keturunan menurut garis keturunan ibu atau wanita. Dalam budaya
Minangkabau yang matrilineal ini, laki-laki tidak memiliki harta pusaka berupa
tanah, sawah dan rumah.
Sistem matrilineal merupakan satu di antara dua tipe sistem keturunan
unilineal (menarik keturunan melalui satu garis tunggal). Tipe sistem unilineal
lain adalah sistem patrilineal, seperti yang diamalkan orang Balak. Patrilineal,
yaitu mengikuti nasab atau keturunan sebelah Bapak. Oleh karena itu, hanya
http://www.mandailing.org/kek-ren5.html). Dalam sistem kekerabatan
patrilineal, suatu kelompok kekerabatan dihitung dengan dasar satu ayah,
satu kakek atau satu nenek moyang. Dengan demikian setiap anak dalam
suatu keluarga akan mengikuti dan memakai marga ayahnya, tetapi yang
berhak untuk meneruskan marga ayahnya hanya anak laki-laki saja
sedangkan anak perempuan akan kehilangan marganya jika ia sudah
menikah dengan seorang laki-laki dari marga lain.
Garis keturunan matrilineal ini mempengaruhi ruang lingkup yang lebih luas
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak hanya
sekedar mengambil garis keturunan dari ibu, tetapi lebih luas dari itu
matrilineal merupakan suatu sistem kemasyarakatan yang mendasari
berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti aspek sosial,
politik, ekonomi, dan hukum (Hakimy, 1978; Saanin, 1982).
Kato ( 1982) mengemukakan ciri-ciri masyarakat matrilineal yang tidak hanya
tentang garis keturunan, sebagai berikut :
1. Keturunan dihitung berdasarkan garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu.
5. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari
saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.
Ada empat aspek penting yang diatur dalam sistem matrilineal, yaitu:
a. Pengaturan harta pusaka.
Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut harato jo pusako.
Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun, baik yang
tampak ujud secara material, seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak,
dan sebagainya, maupun yang tidak tampak seperti gelar penghulu, atau
tuah. Sedangkan harato dimaksudkan adalah segala hasil yang diperoleh
dari tanah, sawah milik kaum. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula
dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; sako dan pusako.
1. Sako
Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal
yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah
dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Sako merupakan
hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan
kepada perempuan.
2. Pusako
Pusako adalah milik kaum secara turun temurun, berbentuk material seperti
sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. Pusako dimanfaatkan oleh
25
perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat
tinggalnya. Laki-Jaki berhak mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki.
Karena itu di Minangkabau kata hak milik bukanlah merupakan kata kembar
yang satu makna, tetapi dua kata yang satu sama lain artinya berbeda
namun tetap berada dalam konteks yang sama. Laki-/aki punya hak terhadap
pusako kaum, tetapi dia bukan pemilik pusako kaumnya.
Dalam pengaturan pewarisan pusako, semua harta yang akan diwariskan
harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan harta pusaka itu terbagi
dalam pusako tinggi dan pusako randah (pusaka rendah).
Pusako tinggi adalah harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun
temurun berdasarkan garis ibu. Pusaka tinggi hanya boleh digadaikan bi/a
keadaan sangat mendesak sekali, hanya untuk empat ha/ saja; pertama, jika
mayat terbujur di tengah rumah; kedua, jika ada gadis 'gadang' (yang telah
melewati umur) be/um menikah; ketiga, rumah gadang ketirisan; keempat,
jika penghulu yhendak ditegakkan . Menjual-menggadai dalam ha/-hal itupun
baru bisa dilakukan jika tak ada lagi jalan Jain untuk menutupinya dan jika
Pusako randah (Pusaka rendah) yaitu harta pencaharian yang didapat oleh
suami isteri selama masa perkawinannya. Pusako randah diwariskan
mengikuti hukum pewaris dalam Islam, atau mengikuti hukum faraidh.
b. Peranan laki-laki.
Pola kekerabatan matrilineal dengan sendirinya menempatkan laki-laki
Minangkabau pada posisi yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya.
Laki-laki Minangkabau memiliki kekuasaan tertentu dalam sukunya. la
terutama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kemenakannya. Bila
rumah gadang rusak, atau ada kemenakan yang belurn menikah, maka
mamak bertanggung jawab untuk mengatasinya.
Laki-laki Minangkabau memiliki dua peran dalam kehidupan rumah tangga,
pertama sebagai mamak dalam rumah ibunya dan sebagai urang sumando
dalam rumah istrinya. Peran sebagai mamak dalam rumah ibu pada
hakekatnya bertumpang tindih dengan peran perempuan sebagai bundo.
Keduanya lambang kebijaksanaan, kekuatan, kestabilan, tanggung jawab
dan pengayoman (Prindville dalam Syarifuddin, 1984).
Walaupun mamak tidak tinggal dalam keluarga ibunya, namun kehadirannya
dalam keluarga ibunya selalu dituntut oleh adat. Disanalah ia menghabiskan
mempunyai hubungan yang rapat dan dengan mamaknya. Syarifudin
mengemukakan bahwa mereka lebih membutuhkan mamaknya itu di
samping ibunya.
27
Dari hasil penelitian (Hamdi, 1990) serta berdasarkan uraian dari Amir B dkk
(1984) dapat diketahui peran mamak sebagai berikut:
1. Mengatur perkawinan kemenakan
Dalam hal ini ayah si gadis tetap diajak berunding, tetapi keputusan tetap di
tangan mamak.
2. Mengatur penggunaan dan pembagian pusaka
Menurut adat Minangkabau kemenakanlah yang mewarisi gelar, martabat
dan kekayaan yang dipunyai oleh mamak. Sebagai warisan harta pusaka
yang ditinggalkan oleh pewaris tidak boleh di bagi-bagi oleh yang berhak.
Harta yang telah jadi pusaka harus dijaga agar tinggal utuh demi menjaga
keutuhan kaum kerabat. Pada gilirannya akan diturunkan kepada
kemenakan. Kemenakan laki-laki memiliki hak untuk mengelola sedangkan
kemenakan perempuan berhak memiliki. Kemenakan laki-laki harus
mengusahakan agar harta pusaka tersebut menghasilkan dan mampu
menghidupi kaum kerabat yang ada di rumah gadang, serta tidak boleh di
bawa ke rumah isteri.
Kewajiban seorang mamak terhadap kemenakannya, terutama yang
perempuan adalah memberi makan, pakaian, perumahan dan lain-lain.
Bisaanya dengan memberikan sebidang tanah atau bagian dari harta pusaka
untuk diusahakan dan dikelola oleh kemenakan.
4. Mengatur, membimbing, mengawasi dan melindungi kemenakan
Terhadap kemenakan perempuan diberikan bimbingan agar ia memahami
nlai-nilai sosial yang menempatkan perempuan sebagai sentral di rumah.
Sedangkan pada kemenakan laki-laki bimbingan diberikan sebagai persiapan
untuk menjadi penunjang dan pengembang sanak saudaranya.
Peran orang laki-laki sebagai urang sumando dalam rumah istrinya adalah
lemah sekali. Pepatah Minangkabau mengatakan posisi laki-laki sebagai
urang sumando tersebut ibarat rabuak di ateh tunggue (rabuak adalah bagian
dari pohon ijuk yang mudah diterbangkan oleh angin).
Ada! yang seperti ini menempatkan laki-laki pada posisi yang serba salah. Di
rumah ibunya ia tidak mempunyai hak alas rumah itu, dan di rumah istrinya ia
hanya tamu yang menompang (Syarifuddin, 1984).
Seorang laki-laki Minangkabau harus menjalankan peran sebagai ayah dari
anak-anaknya, sekaligus bertanggung jawab untuk membimbing
29
c. Kaum dan pesukuan.
Orang Minangkabau yang berasal dari satu keturunan dalam garis matrilineal
merupakan anggota kaum dari keturunan/klen tersebut. Sasuku maksudnya
adalah berasal dari keturunan yang sama sejak dari nenek moyangnya. Suku
artinya seperempat atau kaki. Jadi, pengertian sasuku dalam sebuah nagari
adalah seperempat dari penduduk nagari tersebut.
Sebuah kaum mempunyai keleikaitan dengan suku-suku lainnya, terutama
disebabkan oleh perkawinan. Oleh karena itu kaum punya struktur yang
umumnya dipakai oleh setiap suku.
Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat,
pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapl<an pepatah adatnya
amban puruak atau tempat penyimpanan.
Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah
prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban
perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam
kondisi bagaimanapun. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan,
sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya.
Di dalam sistem matrilineal, perempuan juga mempunyai fungsi dan
kedudukan yang spesifik, yaitu sebagai:
1. Bunda Kanduang
Apabila ibu atau tingkatan ibu dari mamak yang jadi penghulu masih hidup,
maka dialah yang disebut Bunda Kanduang, atau mandeh atau niniek. Dialah
perempuan utama dalam kaum itu. Dia punya kekuasaan lebih tinggi dari
searang penghulu karena dia setingkat ibu, atau ibu penghulu itu betul.
2. Perempuan bisaa yang sudah kawin
Mereka adalah bagian dari kepemilikan pusaka. Mereka diatur aleh
tungganai, mamak laki-laki yang ditugaskan mengatur untuk setiap rumah
gadang. Dari mereka inilah nanti akan dapat ditentukan siapa yang akan
dijadikan perempuan utama berdasarkan; wibawa, kecakapan, dan
kebijaksanaan yang dimilikinya.
Perlu pula diperhatikan struktur suku di dalam suatu kaum dan strukturnya
bersama dengan suku lain. Struktur suku dalam suatu kaum diungkap i
Fulan sebagai berikut:
a) Mamak yang dipercaya sebagai pimpinan kaum yang disebut Penghulu
bergelar datuk.
b) Mamak-mamak di bawah penghulu yang dipercayai memimpin setiap
rumah gadang, karena di dalam satu kaum kemungkinan rumah gadangnya
31
tungganai. Seorang laki-laki yang memikul tugas sebagai tungganai rumah,
pada beberapa suku tertentu, mereka juga diberi gelar datuk. Di bawah
tungganai ada laki-laki dewasa yang telah kawin juga, berstatus sebagai
mamak bisaa. Di bawah mamak inilah baru ada kemenakan.
c. Kecenderungan merantau
Nairn dalam studinya tentang Merantau, mengungkap faktor-faktor yang
mendorong laki-laki Minangkabau lebih suka merantau dari pada tinggal di
kampung. Faktor itu antara lain adalah:
1. Struktur sosial di Minangkabau yang matrilineal ticiak cukup memberi
tempat yang kokoh bagi laki-laki dalam kehidupan l<eluarga, dalam arti
bahwa dia tidak mempunyai kekuasaan yang mantap di rumah isterinya
dan tidak pula di rumah ibunya sendiri. la oleh karena itu merasa
terombang-ambing, kurang terjamin dan selalu gelisah.
2. Dengan sistem kekerabatan keluarga besar (extended family sistem)
seperti yang ditemukan dalam masyarakat matrilineal tersebut, suami
dan isteri masing-masingnya tetap merupakan bahagian dari keluarga
induk masing-masing. Dorongan merantau dilihat sebagai usaha untuk
melepaskan diri dari keluarga induk untuk dapat membangun keluarga
batih sendiri yang terhindar dari berbagai intervensi keluarga besar.
3. Laki-laki walaupun terhitung sebagai anggota keluarga di rumah ibunya,
sawah keluarga untuk dibawa hasilnya ke rumah anaknya, kecuali jika
seizin saudara-saudara perempuannya. Sebaliknya, dari tugas dan
tanggung jawabnya, malah dia di dorong untuk memperbanyak tanah
yang ada dari hasil yang diperdapat di rantau. Keluarganya, dan malah
dia sendiri, merasa telah memenuhi panggilan jika dapat berkirim pulang
untuk membeli atau memagang sawah baru.
4. Tanggungjawab ganda yang dia pikul (baik sebagai bapak terhadap
anaknya, sebagai mamak terhadap kemenakannya, sebagai saudara
laki-laki terhadap saudara-saudara perempuannya, maupun sebagai
anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat kampungnya)
mungkin dirasa terlalu berat untuk dihadapi secara sekaligus. Karenanya
dia cenderung untuk mengelakkan dan malah melepaskan tanggung
jawabnya itu. Ada semacam perasaan 'terlalu dibebani' untuk hidup di
kampung, sedang sementara itu dia tahu bahwa di kampung tak banyak
yang bisa dilakukan untuk penyambung hidupnya.
5. Ketidaktergantungan mereka kepada tanah juga menimbulkan sikap
menilai rendah terhadap kehidupan bertani. Masyarakat sebaliknya
melihat ke atas kepada orang dagang dan orang-orang lainnya yang
banyak merantau, apalagi kalau mereka mampu memperlihatkan hasil
jerih payah di rantau. Tantangan untuk merantau oleh karena itu tinggi
33
6. Anak laki-laki telah di dorong untuk meninggalkan rumah sejak dari umur
muda. Di rumah dia tidak diberi akomodasi setimpal seperti kepada anak
perempuan. Dia disuruh tidur di surau, atau di rumah pembujangan, dan
belajar mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang sukar di
kemudian hari. Dorongan untuk pergi merantau oleh karena itu disiapkan
secara berangsur-angsur sejak dari umur muda. lnstitusi merantau oleh
karena itu adalah bahagian yang tak terpisahkan dari lembaga
kehidupan secara menyeluruh (Nairn, 1979: 279-280).
2.1.2. Kemandirian
Berdasarkan tata bahasa Indonesia diketahui bahwa pembentukan kata
kemandirian berasal dari kata sifat mandiri yang berarti dalam keadaan dapat
berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. (Kamus Besar bahasa
Indonesia, 1990 : 55).
Kemandirian adalah "the ability to be self directive rather than dependent on
others for control" (Hurlock, 1974).
Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa kemandirian merupakan
suatu kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dan tidak bergantung pada
Dalam penelitian ini istilah kemandirian merujuk pada istilah autonomy dan
independence. Autonomy shows itself in independence (Hurlock 197 4: 49).
lndividu yang otonom adalah individu yang mandiri, tidak mengandalkan
bantuan dan dukungan dari orang lain yang kompeten. la juga bebas
bertindak. Orang yang mandiri lebih bergantung pada potensi serta sumber
daya diri sendiri dari pada bergantung pada lingkungan fisik dan sosialnya.
Dorongan otonom juga merujuk kepada adanya kecenderungan individu
untuk berusaha agar ia dapat menguasai lingkungannya. (Maslow dan
Angyal, dalam Hjelle & Ziegler, 1981: 390)
Penelitian mengenai kemandirian pada kelompok dewasa muda
mengemukakan bahwa batasan mengenai kemandirian berhubungan clengan
kemandirian dalam aspek interpersonal dan intrapsikis (Frank, Laman dan
Avery, 1988). Menurut Frank dkk, kemandirian berkaitan dengan:
a. Kemampuan atau kompetensi untuk berhubungan dengan lingkungan luar.
b. Kemampuan untuk menguasai konflik intrapsikis.
c. Kemampuan untuk memisahkan diri dari significant others.
Solomon Asch mengemukakan ciri-ciri orang yang mandiri sebagai berikut:
0
Independent tend to be self-reliant, persuasive, expressive and
35
submissive, conventional, easily upset by stress, and suggestible, and lack of
insight into their own motives and antitudes" (Asch, 1952 : 212).
Selain itu kemandirian juga diartikan sebagai: an attitude of self reliance or
self resistence to control by others, yang berarti dapat mengandalkan diri
sendiri dan tidak bersedia untuk dikontrol oleh orang lain (English dan
English, 1959). Sedangkan Rokeach dalam pembagian nilainya menyebut
kemandirian sebagai 0
Self reliance atau independence".
Berdasarkan tata bahasa Indonesia diketahui bahwa pembentukan kata
kemandirian berasal dari kata sifat mandiri yang berarti dalam keadaan dapat
berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. (Kamus Besar bahasa
Indonesia, 1990: 55).
Kemandirian, oleh para ahli juga dijadikan suatu kriteria tertentu, yaitu kriteria
kedewasaan. McCandless & Coop mengemukakan adanya
ketidaktergantungan secara ekonomi (economic independence) untuk
mendefinisikan kedewasaan. Artinya, orang dewasa dapat menopang dirinya
sendiri dalam hal keuangan (McCandless & Coop, 1979, dalam Smolak,
Hoffman 1984 (dalam Moore, 1987; Smolak 1993) menjelaskan kemandirian
sebagai ketidaktergantungan (independence). Ada 4 (empat) bentuk
ketidaktergantungan (independence) yaitu :
1. Ketidaktergantungan secara fungsional (Functional Independence).
2. Ketidaktergantungan dalam sikap (Attitudinal Independence).
3. Ketidaktergantungan dalam hal emosi (Emotional Independence).
4. Ketidaktergantungan konfliktual (Conflictual Independence).
Kemandirian memiliki beberapa aspek yaitu:
1. Aspek ketidaktergantungan (Independence).
2. Aspek pengambilan keputusan (Desicion Making).
3. Kontrol diri (Personal cッョエイ。セN@
4. Aspek pernyataan diri (Self Assertion).
5. Self Other Responsibility.
(Frank, 1979, dalam Smolak, 1993).
Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa kemandirian adalah tingkah laku di
mana individu dapat mengandalkan dan bergantung pada dirinya sendiri dan
bebas dalam membuat keputusan dalam dirinya tanpa menimbulkan
37
lndikator kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil
penelitian dari Frank (1988), serta bentuk-bentuk kemandirian yang
dikemukakan oleh Douvan & Adelson (1966) dan Hoffman (1984), yang
dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah kedewasaan yang mnecakup :
a. Pengaturan diri sendiri.
Kemandirian dapat dilihat dari kemampuan individu untuk dapat mengatur
dan mengarahkan dirinya dengan tepat serta dapat menjaga diri sendiri.
lndividu yang memiliki self govermance yang baik bisaanya merasa dirinya
sudah dewasa dan cukup matang, dapat bertindak secara cepat, melakukan
sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain serta
memiliki pengaturan diri yang baik.
b. Kemandirian secara ekonomi
Merupakan kemampuan seseorang mendapatkan uang untuk menopang
kebutuhan pokoknya, memiliki pekerjaan, tidak tergantung secara finansial
dengan orang lain, dapat menghasilkan uang sendiri serta tidak menerima
bantuan dalam hal keuangan.
c. Dapat mengambil keputusan sendiri
lndividu yang mandiri digambarkan sebagai individu yang mampu mengambil
keputusan sendiri dengan baik, tidak tergantung pada orang tua atau orang
lain dalam membuat dan mengambil keputusan serta dapat menjalankan
d. Terlibat dalam kegiatan di luar rumah
Seorang dikatakan mandiri apabila ia telah dapat tinggal terpisah dari orang
tua atau kampung halamannya, misalnya pada waktu mereka menuntut ilmu,
ataupun bekerja di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Dalam
masyarakat Minangkabau diistilahkan dengan 'merantau'.
e. Kemandirian dalam sikap dan tata nilai
Dalam sikapnya, orang yang mandiri mampu menjadi individu yang unik yaitu
memiliki keyakinan, nilai dan pendapat sendiri.
f. Kemandirian dalam emosi
Tidak lagi membutuhkan dukungan emosi yang berlebihan dari orang tua dan
lingkungannya.
2.1.3. Penelitian terdahulu
Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh
Nurkesuma (Skripsi Fakultas Psikologi Depok, 1995) yang berjudul Nilai
Kemandirian dalam Pola Kekerabatan Matrilineal dan ldentitas Sosial
Perempuan Minangkabau. Hasil penelitiannya ia!ah bahwa: 0
Nilai
kemandirian dapat digunakan sebagai peramal terhadap identitas sosial dan
sebaliknya identitas sosial dapat dijadikan sebagai peramal bagi
kemandirian". Pada penelitian ini identitas sosial tersebut adalah sistem
39
matrilineal dan akan dilihat apakah ada pengaruhnya terhadap kemandirian
laki-laki Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan tersebut.
Disamping temuan bahwa nilai kemandirian dapat digunakan sebagai
peramal terhadap identitas sosial dan sebaliknya, dalam skripsi ini juga
terdapat temuan lain, yaitu : bahwa tidak ada perbedaan nilai kemandirian
antara lbu dan anak perempuannya di Minangkabau sebagai generasi yang
berbeda. Kemudian juga dikatakan bahwa tidak ada perbedaan identitas
sosial antara lbu dan anak perempuannya sebagai generasi yang berbeda.
Sedangkan penelitian ini adalah tentang hubungan sifat kemandirian dengan
sistem kekerabatan matrilineal pada laki-laki Minangkabau. Maka tujuan dan
subyek penelitiannya berbeda sehingga bisa menjadi penyempurnaan dari
penelitian terdahulu.
2.2. Kerangka Berpikir
2.2.1. Sistem kekerabatan dan kemandirian laki-iaki Minangkabau
Berbicara kehidupan manusia sebagai individu tidak akan pernah keluar dari
kerangka pembicaraan mengenai kepribadian, konsep diri dan budaya
diri saling mempengaruhi satu sama lain sekaligus, dan dengan tujuan akhir
bekerja integratif membentuk individu yang utuh (Dayakisni dan Yuniardi,
2003). Skripsi ini meneliti tentang pengaruh budaya pada masyarakat
Minangkabau terhadap kemandirian, yaitu pengaruh sistem kekerabatan
matrilineal terhadap kemandirian laki-Jaki Minangkabau.
Kelompok kekerabatan dapat menjadi pedoman bagi hubungan-hubungan
sosial dimana seseorang terlibat di dalamnya. Hubungan sosial yang
terwujud antara seseorang dengan orang lain dibatasi oleh unsur-unsur
seperti kedudukan jenis kelamin, umur, dan hubungan kekerabatan. Menurut
Keesing hubungan kekerabatan mengacu kepada hubungan antara orang tua
dan anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-iaki, dan pada
jaringan-jaringan hubungan yang terbentuk dari hubungan orang tua dan
anak-anak tersebut (Keesing, 1975).
Sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat Minangkabau adalah
sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi salah satu identitas budaya
masyarakat Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau yang matrilineal ini,
laki-laki tidak memiliki harta pusaka berupa tanah, sawah dan rumah.
Ditinjau dari aspek psikologis, sistem matrilineal juga mempengaruhi laki-laki
41
kepemilikan harta di kampungnya, dia juga hanya sebagai 'urang sumando'
di rumah istrinya sehingga ia tidak dapat memimpin keluarganya secara
langsung, karena dalam sistem matrilineal laki-laki Minangkabau
bertanggung jawab terhadap keluarga matrilialnya, yaitu sebagai mamak
pada kemenakan-kemenakannya. Selain itu, laki-laki Minangkabau juga tidak
mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan yang
vital bagi anak keturunan dalam kaum. Seperti dalam perkawinan, kematian
serta pembagian harta pusaka. Walaupun laki-laki menjadi mamak dan
penghulu dikatakan sebagai pimpinan dalam kaum, akan tetapi
sesungguhnya sejauh itu terkait dengan penggunaan tanah, rumah serta
perlengkapan-perlengkapan adat termasuk titel pemegang kewenangan yang
sesungguhnya adalah terletak pada perempuan senior dalam kaum itu. Suatu
keputusan tidak dapat diambi! kecuali melalui persetujuan dan mufakat
dengannya.
Hal ini juga merupakan salah satu sebab laki-laki Minangkabau mempunyai
kecenderungan untuk merantau agar menemukan poia kehidupan yang dia
inginkan, dimana ia dapat mengatur dan mengarahkan dirinya dan
keluarganya dengan tepat, tidak tergantung kepada orang lain baik dari segi
ekonomi maupun dalam mengambil keputusan, dan dapat membebaskan
dirinya dari sistem matrilineal yang secara tidak langsung menimbulkan
sehingga mereka mewujudkannya dengan merantau yang membuat mereka
bisa menjadi lebih kreatif dan mandiri.
2.3.
Hipotesa
Dalam penelitian ini dimunculkan hipotesa yang nantinya akan dibuktikan
melalui penelitian yang akan dilakukan, berdasarkan dengan apa yang telah
dirumuskan sebelumnya dalam permasalahan penelitian;
- Hipotesa alternatif (Ha) : Ada pengaruh sistem matrilineal terhadap
kemandirian laki-laki Minangkabau.
- Hipotesa nihil (Ho) : Tidal< ada pengaruh sistem matrilineal terhadap
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Subyek Penelitian
3.1.1. Karakteristik subjek
Subyek pada penelitian ini adalah laki-laki yang berasal dari suku
Minangkabau, dengan karakteristik sebagai berikut:
a. Subyek minimal tel ah tinggal di daerah Minangkabau selama 1 O tahun
(dibesarkan dalam lingkungan yang matrilineal).
b. Sedang atau pernah menjalani pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, karena mereka diasumsikan mempunyai pengetahuan agama
yang lebih dari pada yang di perguruan tinggi umum. Dengan
pengetahuan agama yang lebih akan menunjang mereka untuk lebih
mengenal dan menjalankan adat Minangkabau dengan baik, karena
orang Minang mempunyai falsafah adat basandi Syara', Syara' basandi
Kitabullah.
c. Berumur
18-
40 tahun/ dewasa dini, yang telah mempunyai tanggungjawab ekonomi minimal terhadap diri sendiri.
d. Mengisi skala dan memenuhi syarat matrilineal.
3.1.2. Populasi
Berdasarkan data yang didapat dari Komunitas Mahasiswa Minangkbau
(KMM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa laki-laki Minangkabau
(matrilineal) yang sedang dan pernah menjalani pendidikan di UIN Syarif
Hidayatullah dan berusia 18-40 tahun sekitar lebih kurang 300 orang.
3.1.3. Jumlah Subyek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. Terdiri dari 30 orang untuk
penelitian tahap pertama (uji coba skala), dan 40 orang untuk penelitian
tahap kedua. Diharapkan dari 40 orang ini mencakup ke dalam matrilineal
tulen dan matrilineal yang sudah berkurang/terpengaruh oleh sistem lain
sebagai data kontrol.
44
Guilford dan Frunchter (1978) menyatakan bahwa, jurnlah sampel minimal
untuk melakukan penelitian yang baik adalah 30 orang agar hasilnya dapat
dianalisis secara statistik dengan menggunakan asumsi distribusi normal.
Oleh karena itu jika jumlah sampel yang diharapkan tidak terpenuhi, maka
jumlah minimal setidaknya harus tercapai.
3.1.4. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan (purposive sampling) dapat
diambil sebagai subyek penelitian, dan diambil yang paling mudah ditemui
atau paling bersedia (incindental sampling), sampai jumlahnya mencapai
batas yang diperlukan (Guilford & Fruchter, 1981 ).
Teknik ini digunakan karena memiliki kelebihan, yaitu pengambilan sampel
menjadi praktis, mudah dan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat,
dengan catatan bahwa subyek bersedia untuk menjadi sampel dengan tidak
mengabaikan cirri-ciri/ karakteristik subyek penelitian, sehingga dapat
mengurangi bias.
Dalam penelitian ini yang menjadi independent variabel adalah sistem
matrilineaL Sedangkan dependent variabelnya adalah kemandirian.
3.2. lnstrumen
Penelitian
lnstrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini a