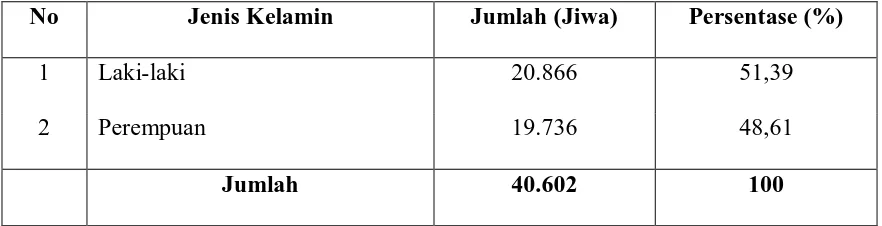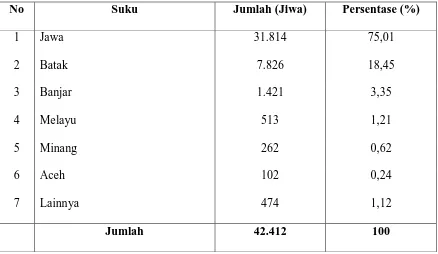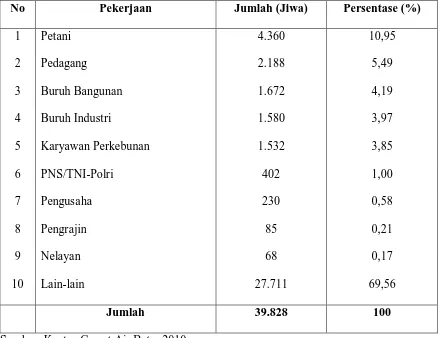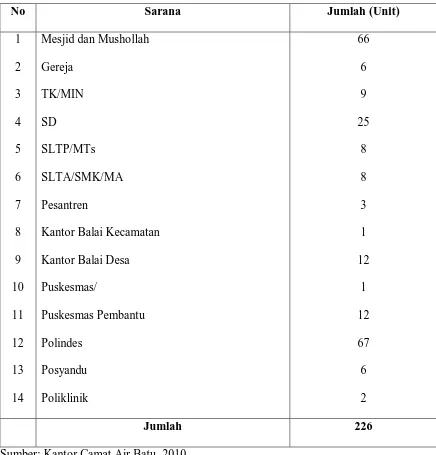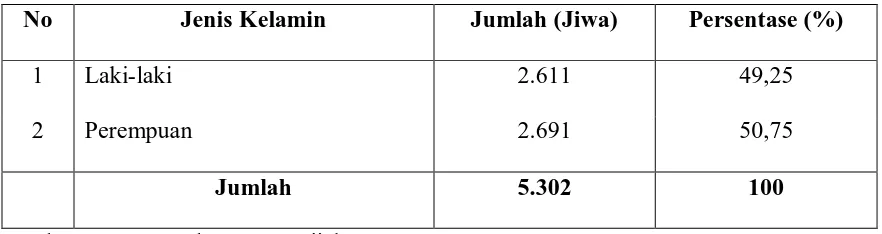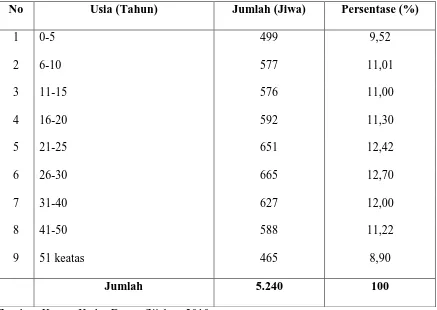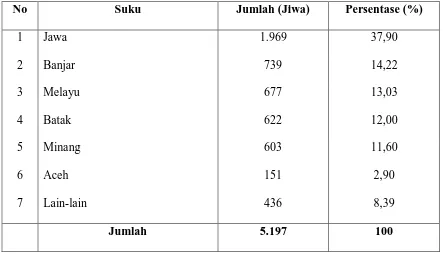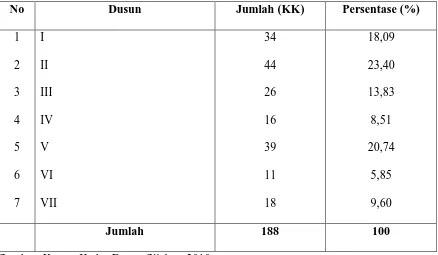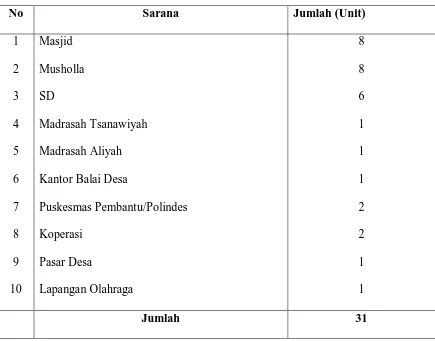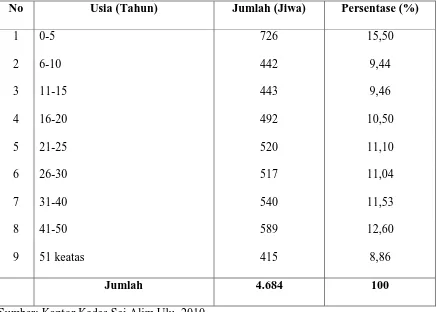IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA
BIDANG PETERNAKAN BINAAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN ASAHAN DI KECAMATAN
AIR BATU KABUPATEN ASAHAN
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi
Syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial
Oleh:
HALIM MURDANI NIM : 060902060
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Halim Murdani, 060902060, Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
(Skripsi ini berisi 6 bab, 94 Halaman, 1 Gambar, 39 Tabel, 23 Kepustakaan dan Lampiran)
ABSTRAK
Dinas Sosial Kabupaten Asahan berusaha untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui program KUBE. Bantuan berupa penguatan dana usaha dalam bentuk dana bergulir, tiap KUBE terdiri 10 anggota. Usaha yang ditempatkan di Kecamatan Air Batu oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan melalui pihak pendamping kecamatan dalam bentuk usaha peternakan kambing dan masing-masing anggota KUBE mendapat dua ekor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program KUBE Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga penerima program KUBE Bidang Peternakan binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air berjumlah 60 Kepala Keluarga. Analisis data dilakukan dengan editing, koding, membuat kategori dan menghitung frekuensi data.
Hasil penelitian menunjukkan 42 responden (70%) menyatakan bahwa dengan adanya program ini pendapatan responden tetap, 48 responden (66,70%) menyatakan program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, 60 responden (100%) menyatakan program ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berusaha dan 10 responden (16,70%) menyatakan bahwa program ini dapat mengembangkan usahanya. Hasil yang dicapai dalam program ini berupa pendapatan responden yang tetap disebabkan hewan ternak masih dalam tahap perkembangbiakan sehingga belum dapat memberikan hasil yang maksimal berupa peningkatan pendapatan. Adanya program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta kemampuan berusaha masyarakat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan oleh :
Nama : Halim Murdani
NIM : 060902060
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA
BIDANG PETERNAKAN BINAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN DI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN
Medan, 11 Januari 2011
Pembimbing Skripsi
Hairani Siregar, S.Sos, MSP NIP. 19710927 199801 2 001
Ketua Departemen
Hairani Siregar, S.Sos, MSP NIP. 19710927 199801 2 001
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini telah dipertahankan didepan panitia penguji skripsi Departemen Ilmu
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2011 Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang FISIP USU
Tim Penguji
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW sehingga skripsi yang berjudul:
Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Skripsi
ini telah selesai disusun untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai salah satu syarat
untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan,
dan saran-saran dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan
ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang
telah membantu dan memberi dukungan serta bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Hairani, S.Sos, MSP. selaku Dosen Pembimbing skripsi dan Ketua
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian
secara ikhlas untuk membimbing serta mengarahkan penulis dari persiapan
hingga penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Syafruddin Harahap, M.Si selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa
4. Bapak Drs. Poniman, M.AP. selaku Camat Kecamatan Air Batu beserta
jajarannya, Bapak Mustapa, SH, Ibu Netti Herawati, SH, Bapak Zainal, Kakanda
Dwi Pratiwi dan lain-lainnya yang telah membantu penulis dalam penelitian untuk
bahan skripsi di Kecamatan Air Batu.
5. Bapak Sutan Horas Pane selaku Kepala Desa Danau Sijabut beserta jajarannya,
Abangda Zainal Arif Sitorus, Kakanda Asnidaniar dan lain-lainnya yang telah
membantu penulis dalam penelitian untuk bahan skripsi di Desa Danau Sijabut.
6. Bapak Zuprijal Lubis selaku Kepala Desa Sei Alim Ulu beserta jajarannya yang
telah membantu penulis dalam penelitian untuk bahan skripsi di Desa Sei Alim
Ulu.
7. Kedua orang tua tercinta, Muhammad Kardi dan Nur’aini Sitorus yang telah
banyak memberikan nasehat, motivasi, do’a dan kasih sayang kepada penulis.
Juga kepada saudara tersayang Hilda Sari Affianti, SKG, Dian Harisa Afiliani dan
Sri Wardani yang selalu siap sedia untuk memberikan bantuan dan semangat
kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan memperoleh sarjana yang
berguna bagi keluarga khususnya. Terima kasih saya ucapkan buat keluarga besar
saya yang telah turut mendo’akan saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah
Departemen Ilmu Kesejahteran Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara di Medan.
8. Sahabat-sahabat terbaik penulis Pandu, Rozi, Beni, Win, Feri, Erwin, Manuel,
Edo, Ari, Nanta, Mantho, Hammad, Anwar, Ade, Bobi, Mustaqim serta semua
9. Bapak-bapak dan sahabat-sahabat yang sebagai penjaga keamanan kendaraan di
parkiran. Pak Naryo, Pak Lundu, Sukron, Lakso dan Abdul.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dalam
penyusunan skripsi ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang
dimiliki penulis. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan
skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
fakultas, pengembangan ilmu dan masyarakat.
Medan, Januari 2011
Penulis
DAFTAR ISI
1.4. Sistematika Penulisan ... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 11
2.1. Pengertian Implementasi ... 11
2.2. Pengertian Program ... 16
2.3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ... 17
2.3.1. Tujuan Penumbuhan KUBE ... 17
2.3.2. Langkah atau Kegiatan Pokok Pembentukan KUBE 18 2.3.3. Kepengurusan KUBE ... 19
2.3.4. Administrasi KUBE... 19
2.4. Peternakan ... 20
2.4.1. Tujuan Peternakan ... 21
2.5. Kemiskinan ... 22
2.5.1. Indikator Kemiskinan di Indonesia ... 22
2.5.2. Dimensi Kemiskinan di Indonesia ... 24
2.5.3. Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan ... 27
2.6. Kesejahteraan Sosial ... 28
2.6.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial ... 28
2.6.2. Pendekatan ... 30
2.7. Kerangka Pemikiran ... 33
2.8. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional ... 35
2.8.2. Defenisi Operasional ... 36
4.5.2. Kondisi Demografis... 47
4.5.3. Kondisi Sosial Ekonomi ... 52
4.5.4. Pertanian, Perikanan dan PemanfaatanLahan ... 53
4.5.5. Sarana ... 53
4.6. Desa Sei Alim Ulu ... 55
4.6.1. Deskripsi Wilayah ... 55
4.6.2. Kondisi Demografis... 55
4.6.3. Kondisi Sosial Ekonomi ... 59
4.6.4. Pertanian, Perikanan dan Pemanfaatan Lahan ... 60
4.6.5. Sarana ... 60
BAB V ANALISA DATA ... 62
5.1. Karakteristik Responden ... 62
5.1.1. Distribusi Responden Berdasarkan Agama ... 64
5.1.2. Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Pendapatan ... 73
5.2. Implementasi Program KUBE ... 74
5.2.1. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tentang Pengetahuan Program... 74
5.2.2. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pemungutan Biaya Dalam Mendapatkan Bantuan Program ... 76
5.2.3. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mendapatkan Pelatihan Program ... 76
5.2.4. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Program ... 77
5.2.5. Distribusi Jawaban Responden Tentang Tepat Waktu Program ... 79
5.3. Pendampingan ... 85
5.3.1. Distribusi Jawaban Responden Tentang Sikap Pendamping ... 86
5.3.2. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengetahuan dan Wawasan ... 87
5.3.3. Distribusi Jawaban Responden Tentang Pendamping Membantu Pelaksanaan Program... 87
BAB VI PENUTUP ... 89
6.1. Kesimpulan ... 89
6.2. Saran-saran ... 91
DAFTAR PUSTAKA ... 93
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Air Batu 42
2. Distribusi penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Air Batu ... 42
3. Distribusi penduduk berdasarkan suku di Kecamatan Air Batu ... 43
4. Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Air Batu ... 44
5. Sarana ... 46
6. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Danau Sijabut 48 7. Distribusi penduduk berdasarkan usia di Desa Danau Sijabut ... 49
8. Distribusi penduduk berdasarkan agama di Desa Danau Sijabut ... 50
9. Distribusi penduduk berdasarkan suku di Desa Danau Sijabut ... 51
10. Distribusi penduduk kategori miskin di Desa Danau Sijabut ... 52
11. Sarana ... 54
12. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sei Alim Ulu 55 13. Distribusi penduduk berdasarkan usia di Desa Sei Alim Ulu... 56
14. Distribusi penduduk berdasarkan agama di Desa Sei Alim Ulu ... 57
15. Distribusi penduduk berdasarkan suku di Desa Sei Alim Ulu... 58
16. Distribusi penduduk kategori miskin di Desa Sei Alim Ulu ... 59
17. Sarana ... 61
18. Distribusi responden berdasarkan usia ... 63
19. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan ... 65
20. Distribusi responden berdasarkan suku ... 66
21. Distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga ... 67
22. Distribusi responden berdasarkan jumlah anak bersekolah ... 68
23. Distribusi responden berdasarkan pendidikan ... 69
24. Distribusi responden berdasarkan lama bertempat tinggal ... 70
25. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan setelah menjalankan program ... 71
26. Distribusi responden berdasarkan penghasilan perbulan sebelum menjalankan program ... 72
27. Distribusi responden berdasarkan pemenuhan kebutuhan ... 73
28. Distribusi jawaban responden tentang informasi program ... 74
29. Distribusi jawaban responden tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk dalam mendapatkan bantuan program ... 75
30. Distribusi jawaban responden tentang pengadaan program ... 77
31. Distribusi jawaban responden tentang jumlah hewan ternak ... 78
34. Distribusi jawaban responden tentang pelayanan petugas ... 81
35. Distribusi jawaban responden tentang peningkatan rasa kekeluargaan antar anggota ... 82
36. Distribusi jawaban responden tentang peningkatan pendapatan ... 83
37. Distribusi jawaban responden tentang pengembangan usaha ... 84
38. Distribusi jawaban responden tentang materi yang dibahas ... 85
DAFTAR LAMPIRAN
1. Daftar Responden
2. Daftar Pertanyaan Kuesioner
3. Peta Kecamatan Air Batu
4. Surat Mohon Izin Penelitian
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Halim Murdani, 060902060, Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
(Skripsi ini berisi 6 bab, 94 Halaman, 1 Gambar, 39 Tabel, 23 Kepustakaan dan Lampiran)
ABSTRAK
Dinas Sosial Kabupaten Asahan berusaha untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui program KUBE. Bantuan berupa penguatan dana usaha dalam bentuk dana bergulir, tiap KUBE terdiri 10 anggota. Usaha yang ditempatkan di Kecamatan Air Batu oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan melalui pihak pendamping kecamatan dalam bentuk usaha peternakan kambing dan masing-masing anggota KUBE mendapat dua ekor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program KUBE Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga penerima program KUBE Bidang Peternakan binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air berjumlah 60 Kepala Keluarga. Analisis data dilakukan dengan editing, koding, membuat kategori dan menghitung frekuensi data.
Hasil penelitian menunjukkan 42 responden (70%) menyatakan bahwa dengan adanya program ini pendapatan responden tetap, 48 responden (66,70%) menyatakan program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, 60 responden (100%) menyatakan program ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berusaha dan 10 responden (16,70%) menyatakan bahwa program ini dapat mengembangkan usahanya. Hasil yang dicapai dalam program ini berupa pendapatan responden yang tetap disebabkan hewan ternak masih dalam tahap perkembangbiakan sehingga belum dapat memberikan hasil yang maksimal berupa peningkatan pendapatan. Adanya program ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta kemampuan berusaha masyarakat.
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki
oleh si miskin. Penduduk pada umumya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan,
produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga
menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya
sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan
formal maupun non formal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal
yang rendah (Supriatna, 2000:196).
Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan
absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi
masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh
lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi
kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan
yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu
yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya
membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah
kesenjangan baik antargolongan penduduk maupun pembangunan antarwilayah, yang
pendapatan dan daya beli, sebagaimana tercermin dari rendahnya angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan
berada dibawah garis kemiskinan yang dijadikan sebagai ukuran resmi kondisi
kemiskinan di Indonesia (Sumodiningrat, 2009:5).
Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di
Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan
dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42
persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret
2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara
di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (BPS, 2009).
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan
Maret 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara
sebanyak 1.499.700 orang atau sebesar 11,51 persen terhadap jumlah penduduk
seluruhnya. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang
jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.613.800 orang. Dengan demikian, ada
penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 114.100 orang atau sebesar 1,04 persen.
Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa dampak
dari program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah cukup
berperan dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini (BPS Sumut, 2009).
Penanggulangan kemiskinan adalah sebuah kebijakan strategis yang mau tidak
mau diambil oleh pemerintah selaku agen pembangunan yang bertanggung jawab atas
terselenggaranya perbaikan sosial pada segenap lapisan masyarakat. Namun demikian,
tidak hanya layak ditujukan pada perspektif masyarakat yang menerima program
perbaikan sosial ekonomi. Tidak kurang pentingnya adalah perlunya memberi perhatian
khusus pada dinamika aparat pelaksana program itu sendiri (Sarman, 2000:vi).
Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan
melindungi masyarakat dari kemiskinan dan beserta segala penyebabnya. Upaya yang
dimaksud tidak saja diarahkan untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan
dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat
miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku dalam berbagai tahap
pembangunan. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat
miskin menjadi sangat penting dan strategis mengingat jumlahnya yang relatif besar,
sehingga berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja berbangsa dan
bernegara.
Makna dari pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang
tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena
masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi-relasi sosial maupun ekonomi,
maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup
secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing
secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan utama untuk tidak
seharusnya membuat dikotomi diantara penanganan permasalahan sosial dan ekonomi.
Kondisi aktual antarindividu, kelompok, maupun komunitas yang berbeda dan
unik menyebabkan upaya yang dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat perlu
dioptimalkan. Selain untuk mengoptimalkan manfaat, upaya pemberdayaan terfokus juga
dibutuhkan dengan mengingat bahwa sumber daya pembangunan yang dimiliki
pemerintah relatif terbatas dan tidak dapat menjangkau semua sasaran penaggulangan
kemiskinan dalam kurun waktu yang singkat (Sumodiningrat, 2009:5-7).
Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi
kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parsons
et.al. (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:
sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian
berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar, sebuah keadaan psikologis yang
ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain,
pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan
dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari
orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah
struktur-struktur yang masih menekan (Suharto, 2009:63).
Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat
khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik kondisi internal
(misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas
oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai kelompok
lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya (Suharto, 2009:60).
Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya pengentasan masalah
kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain
P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok
UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan
Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan),
P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), P2KP (Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi
Dampak Krisis Ekonomi) dan P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan
Pemerintah Daerah). Program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh Bank
Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro (micro financing) bersama beberapa
bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) yang
bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga
Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Salah
satu diantaranya program mengentaskan permasalahan kemiskinan adalah dengan
pemberdayaan fakir miskin, yaitu dengan memberikan bantuan sosial melalui bantuan
stimulan usaha ekonomi produktif kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang dikelola
secara berkelompok melalui pendekatan KUBE (Sumodiningrat, 2009:46-47).
Bantuan stimulan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin
dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak dan mampu melakukan kegiatan
usaha ekonomi produktif. Namun karena keterbatasan kemampuan keluarga miskin
dalam mengelola bantuan sosial tersebut, aksesbilitas pemasaran, kualitas usaha dan cara
usaha, maka harus dibantu dengan suatu mekanisme pendampingan baik oleh supra
struktur maupun infrastruktur sendiri. Karena pembangunan kesejahteraan sosial
merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, bahwa
masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, seperti yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Dinsos Prov. Lampung, 2009).
Melalui program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan tercipta proses
penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin (seperti KUBE) serta
terbentuk jaringan bisnis yang dapat mengantarkan masyarakat miskin menuju
masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan
berlandaskan iman dan takwa. Program ini utamanya adalah menggerakkan spirit
“bangunlah jiwanya-bangunlah badannya”, yaitu sikap dan perilaku masyarakat miskin
menjadi masyarakat entrepreneur yang ulet, tangguh, dan mandiri. Selain menggerakkan
spirit masyarakat madani, ada tiga intervensi yang dilakukan dalam program
pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya pendamping (mulai dari tingkat pusat sampai
tingkat desa), akses modal usaha yang berasal dari Anggaran Perencanaan Belanja
Negara (APBN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Corporate Social
Responsibility (CSR) maupun dana padanan perbankan), dan sistem untuk menjamin
keberhasilan program.
Melalui program pemberdayaan masyarakat ini juga akan terjadi penciptaan
lapangan kerja (mengurangi pengangguran) yang dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin (mengurangi kemiskinan) sehingga mampu menabung untuk
mendorong pertumbuhan wilayah. Inilah prinsip KUTABUNG (Kerja-Untung-Tabung),
sehingga pada gilirannya KUBE tumbuh dan berkembang dalam empat aspek yaitu
peningkatan kapasitas manajemen dan tekhnologi (capacity building), pengembangan
pengembangan karakter kepemimpinan dan kewirausahaan (character building), dan
terjadi pengembangan modal dan aset kelompok atau jaringan (equity building)
(Sumodiningrat, 2009:60-61).
KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan yang dibentuk warga atau
keluarga yang telah dibina melalui proses kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk
melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat
kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE
merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses pemberdayaan
masyarakat. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai
hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans, dan
pendampingan (Sumodiningrat, 2009:88).
Menurut data demografis Kabupaten Asahan dan data statistik pada tahun 2008,
jumlah penduduknya 688.529 jiwa, yang tersebar pada 25 kecamatan dengan 177 desa
dan 27 kelurahan dengan luas wilayah daratan 3.817,5 Km2, tingkat kepadatan penduduk
Kabupaten Asahan 185 jiwa per Km2. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di
daerah pedesaan yaitu sebesar 70,56 persen (setara dengan 485.826 jiwa) dan sisanya
29,44 persen (setara dengan 202.703 jiwa) tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah
tangga sebanyak 162.093 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh
sekitar 4,3 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2008 sebesar
1,76 persen. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar
35,17 persen (setara dengan 242.156 jiwa), persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar
60,74 persen (setara dengan 418.213 jiwa) dan persentase penduduk usia 64 tahun ke atas
produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban
ketergantungan sebesar 64,64 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif
menanggung sekitar 65 orang penduduk usia non produktif (BPS Kab. Asahan, 2008).
Dari total penduduk keluarga miskin sekitar 102.729 jiwa atau setara dengan
14,92 persen dari total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Asahan, sebagian dari
mereka berasal dari kelompok penghasilan rendah yang dalam ekonomi diterminologikan
sebagai orang-orang miskin (Kabar Indonesia, 2008).
Maka dari itu sejak tahun 2008 Dinas Sosial Kabupaten Asahan berusaha untuk
menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut melalui KUBE. Bantuan telah
diberikan kepada 30 KUBE di Kabupaten Asahan. Bantuan berupa penguatan dana usaha
dalam bentuk dana bergulir, tiap KUBE terdiri 10 anggota.
Hubungan antara Kecamatan Air Batu dengan Kabupaten Asahan, Kecamatan Air
Batu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Asahan dengan jumlah penduduk
sekitar 40.602 jiwa atau dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 8.448 Rumah Tangga.
Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kecamatan menunjukkan bahwa
penduduk yang kategorikan miskin di Kecamatan Air Batu untuk bulan Juli 2010 sebesar
1.040 Rumah Tangga Miskin yang tersebar di 12 desa (Kantor Kecamatan Air Batu,
2010).
Usaha yang ditempatkan di Kecamatan Air Batu Desa Danau Sijabut dan Desa
Sei Alim Ulu oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan melalui pihak pendamping kecamatan
dalam bentuk usaha peternakan. Usaha ternak yang dijalankan adalah hewan ternak
berupa kambing dan masing-masing anggota KUBE mendapat dua ekor kambing.
tertarik untuk melihat implementasi program Kelompok Usaha Bersama bidang
peternakan binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu.
1.2Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut: “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama
Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan”.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:
1. Dapat menjadi masukan bagi instansi atau lembaga terkait dan sumber informasi
pemerintah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program
penanggulangan masyarakat miskin yaitu Program Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) khususnya yang menjadi binaan Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
2. Dapat memberikan sumbangan positif terhadap khasanah keilmuan di
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Menambah wawasan ilmiah bagi peneliti, terutama yang berhubungan program
1.4Sistematika Penulisan
Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang
lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika
penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan uraian dan teori-teori yang berkaitan dengan
penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi
operasional.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian,
populasi, tekhnik pengumpulan data dan tekhnik analisa data.
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang
berhubungan dengan masalah objek yang akan diteliti.
BAB V : ANALISIS DATA
Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil
penelitian dan analisisnya.
BAB VI : PENUTUP
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Implementasi
Implementasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sama dengan
pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan
proses kebijaksanaan. Dalam kaitan ini, seperti yang dikemukakan oleh Ujodi dalam
Wahab (1990:51) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu
yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijaksanaan.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang
tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab, 1990:51).
Lebih jauh Van Meter dan Van Horm dalam Wahab (1990:49) merumuskan
proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu
atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
Sedangkan Jefry L. Presman dan Aaron B. Wildavsky mendefenisikan
implementasi sebagai penerapan mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses
interaksi antara suatu perangkat tujuan atau tindakan yang mampu untuk meraihnya.
Pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu rangkaian
yang tidak tampak. Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk
hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan
Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) mengatakan
bahwa defenisi implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul yang sudah
disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata
pada masyarakat (Wahab, 1990:51).
Jadi dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan
yang dimaksudkan untuk mengoperasikan suatu program. Tiga kegiatan berikut ini
adalah pilar-pilarnya :
1. Organisasi yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta
metode-metode untuk menjadikan program ini berjalan.
2. Interpretasi yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan
yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan.
3. Penerapan yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang
disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Jones, 1996:296)
Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau
mengoperasikan sebuah program. Program merupakan tahap-tahap dalam penyeleasian
rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai
tujuan.
Hasil defenisi-defenisi implementasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut
telah dimuat berbagai aspek antara lain :
a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil dalam mencapai tujuan.
c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
d. Adanya strategi dalam pelaksanaan.
Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu
adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut telah gagal
dilaksanakan.
Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur
pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan
penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan
bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.
Dalam tahap implementasi, eksekutif melaksanakan rencana yang tercantum dalam
anggaran dalam bentuk kegiatan nyata. Anggaran merupakan bagian dari program, dan
program merupakan penjabaran dari strategi objektif dan strategi inisiatif. Oleh karena
itu, eksekutif harus menyadari keterkaitan erat antara implementasi, anggaran, program,
strategi objektif, strategi inisiatif dan strategi mewujudkan visi organisasi.
Isi daripada kebijaksanaan pada dasarnya meliputi adanya program yang
bermanfaat, kelompok sasaran, terjadinya jangkauan perubahan. Terdapatnya sumber
daya, serta adanya pelaksanaan program. Hasil akhir dari kegiatan implementasi ini dapat
dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat baik individu maupun kelompok, dan juga
keberhasilan implementasi dapat dilihat dari kemampuan pelakasana secara nyata dalam
mengoperasionalkan program yang telah dirancang.
Dalam mengoperasionalkan implementasi program agar tercapai sesuatu tujuan
serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan tinggi pada organisasi
pelaksananya. Organisasi ini bisa dimulai dari organisasi ditingkat atas sampai yang
berada dilevel baik itu negeri atau swasta. Baik tidaknya suatu program atau
kebijaksanaan yang telah diterapkan merupakan masalah yang sungguh-sungguh
kompleks bagi setiap organisasi, termasuk pemerintah serta menjadi masalah karena
biasanya terdapat kesenjangan waktu antara penetapan program atau kebijaksanaan
dengan pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, Jones mengatakan bahwa implementasi adalah
suatu proses interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya dengan
kata lain pelaksanaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan
sebuah program dengan pilar-pilarnya organisasi, interpretasi dan penerapan (Jones,
1996:294).
Jadi implementasi atau pelaksanaan dapat dikatakan merupakan kemampuan yang
tersusun untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab
akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan
model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab
(1990:67) yang disebut dengan A Frame Work For Implementation dikatakan bahwa
peran penting dari analisa kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel
yang mempengaruhi tercapainya tujuan pada keseluruhan proses implementasi
kebijaksanaan yaitu :
1. Kesukaran teknis.
2. Keseragaman prilaku yang akan diatur.
3. Presentasi atau totalitas penduduk yang mencakup dalam kelompok sasaran
dibandingkan jumlah penduduk.
B. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi
1. Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan resmi yang akan dicapai.
2. Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan.
3. Ketetapan alokasi sumber dana.
4. Keterpaduan hierarki dan lingkungan diantara lembaga atau instansi pelaksana.
5. Aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana.
6. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang
dan peraturan.
7. Akses formal pihak-pihak luar.
C. Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi
1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi.
2. Dukungan publik
3. Sikap dan sumber yang dimiliki masyarakat.
4. Dukungan dari pejabat atasan yang berwenang.
5. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan dari pejabat-pejabat pelaksana.
Didalam mengimplementasikan suatu program pemerintah harus merangsang
masyarakat untuk memikul tanggungjawab yang harus meningkat dan program harus
yang membangkitkan spontanitas dan dukungan masyarakat terhadap program yang
dirancang oleh organisasi pemerintah yang berorientasi pada tujuan.
2.2 Pengertian Program
Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di
dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program
dijelaskan mengenai:
1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.
Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih
mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.
“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and
integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu
program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai
sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.
Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk
mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk
mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:
1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga
diidentifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui
oleh publik.
Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis
yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai
melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap
bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones,
1996:295).
2.3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan yang dibentuk warga atau
keluarga yang telah dibina melalui proses kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk
melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat
kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE
merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses pemberdayaan
masyarakat. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai
hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans, dan
pendampingan.
2.3.1 Tujuan Penumbuhan KUBE
Tujuan penumbuhan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan
1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam
kelompok.
2. Peningkatan pendapatan.
3. Pengembangan usaha.
4. Peningkatan kepeduliaan dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE
dan masyarakat sekitar.
Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah penduduk yang hidup dibawah garis
kemiskinan.
2.3.2 Langkah atau Kegiatan Pokok Pembentukan KUBE
Selain KUBE yang ditumbuhkembangkan melalui program pemberdayaan
masyarakat, langkah atau kegiatan pokok pembentukan KUBE untuk sasaran penduduk
miskin lainnya adalah:
1. Pelatihan keterampilan berusaha dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan
praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan penduduk
miskin serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan
pengembangan hasil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya
rasa percaya diri dan harga diri penduduk miskin untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya.
2. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan
dengan keterampilan penduduk miskin dan kondisi setempat. Bantuan ini
merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi
penduduk miskin penerima bantuan untuk mengembangkan dan meggulirkan
3. Pendampingan mempunyai peran sangat penting bagi keberhasilan dan
berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar penduduk miskin merupakan
kelompok yang paling miskin dan fakir miskin. Secara fungsional pendampingan
dilaksanakan oleh pekerja sosial di kecamatan yang dibantu oleh infrastruktur
kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), dan Wanita Pemimpin Usaha
Kesejahteraan Sosial (WPUKS).
2.3.3 Kepengurusan KUBE
Pada hakikatnya, KUBE dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota kelompok.
Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung
pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa
keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkordinasikan kegiatan anggotanya,
mempunyai keuletan, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup serta yang penting
adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.
Anggota KUBE adalah penduduk miskin sebagai sasaran program yang telah
disiapkan. Jumlah anggota setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang/KK sesuai
dengan jenis usaha atau komunitas penduduk miskin. Khusus untuk pembinaan
masyarakat terasing dan rehabilitasi sosial daerah kumuh pembentukan KUBE
berdasarkan unit pemukiman sosial adalah satu KUBE.
2.3.4 Administrasi KUBE
Agar KUBE dapat berjalan dan berkembang dengan baik, pengurus maupun
keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan, dan lain sebagainya. Catatan
dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE,
pembukuan keuangan/pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya.
Selanjutnya dalam rangka keberlanjutan program, diperlukan pembinaan terhadap
KUBE. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan
kemampuan pelaksanaan di lapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE.
Pembinaan dilaksanakan oleh petugas atau pendamping sosial wilayah mulai dari tingkat
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan secara berjenjang.
Monitoring dan evaluasi perlu senantiasa dilakukan untuk mengetahui
perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya
pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai
dengan rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan
melalui mekanisme secara berjenjang mulai tingkat desa sampai pusat (Sumodiningrat,
2009 : 88-90).
2.4 Peternakan
Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan
mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak hanya
memelihara. Memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang
ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan
prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara
optimal.Peternakan adalah suatu proses biologis yang dikendalikan.Banyak unsur yang
sebagai subjek dan ternak adalah objeknya sedangkan penerapan tekhnologi sebagai alat
untuk mencapai tujuan produksi peternakan. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi
atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda,
sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan
lainnya.
Beternak dapat memberikan berbagai manfaat, misalnya beternak kambing.
Banyak manfaat yang dapat diambil dari usaha beternak kambing. Selain diambil
dagingnya, kambing dapat dimanfaatkan kulitnya, kotorannya dan tulangnya. Bahkan
jenis-jenis kambing tertentu dapat diambil susunya, bulunya untuk kain wol dan
sebagainya.
2.4.1 Tujuan Peternakan
Suatu usaha agribisnis seperti peternakan harus mempunyai tujuan yang hendak
dicapai. Tanpa tujuan sulit bagi peternak untuk mengevaluasi sudah sejauh mana langkah
yang telah dilakukan. Sulit baginya untuk menilai apakah langkah itu salah atau benar.
Dalam suatu kegiatan peternakan, tujuan yang dapat dicapai dapat berupa : peternakan
dibuka untuk tujuan komersial, yaitu kegiatan peternakan untuk memperoleh keuntungan.
Bila tujuan ini yang ditetapkan maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi mikro
dan makro, konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan. Namun apabila
peternakan dibuka untuk tujuan untuk pemanfaatan sumber daya, misalnya tanah atau
untuk mengisi waktu luang tujuan utama memang bukan merupakan aspek komersial,
namun harus tetap mengharapkan modal yang ditanamkan dapat kembali (Wikipedia,
2.5 Kemiskinan
Konsepsi umum mengenai kemiskinan biasa terkait dengan masalah ketiadaan
sumber daya ekonomi dan sosial kultural karena informasi yang diperoleh hanya dari
dalam dan politik masyarakat tertentu. Ketiadaan modal sosial ekonomi inilah yang
kemudian membatasi gerak aktivitas dan aktualisasi diri setiap individu dan dinamika
sosial dalam masyarakat.
Kondisi kemiskinan merupakan masalah yang sampai hari ini tidak kunjung
selesai. Sebab memiliki problematika dan dinamika tersendiri dalam masyarakat.
Terlebih kemiskinan terkait dengan krisis sosial, ekonomi, dan politik (Syaifullah,
2008:9).
2.5.1 Indikator Kemiskinan di Indonesia
Menurut Chazali H. Situmorang dalam tulisannya yang berjudul “Penanganan
Masalah Kemiskinan di Sumatera Utara (Poverty Reduction At North Sumatera)” yang
salah satu sub bagian didalamnya menjelaskan tentang indikator kemiskinan, penduduk
miskin di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu penduduk miskin yang
diakibatkan oleh kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang terjadi
terus-menerus (sebagaimana defenisi ini telah dikemukakan) dan kemiskinan sementara yang
ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat
dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis.
Dalam hal ini, karakteristik masyarakat miskin secara umum ditandai oleh
ketidakberdayaan/ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal :
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan,
2. Melakukan kegiatan usaha produktif
3. Menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi
4. Menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif,
mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik
5. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa
mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.
Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan ini menumbuhkan perilaku miskin yang
bermuara pada hilangnya kemerdekaan untuk berusaha, meningkatkan pendapatan dan
minkmati kesejahteraan secara bermartabat. Indikator nasional dalam menentukan jumlah
penduduk yang dikategorikan miskin ditentukan oleh standar garis kemiskinan dari
Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum.
Baik berupa kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk
hidup layak. Penetapan nilai standar inilah yang digunakan untuk membedakan antara
penduduk miskin dan tidak miskin. Apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu
memenuhi kecukupan makanan setara 2100 kalori/hari ditambah pemenuhan kebutuhan
pokok minimum non-makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan
dasar, transportasi dan aneka barang/jasa lainnya maka ia dapat dikategorikan miskin
(BPS, 1999). Sementara penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi
makanan setara 1800 kalori/hari dikategorikan fakir miskin. Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 1981 mendefenisikan, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak
memiliki sumber daya hidup berupa mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi
mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang layak bagi
kemanusiaan.
Selain indikator-indikator kemiskinan diatas, indikator kemiskinan lainnya yaitu:
1. Angka buta huruf (dewasa) adalah proporsi seluruh penduduk berusia 1 tahun ke
atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
2. Penolong persalinan oleh tenaga tradisional adalah penolong persalinan oleh
dukun, keluarga atau tenaga tradisionil lainnya.
3. Penduduk tanpa akses air bersih adalah proporsi penduduk yang tidak mempunyai
akses air bersih. Yang termasuk air bersih disini adalah air kemasan, air
leding/PAM, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke
tempat penampungan lebih dari 10 meter.
4. Penduduk tanpa akses sanitasi adalah proporsi penduduk yang menggunakan
jamban umum atau lainnya sebagai tempat buang air bersih.
5. Angka kesakitan adalah proporsi penduduk yang mempunyai gangguan kesehatan
sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari.
6. Angka pengangguran adalah proporsi penduduk yang termasuk dalam angkatan
kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya
pekerjaan namun belum mulai bekerja.
2.5.2 Dimensi Kemiskinan di Indonesia
Menurut Bank Dunia (World Bank, 2006) ada tiga ciri yang menonjol dari
1. Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang
setara dengan AS$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun
tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan
batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong
miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar
kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator
pembangunan manusia.
3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar
daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan
nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis
kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara
garis kemiskinan AS$1 dan AS$2 perhari, suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan
menentukan di Indonesia.
Analisis kemiskinan dan faktor-faktor penentunya di Indonesia, dan juga belajar
dari sejarah pengentasan kemiskinan di Indonesia, menunjuk kepada tiga cara untuk
mengentaskan kemiskinan. Cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan
adalah:
a. Melalui Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin
Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan
kemiskinan. Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat
dengan proses pertumbuhan, baik dalam konteks pedesaan dan perkotaan ataupun
dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat
mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam
menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya
konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan
serta kerentanan kemiskinan.
b. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin
Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun
sektor swasta adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia.
Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non pendapatan
kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik,
misalnya angka kematian ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki
kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar
persoalan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan
dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan,
dan bahkan proses kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah
kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang
pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator
pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan
masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani
c. Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin
Disamping pertumbuhan ekonomi, dengan menentukan sasaran pengeluaran
untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi
kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non pendapatan). Pertama,
pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan
terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan
sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi
ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk
memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat
mengatasi kemiskinan dari aspek non pendapatan. Membuat pengeluaran
bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama
mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada di Indonesia saat kini.
Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama
kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi dimensi dan keragaman antar
daerah.
2.5.3 Sasaran dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan
Penduduk miskin dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu :
1. Usia lebih dari 55 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif
(usia sudah lanjut, miskin, dan tidak produktif), untuk kelompok ini program
pemerintah yang dilaksanakan bersifat pelayanan sosial,
2. Usia di bawah 15 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia
sekolah, belum bisa bekerja), program yang dilaksanakan bersifat penyiapan
3. Usia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang produktif (usia kerja tapi tidak
mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilaksanakan bersifat investasi
ekonomi, kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama
penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan pengelompokan tersebut maka program penanggulangan kemiskinan
harus difokuskan kepada penanganan penduduk miskin dalam usia produktif melalui
peningkatan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan kapasitas/pendapatan, dan untuk
selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri
dan berkelanjutan (Sumodiningrat, 2009:49-50).
2.6 Kesejahteraan Sosial
2.6.1 Pengertian Kesejahteraan
Secara yuridis konsepsional pengertian kesejahteran sosial termuat dalam UU
No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut :
“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.
Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilakukan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut : “Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
a. perseorangan
b. keluarga
c. kelompok
Pasal 5 ayat 2 adalah sebagai berikut : “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki
kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
a. kemiskinan
b. ketelantaran
c. kecacatan
d. keterpencilan
e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
f. korban bencana
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Depsos RI, 2009).
Walter A. Friedlander, mengutarakan bahwa konsep dan istilah kesejahteraan
sosial dalam pengertian program yang ilmiah baru saja dikembangkan sehubungan
dengan masalah sosial dari pada masyarakat kita yang industrial. Kemiskinan, kesehatan
yang buruk, penderitaan dan disorganisasi sosial telah ada dalam sejarah kehidupan umat
manusia, namun masyarakat yang industrial dari abad ke 19 dan 20 itu menghadapi
begitu banyak masalah sosial sehingga lembaga-lembaga insani yang sama.
Menurut Walter A. Friedlander mendefenisikan : “Kesejahteraan sosial adalah
sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan
untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan
kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan sosial
kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan
kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat” (Muhaidin, 1984:1-2).
1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, yakni arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga
kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan
usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai
kondisi sejahtera (Suharto, 2009:2).
2.6.2 Pendekatan
Mengacu pada buku Charles Zastrow (2000), Introduction to Social Work and
Social Welfare, ada tiga pendekatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yaitu
perspektif residual, institusional, dan pengembangan. Ketiga perspektif tersebut sangat
berpengaruh dalam membentuk model welfare state (negara kesejahteraan) yang
merupakan basis pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pemberantasan
kemiskinan di negara-negara demokratis.
a. Pendekatan Residual
Pandangan residual menyatakan bahwa pelayanan sosial baru perlu diberikan
hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh
lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti institusi keluarga dan ekonomi pasar.
Bantuan finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam jangka pendek, pada masa
kedaruratan, dan harus dihentikan manakala individu atau lembaga-lembaga
kemasyarakatan tadi dapat berfungsi kembali. Perspektif residual sering disebut
sebagai pendekatan yang “menyalahkan korban” atau blaming the victim
kesalahan-kesalahan individu dan karenanya menjadi tanggungjawab dirinya, bukan sistem
sosial. Metoda pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah sosial melibatkan
pendekatan klinis dan pelayanan langsung yang ditujukan untuk membantu orang
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Program-program pengentasan
kemiskinan yang bergaya Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau subsidi BBM adalah
“anak kandung” faham residual. Penerima pelayanan sosial dianggap sebagai
klien, pasien, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri atau bahkan
penyimpang (deviant) (Parsons et.al, 1994).
b. Pendekatan Institusional
Pendekatan Institusioanal melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai
fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modern serta pelayanan sosial
dipandang sebagai hak warga negara. Perspektif institusional termasuk dalam
gugus pendekatan “yang menyalahkan sistem” atau blaming the system approach
(Parsons, et.al, 1994). Individu dan kelompok dipandang sebagai warga negara
yang sehat, aktif dan partisipatif. Kemiskinan bukan disebabkan oleh kesalahan
individu. Melainkan produk dari sistem sosial yang tidak adil, menindas dan rasis.
Metoda pekerjaan sosial yang sering digunakan mencakup program-program
pencegahan, pendidikan, pemberdayaan dan penguatan struktur-struktur
kesempatan. Tiga bentuk program pemerintah yang umum ditekankan oleh
pendekatan institusional meliputi: penciptaan distribusi pendapatan, stabilisasi
mekanisme pasar swasta, dan penyediaan barang-barang publik tertentu
(pendidikan, kesehatan, perumahan sosial, rekreasi), yang tidak disediakan oleh
c. Pendekatan Pengembangan
Konsep pembangunan nasional yang diajukan Midgley (1995) dalam buku Social
Development: The Development Perspective in Social Welfare (1995)
menawarkan pendekatan alternatif, yakni perspektif pengembangan
(developmental perspective) yang memadukan aspek-aspek positif dari
pendekatan residual maupun institusional (Zastrow, 2000). Perspektif
pengembangan ini sering disebut juga sebagai pendekatan pembangunan sosial
oleh Midgley (1995) didefenisikan sebagai “a process of planned social change
designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a
dynamic process of economic development”. Midgley mendukung pengembangan
program-program kesejahteraan sosial, peran aktif pemerintah, serta keterlibatan
tenaga-tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Menurut Midgley (2005):
Selain memfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga
seharusnya memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sosial lewat
bermacam kebijakan dan program sektor publik. Perspektif institusional
membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggungjawab untuk mengatur
usaha pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi dari berbagai
pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi seperti ini berada pada tingkat
yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinasikan pada tingkat nasional. Mereka
juga mempekerjakan tenaga spesialis yang telah terlatih dan terampil untuk
mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Metoda pekerjaan sosial
yang digunakan adalah metode casework atau terapi individu dan konseling
2.7 Kerangka Pemikiran
Sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan, dibentuk
suatu program KUBE yang diberikan kepada keluarga miskin. Bantuan KUBE ini
merupakan bagian Program Penanggulangan Fakir Miskin (P2FM) dimaksudkan untuk
menanggulangi masalah kemiskinan. Diharapkan dengan program ini dapat
meningkatkan dan memperbaiki kondisi keluarga miskin di Kecamatan Air Batu terutama
di Desa Danau Sijabut dan Desa Sei Alim Ulu seperti: 1) Peningkatan kemampuan
berusaha, 2) Peningkatan pendapatan, 3) Pengembangan usaha, 4) Peningkatan
kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
KUBE merupakan salah satu program Departemen Sosial RI untuk mengentaskan
kemiskinan di desa-desa dengan sasaran rumah tangga miskin yang dibina melalui
kelompok-kelompok usaha potensial. Masing-masing KUBE terdiri dari 10 Kepala
Keluaraga miskin. Sistem pelaksanaan program ini sangat ketat karena masing-masing
kelompok diawasi oleh pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Sosial Kabupaten Asahan
menyalurkan bantuan KUBE yang diwakilkan pendamping kabupaten yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil ke pihak kecamatan. Pihak kecamatan menyalurkan bantuan
tersebut ke pihak kelurahan atau desa melalui pendamping kecamatan yang berasal dari
non Pegawai Negeri Sipil. Pihak kelurahan atau desa menyalurkan bantuan tersebut
kepada rumah tangga miskin disaksikan oleh tokoh masyarakat, organisasi sosial dan
karang taruna.
Bagan Kerangka Pemikiran
PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
PIHAK KECAMATAN
Hasil yang ingin dicapai:
- Peningkatan kemampuan berusaha - Peningkatan pendapatan
- Pengembangan usaha
- Peningkatan rasa kekeluargaan PIHAK KELURAHAN/DESA
MASYARAKAT PEMKAB. ASAHAN
melalui
2.8 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.8.1 Defenisi Konsep
Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak
kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.
Konsep pada hakikatnya merupakan istilah, yaitu satu kata atau lebih yang
menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide atau gagasan tertentu
(Soehartono, 2004:4).
Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara
mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari
salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian..
Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang akan diteliti, maka penulis
membatasi konsep yang akan digunakan sebagai berikut :
1. Implementasi : suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau
mengoperasikan sebuah program baik itu yang dilakukan individu, kelompok,
organisasi, masyarakat maupun pemerintah sendiri.
2. Kelompok Usaha Bersama : kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang
dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses
kegiatan Program Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan kegiatan
kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai
sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
3. Pemberdayaan Masyarakat : upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat
lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari
masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan
dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.
4. Dinas Sosial : Lembaga Pemerintahan dibawah naungan Departemen Sosial yang
berfungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.
2.8.2 Defenisi Operasional
Defenisi operasional menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan harus
dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukkan konsep yang
dimaksud. Defenisi inilah yang diperlukan dalam penelitian karena defenisi ini
menghubungkan konsep atau konstruk yang diteliti dengan gejala empirik (Soehartono,
2004:29).
Adapun indikator yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Implementasi program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat
pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan yang
dilaksanakan di Kecamatan Air Batu dengan indikator:
a. Peningkatan kemampuan berusaha
b. Peningkatan pendapatan
c. Pengembangan usaha
d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial
2. Pelaksanaan program dengan indikator:
a. Penafsiran yang dimaksud dengan program
b. Organisasi dan unit kerja
d. Kendala dan solusi pemecahan
3. Program KUBE kepada keluarga miskin dengan indikator:
a. Tepat waktu