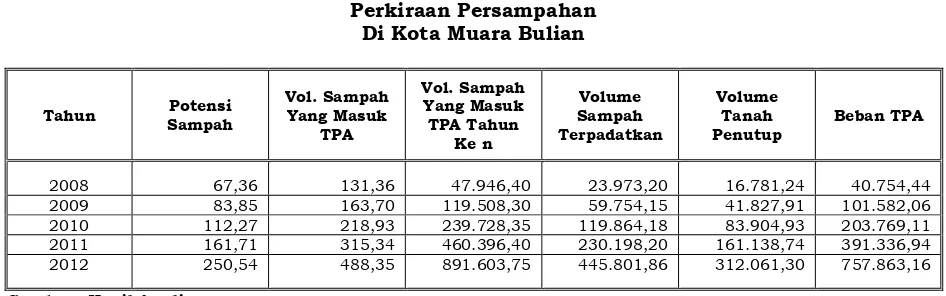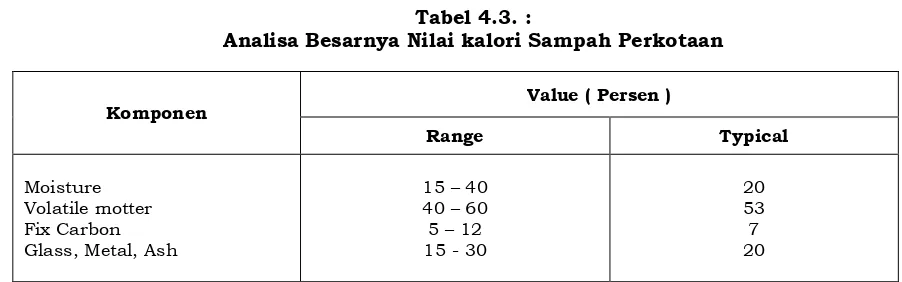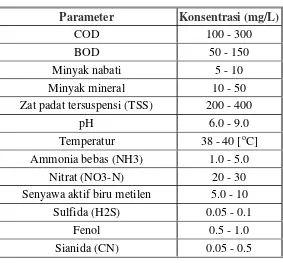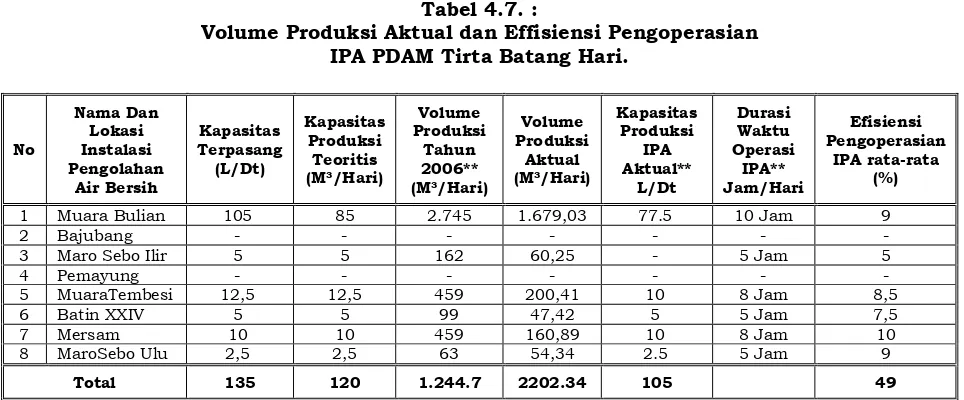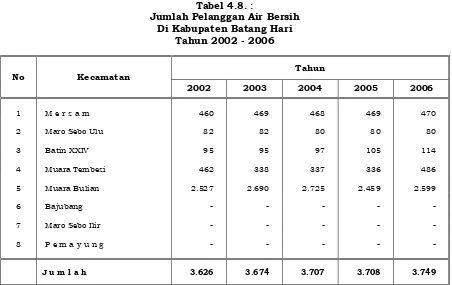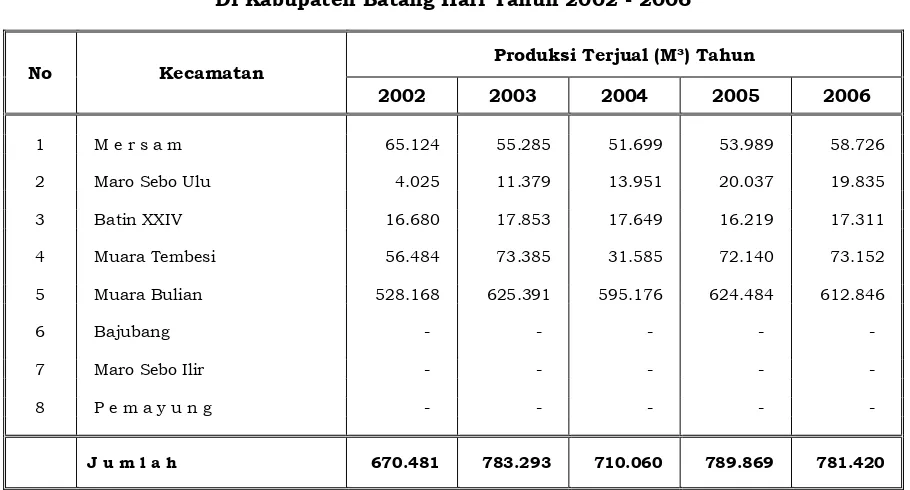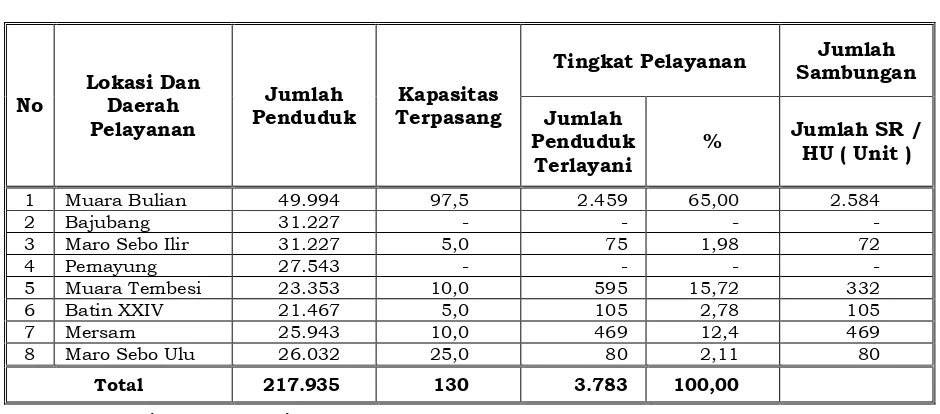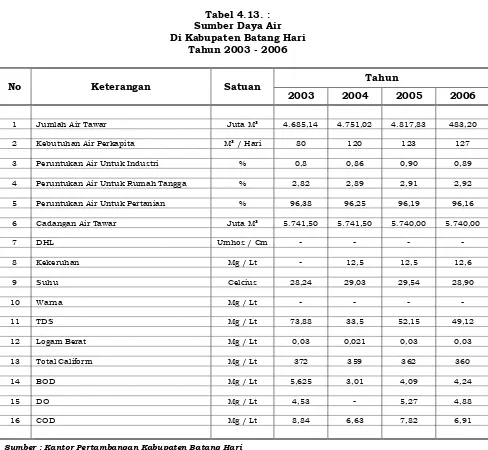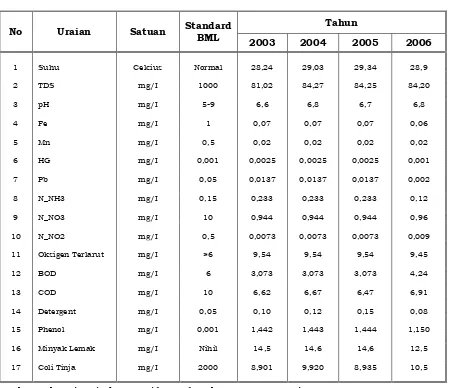Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
1
BAB IV
RENCANA PROGRAM INVESTASI
INFRASTRUKTUR
4.1. Pengembangan Permukiman
4.1.1. Perkembangan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
a) Secara umum perkembangan perumahan dan permukiman yang berlangsung
selama ini memperlihatkan semakin perlunya pembangunan permukiman yang
lebih berbasis wilayah bukan sektor. Sifat dikotomis yang menimbulkan
pertentangan antara yang baru dengan yang lama, lokal dan pendatang, antara
satu sektor kegiatan dengan sektor kegiatan lainnya, modern dengan tradisional,
kota dengan desa dan seterusnya, harus dihilangkan sehingga laju ketimpangan
yang menumbuhkan konflik dapat diperlambat bahkan dihentikan.
b) Pembangunan baru memerlukan pengalihan orientasi dari membangun rumah
ke membangun permukiman. Pengelolaan pembangunan permukiman harus
memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri
melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Di pihak lain kemampuan
membangun permukiman secara komunitas harus direspon secara tepat oleh
pemerintah, sehingga kebutuhan akan identitas tetap terjaga dalam kerangka
pembangunan permukiman yang lebih menyeluruh.
c) Kelangkaan prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta
memperbaiki permukiman merupakan masalah utama dari perumahan dan
permukiman yang ada. Masalah tersebut justru menjadi lebih besar dengan
adanya pembangunan baru yang cenderung dibangun untuk kepentingan
pembangunnya sendiri, dibandingkan sebagai bagian membangun permukiman
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
2
4.1.2. Isu-Isu Perkembangan Perumahan Dan Permukiman
4.1.2.1. Isu-isu Perkembangan Perumahan dan Permukiman Yang Ada
a. Perbedaan Peluang Antar Pelaku Pembangunan
Terjadinya ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan,
perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha. Rentang kualitas berbagai
pelayanan kota cukup besar, di mana kelompok menengah ke bawah yang
memerlukan peningkatan kualitas berbagai pelayanan kota menjadi terabaikan.
b. Konflik Kepentingan
Kebijakan yang memihak kepada kepentingan suatu kelompok masih sering
terjadi dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang masih bias, serta
belum sepenuhnya keberpihakan untuk kepentingan masyarakat setempat.
c. Alokasi Tanah dan Ruang yang Tidak Tepat
Pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang
berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak tepat, yang menyebabkan
penggunaan tanah atau ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan
pembangunan lainnya dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan.
d. Masalah Lingkungan
Masalah lingkungan yang serius umumnya terdapat di daerah yang mengalami
tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam.
e. Penyisihan Komunitas Lokal
Orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek
pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok
masyarakat yang mampu dan menguntungkan, seringkali meminggirkan
masyarakat setempat yang peluangnya menjadi terbatas kepada usaha marjinal.
4.1.2.2. Isu-isu Perkembangan Perkim Masa Yang Akan Datang
a. Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat
Tantangan bagi Pemerintah ke depan adalah secara positif berupaya agar
pertumbuhan lebih merata, antara lain dengan meningkatkan daya saing daerah
yang lamban bertumbuh. Pemerintah perlu lebih aktif memperkuat permukiman
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
3
b. Perkembangan tak terkendali dari daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh
Urbanisasi dan pertumbuhan cepat dapat terjadi pada daerah yang kepadatannya
rendah atau sangat rendah. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah
mengembangkan instrumen agar pertumbuhan yang terjadi dapat lebih
dikendalikan supaya unsur ruang permukiman yang terjadi lebih terintegrasi dan
terpola.
c. Marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global
Pertumbuhan dan pengembangan yankg berorientasi pada sector formal,
cenderung hanya memberi peluang kepada kegiatan atau kekuatan yang bersifat
regional, nasional dan global. Dengan kearifan dan kemampuan mengelola dengan
tepat potensi lokal dapat menjadi keunikan yang mempunyai daya jual ke luar,
sehingga menjadi faktor peningkat daya saing setempat.
4.1.3. Agenda Perumahan Dan Permukiman
4.1.3.1. Proposisi Dasar Pengembangan Agenda Perumahan dan Permukiman
Proses pembangunan perkim di Indonesia telah mengakibatkan tiga masalah
besar dalam pembangunan perumahan dan permukiman yaitu di bidang pertanahan
dan tata ruang; dikotomi dan konflik; serta ketidakadilan. Terkait dengan
desentralisasi, perlu diperhatikan sejauh mana orientasi kebijakan dan
pengembangan perumahan dan permukiman dapat dianggap cukup antisipatif dan
responsif terhadap permasalahan yang berkembang dan perubahan yang sedang
dan/ atau akan berjalan dengan berbagai implikasinya.
Diperlukan suatu pengembangan kepranataan perumahan dan permukiman
secara luas, yang dapat memunculkan norma-norma kehidupan perkotaan dan
perdesaan yang menunjang kehidupan yang beranekaragam dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat.
Tiga usulan yang menjadi dasar perumusan agenda pembangunan perumahan
dan permukiman di masa depan adalah seperti diuraikan berikut.
1. Kesetaraan Mendapatkan Peluang dan Akses
Upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakadilan, konflik serta
marjinalisasi yang dirasakan kelompok bahkan sebagian besar masyarakat yang
rentan dan kurang berdaya adalah dengan memberdayakan kelompok
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
4
yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di
dalam pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman, serta
diberikannya hak yang setara untuk mendapatkannya.
2. Keseimbangan Pertumbuhan Makro dan Mikro
Pengaturan ruang lokal dan akuntabilitaas penataan ruang diperlukan untuk
mencapai keseimbangan tata ruang dan sekaligus di dalamnya adalah
menciptakan keadilan tata ruang.
3. Reorientasi Pembangunan dan Perkembangan Permukiman
Sejak program pengadaan perumahan pertama kali diadakan, masalah utama
yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan
perumahan yang layak bagi masyarakat dalam arti luas, khususnya bagi
masyarakat miskin, dan berpenghasilan rendah serta tidak tetap. Kelayakan
tampaknya perlu dipahami dengan cara pandang lain yaitu bukan secara teknis
rasional melainkan dengan memahami kehidupan atau sifat sosio-ekonomi
masyarakat yang bersangkutan.
4.1.3.2. Tujuan Jangka Panjang Pengembangan Permukiman
a. Pembangunan suatu kepranataan pembangunan dan perkembangan perumahan
dan permukiman yang partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
(accountable).
b. Pengembangan suatu proses pembangunan dan perkembangan perumahan dan
permukiman.
c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan
mengembangkan kemampuannya di dalam pengelolaan pembangunan dan
perkembangan perumahan dan permukiman.
4.1.4. Agenda
Agenda sektor permukiman pada hakekatnya dirumuskan atas dasar
komitmen kepada keberlanjutan pembangunan manusia seutuhnya. Reorientasi
kebijakan pembangunan permukiman dilakukan dengan lebih eksplisit ditujukan
kepada manusia yang membutuhkannya, dengan dukungan politik berupa good
governance sebagai bingkai politik bagi terlaksananya pembangunan permukiman
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
5
Dua agenda utama sektor permukiman adalah sebagaimana diuraikan berikut
ini:
a) Pengembangan Institusi (Kepranataan) Permukiman
i. Mengembangkan kepranataan dan instrumen pembangunan dan
perkembangan permukiman bagi masyarakat banyak.
ii. Membangun kesatuan sistem perencanaan dan system pembangunan
(implementasi rencana) tata ruang yang partisipatif dan memberdayakan
masyarakat maupun Pemerintah Daerah
iii. Membangun mekanisme perencanaan dan pembangunan perumahan yang
terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan pembangunan tata ruang
iv. Mengembangkan sistem pelatihan untuk mensosialisasikan pendekatan
alternatif dan meningkatkan kemampuan profesional di bidang perumahan
bagi aparat pemerintah pusat, daerah maupun pelaku pembangunan
perumahan dan permukiman lainnya.
v. Mengembangkan fungsi/sistem informasi dan diseminasi mengenai hidup
bermukim yang baik bagi masyarakat di dalam pemerintahan daerah.
b) Program-program Aksi Untuk Mengatasi Masalah dalam Perkembangan
Permukiman Yang Ada
i. Program-program antisipasi urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat
ii. Pemberdayaan masyarakat dan permukimannya yang termarjinalkan
iii. Melestarikan dan mengembangkan lingkungan yang memiliki nilai unik
iv.
Pemanfaatan lahan terlantar/tidur4.1.5. Rencana Pengembangan Permukiman
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25
tahun 2000 yang meletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi di-daerah
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan,
demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal serta mempersatukan
potensi dan keaneka ragaman daerah segera diberlakukan. Pada prinsipnya
kewenangan tersebut berada pada pemerintah kabupaten/kota, termasuk bidang
perumahan permukiman yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
Pengembangan permukiman berbasis kawasan pada intinya merupakan suatu
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
6
perumahan dan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang yang serasi
dengan lingkungan fisik, sosial dan ekonomi disekitarnya, sehingga dapat menjadi
suatu konsep pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan
dengan melakukan :
Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman.
Kebijakan akan ditetapkan bersama masyarakat yang disyahkan dengan
Peraturan Daerah (PERDA)
Pembinaan dan pengaturan perumahan dan permukiman.
Pembinaan ditekankan pada upaya menggerakan peran aktif masyarakat dengan
layanan informasi yang transparan, pendampingan, pemberian fasilitas dan atau
kemudahan pada masyarakat yang kurang mampu, serta pengaturan sesuai
dengan kondisi setempat
Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
Pengendalian diselenggarakan untuk mencapai sasaran sebagai kebijakan yang
ditetapkan bersama masyarakat (sebagai kebijakan daerah), serta tetap mengacu
pada penciptaan negara kesatuan yang berkeadilan dan berkeseimbangan dalam
menumbuhkan setiap daerah.
Pembangunan perumahan dan permukiman dapat diselenggarakan oleh
masyarakat secara mandiri, namun karena perumahan dan permukiman merupakan
kepentingan bersama, maka fungsi pemerintah adalah untuk memberikan :
1. Arahan dengan penyiapan kebijakan dan strategi yang diusulkan untuk disepakati
bersama masyarakat,
2. Pembinaan dan pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan bersama secara
transparan dan berkeadilan,
3. Pengendalian melalui pengawasan bersama masyarakat yang memerlukan
prosedur dan mekanisme yang transparan dan mudah diikuti oleh semua pelaku.
4.1.5.1. Penyiapan Kebijakan Dan Strategi Pembangunan
Pendataan untuk memperhitungkan kebutuhan peningkatan kualitas dan
pembangunan perumahan dan permukiman, merupakan upaya untuk mendapatkan
data dasar yang dapat memberikan gambaran kondisi perumahan dan permukiman
yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan dan lingkungan perumahan
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
7
Pendataan untuk menyiapkan strategi pembangunan perumahan dan
permukiman.Merupakan upaya untuk mendapatkan data dasar dalam rangka
pengembangan kebijakan daerah yang diturunkan antara lain dari :
Kebijakan nasional, propinsi dan daerah kabupaten / walikota yang terkait, Kondisi/potensi sosial dan budaya masyarakat setempat,
Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat yang dapat mendukung
pengembangan perumahan dan permukiman;
Kondisi alam setempat (termasuk ketersediaan tanah), Penguasaan teknologi yang dapat diterapkan di daerah.
Pengkajian untuk menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah
merupakan proses analisis dan sintesis yang memadukan pemenuhan kebutuhan
dan kepentingan masyarakat dan daerah dengan kepentingan nasional yang
mencerminkan penyeimbangan dan pengembangan perumahan dan permukiman
antar daerah. Disamping itu secara khusus wajib dikaji penyediaan biaya jangka
panjang untuk perumahan dan permukiman yang berasal dari masyarakat dengan
tata mobilisasi dan pemanfaatan dana yang dapat diselenggarakan secara
berkelanjutan bersama masyarakat.
Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman
merupakan upaya menyiapkan materi yang siap disepakati bersama masyarakat,
antara lain berupa :
Visi, Misi pembangunan perumahan dan permukiman, strategi dan program
jangka panjang, menengah dan tahunan (termasuk penganggaran dan mekanisme
penyelenggaraannya),
Rencana induk pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi
rencana penataan dan pengembangan kawasan permukiman melalui Kasiba dan
Lisiba yang tidak terlepas dari bina sosial budaya serta fasilitasi pembiayaan yang
mendukung pengembangan perumahan dan permukiman.
Pengusulan, dan pembahasan kebijakan dan strategi pembangunan
perumahan dan permukiman merupakan langkah untuk memberikan peran kepada
masyarakat melalui kesepakatan dengan tokoh dan pemuka masyarakat, asosiasi
profesi, serta DPRD. Kesepakatan akan dapat diberlakukan pada masyarakat setelah
ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) setempat.
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
8
upaya menyiapkan jejaring antara masyarakat dan lembaga struktural yang
menangani perumahan dan permukiman dengan mekanisme serta prosedur kerja
yang mudah dipedomani oleh semua pelaku yang terlibat. Sebagai upaya awal adalah
menumbuhkan terbentuknya forum komunikasi atau dewan kota/kabupaten yang
dapat mewakili kepentingan seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Perlu
ditegaskan bahwa jejaring akan berjalan secara berkelanjutan bila dapat disepakati
prosedur dan mekanisme kerja yang jelas serta mudah dilaksanakan bersama.
4.1.5.2. Pembinaan Dan Pengaturan Perumahan Dan Permukiman
a) Layanan informasi komunikasi.
Merupakan layanan kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk :
Menyampaikan informasi dan menyelenggarakan dialog mengenai kebijakan,
strategi dan program pembangunan perumahan dan permukiman,
Memberikan layanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman bersama dengan
masyarakat (termasuk pola pembiayaan),
Memberikan layanan masalah-masalah sengketa yang dapat dilakukan dengan
dialog pada pihak-pihak terkait bila masih dapat diselesaikan tanpa prosedur
peradilan.
b) Pemberdayaan masyarakat.
Merupakan upaya untuk menyetarakan peran seluruh pelaku pembangunan
perumahan dan permukiman dengan :
Pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dalam mencukupi kebutuhan
akan rumah yang layak dalam lingkungan sehat,
Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas
permukiman,
Pemberdayaan para pelaku pembangunan dalam menghimpun dan
memobilisasi dana masyarakat dan sumber lain yang memungkinkan,
pengembangan pasar primer dan hipotik sekunder sebagai salah satu
penggerak pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.
c) Peningkatan peran pelaku kunci.
Merupakan upaya pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
9
negara terutama bagi para pelaku pendukung. Secara operasional dapat
diwujudkan dengan :
Pengembangan pola-pola kemitraan untuk menyediakan dan meningkatkan
kualitas perumahan dan permukiman,
Pembentukan jejaring kemitraan yang dapat menggalang para pelaku kunci
untuk mendukung pembiayaan perumahan dan permukiman.
d) Penyiapan produk pengaturan.
Merupakan upaya penyediaan piranti untuk mengatur semua pelaku dalam
menyelenggarakan pembangunan dan atau peningkatan kualitas perumahan dan
permukiman yang terapan. Penyusunannya mengacu kepada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dengan tetap mempertimbangkan kondisi setempat. Secara
operasional produk pengaturan harus diakui semua pelaku, berkeadilan dan
dilandasi kekuatan hukum yang dapat diberlakukan untuk semua lapisan
masyarakat di daerah. Untuk itu penyiapannya dapat langsung melibatkan para
profesi ahli dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun penetapannya harus
melalui forum resmi (DPRD) dan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah
(PERDA). Produk pengaturan antara lain meliputi aspek : penataan ruang,
pertanahan, pembangunan, pemilikan dan penghunian serta dukungan sistem
pembiayaan dan teknik teknologi.
e) Sosialisasi pengaturan.
Merupakan upaya untuk menyiapkan masyarakat hingga dapat mengetahui,
memahami dan mengindahkan penerapan produk pengaturan yang ditetapkan.
Secara operasional dapat disebar luaskan melalui berbagai forum komunikasi
melalui mekanisme :
Sosialiasi rancangan peraturan dalam upaya mencari masukan dan tanggapan
masyarakat,
Sosialisasi peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka penerapannya.
f) Fasilitasi kepada masyarakat.
Merupakan layanan formal pemerintah daerah kabupaten/kota melalui unit kerja
yang ditugasi dengan :
Dukungan fasilitas serta penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana
lingkungan perumahan dan permukiman terutama yang berfungsi sosial
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
10 Layanan perizinan yang lugas dan transparan bagi seluruh lapisan
masyarakat,
Penyediaan berbagai pola kredit dan atau dukungan pola pembiayaan yang
mudah diikuti oleh masyarakat,
Dukungan mobilisasi dana masyarakat untuk pembangunan perumahan dan
permukiman yang berjangka panjang,
Penyediaan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dan
yang tidak terlayani oleh perbankan (tidak bankable) untuk menjangkau
sumber daya kunci,
Penyediaan dana talangan bagi masyarakat kurang mampu yang dapat dikelola
secara mandiri.
g) Penanggulangan bencana dan kondisi darurat bidang perumahan dan
permukiman.
Merupakan upaya layanan pemerintah guna membantu masyarakat yang terkena
musibah bencana alam ataupun kondisi darurat akibat musibah lainnya. Secara
operasional dapat diberikan dalam bentuk :
Penanganan tanggap darurat dalam bentuk penyediaan hunian sementara
yang dapat dimanfaatkan untuk memulai kehidupannya kembali,
Pemukiman kembali dengan upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan atau
penyediaan lingkungan permukiman yang lebih permanen setelah semua
penyebab kejadian dapat teratasi.
Khusus bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, stimulan penyediaan
rumah menjadi tanggung jawab daerah, kecuali apabila dinyatakan sebagai
bencana berskala nasional.
h) Pelayanan izin pembangunan dan pemanfaatan / penghunian.
Merupakan upaya pembinaan yang diharapkan akan dapat meberikan landasan
dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perumahan dan
permukiman termasuk prasana dan sarana lingkungannya. Perizinan agar
dipahami lebih sebagai upaya pembinaan yang mendasari pengendalian dari pada
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Secara teknis dalam
perizinan yang perlu ditekankan adalah kesesuaian/ kebenarannya atas :
Lokasi yang akan dimanfaatkan ditinjau dengan dasar rencana tata ruang dan
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
11
RP4D yang dimiliki daerah),
Perolehan tanah/lahan ditinjau dengan dasar pada hukum untuk pemilikan
atau pemanfaatannya,
Rancangan tapak yang memperhitungkan tata lingkungan dengan kondisi
lokasi yang ada/direncanakan mendatang,
Rancangan bangunan yang memperhitungkan fungsi bangunan/ruangan, kuat
konstruksi, layak kesehatan, kebakaran, tidak memberikan dampak negatif
pada lingkungan,
Pemanfaatan bangunan yang memberikan jaminan bahwa hasil pembangunan
aman untuk dimanfaatkan,
Sewa menyewa dengan peraturan yang diberlakukan setempat,
Kemampuan perusahaan yang bekerja dibidang jasa konstruksi maupun
konsultan yang melayani pembangunan perumahan dan permukiman.
Khusus untuk fasilitasi pada masyarakat kurang mampu dan penanggulangan
bencana dapat diselenggarakan dengan pemerintah propinsi atau pusat sejauh
belum dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri atau kondisi tersebut
dinyatakan sebagai masalah yang harus ditanggulangi secara nasional.
4.1.5.3. Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
a) Pengawasan Pembangunan.
Merupakan upaya pengendalian pembangunan melalui pengawasan kegiatan
pembangunan dilapangan dengan mengacu kepada standar teknis (untuk
perencanaan dan perancangan) dan standar pelayanan minimal (untuk
pencapaian manfaat) yang diberlakukan setempat dengan Perda, serta
pengawasan pemanfaatan dana-dana pendukung dari pemerintah maupun
lembaga-lembaga lain.
b) Pengawasan Pemanfaatan/Penghunian.
Merupakan upaya melaksanakan “tera” kelayakan hasil pembangunan hingga
secara fungsional dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan sebagai perumahan dan
permukiman. Pengawasan penghunian juga ditujukan untuk menangani
hubungan antara pemilik dan pemanfaat/penyewa rumah hingga dapat
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
12
pengawasan pemanfaatan hunian yang didukung dengan fasilitas/subsidi
pemerintah.
c) Penerapan prosedur dan mekanisme pengendalian.
Merupakan upaya pengendalian terpadu baik vertikal maupun horizontal antar
sesama lembaga yang terkait dalam penanganan perumahan dan permukiman
yang dapat diikuti oleh pengawasan oleh masyarakat.
Secara operasional pengawasan oleh masyarakat diawali dengan penyebar luasan
produk pengaturan serta prosedur dan mekanisme pengawasan hingga
masyarakat mampu mengawasi melalui :
Dewan Kota atau forum komunikasi lain yang dapat menyalurkan aspirasi
masyarakat pada lembaga yang bewenang,
Laporan masyarakat secara langsung kepada instansi yang berwenang.
4.2. Pengembangan Persampahan
Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap
aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume
sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita
gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari
jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pegelolaan sampah tidak bisa
lepas juga dari „pengelolaan‟ gaya hidup masyarakat.
Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada
volume sampah, secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu:
1. Sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah), merupakan sampah
yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll.
Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami
2. Sampah anorganik (sampah kering), merupakan jenis sampah yang tidak dapat
terdegradasi secara alami.
Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Kabupaten Batang
Hari merupakan sampah basah, yaitu mencakup 60-70% dari total volume sampah.
Oleh karena itu pengelolaan sampah yang terdesentralisisasi sangat membantu dalam
meminimasi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada
prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
13
berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan sapah bersifat terpusat.
Misanya saja, seluruh sampah dari kota Muara Bulian dan sekitarnya harus dibuang
di Tempat Pembuangan Akhir di daerah Jalan AMD. Dapat dibayangkan berapa
ongkos yang harus dikeluarkan untuk ini. Belum lagi, sampah yang dibuang masih
tercampur antara sampah basah dan sampah kering. Padahal, dengan mengelola
sampah besar di tingkat lingkungan terkecil, seperti RT atau RW, dengan
membuatnya menjadi kompos maka paling tidak volume sampah dapat
diturunkan/dikurangi.
4.2.1. Sampah Berkontribusi terhadap Pencemaran Sumber Daya Air
Semakin bertambahnya tingkat aktivitas akan berdampak pada meningkatnya
produksi limbah yang dihasilkan baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah
tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi permasalahan serius karena
selain berdampak pada kesehatan masyarakat juga dapat menjadi penyebab
pencemaran lingkungan. Besarnya volume sampah yang dibuang ke kali atau
dibuang sembarangan berpotensi pada terjadinya pencemaran sungai. Jumlah
sampah yang dibuang ke kali atau dibuang sembarangan tersebut berkontribusi
terhadap pencemaran sungai sebanyak 60-70% dari semua jenis polutan sungai.
Sampah baik berupa sampah organik maupun anorganik di dalam sungai akan
mengalami pembusukan dan akan menurunkan kualias air, sehingga akhirnya
sumberdaya air sungai tersebut sudah tidak memenuhi syarat baku mutu sebagai
sumber air bersih bagi masyarakat. Sarana untuk pembuangan sampah pun masih
dirasakan jauh dari cukup. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih banyak pula
masyarakat yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya.
Masyarakat belum memiliki budaya takut dan malu dalam membuang sampah.
Sampai dengan saat ini pengelolaan persampahan oleh pemerintah masih
menitikberatkan pada pengelolaan ketika sampah telah dihasilkan. Kegiatan
pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) sampah menjadi hal yang menonjol dilakukan oleh pemerintah.
Sesampainya di TPA pun permasalahan sampah ini bukan berarti selesai, karena
pada kenyataannya TPA hampir selalu bermasalah. Di mana fasilitas TPA ini hanya
dianggap sebagai tempat membuang sampah. Padahal dalam menentukan sebuah
TPA perlu dicari lokasi yang cocok dan baik, perlu dirancang dan dibangun dengan
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
14
Sehingga dibutuhkan dana anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang
memadai, dan SDM yang terampil dan terlatih. Tanpa prasyarat itu semua, dapat
dipastikan TPA akan selalu bermasalah dan masyarakat sekitar TPA tetap enggan
untuk menerima sampah orang kota. Karena hal ini akan menimbulkan ketika TPA
mulai berfungsi, maka mata air yang semula digunakan untuk mandi, memasak, dan
pengairan, sama sekali tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Ini karena mata air itu telah tertimbun oleh sampah. Setelah ada
sampah, mata air itu bercampur air hitam seperti air kopi dari rembesan sampah.
4.2.2. Perkiraan Volume Sampah
Timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Muara Bulian berasal
dari berbagai tempat antara lain dari rumah tangga, pasar, tempat penjagalan hewan,
rumah sakit fasilitas umum dan lain-lain, dengan penghasil sampah terbesar berasal
dari pasar dan fasilitas umum.
Jumlah sampah yang dihasilkan dalam kecamatan secara keseluruhan tidak
semuanya terangkut dari TPS ke TPA karena diperkirakan hanya sekitar 90 %
sampah yang terlayani dan diperkirakan 84 % sampah yang terangkut ke TPA, hal ini
disebabkan ada sebagian sampah yang diolah sendiri oleh penduduk dengan cara
ditimbun atau dibakar dan recycling/ dipulung sebelum diangkut ke TPA. Berikut
perhitungan total volume sampah jumlah Dump Truck 2 unit dalam 1 hari 2 rate
sehingga 1 Unit Dump Truck dalam 1 hari diperkirakan mampu mengangkut sampah
adalah 18 m3 x 2 x 1 = 36 m3 / hari.
Analisa produksi timbulan sampah mliputi produksi timbulan sampah pada
daerah pelayanan diseluruh wilayah Kota Muara Bulian. Oleh karena itu perhitungan
proyeksi ini adalah total produksi sampah yang dibuang pada TPA Muara Bulian.
Dasar proyeksi produksi timbulan sampah adalah sebagai berikut :
Proyeksi produksi sampah dilaksanakan dengan jumlah penduduk total di wilayah
Kota Muara Bulian.
Proyeksi penduduk dihitung dengan metode eksponensial dengan pertumbuhan
penduduk rata-rata 7,67 % pertahun
Persentase penduduk yang terlayani sebesar 100 % Persentase sampah yang terangkut sebesar 100 %
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
15
Prakiraan sampah yang ditimbulkan di wilayah perencanaan didasarkan
pada perhitungan berikut ini:
1. Potensi Sampah (Qk)
Perhitungan potensi volume sampah yang dihasilkan penduduk digunakan
pendekatan dengan menggunakan rumus:
Qk = q x p
Dimana:
Qk : potensi volume sampah yang dihasilkan
q : koefisien kuantitas sampah (liter/orang/hari) dengan ketentuan:
q : 1,873 lt/orang/hari
p : jumlah penduduk
2. Volume Sampah yang masuk TPA melalui TPS per hari (QTPA)
QTPA = Kp x Qk (l/h) + sampah jalan (5%) + sampah pasar (10%)
dimana:
Kp : faktor kompaksi (0,8)
3. Volume Sampah yang masuk TPA melalui TPS tahun ke-n
Qn = 365 x n x QTPA
4. Volume Sampah terpadatkan (Vp)
Vp = Km x Qn
Dimana:
Km : koefisien pemadatan (0,5)
5. Volume Tanah Penutup (Vtp)
Vtp = 70% x Vp
6. Beban TPA (VTPA)
VTPA = Vp + Vtp (m3)
Berdasarkan perhitungan dengan standar yang digunakan, perkiraan timbulan
sampah pada akhir tahun rencana di wilayah perencanaan 250,54 m³/hari
sedangkan volume sampah yang diperkirakan akan masuk ke TPA adalah 488,55
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
16
komponen sampah dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.1. : 2009 83,85 163,70 119.508,30 59.754,15 41.827,91 101.582,06 2010 112,27 218,93 239.728,35 119.864,18 83.904,93 203.769,11 2011 161,71 315,34 460.396,40 230.198,20 161.138,74 391.336,94 2012 250,54 488,35 891.603,75 445.801,86 312.061,30 757.863,16 Sumber : Hasil Analisa
Sumber : Hasil Analisa dan Data Statistik Lingkungan Hidup
4.2.3. Alternatif Pengelolaan Sampah
Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan
alternatif-alternatif pengelolaan. Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai,
karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan
alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan
pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang dibuang
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
17
pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip–prinsip baru. Daripada
mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus
meningkat, minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utama.
Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem
pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri
harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses
daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.
Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari
material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat
mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang
dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Sebagai tambahan, suatu
porsi peningkatan alur limbah yang berasal dari produk sintetis dan
produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur-ulang; perlu dirancang ulang agar
sesuai dengan sistem daur-ulang atau tahapan penghapusan penggunaan.
Program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat
agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama
program-program di negara-negara berkembang seharusnya tidak begitu saja
mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju,
mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya
sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting
dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka
harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara
berkembang. Salah satu contoh sukses adalah zabbaleen di Kairo, yang telah berhasil
membuat suatu sistem pengumpulan dan daur-ulang sampah yang mampu
mengubah/memanfaatkan 85 persen sampah yang terkumpul dan mempekerjakan
40,000 orang.
Secara umum, di negara Utara atau di negara Selatan, sistem untuk
penanganan sampah organik merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu
sistem penanganan sampah kota. Sampah-sampah organik seharusnya dijadikan
kompos, vermi-kompos (pengomposan dengan cacing) atau dijadikan makanan ternak
untuk mengembalikan nutirisi-nutrisi yang ada ke tanah. Hal ini menjamin bahwa
bahan-bahan yang masih bisa didaur-ulang tidak terkontaminasi, yang juga
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
18
sampah menciptakan lebih banyak pekerjaan per ton sampah dibandingkan dengan
kegiatan lain, dan menghasilkan suatu aliran material yang dapat mensuplai industri.
Tanggung Jawab Produsen dalam Pengelolaan Sampah, hambatan terbesar daur-ulang, bagaimanapun, adalah kebanyakan produk tidak dirancang
untuk dapat didaur-ulang jika sudah tidak terpakai lagi. Hal ini karena selama ini
para pengusaha hanya tidak mendapat insentif ekonomi yang menarik untuk
melakukannya.
Perluasan Tanggungjawab Produsen (Extended Producer Responsibility - EPR)
adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali
produk-produk dan kemasannya. Kebijakan ini memberikan insentif kepada mereka
untuk mendisain ulang produk mereka agar memungkinkan untuk didaur-ulang,
tanpa material-material yang berbahaya dan beracun. Namun demikian EPR tidak
selalu dapat dilaksanakan atau dipraktekkan, mungkin baru sesuai untuk kasus
pelarangan terhadap material-material yang berbahaya dan beracun dan material
serta produk yang bermasalah.
Di satu sisi, penerapan larangan penggunaan produk dan EPR untuk memaksa
industri merancang ulang ulang, dan pemilahan di sumber, komposting, dan
daur-ulang di sisi lain, merupakan sistem-sistem alternatif yang mampu menggantikan
fungsi-fungsi landfill atau insinerator. Banyak komunitas yang telah mampu
mengurangi 50% penggunaan landfill atau insinerator dan bahkan lebih, dan malah
beberapa sudah mulai mengubah pandangan mereka untuk menerapkan “Zero
Waste” atau “Bebas Sampah”.
Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sampah atau limbah dari alat-alat pemeliharaan kesehatan merupakan suatu faktor penting dari sejumlah sampah yang
dihasilkan, beberapa diantaranya mahal biaya penanganannya. Namun demikian
tidak semua sampah medis berpotensi menular dan berbahaya. Sejumlah sampah
yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas medis hampir serupa dengan sampah domestik
atau sampah kota pada umumnya. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal
yang paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan berbahaya dari
sampah yang umum.
Sampah yang secara potensial menularkan penyakit memerlukan penanganan
dan pembuangan, dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi
sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah, secara teknis tidak
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
19
Banyak jenis sampah yang secara kimia berbahaya, termasuk obat-obatan,
yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Sampah-sampah tersebut tidak
sesuai diinsinerasi. Beberapa, seperti merkuri, harus dihilangkan dengan cara
merubah pembelian bahan-bahan; bahan lainnya dapat didaur-ulang; selebihnya
harus dikumpulkan dengan hati-hati dan dikembalikan ke pabriknya. Studi kasus
menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara luas di berbagai
tempat, seperti di sebuah klinik bersalin kecil di India dan rumah sakit umum besar
di Amerika.
Sampah hasil proses industri biasanya tidak terlalu banyak variasinya seperti
sampah domestik atau medis, tetapi kebanyakan merupakan sampah yang berbahaya
secara kimia.
4.2.4. Sistem Disposal
Sebagai dasar untuk memberikan penanganan sistim disposal yang baik dan
flesibel pada persampahan pada Kota Muara Bulian, maka dengan komposisi yang
ada pada sub bab ini akan diterangkan suatu ilustrasi mengenai sistim disposal yang
ada dan sudah diterapkan oleh Negara-negara lain baik Negara berkembang seperti
Thailand maupun Negara yang sudah maju seperti Amerika, Jepang dan
Negara-negara eropa. DisIni akan dijelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari
masIng-masIng sistim disposal dan sifat sampah yang dikehendaki oleh disposal,
agar memberikan keuntungan optimum serta batasan-batasan non teknis yang
mungkIn ada. Dari suatu ilistrasi yang diberikan tersebut dengan memperhatikan
komposisi sampah yang dihasilkan, maka secara teknis dapat ditentukan sistim
disposal yang paling tepat dan fleksibel bagi sampah Kota Muara Bulian.
Sistim disposal yang mungkIn digunakan sebagai pilihan setelah evaluasi
dilapangan adalah sebagi berikut :
1. KompostIng
2. Sanitary Landfill
3. Control Landfill
4. Incenerator
Keempat sistim disposal tersebut telah banyak diterapkan di Asia dan Amerika,
Eropa dan Australia. MasIng-masIng memiliki penerapan yang berbeda terhadap
sistim disposal yang ada. Yang pasti dari keempat sistim disposal tersebut memiliki
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
20
disposal yang baik untuk TPA Muara Bulian, diperlukan suatu studi kelayakan
tersendiri yang memperhatikan bebrbagai macam factor variable pendukung sistim
disposal tersebut. Aspek teknis mencakup komposisi sampah yang dihasilkan,
kelayakan desa dan kesiapan pengelolaan sistim. Aspek ekonomis mencakup masalah
kemampuan masyarakat dan PemerIntah untuk mengadakan pembiayaan awal.
Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang dicermInkan dalam peraturan
dan kebijaksanaan PemerIntah merupakan fakta aspek social budaya. Study evaluasi
perencanaan ini akan memberikan pembahasan tentang study kelayakan aspek
teknis yang mencakup sistim disposal yang paling sesuai untuk komposisi sampah
yang ada.
4.2.4.1. Komposting
Pengomposan merupakan upaya pengelolaan sampah yang sekaligus
mendapatkan bahan-bahan kompos yang dapat menyuburkan tanah. Metode Ini
mempunyai prInsip dasar menurunkan atau mendegradasi bahan-bahan organic
secara terkontrol menjadi bahan-bahan anorganik dalam mempergunakan aktifitas
mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam pengelolaan Ini dapat berupa
bakteri, jamur atau yang lainnya. Agar supaya pertumbuhan mikroorganisme
optimum maka diperlukan beberapa kondisi diantaranya suhu, kelembaban udara
dan ada tidaknya oksigen. Kelembaban udara umumnya berkisar antara 40 hIngga
60 persen, sedangkan yang optimum berkisar antara 50 hIngga 60 persen. Keadaan
temperature diharapkan berkisar antara 45 – 55 OC, karena pada sushu tersebut
organisme mesofilik akan mencapai keadaan yang optimum.
Pengomposan Ini dapat dilakukan secara aerobic maupun anaerobic. Pada
kondisi aerobic yang berperan adalah mikro organisme aerobic, sedangkan pada
kondisi anerobik yang berperan adalah bakteri anaerobic. Tahapan-tahapan dalam
pembuatan kompos adalah sebagai berikut :
a. Penimbangan
b. Pemisahan bahan-bahan yang dapat dikomposkan dengan bahan bahan yang
tidak dapat dikomposkan.
c. Pemotongan bahan menjadi ukuran kecil dan homogen, dengan ukuran berkisar 5
hIngga 10 cm. Pemisahan Ini dapat menggunakan alat seperti penggilIng Godam,
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
21
d. Pengomposan dengan cara digester secara biologis, dengan kondisi suhu dan
kelembaban tertentu.
e. Pemisahan bahan yang telah menjadi dari yang jelek, dan diambil yang bagus.
f. Pengemasan dan penjualan.
Sedangkan metode yang dilaksanakan dalam pembuatan kompos yang cukup
sederhana adalah sebagai berikut, mula-mula menumpuk sampah yang telah
dipotong-potong dan dibasahi pada tempat persegi panjang hIngga ketInggiannya
mencapai 1.5 m, kemudian ditutup dengan tanah pada cetakan berkistIng. Setelah
hari ke enam belas dan hari keempat puluh enam, kompos dibalik, kemudian
dibiarkan sampai tiga bulan umumnya kompos sudah jadi. Kompos Ini kemudian
dibongkar dan diambil yang baik untuk dijadikan pupuk.
4.2.4.2. Santary Landfill
Sanitary Landfill adalah fasilitas pembuangan sampah padat dimana sampah
dibuang dalam keadaan densitas tInggi, tanpa ada polusi air dan dilakukan penutup
tanah tiap waktu operasi tanah harian. Terdapat tiga macam metode pengisian
operasi sampah sanitary landfill, yaitu antara lain metode parit, metode datar, metode
depresi dan metode lereng.
A. Metode Parit
Cara Ini baik sekali untuk daerah-daerah yang memberikan bahan penutup
dengan cara menggali parit-parit ditempat tersebut. Mula-mula sampah diletakkan
pada parit berukuran panjang 100 – 400 ft, kedalaman 3 – 6 ft dan lebar 15 – 25 ft.
Pertama-tama parit digali, tanah hasil galian digunakan cadangan untuk menimbun.
Kemudian sampah ditebarkan dalam lapisan tipis (18 – 24 Inc) dan dipadatkan.
Operasi dilanjutkan sampai kedalaman yang diinginkan. Bahan penutup diperoleh
dengan menggali parit yang akan diisi sampah.
B. Metode Datar
Metode Ini digunakan bila tanah datar tidak baik untuk penggalian parit guna
menaruh sampah. Mula-mula sampah ditebarkan menurut garis yang panjang dan
sempit diatas permukaan tanah selebar 16 – 30 inc. Tiap-tiap lapisan Ini dipadatkan
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
22
ditutup dengan tanah dengan ketebalan 6 – 12 In. Bahan penutup diangkut dengan
truck atau alat-alat lain dari tempat galian atau pada galian terdekat. Pengisian
biasanya dimulai dengan pembuatan tanggul tanah. Panjang alur-alur sampah
tergantung pada keadaan setempat dan besarnya operasi. Lebar sampah yang
dipadatkan berkisar antara 8 – 10 fit. Tiap-tiap bagian yang terdiri dari sampah
setelah dipadatkan termasuk bahan penutup disebut sel.
C. Metode Depresi
Pada metode Ini memakai sistim sebagai penutup jurang, sumur kerIng, tebIng
yang terjadi secara alami maupun buatan. Teknik pengisian dan pemadatan sampah
tergantung keadaan lokasi, sifat bahan penutup, sifat geologi, sifat hidrologi dan
luasnya jurang pada tempat tersebut. Bila dasar tebIng datar, bisa dimodifikasi
dengan metode parit. Bila dasar telah tampak datar maka pengisian dilanjutkan
sampai tebIng penuh, karena penurunannya nati biasanya akan diperlukan pengisian
sumuran atau galian tambang lebih tinggi dari tanah sekitarnya.
D. Metode Lereng
Metode Ini merupakan variasi dari metode datar. Yaitu dalam hal kekurangan
bahan penutup, tanah penutup diperoleh dari dasar tanah tersebut. Tanah penutup
tambahan diangkut seperti metode datar.
Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan metode operasi yang digunakan
pada sanitary landfill, diantaranya adalah topografi, geologi lahan, ketersediaan lahan
penutup, komposisi sampah yang dibuang, hidrologi air tanah dan air permukaan.
Topografi lahan banyak menentukan pemilihan tipe teknik pembuangan yang
dilakukan. Geologi tanah pada landfill, sangat pentIng untuk operasi landfill.
Keberadaan tanah penutup banyak diperlukan dalam operasi sanitary landfill,
dimana sifat tersebut menunjukkan kemampuan tanah melewati air hujan dari
Leacheate. Keberadaan tanah penutup baik kualitas maupun kuantitas akan
mempengaruhi efisiensi operasi landfill. Jika tak tersedia lahan penutup yang
Permeabilitasnya rendah pada daerah tersebut, maka dibutuhkan lagi biaya
transportasi untuk mengangkut tanah penutup yang diambil dari daerah lainnya,
tentunya hal Ini akan menambah biaya operasional. Reaksi yang terjadi pada landfill
yaitu landfill akan mengalami perubahan secara biologi, fisik dan kimia. Perubahan
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
23
a. Peluruhan secara biologis terhadap bahan-bahan organic yang dapat membusuk
baik dengan aerobic maupun dengan anaerobic yang menghasilkan bahan cair
atau gas.
b. Oksigen Kimiawi dari bahan-bahan.
c. Keluarnya gas-gas dari timbunan
d. Mengalirnya aliran karena perbedaan tekanan
e. Larut dan merembesnya bahan organik dan anorganik oleh air yang merembes
melalui sampah dalam landfill.
f. Idak seimbangnya kedudukan disebabkan adanya konsolidasi di beberapa bagian
landfill sehingga menyebabkan tanah menjadi kosong.
Gas yang terbentuk akan dilepas ke udara atau ditampung untuk produksi
energi. Rembesan dapat terkandung dalam landfill atau dipisahkan untuk diolah.
Gas yang dihasilkan 90% terdiri dari gas methan dan karbondioksida. Bila gas
methan yang terkandung dalam udara sampai 5 – 15 % maka akan bersifat meledak.
Bila gas methan dilepaskan ke udara tanpa pengawasan yang baik maka akan
berakumulasi di bawah bangunan atau gedung tertutup. Dengan Ventilasi yang baik
maka gas methan tidak akan menimbulkan masalah. Sedangkan gas karbondioksida
menjadi masalah karena kepadatannya. Karbondioksida 1,5 kali lebih padat
dibandingkan dengan udara dan 2,8 kali lebih padat dibandIngkan dengan gas
methan, sehingga cendrung untuk lebih mengumpul di bawah landfill. Yang akhirnya
akan mencapai tanah dan dapat menyebabkan turunnya pH, sehingga akan
mengakibatkan kesadaran dan kandungan mIneral dalam tanah. Cara pengawasan
ada dua macam metode yaitu permeable dan impermeable, cara permeable
menggunakan batu geragal yang dimasukkan diantara sel, tebal geragal antara 12 –
18 In.
Sering juga pada dasar sumuran ini dilengkapi dengan penghembus udara.
Dalam hal demikian perlu dilengkapi pembakar gas pada bagian atasnya. Pada
metode impermieble dilaksanakan dengan jalan membatasi aliran gas mengunakan
bahan-bahan yang lebih kedap dibandIng tanah. Misalnya tanah liat yang
didapatkan. Hal Ini dilakukan bla gas-gas yang dihasilkan akan ditampung sebagai
sumber energi.
Aliran rembesan pada keadaan normal remesan mengalir didasar landfill.
Untuk mengawasInya agar tidak mencemari air tanah atau lIngkunggannya dibangun
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
24
untuk tujuan mendapatkan gas dan mengawasi rembesan.
Tujuan dari sanitary landfill adalah untuk menghindari bau, menghIndari
leacheate, estetika dan menghIndari ganguan lalat, tikus dan burung sebagi Vektor
penyakit.
Keuntungan dari sanitary landfill Ini adalah :
1. Merupakan metode yang paling memenuhi kesehatan operasinya dan paling
sesuai untuk lahan yang paling luas.
2. Modal awal tak sebesar metode lain.
3. Merupakan cara terakhir pembuangan sampah.
4. Dapat menerima segala jenis sampah.
5. Fleksibel, dapat menerima jumlah sampah yang besar tampa tambahan tenaga
kerja dan pefalaatan
Sedangkan kerugian dari sanitary landfill adalah sebagai berikut.
1. Tidak sesuai dengan daerah yang padat penduduknya..
2. Kriteria operasi sanitary landfill harus ditrerapkan benar-benar sebagai mana
mestInya, jika tidak akan sama dengan operasi open dumping.
3. Landfill yang penuh akan memerlukan waktu yang lama untuk menjadi stabil dan
memerlukan pemeliharaan periodik.
4. Terjadinya gas mentah yang dapat menimbulkan kebakaran.
5. Lahan bekas sanitari landfill tersebut tidak dapat digunakan untuk kantor atau
pun perumahan.
4.2.4.3. Incenerator
Incenerator adalah alaat proses pembakaran terkontrol untuk mengurangi
buangan berupa bahan padat., cairan atau gas yang mudah menjadi karbondioksida
atau gas lain yang relatip tidak berbahaya bagi kesehatan. Sisa pembakaran Ini
biasanya dibuang dalam landfill setelah bahan-bahan yang dapat dimanpaatkan
dipisahkan.
Proses pembakaran Ini telah berumur lebih dari seratus tahun yang lalu.
Maksud dari pemilihan alat Ini adalah alasan ekonomi. Bebas dari ganguan bau dan
lalat serta merupakan metode seniter pembuagan sampah. Dengan pertimbagan
keuntugan dan kerugian dengan pengunaan Insenerator dapat diputus kan perlu
tidak nya penggunaan alat Ini pada suatu disposal sampah.
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
25
1. tanah yang dibutuhkan untuk disposl relatif lebih kecil dari pada lahan untuk
landfill.
2. memungkInkan untuk menempatkan Instalasi Incenerator pada kawasan yang
terpusat.
3. suatu Insenertor menghasilkan abu dimana kandungan organiknya dapat
diabaikan tak menimbulkan gangguan.
4. pada alat Insenerator moderen dapat membakar segala jenis sampah.
5. Incenerator dapat dipengaruhi iklim.
6. Incenerator relatip fleksibel karena dapat menangani kenaikan atau penurunan
volume sampah karena perubahan musim dan keadaan.
Sedangkan kerugian Incenerator adalah :
1. Modal awal untuk pengadaan Instalasi Incenerator cukup mahal.
2. Biaya operasional, biasa pemeliharaan dan biaya perbaikan cukup tInggi.
3. Incenerator bukan pembuangan akhir, karena masih menghasilkan abu yang
berterbangan dari sisa pembakaran, dan masih harus dibuang dengan cara lain.
Beberapa parameter optimum yang mempengaruhi efesiensi dari operasi alat
Incenerator, adalah tidak dapat ditangani atau dikontrol oleh manejer Incenerator itu
sendiri. Sebagai contoh, utilitas komposisi yang dibawa Incenerator tidak dapat
dikontrol oleh operator. Namun dipihak proses perubahan komposisi dikontrol oleh
pemasukan sampa, supply udara dan lain-lain. Beberapa parameter dari operasi
tersebut adalah :
1
Kualitas sampah adalah salah satu yang paling pentIng didalam desaIn Incenerator. Berdasarkan kualitas sampah yang dihasilkan, efesiensi operasi yangdikehendaki dan periode desain yang direncanakan dapat ditentukan besarnya.
Keanekaragaman sampah yang hendak dibuang mempengaruhi besarnya nilai
kalori sampah tersebut.
Tabel 4.3. :
Analisa Besarnya Nilai kalori Sampah Perkotaan
Komponen
Sumber : “Solid Waste, EngInerIng PrInciples and Managemen Issues” Tchobanoglous, George, Thiesen, Hilary
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
26
Pada tabel tersebut memperlihatkan range komposisi sampah yang dibakar pada
IncInerator di Amerika. Komposisi sampah kota cendrung berubah fungsi
sepanjang tahun, lokasi dan tIngkat pendapatan penduduk juga dapat
mepengaruhi komposisi sampah.
2 Kontrol Pembebanan.
3 Supplay udara
4 bahan bakar tambahan pada operasi IncInerator. Bahan baker tambahan
digunakan untuk memanaskan kamar pembakar, memperbesar pembakaran
apabila sampah yang dimasukkan nilai kalorInya rendah.
5 Pengontrolan gas buang merupakan salah satu perhatian operasi IncInerator yang
pentIng. Karbondioksida, uap air Nitrogen yang dilepaskan selama pembakaran.
Gas-gas Ini secara Alamiah tidak menimbulkan polusi udara. Namun karena
komposisi sampah dan karena terjadi pembakaran yang tidak sempurna maka
Nitro oxid, Sulfur dioksida. Sulfur triokdida dan KorbIn monoksida akan
dihasilkan selama pembakaran. Gas-gas Inilah yang dapat menimbulkan
pencemaran.
4.2.4.4. Control Landfill
Sistim Ini mengunakan cara yang hampir sama dengan sistim sanitary landfill,
tetapi dalam sistim Ini timbulah leacheate tidak dikontrol, sehInga apa bila terjadi
curah hujan yang cukup tInggi maka air dapat masuk melalui pori-pori tanah dan
akhirnya leacheate akan dapat terbawa oleh air hujan dan masuk kebadan air.
SehInga dapat menimbulkan pencemaran. Adapun proses pengolahan persampahan
dengan mengunakan sistim control landfill pada tempat pembuagan akhir adalah
mula-mula sampah yang terangkut ditampung pada suatu tempat pembuagan akhir.
Kemudian pada setiap hari kerja sampah ditutup dengan tanah penutup dan
dipadatkan. Selanjutnya setiap dua mInggu tanah ditutup lagidengan tanah urung
{Cover}, yang dilakukan secara berlapis.
Kelemahan dari sistim control landfill Ini adalah sebagai berikut :
1. Timbulan leacheate tidak dikontrol sehInga apabila terjadi curah hujan yang
cukup tInggi, maka air hujan akan dapat masuk kedalam pori-pori tanah dan apa
bila terbawa sampai ke badan air maka dapat mencemari badan air tersebut .
2. Keadaan tanah penutup tidak dikontrol apakah itu tanah yang kedap air atau
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
27
3. Tanah yang dipadatkan tidak trpadat seperti p[ada sistim sanitary landfill, sehInga
masih dimungkInkan air hujan menembus pori-pori tanah.
4. Timbulan gas Menthan diabaikan sehInga sanggat dimungkInkan akan terjadi
kebakaran dan ledakan.
Sedangkan keuntungan dari sistim control landfill Ini adalah :
1. Biaya yang dibutuhkan lebih murah dari pada sistim sanitary landfill.
2. Dapat menerima semua jenis sampah.
3. merupakan cara pengolahan yang lebih baik dari pada sistim open dumpIng.
4.3. Rencana Pengelolaan Air Limbah
Pembuangan air limbah baik yang bersumber dari kegiatan domestik (rumah
tangga) maupun industri ke badan air dapat menyebabkan pencemaran lingkungan
apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah. Sebagai contoh, mari
kita lihat Kota Jakarta. Jakarta merupakan sebuah ibukota yang amat padat
sehingga letak septic tank, cubluk (balong), dan pembuangan sampah berdekatan
dengan sumber air tanah. Terdapat sebuah penelitian yang mengemukakan bahwa
285 sampel dari 636 titik sampel sumber air tanah telah tercemar oleh bakteri coli.
Secara kimiawi, 75% dari sumber tersebut tidak memenuhi baku mutu air minum
yang parameternya dinilai dari unsur nitrat, nitrit, besi, dan mangan.
Dalam kegiatan industri, air limbah akan mengandung zat-zat/kontaminan
yang dihasilkan dari sisa bahan baku, sisa pelarut atau bahan aditif, produk
terbuang atau gagal, pencucian dan pembilasan peralatan, blowdown beberapa
peralatan seperti kettle boiler dan sistem air pendingin, serta sanitary wastes. Agar
dapat memenuhi baku mutu, industri harus menerapkan prinsip pengendalin limbah
secara cermat dan terpadu baik di dalam proses produksi (in-pipe pollution prevention)
dan setelah proses produksi (end-pipe pollution prevention). Pengendalian dalam
proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan,
juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Sedangkan pengendalian setelah
proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan peencemar sehingga
pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan.
Sasaran yang dicapai didalam pengelolaan air limbah adalah :
1. Tersedianya sarana pengelolaan air limbah secara terpusat (offsite) maupun
setempat (onsite) yang terkendali.
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
28
dengan terwujudnya pemukiman yang bersih dan sehat.
Sedangkan harapan yang ingin diwujudkan adalah :
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi tingkat pencemaran
air tanah dan air permukaan seperti saluran, kali atau sungai.
2. Mengubah perilaku masyarakat sehingga tidak menganggap kali/sungai (badan
air) sebagai tempat pembuangan air limbah.
3. Memulihkan fungsi saluran drainase sebagai saluran pembuangan air hujan
untuk mengurangi dan mencegah bahaya banjir.
4. Mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk, lalat, tikus serta
menghindari terjangkitnya wabah penyakit menular seperti typus, muntaber dan
sebagainya.
5. Mendukung terwujudnya citra Kota yang bersih.
Tabel 4.4. :
Batasan Air Limbah untuk Industri Kepmen LH No. KEP-51/MENLH/10/1995
Parameter
Konsentrasi (mg/L)
COD
100 - 300
BOD
50 - 150
Minyak nabati
5 - 10
Minyak mineral
10 - 50
Zat padat tersuspensi (TSS)
200 - 400
pH
6.0 - 9.0
Temperatur
38 - 40 [
oC]
Ammonia bebas (NH3)
1.0 - 5.0
Nitrat (NO3-N)
20 - 30
Senyawa aktif biru metilen
5.0 - 10
Sulfida (H2S)
0.05 - 0.1
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
29
4.3.1. Teknologi Pengolahan Air Limbah
Tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurangi kandungan
bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan tersuspensi,
mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh
mikroorganisme yang terdapat di alam. Pengolahan air limbah tersebut dapat dibagi
menjadi 5 (lima) tahap:
a) Pengolahan Awal (Pretreatment)
Tahap pengolahan ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk
menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air limbah.
Beberapa proses pengolahan yang berlangsung pada tahap ini ialah screen and
grit removal, equalization and storage, serta oil separation.
b) Pengolahan Tahap Pertama (Primary Treatment)
Pada dasarnya, pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama
dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya ialah pada proses yang
berlangsung. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama ialah
neutralization, chemical addition and coagulation, flotation, sedimentation, dan
filtration.
c) Pengolahan Tahap Kedua (Secondary Treatment)
Pengolahan tahap kedua dirancang untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari
air limbah yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik biasa. Peralatan
pengolahan yang umum digunakan pada pengolahan tahap ini ialah activated
sludge, anaerobic lagoon, tricking filter, aerated lagoon, stabilization basin,
rotating biological contactor, serta anaerobic contactor and filter.
d) Pengolahan Tahap Ketiga (Tertiary Treatment)
Proses-proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah tahap ketiga ialah
coagulation and sedimentation, filtration, carbon adsorption, ion exchange,
membrane separation, serta thickening gravity or flotation.
e) Pengolahan Lumpur (Sludge Treatment)
Lumpur yang terbentuk sebagai hasil keempat tahap pengolahan sebelumnya
kemudian diolah kembali melalui proses digestion or wet combustion, pressure
filtration, vacuum filtration, centrifugation, lagooning or drying bed, incineration,
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
30
4.3.2. Pemilihan Teknologi
Pemilihan proses yang tepat didahului dengan mengelompokkan karakteristik
kontaminan dalam air limbah dengan menggunakan indikator parameter yang sudah
ditampilkan di tabel di atas. Setelah kontaminan dikarakterisasikan, diadakan
pertimbangan secara detail mengenai aspek ekonomi, aspek teknis, keamanan,
kehandalan, dan kemudahan peoperasian. Pada akhirnya, teknologi yang dipilih
haruslah teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan
diolah. Setelah pertimbangan-pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi
kelayakan atau bahkan percobaan skala laboratorium yang bertujuan untuk:
1. Memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-proses yang sesuai
dengan karakteristik limbah yang akan diolah.
2. Mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan
efisiensi pengolahan yang diharapkan.
3. Menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk penerapan
skala sebenarnya.
4.3.3. Pengolahan Secara Alamiah
Pemanfaatan tanah sebagai media pengolahan air limbah dikenal dengan
pengolahan secara alamiah. Pengolahan secara alamiah diharapkan dapat lebih
dikembangkan karena pengolahan jenis ini relatif lebih ekonomis dengan tujuan
memanfaatkan potensi alam setempat. Telah banyak dilakukan penelitian yang
memanfaatkan tanah sebagai bahan pengadsorpsi. Pada Tabel 1 ditunjukkan
beberapa penelitian yang menggunakan tanah sebagai bahan pengadsorpsi terhadap
beberapa polutan, baik bahan organik maupun anorganik. Berdasarkan hasil
penelitian di atas, dapat dikembangkan suatu teknologi pengolahan air limbah yang
memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh tanah, yaitu potensi berlangsungnya
proses fisik, fisik-kimiawi, dan biologis. Proses-proses tersebut mempunyai
kemungkinan yang sangat besar dalam hal penurunan kadar bahan pencemar yang
dibawa oleh air limbah.
Pada pengolahan ini, air limbah dialirkan di atas lahan secara terbuka. Air
limbah akan mengalir di atas lahan atau meresap ke dalam tanah, maka terjadilah
berbagai proses alamiah, yaitu proses fisika, fisik-kimiawi, maupun biologis
Pengolahan alamiah sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19 di Inggris. Namun,
Laporan Akhir IV -
RPIJM Bidang PU / Cipta Karya
31
mendapat perhatian. Di Indonesia, pengolahan alamiah telah lama ada, meskipun
tanpa disadari hal itu sebagai salah satu bentuk pengolahan. Ide pengolahan air
limbah secara alamiah bermula dari fakta bahwa dalam tanah terdapat banyak
proses alamiah, seperti adsorpsi, pertukaran ion, presipitasi kimiawi, transfer gas,
sedimentasi, filtrasi, biofiltrasi, biodegradasi, dan sebagainya. Proses tersebut mampu
menurunkan kadar bahan-bahan yang umumnya terkandung dalam air limbah,
sebagaimana hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas. Hal inilah yang mendasari
perlunya mengangkat kembali pengolahan alamiah sebagai bentuk teknologi
pengolahan air limbah terkini.
Luas lahan yang diperlukan untuk pengolahan alamiah dapat diperkirakan
dengan perhitungan matematisyang diperoleh berdasarkan penelitian. Dari penelitian
dengan percobaan secara batch atau aliran kontinyu, dapat dihitung besarnya
kebutuhan tanah untuk menyisihkan bahan pencemar tertentu. Kemungkinan yang
bisa terjadi dengan penerapan sistem pengolahan secara alamiah adalah pencemaran
air tanah oleh air limbah. Oleh karena itu perlu ada pemikiran lebih lanjut upaya
pengendaliannya dan perlunya ditetapkan kriteria pemilihan lokasi.
4.4. Rencana Pengembangan Drainase
Sejalan dengan kecenderungan masyarakat akan kelestarian lingkungan
semakin menguat, sehingga dalam pengelolaan drainase pada daerah perkotaan telah
timbul pemikiran dan usaha untuk merubah konsep dan prinsip-prinsip penanganan
drainase perkotaan cara lama yaitu mengalirkan air secepatnya keluar dari daerah
pengaliran. Air permukaan secara kuantitatif semakin lama tersedia semakin terbatas
dan secara kualitatif semakin lama semakin menurun juga. Sedangkan keperluan air
di daerah perkotaan semakin lama semakin meningkat sejalan dengan peningkatan
jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi.
Untuk menjawab tantangan itu perlu dilaksanakan usaha-usaha pelestarian
sumber daya air, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan sistem drainase di
daerah perkotaan. Prinsip sistem drainase resapan adalah mengendalikan kelebihan
air permukaan sedemikian rupa sehingga air permukaan dapat mengalir secara
terkendali dan lebih banyak mendapat kesempatan untuk meresap ke dalam tanah.
Dengan debit pengaliran yang terkendali dan semakin bertambahnya air hujan yang
dapat meresap ke dalam tanah, maka kondisi air tanah akan semakin baik dan