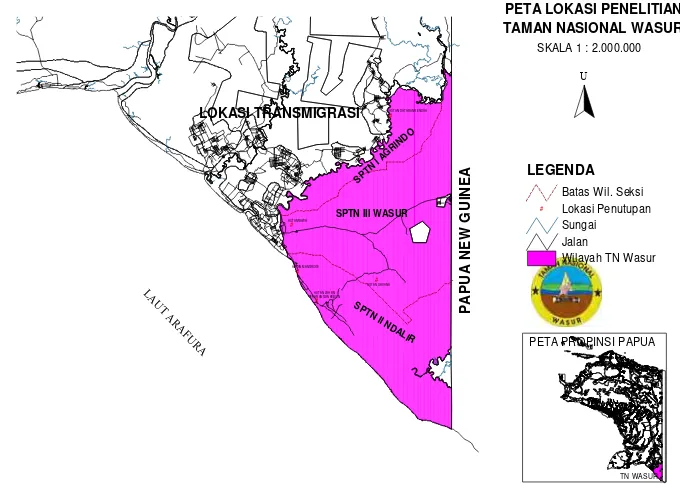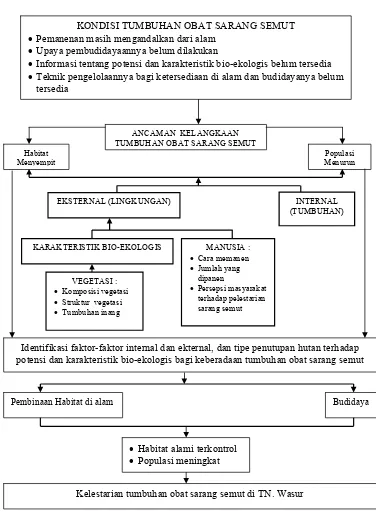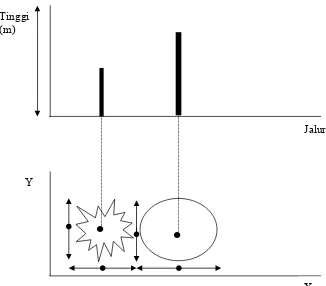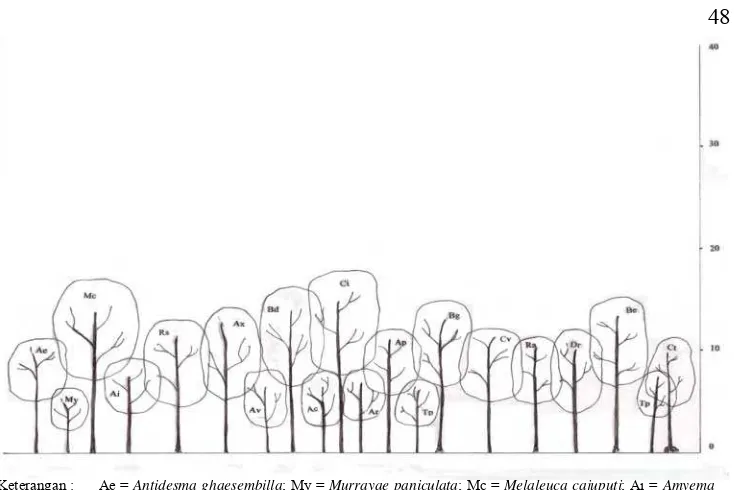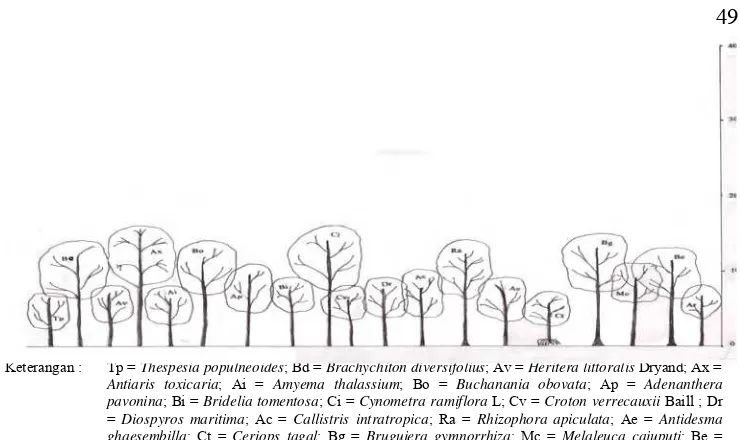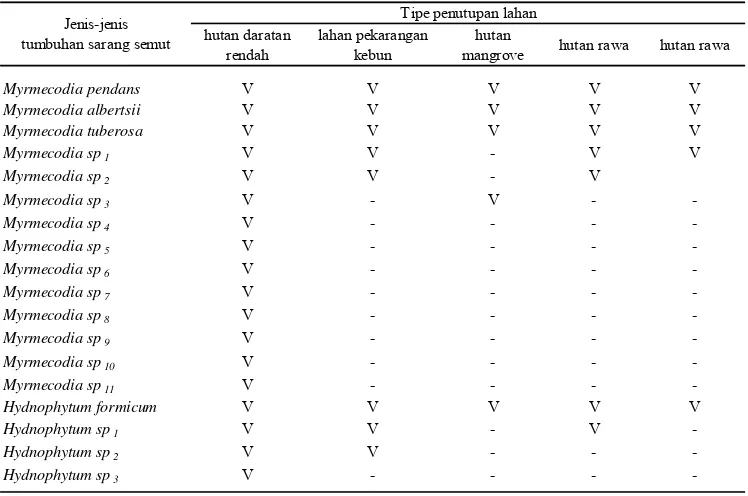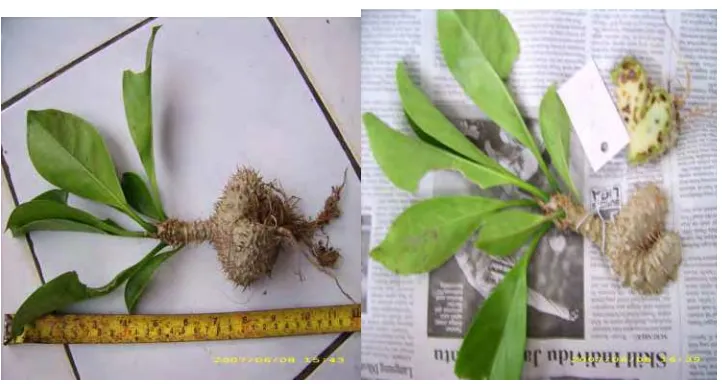TUMBUHAN SARANG SEMUT
DI TAMAN NASIONAL WASUR MERAUKE PAPUA
ZETH PARINDING
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN
SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Potensi dan
Karakteristik Bio-ekologis Tumbuhan Sarang Semut di Taman Nasional Wasur
Merauke Papua” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk
apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau
dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain,
telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian
akhir tesis ini.
Bogor, Desember 2007
Zeth Parinding
ZETH PARINDING. Potensi dan Karakteristik Bio-ekologis Tumbuhan Myrmecodia spp. di Taman Nasional Wasur Merauke Papua. Dibimbing oleh SISWOYO dan AGUS PRIYONO KARTONO.
Tumbuhan sarang semut termasuk salah satu spesies tumbuhan obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tumbuhan tersebut di Taman Nasional Wasur Merauke belum dilakukan upaya pembudidayaan dan pemanenannya masih dilakukan dari alam. Informasi tenang potensi dan karakteristik bio-ekologis belum tersedia dan teknik pengelolaannya bagi ketersediaan di alam dan budidayanya belum tersedia.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengidentifikasi bio-ekologis tumbuhan obat sarang semut, (2) menentukan potensi tumbuhan obat sarang semut berdasarkan tipe penutupan lahan di TN Wasur, (3) menentukan interaksi karakteristik bio-ekologis dengan kerapatan tumbuhan sarang semut di kawasan TN Wasur, dan (4) menentukan preference tumbuhan sarang semut terhadap jenis tumbuhan inang..
Dalam penelitian ini peubah yang diamati dan diukur adalah diameter jenis vegetasi tingkat pohon tumbuhan inang, diameter jenis vegetasi tingkat pohon tumbuhan inang, diameter jenis vegetasi tingkat pohon tumbuhan inang, kerapatan tumbuhan habitus epifit, kerapatan tingkat pohon tumbuhan inang, kerapatan tingkat tiang tumbuhan inang, kerapatan tingkat pancang tumbuhan inang, jumlah spesies tumbuhan inang tingkat pohon, tiang dan pancang dan persentase keterbukaan tajuk.
Metode pengambilan data menggunakan metode gabungan (metode jalur-garis berpetak) dan metode analisis data menggunakan Analisa vegetasi (kerapatan, frekuensi, dominansi dan indeks nilai penting), indeks Morisita untuk uji pola sebaran, Indeks Keragaman Shannon-Wiener untuk uji nilai keanekaragaman, Indeks Neu uji untuk uji tingkat kesukaan, Analisis Sidik Ragam menggunakan software SPSS 12 meliputi analisis faktor dan analisis regresi stepwise.
Hasil penelitian berhasil menemukan, hal-hal sebagai berikut: 1. karakteristik bio-ekologis tumbuhan sarang semut banyak ditemukan pada: (a) hutan dataran rendah, (b) Keterbukaan tajuk antara 41,0 % - 51,0 %, (c) kerapatan tumbuhan inang antara 284 individu/ha sampai dengan 2.840 individu/ha, (d) cominansi tumbuhan inang antara 4,00 m2/ha sampai dengan 6,51 m2/ha, (e) Nilai keanekaragaman tumbuhan inang pada tingkat pertumbuhan pohon sebesar 2,7411, tingkat tiang sebesar 2,8393 dan tingkat pancang sebesar 2,5879, (f) Arah sebelah Timur tumbuhan inang, (g) kelima tipe penutupan lahan adalah jenis Myrmecodia pendans, Myrmecodia albertsii, Myrmecodia tuberosa dan
Hydnophitum formicum dan (h) Pola sebaran yang bergerombol/mengelompok
sarang semut yang dibagi kedalam 2 (dua) genus yakni 1) genus Myrmecodia, yaitu Myrmecodia pendans, Myrmecodia albertsii, Myrmecodia tuberosa,
Myrmecodia sp1, Myrmecodia sp2, Myrmecodia sp3, Myrmecodia sp4,
Myrmecodia sp5, Myrmecodia sp6, Myrmecodia sp7, Myrmecodia sp8,
Myrmecodia sp9, Myrmecodia sp10 dan Myrmecodia sp11, 2) genus Hydnophytum,
yaitu Hydnophytum formicum, Hydnophytum sp1, Hydnophytum sp2, dan
Hydnophytum sp3, (b) Kerapatan tumbuhan sarang semut antara 1.387 individu/ha
sampai dengan 1.697 individu/ha, (c) Jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan pada kelima tipe penutupan lahan di TN Wasur Merauke sebanyak 86 jenis, 73 genus dan 36 famili, dan (d) berhasil ditemukan 3 jenis semut yang bersimbiosis dengan tumbuhan sarang semut yakni Ochetelus sp, Iridomyrmex sp1, dan
Iridomyrmex sp2serta 1 jenis rayap. 3. Interaksi antara karakteristik bio-ekologis
dengan kerapatan tumbuhan sarang semut, dilakukan dengan cara menentukan a) Faktor dominan komponen tipe penutupan lahan diperoleh hasil persamaan regresi linier, yaitu: Y = -3,761 + 26,281 X8 artinya bahwa apabila peningkatan jumlah spesies tumbuhan inang tingkat pohon, tiang dan pancang (X8) sebesar 1 unit akan meningkatkan kerapatan tumbuhan sarang semut (Y) sebesar 26,281 individu/hektar. Jadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kerapatan tumbuhan sarang semut adalah jumlah spesies tumbuhan inang tingkat pohon, tiang dan pancang, namun secara keseluruhan semua faktor (delapan peubah lainnya berpengaruh). b) Preferensial tumbuhan sarang semut terhadap tumbuhan inang dari ke-18 jenis yang berada di kawasan TN Wasur Merauke lebih menyukai jenis-jenis tumbuhan inang dari famili Myrtaceae (Melaleuca cajuputi, Melaleuca leucadendron dan Melaleuca symphiocarpa) dan famili Mimosaceae (Acacia auriculiformis) dan tumbuhan sarang semut lebih menyukai hutan dataran rendah. dan 4. Preferensi tumbuhan sarang semut lebih menyukai hutan dataran rendah dan jenis paling disukai dari 24 jenis tumbuhan inang yang ada adalah jenis Melaleuca cajuputi.
ZETH PARINDING. The Potential and Bio-ecological Characteristics of “Sarang Semut” Plant in Wasur National Park, Merauke Papua. Under supervised by SISWOYO and AGUS PRIYONO KARTONO.
The medicinal plant spesies of “sarang semut” can be found in Wasur National Park, Merauke-Papua, but its potential and bio-ecological characteristics are not known yet. The aims of this research are : a) to identify the bio-ecological parameters of “sarang semut” species; b) to determine the numbers of “sarang semut” species based on land cover in Wasur National Park; c) to determine the interaction between bio-ecological characteristics and density of “sarang semut” in Wasur National Park; and d) to determine preference “sarang semut” at host plat species.
The research were conducted from May to June 2007. In this research had observed 18 spesies of “sarang semut”, that consist of 2 genera of Myrmecodia (with 14 species) and of Hydnophytum (with 4 species). “Sarang semut” can be found in lowland forest, as well as in the garden, mangrove forest, swamp forest and savannah. Preference host plant species are genera Myrtaceae (Melaleuca cajuputi, Melaleuca leucadendron dan Melaleuca symphiocarpa) and genera Mimosaceae (Acacia auriculiformis). “Sarang semut” in TN Wasur Merauke be found is more at: lowland forest, Canopy Covered between 41,0 % up to 51,0%, Closeness of host plant between 284 pcs/acre up to 2.840 pcs/acre, Diversity value of host plant at level of growth of tree equal to 2,7411, level of pole equal to 2,8393 and level of sapling equal to 2,5879 and distribution pattern in general at fifth of type of canopy cover of lowland forest, as well as in the garden, mangrove forest, savannah and swamp forest are clumped.
@ Hak Cipta Milik Zeth Parinding, tahun 2007 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
mencantumkan atau menyebut sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Zeth
Parinding.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh
TUMBUHAN SARANG SEMUT
DI TAMAN NASIONAL WASUR MERAUKE PAPUA
ZETH PARINDING
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi pada
Sub Program Konservasi Keanekaragaman Hayati, Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TUMBUHAN SARANG SEMUT DI TAMAN NASIONAL WASUR MERAUKE PAPUA
Nama : ZETH PARINDING
NRP : E. 051054145
Program Studi : Ilmu Pengetahuan Kehutanan
Sub Program Studi : Konservasi Keanekaragaman Hayati
Disetujui, Komisi Pembimbing
Ir. Siswoyo, MSi Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, MSi
Ketua Anggota
Diketahui,
Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana
Ilmu Pengetahuan Kehutanan
Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
segala Karunia-Nya sehingga penyusunan tesis berjudul “Potensi dan
Karakteristik Bio-ekologis Tumbuhan Sarang Semut di Taman Nasional Wasur
Merauke Papua” dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan di TN Wasur dan masyarakat di dalam dan di
sekitarnya.
Tesis ini menguraikan tentang bagaimana mengidentifikasi bio-ekologis
tumbuhan sarang semut, menentukan potensi tumbuhan obat sarang semut
berdasarkan tipe penutupan lahan di TN Wasur dan menentukan hubungan
karakteristik bio-ekologis dengan kerapatan tumbuhan sarang semut di kawasan
TN Wasur.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, baik isi
maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan tesis in.
Bogor, Desember 2007
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya
ditujukan kepada Bapak Ir. SISWOYO, MSi selaku ketua komisi pembimbing dan
Bapak Dr. Ir. AGUS PRIYONO KARTONO, MSi selaku anggota komisi
pembimbing yang telah bekerja keras memberikan bimbingan dengan penuh
kesabaran, serta Dr. Ir. H. YANTO SANTOSA, DEA sebagai penguji di luar
komisi pembimbing yang telah menguji dan memberikan masukan terhadap
penyempurnaan tesis ini.
Terima kasih penulis tujukan kepada ibunda, kakak, adik, isteri terkasih dan
anak-anak tercinta yang telah memberikan memberikan dukungan moral serta
material selama belajar di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Pada kesempatan ini penulis sampaikan juga terima kasih kepada Sekretaris
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen
Kehutanan, yang telah memberikan kesempatan berupa beasiswa untuk
mengikuti pendidikan pascasarjana, Dekan Sekolah Pascasarjana beserta staf atas
fasilitas yang diberikan selama pendidikan, Kepala Balai TN Wasur Merauke
Papua beserta staf atas semua bantuannya dan teman-teman, kerabat dan relasi
yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah
RIWAYAT HIDUP
Penulis adalah putra keempat dari lima bersaudara, dari
keluarga sederhana pasangan bapak M.L. Parinding
(almarhum) dan ibu Ch. Parinding Tarukla’bi. Penulis
dilahirkan di Kota Manokwari pada tanggal 19 Oktober
1972 dan menikah dengan Istri Helena T. Kaseroan pada
tahun 2000. Saat ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu
Mega Citra Parinding (6 tahun) dan Dwi Miryam I.
Kaseroan (4 tahun).
Penulis masuk Sekolah Dasar pada tahun 1979 di tiga sekolah dasar yakni
SD Negeri Kota di Manokwari, SD Negeri Kotaraja di Jayapura dan SD Negeri
VIM III Kotaraja Dalam di Jayapura dan lulus pada tahun 1985. Sekolah
Menengah Pertama pada tahun 1985 di SMP YPK Diaspora Kotaraja Dalam di
Jayapura dan lulus pada tahun 1988. Sekolah Menengah Atas pada tahun 1988 di
dua sekolah menengah atas yakni SMA Negeri I Abepura di Jayapura dan SMA
Negeri 2 Ujung pandang di Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1991. Pada
tahun 1992 penulis diterima di Fakultas Pertanian, Universitas Cenderawasih
Manokwari dan lulus pada tahun 1998.
Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan dan pelatihan Jagawana selama 6
bulan di Pusdik Brimob Watukosek Surabaya dan Pusdiklat Kehutanan Kadipaten
Majalengka. Tahun 1999 bekerja di Taman Nasional Wasur Merauke terhitung
mulai bulan Maret 1999. Selain tugas utama sebagai polisi hutan (jagawana)
dipercayakan mengemban tugas sebagai koordinator administrasi umum Polhut
Balai TN Wasur, plt kasanit polhut, plt sub seksi wilayah konservasi dan seksi
konservasi wilayah, wakil komandan polhut Balai TN Wasur. Penulis adalah
anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Departemen Kehutanan.
Tujuh tahun kemudian, yaitu bulan Juni 2006, penulis mendapat
kesempatan berupa beasiswa dari Departemen Kehutanan untuk mengikuti
program Magister Profesi (S2) pada Sub Program Studi Konservasi
Keanekaragaman Hayati dan Ekowisata, Program Studi Ilmu Pengetahuan
MOTTO
Kemampuan dan ketidakmampuan seseorang adalah proses karena ruang, waktu dan kesempatan, namun tingkatkan terus hasil dan karya yang dimiliki dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan ini.
Kembangkan budi luhur Saudara yang ada, baik telah diketahui maupun belum diketahui bagi kesetimbangan alam ini.
Sesuatu obsesi perlu digali dan dikembangkan secara bersama-sama dengan kemampuan dan ketidakmampuan, bukan saling menghancurkan atau merugikan orang lain.
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ... i
DAFTAR TABEL ... iii
DAFTAR GAMBAR ………... v
DAFTAR LAMPIRAN ………... vii
PENDAHULUAN ……….... 1
Latar Belakang ………...……….. 1
Tujuan Penelitian ………...……… 2
Manfaat Penelitian ………...……….. 2
TINJAUAN PUSTAKA ……… 3
Deskripsi Tumbuhan Sarang Semut ... 3
Taksonomi ………...………... 3
Ciri Morfologi ... 3
Umbi ... 4
Batang ... 4
Daun ... 4
Bunga ... 5
Penyebaran dan Ekologi Tumbuhan Sarang Semut ... 5
Penyebaran tumbuhan sarang semut ... 5
Ekologi tumbuhan sarang semut ... 6
Kandungan Kimia dan Kegunaan Tumbuhan Sarang Semut ... 6
Flavonoid ... 7
Tanin ... 8
Perkembangbiakan/Perbanyakan Tumbuhan Sarang Semut .... 10
Pertumbuhan Tumbuhan Sarang Semut ... 10
Pengertian Pertumbuhan ... 10
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman .... 12
Faktor genetik ... 12
Faktor lingkungan ... 14
Pengaruh Manusia ... 22
KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ... 24
Sejarah Kawasan ... 24
Letak dan Luas ... 25
Topografi ... 25
ii
Geologi dan Tanah ... 26
Geologi ... 26
Tanah ... 27
Formasi Vegetasi di Dalam Kawasan Taman Nasional Wasur ... 28
METODOLOGI PENELITIAN ………...……… 30
Tempat dan Waktu Penelitian ………...……… 30
Peralatan dan Bahan ………..……… 30
Jenis Data yang Dikumpulkan ……...……….. 31
Perumusan Masalah ………...……… 31
Kerangka Pemikiran ………....………. 32
Metode Pengumpulan Data ………..………… 34
Metode Analisis Data ... 39
Analisis Vegetasi ... 39
Preferensial Tumbuhan inang ... 40
Analisis Nilai Keanekaragaman ... 41
Analisis Pola Sebaran Spesies Sarang semut ... 41
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 44
Karakteristik Kondisi Bio-ekologis Tumbuhan Sarang Semut ... 44
Stratifikasi Janis Tumbuhan ... 44
Keterbukaan Tajuk Jenis Tumbuhan ... 52
Jumlah Jenis Tumbuhan ... 53
Kerapatan Jenis Tumbuhan ... 55
Dominansi Jenis Tumbuhan ... 59
Keanekaragaman Jenis Tumbuhan ... 64
Pola Penyebaran Jenis Tumbuhan ... 65
Potensi Tumbuhan Sarang Semut ... 68
Jumlah Jenis Tumbuhan Sarang Semut ... 68
Kerapatan Tumbuhan Sarang Semut ... 81
Jenis-Jenis Semut pada Tumbuhan Sarang Semut ... 82
Potensi yang Menambah Khasanah tentang Tumbuhan Sarang Semut ... 85
Gangguan Manusia ... 88
Interaksi Karakteristik Bio-ekologis dengan Kerapatan Tumbuhan Sarang Semut ... 89
Preferensi Tumbuhan Sarang Semut pada Tumbuhan Inang …… 92
SIMPULAN DAN SARAN ... 94
DAFTAR PUSTAKA ... 96
DAFTAR TABEL
No. Halaman
1. Jenis-jenis tumbuhan sarang semut di Indonesia ... 3
2. Komposisi dan kandungan senyawa aktif tumbuhan sarang semut .. 7
3. Beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan
senyawa aktif yang berperan menaklukan penyakit ... 9
4. Data sekunder studi interaksi kondisi karakteristik bio-ekologis
dengan potensi tumbuhan sarang semut di TN. Wasur ... 34
5. Pemanen dari ke-empat sub-sub suku di dalam kawasan TN. Wasur. 35
6. Banyaknya jalur pengamatan ... 36
7. Kriteria yang diukur pada metode Neu versi Manly et al. (1993) .... 40
8. Stratifikasi tajuk pohon pada tipe penutupan lahan di TN Wasur
Merauke ... 44
9. Persentase rata-rata keterbukaan tajuk tumbuhan pada tingkat
pohon, tiang dan pancang pada tipe penutupan lahan ... 52
10.Jumlah jenis tumbuhan pada tipe penutupan lahan ... 53
11.Kerapatan tumbuhan tingkat pohon, tiang dan pancang pada
beberapa tipe penutupan lahan ... 55
12.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di hutan dataran rendah ... 56
13.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di lahan pekarangan kebun ... 57
14.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di hutan mangrove ... 57
15.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di hutan rawa ... 58
16.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di savana ... 58
17.Dominansi tumbuhan tingkat pohon, tiang dan pancang pada
beberapa tipe penutupan lahan ... 59
18.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di hutan dataran rendah ... 60
19.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di lahan pekarangan kebun ... 61
20.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
iv
No. Halaman
21.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di hutan rawa ... 62
22.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat
pertumbuhan di savana ... 62
23.Keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan pada tipe penutupan lahan .. 64
24.Pola sebaran jenis-jenis tumbuhan pada tipe penutupan lahan ... 65
25.Jumlah jenis-jenis tumbuhan sarang semut pada tipe penutupan
lahan ... 68
26.Kerapatan tumbuhan sarang semut pada tipe penutupan lahan ... 81
27.Kerapatan tumbuhan sarang semut berdasarkan posisi Barat -
Timur pada beberapa tipe penutupan lahan ... 82
28.Pemanenan dan persepsi responden terhadap keberadaan tumbuhan
sarang semut ... 88
29.Preferensi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang di kelima
tipe penutupan lahan ……… 93
30.Preferensi tumbuhan sarang semut tanpa membedakan tipe
DAFTAR GAMBAR
No. Halaman
1. Peta lokasi penelitian tumbuhan sarang semut di TN Wasur
Merauke Papua ... 30
2. Kerangka pemikiran penelitian potensi dan karakteristik bio-ekologis tumbuhan sarang semut di TN Wasur Merauke Papua .... 33
3. Skema penempatan transek dan petak-petak pengukuran pada analisis vegetasi dengan metode jalur-garis berpetak ... 35
4. Teknik proyeksi diagram profil arsitektur pohon ... 38
5. Cara penentuan posisi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang ... 39
6. Profil arsitektur pohon di hutan dataran rendah tidak terganggu ... 45
7. Profil arsitektur pohon di hutan dataran rendah terganggu ... 46
8. Profil arsitektur pohon di lahan pekarangan kebun tidak terganggu .. 46
9. Profil arsitektur pohon di lahan pekarangan kebun terganggu ... 47
10.Profil arsitektur pohon di hutan mangrove tidak terganggu ... 48
11.Profil arsitektur pohon di hutan mangrove terganggu ... 49
12.Profil arsitektur pohon di hutan rawa tidak terganggu ... 49
13.Profil arsitektur pohon di hutan rawa terganggu ... 50
14.Profil arsitektur pohon di savana tidak terganggu ... 51
15.Profil arsitektur pohon di savana terganggu ... 52
16.Myrmecodia pendans ... 69
17. Myrmecodia albertsii ... 70
18. Myrmecodia tuberosa ... 71
19. Myrmecodia sp1 ... 71
20. Myrmecodia sp2 ... 72
21. Myrmecodia sp3 ... 73
22. Myrmecodia sp4 ... 73
23. Myrmecodia sp5 ... 74
24. Myrmecodia sp6 ... 75
25.Myrmecodia sp7 ... 75
26.Myrmecodia sp8 ... 76
vi
No. Halaman
28.Myrmecodia sp10 ... 77
29.Myrmecodia sp11 ... 78
30.Hydnophytum formicum ... 79
31. Hydnophytum sp1 ... 79
32. Hydnophytum sp2 ... 80
33. Hydnophytum sp3 ... 80
34. Jenis semut Ochetellus sp ... 83
35. Jenis semut Iridomyrmex sp1 ... 83
36. Jenis semut Iridomyrmex sp2 ... 84
37. Jenis rayap sp1 ... 84
38. Bentuk tumbuhan sarang semut berukuran kecil (diameter ± 1 cm)... 85
39. Pengkristalan batu, adanya katak dan ulat pada tumbuhan obat sarang semut ... 86
40. Tumbuhan sarang semut yang dapat tumbuh pada tumbuhan liana dan batang pohon yang bertekstur tidak kasar (Eucalypthus spp) .... 87
41. Tumbuhan sarang semut dan anggrek yang berdampingan ... 87
DAFTAR LAMPIRAN
No. Halaman
1. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan dataran rendah tidak
terganggu ... 100
2. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan dataran rendah terganggu .... 102
3. Indeks nilai penting tumbuhan di lahan pekarangan kebun tidak terganggu ... 104
4. Indeks nilai penting tumbuhan di lahan pekarangan kebun terganggu ... 105
5. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan mangrove tidak terganggu ... 106
6. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan mangrove terganggu ... 108
7. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan rawa tidak terganggu ... 110
8. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan rawa terganggu ... 111
9. Indeks nilai penting tumbuhan di savana tidak terganggu ... 112
10.Indeks nilai penting tumbuhan di savana terganggu ... 113
11.Preferensi tumbuhan Myrmecodia pendans pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 114
12.Preferensi tumbuhan Myrmecodia albertsii pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 115
13.Preferensi tumbuhan Myrmecodia tuberosa pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 116
14.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp1 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 117
15.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp2 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 118
16.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp3 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 119
17.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp4 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 120
18.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp5 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 121
19.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp6 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 122
viii
No. Halaman
21.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp8 pada tumbuhan inang di
kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 124
22.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp9 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 125
23.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp10 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 126
24.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp11 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 127
25.Preferensi tumbuhan Hydnophytum formicum pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua... 128
26.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp1 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 129
27.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp2 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 130
28.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp3 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 131
29.Preferensi tumbuhan Myrmecodia pendans pada tumbuhan inang .. 132
30.Preferensi tumbuhan Myrmecodia albertsii pada tumbuhan inang .. 134
31.Preferensi tumbuhan Myrmecodia tuberosa pada tumbuhan inang .. 136
32.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp1 pada tumbuhan inang ... 138
33.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp2 pada tumbuhan inang ... 140
34.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp3 pada tumbuhan inang ... 142
35.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp4 pada tumbuhan inang ... 144
36.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp5 pada tumbuhan inang ... 146
37.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp6 pada tumbuhan inang ... 148
38.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp7 pada tumbuhan inang ... 150
39.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp8 pada tumbuhan inang ... 152
40.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp9 pada tumbuhan inang ... 154
41.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp10 pada tumbuhan inang ... 156
ix
No. Halaman
43.Preferensi tumbuhan Hydnophytum formicum pada tumbuhan
inang ... 160
44.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp1 pada tumbuhan inang ... 162
45.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp2 pada tumbuhan inang ... 164
46.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp3 pada tumbuhan inang ... 166
47.Preferensi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang di
kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 168
48.Preferensi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang di kelima
tipe penutupan lahan ... 169
49.Hasil analisis faktor terhadap ke-9 peubah ... 171
Latar Belakang
Menurut Primack et al. (1998), Indonesia termasuk negara yang memiliki
kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brasil. Diperkirakan
jumlah spesies pada takson tumbuhan berbunga yang terdapat di Indonesia
sebesar 10% atau sebanyak 25.000 jenis, sedangkan di dunia terdapat sebanyak
250.000 jenis. Diantara jenis tumbuhan berbunga yang terdapat di Indonesia,
1.845 jenis diantaranya diketahui berkhasiat sebagai obat; yang telah
dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh berbagai
etnis di Indonesia (Zuhud dan Siswoyo 2003). Salah satu jenis tumbuhan obat
tersebut adalah sarang semut (Myrmecodia spp.).
Pada kawasan Taman Nasional Wasur (TN Wasur), terdapat masyarakat
adat yang terdiri atas sub-sub Suku yakni Suku Marind, Kanume, Marori
Men-Gey dan Yeinan. Sampai saat ini kearifan tradisional mereka dalam
memanfaatkan dan menggunakan tumbuhan sarang semut tersebut belum banyak
dipelajari.
Pemanfaatan tumbuhan sarang semut oleh masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan TN Wasur masih mengandalkan pada ketersediaan di alam.
Pemungutan secara langsunng dari alam dikhawatirkan dapat mengakibatkan
penurunan populasi alami dalam waktu yang cepat.
Salah satu tahapan kelestarian sarang semut di habitat alaminya secara garis
besar dipengaruhi oleh 2 (tiga) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal
(lingkungan tempat tumbuhnya dan manusia). Faktor internal yang berpengaruh
terhadap kelestarian jenis sarang semut di habitat alaminya adalah jenis atau
varietas; sedangkan faktor lingkungan yang berpengaruh, antara lain: karakteristik
bio-ekologis (fisik, kimia, dan biologi) dan manusia yang memanennya. Jika data
dan informasi tentang potensi dan karakteristik bio-ekologis sarang semut
diketahui oleh masyarakat luas (pendatang dan pemilik hak ulayat) baik di dalam
maupun sekitar TN Wasur, maka diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang
2
Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian tentang potensi dan
karakteristik bio-ekologis tumbuhan sarang semut untuk mendukung
ketersediaannya sehingga mendukung informasi tentang kesesuaian kondisi
bio-ekologis tumbuhan obat sarang semut dan teknik pembudidayaannya. Upaya
pengelolaan dan pembudidayaan tumbuhan sarang semut tersebut dimaksudkan
untuk dapat mengantisipasi tingginya tingkat permintaan akan tumbuhan sarang
semut dan akibat yang ditimbulkan dengan ketersediaannya di alam. Hal ini
berarti perlu studi untuk mempelajari potensi dan karakteristik bio-ekologis
tumbuhan obat sarang semut.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengidentifikasi
bio-ekologis tumbuhan sarang semut, (2) menentukan potensi tumbuhan sarang semut
berdasarkan tipe penutupan lahan di TN Wasur, (3) menentukan interaksi
karakteristik bio-ekologis dengan kerapatan tumbuhan sarang semut di kawasan
TN Wasur dan (4) menentukan preferensi tumbuhan sarang semut terhadap jenis
tumbuhan inang.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat a) sebagai data
dan informasi guna menyusun pengelolaan tumbuhan obat sarang semut di TN
Wasur secara lestari sehingga keberadaan tumbuhan obat sarang semut di habitat
alaminya akan tetap lestari serta pemanfaatannya dapat dilakukan secara terus
menerus dan (b) bagi masyarakat di dalam dan di sekitar TN Wasur, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemanenan
Deskripsi Tumbuhan Sarang Semut
Taksonomi
Menurut Subroto dan Hendro (2006), secara taksonomi tumbuhan sarang
semut (Myrmecodia spp.) termasuk dalam Divisi Tracheophyta, Kelas
Magnoliopsida, Sub Kelas Lamiidae, Ordo Rubiales, Famili Rubiaceae, dan
Genus Myrmecodia. Tumbuhan sarang semut yang terdapat di Indonesia terdiri
atas 26 spesies seperti disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan sarang semut di Indonesia
Nama Spesies Nama Spesies
M. pendans Merr. & L.M. Perry M. agustifolia Valeton
M. tuberosa Jack M. strerrophylla Merr. & Perry
M. kutubuensis Huxley & Jebb M. oksapminensis Hxley & Jebb
M. jobiensis Becc M. paradoxa Huxley & Jebb
M. erinacea Becc M. aureospina Huxley & Jebb
M. alata Becc M. brassii Merr. & Perry
M. beccerii J.D. Hooker M. lamii Merr. & Perry
M. platytyrea Becc M. archboldiana Merr. & Perry
M. longissima Valeton M. pteroaspida Huxley & Jebb
M. oblongata Valeton M. melanacantha Huxley & Jebb
M. longifolia Valeton M. horrida Huxley & Jebb
M. schlechteri Valeton M. ferox Huxley & Jebb
M. albertisii Becc. M. gracilispina Huxley & Jebb
Sumber : Subroto dan Hendro 2006
Ciri Morfologi
Berdasarkan Kamus Pertanian Umum tahun 2001 yang dimaksudkan
morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk dari susunan dan
4
dalam pengenalan tumbuhan sarang semut dibedakan dalam beberapa kriteria
yaitu: umbi, batang, daun dan bunga.
Umbi
Tjitrosoepomo (2000), umbi biasanya merupakan suatu badan yang
membengkak, bangun bulat seperti kerucut atau tidak beraturan, merupakan
tempat penimbunan makanan seperti rimpang dan dapat merupakan penjelmaan
batang atau akar. Umbi pada tumbuhan sarang semut umumnya hampir selalu
berduri dan berbentuk bulat saat muda, kemudian berubah menjadi lonjong
memendek atau berbentuk memanjang setelah tua. Umbi sarang semut memiliki
sistem jaringan yang lubang-lubang serta interkoneksi jaringan yang sangat khas.
Sistem jaringan tersebut dapat digunakan untuk menentukan genus ini (Subroto
dan Hendro 2006).
Batang
Tjitrosoepomo (2000) menyatakan bahwa batang merupakan bagian tubuh
tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi
tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Tim
Penyusun Kamus PS (2001), Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang berasal
dari epikotil dan tumbuh di atas permukaan tanah walaupun ada jenis yang
tumbuh di dalam tanah; memiliki struktur pembentuk batang seperti floem dan
xilem; biasanya berbuku dan beruas; selalu tumbuh mengarah ke atas dan mencari
arah datangnya sinar matahari; dapat tumbuh tegak menggantung, memanjat,
membelit, mengangguk, menjangkit; berfungsi sebagai pendukung dan tempat
tumbuhnya bagian tanaman yang ada di atas tanah, sebagai lalu lintas air dan zat
makanan dari daun ke seluruh tubuh tanaman, sebagai tempat penimbunan zat
makanan cadangan, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan sarang
semut biasanya hanya memiliki satu atau beberapa batang yang bercabang.
Batang tebalnya dan internodanya sangat dekat, kecuali pada pangkal sarang
semut dari beberapa spesies (Subroto dan Hendro 2006).
Daun
Menurut Subroto dan Hendro (2006), daun sarang semut tebal seperti kulit.
(penumpu) besar, persisten, terbelah dan berlawanan dengan tangkai daun (petiol),
serta membentuk “telinga” pada klipeoli. Kadang-kadang terus berkembang
menjadi sayap di sekitar bagian atas klipeolus.
Bunga
Menurut Tjitrosoepomo (2000), bunga adalah penjelmaan suatu tunas
(batang dan daun-daun) yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan
kepentingan tumbuhan, sehingga pada bunga ini dapat berlangsung penyerbukan
dan pembuahan, dan akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan.
Menurut Tjitrosoepomo (2000) bahwa daun merupakan suatu bagian tumbuhan
yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun.
Alat ini hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian
lain pada tubuh tumbuhan. Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa
pembungaan pada sarang semut mulai sejak beberapa ruas (internoda) terbentuk
dan ada pada tiap nodus (buku). Dua bagian pada setiap bunga berkembang pada
suatu kantong udara (alveolus) yang berbeda. Alveoli tersebut mungkin
ukurannya tidak sama dan terletak pada tempat yang berbeda di batang. Kuntum
bunga muncul pada dasar alveoli. Setiap bunga berlawanan oleh suatu brakteola.
Bunga jarang kleistogamus (menyerbuk tidak terbuka) dan kadang-kadang
heterostilus. Kelopak biasanya terpotong. Polen adalah 1-, 2-, atau 3- porat
(kolporat) dan sering 1, 2, atau 3 visikel sitoplasma yang besar. Buah berkembang
dalam alviolus dan memanjat pada dasarnya menjadi menonjol keluar hanya
setelah masak.
Penyebaran dan Ekologi Tumbuhan Sarang Semut
Penyebaran Tumbuhan Sarang Semut
Menurut Subroto dan Hendro (2006), penyebaran tumbuhan sarang semut
mulai dari Semenanjung Malaysia, Filipina, Kamboja, Sumatera, Kalimantan,
Jawa, Papua, Papua New Guinea, Cape York hingga Kepulauan Solomon. Di
Propinsi Papua, tumbuhan sarang semut dapat dijumpai terutama di daerah
Pegunungan Tengah, yaitu di hutan belantara Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan
6
Salah satu lokasi penyebaran jenis tumbuhan tersebut di Papua, tumbuhan ini juga
ditemukan di hutan dataran rendah di wilayah Kabupaten Bintuni, Fak-fak dan
Sorong..
Ekologi Tumbuhan Sarang Semut
Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa tumbuhan sarang semut
tersebar dari hutan mangrove dan pantai hingga ketinggian 2.400 m di atas
permukaan laut (dpl). Sarang semut banyak ditemukan menempel di beberapa
pohon, umumnya di pohon kayu putih (Melaleuca), cemara gunung (Casuarina),
kaha (Castanopsis), dan pohon beech (Nothofagus). Sarang semut jarang
menempel pada pohon-pohon dengan batang halus dan rapuh seperti Eucalyptus.
Di habitat liarnya, tumbuhan sarang semut dihuni oleh beragam jenis semut.
Setiap tumbuhan obat sarang semut hanya dihuni oleh satu jenis semut. Secara
umum ditemukan tiga spesies semut yang menghuni tumbuhan sarang semut dari
genus Iridomyrmex, salah satu diantaranya adalah jenis Iridomyrmex cordatus.
Sebagai contoh, tumbuhan obat sarang semut (Myrmecodia pendans Merr. &
Perry) dihuni oleh koloni semut dari jenis Ochetellus sp. Selain itu, pada umbi
sarang semut juga ditemukan dua spesies jamur ketika dihuni oleh simbion
Iridomyrmex cordatus (Subroto dan Hendro 2006).
Kandungan Kimia dan Kegunaan Tumbuhan Sarang Semut
Berdasarkan aspek pemanfaatan untuk pengobatan maka tumbuhan sarang
semut memiliki berbagai kandungan senyawa kimia. Kandungan senyawa kimia
dari tumbuhan sarang semut diduga memiliki peranan dalam aktivitas resistensi
patogen, alelopati dan pertahanan tubuh terhadap serangan hama. Senyawa yang
mendapat perhatian luas adalah tiga golongan senyawa fenolik, yaitu tanin
terhidrolisa, flavonoid dan tanin terkondensasi. Senyawa-senyawa tersebut
digunakan oleh tanaman sebagai sistem pertahanan diri, sedangkan bagi manusia
dimanfaatkan sebagai bahan aktif untuk obat.
Berdasarkan hasil uji penapisan kimia dari tumbuhan obat sarang semut
yang dilakukan oleh Subroto dan Hendro (2006) menunjukkan bahwa tumbuhan
Parameter Satuan Nilai
Energi Kkal/100g 350,52
Kadar air g/100g 4,54
Kadar abu g/100g 11,13
Kadar lemak g/100g 2,64
Kadar protein g/100g 2,75
Kadar karbohidrat g/100g 78,94
Tokoferol mg/100g 31,34
Total fenol g/100g 0,25
Kalsium (Ca) g/100g 0,37
Natrium (Na) mg/100g 68,58
Magnesium (Mg) g/100g 1,50
Kalium (K) g/100g 3,61
Seng (Zn) mg/100g 1,36
Besi (Fe) mg/100g 29,24
Fosfor (P) g/100g 0,99
Komposisi dan kandungan senyawa aktif tumbuhan obat sarang semut seperti
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Komposisi dan kandungan senyawa aktif tumbuhan sarang semut
Sumber : Subroto dan Hendro (2006)
Kandungan senyawa-senyawa kimia dari golongan flavonoid dan tanin
memiliki peran sebagai berikut
Flavonoid
Vickery & Vickery (1981) menyatakan bahwa flavonoid pada tumbuhan
dapat meningkatkan dormansi, meingkatkan pembentukan sel-sel kalus, sebagai
enzim penghambat pembentukan protein, menghasilkan zat warna pada bunga
untuk merangsang serangga, burung dan satwa lainnya untuk mendatangi
tumbuhan tersebut sebagai agen dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Dalam
dunia pengobatan beberapa jenis senyawa flavonoid berfungsi sebagai zat
antibiotik, misalnya anti virus dan jamur, peradangan pembuluh darah dan dapat
digunakan sebagai racun ikan.
Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa flavonoid merupakan
golongan senyawa bahan alami dari senyawa fenolik yang merupakan unsur
pigmen tumbuhan. Saat ini lebih dari 6.000 senyawa yang berbeda masuk ke
dalam golongan flavonoid. Flavonoid merupakan bagian penting dari manusia
8
tubuh manusia adalah sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan
kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel,
memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C (meningkatkan efektivitas vitamin
C), anti-inflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik.
Selain itu flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik
dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus.
Fungsi flavonoid sebagai antivirus telah banyak dipublikasikan, termasuk untuk
virus HIV (AIDS) dan virus herpes. Flavonoid juga berperan dalam pencegahan
dan pengobatan beberapa penyakit lain seperti asma, katarak, diabetes,
encok/rematik, migrain, wasir dan periodontitis (radang jaringan ikat penyangga
akar gigi). Flavonoid ternyata bukan untuk pencegahan saja tetapi dapat juga
sebagai pengobat kanker (Subroto dan Hendro 2006).
Tanin
Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa tanin merupakan astringen
dan polifenol tanaman berasa pahit yang dapat mengikat dan mengendapkan
protein. Umumnya tanin digunakan untuk penyamakan kulit, tetapi tanin juga
banyak aplikasinya dibidang pengobatan misalnya untuk pengobatan diare,
hemostatik (menghentikan pendarahan) dan wasir. Kemampuan sarang semut
secara empiris untuk pengobatan ambeien (wasir) dan mimisan diduga kuat
berkaitan dengan kandungan taninnya.
Tumbuhan sarang semut kaya akan antioksidan tokoferol (vitamin E) dan
beberapa mineral penting untuk tubuh seperti kalsium, natrium, kalium, seng,
besi, fosfor dan magnesium. Dalam sistem metabolisme tubuh, kalsium berfungsi
dalam kerja jantung, impuls saraf dan pembekuan darah. Besi berfungsi dalam
pembentukan hemoglobin, transfer oksigen dan aktivator enzim. Fosfor berfungsi
dalam memproduksi energi. Natrium memiliki peranan dalam kesetimbangan
elektrolit, volume cairan tubuh, dan impuls saraf. Kalium berfungsi dalam ritme
jantung, impuls saraf, dan keseimbangan asam-basa. Seng memiliki fungsi dalam
sintesis protein, fungsi seksual, penyimpanan insulin, metabolisme karbohidrat,
dan penyembuhan luka. Magnesium memiliki peranan dalam fungsi tulang, hati,
otot, transfer air intraseluler, keseimbangan basa, dan aktivitas neuromuskuler.
semut seperti untuk membantu mengatasi berbagai macam penyakit/gangguan
jantung, melancarkan darah, mengobati migren (sakit kepala sebelah), gangguan
fungsi ginjal dan prostat, memulihkan kesegaran dan stamina tubuh serta
memulihkan gairah seksual (Subroto dan hendro 2006).
Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa hasil analisis ekstrak
tumbuhan sarang semut yang dilakukan olehnya dapat menghambat aktivitas
enzim xanthin oxidase dengan aktivitas yang setara dengan allopurinol, obat
komersial yang digunakan untuk pengobatan asam urat, salah satu jenis penyakit
rematik. Diduga senyawa inhibitor xanthin oxidase yang bertanggung jawab
dalam mekanisme ini adalah senyawa dari golongan flavonoid. Fenomena ini
yang kemungkinan dapat memperkuat khasiat tumbuhan sarang semut untuk
pengobatan rematik yang telah terbukti secara empiris.
Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa secara empiris rebusan
bubuk tumbuhan sarang semut atau kapsulnya telah terbukti dapat menyembuhkan
beragam penyakit ringan dan berat seperti kanker dan tumor, asam urat, jantung
koroner, wasir, TBC, migren, rematik, dan leukemia. Mekanisme kerja
kandungan senyawa aktif sarang semut dalam mengobati berbagai penyakit
tersebut memang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa
penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan senyawa aktif yang berperan
menaklukan penyakit disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan senyawa aktif yang berperan menaklukan penyakit.
Jenis Senyawa Manfaat Pengobatan
Flavonoid Asma, katarak, diabetes, encok/rematik, migrain (sakit kepala sebelah),
periodontitis (radang jaringan ikat penyangga akar gigi), kanker dan tumor, gangguan jantung, terutama jantung koroner, stroke ringan dan berat, benjolan-benjolan dalam payudara bagi wanita (tanpa perlu diangkat melalui operasi), gangguan fungsi ginjal dan prostat, haid dan keputihan, melancarkan peredaran darah, penyakit lainnya seperti pegal-pegal, nyeri otot, sakit tulang, asam urat, melancarkan dan meningkatkan air susu ibu (ASI), mempercepat proses pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, memulihkan kewanitaan (sari rapet), memulihkan gairah seksual bagi pria maupun wanita, meningkatkan keperkasaan/kejantanan pria, memulihkan kesegaran dan stamina tubuh sepanjang hari.
Tanin Pengobatan diare, hemostatik (menghentikan pendarahan), wasir (ambeien)
baru maupun lama, gangguan alergi hidung, mimisan, bersin-bersin pada pagi hari atau pada perubahan cuaca, sakit maag, penyakit paru-paru.
Biji-biji tersebut disemai harus dalam bentuk biji segar dan dapat
10
kelapa lembab. Hipokotil atau batang bagian bawah setelah biji berkecambah
akan membengkak dengan cepat diikuti dengan pembentukan alur-alur pada
bagian dalam batang tersebut setelah beberapa bulan. Kecambah tumbuhan
sarang semut memerlukan kecukupan cahaya, bila kekurangan cahaya akan
menyebabkan tumbuhan memanjang dan bagian umbinya menciut serta lebih
banyak memiliki daun.
Perkembangbiakan/Perbanyakan Tumbuhan Sarang Semut
Menurut Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa tumbuhan sarang
semut dapat melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan banyak buah beri.
Buah beri tersebut berwarna merah atau orange ketika masak. Dalam setiap buah
beri umumnya terdapat dua biji. Di tempat yang sesuai, misalnya dalam pot yang
mengandung media sabut kelapa lembab, biji-biji tersebut akan berkecambah
dengan cepat. Biji-biji tersebut akan berkecambah apabila disemai dalam bentuk
biji yang sudah matang (tua) dan masih segar (tidak sampai kering).
Ketika biji berkembang, batang bagian bawah atau yang disebut dengan
hipokotil akan membengkak dengan cepat. Tanaman mulai membentuk
lubang-lubang dalam batang yang membengkak tersebut ketika berumur beberapa bulan.
Dalam memelihara kecambah, kecukupan cahaya perlu diperhatikan karena
kekurangan cahaya akan menyebabkan tumbuhan memanjang dan bagian
umbinya menciut. Pencahayaan yang kurang juga menyebabkan pembentukan
daun lebih banyak.
Pertumbuhan Tumbuhan Sarang Semut
Pengertian Pertumbuhan
Prawirohartono dan Suhargono (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan
merupakan proses pertambahan ukuran (volume, massa, tinggi atau panjang) yang
bersifat kuantitatif yang dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Dalam
peristiwa biologis yang terjadi pada makluk hidup istilah pertumbuhan dan
perkembangan senantiasa berbarengan dan saling melengkapi. Perkembangan
merupakan proses menuju kedewasaan pada makluk hidup. Peristiwa ini bersifat
perkembangan suatu makluk hidup dikatakan sudah dewasa apabila alat
perkembangbiakannya telah berfungsi. Biasanya pada tumbuhan ditandai dengan
adanya kemampuan untuk berbunga dan pada tumbuhan berbiji yang
berkembangbiak secara kawin, kehidupannya selalu diawali dari satu sel yaitu sel
zigot.
Zigot tersebut terbentuk dari hasil pembuahan sel kelamin betina oleh sel
kelamin jantan. Zigot sebagai hasil pembuahan akan membelah menghasilkan
embrio. Selanjutnya embrio akan berkecambah menghasilkan individu muda.
Dalam perkecambahan tersebut sel-sel embrio membelah. Proses ini
menghasilkan banyak sel dengan bentuk, letak dan fungsi serta struktur dan
susunan biokimianya berbeda. Proses perubahan yang terjadi selama masa
pertumbuhan hingga terjadi organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi
yang berbeda disebut diferensiasi.
Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yakni pertumbuhan
primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil
pembelahan sel-sel jaringan meristem primer, sedangkan pertumbuhan sekunder
merupakan hasil aktivitas jaingan meristem sekunder. Pertumbuhan primer
biasaya terjadi pada embrio, ujung akar, dan ujung batang; sedangkan
pertumbuhan sekunder biasanya terjadi pada jaringan meristerm primer diujung
akar dan ujung batang, juga memiliki jaringan meristem sekunder, yaitu berupa
kambium dan kambium gabus.
Menurut Subroto dan Hendro (2006), tumbuhan sarang semut sejak dari biji
berkecambah batang bagian bawahnya secara progresif menggelembung dengan
sendirinya. Batang yang menggelembung tersebut dalam beberapa bulan akan
membentuk rongga-rongga yang cukup kompleks mirip sarang semut. Kini
tumbuhan sarang semut sudah berhasil diperbanyak dengan menggunakan teknik
kultur jaringan. Dengan demikian teknik perbanyakan tersebut, dapat dipastikan
tumbuhan sarang semut bisa dibudidayakan dengan baik. Tumbuhan ini termasuk
tanaman sukulen, yaitu tanaman yang dapat menyimpan air dalam jaringannya
dan mempunyai penampakan berdaging (seperti kaktus dan lidah buaya).
Tumbuhan tersebut pada habitat alaminya memperoleh pupuk dari debris atau
12
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman
Kramer & Kozlowski (1960), Siswoyo (1999) dan Abisena (2006)
menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu
faktor-faktor genetik dan faktor lingkungan tempat tumbuhnya.
Faktor genetik
Faktor genetik (intern) adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh
tumbuhan sendiri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, yakni: a) Faktor
intrasel adalah sifat menurun atau faktor hereditas dan b) Faktor intersel adalah
hormon
1. Sifat menurun atau hereditas
Ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan banyak dipengaruhi oleh sifat
menurun atau hereditas. Sifat tersebut adalah gen yang terdapat di dalam
setiap kromosom yang ada di dalam inti sel.
2. Hormon
Hormon merupakan substansi kimia yang sangat aktif, yang tersusun
atas senyawa protein. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan ini sering
disebut juga zat tumbuh. Hormon tumbuh pada tumbuhan banyak jenisnya,
yang penting antara lain auksin, giberelin, sitokinin, gas etilin dan asam
absisat.
a) Auksin
Auksin adalah senyawa indol asam asetat, yang merupakan sekresi
titik tumbuh tanaman, seperti ujung tunas, daun muda, buah, bunga,
kambium, dan ujung akar. Pengaruh auksin terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan adalah sebagai berikut:
1) Merangsang perpanjangan sel batang dan menghambat perpanjangan
sel akar.
2) Merangsang pertumbuhan akar lateral atau samping dan akar serabut
3) Mempercepat aktivitas pembelahan sel-sel titik tumbuh atau kabium
sehingga mempercepat pertumbuhan jaringan vaskuler sekunder.
4) Menyebabkan diferensiasi sel menjadi xylem sehingga dapat
meningkatkan transportasi air dan mineral.
5) Merangsang pembentukan bunga dan buah
b) Giberelin
Giberelin merupakan zat tumbuh yang memiliki sifat menyerupai
auksin, yakni:
1) Mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel.
2) Mempengaruhi perkembangan embrio dan kecambah, yaitu
merangsang lapisan butir-butir aleuron untuk mensintesis amilase.
3) Menghambat pembentukan biji, merangsang pertumbuhan saluran
polen, memperbesar ukuran buah, merangsang pembungaan, serta
menghambat dormansi dalam biji dan kuncup tunas.
c) Sitokinin
Sitokinin merupakan zat tumbuh yang mempunyai fungsi antara lain
sebagai berikut:
1) Merangsang pembelahan sel dengan cepat. Bersama-sama giberelin
dan auksin, dapat membantu pembelahan sel di daerah meristem
sehingga pertumbuhan titik tumbuh normal.
2) Memperkecil dominansi apikal dan dapat menyebabkan pembesaran
daun muda
3) Mengatur pembentukan bunga dan buah
4) Membantu proses pertumbuhan akar dan tunas pada pembuatan kultur
jaringan.
5) Menunda pengguguran daun, bunga dan buah, dengan cara
meningkatkan transpor zat makanan ke organ tersebut.
d) Gas Etilen
Gas etilen adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua.
Gas tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan
14
karakteristik, misalnya bersama giberelin dapat mengatur perbandingan
bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan berumah satu.
e) Asam absisat
Asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan
tanaman, yaitu dengan mengurangi kecepatan pembelahan sel maupun
perbesaran sel ataupun kedua-duanya. Hormon ini aktif pada saat
tumbuhan berada pada kondisi yang tidak baik sehingga tumbuhan mampu
bertahan hidup. Pada saat tumbuhan kekurangan air, asam absisat akan
terkumpul pada sel penutup stomata. Akumulasi asam absisat ini akan
menyebabkan stomata menutup.
Faktor lingkungan
1. Karakteristik bio-ekologis
Lingkungan pada umumnya dibagi menjadi faktor-faktor yang bersifat
fisik dan biologis. Faktor fisik atau abiotik, yaitu faktor-faktor lingkungan
yang bersifat non biologis seperti iklim (curah hujan, suhu udara, kelembaban
udara, intensitas cahaya), tanah dan kondisi fisiografi lingkungan. Faktor
yang bersifat biologis atau biotik, yaitu organisme yang berpengaruh terhadap
organisme lain contoh tumbuhan lain, satwa maupun manusia. Tumbuhan
dapat tumbuh dengan berhasil bila lingkungan mampu menyediakan berbagai
keperluan untuk pertumbuhan sesama daur hidupnya. Oleh karena sifat
lingkungan tidak hanya bergantung pada kondisi fisik dan kimia tetapi juga
karena kehadiran organisme lain faktor yang berperan dapat dibagi menjadi
tiga kelompok utama, yakni iklim, tanah dan biotik (Loveles 1989).
Faktor lingkungan tempat tumbuh tersebut dipengaruhi oleh beberapa
hal, yaitu
a) Iklim
1) Curah hujan
Menurut Polunin (1990), curah hujan tahunan minimum pada
tipe hujan hujan tropis sebesar 1.300 mm yang terbagi merata
datangnya musiman menyebabkan munculnya hutan sabana,
sedangkan curah hujan 250 mm atau kurang yang datangnya secara
tidak teratur adalah khas bagi gurun tropis.
Apabila curah hujan pada hutan hujan tropis berlimpah sekitar
2.000 – 4.000 mm setahun, suhu tahunan rata-rata berkisar antara 20
o
C - 28 oC dan rata-rata kelembaban 80 %, maka suhu akan menurun
sekitar 0,4 oC - 0,7 oC untuk setiap kenaikan 100 meter. Curah hujan
yang tinggi mampu menumbuhkan tumbuhan hutan dengan baik (Arief
1994).
2) Suhu
Umumnya respirasi menjadi lambat pada suhu rendah dan
meningkat pada suhu tinggi. Proses penyerapan unsur hara oleh
tanaman akan terhambat jika suhu tanah rendah. Menurut Sanchez
(1992), temperatur dapat mempengaruhi proses dekomposisi. Proses
dekomposisi akan nampak pada temperatur 5 oC – 34 oC dan apabila
temperatur lebih rendah, maka proses dekomposisi berjalan lambat,
sehingga dapat menurunkan tingkat kehilangan bahan organik serta
dapat meningkatkan kandungan bahan nitrogen dari kompos. Pada
temperatur yang tinggi (45 oC – 75 oC), bahan organik dan kandungan
N organik dari kompos akan hilang sejalan dengan naiknya temperatur.
3) Kelembaban
Kelembaban atau kadar air di suatu tempat sangat berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Udara yang
kurang lembab umumnya berpengaruh baik terhadap pertumbuhan
tersebut, karena kondisi ini akan meningkatkan penyerapan air dan
menurunkan penguapan atau transpirasi. Hal inilah yang
memungkinkan terjadinya pembentangan sel, sehingga sel dapat segera
mencapai ukuran maksimum. Namun, sering terjadi suatu jenis
tumbuhan bahkan bertunas, bersemi, dan berbunga pada akhir musim
16
b) Vegetasi
Jongman (1987) menyatakan bahwa karakteristik suatu spesies
tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, baik dengan lingkungan
fisik maupun biotiknya dapat dipelajari melalui pendekatan autecology,
sedangkan karakteristik tumbuhan sebagai komunitas (vegetasi) dipelajari
dalam synecology, yaitu studi mengenai berbagai spesies dan interaksinya
dengan lingkungan. Bidang yang mempertemukan kedua studi tersebut
dikenal dengan evolutionary ecology yang menitikberatkan
pembahasannya pada stabilitas komunitas, demografi, pola-pola alokasi
dan keanekaragaman spesies (Barbour et al. 1987). Dalam pemakaian
kedua pendekatan baik pendekatan autecology dan pendekatan synecology
selalu mengacu pada dua karakter dasar suatu sistem, yaitu aspek
struktural dan aspek fungsional.
Ciri struktural dari suatu spesies tumbuhan umumnya digunakan
dalam analisis ekologi antara lain: kerapatan, pola distribusi, regenerasi,
biomas, pertumbuhan dan penutupan tajuk, sedangkan ciri fungsional
meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan proses-proses fisiologis
tumbuhan, dinamika populasi (demografi) serta mekanisme interaksinya
dengan komponen fisik dan biotik. Selain aspek struktural dan fungsional
ekositem juga memiliki ciri tipologis, yaitu ciri yang berhubungan dengan
ukuran. Meskipun tidak ada batas ukuran yang pasti, namun dapat
diketahui bahwa suatu ekosistem mungkin hanya memiliki satu komunitas
tumbuhan, tetapi mungkin juga memiliki beberapa komunitas tumbuhan
yang saling berinteraksi (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974).
Pendekatan struktural bersifat statis, sepanjang tidak dikaitkan
dengan perubahan komposisi biomas atau keanekaragaman spesies
menurut waktu. Proses temporal merupakan bagian dari analisis fungsi
ekosistem, misalnya aliran/dinamika energi, siklus hara dan suksesi
(Golley 1983). Odum (1993) menyatakan bahwa analisis fungsional juga
dapat dilakukan melalui studi terhadap rantai makanan, pola
keanekaragaman spesies, perkembangan evolusioner, dan pengendalian
Unit ekologis yang umum digunakan dalam analisis vegetasi adalah
formasi vegetasi. Kimmins (1987) mendefinisikan istilah formasi sebagai
tipe utama komunitas tumbuhan di suatu benua yang dicirikan oleh
fisiognominya dan kisaran komponen lingkungan dimana kondisi
fisioognomi tersebut beradapasi. Penamaan tipe vegetasi selalu menjadi
permasalahan dalam klasifikasi vegetasi, namun dalam kaitannya dengan
formasi-formasi vegetasi di ekosistem hutan hujan tropika, nama yang
diberikan mencerminkan keadaan habitat, struktur dan fisiognominya.
Analisis vegetasi adalah suatu studi untuk mengetahui susunan
(komposisi jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat
tumbuh-tumbuhan, yaitu mempelajari tegakan hutan (tingkat pohon dan
permudaannya) dan tegakan tumbuhan bawah. Berdasarkan data pada unit
contoh vegetasi tersebut dapat diketahui jenis dominan dan kodominan,
pola asosiasi, nilai keanekaragaman jenis, dan atribut komunitas tumbuhan
lainnya yang berguna bagi pengelolaan hutan.
Untuk melakukan analisis vegetasi pada dasarnya ada dua macam
metode yang dapat dilakukan yaitu metode dengan petak dan metode tanpa
petak. Salah satu metode dengan petak yang banyak digunakan adalah
metode kombinasi antara metode jalur (untuk risalah pohon) dengan
metode garis berpetak (untuk risalah permudaan). Adapun petak-petak
contoh yang digunakan untuk risalah permudaan dibuat secara "nested
sampling".
Herbarium adalah koleksi spesimen tumbuhan yang terdiri dari
bagian-bagian tumbuhan (ranting lengkap dengan daun, serta kalau ada
bunga dan buahnya). Spesimen ini pada umumnya telah dikeringkan dan
dipres, serta ditempelkan pada kertas manila disertai dengan
keterangan-keterangan yang perlu mengenai hal-hal yang sulit dikenali secara
langsung dari spesimen kering tersebut. Herbarium sangat penting dalam
kegiatan inventarisasi hutan, terutama apabila inventarisasi dilakukan
dalam plot permanen, sebab selain digunakan untuk kepentingan
18
bukti bahwa spesies tumbuhan tersebut terdapat di daerah dimana kegiatan
inventarisasi atau analisis vegetasi dilakukan.
Ciri utama hutan hujan tropika adalah adanya lapisan-lapisan tajuk
pohon (stratifikasi) yang terjadi karena perbedaan tinggi pohon/tumbuhan.
Stratifikasi terbentuk melalui mekanisme persaingan dan pergantian
tumbuhan yang merupakan bukti adanya dinamika masyarakat
tumbuh-tumbuhan. Akibat persaingan, jenis-jenis tertentu lebih berkuasa
(dominan) daripada jenis yang lain. Pohon-pohon dominan dari lapisan
teratas mengalahkan atau menguasai pohon-pohon yang lebih rendah.
Soerianegara dan Indrawan (1988) menyatakan bahwa di hutan hujan
tropika bisa terdapat 5 lapisan (stratum) tajuk, yaitu lapisan A, B, C, D,
dan E. Lapisan A, B, dan C merupakan lapisan tajuk dari tingkat pohon,
lapisan D merupakan perdu dan semak, sedangkan lapisan E adalah
lapisan tumbuh-tumbuhan penutup tanah (ground cover). Ciri dan kriteria
masing-masing lapisan adalah:
1. Lapisan A : Lapisan teratas, tinggi total pohon > 30 m, tajuk
diskontinyu (tersebar), pohon tinggi, lurus dan
batang bebas cabang tinggi, semi-toleran.
2. Lapisan B : Lapisan kedua, tinggi total pohon 20 - ≤ 30 m,
tajuk kontinyu (rapat), pohon banyak cabang,
batang bebas cabang tidak terlalu tinggi, jenis
toleran.
3. Lapisan C : Lapisan ketiga, tinggi pohon 4 - ≤ 20 m, tajuk
kontinyu (rapat), rendah, kecil, dan banyak
cabang.
4. Lapisan D : Perdu dan semak, tinggi 1 - ≤ 4 m.
5. Lapisan E : Tumbuhan penutup tanah, tinggi ≤ 1 m.
Batas tinggi lapisan tersebut berbeda-beda tergantung pada tempat
tumbuh dan komposisi hutan. Antara lapisan A dan lapisan B jelas dapat
dibedakan berdasarkan kekontinuan tajuk, tetapi lapisan B dan C kurang
hutan mempunyai ketiga lapisan di atas, ada yang mempunyai lapisan A -
B atau A - C saja.
Dalam studi synekologi, terutama studi komposisi dan struktur
hutan, mempelajari profil (stratifikasi) sangat penting artinya. Untuk
mengetahui dimensi (bentuk) atau struktur vertikal dan horizontal suatu
vegetasi dari hutan yang dipelajari, dengan melihat bentuk profilnya akan
dapat diketahui proses dari masing-masing pohon dan kemungkinan
peranannya dalam komunitas tersebut, serta dapat diperoleh informasi
mengenai dinamika pohon dan kondisi ekologinya.
2. Komposisi vegetasi
Menurut Rumahorbo (1994) dan Kamaebun (2000), komposisi
vegetasi merupakan susunan dan jumlah jenis yang terdapat dalam suatu
komunitas tumbuhan. Mueller-Dombois & Ellenberg (1974),
Soerianegara dan Indrawan (1985) dan McNaughton & Wolf (1990)
menyatakan bahwa dalam mempelajari ekologi vegetasi untuk tujuan
deskriptif, maka kerapatan/kelimpahan, frekuensi dan dominansi
(penutupan/cover) merupakan variabel kuantitatif yang terpenting.
3. Struktur vegetasi
Ciri struktural komunitas tumbuhan menyangkut komposisi floristik dan
struktur vegetasi. Kucler (1988) mendefinisikannya sebagai pola distribusi
spasial dari bentuk-bentuk pertumbuhan (growth form) dalam suatu vegetasi,
sedangkan Kimmins (1987) mendefinisikannya sebagai susunan vertikal dan
distribusi spasial dari tumbuh-tumbuhan dalam suatu komunitas. Halle et al.
(1978) dan MacKinnon et al. (1990), analisis struktural dari komunitas
vegetasi berdasarkan arsitektur pohonnya digunakan untuk menggambarkan
keanekaragaman morfologi tumbuh-tumbuhan yang merupakan komponen
hutan tropika. Begitu juga beberapa penulis lainnya seperti Bourgeron (1983)
dan Brunig (1983) menekankan aspek spasial, baik vertikal maupun
horisontal, juga untuk menggambarkan struktur vegetasi hutan tropika.
Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) dalam ekologi vegetasi, analisis
20
a. fisiognomi vegetasi
b. struktur biomas
c. struktur bentuk kehidupan (life form)
d. struktur floristik, dan
e. struktur tegakan.
Kelima level struktur vegetasi ini secara hirarkis terpadu, dimana kajian yang
pertama mencakup yang kedua, yang kedua mencakup yang ketiga dan
seterusnya. Dalam hal ini level pertama adalah yang paling umum sedangkan
level kelima merupakan yang paling spesifik.
Menurut Kershaw (1973), struktur vegetasi ditentukan oleh tiga
komponen, yaitu:
a. susunan vertikal vegetasi, misalnya stratifikasi vegetasi
b. susunan horizontal vegetasi, misalnya distribusi spasial individu
c. kelimpahan spesies atau struktur kuantitatif yang dapat dinyatakan dengan
berbagai cara mulai dari penghitungan langsung jumlah individu dalam
suatu areal (kerapatan) hingga bobot kering produksi material (produksi).
Arief (1994), pohon tertinggi (emergent) mencapai 40 - 55 m yang
menguak atap hutan. Pada umumnya tinggi pohon dalam hutan dataran
rendah berkisar antara 30 - 50 m, tetapi ada pula pohon yang ketinggiannya
dapat mencapai 50 m atau lebih dan mempunyai diameter batang dapat
mencapai 2,5 m (Paijmans, 1976).
Paijmans (1976) yang dikutip Petocz (1987) menyatakan bahwa hutan
dataran rendah kaya sekali akan spesies dan mengandung sebagian besar dari
jenis-jenis kayu Irian Jaya yang penting. Tajuk pohon hutan ini bertingkat
banyak dan tidak rata dengan tonjolan di sana-sini banyak sekali, sedangkan
tingkat bawahnya ditumbuhi perdu dan semak yang mendukung berbagai
tanaman pemanjat, epifit dan paku-pakuan. Jenis-jenis tumbuhan yang khas
membentuk tajuk lapisan atas ialah Pometia, Ficus, Diospyros, Meristica, dan
lain sebagainya.
4. Tumbuhan inang
Tumbuhan inang dalam penelitian ini dibahas sebagai tempat untuk
sarang semut. Lakitan (1993), menyatakan bahwa tumbuhan epifit adalah
tumbuhan yang hanya menempel atau menggantung pada tumbuhan lain,
tetapi tidak hidup parasit pada inangnya. Berdasarkan pengertiannya lebih
tepat istilah yang dipakai untuk jenis tumbuhan obat sarang semut adalah
tumbuhan efifit. Tim Penyusun Kamus PS (2001) tumbuhan saprofit adalah
tumbuhan yang memperoleh bahan makanan dari jaringan yang sudah mati,
sedangkan pengertian tumbuhan adalah sesuatu yang sifatnya hidup dan
bertambah besar atau berkembang yang mempunyai batang, akar, daun, dan
sebagainya serta mempunyai inti sel dan klorofil.
Indriyanto (2006), menyatakan bahwa epifit merupakan semua
tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat
sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang
berasal dari tumbuhan yang ditempeli, karena untuk mendapatkan unsur hara
dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air hujan, atau aliran batang
dan cabang tumbuhan lain. Epifit mampu melakukan proses fotosintesis
untuk pertumbuhan dirinya, sehingga bukan merupakan parasit. Keberadaan
epifit tersebut sangat penting dalam ekosistem tumbuhan karena kadangkala
tumbuhan epifit mampu menyediakan tempat tumbuh bagi semut-semut
pohon.
Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting karena
dapat dikaitkan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Jika membandingkan
berbagai jenis tumbuhan ada yang jelas kekhasan batangnya dan ada yang
tidak jelas, sehingga dapat dibedakan, yaitu:
a. Tumbuhan yang tidak berbatang (tampaknya) misalnya sawi (Brassica
juucea L.)
b. Tumbuhan yang jelas berbatang
1. batang basah misal bayam (Amaranthus spinosus L.)
2. batang berkayu
Percabangan pada batang dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :
a. Monopodial, jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan
22
misalnya pohon cemara Casuarina equisetifolia L. (Tjtrosoepomo 2000).
Tim Penyusun Kamus PS (2001), monopodial adalah tanaman yang ujung
tunasnya kuat/kokoh dan membentuk batang tunggal yang tumbuh tegak
lurus misalnya kelapa; atau tanaman berbatang tegak lurus yang secara
terus menerus tumbuh tegak dari tahun ke tahun misalnya anggrek vanda.
b. Simpodial, batang pokok sukar ditentukan karena dalam perkembangan
selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan
kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya misalnya
pada sawo manila Achras zapota L. (Tjtrosoepomo 2000). Tim Penyusun
Kamus PS (2001), mendefinisikan simpodial adalah bentuk pertumbuhan
ujung batang tanaman terbatas yang diikuti dengan pertumbuhan tunas
baru pada pangkal batang sebagai cabang atau anakan sehingga
membentuk rumpun; atau luka pada tanaman yang disebabkan oleh
intensitas cahaya yang terlalu tinggi dan panas pancaran.
c. Dikotomi, bentuk percabangan menggarpu, yaitu cara percabangan, yang
batang setiap kali menjadi dua cabang yang sama besarnya, misalnya paku
andam Gleichenia linearis Clarke (Tjtrosoepomo 2000). Tim Penyusun
Kamus PS (2001), mendefinisikan dikotomi adalah pembentukan cabang
sekunder dari batang yang selalu muncul berpasangan.
Pengaruh manusia
Secara sistematis ada 4 (empat) penyebab utama ancaman terhadap
kelestarian keanekaragaman hayati (Diamond 1984 yang dikutip De Fretes 1998),
yaitu :
1. Perusakan dan pemusnahan habitat alam lewat pelebaran lahan buat
transmigrasi, pembuatan dam, pembuatan jalan dan sebagainya.
2. Pemanfaatan yang berlebihan dan tidak terkendali
3. Masuknya spesies asing
4. Pemusnahan sekunder, misalnya tumbuhan/binatang yang punah secara tidak
langsung karena habitat atau inangnya hilang.
Primack dkk. (1998), ancaman utama hilangnya keanekaragaman hayati
manusia diantaranya adalah kegiatan eksplorasi pertambangan, kegiatan HPH
(Hak Pengusahaan Hutan), HTI (hutan Tanaman Industri), pemukiman
transmigrasi, perkembangan industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan serta
kegiatan lainnya. Ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Irian Jaya
(Papua) adalah perusakan dan pemusnahan habitat. Perusakan dan pemusnahan
habitat di Irian Jaya (Papua) diperkirakan s