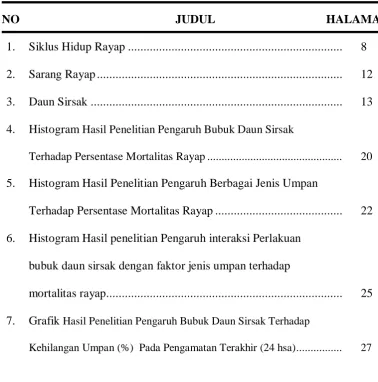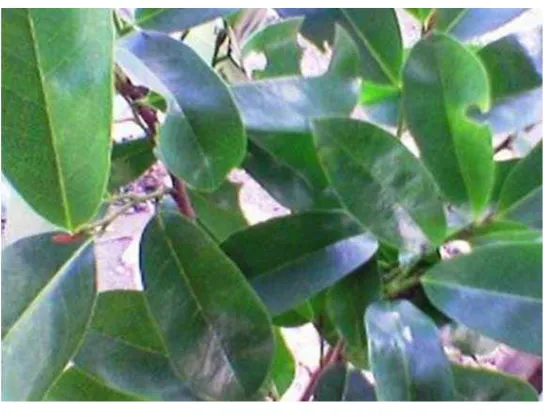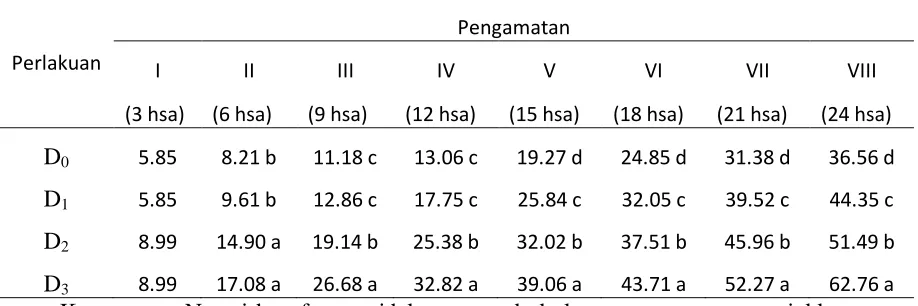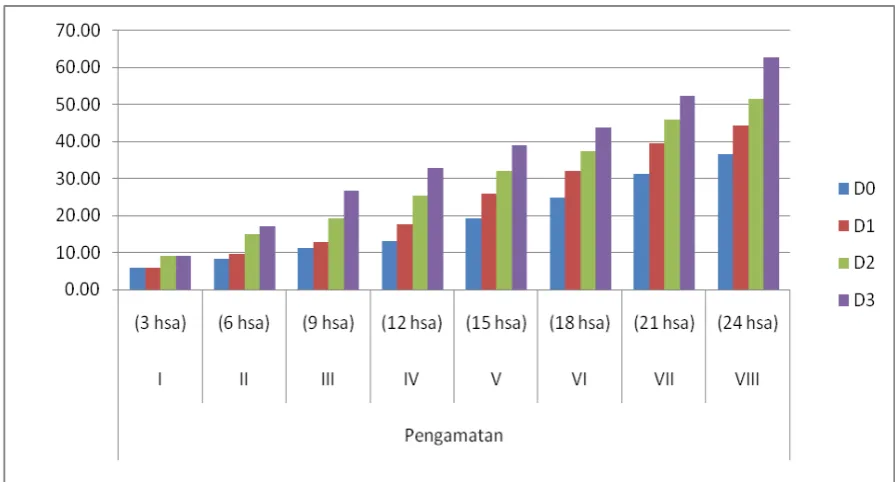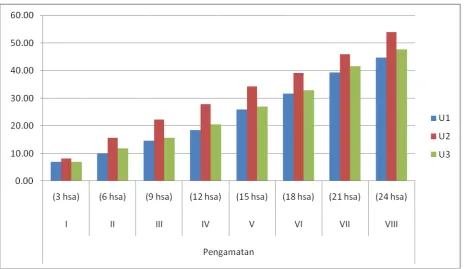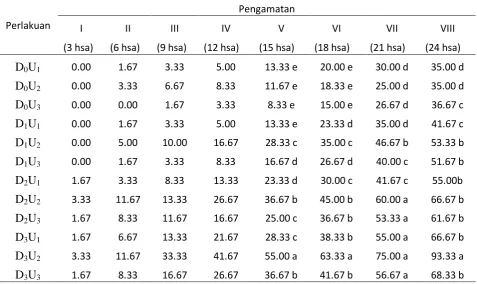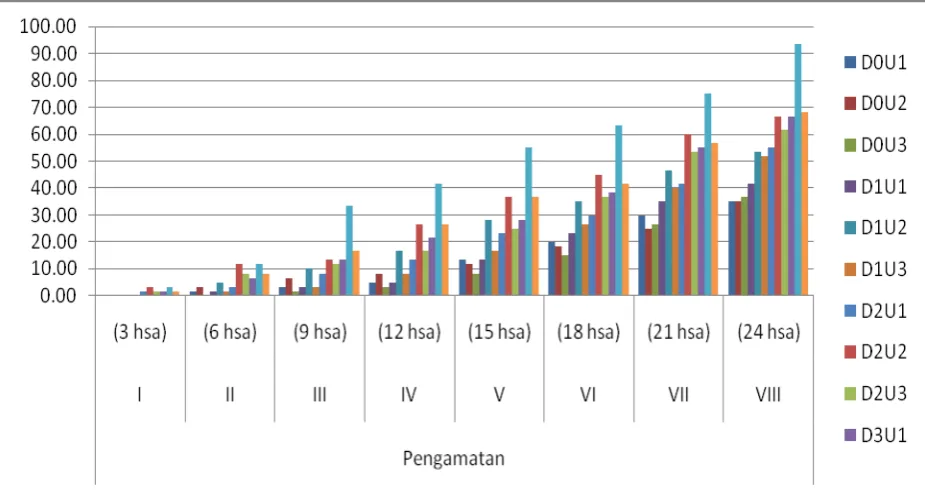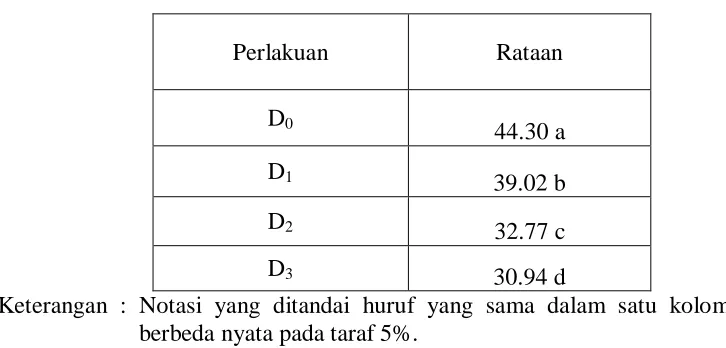PENGENDALIAN RAYAP Coptotermes curvignatus Holmgren.
(Isoptera: Rhinotermitidae) DENGAN MENGGUNAKAN DAUN
SIRSAK (Annona muricata Linn.) PADA BERBAGAI
JENIS UMPAN DI LABORATORIUM
SKRIPSI
ADE GUNAWAN MANURUNG
050302005
HPT
DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
PENGENDALIAN RAYAP Coptotermes curvignatus Holmgren.
(Isoptera: Rhinotermitidae) DENGAN MENGGUNAKAN DAUN
SIRSAK (Annona muricata Linn.) PADA BERBAGAI
JENIS UMPAN DI LABORATORIUM
SKRIPSI
ADE GUNAWAN MANURUNG
050302005
HPT
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Meemperoleh Gelar Sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara, Medan
Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing
(Ir. Mena Uly Tarigan, MS) (Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS) Ketua Anggota
DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
ABSTRACT
Ade Gunawan Manurung, "Control Termite Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) by Using the Soursop Leaves (Annona muricata L.) in Various Types of Bait The Laboratory ", under the guidance of Ir. Mena Uly Tarigan, MS as Chairman and Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS as a Member. Research was conducted at the Laboratory of Pest Department of Plant Pests and Diseases Faculty of Agriculture, University of North Sumatera, Medan with altitude ± 25 feet above sea level. Research was conducted in May 2010 to complete. This research used Completely Randomized Design (CRD) with 2 factors and treatment of soursop leaf powder factor and the factor type of bait / media with 12 treatment combinations and was repeated three (3) times. The result showed the highest mortality percentage contained in the interaction treatment D3U2 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper (15 g/20 larvae
/ jar)) that is equal to 93.33% and the lowest in the interaction treatment D0U1
treatment interaction (without the leaf powder soursop (control) and feed sawdust (15 g/20 larvae / jar)), D0U2 (without the powdered leaves of soursop (control)
and feed the tissue paper (15 g/20 larvae / jar)) that is equal to 35.00%. Percentage of weight loss on the highest material found on the D3 treatment amounted to
44.30% and the lowest at 30.94% D0 treatment. The results showed that the interaction of treatment D2U3 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper
ABSTRAK
Ade Gunawan Manurung, “Pengendalian Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) dengan Menggunakan Daun Sirsak
(Annona muricata L.) pada Berbagai Jenis Umpan Di Laboratorium”, di bawah
bimbingan Ir. Mena Ully Tarigan, MS selaku Ketua dan Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS sebagai Anggota. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan dengan ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor perlakuan yaitu faktor bubuk daun sirsak dan faktor jenis umpan/media dengan 12 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak tiga (3) kali. Hasil penelitian menunjukan persentase mortalitas tertinggi terdapat pada interaksi perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue
(15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 93.33 %dan yang terendah pada interaksi perlakuan interaksi perlakuan D0U1 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan
serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D0U2 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)
dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 35.00%. Persentase susut bobot bahan tertinggi terdapat pada perlakuan D3 sebesar 44,30% dan
terendah pada perlakuan D0 sebesar 30.94%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
interaksi perlakuan D2U3 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue
RIWAYAT HIDUP
Ade Gunawan Manurung, dilahirkan di Martebing Kec. Dolok Masihul
pada tanggal 12 Agustus 1986 dari Ayah C. Manurung dan Ibunda L. Br. Dolok
Saribu. Penulis merupakan anak keempat dari empat (4) bersaudara
Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:
- Lulus dari Sekolah Dasar Negeri 102062 Desa Martebing pada tahun 1999
- Lulus dari SMP Swasta Ost. Methodist pada tahun 2002
- Lulus dari SMA Negeri 2 Tebing tinggi pada tahun 2005
Kegiatan akademis yang pernah diikuti penulis selama perkuliahan adalah:
Menjadi anggota organisasi IMAPTAN (Ikatan Mahasiswa Perlindungan
Tanaman) tahun 2005-2010, Wakil Ketua Liga Pertanian XI.
Pada tahun 2005 diterima di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera
Utara. Selama mengikuti perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) di PTPN III Kebun Bangun Kab. Simalungun pada bulan
Juni-Juli 2009. Melaksanakan Praktek skripsi di Laboratorium Ilmu Hama Fakultas
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas anugerah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan baik.
Judul dari skripsi adalah “Pengendalian Rayap Coptotermes
curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) dengan Menggunakan
Daun Sirsak (Annona muricata L.) pada Berbagai Jenis Umpan Di Laboratorium” yang bertujuan untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara, Medan.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi
Pembimbing Ir. Mena Uly Tarigan, MS selaku Ketua, Ir. Yuswani
Pangestiningsih, MS selaku Anggota yang telah memberi saran dan kritik dalam
menyelesaikan skripsi.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan
mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
Medan, Oktober 2010
DAFTAR ISI
Hipotesis Penelitian... 4
Kegunaan Penelitian ... 4
TINJAUAN PUSTAKA Biologi Coptotermes curvignathus Holmgren ... 5
Siklus Hidup Rayap ... 7
Pengendalian Rayap ... 9
Perilaku Rayap ... 10
Sistem Sarang ... 11
Insektisida Nabati (Daun Sirsak) ... 12
BAHAN DAN METODA Tempat dan Waktu Penelitian... 14
Bahan dan Alat ... 14
Metodologi Penelitian ... 14
Pelaksanaan Penelitian ... 17
Persiapan Rayap... 17
Persiapan Insektisida Nabati... 17
Aplikasi ... 17
Peubah Amatan ... 18
Persentase Mortalitas (%) ... 18
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Perlakuan Bubuk Daun Sirsak Terhadap
mortalitas Rayap ... 19
Pengaruh Perlakuan Berbagai Jenis Umpan Terhadap
mortalitas Rayap ... 21
Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap ... 24
Pengaruh Perlakuan Daun Sirsak Terhadap Kehilangan Umpan ... 27
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan ... 29 Saran ... 29
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR GAMBAR
NO JUDUL HALAMAN 1. Siklus Hidup Rayap ... 8
2. Sarang Rayap ... 12
3. Daun Sirsak ... 13
4. Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak
Terhadap Persentase Mortalitas Rayap ... 20
5. Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan
Terhadap Persentase Mortalitas Rayap ... 22
6. Histogram Hasil penelitian Pengaruh interaksi Perlakuan
bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap
mortalitas rayap... 25
7. Grafik Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap
DAFTAR TABEL
NO JUDUL HALAMAN
1. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap
Persentase Mortalitas Rayap ... 19
2. Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan Terhadap
Persentase Mortalitas ... 21
3. Hasil Penelitian Pengaruh Interaksi Perlakuan Bubuk Daun
Sirsak dengan Faktor Jenis Umpan terhadap Mortalitas Rayap ... 24
4. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap
DAFTAR LAMPIRAN
NO JUDUL HALAMAN
1. Bagan Penelitian ... 32
2. Data Pengamatan 3 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 34 3. Data Pengamatan 6 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 36 4. Data Pengamatan 9 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 39 5. Data Pengamatan 12 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 42 6. Data Pengamatan 15 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 45 7. Data Pengamatan 18 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 48 8. Data Pengamatan 21 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 51 9. Data Pengamatan 24 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap
Coptotermes curvignatus Holmgren ... 54 10. Data Susut Bobot Bahan ... 57
ABSTRACT
Ade Gunawan Manurung, "Control Termite Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) by Using the Soursop Leaves (Annona muricata L.) in Various Types of Bait The Laboratory ", under the guidance of Ir. Mena Uly Tarigan, MS as Chairman and Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS as a Member. Research was conducted at the Laboratory of Pest Department of Plant Pests and Diseases Faculty of Agriculture, University of North Sumatera, Medan with altitude ± 25 feet above sea level. Research was conducted in May 2010 to complete. This research used Completely Randomized Design (CRD) with 2 factors and treatment of soursop leaf powder factor and the factor type of bait / media with 12 treatment combinations and was repeated three (3) times. The result showed the highest mortality percentage contained in the interaction treatment D3U2 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper (15 g/20 larvae
/ jar)) that is equal to 93.33% and the lowest in the interaction treatment D0U1
treatment interaction (without the leaf powder soursop (control) and feed sawdust (15 g/20 larvae / jar)), D0U2 (without the powdered leaves of soursop (control)
and feed the tissue paper (15 g/20 larvae / jar)) that is equal to 35.00%. Percentage of weight loss on the highest material found on the D3 treatment amounted to
44.30% and the lowest at 30.94% D0 treatment. The results showed that the interaction of treatment D2U3 (soursop leaf powder 8 g / bait jar and tissue paper
ABSTRAK
Ade Gunawan Manurung, “Pengendalian Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren. (Isoptera: Rhinotermitidae) dengan Menggunakan Daun Sirsak
(Annona muricata L.) pada Berbagai Jenis Umpan Di Laboratorium”, di bawah
bimbingan Ir. Mena Ully Tarigan, MS selaku Ketua dan Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS sebagai Anggota. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan dengan ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor perlakuan yaitu faktor bubuk daun sirsak dan faktor jenis umpan/media dengan 12 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak tiga (3) kali. Hasil penelitian menunjukan persentase mortalitas tertinggi terdapat pada interaksi perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue
(15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 93.33 %dan yang terendah pada interaksi perlakuan interaksi perlakuan D0U1 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan
serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D0U2 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)
dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 35.00%. Persentase susut bobot bahan tertinggi terdapat pada perlakuan D3 sebesar 44,30% dan
terendah pada perlakuan D0 sebesar 30.94%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
interaksi perlakuan D2U3 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) diperkirakan berasal dari
Nigeria, Afrika Barat. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada 1848 sebanyak
empat bibit yang berasal dari Mauritius, yang mana keempat bibit sawit ini
ditanam di kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. Selanjutnya percobaan
penanaman kelapa sawit dilakukan di Muara Enim (1869), Musi Hulu (1870) dan
Belitung (1890). Pada tahun 1911 kelapa sawit baru dibudidayakan secara
komersial dalam bentuk perkebunan di Sungai Liput (Aceh) dan Pulau Raja
(Asahan) (Risza, 1994).
Ekspor minyak dan inti sawit dari Afrika dimulai pada abad ke-19. pada
masa itu, sumber minyak hanya berasal dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh
liar dan minyak masih diekstrak dengan cara yang sederhana dan tidak efisien.
Pada saat ini, perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan
dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri oleochemical.
Produk minyak sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak
nabati dunia (Pahan, 2005).
Pada areal perkebunan kelapa sawit dapat dijumpai beberapa jenis rayap,
tetapi yang menimbulkan masalah adalah Coptotermes curvignathus Holmgren
dan Macrotermes gilvus Hagen. Rayap C.curvignathus lebih berbahaya karena
menyerang jaringan hidup dan dapat mematikan tanaman kelapa sawit. Rayap ini
merupakan spesies asli yang banyak terdapat pada hutan primer di Indonesia dan
merata sepanjang tahun C. curvignathus mudah dibedakan dengan jenis rayap
lainnya dari ciri pertahanan dirinya, prajurit yang terganggu segera mengeluarkan
cairan putih dari kelenjar di kepalanya untuk mempertahankan diri. Banyak jenis
tanaman yang dapat diserang oleh C. curvignathus diantaranya karet, kapuk, kopi,
kelapa, ubi kayu dan kelapa sawit (Ginting dkk, 2002).
Rayap subteran Coptotermes curvignathus merupakan salah satu serangga
hama utama pada kelapa sawit terutama pada kelapa sawit khususnya di lahan
gambut. Serangannya dapat mematikan tanaman dan kasusnya semakin berat
dengan diterapkannya zero burning dalam pembukaan lahan. Pengendaliannya
sulit dilakukan karena banyaknya sisa kayuan yang merupakan bahan makanan
dan tempat berkembangbiak yang sesuai. Selama ini pengendalian dilakukan
dengan insektisida. Beberapa insektisida efektif menekan serangan rayap tapi
tidak mampu mencegah reinfestasi baru. Dalam jangka panjang, pengendalian
secara kimiawi ini tidak efisien dan dapat mencemari lingkungan. Suatu strategi
pengendalian rayap pada kelapa sawit pada kelapa sawit di lahan gambut dapat
dilakukan dengan pendekatan ekologi dan hayati serta aplikasi selektif
teknik-teknik pengendalian yang kompatibel dan yang memiliki dampak negatif minimal
(Purba dkk, 2002).
Rayap dapat menimbulkan masalah di perkebunan kelapa sawit terutama
pada areal baru bekas hutan. Ada dua jenis yang menyerang kelapa sawit, yakni
Coptotermes curvignathus dan Macrotermes gilvus, yang menyerang batang dan
pelepah daun, baik jaringan yang masih hidup maupun jaringan mati
Rayap memiliki habitat yang unik dalam suatu ekosistem. Keberadaan
koloni rayap berperan penting dalam siklus biogeoghemical (dekomposer bahan
organik) seperti siklus nitrogen, karbon, sulfur, oksigen dan fosfor. Mudahnya
rayap beradaptasi dengan lingkungan mengakibatkan mereka bisa ditemui di
hampir semua bentuk ekosistem (Prasetiyo dan Yusuf, 2005).
Rayap merupakan salah satu jenis serangga dalam ordo Isoptera yang
tercatat ada sekitar 200 jenis dan baru 179 jenis yang sudah teridentifikasi di
Indonesia. Beberapa jenis rayap di Indonesia yang secara ekonomi sangat
merugikan karena menjadi hama adalah tiga jenis rayap tanah/subteran
(Coptotermes curvignathus Holmgren, Macrotermes gilvus Hagen, serta
Schedorhinotermes javanicus Kemner) dan satu jenis rayap kayu kering
(Cryptotermes Cynocephalus Light). Tiap tahun kerugian akibat serangan rayap di
Indonesia tercatat sekitar Rp 224 miliar - Rp 238 miliar (Kalsholven, 1981).
Pestisida sering digunakan sebagai pilihan utama untuk memberantas
organisme pengganggu tanaman. Sebab, pestisida mempunyai daya bunuh yang
tinggi, penggunaannya mudah, dan hasilnya cepat untuk diketahui. Namun bila
diaplikasikan kurang bijaksana dapat membawa dampak pada pengguna, hama
sasaran, maupun lingkungan yang sangat berbahaya (Surbakti, 2008).
Dampak negatif penggunaan pestisida sintetik yang berspektrum luas
menyebabkan masalah pengendalian OPT menjadi lebih sulit dan kompleks serta
diikuti dengan masalah akibat residu pestisida yang mencemari hasil pertanian
dan lingkungan. Pengendalian OPT dengan pestisida nabati menjadi alternatif
yang menjanjikan oleh karena relatif sedikit menimbulkan dampak negatif
Insektisida nabati dapat digunakan sebagai alternatif pengendalian
serangga hama utama karena memenuhi kriteria yang diinginkan yaitu aman,
murah, mudah diterapkan petani dan efektif membunuh hama serta memiliki
keuntungan mudah dibuat dan berasal dari bahan alami/nabati yang mudah terurai
(biodegradable) sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi
manusia dan ternak, karena residunya mudah hilang. Salah satu tanaman yang
memiliki senyawa untuk digunakan sebagai insektisida nabati yaitu daun sirsak.
Bagian tanaman sirsak yang dapat digunakan sebagai insektisida nabati adalah
daun dan biji (Kardinan, 2004).
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dosis bubuk sirsak yang paling efektif pada berbagai
jenis umpan untuk mengendalikan rayap (Coptotermes curvignatus Holmgren).
Hipotesa Penelitian
Diduga pemberian bubuk daun sirsak dengan dosis 4 gr/stoples dengan umpan serbuk gergaji yang paling efektif untuk mengendalikan rayap
(Coptotermes curvignatus Holmgren).
Kegunaan Penelitian
− Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di
Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara, Medan.
TINJAUAN PUSTAKA
Biologi Coptotermes curvignathus Holmgren
Menurut Nandika dkk (2003) sistematika dari rayap (C. curvinagthus)
adalah sebagai berikut :
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Isoptera
Famili : Rhinotermitidae
Genus : Coptotermes
Spesies: Coptotermes curvinagthus Holmgren
Rayap adalah kelompok serangga yang memiliki kemampuan mencerna
selulosa, yaitu produk alami yang banyak terdapat di alam misalnya pada kayu,
daun, batang, kertas dan karton. Sudah sejak lama rayap diidentikkan dengan
terjadinya kerusakan pada bangunan, komponen kayu dalam rumah, buku, arsip,
dokumen serta beberapa jenis tanaman pertanian atau perkebunan seperti karet
dan kelapa sawit yang tidak luput dari serangannya (Anonimus, 2009).
Rayap juga hidup berkoloni dan mempunyai sistem kasta dalam
kehidupannya. Kasta dalam rayap terdiri dari 3 (tiga) kasta yaitu:
1. Kasta prajurit, kasta ini mempunyai ciri-ciri kepala yang besar dan penebalan
yang nyata dengan peranan dalam koloni sebagai pelindung koloni terhadap
gangguan dari luar. Kasta ini mempunyai mandible yang sangat besar yang
2. Kasta pekerja, kasta ini mempunyai warna tubuh yang pucat dengan sedikit
kutikula dan menyerupai nimfa. Kasta pekerja tidak kurang dari 80-90%
populasi dalam koloni. Peranan kasta ini adalah bekerja sebagai pencari
makan, memberikan makan ratu rayap, membuat sarang dan memindahkan
makanan saat sarang terancam serta melindungi dan memelihara ratu.
3. Kasta reproduktif, merupakan individu-individu seksual yang terdiri dari jantan
dan betina yang bertugas melakukan perkawinan untuk menghasilkan
keturunan selanjutnya. Ukuran tubuh ratu ± mencapai 5-9 cm
(Hasan, 1986).
Rayap bertubuh lunak dan berwarna putih. Sayap depan dan belakang
ukurannya hampir sama dan diletakkan datar di atas abdomen pada waktu
beristirahat. Bila sayap rayap terputus sepanjang sutera, hanya meninggalkan
dasar sayap atau potongan yang menempel pada thoraks. Abdomen pada rayap
lebih berhubungan dengan thoraks, kasta yang mandul (pekerja dan serdadu) pada
rayap terdiri dari 2 kelamin. Kasta–kasta reproduktif terbentuk dari telur yang
dibuahi (Borror dkk, 1992).
Rayap adalah hewan tanah yang besar peranannya dalam proses
dekomposisi material organik tanah dan mendekomposisi kayu yang mati. Namun
rayap juga dapat merugikan, karena serangga ini ada yang menyerang bangunan,
perabotan, terutama yang ter terbuat dari kayu dan buku–buku atau bahan–bahan
lain yang mengandung bahan selulosa. Selain itu bila bahn atau kayu yang mati
sukar diperoleh, maka rayap akan menyerang tanaman dan bila tanaman yang
terserang mempunyai arti penting, rayap tersebut dikategorikan sebagai hama
Sebagai hama, rayap hidup di bawah permukaan sampah-sampah tanaman
atau di bawah permukaan tanah sekitar tempat tanaman tumbuh secara berkoloni.
Rayap dapat menyerang beberapa jenis tanaman (Polypag), antara lain kelapa
sawit, karet, kopi, coklat, teh, kelapa dan tanaman yang lainnya. Penyebarannya
terutama di daerah–daerah tropis sampai sub tropis. Gejala serangan dimulai
dengan terlebih dahulu membuat jalur–jalur dari tanah, dimulai dari pangkal
batang menuju ke bagian atas sambil merusak kulit batang tanaman. Oleh karena
itu, tanaman muda atau bibit–bibit tanaman yang diserang akan mati (Kalshoven,
1981).
Rayap merupakan jenis serangga yang secara ekonomi sangat merugikan.
Rayap yang pada mulanya berfungsi sebagai pengurai dari sisa-sisa tumbuhan
menjadi bahan organik yang berguna, sekarang menjadi salah satu hama perusak
yang harus diperhitungkan keberadaannya. Penggunaan insektisida nabati yang
dimodifikasi dengan berbagai jenis umpan dapat digunakan untuk mengendalikan
rayap (Anonimus, 2007).
Siklus Hidup Rayap
Siklus hidup perkembangan rayap adalah melalui metamorfosa
hemimetabola, yaitu secara bertahap, yang secara teori melalui stadium (tahap
pertumbuhan) telur, nimfa, dewasa. Walau stadium dewasa pada serangga
Gambar 1. Siklus hidup rayap
Sumber :
April 2010
Panjang telur bervariasi antara 1-1,5 mm. Telur C. curvignathus akan
menetas setelah berumur 8-11 hari. Jumlah telur rayap bervariasi, tergantung
kepada jenis dan umur. Saat pertama bertelur betina mengeluarkan 4-15 butir
telur. Telur rayap berbentuk silindris, dengan bagian ujung yang membulat yang
berwarna putih. Telur yang menetas yang menjadi nimfa akan mengalami
5-8 instar (Anonimus 2009).
Nimfa yang menetas dari telur pertama dari seluruh koloni yang baru akan
berkembang menjadi kasta pekerja. Kasta pekerja jumlahnya jauh lebih besar dari
seluruh kasta yang terdapat dalam koloni rayap. Waktu keseluruhan yang
dibutuhkan dari keadaan telur sampai dapat bekerja secara efektif sebagai kasta
pekerja pada umumnya adalah 6-7 bulan. Umur kasta pekerja dapat mencapai
Pengendalian Rayap
Pengendalian rayap pada perkebunan kelapa sawit di lahan gambut
umumnya dilakukan secara konvensional, yaitu dengan lebih mengutamakan
insektisida, bahkan sering dilakukan aplikasi terjadwal tanpa didahului dengan
monitoring populasi rayap. Cara ini tidak efisien karena seluruh areal tanaman
diaplikasi dengan insektisida. Disamping memboroskan uang, juga akan
menimbulkan dampak buruk berupa pencemaran lingkungan (Purba dkk, 2002).
Pengendalian rayap hingga saat ini masih mengandalkan penggunaan
insektisida kimia (termisida), yang dapat diaplikasikan dalam beberapa cara yaitu
melalui penyemprotan, atau pencampuran termisida dalam bentuk serbuk atau
granula dengan tanah. Teknik penyuntikan pada bagian pohon atau sistem
perakaran tanaman yang terserang atau dengan cara penyiraman disekitar tanaman
(Nandika dkk, 2003).
Pengendalian hama terpadu (PHT) termasuk pengendalian rayap pada
kelapa sawit berpedoman pada Undang- undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman. Dalam sistem tersebut pengendalian hayati dengan
memanfaatkan musuh alami hama seperti parasitoid, predator dan pathogen
menjadi komponen utama, sedangkan secara kimiawi merupakan alternatif
terakhir (Purba dkk, 2002).
Pengumpanan adalah salah satu teknik pengendalian yang ramah
lingkungan. Dilakukan dengan menginduksi racun slow action ke dalam kayu
umpan, kemudian kayu tersebut dimakan rayap pekerja dan di sebarkan ke dalam
koloninya. Teknik pengumpanan selain untuk mengendalikan juga dapat
Perilaku Rayap
Semua rayap makan kayu dan bahan berselulosa, tetapi perilaku makan
(feeding behavior) jenis-jenis rayap bermacam-macam. Hampir semua jenis kayu
potensial untuk dimakan rayap. Memang ada yang relatif awet seperti bagian teras
dari kayu jati tetapi kayu jati kini semakin langka. Untuk mencapai kayu bahan
bangunan yang terpasang rayap dapat keluar dari sarangnya melalui
terowongan-terowongan atau liang-liang kembara yang dibuatnya. Bagi rayap subteran
(bersarang dalam tanah tetapi dapat mencari makan sampai jauh di atas tanah),
keadaan lembab mutlak diperlukan. Hal ini menerangkan mengapa
kadang-kadang dalam satu malam saja rayap Macrotermes dan Odontotermes telah
mampu menginvasi lemari buku di rumah atau di kantor jika fondasi bangunan
tidak dilindungi. Sebaliknya, rayap kayu kering (Cryptotermes) tidak memerlukan
air (lembab) dan tidak berhubungan dengan tanah. Juga tidak membentuk
terowongan-terowongan panjang untuk menyerang obyeknya. Mereka bersarang
dalam kayu, makan kayu dan jika perlu menghabiskannya sehingga hanya lapisan
luar kayu yang tersisa dan jika di tekan dengan jari serupa menekan kotak kertas
saja (Tarumingkeng, 2007).
Pola perilaku rayap adalah kriptobiotik atau sifat selalu menyembunyikan
diri, mereka hidup didalam tanah dan bila akan invasi mencari objek makanan
juga menerobos di bagian dalam, bila terpaksa harus berjalan dipermukaan yang
terbuka, mereka membentuk pipa pelindung dari bahan tanah atau humus
(Tarumingkeng, 2004).
Setiap koloni rayap mengembangkan karakteristik tersendiri berupa bau
menemukan sumber makanan karena mereka mampu untuk menerima dan
menafsirkan setiap ransangan bau yang esensial bagi kehidupannya. Bau yang
dapat dideteksi rayap berhubungan dengan sifat kimiawi feromonnya sendiri
(Borror dkk, 1992).
Sistem Sarang
Membuat sarang dan hidup di dalam sarang merupakan karakteristik dari
serangga social. Beberapa jenis rayap membuat sarangnya dalam bentuk
lorong-lorong di dalam kayu atau atau lorong-lorong-lorong-lorong dalam tanah, tetapi jenis rayap
tertentu sarangnya membentuk bukit - bukit dengan konstruksi sarang yang sangat
kokoh dan sangat luas (Nandika dkk, 2003).
Bahan yang digunakan untuk membangun sarang sangat tergantung pada
makanan dan bahan yang tersedia di habitatnya. Tanah, kotoran dan sisa
tumbuhan serta air liur merupakan bahan utama untuk pembuatan sarang. Partikel
tanah yang seringkali digunakan untuk membangun sarang dan merupakan
komponen yang dominan dapat diklasifikasikan menurut ukurannya, yaitu kerikil
>2,00 mm, pasir kuarsa 2,0-0,2 mm, pasir halus 0,2-0,02 mm, lumpur 0,02-0,002
mm, dan liat < 0,002 mm. Sedangkan kotoran dan air liur berfungsi sebagai
Gambar 2. Sarang Rayap Sumber: Majalah Proyeksi
Insektisida Nabati (Daun Sirsak)
Sirsak dapat tumbuh hampir di semua tempat sampai ketinggian
900 m dpl. Sirsak merupakan pohon dengan tinggi dapat mencapai sekitar 8 m.
Batang berkayu, bulat dan bercabang. Daun tunggal, bulat telur, ujung runcing,
tepi rata, panjang antara 6-18 cm dan berwarna hijau kekuningan. Bunga tunggal
terletak pada batang dan ranting, ukuran kelopak kecil dan berwarna kuning
keputihan atau kuning muda. Buah majemuk, bulat telur, panjang 15-35 cm,
diameter 10-15 cm dan berwarna hijau. Biji bulat telur, keras dan berwarna hitam
(Mulyaman dkk, 2000).
Kandungan yang terdapat pada buah yang mentah, biji, daun dan akar
sirsak yaitu senyawa annonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida,
repellent (penolak serangga) dan antifeedant (penghambat makan) dengan cara
kerja racun kontak dan racun perut. Untuk ramuan insektisida nabati, daun dan
Gambar 3. Daun Sirsak Sumber: Foto Langsung
Dari tanaman sirsak telah berhasil diisolasi beberapa senyawa acetogenin
antara lain asimisin, bulatacin, dan squamosin. Pada konsentrasi tinggi,
acetogenin akan bersifat anti feedant bagi serangga, sehingga menyebabkan
serangga tidak mau makan. Pada konsentrasi rendah bersifat racun perut dan dapat
menyebabkan kematian. Senyawa acetogenin bersifat sitotoksin sehingga
menyebabkan kematian sel. Bulatacin diketahui menghambat kerja enzim NADH
ubiquinone reduktase yang diperlukan dalam reaksi respirasi di mitokondria
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Departemen Hama dan
Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan dengan
ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan
pada bulan Juni 2010 sampai dengan selesai.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rayap, bubuk daun
sirsak, serbuk gergaji, tissue dan rumah rayap.
Alat yang digunakan adalah kuas kecil, kain kasa, stoples plastik, lesung,
karet, timbangan analisis, dan alat-alat lain yang diperlukan dalam penelitian.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL)
faktorial dengan 2 faktor perlakuan, yaitu:
Faktor bubuk daun sirsak yaitu :
Do = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)
D1 = bubuk daun sirsak 4 g/toples (20 ekor/toples)
D2 = bubuk daun sirsak 6 g/toples (20 ekor/toples)
D3 = bubuk daun sirsak 8 g/toples (20 ekor/toples)
Faktor jenis umpan/media yaitu : U1 = umpan serbuk gergaji (15 g/toples)
U3 = umpan rumah rayap (15 g/toples)
Kombinasi perlakuan (t) : 4 X 3 = 12 perlakuan.
D0U1 D1U1 D2U1 D3U1
D0U2 D1U2 D2U2 D3U2
D0U3 D1U3 D2U3 D3U3
Keterangan :
D0U1 = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan serbuk gergaji (15 g/20
ekor/toples)
D0U2 = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan kertas tissue (15 g/20
ekor/toples)
D0U3 = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan rumah rayap (15 g/20
ekor/toples)
D1U1 = bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20
ekor/toples)
D1U2 = bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20
ekor/toples)
D1U3 = bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20
ekor/toples)
D2U1 = bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20
ekor/toples)
D2U2 = bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20
ekor/toples)
D2U3 = bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20
D3U1 = bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20
ekor/toples)
D3U2 = bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20
ekor/toples)
D3U3 = bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20
ekor/toples)
Model linear yang digunakan adalah :
Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + ξijk
Keterangan :
Yijk = respon atau nilai pengamatan taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari
faktor B pada ulangan ke-k
μ = nilai tengah umum
αi = pengaruh taraf ke-i dari faktor A
βj = pengaruh taraf ke-j dari faktor B
(αβ)ij = pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B
ξijk = pengaruh galat percobaan taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari
faktor B pada ulangan ke-k
Jumlah ulangan diperoleh dengan rumus :
((t1.t2)-1) ( r-1) ≥ 15
((4.3)-1) (r-1) ≥ 15
11r ≥ 26
r ≥ 2,36
r = 3
Jumlah Ulangan (r) = 3
Pelaksanan Penelitian Persiapan Rayap
Serangga rayap yang telah dewasa diambil masing-masing 20 ekor untuk
setiap perlakuan. Setelah rayap tersebut dimasukkan ke dalam stoples yang telah
berisi umpan maka stoples ditutup dengan kain kasa dan selanjutnya
stoples-stoples tersebut disusun sesuai dengan perlakuan yang telah ditetapkan.
Pengambilan rayap dilakukan dengan memeriksa batang sisa-sisa dari
perkebunan kelapa sawit atau diambil dari bongkahan kayu pada perkebunan
kelapa sawit. Kemudian diambil koloni rayap dari kasta pekerja dan dibawa ke
laboratorium.
Persiapan Insektisida Nabati
Diambil daun yang segar dari lapangan, kemudian dicuci untuk
membersihkan dari kotoran yang melekat. Daun yang telah dicuci dan dibersihkan
dari kotoran ditumbuk sampai halus kemudian dijemur di bawah terik matahari.
Setelah daun sirsak tersebut kering siap untuk diaplikasikan.
Aplikasi
Rayap yang telah diambil dari lapangan kemudian dimasukkan ke dalam
stoples yang telah berisi serbuk gergaji, kertas tissue dan rumah rayap yang telah
dicampur dengan bubuk sirsak secara merata masing-masing 20 rayap. Kemudian
ditutup dengan menggunakan kain kasa dan diikat dengan karet gelang. Sebaiknya
Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren. kasta pekerja yang telah
diaplikasikan dengan menggunakan bubuk sirsak diamati 3 hari setelah aplikasi.
Pengamatan dilakukan selama 8 kali dengan interval 3 hari sekali.
Peubah Amatan
Persentase Mortalitas (%)
Persentase mortalitas dihitung dengan menggunakan rumus:
P = a x 100%
b a+
Keterangan:
P = Persentase mortalitas
a = Jumlah rayap yang mati
b = Jumlah rayap yang hidup
Persentase Kehilangan Umpan (%)
Penimbangan berat berbagai jenis umpan yang telah diberi perlakuan
dilakukan sebelum dan setelah akhir pengamatan dengan menggunakan rumus:
Kehilangan umpan = x 100% a
b -a
Keterangan:
a = berat awal
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh Perlakuan Bubuk Daun Sirsak Terhadap mortalitas Rayap Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mulai dari 3 hsa menunjukkan
tidak adanya perbedaan yang nyata diantara perlakuan. Sedang pada pengamatan
berikutnya yaitu mulai pada 6–24 hsa terlihat hasil bahwa semua perlakuan
berbeda nyata terhadap kontrol. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap Persentase Mortalitas Rayap.
Keterangan: Notasi huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji jarak Duncan.
Do = tanpa bubuk daun sirsak (kontrol)
D1 = bubuk daun sirsak 4 g/toples (20 ekor/toples)
D2 = bubuk daun sirsak 6 g/toples (20 ekor/toples)
D3 = bubuk daun sirsak 8 g/toples (20 ekor/toples)
Sesuai pendapat Agus Kardiman (1999) yang menyatakan bahwa pestisida
sirsak tidak membunuh hama secara cepat, tetapi berpengaruh mengurangi nafsu
makan, pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti kulit, hambatan menjadi
serangga dewasa, sebagai pemandul, mengganggu dan menghambat proses
perkawinan serangga, menghambat peletakan dan penurunan daya tetas telur dan
Tabel 1 menunjukan pada pengamatan 24 hsa diperoleh hasil D0 (kontrol)
berbeda sangat nyata dengan perlakuan yang lainnya, perlakuan D0 (umpan
dicampur bubuk daun sirsak 4 g/toples) berbeda sangat nyata dengan perlakuan
lainnya, D2(umpan dicampur bubuk daun sirsak 6 g/toples) berbeda sangat nyata
dengan perlakuan lainnya dan D3 (umpan media dicampur bubuk daun sirsak 8
g/toples) berbeda sangat nyata dengan perlakuan lainnya.
Persentase mortalitas tertinggi pada pengamatan 24 hsa terdapat pada
perlakuan D3 (umpan media dicampur bubuk daun sirsak 8 g/toples) yaitu sebesar
62.76% dan terendah terdapat pada perlakuan D0 (kontrol) yaitu sebesar 36.56%.
Gambar 4 : Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap Persentase Mortalitas Rayap
Gambar Histogram di atas menunjukkan bahwa pemberian dosis yang
berbeda menghasilkan mortalitas rayap yang berbeda. Diantara semua perlakuan,
mortalitas rayap tertinggi terdapat pada perlakuan D3 yaitu umpan media
dicampur bubuk daun sirsak 8 g/toples sebesar 62.76 % pada pengamatan 24 hsa,
51.49%. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Kardiman (2005), yang
menyatakan bahwa daun sirsak yang mengandung senyawa acetogenin, antara lain
asimisin, bulatacin dan squamosin. Pada konsentrasi tinggi, senyawa acetogenin
memiliki keistimewaan sebagai anti feedent. Dalam hal ini, serangga hama tidak
lagi bergairah untuk melahap bagian tanaman yang disukainya. Sedangkan pada
konsentrasi rendah, bersifat racun perut yang bisa mengakibatkan serangga hama
menemui ajalnya. Sehingga ekstrak daun sirsak dapat dimanfaatkan untuk
menanggulangi hama seperti belalang dan hama-hama lainnya.
2. Pengaruh Perlakuan Berbagai Jenis Umpan Terhadap mortalitas Rayap
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan mulai dari 3 hsa tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata. Sedang pada pengamatan berikutnya yaitu di 6
hsa terlihat hasilnya bahwa semua perlakuan tidak berbeda nyata seperti yang tertera
dalam Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan Terhadap Persentase Mortalitas
Keterangan: Notasi huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji jarak Duncan.
U1 = umpan serbuk gergaji (15 g/toples)
U2= umpan kertas tissue (15 g/toples)
U3 = umpan rumah rayap (15 g/toples)
Hasil penelitian terlihat pada 6 hsa menunjukkan bahwa perlakuan umpan
rumah rayap (U3). Sedangkan perlakuan serbuk gergaji (U1) dan rumah rayap (U3)
tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan tidak berkembangnya rayap yang diberi
umpan atau media dikarenakan media atau bahan makanan yang dibutuhkan rayap
tidak sesuai dengan kebutuhannya.
Hasil penelitian 18 hsa menunjukkan pada perlakuan umpan media serbuk
gergaji (U1) tidak berbeda nyata dengan umpan media rumah rayap (U3), tetapi
berbeda nyata dengan perlakuan umpan media tissue (U2). Pada hasil penelitian 21-24
hsa, perlakuan umpan media tissue (U2) berbeda nyata dengan perlakuan umpan
media serbuk gergaji (U1) dan perlakuan umpan media rumah rayap (U3).
Gambar 5: Histogram Hasil Penelitian Pengaruh Berbagai Jenis Umpan Terhadap Persentase Mortalitas.
Dari gambar Histogram di atas menjelaskan mulai dari setiap waktu
pengamatan (3-24 has) bahwa tingkat mortalitas rayap lebih tinggi pada perlakuan
umpan media tissue (U2) jika dibandingkan dengan kedua perlakuan media lainnya
dengan pendapat Elri Ritonga (2006), bahwa pengendalian rayap dapat dilakukan
dengan memberikan umpan berupa kertas yang diperkaya enzim heksaflumuron
yang berfungsi menghambat pembentukkan kulit luar sehingga rayap mati.
Umpan ini akan diboyong rayap ke sarangnya, umpan yang diberikan dalam
2 sampai 3 bulan maka satu koloni rayap mati. Hasil rata-rata tingkat kematian
yang tinggi pada hari ke 24 hsa. Sedang perlakuan (U3) yaitu umpan media rumah
rayap yang diambil dari sarang rayap di tanah, tingkat kematian jauh lebih tinggi
jika dibandingkan dengan perlakuan umpan serbuk gergaji (U1).
Menurut pendapat Rudi Tarumingkeng (1971), semua rayap makan kayu dan
bahan berselulosa, hampir semua jenis kayu potensial untuk dimakan rayap. Hal ini
menerangkan mengapa kadang-kadang dalam satu malam saja rayap Macrotermes
dan Odontoterme telah mampu menginvasi lemari buku di rumah atau di kantor jika
fondasi bangunan tidak dilindungi. Mereka bersarang dalam kayu, makan kayu dan
jika perlu menghabiskannya sehingga hanya lapisan luar kayu yang tersisa, dan jika
di tekan dengan jari serupa menekan kotak kertas saja. Ada pula rayap yang makan
kayu yang masih hidup dan bersarang di dahan atau batang pohon, seperti pada
tanaman jati.
Menurut Dodi Nandika (2003), habitat rayap membutuhkan kisaran suhu
21,1-26,6
0
C dengan kelembaban optimal 95-98% yang merupakan surga bagi rayap.
Sementara suhu pada tempat penelitian berkisar 27–28
0
C, hal ini merupakan neraka
bagi rayap, sehingga tingkat kematian rayap lebih tinggi dibandingkan dengan 2
perlakuan lainnya. Hal lain yang menyebabkan rayap mati dikarenakan makanan
3. Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap.
Pada Table 3 dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya
perbedaan yang nyata diantara semua perlakuan mulai dari 3-12 hsa. Sedang pada
pengamatan berikutnya yaitu 15–24 hsa terlihat hasilnya bahwa semua perlakuan
berbeda nyata diantara perlakuan (Tabel 3).
Tabel 3. Hasil penelitian Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap.
Perlakuan
Keterangan: Notasi huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji jarak Duncan.
Dari Tabel di atas jelas terlihat bahwa 3 hsa sampai 12 hsa tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata diantara semua perlakuan. Hasil penelitian
terlihat pada perlakuan 24 hsa menunjukkan bahwa interaksi perlakuan D0U1
(kontrol dan umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D0U2 (kontrol dan
nyata dengan perlakuan D0U3 (kontrol dan umpan rumah rayap (15 g/20
ekor/toples)) dan D1U1 (bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan serbuk gergaji
(15 g/20 ekor/toples)). D1U2 (bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan kertas
tissue (15 g/20 ekor/toples)), D1U3 (bubuk daun sirsak 4 g/toples dan umpan
rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)), D2U1 (bubuk daun sirsak 6 g/toples dan
umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D2U2 (bubuk daun sirsak 6 g/toples
dan umpan tissue (15 g/20 ekor/toples)), D2U3 (bubuk daun sirsak 6 g/toples dan
umpan rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)), D3U1 (bubuk daun sirsak 8 g/toples
dan umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)), D3U3 (bubuk daun sirsak 8
g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)) berbeda nyata dengan
perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan tissue (15 g/20
ekor/toples))
Gambar 6: Histogram Hasil penelitian Pengaruh interaksi Perlakuan bubuk daun sirsak dengan faktor jenis umpan terhadap mortalitas rayap.
Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa pengaruh interaksi antar
24 hsa mortalitas rayap tertinggi terdapat pada perlakuan D3U2 (bubuk daun sirsak
8 g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 93.33 %
yang diikuti D3U3 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20
ekor/toples)) yaitu sebesar 68.33 %, D3U1 (bubuk daun sirsak 8 g/toples dan
umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)) dan D2U2 (bubuk daun sirsak 6
g/toples dan umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 66.67 %,
D2U3 (bubuk daun sirsak 6 g/stoples dan umpan rumah rayap (15 g/20
ekor/stoples)) 61.67 %, D2U1 (bubuk daun sirsak 6 g/toples dan umpan serbuk
gergaji (15 g/20 ekor/toples)) 55.00%, D1U2
(bubuk daun sirsak 4 g/toples dan
umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) 53.33%, D1U3 (bubuk daun sirsak 4
g/toples dan umpan rumah rayap (15 g/20 ekor/toples)) 51.67 %, D1U1 (bubuk
daun sirsak 4 g/toples dan umpan serbuk gergaji (15 g/20 ekor/toples)) 41.67 %,
D0U3 ( tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan rumah rayap (15 g/20
ekor/toples)) 36.67%, D0U1 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan umpan serbuk
gergaji (15 g/20 ekor/toples) dan D0U2 (tanpa bubuk daun sirsak (kontrol) dan
umpan kertas tissue (15 g/20 ekor/toples)) yaitu sebesar 35.00%.
Menurut Dodi Nandika (2003), interaksi perlakuan ini terjadi dikarenakan
penanggulangan dengan menggunakan insektisida nabati pada rayap sifatnya
sementara. Keandalannya hanya berlangsung selama zat penghalang masih ada,
sejalan dengan menyusutnya konsentrasi zat maka keampuhannya menurun.
Rayap akan kembali begitu zat habis sama sekali. Sedangkan disisi lain pestisida
kimia dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran
4. Pengaruh Perlakuan Daun Sirsak Terhadap Kehilangan Umpan.
Tabel 4. Hasil Penelitian Pengaruh Bubuk Daun Sirsak Terhadap Kehilangan Umpan (%) Pada Pengamatan Terakhir (24 hsa).
Perlakuan Rataan
D0
44.30 a
D1 39.02 b
D2 32.77 c
D3 30.94 d
Keterangan : Notasi yang ditandai huruf yang sama dalam satu kolom tidak berbeda nyata pada taraf 5%.
Hasil penelitian menunjukkan pada pengamatan terakhir (24 hsa) dapat dilihat
pada tabel ke 4, dimana perlakuan D0 (kontrol) berbeda sangat nyata terhadap
perlakuan yang lainnya, D1(bubuk daun sirsak 4 g/toples) berbeda sangat nyata
terhadap perlakuan yang lainnya, D2 (bubuk daun sirsak 6 g/toples) berbeda
sangat nyata terhadap perlakuan yang lainnya dan perlakuan D3 (bubuk daun sirsak 8
g/toples) berbeda sangat nyata terhadap perlakuan yang lainnya.
Dari gambar Grafik dapat kita lihat bahwa perlakuan D3 lebih efektif
dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya, yang ditandai dengan nilai susut
bobot bahan yang paling terendah. Sementara D0 memiliki nilai susut bobot yang
paling tinggi, sehingga kita mengetahui bahwa persentase penyusutan bobot bahan
banding terbalik dengan persentase nilai mortalitas imago rayap.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pengaruh perlakuan bubuk daun sirsak yang terbaik untuk mengendalikan rayap
adalah pada perlakuan D3 (dosis bubuk daun sirsak 8 g/toples).
2. Berbagai jenis umpan untuk mengendalikan hama rayap, yang terbaik adalah
dengan menggunakan perlakuan U2(umpan media tissue).
3. Penggunaan insektisida nabati yang dimodifikasi dengan berbagai jenis umpan
dapat digunakan untuk mengendalikan rayap. Perlakuan yang terbaik adalah D3U2
(dosis 8 g/toples dengan umpan tissue)
yaitu 93.33%.
4. Pemanfaatan daun sirsak dapat digunakan untuk mengendalikan rayap pada area
pertanaman ataupun area pemukiman.
5. Pengaruh kehilangan umpan terhadap perlakuan bubuk sirsak yang menunjukkan
hasil kehilangan yang tertinggi adalah pada perlakuan D0(kontrol). Dimana bahwa
semakin rendah mortalitas hama rayap, maka kehilangan umpan semakin besar
dan sebaliknya semakin tinggi mortalitas hama rayap, maka kehilangan umpan
semakin rendah.
Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan insektisida nabati
dan berbagai jenis umpan untuk mengendalikan hama rayap di area pertanaman atau
area permukiman.
DAFTAR PUSTAKA
Anonimus, 2007. Chitosan.
.
, 2009. Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Menuju Sustainable
Palm Oil.
Bakti, D. 2004. Pengendalian Rayap coptotermes curvinagthus Holmgren menggunakan Nematoda steinernema carpocapsae W. Dalam skala Laboratorium. Jurnal Natur Indonesia, 6(2):81-83.
Borror, Triplehorn dan Johnson. 1992. Pengenalan Pelajaran Serangga. UGM Press Yogyakarta.
Ritonga, E., 2006. Jamur Pembunuh ‘Musuh dalam Selimut’ Deptan, Bogor. Tempo, 14 Mei 2006.
Ginting, C.S, Ps. Sudarto, dan Chenon, D. R. 2002. Strategi Pengendalian Rayap Pada Kelapa Sawit di Lahan Gambut. Warta PPKS. Medan.
Hasan, T. 1986. Rayap dan Pemberantasannya (Penanggulangan dan Pencegahan). Yasaguna, Jakarta.
Kalshoven, L.G.H. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. PT. Ichtiar Baru van Hoove, Jakarta.
Kardiman, A. 2004. Pestisida Nabati Ramusan dan Aplikasi. Penebar Swadaya, Jakarta.
Kardiman, A. 1999. Pestisida Nabati, Rumusan dan Aplikasi.Penebar Swadaya. Jakarta II. RAMUAN DAN APLIKASI PESTISIDA NABATI http://www.softwarelabs.com
Mulyaman, S., Cahyaniati, I. Adam dan T. Mustofa. 2000. Pengendalian Pestisida Nabati Tanaman Hortikultura. Direktorat Perlindungan Tanaman, Jakarta.
Nandika, D., Y. Rismayadi dan F. Diba. 2003. Rayap, Biologi dan Pengendalian. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
Prasetiyo, K.W. dan S. Yusuf, 2005. Mencegah dan membasmi Rayap secara Ramah Lingkungan dan Kimiawi.
Purba, Y.R., Sudharto Ps, dan R. D. de Chenon. 2002. Strategi Pengendalian Rayap pada Lahan Gambut. Warta PPKS. Medan Sumatera Utara.
Risza, S.,1994. Seri Budidaya Kelapa Sawit. Kanisius, Yogyakarta
Soepadiyo, M. dan S. Haryono. 2003. Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Surbakti, J. 2008. Pestisida Nabati Cara Pembuatan dan Pemanfaatannya. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Karo, Kabanjahe
Tarumingkeng, R.C., 2004. Biologi Dan Pengendalian Rayap Hama Bangunan di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2010.
Tarumingkeng, R.C., 2005. Biologi Dan Perilaku Rayap. 19 April 2010.
Tarumingkeng, R.C. 2007. Biologi Dan Perilaku Rayap.
Lampiran 2. Data Pengamatan 3 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan I Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Lampiran 3. Data Pengamatan 6 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan II Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Tabel Dwi Kasta Total
Tabel Dwi Kasta Rataan
Uji Jarak Duncan
Faktor D
sy 1.24
P 2 3 4
SSR 0.05 2.92 3.07 3.15
LSR 0.05 3.62 3.81 3.91
Perlakuan D0 D1 D2 D3
Rataan 8.21 9.61 14.90 17.08
a
b
Uji Jarak Duncan
Faktor U
sy 1.07
P 2 3
SSR 0.05 2.92 3.07
LSR 0.05 3.14 3.30
Perlakuan U1 U3 U2
Rataan 9.84 11.81 15.68
∙a
Lampiran 4. Data Pengamatan 9 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan III Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Tabel Dwi Kasta Total
Tabel Dwi Kasta Rataan
Uji Jarak Duncan Faktor D
sy 1.56
P 2 3 4
SSR 0.05 2.92 3.07 3.15
LSR 0.05 4.55 4.78 4.91
Perlakuan D0 D1 D2 D3
Rataan 11.18 12.87 19.14 26.68
∙a ∙b
c
Uji Jarak Duncan
Faktor U
sy 1.35
P 2 3
SSR 0.05 2.92 3.07
LSR 0.05 3.94 4.14
Perlakuan U1 U3 U2
Rataan 14.62 15.60 22.18
∙a
Lampiran 5. Data Pengamatan 12 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan IV Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Tabel Dwi Kasta Total
Tabel Dwi Kasta Rataan
Uji Jarak Duncan
Faktor D
sy 1.63
P 2 3 4
SSR 0.05 2.92 3.07 3.15
LSR 0.05 4.75 4.99 5.12
Perlakuan D0 D1 D2 D3
Rataan 13.06 17.75 25.38 32.83
∙a
∙b
c
Uji Jarak Duncan
Faktor U
sy 1.41
P 2 3
SSR 0.05 2.92 3.07
LSR 0.05 4.11 4.32
Perlakuan U1 U3 U2
Rataan 18.50 20.50 27.77
∙a
Lampiran 6. Data Pengamatan 15 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan V Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Tabel Dwi Kasta Total
Tabel Dwi Kasta Rataan
Lampiran 7. Data Pengamatan 18 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan VI Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Tabel Dwi Kasta Total
Tabel Dwi Kasta Rataan
Lampiran 8. Data Pengamatan 21 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan VII Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Tabel Dwi Kasta Total
Tabel Dwi Kasta Rataan
Lampiran 9. Data Pengamatan 24 hsa Persentase (%) Mortalitas Rayap Coptotermes curvignatus Holmgren.
Data Pengamatan VIII Mortalitas
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Data Tranformasi √x
Perlakuan Ulangan Total Rataan
Tabel Dwi Kasta Total
Tabel Dwi Kasta Rataan
Lampiran 10. Data Susut Bobot Bahan.
Perlakuan Ulangan Total Rataan
I II III
Tabel Dwi Kasta Rataan
Uji Jarak Duncan Faktor D
sy 0.15
P 2 3 4
SSR 0.05 2.92 3.07 3.15
LSR 0.05 0.43 0.45 0.46
Perlakuan D3 D2 D1 D0
Rataan 30.94 32.77 39.02 44.30
.a .b
.c
Lampiran 11.
DESKRIPSI BAGAN PENELITIAN
Gambar 2. U1 (Umpan Serbuk gergaji)
Gambar 3. U2 (Umpan kertas Tissue)