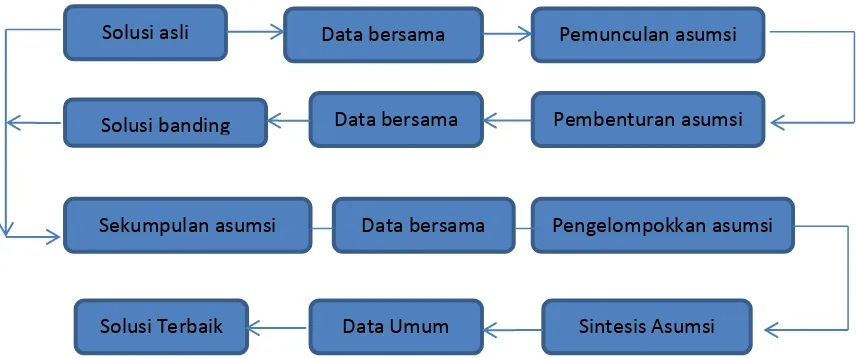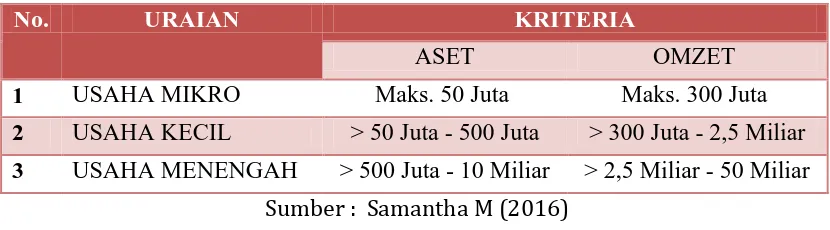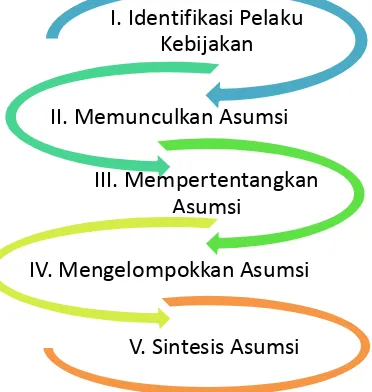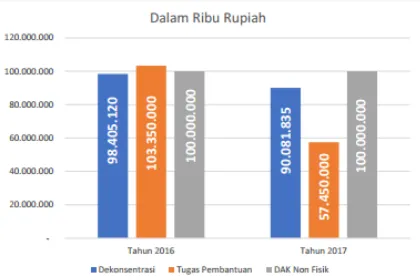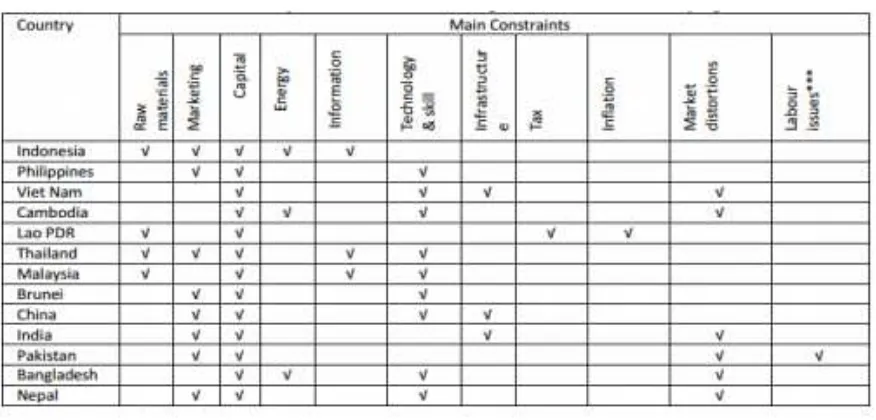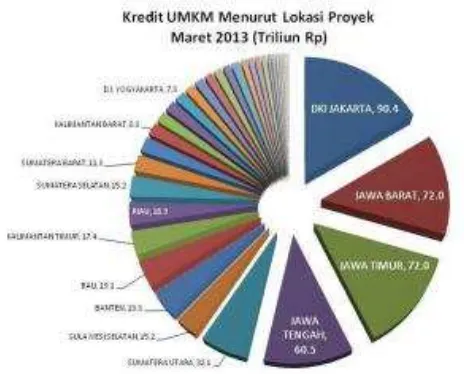i
TELAAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA
DALAM KERANGKA ANALISIS ASUMSI
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iii
DAFTAR GAMBAR ... iv
A. Pendahuluan ... 1
B.Teknik Analisis Asumsi ... 3
C. Perumusan Masalah Pengembangan UKM di Indonesia ... 6
I. Identifikasi Pelaku Kebijakan ... 9
II. Asumsi Pemerintah: Pemberdayaan melalui Lembaga Pembiayaan ... 11
III. Mempertentangkan Asumsi ... 14
IV. Pengelompokkan Asumsi ... 16
V. Sintesis Asumsi ... 20
D.Rekomendasi Kebijakan ... 21
iii DAFTAR TABEL
Tabel 1. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia ... 6
Tabel 2. Kendala Utama UMKM di Beberapa Negara ... 15
iv DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Proses Analisis Asumsi ... 5
Gambar 2. Kontribusi UKM terhadap PDB, Penyerapan Tenaga Kerja, dan
Total Ekspor di Indonesia 2015 ... 8
Gambar 3. Tahapan Metode Analisis Asumsi ... 8
Gambar 4. Sumber Pembiayaan Pemberdayaan Koperasi dan UKM oleh
Kementerian Koperasi dan UKM 2017 ... 11
Gambar 5. Alokasi Anggaran Kemenkoukm terhadap
Pembiayaan UMKM Tahun 2017 ... 12
Gambar 6. Alokasi Kredit UMKM di Indonesia ... 17
1 A. PENDAHULUAN
Daya dukung terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, salah satu dapat
ditinjau melalui kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Indonesia
telah memiliki payung hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20
tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga turut mencerminkan
komitmen pemerintah mewujudkan masyarakat ekonomi produktif. Disisi lain peran
pentingnya dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai upaya alternatif penyerapan
tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan.
Bersamaan dengan sejarah bangsa yang mengalami krisis ekonomi sekitar tahun
1997-1998, tidak banyak UMKM mampu berdikari. Sebaliknya justru pasca krisis
terjadi peningkatan UMKM dan terhitung hingga tahun 2012 mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 85 – 107 juta/orang. Pada tahun yang sama jumlah UMKM
sebanyak 56.534.592 unit dari total pengusaha di Indonesia 56.539.560 unit, dan
usaha besar tercatat sejumlah 4.968 unit. Tentu jika melihat data tersebut
menegaskan kembali eksistensi UMKM sangat berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Dimana Badan Pusat Statistik di tahun
2012 juga merilis tingkat pengangguran mengalami penurunan sebanyak 0,6% dari
6,8% (Februari 2011) menjadi 6,32% (Februari 2012).
Selanjutnya melihat perbaikan kondisi tersebut, lalu apa saja yang telah
dilakukan sekaligus sebagai terobosan kerja pemerintah?. Bukan hanya berpijak
pada kebijakan yang telah diterbitkan seperti diungkapkan diatas, ternyata
pemerintah telah melakukan upaya sinergitas inovasi program-program dari
berbagai departemen dan lembaga pemerintah cukup memiliki andil besar dalam
upaya pengembangan UMKM. Meliputi program 1)Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) binaan Departemen Sosial, 2)Proyek Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP), lebih dikenal dengan nama BKM (Badan Keswadayaan
Masyarakat), binaan Departemen Pekerjaan Umum, 3)Proyek Pemberdayaan
Kecamatan (PPK), binaan Departemen Dalam Negeri, 4)Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), binaan BKKBN, 5)Proyek Peningkatan
Pendapatan Petani Kecil (P4K), binaan Departeman Pertanian, 6)Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), binaan Departemen Kelautan dan Perikanan,
2 Koperasi UMKM. Dengan begitu kompleksnya program yang diselenggarakan
pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, menjadi tantangan bagaimana
proses implementasi agar sesuai dengan track dan tidak tumpang tindih satu dengan
lainnya. Adapun hadirnya tantangan dalam pengembangan UMKM ini dapat bermula
dari masalah internal UMKM dan/atau faktor eksternal seperti kondisi iklim usaha
UMKM.
Kementerian Koperasi dan UMKM (2015) menyebutkan terdapat 2 aspek utama
masalah internal UMKM yang tercantum dalam Data Inventarisasi Masalah (DIM),
antara lain: (1) Aspek rendahhnya kualitas Sumber Daya Manusia baik dari tingkat
pendidikan, pengalaman, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi; (2) Aspek usaha
permasalahan yang dihadapi berupa rendahnya rata-rata kepemilikan aset modal
kerja, dan terbatasnya jaringan usaha atau networking. Sementara itu, masalah
eksternal yang menyelimuti upaya pengembangan UMKM adalah pertama,
kurangnya ketersediaan prasarana baik fisik maupun non fisik kelembagaan atau
peraturan Perundang-undangan dan organisasi pendukug pengembangan eksistensi
UMKM. Kedua, pengaruh dari kebijakan makro berupa kebijakan fiskal termasuk
subsidi dan pajak, dan kebijakan moneter termasuk peranan bank sebagai pihak
kemitraan dalam permodalan UMKM. Ketiga, masalah terkait iklim usaha yang
harus dihadapi UMKM berupa peluang usaha, kondisi pasar input dan output belum
berpihak sepenuhnya pada UMKM, serta belum mudahnya akses terhadap
sumberdaya produktif. Hal ini akan diperparah dengan posisi Indonesia yang telah
mendatangi perjanjian perdagangan lintas negara Asean dan China disebut dengan
Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Dengan perjanjian tersebut pemerintah
berharap dapat menjadi peluang pengembangan ekspor bagi usaha-usaha di
Indonesia.
Adapun beberapa stakeholder lain menyepakati bahwa masalah utama
pengembangan UMKM di Indonesia berpaku pada akses pembiayaan atau modal,
selanjutnya diikuti dengan permasalahan administrasi, teknologi dan inovasi produk,
riset pasar, dan inefisiensi (Andi dan Rizal, 2014). Mengenai akses pembiayaan,
peran serta perbankan sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004, yang menyatakan
tentang kebijakan Bank Indonesia membantu pengembangan usaha kecil dan
3 Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Selanjutnya, apabila meninjau dari aspek inovasi
produk yang dihasilkan oleh UMKM di Indoensia, Menteri BUMN, Rini Soemarno
(2016) mengatakan masih perlunya inovasi dalam packaging. Hal ini dikarenakan
kemasan merupakan hal yang terkadang sederhana tetapi memiliki dampak besar
sebagai daya pikat beli oleh konsumen.
Demikian, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai leading
sector dirasa telah cukup banyak melakukan upaya dalam pengembangan UMKM
seperti program dan kegiatan yang terjabarkan sebelumnya. Namun upaya yang
sudah dilakukan belum mampu memberikan banyak perubahan. Oleh karenanya,
diperlukan pengkajian kembali perumusan masalah agar menghasilkan
konseptualisasi atas kondisi masalah yang terjadi.
B.TEKNIK ANALISIS ASUMSI
Dalam tahapan formulasi kebijakan terlebih yang dilakukan adalah bagaimana
masalah yang ada terdefinisikan dengan jelas dan benar. Ackoff (Dunn, 2000)
menyebutkan bahwa kegagalan sering terjadi ketika analis memecahkan masalah
yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar.
Oleh karenanya, keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan solusi
yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Selain itu, untuk memahami lebih jauh
dalam merumuskan masalah maka tuntutan bagi analisis yaitu harus mampu
berpikir secara kreatif. Dunn (226: 2000) telah mendefinisikan kriteria menilai
tindakan kreatif analis apabila produk analisis cukup baru sehingga menghasilkan
solusi yang terbaru dan berbeda, dan produk analisis bermanfaat bagi para analis,
pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan.
Perumusan masalah juga dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari
empat tahap yakni, (1) pencarian masalah; (2) pendefinisian masalah; (3) spesifikasi
masalah; dan (4) pengenalan masalah (Dunn, 2000). Selain itu, Patton dan Sawicki
(Subarsono, 2013) memberikan usulan 7 tahap yang sebaiknya dilalui dalam
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. memikirkan mengapa suatu gejala dianggap sebagai masalah
2. tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan
3. kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang
4 4. rumuskan tujuan dan sasaran yang dicapai
5. identifikasi policy envelope (variabel-variabel yang mempengaruhi masalah)
6. tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi
7. rumuskan masalah kebijakannya dengan baik.
Untuk mempermudah analis dalam merumuskan masalah, Dunn menawarkan
berbagai metode-metode perumusan masalah antara lain analisis batas, analisis
krarifikasi, analisi hirarkis, sinektika, brainstorming, analisis perspektif berganda,
analisis asumsi, dan terakhir pemetaan argumentasi. Berkaitan dengan bahasan yang
menjadi ketertarikan penulis maka akan digunakan metode analisis batas, sehingga
diharapkan mampu menghasilkan rumusan masalah yang tepat termasuk
mengakomodasi informasi secara komprehensif dari beberapa stakeholders terkait.
Adapun untuk mengapikasikan analisis asumsi dalam merumuskan masalah
seharusnya melalui 5 tahapan (Dunn, 2000: 272-275), sebagai berikut:
1. Identifikasi Pelaku Kebijakan
Tahapan pertama yang harus dilalui oleh analis yaitu melakukan identifikasi,
pengurutan, dan memprioritaskan pelaku kebijakan berdasarkan pada
penilaian sejauh mana masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
proses kebijakan.
2. Memunculkan asumsi
Memunculkan asumsi termasuk tahapan kedua setelah berakhirnya
identifikasi pelaku kebijakan. Secara teknis dilakukan dengan berfikir ke
belakang dari solusi masalah yang direkomendasikan untuk menelaah
data-data yang mendukung rekomendasi tersebut yang kemudian menjadi dasar
memunculkan asumsi-asumsi. Oleh karenanya, akan memperoleh daftar
asumsi dari masing-masing pelaku kebijakan baik secara eksplisit dan
implisit.
3. Mempertentangkan Asumsi
Tahapan ketiga ini mengarahkan analis untuk melakukan perbandingan dan
evaluasi terhadap serangkaian rekomendasi dan asumsi yang mendasarinya.
Apabila asumsi tandingan tidak masuk akal maka tidak perlu dilakukan
pertimbangan lebih lanjut yang berarti adanya sistem gugur pada
5 maka dilakukan uji lanjutan sebagai landasan konseptualisasi baru terhadap
masalah dan solusi secara menyeluruh.
4. Mengelompokkan asumsi
Pada tahap keempat ini merupakan upaya negosiasi dengan
memprioritaskan asumsi-asumsi dari segi kepastian dan kepentingannya
bagi para pelaku kebijakan yang berbeda. tujuan akhir dari tahapan ini
adalah menciptakan dasar asumsi yang dapat diterima oleh banyak mungkin
pelaku kebijakan secara komprehensif.
5. Sintesis asumsi
Tahapan terakhir yang harus dilalui adalah penciptaan solusi gabungan atau
sintesis terhadap masalah. Suatu satuan gabungan asumsi yang diterima
dapat menjadi basis untuk menciptakan konseptualisasi baru dari masalah.
Ketika isu-isu seputar konseptualisasi masalah dan potensi pembuat
kebijakan dapat menjadi kooperatif dan secara kumulatif produktif.
Mendasarkan pada 5 tahapan menurut Dunn, Ian dan James (1970) menggambarkan
proses analisis asumsi, seperti ilustrasi gambar berikut.
Gambar 1. Proses Analisis Asumsi
Solusi asli Data bersama Pemunculan asumsi
Solusi banding Data bersama Pembenturan asumsi
Sekumpulan asumsi Data bersama Pengelompokkan asumsi
Sintesis Asumsi Data Umum
6
C. PERUMUSAN MASALAH PENGEMBANGAN UKM DI INDONESIA
Telah diaturnya UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka
terbagi menjadi 3 jenis masing-masing definisi antara lain, pertama, Usaha Mikro
adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria
sesuai UU tersebut. Kedua, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, didirikan oleh perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan
oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasik penjualan tahunan yang telah diatur dalam
Undang-Undang tersebut. Berikut rincian jelas tentang kategori usaha mikro, kecil, dan
menengah ditinjau dari indikator aset dan omzet.
Tabel 1. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia
No. URAIAN KRITERIA
Dari data tabel diatas, pengkategorian usaha yang dilihat melalui kepemilikan
aset dengan jumlah batasan minimal sebanyak 50 juta sedangkan omzet yang
diperoleh sebesar 300 juta termasuk kategori usaha mikro. Selanjutnya apabila aset
berjumlah diatas 50 juta hingga 500 juta, dan perolehan omzet sebanyak 300 juta –
2,5 milliar, maka kegiatan usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha kecil. Bersifat
seperti tingkatan ketika aset yang dimiliki usaha perseorangan atau badan usaha
mencapai 500 juta – 10 milliar, dengan perolehan omzet sebanyak 2,5 milliar – 50
milliar maka termasuk pada usaha menengah. Selain itu, Badan Pusat Statistik
7 milliar, dan pendapatan omzet sebesar lebih dari 50 milliar/tahun maka terkategori
sebagai usaha besar.
Dengan pengkategorian tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah merilis
hingga tahun 2015 jumlah dari masing-masing unit UMKM di Indonesia. Terjadinya
penggabungan jumlah usaha mikro dan kecil yang tercatat sebanyak ± 59.203.509
unit, yang oleh Kemenkoukm dikatakan sebagai pondasi perekonomian Indonesia.
Jumlah yang sama banyaknya juga dimiliki oeh usaha menengah sebanyak ± 59.263
unit, yang oleh Kemenkoukm disebut sebagai pilar perekonomian Indonesia.
Terakhir sebagai atap perekonomian Indonesia menurut Kemenkoukm adalah usaha
besar hingga tahun 2015 tercatat sebanyak ± 4.987 unit. Dengan angka yang
menunjukkan dari jumlah masing-masing usaha terdapat pada usaha menengah,
kemudian usaha mikro dan kecil, dan usaha besar termasuk dengan jumlah relatif
kecil dibanding usaha menengah dan usaha mikro, kecil. Oleh karenanya, pemerintah
turut menyadari bahwa perlu adanya pemberdayaan ekonomi produktif pada UMKM
karena sebagai subek-subjek pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal
tersebut telah disepakati bersama oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, dan
masyarakat dengan telah adanya program-program pemberdayaan UMKM sejak
tahun 2000 (Syarif dan Ethy, 2014).
Potensi ekonomi produktif oleh UMKM ternyata juga berdampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada Pendapatan Domestik Bruto,
penyerapan tenaga kerja, dan ekspor non migas. Badan Pusat Statistik (2015) merilis
tentang kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sebesar 61,41%, sementara untuk
penyerapan tenaga kerja sebanyak 96,71%, dan 15,73% adalah prosentase
kontribusi positif UMKM terhadap ekspor non migas.
sependapat dengan hasil data BPS tetapi terdapat selisih angka berbeda bahwa Asian
Development Bank (ADB) Institute (2015) menyatakan bahwa Indonesia
merupakan negara yang memiliki kontribusi terbanyak dari SME / UKM
terhadap PDB57,8%, penyerapan tenaga kerja 97,2 %, serta total ekspor 15,8
8 Gambar 2. Kontribusi UKM terhadap PDB, Tenaga Kerja dan total ekspor
Indonesia
Sumber: Slamet, dkk (2016)
Selanjutnya, segera diperlukan pemetaan apa yang menjadi kendala utama
dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Dimaksudkan agar mempermudah
menghasilkan rumusan masalah yang baik dan mengarahkan pada pencapaian
rekomendasi kebijakan yang juga tepat. Oleh karenanya, untuk memahami kerangka
masalah dalam pengembangan UMKM di Indonesia, penulis menggunakan salah satu
metode perumusan masalah yang dipopulerkan oleh William N. Dunn yaitu metode
analisis asumsi. Ilustrasi penggunaan metode analisis asumsi mengacu pada
pemikiran William N. Dunn, sebagai berikut.
Gambar 3. Tahapan Metode Analisis Asumsi
I. Identifikasi Pelaku Kebijakan
II. Memunculkan Asumsi
III. Mempertentangkan Asumsi
IV. Mengelompokkan Asumsi
9 Untuk memudahkan pemahaman bagaimana teknis pemetaan masalah
menggunakan analisis asumsi, maka akan diuraikan mengikuti alur atau tahapan
sesuai pemikiran Dunn. Dengan mengangkat kasus kebijakan pengembangan UMKM
di Indonesia melalui aspek permodalan atau pendanaan yang kemudian masih
menuai kendala.
I. Identifikasi Pelaku Kebijakan
Adapun dalam proses pengembangan UMKM tidak berjalan mulus, kendala dan
hambatan masih sering dijumpai oleh baik pemerintah sebagai fasilitator, swasta
sebagai mitra, dan UMKM sebagai pelaku usaha. Kendala dan hambatan muncul atas
faktor internal dan eksternal, Bank Indonesia mencatat faktor internal terdiri dari:
1) Modal, hanya sekitar 60 -70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan dikarenakan hambatan geografis. Dalam artian belum
banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan
terpencil. Selain itu, hambatan pada administratif yaitu manajemen bisnis
UMKM masih dikelola secara tradisional.
2) Sumber Daya Manusia (SDM), menjadi kendala bagi internal UMKM karena komponen vital yang berpengaruh terhadap baik buruknya, maju mundurnya
eksistensi UMKM. Pandangan bahwa SDM di UMKM masih memiliki
pengetahuan rendah terkait teknologi produksi baru dan quality control
terhadap produk; kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam;
pemasaran produk masih dengan cara tradisional mouth to mouth marketing;
belum banyak melibtakan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan
penggajian.
3) Hukum, bahwa pelaku UMKM masih berbadan hukum peorangan secara umum.
4) Akuntabilitas, dianggap belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik. Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi oleh
UMKM menurut Bank Indonesia, meliputi:
1)Iklim usaha masih belum kondusif, tercermin dari belum terjalin penuh koordinasi antar stakeholder UMKM diantaranya lembaga peerintah, institusi
10 penanganan legalitas badan usaha dan kemudahan prosedur perizinan,
penataan lokasi usaha, biaya infrastruktur, dan kebijakan dalam pendanaan
UMKM.
2)Infrastruktur, terbatasnya sarana prasaranan berupa alat-alat teknologi sehingga kebanyakan UMKM masih mengandalkan teknologi yang sederhana.
3)Akses, meliputi keterbatasan memperoleh bahan baku dengan kualitas baik; sulit mendapatkan akses kepemilikan teknologi terbarukan apabila pasar
telah dikuasai perusahaan atau group bisnis tertentu; dan masih rendahnya
kemampuan untuk mengimbangi selera konsumen yang berubah-ubah.
M. Rizal, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) (2014), juga
sepakat bahwa permodalan menjadi kendala awal atau prioritas dalam
pengembangan UMKM. Ia menjabarkan terdapat 4 kendala berupa (1), askes
pembiayaan; (2) Teknologi dan inovasi produk; (3) Riset Pasar, dan (4) Inefisiensi.
Sedikit berbeda dengan pendapat kedua pihak tersebut, Kementerian Koperasi dan
UKM (2017) telah mengklasifikasikan kendala dan permasalahan yang dihadapi
UMKM di Indonesia terdiri dari 3 aspek antara lain:
1)Pengaruh Perekonomian Global, ditunjukkan dengan penguatan nilai tukar Dollar sehingga melemahkan nilai tukar rupiah; Bank Dunia memangkas
proyeksi pertumbuhan ekonomi; Perekonomian Yunani terus mengalami
penurunan; dan Bank Sentral Tiongkok melakukan devaluasi nilai mata uang
China dan memangkas pertumbuhan ekonomi.
2)Pengaruh Perekonomian Regional, tercermin dengan adanya depresiasi mata uang ringgit Malaysia dan Baht Thailand; penurunan nilai ekspor dan
impor, berlakunya MEA; pelaku usaha UMKM mengandalkan bahan baku
impor; dan penyerapan APBN & APBD masih relatif rendah.
3)Pengaruh Perekonomian Nasional, dalam taraf ini kendala berupa penghentian sebagian belanja bantuan langsung masyarakat (BLM) atau
Bantuan Sosial (Bansos) pada K/L; penyerapan APBN &APBD masih rendah;
ketergatungan pada bahan baku impor dan industri jasa keuangan mikro
11 II. Asumsi Pemerintah: Pemberdayaan melalui Lembaga Pembiayaan
Setelah mengidentifikasi aktor (pelaku atau policy maker), seperti yang telah
teruraikan diatas mengarahkan pada tahapan selanjutnya adalah memunculkan
asumsi masalah. Berkat selesainya tahapan pertama sehingga diperoleh pendapat
dari masing-masing pelaku kebijakan terkait apa saja yang menjadi kendala-kendala
utama pada pelaksanaan pengembangan UMKM di Indonesia. Adapun pemerintah
sepakat bahwa aspek modal menjadi kendala utama dan mendorong pemerintah
untuk menjalin seluas-luasnya kemitraan dalam pembiayaaan UMKM. Seperti yang
dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM membagi kedalam 4 kategori
pembiayaan program pemberdayaan koperasi dan UKM, sebagai berikut.
Gambar 4. Sumber Pembiayaan Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Sumber: Agus M, Sekretaris Kemenkoukm (2017)
Sementara itu, terjadi penurunan alokasi anggaran dalam pembiayaan program
UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2017. Dengan
asumsi bahwa akan memberikan tempat bagi pihak lain turut berkontribusi
mensejahterakan eksistensi UMKM. Penurunan terjadi pada alokasi tugas
pembantuan sebesar 0,91% dan dekonsentrasi sebesar 0,55%, sebaliknya anggaran
untuk DAK non fisik tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Tercantum seperti
12 Gambar 5. Alokasi Anggaran Kemenkoukm terhadap Pembiayaan UMKM
Sumber: Agus M, Sekretaris Kemenkoukm (2017)
Bukan berarti sebagai aktor utama yang menaruh konsentrasi terhadap
pemberdayaan UMKM harus menganggarkan pembiayaan yang lebih. Prinsip yang
melekat pada Kementerian Koperasi dan UK M dalam implementasi program telah
mengadopsi prinsip money follow program. Dibenarkan bahwa pekerjaan dalam
pengembangan UMKM bukan saja tanggung jawab satu pihak melainkan perlunya
sinergi berbagai pihak untuk menjalankannya. Oleh karenanya, tidak hanya terbatas
pada peran lembaga kementerian, dukungan juga dibutuhkan dari lembaga non
kementerian seperti Bank Indonesia, BUMN, dan lembaga keuangan non bank.
Adapun beberapa kebijakan pengembangan UMKM melalui lembaga pembiayaan
bank berupa:
(1) Kredit Usaha Rakyat, telah diterbitkan sejak 2007 yang bertujuan untuk
mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada pembiayaan dari
perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin. KUR adalah
skeman pembiayaan yang diperuntukkan khusus bagi UMKM dan koperasi yang
usahanya layak namun tidak mempunai agunan yang cukup sesuai persyaratan
yang ditetapkan. Program KUR terbagi menjadi KUR Mikro dan KUR Ritel.
Adapun penetapan bunga sebesar 22%/tahun bagi KUR Mikro dan 14%/ tahun
bagi KUR Ritel.
(2) Kebijakan Bank Indonesia, dengan diterbitkan UU No. 3 Tahun 2004
menjadikan peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM menjadi tidak
langsung. Namun demikian, berfokus pada penguatan lembaga pendamping
13 yang tetap menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Untuk mendukungnya
Bank Indonesia menetapkan 3 kebijakan antara lain, pertama, kebijakan yang menganjurkan bank menyalurkan sebagian kreditnya kepada usaha kecil
(Peraturan Bank Indonesia [PBI] No.3/2/PBII/2001 tentang pemberian Kredit
Usaha Kecil). Kedua, diwajibkan kepada bank konvensional ataupun syariah mencatatkan realisasi kredit usaha UKM dalam rencana bisnisnya (PBI No.
12/21/PBI/2010 tentang rencana bisnis bank umum dalam penyaluran kredit
UMKM). Ketiga, kebijakan mewajibkan Bank Umum memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan penetapan jumlah pembiayaan paling rendah
20% dari total kredit yang disalurkan oleh bank secara bertahap dari tahun 2013
hingga 2018 (PBI No.14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau
pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan
UMKM).
Kebijakan tersebut mendasarkan pada klaim pemerintah bahwa dengan
pembiayaan mampu mendorong berkembangnya UMKM di Indonesia. Berikut
asumsi yang mendasari keputusan kebijakan pemerintah:
(1) Karena sumber modal yang dimiliki UMKM pada umumnya terdiri dari dua
sumber yaitu modal sendiri dan pinjaman. Disinilah peran lembaga pembiayaan
dibutuhkan untuk mampu mencukupi kekurangan modal yang diperlukan oleh
UMKM dalam menjalankan usahanya, dengan memperhatikan prinsip 3C yaitu
character, capability, dan collateral.
(2) Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit
(3) Suku bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif
(4) Sistem pembayaran fleksibel, dengan mencetuskan inovasi pembayaran dengan
sistem pick up. Dimana diterapkan pembayaran dengan cicilan perhari dengan
mendatangi secara langsung, hal inipun disambut baik oleh pelaku usaha
UMKm karena cukup meringankan dan menghemat waktu untuk melakukan
pembayaran
(5) Informasi mudah didapat, kemudahan memperoleh informasi mengenai
produk pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan bank atau
pembiayaan non bank. Sumber informasi didapat dari sales dan teman atau
14 III. Mempertentangkan asumsi
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan pemerintah melalui
lembaga pembiayaan guna mendorong berkembangnya UMKM mendapat
tanggapan berbeda dari Indonesia Marketing Association (IMA). IMA menganggap
bahwa permodalan untuk saat ini bukanlah concern utama tetapi pemerintah perlu
menaruh perhatian justru pada menangkap peluang untuk memanfaatkan
informasi dan teknologi dengan istilah poplernya pemanfaatan Information &
Communication Technology (ICT)1. Di era digital tentu tuntutan berkembangnya
UMKM semakin kompleks, oleh karenanya sangat dibutuhkan bekal pengetahuan
teknologi yang juga mendorong pada peningkatan kapasitas inovasi dan kreativitas.
Selain itu, juga dengan pengaruh perekonomian global memiliki kaitan erat
dengan bagaimana kemampuan daya saing produk UMKM Indonesia dikancah
internasional. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri,
daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor
pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan
internasional. Adapun tingkat daya saing suatu negara di taraf internasional
dipengaruhi 2 hal, yaitu faktor keunggulan komparatif, dan faktor keunggulan
kompetitif (Tambunan, dalam Sudaryanto). Sementara itu, tingkat daya saing
Indonesia di kancah internasional menempati posisi ke 46 di tahun 2011, justru
mengalami penurunan yang sebelumnya diposisi ke 44 pada tahun 2010. Tidak
terlepas dari itu, Tambunan telah mengklasifikasikan kendala-kendala utama UMKM
Indonesia dengan negara lainnya, sebagai berikut.
1
15 Tabel 2. Kendala Utama UMKM di Beberapa Negara
Sumber: Tambunan, dalam Sudaryanto.
Berdasarkan penjelasan oleh Tambunan mengenai kendala utama yang dihadapi
UMKM di Indonesia mengacu pada aspek raw materials, marketing, capital, energy,
dan information. Sebaliknya terkait aspek infrastruktur dan teknologi justru bukan
menjadi kendala utama UMKM di Indonesia sehingga bertentangan dengan uraian
yang dikemukakan oleh Kememkoukm dan BI sebelumnya. Hal ini juga berlaku pada
aspek pajak, inflasi, distorsi pasar, dan isu tenaga kerja bukanlah kendala utama
pengembangan UMKM di Indonesia.
Selain itu, pelaku kebijakan lain seperti Indonesia Marketing Association (IMA)
mengemukakan bahwa yang menjadi kendala utama berdasarkan dari aspirasi
pelaku usaha UMKM adalah aspek modal. Hal inipun dibenarkan oleh Tim Kreatif
Smesco, Fina Silmi yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan FGD
bersama 250 pelaku UMKM dan memperoleh temuan masalah yang dihadapi pelaku
UMKM di Indonesia. Temuan hasil menunjukkan selain aspek permodalan, faktor
masalah utama lainnya adalah legalitas, terutama untuk mematenkan hasil
produk-produk UMKM2. Selain itu, justru memunculkan gagasan yang dibutuhkan para
pelaku UMKM adalah pengetahuan (knowledge) terkait pengetahuan bisnis dan
marketing. Karena ditemukan fakta bahwa banyakUMKM dengan bermodalkan ide
dan modal minim, tetapi memiliki kecakapan pengetahuan tersebut justru semakin
berkembang bisnisnya.
2
16 IV. Pengelompokkan Asumsi
Tahapan keempat dari proses analisis asumsi adalah mengelompokkan
asumsi-asumsi yang bertentangan untuk kemudian ditinjau dari segi kepastian dan
kepentingannya. Diharapkan dengan melalui tahapan ini asumsi-asumsi tersebut
dapat dinegosiasikan, diprioritaskan, dan ditemukan dasar asumsi yang paling dapat
diterima oleh pelaku-pelaku kebijakan. Merujuk pada kasus yang telah dibahas
sebelumnya yaitu kebijakan pengembangan UMKM dengan pemenuhan permodalan
melalui lembaga permodalan. Berikut pengelompokkan asumsi berdasarkan uraian
sebelumnya:
Tabel 3. Asumsi Aktor-aktor Kebijakan
Permodalan VS Bukan Prioritas Utama
Belum terakses secara merata
60-70% UMKM belum mudah
memperoleh bantuan dana modal. vs
Telah terakses di hampir sebagian
terjadi pada tahun 2011 pada posisi
46 di tingkat Internasional.
Pendampingan dan pelatihan oleh
lembaga pembiayaan vs
Belum mampu menyentuh
pemanfaatan IT
Mengacu uraian pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa asusmi baik dari aktor
atau pelaku kebijakan yang memprioritaskan pada dukungan permodalaan maupun
yang kurang sepakat, dikelompokkan ke dalam 3 aspek antara lain akses
pembiayaan, perbaikan kualitas produk, dan peranan lembaga pembiayaan. Sebagai
catatan tidak adanya penilaian bahwa asumsi dari masing-masing aktor kebijakan
tersebut benar atau salah tetapi dengan analisis asumsi mencoba melihat sejauh
17 kepentingan (Firman,dkk: 2017). Langkah selanjutnya untuk mendukung kepastian
dan kepenitngan asumsi dari para aktor tersebut, maka perlunya analisis lebih lanjut
dengan menghadirkan data-data pendukung.
Pertama, akses pembiayaan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM
sebagai aktor utama menaungi pemberdayaan UKM mengklaim bahwa modal
merupakan kendala utama kurang berkembangnya UMKM di Indonesia. Perhitungan
ini berdasarkan pengaruh perekonomian internasional, melihat mulai melemahnya
nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS tentu sangat berdampak terhadap berjalannya
usaha UMKM. Terlebih bagi pelaku usaha UMKM yang masih merintis dan berproses
mengembangkan bisnisnya, situasi seperti ini sangat membutuhkan peran
pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung. Ditambah lagi terdapat data sekitar
60-70% bahwa dana pembiayaan belum terakses secara merata bagi UMKM. Oleh
karenanya, prioritas bantuan atas modal. pendanaan, atau pembiayaan proses usaha
UMKM lebih sangat dibutuhkan.
Sebaliknya, kondisi ini akan menuai penolakan atau ketidaksepahaman dengan
data yang ada bahwa bantuan modal bagi UMKM di Indonesia dirasa sudah cukup
merata. Dalam artian sebagian pelaku usaha merasa bahwa bantuan modal bukan
kendala utama lagi karena sudah adanya pemerataan pemberian kredit UMKM
sebagai salah satu wujud pembiayaan, seperti berikut.
Gambar 6. Alokasi Kredit UMKM di Indonesia
Dari gambar diatas, alokasi pembiayaan sudah mampu mengakses seluruh
wilayah di Indonesia, memang terdapat kesenjangan prosentase yang ditunjukkan
18 kondisi atau iklim bisnis dikota besar dengan kota lainnya tentu sangat berbeda, di
perkotaan supply demand yang tinggi tentu adanya bantuan permodalan sangat
diperlukan juga sebagai penunjang bersaing dengan kompetitor lainnya. Akan tetapi,
hal tersebut tidak lantas mengesampingkan kondisi pelaku UMKM di Kota-kota
lainnya. Justru akan memunculkan kebutuhan baru selain modal adalah sejauh mana
kapasitas yang dimiliki UMKM sebagai bekal mendorong eksistensi UMKM di wilayah
selain kota-kota besar. Hal ini lantas membenarkan bahwa perlunya pengetahuan
dan kemampuan untuk menguasai aspek lain seperti memanfaatkan teknologi dan
perluasan networking. Disisi lain, beberapa temuan penelitian juga mengungkapkan
bahwa sebagian besar modal UMKM di Indonesia bersumber pada modal sendiri.
Dengan uraian yang melandasi masing-masing asumsi para aktor kebijakan apabila
ditinjau dari aspek pembiayaan keduanya termasuk dalam posisi setara (-); dari segi
kepastian dinilai menempati posisi rendah (X); dan ditinjau dari segi kepentingan
termasuk pada posisi tinggi √ .
Kedua, perbaikan kualitas produk. Dengan adanya alokasi anggaran yang lebih
untuk mengembangkan UMKM adalah bagian dari prioritas program Kementerian
Koperasi dan UKM. Berbagai kegiatan unggulan pendukung yang telah dilakukan
pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM antara lain: (1) Sertifikasi dan
Standarisasi Produk KUKM; (2) Fasilitasi UKM Tenant dalam Galeri Indonesia WOW;
dan (3) Pengembangan Kewirausahaan. Namun, upaya pemerintah ternyata belum
terwujud sebaik mungkin. Hal ini tercermin pada tingkat daya saing produk UMKM di
Indonesia justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2010
menempati posisi ke 44 menjadi 46 di tahun 2011. Selanjutnya, penilaian terhadap
aspek perbaikan kualitas produk dalam posisi rendah (X), sementara dari segi
kepastian dan kepentingan pada posisi setara (-).
Ketiga, peranan lembaga pembiayaan. Pada aspek ketiga ini peranan lembaga
pembiayaan memfokuskan pada pelatihan penggunaan IT, juga pendampingan
lainnya seperti manajemen usaha. Akan tetapi, hal ini belum cukup memberikan
dampak positif kepada pelaku usaha UMKM dengan ditunjukkan data olahan Bank
Indonesia (2013) bahwa kondisi saat ini justru peranan lembaga pembiayaan jarang
sekali atau hampir tidak pernah (84,7%) menyentuh hal tersebut. Sebaliknya terjadi
kontradiktif bahwa 31% UMKM sudah merasa memerlukan pelatihan dan
19 sudah sudah berkembang dan memiliki pangsa pasar di lintas negara tentu
dukungan IT sangat dibutuhkan. Akan tetapi, tetap harus memfokuskan pada
pemasaran di dalam negeri juga karena diperkirakan Market size consumer digital
Indonesia tahun 2020 akan mencapai Rp 170 Trilyun. Karena sebagai upaya
mendukung produk dalam negeri dan wujud nasionalisme bangsa. Disisi lain, dengan
data yang mendukung bahwa adanya pergeseran perilaku masyarakat Indonesia
dalam menggunakan teknologi digital. Menjadi faktor pendukung yang positif untuk
mewujudkan terjadinya pertumbuhan e-commerrce di Indonesia. Seperti hasil data
penelitian oleh Spire Research, sebagai berikut.
Gambar 7 . Perkembangan Pasar e-Commerce di Indonesia
Sumber: Slamet, dkk. (2016)
Dari data riset tersebut, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pemanfataan
teknologi oleh pelaku usaha termasuk UKM di Indonesia. Hingga tahun 2016, usaha
online yang telah memanfaatkan teknologi mencapai 8,7 juta, sedangkan online retail
sales mencapai angka fantastik melebihi online shoppers sebanyak 4,4 milliar
pengakses. Oleh karenanya, semakin menguatkan bahwa di era saat ini bahwa
pemanfaatan teknologi harus menjadi perhatian bersama sebagai strategi
pengembangan UMKM. Walaupun hal ini juga tidak terlepas dengan dukungan modal
baik secara pribadi atau dengan bantuan pemerintah melalui lembaga pembiayaan.
Dengan uraian penjelasan melalui data-data pendukung aspek ketiga ini, bahwa
20 dari segi kepastian dalam posisi rendah (-), sementara itu dari segi kepentingan menempati posisi tinggi √ .
V. Sintesis Asumsi
Pada tahapan terakhir mencoba untuk menghasilkan asumsi yang memiliki segi
kepastian dan kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki argumen tentang
pengembangan UMKM melalui lembaga pembiayaan atau justru fokus terhadap
aspek lainnya. Asumsi yang berhasil ditemukan melalui tahapan-tahapan
sebelumnya meliputi perlunya prioritas pembiayaan atau bantuan modal dalam
pengembangan UMKM (tesis) , dan pendanaan belum mampu mendorong capacity
building UMKM seperti tingkat daya saing dan pemanfaatan IT (antisesis). Dengan
telah menemukan benang merah asumsi kebijakan melalui pengelompokkan dan
filterisasi, kemudian sebagai pertimbangan menentukan sintesis sehingga
menciptakan konseptualisasi dan pemecahan masalah terkait. Sintesis yang dapat
dimunculkan dengan berangkat dari kedua asumsi filter tersebut adalah pertama,
apabila peranan lembaga pembiayaan sebagai pioner dalam pengembangan UMKM
sebaiknya adanya keseimbangan dengan kemudahan akses. serta tinjauan kembali
perlu dilaksanakan terkait hal ini. Kedua, peningkatan kualitas produk UMKM
sebaiknya difokuskan pada paradigma kemampuan menguasai pangsa pasar
internasional. Walaupun tidak memungkiri bahwa upaya pemerintah sebagai tangga
proses menuju ke tujuan yang diuraikan kalimat sebelum. Ketiga, dengan bantuan
pembiayaan belum sepenuhnya mampu mendorong pemanfaatan IT dan
pengembangan jaringan. Hal ini akan terwujud dengan sinergi berbagai K/L dengan
menggandeng K/L atau organisasi di luar pemerintah yang ahli dalam bidang
teknologi, seperti kerjasama Kemenkoukm, Kominfo, dan pelaku usaha UMKM untuk
ikut serta mempromosikan hasil produksi dan mendukung pemanfaatan digital
sesuai Permen Kominfo No. 36/ /HM/KOMINFO/03/20173.
Dengan uraian diatas, analisis asumsi yang digunakan sebagai alat bantu metode
untuk merumuskan masalah terkait pengembangn UMKM maka mendorong adanya
temuan konseptualisasi permasalahan baru yaitu berupa permasalahan forecasting
3
21 terhadap tingkat daya saing produk dalam lingkup internasional dan pemanfaatan
teknologi sebagai pendukung eksistensi UMKM.
D. REKOMENDASI KEBIJAKAN
Menurut Dunn (2000: 440) mengenai pembuatan rekomendasi kebijakan bahwa
analis sebaiknya memiliki inisiatif mengarahkan kepada sejumlah pertanyaan yang
saling berhubungan. Seperti halnya mencakup aspek kebutuhan, nilai, dan peluang apa
yang tengah menjadi isu, dan alternatif-alternatif apa yang tersedia dan memuaskan
pihak-pihak terlibat dan terdampak. Selain itu, terkait dengan apa saja tujuan dan
sasaran yang harus dicapai dan bagaimana itu semua harus diukur. Berapa besar biaya
yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan dan tidak luput pula memprediksi atau
meramalkan kemungkinan hambatan-hambatan yang muncul.
Untuk menilai aspek kebutuhan, nilai, dan peluang dalam pengembangan UMKM
yang menaruh perhatian terhadap diakuinya hasil produksi UMKM dan dapat
dikonsumsi secara massal oleh masyarakat. Dengan perkembangan zaman selain
semakin kompleksnya tuntutan disisi lain lahirlah peluang-peluang untuk
memperkenalkan produk dengan kreasi yang unik dan diminati pasar termasuk masih
terdapat 80% peluang pangsa pasar halal di Indonesia4. Ditambah lagi dukungan
dengan adanya kegiatan World Islamic Economic Forum ( WIEF )yang tidak lain
adalah fasilitasi UKM dan bisnis syariah dalam memanfaatkan dana repatriasi atau
dana-dana lainnya yang belum diakses UKM.
Terkait tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam pengembangan UMKM
sebaiknya terdapat kesepakatan bersama antar pihak berwenang dalam mengadakan
kegiatan pendukung eksistensi UKM. Pertimbangan tujuan dan sasaran sebisa
mungkin dapat menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antar pihak.
Pengadaan berbagai kegiatan antara K/L atau organisasi kemitraan haruslah
berpedoman pada kesepahamam bersama dan parturan baru dibawahnya merupakan
representasi aplikatif atas peraturan diatas yang menaungi.
4
22 Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah kebijakan
incremental dengan pembiayaan yang mengarahkan kepada strategi pengembangan
secara digital terhadap UKM dalam menyediakan infrastruktur ICT, proses produksi,
dan perluasan pasar. Dimaksudkan agar UKM memiliki daya saing dan mampu
berkompetisi dengan hasil-hasil produksi negara lain di kancah internasional, dan pada
akhirnya terjadi peningkatan kinerja UKM di Indonesia. Mengenai kerangka strategi
implementasi dapat mengadopsi Kampung UKM Digital, dengan beberapa kriteria
yang harus terpenuhi dahulu, antara lain :
(1) Tersedianya jaringan infrastruktur telekomunikasi baik berupa jaringan
fixed,wirelles maupun satelit yang menjangkau seluruh wilayah kampung UKM.
(2) Adanya wadah komunitas/ Tenaga Wira IT dan sarana pelatihan
berupaBroadband Learning Center.
(3) Dilakukan pemanfaatan solusi dan layanan Teknologi Infomasi di
23 DAFTAR PUSTAKA
Dunn, N William. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Subarsono. Ag. (2013). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Kementerian Perdagangan. (2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM. Retrieved from
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikto, Kecil, dan Menengah. retrieved from www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/.../Profil%20Bisnis%20UM KM.pdf
Muharram, Agus. (2017). Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menegah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
Mutiara, Samantha. (2016) Retrieved from
https://www.academia.edu/31033112/UMKM
Nugroho, Eko., Syahril, H., dan Anwar Firmansyah. (2017). Menelurusui Kebijakan Impor Raw Sugar di Indonesia melalui Analisis Asumsi
Slamet, Rachmat, dkk. (2016). Strategi Pengembangan UKM Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 16 (2) April 2016. Retrieved from https://media.neliti.com/.../24200-ID-peningkatan-daya-saing-umkm-berbasis-inovasi.
Sudaryanto, R., Ragimun, dan Rahma R. W. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Retrieved from
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%2 0UMKM.pdf
Syarif, Teuku dan Ethy Budiningsih. (2010). Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung UMKM dan Koperasi dalam mengahadapi ACFTA. Jurnal INFOKOP Vol. 18 Juli 2010 Pg: 66-82
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia