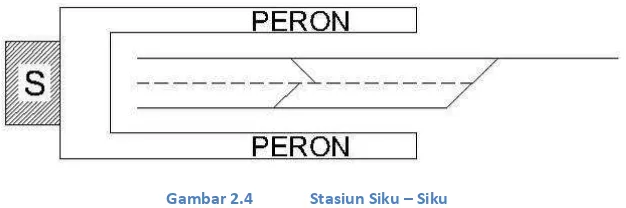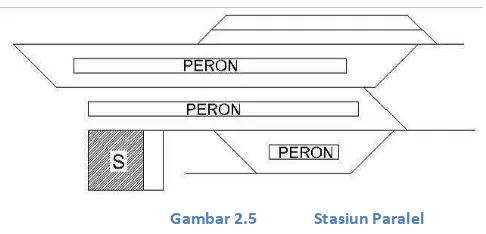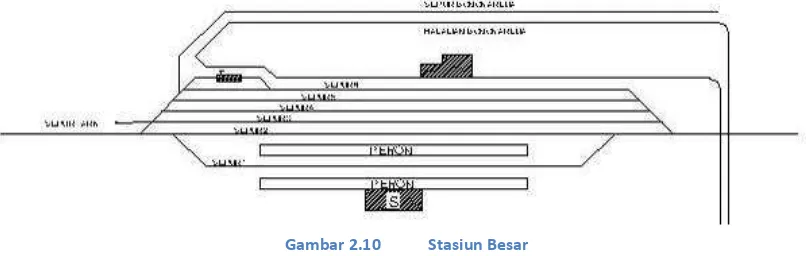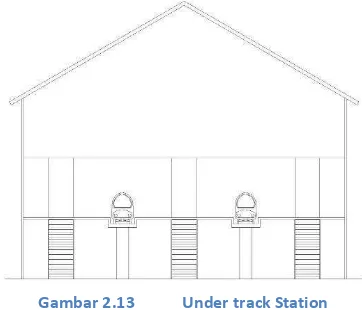BAB II
BAB II
DESKRIPSI PROYEK
2.1Tinjauan Umum
Judul : Redesain Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi
Sifat : Fiktif
Lokasi : Tebing Tinggi
Luas Lahan : 8500 m2
Luas Bangunan : 2300 m2
Tema : Arsitektur Simbiosis
2.2Tinjauan Khusus
Lokasi site berada di kota Tebing Tinggi, provinsi Sumatera Utara.
2.2.1 Terminologi Judul
Pengertian tentang terminology judul proyek Redesain Stasiun Kereta Api Tebing
Tinggi
Redesain : Dalam Bahasa Inggris dapat di terjemahkan sebagai mendesain ulang dengan cara yang berbeda
Stasiun : Berdasarkan terjemahan Bahasa Inggris berarti tempat pemberhentian regular rute transportasi terutama
kereta api. Biasanya memiliki 1 peron atau lebih
Tempat atau bangunan yang digunakan berdasarkan
kegiatan tertentu
Kereta Api : Adalah serangkaian gerbong yang berada diatas rel yang
bergerak sebagai satu unit dengan lokomotif atau motor
yang tidak terpisahkan
Tebing Tinggi : Salah satu Kota di Sumatera Utara
Redesain Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi
Mendesain ulang tempat pemberhentian regular kereta api yang berada di salah
satu kota di Sumatera Utara
2.3Sejarah Kereta Api di Indonesia
Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum’at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan
ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.
Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen –
Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan
kota Semarang – Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk
membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan
panjang jalan rel antara 1864 – 1900 tumbuh de-ngan pesat. Kalau tahun 1867
baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun
Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874),
Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan
tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara
Makasar–Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya
Ujungpandang – Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan,
meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak – Sambas (220 Km)
sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan
studi pembangunan jalan KA.
Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811
Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang
Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan
Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.
Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067
mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota.
Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 – 1943) sepanjang 473
Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km
antara Bayah – Cikara dan 220 Km antara Muaro – Pekanbaru. Ironisnya, dengan
teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro – Pekanbaru diprogramkan selesai
pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000
diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta
sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran
sepanjang Muaro- Pekanbaru.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa
bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan
pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya,
menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian
tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi
ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta
dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI).
Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia
Pada tahun 1864 Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara
Kemijen (Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda)
1864 s.d 1945 Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS) Deli
Spoorwegen Maatschappij (DSM)
1945 s.d 1950 disingkat DKA
1950 s.d 1963 disingkat DKA-RI
1963 s.d 1971 disingkat PNKA
1971 s.d.1991 disingkat PJKA
1991 s.d 1998 disingkat PERUMKA
1998 s.d. 2010 PT. KERETA API (Persero)
Mei 2010 s.d sekarang PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
2.4Tinjauan Umum Mengenai Stasiun Kereta Api
2.4.1 Pengertian Stasiun Kereta Api 1. Kereta Api (Commuter Rail)
Commuter rail atau kereta api berskala regional adalah moda
pengangkutan umum dengan menggunakan pelayanan rel yang melayani
perpindahan dari pusat kota dengan daerah sub urban dan kota-kota
komuter lainnya. Seperti namanya kereta ini dipergunakan untuk
mengangkut para penglaju atau commuter dari daerah-daerah tersebut
setiap harinya. Kereta ini beroperasi dengan jadwal yang sudah ditentukan,
dengan laju rata-rata mulai dari 50 sampai 200 km/jam (35 – 125 mph).
Perkembangan kereta api jenis ini tengah populer saat ini, seiring
dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan pemakaian
bahan bakar, dan isu-isu permasalahan lingkungan lainnya, serta
meningkatnya angka kepemilikan mobil yang akhirnya meningkatkan
Dibandingkan dengan rapid transit (subway), kereta ini memiliki
frekuensi yang lebih rendah, lebih kepada mengikuti jadwal dari pada
interval. Kereta ini melayani area yang lebih berkepadatan rendah, dan
sering berbagi jalur dengan kereta antarkota atau kereta barang. Terkadang
dalam kondisi tertentu beberapa kereta melayani saat jam-jam sibuk.
Kereta ini memiliki gerbong dengan satu level dan dua level, dan ditujukan
agar semua penumpang mendapatkan tempat duduk. Biasanya kereta ini
memiliki jangkauan antara 15 sampai 200 km (10 sampai 125 mil)1. Dari
tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat spesifikasi fisik commuter rail.
Karakteristik Fisik Commuter Rail Infrastruktur Ukuran
Panjang kereta 20 sampai 26 meter
Lebar kereta 3,05 sampai 3,2 meter
Tinggi kereta single-level 4 meter
Tinggi kereta double-level 5 meter
Jumlah penumpang single-level Lebih dari 128 kursi Jumlah penumpang double-level Lebih dari 175 kursi
Kapasitas berdiri 360 orang
Jumlah gerbong dalam kereta 1 sampai 12 gerbong
Laju kecepatan maksimal 80 mph (130 km/jam)
Kecepatan rata-rata 18-50 mph (30-75 km/jam)
Maksimum kurva rel : Jalur utama
Jalur stasiun
Radius 174 meter
Radius 91 meter
Maksimum Kenaikan Rel : Jalur utama
Jalur utama tergabung
Jalur dengan kebutuhan maksimal
Kenaikan 3%
Kenaikan 1%
Kenaikan 2%
Jarak senggang sepur 1,435 meter
Minimum tinggi selubung 5,4 meter Minimum tinggi selubung kereta barang 6,7 sampai Tabel 2.4.1.1 Karekteristik Kereta API
Berdasarkan jenis penggeraknya kereta ini dibagi atas dua macam, yaitu:
a. Penggerak dengan menggunakan motor tenaga diesel, dan
b. Berpenggerak tenaga listrik. Sedangkan berdasarkan jumlah kapasitas
penumpang, kereta ini juga dibagi atas dua kategori, yakni: 1). Single
level cars, dan 2).Bi-level cars,
2. Stasiun Kereta Api (Commuter Rail Station)
Stasiun merupakan bagian dari perkeretaapian yang memiliki peran
penting dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa kereta
api. Beberapa pengertian mengenai stasiun:
Stasiun adalah tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang, dimana penumpang dapat membeli karcis, menunggu kereta dan mengurus
Gambar2.2 Single-Level Cars
bagasinya. Di stasiun itu juga diadakan kesempatan untuk mengirim dan
menerima barang kiriman, serta kesempatan untuk bersimpangan atau
bersusulan dua kereta api atau lebih2.
Stasiun adalah tempat akhir dan awal perjalanan kereta api, bukan merupakan tujuan atau awal perjalanan yang sebenarnya. Dari stasiun
masih dibutuhkan moda angkutan lain untuk sampai ke tujuan akhir
2.4.2 Klasifikasi Stasiun Kereta Api
Stasiun sendiri menurut Imam Subarkah (1981), memiliki jenisnya masing-masing,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Menurut bentuknya
1. Stasiun siku-siku, letak gedung stasiun adalah siku-siku dengan letak sepur
sepur yang berakhiran di stasiun tersebut.
2. Stasiun paralel, gedungnya sejajar dengan sepur-sepur dan merupakan stasiun
pertemuan.
3. Stasiun pulau, posisi stasiun sejajar dengan sepur-sepur tetapi letaknya di
tengah-tengah antara sepur.
4. Stasiun semenanjung, letak gedung stasiun pada sudut dua sepur yang
bergandengan.
b. Menurut jangkauan pelayanan
1. Stasiun jarak dekat (Commuter Station).
2. Stasiun jarak sedang (Medium Distance Station).
3. Stasiun jarak Jauh (Long Distance Station).
c. Menurut letak
1. Stasiun akhiran, stasiun tempat kereta api mengakhiri perjalanan.
2. Stasiun antara, stasiun yang terletak pada jalan terusan. Gambar 2.5 Stasiun Paralel
Gambar 2.6 Stasiun Pulau
3. Stasiun pertemuan, stasiun yang menghubungkan tiga jurusan.
4. Stasiun silang, stasiun terdapat pada dua jalur terusan.
d. Menurut ukuran
1. Stasiun kecil, disini biasanya kereta api ekspress tidak berhenti, hanya ada
dua
atau tiga rel kereta api.
2. Stasiun sedang, disinggahi kereta api ekspress, terdapat gudang barang dan
melayani penumpang jarak jauh.
3. Stasiun besar, melayani pemberangkatan dan pemberhentian kereta yang
banyak dari berbagai jenis perjalanan, fasilitasnya lengkap dengan system
pengaturan yang sangat kompleks.
e. Menurut posisi
Gambar 1.8 Stasiun Kecil
Gambar 2.9 Stasiun Sedang
1. Ground level station, bangunan stasiun yang letaknya sejajar dengan
platform/
peron diatas tanah.
2. Over track station, letak bangunan stasiunnya diatas platform/ peron.
3. Under track station, letak bangunan stasiunnya di bawah peron Gambar 2.11 Ground level Station
Gambar 2.12 Over Track Station
Sedangkan menurut PT. Kereta Api, stasiun digolongkan/ diklasifikasikan dalam
beberapa kelas yang diputuskan oleh PT. Kereta Api Indonesia dengan mempertimbangkan
nilai bobot stasiun. Penilaian bobot stasiun menggunakan rumus Point Method yang terdiri
dari 10 faktor penilaian/ klasifikasi, yaitu :
1. Jumlah Personel.
2. Jumlah kereta api yang dilayani.
3. Jumlah kereta api yang berhenti.
4. Jumlah kereta api yang dilangsir.
5. Daerah tingkat kedudukan stasiun.
6. UPT lain disekitarnya.
7. Potensi angkutan.
8. Volume penumpang.
9. Volume barang.
10. Pendapatan stasiun.
Dengan menggunakan Point Methode di atas, stasiun kereta api dikelompokkan
menjadi 4 kelas stasiun, yaitu :
1. Stasiun kelas besar.
2. Stasiun kelas 1.
3. Stasiun kelas 2.
4. Stasiun kelas 3.
Perubahan kelas suatu stasiun diputuskan oleh Dirut PT. Kereta Api Indonesia dengan
memperhatikan penilaian di atas dan juga memperhatiakan usulan-usulan yang disampaikan
Secara organisasi PT. Kereta Api (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang diberi
tanggung jawab penuh terhadap manajemen perkereta apian di Indonesia, memiliki struktur
organisasi perusahaan, seperti yang terihat pada Diagram 2.1 di bawah ini.
Dari struktur organisasi di atas dapat diperkirakan jumlah personel pengelola stasiun
kereta api Tebing Tinggi, yaitu :
Jumlah Personel Pengelola
No Jabatan Jumlah
1. Kepala Stasiun 1 orang
2. Wakil Kepala Stasiun 1 orang
3. Bendahara 1 orang
5. Kepala Kascis 2 orang
6. Staff Loket 6 orang
7. Pimpinan Perjalanan KA 4 orang
8. Kondektur 15 orang
9. Staff Kondektur/TU Kondektur 1 orang
10. Pengawas Peron 4 orang
11. Staff kawat 1 orang
12. Staff Langsir 8 orang
13. Kepala Kantor Kawat 1 orang
14. Staff Teleks -
15. Kepala Administrasi 1 orang
16. Staff Administrasi 2 orang
17. Staff Statistik 1 orang
orang yang bertanggung jawab atas urusan perjalanan kereta api, berkuasa atas
aktivitas kereta api dan penanggung jawab keuangan.
b. Wakil Kepala Stasiun : bertugas membantu tugas-tugas kepala stasiun, jabatan ini
hanya
ada pada stasiun besar.
c. Bendahara :
bertugas mengurusi masalah administrasi keuangan stasiun kereta api.
d. Wakil Bendahara :
e. Pimpinan Perjalanan Kereta Api (PPKA) :
mengatur operasional perjalanan kereta api.
f. Kondektur :
orang yang bertugas sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api dan bertanggung
jawab penuh.
g. Staff Kondektur/ TU Kondektur :
orang yang mengatur jadwal dinas kondektur.
h. Pengawas Peron :
pembantu PPKA mengawasi segala kegiatan peron dan mengawasi emplasement.
i. Emplasement :
ruangan/ lapangan/ halaman tempat lintas keluar-masuknya kereta api untuk
menaikkan dan menurunkan penumpang.
j. Staff Langsir :
juru langsir yang menyusun dan melepaskan satu ruangan kereta api atau
memuntahkan materil dari satu spoor ke spoor lainnya.
k. Kepala Kantor Kawat :
kepala urusan telegram berita.
l. Administrasi :
mengurus surat menyurat kepala stasiun.
m. Statistik :
staff kepala stasiun besar dalam urusan pendataan berbagai hal secara statistik.
n. Bagasi :
2.3.1.3 Jaringan Eksisting Kereta Api Medan
2.5 Aktivitas di Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi
Aktivitas-aktivitas yang
terjadi dalam stasiun kereta
api Tebing Tinggi adalah :
a. Penumpang,
melakukan aktivitas
berangkat dan datang.
b. Pengantar/penjempu
t, mengantar /menjemput
sanak saudara yang
berangkat/datang.
c. Barang bagasi,
mengirim dan menjemput
barang kiriman
d. Pemberi jasa.
2.6 Hal-hal yang dapat dipelajari
a. Menurut jangkauan pelayanannya merupakan stasiun jarak sedang.
b. Menurut letaknya merupakan stasiun antara.
c. Menurut ukurannya merupakan stasiun sedang.
d. Jumlah personil pengelola adalah 60 orang.
2.7 Studi Banding Proyek Sejenis
1. Estacion de Atocha, Spanyol
Di dalam stasiun ini dibuat sebuah miniatur taman yang menyerupai hutan rimba
untuk menambah kesan alam di stasiun ini. Stasiun ini awalnya dibuat pada tahun 1851,
kemudian pada tahun 1992, mulailah ditambahkan hutan mini seluas 4.000 meter persegi
untuk ditempatkan sebagai taman tropis yang menakjubkan. Stasiun ini merupakan stasiun
kereta api terbesar di Madrid. Jenis
Lubuk Pakam – Pertumbukan
Tebing Tinggi – Siantar
Kisaran – Tanjung Balai
Taman tersebut ditumbuhi lebih dari 7.000 tanaman serta memiliki 260 spesies yang
berbeda, semuanya diatur dan ditata sedemikian rupa dari mulai jenis tanaman yang tinggi
besar hingga tanaman yang kecil, sehingga membentuk sebuah taman yang indah serta
memberikan kenyamanan bagi calon para penumpang kereta. Apalagi dilengkapi dengan
adanya kolam yang berisikan 22 spesies ikan dan kura-kura. Maka lengkaplah sudah
panorama hutan tropis di dalam stasiun kereta api tersebut.
Melihat dari bentuk atap stasiun sendiri yang melengkung, memberikas kesan sebuah
rumah kaca. Stasiun ini memang sudah sejak pertama kali diresmikan pada tahun 1851
memiliki bentuk seperti itu, namun belum semegah ini tentunya dirancang oleh Rafael
Moneo.
. Meskipun sempat mengalami kebakaran dan rusak ditelan api pada tahun 1892,
namun stasiun ini direnovasi kembali tahun 1992 hingga mengalami berbagai perubahan
bentuk. Bentuk aslinya yang pertama kali dibangun berubah fungsi tidak hanya dijadikan
sebagai tempat layanan terminal saja melainkan menjadi kumpulan toko-toko, kafe, juga klub
malam, melengkapi megahnya rumah kaca tersebut.
Wuhan Train Station merupakan sebuah stasiun yang berada di wilayah selatan
china yang selesai dibangun pada September 2008.
Rancangan stasiun kereta api Wuhan mengikutsertakan budaya dan sejarah
lokal serta mempertimbangkan kondisi iklim lokal, hal tersebut merepresentasikan
trend di Cina yang melihat melihat lingkungan sekitarnya sebagai inspirasi untuk
Dengan mengambil ide rancangan dari sejarah dan budaya Wuhan, atap
berbentang lebar yang merupakan fitur visual yang paling kuat pada struktur yang
besar ini memiliki banyak arti. Pertama, atap ini menggambarkan seekor bangau
kuning : sebuah referensi untuk Yellow Crane Tower (menara bangau kuning), salah
satu landmark Wuhan yang paling penting dan merupakan salah satu legenda lokal
Wuhan serta sebuah puisi yang terkenal pada zaman dinasti Tang. Dari kejauhan,
rancangan atap yang masif ini dirancang tampak seperti seekor burung yang
membentangkan sayapnya, dengan atap transparan dan arch raksasa yang
menyimbolkan bulu-bulu burung. Pada siang hari, cahaya matahari masuk ke bagian
dalam bangunan melalui ruang-ruang antara arch, sedangkan pada malam hari
bangunan ini bersinar seperti lampion kertas. Bentuk atap yang bergelombang ini juga merepresentasikan tujuan Wuhan sebagai ibukota dari “provinsi dengan seribu danau”. Terakhir, siluet atap bangunan ini mengingatkan kita pada struktur sebuah pagoda.
Ventilasi pasif disediakan untuk kepentingan mekanis untuk menyediakan
udara segar yang banyak pada bangunan ini. Sistem pengkondisian udara
menyediakan udara segar ke bagian bangunan yang lebih rendah, dimana kerumunan
berkumpul; kereta api yang bergerak melalui stasiun membantu untuk menyediakan
pergerakan udara. Udara yang lebih hangat dan tercemar yang dihasilkan oleh
lokomotif bertenaga diesel naik ke bagian atas bangunan untuk dibuang melalui
sistem ventilasi.
Stasiun Wuhan menginovasi sirkulasi penumpang dengan menggabungkan sistam “waiting and boarding” (tunggu dan berangkat) yang tradisional dengan sistem transit “pass-through”. Ketika memasuki lobi utama, penumpang dapat memilih untuk
menunggu di ruang tunggu atau pergi langsung ke “green express line” (jalur ekspres hijau) yang langsung menuju peron. Untuk meningkatkan hubungan dengan daerah
Wuhan lainnya, stasiun dan jalur kereta api dinaikkan. Ruang di bawahnya digunakan
untuk parkir kendaraan publik dan menyediakan akses ke stasiun kereta api bawah
penginapan dan fasilitas-fasilitas hiburan akan dibangun di sekitar stasiun kereta untuk
menguatkan posisi bangunan ini sebagai pusat dari pembangunan kota baru Wuhan.
3. Stasiun KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia
Stasiun Sentral Kuala Lumpur, atau biasa dikenal dengan Kl Sentral adalah
stasiun kereta api terbesar di Kuala Lumpur, yang didisain sebagai pusat transportasi.
Dibangun untuk dapat mengakomodasi perpindahan antara bus dengan KA. Ditandai
sebagai pusat utama basis transportasi bermoda rel Kuala Lumpur, dan juga sebagai
titik transisi kereta api antar lintas wilayah yang melayani sepenanjung Malaysia dan
Singapura.
Di dalamnya terdapat retail-retail dan outlet makanan atau food court, didisain
untuk dapat mengakomodasi 50 juta penumpang dalam setahun dan akan meningkat
KL Sentral juga melayani Skybus yang melayani penumpang yang akan
langsung dari dan menuju bandara Low Cost Carrier Terminal (LCCT) KLIA.
KL Sentral dibangun dengan mengakomodasi enam jaringan rel yang selesai
Desember tahun 2000 lalu sedangkan kereta, retail serta food court nya mulai
beroperasi pada April 2001. Terbentang diatas lahan seluas 9,5 are, bangunan
utamanya memiliki luas 500 ribu m2 dan spesifikasinya berdasarkan pada proyeksi
penumpang di masa mendatang hingga 2020, yang mana Malysia dicita-citakan
menjadi Negara yang sepenuhnya berkembang.
Bangunan ini juga berusaha menerapkan konsep keberlanjutan dalam
desainnya dengan tetap mengupayakan pencahayaan dan penghawaan alami. Karena
bangunan ini menaungi ratusan ribu orang setiap harinya, sehingga harus dapat
menciptakan kenyamanan tanpa harus menghabiskan energi.
KL Sentral dibagi menjadi beberapa seksi dengan pelayanan jalur rel yang
berebeda-beda:
Lantai 1 Transit Concourse (Hall utama umum) yang ditujukan sebagai tempat bagi para penumpang dan calon penumpang yang akan menggunakan KTM Komuter,
KLIA Transit dan Kelana Jaya Line yang dikenal juga sebagai kereta ringan cepat
(LRT).
Lantai 2 Transit Concourse yang ditujukan sebagai tempat bagi para penumpang dan calon penumpang yang akan menggunakan layanan kereta antar lintas semenanjung
KTM Intercity Train.
KL City Air Terminal (KL CAT) pada lantai satu yang melayani KLIA
Ekspres, jereta berkecepatan tinggi yang langsung menuju Kuala Lumpur International
Airport (KLIA). Tersembunyi dari jangkauan umum KL Sentral juga memiliki
fasilitas sebagai depot perawatan KTM (Kereta Tanah Melayu) dibagian bawahnya.
No Studi Banding Pendekatan Struktur
1. Estacion de Atocha, Spanyol Mengikuti
suasana alam
hutan tropis
Bentang Lebar
2. Wuhan Train Station Bangunan public
berskala besar
yang terinspirasi
dari alam
Bentang Lebar
3. Stasiun KL Sentral, Kuala
Lumpur, Malaysia