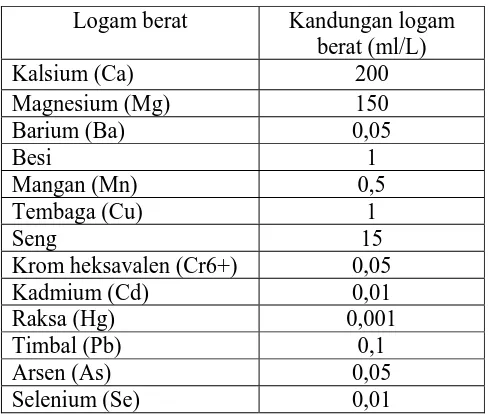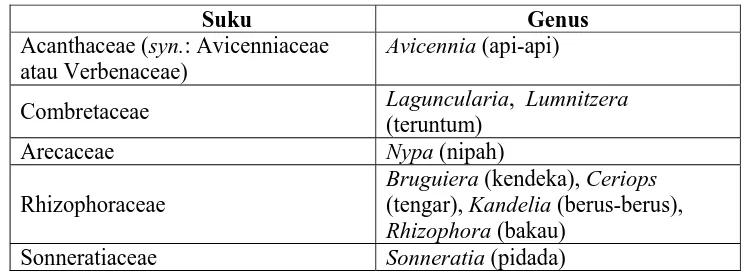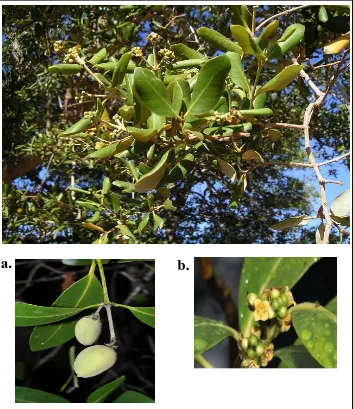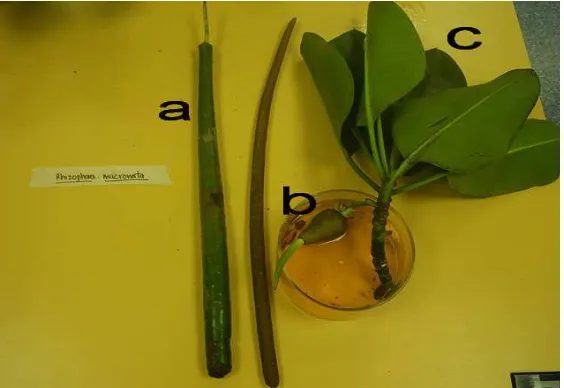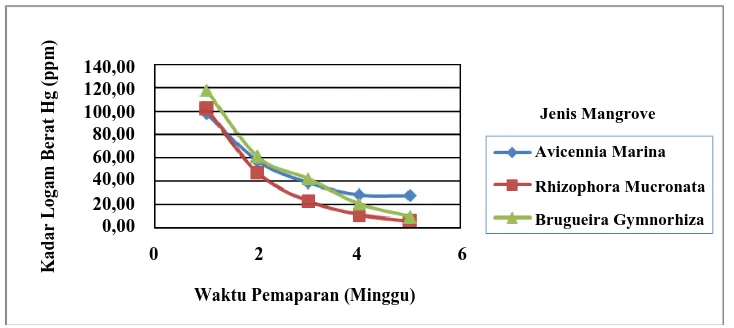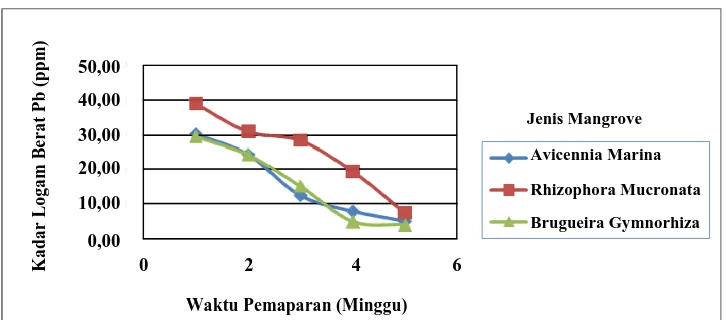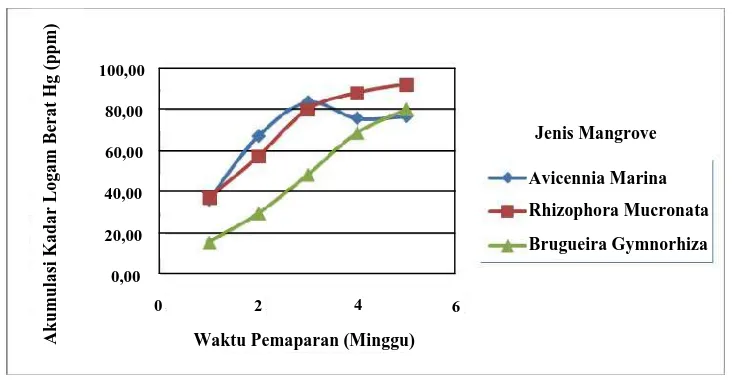MENYERAP LOGAM BERAT MERKURI (Hg) DAN
TIMBAL(Pb)
O l e h :
NPM : 0652010015
RINA
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JATIM
SURABAYA
CURRICULUM VITAE
1 FTSP UPN”Veteran” Jatim Teknik Lingkungan 2006 2010 LULUS
2 SMU Negeri 21 Surabaya I PA 2003 2006 LULUS
3 SMP Hang Tuah I Surabaya 2000 2003 LULUS
4 SD Al-Hikmah Surabaya 1994 2000 LULUS
Tugas Akademik
No. Kegiatan Tempat/ Judul Selesai tahun
1 Kuliah Lapangan Waret Treatment Megumi dan pengelolaan Hutan
Mangrove, Bali.
2008
2 Kunj. Pabrik Pabrik PT. Kertas Leces dan PT. PJB Paiton 2008
3 KKN Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. 2008
4 Kerja Praktek Studi Proses Pengelolaan dan Pengelolaan Limbah
Cair, Padat, Gas & B3 PT. Pabrik Gula Candi Baru, Sidoarjo.
2010
5 PBPAB Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buangan
I ndustri Gula.
2010
6 SKRI PSI Kemampuan Tanaman Mangrove untuk Menyerap
Logam Berat Merkuri (Hg) DAN Timbal(Pb). 2010
Orang Tua
Nama : Dwi Hendrata Bayuhardi
Alamat : Tamtama 35, Surabaya
vii proses-proses metabolisme.
Dari hasil analisa organolaptik terdapat bukti nyata bahwa mangrove jenis Bruguiera gymnorrhiza tahan terhadap konsentrasi toksik sedangkan mangrove jenis Avicennia marina dan Rhizophora mucronata tidak tahan terhadap konsentrasi toksik. Tetapi mangrove jenis Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan Bruguiera gymnorrhiza dapat menyerap logam berat dengan efektif terbukti pada analisa logam berat yang dilakukan.
Kemampuan mangrove dalam menyerap logam berat memiliki perlakuan yang berbeda terhadap konsentrasi toksik pada setiap jenisnya, agar dapat mengurangi tingkat pencemaran di atmosfer, tanah sedimen, dan air logam berat dengan maksimal.
vii
Bruguiera gymnorhiza, can stand from toxic consentrasion. But for another various like Avicennia marina and Rhizophora mucronata can’t against from toxic consentration.
It proved by the heavy metal analisis that kind of mangrove such as Avicennia marina, Rhizophora mucronata and Bruguiera gymnorhiza can reserve heavy metal effectively.
The power of mangrove reserve the heavy metal which has different treath whent from toxic consentration in every various so that can decrease the level of land soil at atmosphere, sedimen, and heavy metal until maximum.
Keyword: mangrove, Pb and Hg heavy metal
1
I.1 Latar Belakang
Keberadaan kadar logam berat yang terlarut baik pada air laut, sediment
maupun Lokan (Geloina coaxans) sangat tergantung pada baik buruknya
kondisi perairan tersebut. Semakin tinggi aktivitas yang terjadi disekitar
perairan baik di darat maupun areal pantainya maka kadar logam berat dapat
meningkat pula (Anonim, 2009).
Pantai Timur Surabaya diberitakan telah tercemar oleh merkuri (Hg) dan
timbal (Pb) saat ini, bila melihat data-data kesehatan dari beberapa hasil
penelitian memberikan indikasi bahwa kadar logam berat dalam tubuh warga
Surabaya telah di atas ambang batas. Menurut Anwar, 2006, pada darah
masyarakat nelayan di Kenjeran mengandung merkuri (Hg) sebesar 2,48 ppb.
Menurut Vera Hakim, 1998, rata-rata kadar timbal (Pb) darah anak-anak di
Kenjeran 59,62 mikrogram/dl. Menurut Abdul Rohim T 2008, kondisi ini
sudah cukup berdampak pada anak-anak Surabaya yang disebabkan karena
mengonsumsi ikan yang tercemar limbah antara lain menurunnya IQ sampai
empat poin, kurang konsentrasi dalam belajar sehingga prestasi belajar
menurun, berperilaku agresivitas tinggi, penyakit kanker serta
I.2 Perumusan Masalah
1. Keberadaan kadar logam berat yang terlarut pada perairan telah
melebihi ambang batas yang diakibatkan karena aktivitas yang terjadi disekitar
perairan baik di darat maupun areal pantai tersebut.
2. Tumbuhan mangrove termasuk jenis tumbuhan air yang banyak
dijumpai di sekitar wilayah perairan yang mempunyai kemampuan sangat
tinggi untuk mengakumulasi logam berat yang ada pada wilayah perairan.
I.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kemampuan tanaman mangrove jenis Avicennia Marina,
Rhizophora Mucronata, dan Brugueira Gymnorhiza dalam menyerap logam
berat timbal (Pb) dan merkuri (Hg).
2. Mengetahui diantara jenis mangrove Avicennia Marina, Rhizophora
Mucronata, dan Brugueira Gymnorhiza yang mempunyai daya serap logam
berat merkurti (Hg) dan timbal (Pb) yang paling tinggi.
I.4 Manfaat Penelitian
Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau
pemerintah kota tentang kemampuan jenis mangrove Avicennia Marina,
Rhizophora Mucronata, dan Brugueira Gymnorhiza dalam menyerap logam
I.5. Ruang Lingkup
1. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan daya serap mangrove umur
4 bulan terhadap logam berat timbal (Pb) dan merkuri (Hg).
2. Mangrove yang digunakan dalam penelitian ini adalah mangrove jenis
Avicennia Marina, Rhizophora Mucronata, dan Bruguiera
Gymnorrhiza.
3. Acuan untuk menentukan penambahan logam berat adalah hasil analisa
air dan media muara sungai Wonorejo.
4. Menggunakan media tanam, yaitu : tanah taman, pupuk kandang (2:1)
dan air rawa belakang FTSP.
5. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah media tanam, dan akar
tanaman mangrove.
6. Penelitian dan analisa logam berat timbal (Pb) dan mangrove (Hg)
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1. Pencemaran Air oleh Logam Berat
Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal,
bukan dari kemurniannya. Ciri-ciri air yang tercemar sangat bervariasi
tergantung dari jenis air dan polutannya. Untuk mengetahui suatu air tercemar
atau tidak, diperlukan suatu pengujian untuk mengetahui apakah terjadi
penyimpangan dari batasan pencemaran air (Anonim, 2009). Baku mutu air
golongan A yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No: Kep-02/MENKLH/I/ 1988.
Tabel 2.1 Kandungan Maksimal Logam yang Diperbolehkan dalam Air (mg/L)
Sumber : Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No : Kep-02/MENKLH/1988
Logam berat Kandungan logam
berat (ml/L)
Krom heksavalen (Cr6+) 0,05
Logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), cadmium
(Cd), kromium (Cr), seng (Zn), dan nikel (Ni), merupakan salah satu bentuk
materi anorganik yang sering menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup
serius pada perairan. Penyebab terjadinya pencemaran logam berat pada
perairan biasanya berasal dari masukan air yang terkontaminasi oleh limbah
buangan industri dan pertambangan (Anonim, 2010).
Pencemaran logam berat tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan
penyakit pada konsumen, karena di dalam tubuh unsur yang berlebihan akan
mengalami detoksifikasi sehingga membahayakan manusia. Logam berat
umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup walaupun beberapa
diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Melalui berbagai perantara, seperti
udara, makanan, maupun air yang terkontaminasi oleh logam berat, logam
tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan
terakumulasikan. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus, dalam jangka
waktu lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia
(Anonim, 2007).
Menurut Hutagalung, 1984, pengendapan logam berat di suatu perairan
terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil dan klorida. Menurut
Hutagalung, 1991, logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan
organik dan mengendap di dasar perairan dan bersatu dengan sedimen sehingga
kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibanding dalam air (Anonim,
Menurut Bryan, 1976, logam berat yang masuk ke sistem perairan, baik
di sungai maupun lautan akan dipindahkan dari badan airnya melalui tiga
proses yaitu pengendapan, adsorbsi, dan absorbsi oleh organisme-organisme
perairan. Pada saat buangan limbah industri masuk ke dalam suatu perairan
maka akan terjadi proses pengendapan dalam sedimen. Hal ini menyebabkan
konsentrasi bahan pencemar dalam sedimen meningkat. Logam berat yang
masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan,
pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di
perairan tersebut (Anonim, 2009).
II.1.1. Logam Berat Merkuri (Hg)
Sampai saat ini mercury bahan beracun yang tidak diketahui fungsi
positifnya bagi metaboilsma biokimia tubuh atau fisiologi mahluk hidup.
Mercury secara alami tidak ditemukan keberadaannya di dalam tubuh mahluk
hidup (Anonim, 2010).
Merkuri adalah polutan global dengan sifat fisika dan kimia yang
kompleks. Sumber utama alami merkuri adalah dari pelepasan gas dari tanah,
emisi dari gunung berapi, dan penguapan alami air. Kegiatan penambangan
logam-logam secara global juga secara tidak langsung menyumbang emisi
merkuri ke atmosfer. Merkuri digunakan secara luas dalam proses industri dan
pada bermacam-macam produk (spt batery, lampu, dan thermometer). Merkuri
juga banyak digunakan dalam dunia kedokteran gigi sebagai bahan isian
Perhatian terhadap keberadaan merkuri di lingkungan hidup meningkat
karena merkuri bisa muncul dalam bentuk dan sifat yang sangat beracun
(toxic). Merkuri umumnya berada di atmosfer dalam bentuk gas yang relatif
tidak reaktif. Panjangnya life time (umur) merkuri di atmosfer (lebih dari 1
tahun) menyebabkan polusi merkuri di atmosfer menjadi isu global, melewati
batas Negara (Anonim, 2010).
Proses biologis alami dapat menyebabkan merkuri ini mengalami
perubahan bentuk menjadi methylated form yang kemudian akan terakumulasi
dan terkonsentrasi pada organisme hidup seperti ikan. Bentuk-bentuk merkuri
ini: monomethyl mercuriy dan dimethyl mercury bersifat sangat beracun
(toxic), menjadi penyebab gangguan keracunan pada saraf pusat (Firlianasari,
2002).
Jalan utama masuknya merkuri ke tubuh manusia adalah melalui rantai
makanan, bukan melalui pernafasan. Sumber utama emisi merkuri adalah dari
kegiatan manufaktur chlorine di mercury cells, produksi logam-logam
non-ferrous, pembakaran batu bara dan crematorium (Anonim, 2010).
II.1.2. Logam Berat Timbal (Pb)
Timbal (Pb) adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang
lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur
mineral-mineral lain, terutama seng dan tembaga. Penggunaan timbal terbesar adalah
dalam industri baterai kendaraan bermotor seperti timbal metalik dan
komponen-komponennya. Timbal digunakan pada bensin untuk kendaraan, cat
debu sekitar jalan raya pada umumnya telah tercemar bensin bertimbal selama
bertahun-tahun, Sunu (2001) dalam Panjaitan, G.C (2009).
Pada manusia, timbal dapat mengakibatkan bermacam-macam dampak
biology, bergantung pada tingkatan dan durasi terpaannya. Dampak yang
bervariasi terjadi pada rentang dosis yang luas, dimana janin dan bayi lebih
rentan terkena dampak dibanding manusia dewasa (Firlianasari, 2002).
Meskipun kebanyakan jalan masuk timbal ke dalam tubuh adalah melalui
makanan, pada beberapa daerah, dimana sistem perpipaan air dan
plumbing-nya mengandung timbal, tingkat kontaminasi timbal ke dalam tubuh dapat jauh
lebih banyak melalu air minum. Demikian juga di area-area yang terletak
berdekatan dengan sumber emisi timbal, tanah, debu, serta cat pada
rumah-rumah tua atau tanah yang terkontaminasi timbal, kontaminasi melalui udara
dapat lebih tinggi (Anonim, 2010).
Pencemaran timbal pada bahan makanan terjadi terutama melalui
pengendapan debu yang mengandung bahan timbal ini dari udara serta hujan
yang membawa bahan ini ke tanaman perkebunan dan lahan pertanian
(Anonim, 2007).
Di Indonesia dan negara berkembang lain, tidak semua bahan bakar
minyak yang digunakan telah bebas timbal. Polusi timbal dari asap kendaraan
II.2. Dampak Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Logam Berat Merkuri (Hg)
Tersebarnya logam berat di dalam perairan mengakibatkan terjadinya
pencemaran pada suatau badan air. Dampak dari masuknya material logam ke
dalam perairan adalah terserapnya logam tersebut dalam tubuh makhluk hidup
air, baik ikan maupun tumbuhan (Firda, F., 2002).
Berdasarkan penelitian 3 staff dosen Psikologi Universitas Surabaya
menunjukkan bahwa 80% dari populasi anak sekolah di kenjeran mengalami
kemunduran intelektual atau Slow learner. Sebagian besar anak-anak di
Kenjeran tersebut diketahui banyak mengkonsumsi ikan yang kemungkinan
besar tercemar logam berat (Anonim, 2007).
Kehidupan organisme perairan yang tercemar merkuri (Hg) akan
mengkonsumsi merkuri (Hg) jauh lebih tinggi dari organisme yang hidup di
perairan belum tercemar, contoh kasus Minamata dimana penduduk di sekitar
Teluk Minamata banyak mengkonsumsi ikan yang mengandung merkuri (Hg)
sekitar 2.600 – 6.600 ug metil-merkuri (Hg) kg, yaitu kandungan metil-merkuri
(Hg) dalam taraf yang meracun, sementara ambang batas yang ditentukan oleh
FAO/WHO yaitu maksimum 30 ug (Anonim, 2001).
Daud Anwar SKM, Mkes,1996, menyatakan dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa darah dari sampel warga Kenjeran/Sukolilo mengandung
Merkuri (Hg) 2,48 ppb. Sedangkan pada penelitian terbaru A. Vera Hakim,
Pusat Kajian Regional Gizi Masyarakat Universitas Indonesia, menyatakan
darah ibu-ibu warga Kenjeran sebesar 2,8 mg/l (Ambang WHO/< 1 mg/l),
kandungan timah hitam (Pb) sebesar 416 mg/l (Ambang WHO/< 200 mg/l),.
Hasil tes terhadap air susu ibu juga menunjukkan adanya kandungan timbal
sebesar 543,2 mg/l (Normal<5 mg/l) (Anonim, 2007).
Apabila logam berat tersebut termakan oleh makhluk air dampak
terburuk adalah kematian pada organism tersebut yang mengakibatkan
kepunahan. Dan pada Organisme yang mampu mengakumulasi logam berat
lalu dikonsumsi oleh manusia maka dapat menyebabkan keguguran atau
kecacatan janin atau perubahan-perubahan psikologi lainnya. Sedangkan
terpaan pada tingkat yang tinggi dapat mengakibatkan dampak keracunan
biokimia pada manusia, yang selanjutnya dapat mengarah pada berbagai
problem seperti mengganggu proses sintesa hemoglobin, menyerang ginjal,
saluran pencernaan, persendian, dan sistem reproduksi, serta menimbulkan
kerusakan akut maupun kronis pada sistem saraf (Anonim, 2007).
Pada sedimen yang mengandung logam berat, khususnya mercuri (Hg)
dan timbal (Pb) termasuk bersifat toksik untuk kebanyakan tumbuhan.
Kontaminasi logam berat juga terjadi di daerah industri, baik yang berbentuk
debu ataupun garam dalam perairan di daerah industri tersebut. Kebanyakan
tumbuhan sensitive terhadap logam berat. Membukanya stomata dipengaruhi,
fotosintesis turun, respirasi terganggu dan akhirnya pertumbuhan terhambat.
Sebagian besar logam berat ini merupakan deposit di dinding sel-sel perakaran
Efek dari toksisitas logam berat terhadap tumbuhan pada umumnya
meliputi:
1. Dalam keadaan yang ekstrim dapat menghentikan pertumbuhan.
2. Menghambat fotosintesis.
3. Mengurangi kandungan klorofil.
4. Meningkatkan permialitas dan hilangnya ion kalium dari dalam sel.
Dampak yang diakibatkan oleh logam berat pada konsentrasi tinggi pada
tumbuhan akan menderita kerusakan akut dengan menampakkan gejala
seperti khlorosis, perubahan warna, nekrosis dan kematian seluruh bagian
tumbuhan (Anonim, 2006).
II.3. Hutan Mangrove
Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang
didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan
berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi
ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup
mendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang-surut
yang kuat. Karena itu hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk
yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung (Anonim,
Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove
di suatu lokasi dalam anonim, 2009 adalah :
1. Fisiografi pantai (topografi)
Fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies dan
lebar hutan mangrove. Pada pantai yang landai, komposisi ekosistem mangrove
lebih beragam jika dibandingkan dengan pantai yang terjal. Hal ini disebabkan
karena pantai landai menyediakan ruang yang lebih luas untuk tumbuhnya
mangrove sehingga distribusi spesies menjadi semakin luas dan lebar. Pada
pantai yang terjal komposisi, distribusi dan lebar hutan mangrove lebih kecil
karena kontur yang terjal menyulitkan pohon mangrove untuk tumbuh.
2. Pasang (lama, durasi, rentang)
Pasang yang terjadi di kawasan mangrove sangat menentukan zonasi
Tumbuhan dan komunitas hewan yang berasosiasi dengan ekosistem
mangrove. Secara rinci pengaruh pasang terhadap pertumbuhan mangrove
dijelaskan sebagai berikut:
1) Lama pasang
a) Perubahan salinitas air dimana salinitas akan meningkat pada saat
pasang dan sebaliknya akan menurun pada saat air laut surut.
b) Perubahan salinitas yang terjadi sebagai akibat lama terjadinya pasang
merupakan faktor pembatas yang mempengaruhi distribusi spesies secara
horizontal.
c) Perpindahan massa air antara air tawar dengan air laut mempengaruhi
2) Durasi pasang
a) Struktur dan kesuburan mangrove di suatu kawasan yang memiliki
jenis pasang diurnal, semi diurnal, dan campuran akan berbeda.
b) Komposisi spesies dan distribusi areal yang digenangi berbeda
menurut durasi pasang atau frekuensi penggenangan. Misalnya :
penggenagan sepanjang waktu maka jenis yang dominan adalah
Rhizophora mucronata dan jenis Bruguiera serta Xylocarpus
kadang-kadang ada.
3) Rentang pasang (tinggi pasang)
a) Akar tunjang yang dimiliki Rhizophora mucronata menjadi lebih
tinggi pada lokasi yang memiliki pasang yang tinggi dan sebaliknya.
b) Pneumatophora Sonneratia sp menjadi lebih kuat dan panjang pada
lokasi yang memiliki pasang yang tinggi.
3. Gelombang dan arus
1) Gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem
mangrove. Pada lokasi-lokasi yang memiliki gelombang dan arus yang
cukup besar biasanya hutan mangrove mengalami abrasi sehingga terjadi
pengurangan luasan hutan.
2) Gelombang dan arus juga berpengaruh langsung terhadap distribusi
3) Spesies misalnya buah atau semai Rhizophora terbawa gelombang dan
arus sampai menemukan substrat yang sesuai untuk menancap dan akhirnya
4) Gelombang dan arus berpengaruh tidak langsung terhadap sedimentasi
pantai dan pembentukan padatan-padatan pasir di muara sungai. Terjadinya
sedimentasi dan padatan-padatan pasir ini merupakan substrat yang baik
untuk menunjang pertumbuhan mangrove.
5) Gelombang dan arus mempengaruhi daya tahan organisme akuatik
melalui transportasi nutrien-nutrien penting dari mangrove ke laut.
Nutrien-nutrien yang berasal dari hasil dekomposisi serasah maupun yang berasal
dari runoff daratan dan terjebak di hutan mangrove akan terbawa oleh arus
dan gelombang ke laut pada saat surut.
4. Iklim (cahaya,curah hujan, suhu, angin)
Mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik
(substrat dan air). Pengaruh iklim terhadap pertimbuhan mangrove melalui
cahaya, curah hujan, suhu, dan angin :
1) Cahaya
a) Cahaya berpengaruh terhadap proses fotosintesis, respirasi, fisiologi,
dan struktur fisik mangrove.
b) Intensitas, kualitas, lama (mangrove adalah tumbuhan long day plants
yang membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi sehingga sesuai untuk
hidup di daerah tropis) pencahayaan mempengaruhi pertumbuhan
mangrove.
c) Laju pertumbuhan tahunan mangrove yang berada di bawah naungan
sinar matahari lebih kecil dan sedangkan laju kematian adalah
d) Cahaya berpengaruh terhadap perbungaan dan germinasi dimana
tumbuhan yang berada di luar kelompok (gerombol) akan menghasilkan
lebih banyak bunga karena mendapat sinar matahari lebih banyak
daripada tumbuhan yang berada di dalam gerombol.
2) Curah hujan
a) Jumlah, lama, dan distribusi hujan mempengaruhi perkembangan
tumbuhan mangrove.
b) Curah hujan yang terjadi mempengaruhi kondisi udara, suhu air,
salinitas air dan tanah.
c) Curah hujan optimum pada suatu lokasi yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan mangrove adalah yang berada pada kisaran 1500-3000
mm/tahun.
3) Suhu
a) Suhu berperan penting dalam proses fisiologis (fotosintesis dan
respirasi).
b) Produksi daun baru Avicennia marina terjadi pada suhu 18-20ºC dan
jika suhu lebih tinggi maka produksi menjadi berkurang.
c) Rhizophora stylosa, Ceriops, Excocaria, Lumnitzera tumbuh optimal
pada suhu 26-28C.
d) Bruguiera tumbuah optimal pada suhu 27C, dan Xylocarpus tumbuh
optimal pada suhu 21-26C.
4) Angin
b) Angin merupakan agen polinasi dan diseminasi biji sehingga
membantu terjadinya proses reproduksi tumbuhan mangrove.
5. Salinitas
1) Salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh berkisar
antara 10-30 ppt.
2) Salinitas secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan
zonasi mangrove, hal ini terkait dengan frekuensi penggenangan.
3) Salinitas air akan meningkat jika pada siang hari cuaca panas dan dalam
keadaan pasang.
4) Salinitas air tanah lebih rendah dari salinitas air.
6. Oksigen terlarut
1) Oksigen terlarut berperan penting dalam dekomposisi serasah karena
bakteri dan fungsi yang bertindak sebagai dekomposer membutuhkan
oksigen untuk kehidupannya.
2) Oksigen terlarut juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis.
3) Oksigen terlarut berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan
kondisi terendah pada malam hari.
7. Subtrat
1) Rhizophora mucronata dapat tumbuh baik pada substrat yang
dalam/tebal dan berlumpur.
3) Tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan kerapatan
tegakan Misalnya jika komposisi substrat lebih banyak liat (clay) dan debu
(silt) maka tegakan menjadi lebih rapat.
4) Konsentrasi kation Na>Mg>Ca atau K akan membentuk konfigurasi
hutan Avicennia/Sonneratia/Rhizophora/Bruguiera.
5) Mg>Ca>Na atau K yang ada adalah Nipah.
6) Ca>Mg, Na atau K yang ada adalah Melauleuca.
8. Hara
Unsur hara yang terdapat di ekosistem mangrove terdiri dari hara inorganik
(P,K,Ca,Mg,Na) dan organik(Allochtonous dan Autochtonous (fitoplankton,
bakteri, alga).
Hutan mangrove yang umumnya didominasi oleh pohon mangrove dari
empat genera (Rhizophora, Avicennia, Sonneratia dan Bruguiera), memiliki
kemampuan adaptasi yang khas untuk dapat hidup dan berkembang pada
substrat berlumpur yang sering bersifat asam dan anoksik. Kemampuan
adaptasi ini meliputi:
1. Adaptasi Terhadap Kadar Oksigen Rendah
Pohon mangrove memiliki sistem perakaran yang khas bertipe cakar
ayam, penyangga, papan dan lutut. Sistem perakaran cakar ayam yang
menyebar luas di permukaan substrat, memiliki sederet cabang akar berbentuk
pinsil yang tumbuh tegak lurus ke permukaan substrat. Cabang akar ini disebut
pneumatofora dan berfungsi untuk mengambil oksigen (Avicennia spp.,
dengan sistem perakaran cakar ayam, dimana akar-akar penyangga tumbuh dari
batang pohon menembus permukaan substrat. Pada akar penyangga ini tidak
ditemukan pneumatofora seperti pada akar cakar ayam (Rhizophora spp) dan
akar lutut (Bruguiera spp.), tapi mempunyai lobang-lobang kecil yang disebut
lentisel yang juga berfungsi untuk melewatkan udara (mendapatkan oksigen).
2. Adaptasi Terhadap Kadar Garam Tinggi
Berdaun tebal dan kuat yang mengandung kelenjar-kelenjar garam
untuk dapat menyekresi garam. Mempunyai jaringan internal penyimpan air
untuk mengatur keseimbangan garam. Daunnya memiliki struktur stomata
khusus untuk mengurangi penguapan.
1) Mangrove yang dapat mensekresi garam (salt-secretors).
Jenis mangrove ini memiliki salt glands di daun yang memungkinkan
untuk mensekresi cairan Na+ dan Cl-.
contoh : Aegiceras, Aegialitis, Avicennia, Sonneratia, Acanthus,
Laguncularia.
2) Mangrove yang tidak dapat mensekresi garam (salt-excluders).
Mangrove jenis ini memiliki ultra filter di akarnya sehingga air dapat
diserap dan garam dapat dicegah masuk ke dalam jaringan.
contoh : Rhizophora, Ceriops, Sonneratia, Avicennia, Osbornia, Bruguiera,
Excoecaria, Aegiceras, Aegialitis, Acrostichum, Lumnitzera, Hibiscus,
Eugenia.
3) Mangrove yang dapat mengakumulasi garam di dalam jaringan tubuhnya
contoh : Xylocarpus, Excoecaria, Osbornia, Ceriops, Bruguiera.
Beraneka jenis tumbuhan ini dijumpai di hutan bakau. Akan tetapi hanya
sekitar 54 spesies dari 20 genera, anggota dari sekitar 16 suku, yang dianggap
sebagai jenis-jenis mangrove sejati. Yakni jenis-jenis yang ditemukan hidup
terbatas di lingkungan hutan mangrove dan jarang tumbuh di luarnya (Anonim,
2009).
Menurut Noor dkk, 1999, menyatakan dari jenis-jenis itu, sekitar 39
jenisnya ditemukan tumbuh di Indonesia; menjadikan hutan bakau Indonesia
sebagai yang paling kaya jenis di lingkungan Samudera Hindia dan Pasifik.
Total jenis keseluruhan yang telah diketahui, termasuk jenis-jenis mangrove
ikutan, adalah 202 spesies (Anonim, 2009).
Menurut Tomlinson 1986 dalam anonim, 2009, daftar suku dan genus
mangrove sejati, beserta jumlah jenisnya :
1. Penyusun utama
Tabel 2.2 Daftar Suku dan Genus Mangrove Penyusun Utama
Suku Genus
Acanthaceae (syn.: Avicenniaceae atau Verbenaceae)
Avicennia (api-api)
Combretaceae Laguncularia, Lumnitzera
2. Penyusun minor
Tabel 2.3 Daftar Suku dan Genus Mangrove Penyusun Minor
Suku Genus
Acanthaceae Acanthus (jeruju), Bravaisia
Bombacaceae Camptostemon Cyperaceae Fimbristylis (mendong)
Euphorbiaceae Excoecaria (kayu buta-buta) Lythraceae Pemphis (cantigi laut) Meliaceae Xylocarpus (nirih) Myrsinaceae Aegiceras (kaboa)
Myrtaceae Osbornia Pellicieraceae Pelliciera
Plumbaginaceae Aegialitis
Pteridaceae Acrostichum (paku laut)
Rubiaceae Scyphiphora Sterculiaceae Heritiera (dungun)
Sumber : URL:http://id.Wikipedia.org
Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran
yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi,
serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit
jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini dan jenis-jenis ini
kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi
dan evolusi (Anonim, 2009).
Sebagai suatu ekosistem khas wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki
beberapa fungsi ekologis penting :
1. Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pe-lindung pantai dari abrasi,
penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air
2. Sebagai tumbuhan tingkat tinggi yang mampu mentransporranspor logam
berat yang diserap dari sel ke sel menuju jaringan vaskuler agar dapat
didistribusikan ke seluruh bagian tubuh.
3. Sebagai penghasil sejumlah besar detritus, terutama yang berasal dari daun
dan dahan pohon mangrove yang rontok. Sebagian dari detritus ini dapat
dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi para pemakan detritus, dan
sebagian lagi diuraikan secara bakterial menjadi mineral-mineral hara yang
berperan dalam penyuburan perairan.
4. Sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makanan (feeding
ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) bermacam biota perairan
(ikan, udang dan kerang-kerangan) baik yang hidup di perairan pantai maupun
lepas pantai (Anonim, 2009).
Hutan mangrove dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu untuk
bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku untuk membuat arang, dan juga
untuk dibuat pulp. Di samping itu ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai
pemasok larva ikan dan udang alam (Anonim, 2009).
II.4. Landasan teori
II.4.1. Proses Penyerapan Akar Mangrove Terhadap Logam Berat
Komunitas mangrove sering kali mendapatkan suplai bahan polutan
seperti logam berat yang berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan
mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakumulasi logam berat yang
berada pada wilayah perairan.
Proses absorpsi pada tumbuhan terjadi seperti pada hewan dengan
berbagai proses difusi, dan istilah yang digunakan adalah translokasi. Transpor
ini terjadi dari sel ke sel menuju jaringan vaskuler agar dapat didistribusikan ke
seluruh bagian tubuh.
Menurut Soemirat (2003) dalam Panjaitan, G.C. (2009), menyatakan
bahwa proses absorpsi dapat terjadi lewat beberapa bagian tumbuhan, yaitu :
1. Akar, terutama untuk zat anorganik dan zat hidrofilik.
2. Daun bagi zat yang lipofilik.
3. Stomata untuk masukan gas.
Tumbuhan mangrove mampu mengalirkan oksigen melalui akar ke
dalam sedimen tanah untuk mengatasi kondisi anaerob pada sedimen tersebut.
Jika logam berat memasuki jaringan, terdapat mekanisme yang sangat jelas,
pengambilan (up taken) logam berat oleh tumbuhan di lahan basah adalah
melalui penyerapan dari akar, setelah itu tumbuhan dapat melepaskan senyawa
kelat, seperti protein dan gukosida yang berfungsi mengikat logam dan
dikumpulkan ke jaringan tubuh kemudian ditransportasikan ke batang, daun
dan bagian lainnya, sedangkan ekskresinya terjadi melalui transpirasi (Anonim,
Tumbuhan mempunyai kemampuan untuk menyerap ion-ion dari
lingkungan ke dalam tubuh melalui membrane sel. Dua sifat penyarapan ion
dari tumbuhan, yaitu:
1. Faktor konsentrasi, yaitu kemampuan tumbuhan dalam mengakumulasi ion
sampai tingkat konsentrasi tertentu bahkan dapat mencapai beberapa tingkat
dari konsentrasi ion di dalam mediumnya.
2. Perbedaal kuantitatif akan kebutuhan hara yang brebeda pada tiap jenis
tumbuhan (Fitter dan Hay, 1991) dalam anonim (2009).
Beraneka ragam unsur dapat ditemukan di dalam tubuh tumbuhan, tetapi tidak
berarti bahwa seluruh unsur-unsur tersebut dibutuhkan tumbuhan untuk
kelangsungan hidupnya.
Unsur hara dapat kontak dengan pernukaan akar melalui :
1. Secara difusi dalam larutan tanah.
2. Secara pasif oleh aliran air tanah.
3. Akar tumbuh ke arah posisis hara dalam matrik tanah.
Serapan hara oleh akar dapat bersifat akumulatif, selektif, satu arah, dan tidak
dapat jenuh. Penyerapan hara pada waktu yang lama menyebabkan konsentrasi
hara dalam sel jauh lebuh tinggi ini disebut sebagai akumulasi hara.
Menurut Fitter dan Hay (1991) dalam Panjaitan, G.C. (2009), mekanisme
yang mungkin dilakukan oleh tumbuhan untuk menghadapi konsentrasi toksik
adalah :
1. Penanggulangan, jika konsentrasi internal harus dihadapi maka ion-ion akan
toleran di dalam sitoplasma. Terdapat empat pendekatan dalan
penanggulangan :
1) Lokalisasi (intraseluler dan ekstraseluler) pada umunnya di akar.
2) Ekskresi, secara aktif melalui kelenjar pada tajuk atau secara pasif
melalui akumulasi pada daun-daun tua yang diikuti dengan absisi daun.
3) Dilusi (melemahkan), yaitu melalui pengenceran.
4) Inaktivasi secara kimia.
2. Toleransi, yaitu tumbuhan mengembangkan sistem metabolik yang dapat
berfungsi pada konsentrasi toksik.
Tumbuhan yang tumbuh di air akan terganggu oleh bahan kimia toksik
dalam limbah. Pengaruh polutan terhadap tumbuhan dapat berbeda tergantung
pada macam polutan, konsentrasinya, dan lamanya polutan itu berada.
Menurut Fitter (1982) dalam anonim (2009), mekanisme yang mungkin
dilakukan oleh tumbuhan untuk menghadapi konsentrasi toksik adalah
penanggulangan (ameliorasi) untuk meminimumkan pengaruh toksin terdapat
empat pendekatan:
1. Lokalisasi (intraseluler atau ekstraseluler); biasanya pada organ akar.
2. Ekskresi secara aktif melalui kelenjar pada tajuk atau secara pasif melalui
akumulasi pada daun-daun tua yang diikuti dengan pengguguran daun.
3. Dilusi (melemahkan) melalui pengenceran.
4. Inaktivasi secara kimia.
Disamping itu, sistem perakaran tumbuhan mangrove yang besar dan
tersebarnya bahan tercemar ke area yang lebih luas dan memungkinkan
tersebarnya bahan pencemar secara fisik. Terserap dan tertahannya logam berat
oleh lapisan rhizosfer disekitar akar menyebabkan terjadinya penurunan tajam
konsentrasi logam berat pada permukaan atas lapisan sedimen dan mencegah
perpindahan keperairan pantai disekitarnya.
Silva dkk, 1990 dalam anonim (2009), melaporkan bahwa sedimen
dimana komunitas mangrove tumbuh di Teluk Sepetiba, Rio De Janerio, Brasil,
logam beratb timbal (Pb) hampir mencapai 100% dari total kandungan logam
berat pada ekosistem mangrove tersebut.
II.4.2. Mangrove
Mangrove adalah tanaman yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau
yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
Tanaman ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran
dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari
gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan
mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu (Anonim, 2009).
Jenis mangrove yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Avicennia Marina
1) Deskripsi : Belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar,
ketinggian pohon mencapai 30 meter. Memiliki sistem perakaran horizontal
yang rumit dan berbentuk pensil (atau berbentuk asparagus), akar nafas tegak
terkelupas dalam bagian-bagian kecil. Ranting muda dan tangkai daun
berwarna kuning, tidak berbulu.
2) Daun : Bagian atas permukaan daun ditutupi bintik-bintik kelenjar
berbentuk cekung. Bagian bawah daun putih- abu-abu muda. Unit dan letak:
sederhana & berlawanan. Bentuk: elips, bulat memanjang, bulat telur terbalik.
Ujung: meruncing hingga membundar. Ukuran: 9 x 4,5 cm.
3) Bunga : Seperti trisula dengan bunga bergerombol muncul di ujung
tandan, bau menyengat, nektar banyak. Letak: di ujung atau ketiak tangkai
atau tandan bunga. Formasi: bulir (2-12 bunga per tandan). Daun Mahkota: 4,
kuning pucat-jingga tua, 5-8 mm. Kelopak Bunga: 5. Benang sari: 4.
4) Buah : Buah agak membulat, berwarna hijau agak keabu-abuan.
Permukaan buah berambut halus (seperti ada tepungnya) dan ujung buah agak
tajam seperti paruh. Ukuran: sekitar 1,5x2,5 cm.
5) Ekologi : Merupakan tumbuhan pionir pada lahan pantai yang terlindung,
memiliki kemampuan menempati dan tumbuh pada berbagai habitat
pasang-surut, bahkan di tempat asin sekalipun. Jenis ini merupakan salah satu jenis
tumbuhan yang paling umum ditemukan di habitat pasang-surut. Akarnya
sering dilaporkan membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses
pembentukan tanah timbul. Jenis ini dapat juga bergerombol membentuk
suatu kelompok pada habitat tertentu. Berbuah sepanjang tahun,
kadang-kadang bersifat vivipar. Buah membuka pada saat telah matang, melalui
lapisan dorsal. Buah dapat juga terbuka karena dimakan semut atau setelah
6) Penyebaran : Tumbuh di Afrika, Asia, Amerika Selatan, Australia,
Polynesia dan Selandia Baru. Ditemukan di seluruh Indonesia.
7) Manfaat : Daun digunakan untuk mengatasi kulit yang terbakar. Resin
yang keluar dari kulit kayu digunakan sebagai alat kontrasepsi. Buah dapat
dimakan. Kayu menghasilkan bahan kertas berkualitas tinggi. Daun
digunakan sebagai makanan ternak.
Gambar 2.1 Mangrove Avicennia marina a. Buah ; b. Bunga.
2. Rhizophora Mucronata
1) Deskripsi : Pohon dengan ketinggian mencapai 27 m, jarang melebihi 30
m. Batang memiliki diameter hingga 70 cm dengan kulit kayu berwarna
gelap hingga hitam dan terdapat celah horizontal. Akar tunjang dan akar
udara yang tumbuh dari percabangan bagian bawah.
2) Daun : Daun berkulit. Gagang daun berwarna hijau, panjang 2,5-5,5 cm.
Pinak daun terletak pada pangkal gagang daun berukuran 5,5-8,5 cm. Unit
dan Letak: sederhana dan berlawanan. Bentuk: elips melebar hingga bulat
memanjang. Ujung: meruncing. Ukuran: 11-23 x 5-13 cm.
3) Bunga : Gagang kepala bunga seperti cagak, bersifat biseksual,
masing-masing menempel pada gagang individu yang panjangnya 2,5-5 cm. Letak:
di ketiak daun. Formasi: Kelompok (4-8 bunga per kelompok). Daun
mahkota: 4; putih, berambut 9 mm. Kelopak bunga: 4; kuning pucat,
panjangnya 13-19 mm. Benang sari: 8; tak bertangkai.
4) Buah : Buah lonjong/panjang hingga berbentuk telur berukuran 5-7 cm,
berwarna hijaukecoklatan, seringkali kasar di bagian pangkal, berbiji
tunggal. Hipokotil silindris, kasar dan berbintil. Leher kotilodon kuning
ketika matang. Ukuran: Hipokotil: panjang 36-70 cm dan diameter 2-3 cm.
5) Ekologi : Di areal yang sama dengan R.apiculata tetapi lebih toleran
terhadap substrat yang lebih keras dan pasir. Pada umumnya tumbuh dalam
kelompok, dekat atau pada pematang sungai pasang surut dan di muara
sungai, jarang sekali tumbuh pada daerah yang jauh dari air pasang surut.
tanah yang kaya akan humus. Merupakan salah satu jenis tumbuhan
mangrove yang paling penting dan paling tersebar luas. Perbungaan terjadi
sepanjang tahun. Anakan seringkali dimakan oleh kepiting, sehingga
menghambat pertumbuhan mereka. Anakan yang telah dikeringkan dibawah
naungan untuk beberapa hari akan lebih tahan terhadap gangguan kepiting.
Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya akumulasi tanin dalam jaringan
yang kemudian melindungi mereka.
6) Manfaat : Kayu digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Tanin dari
kulit kayu digunakan untuk pewarnaan, dan kadang-kadang digunakan
sebagai obat.
Gambar 2.3 Bagian Organ Mangrove Rhizophora Mucronata a. Buah ; b. Bunga ; c. Daun
3. Bruguiera Gymnorhiza
1) Deskripsi : Pohon yang selalu hijau dengan ketinggian kadang-kadang
mencapai 30 m. Kulit kayu memiliki lentisel, permukaannya halus hingga
kasar, berwarna abu-abu tua sampai coklat (warna berubah-ubah). Akarnya
seperti papan melebar ke samping di bagian pangkal pohon, juga memiliki
sejumlah akar lutut.
2) Daun : Daun berkulit, berwarna hijau pada lapisan atas dan hijau
kekuningan pada bagian bawahnya dengan bercak-bercak hitam (ada juga
yang tidak). Unit & Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: elips sampai
elips-lanset. Ujung: meruncing Ukuran: 4,5-7 x 8,5-22 cm.
3) Bunga : Bunga bergelantungan dengan panjang tangkai bunga antara
Mahkota: 10-14; putih dan coklat jika tua, panjang 13-16 mm. Kelopak
Bunga: 10-14; warna merah muda hingga merah; panjang 30-50.
4) Buah : Buah melingkar spiral, bundar melintang, panjang 2-2,5 cm.
Hipokotil lurus, tumpul dan berwarna hijau tua keunguan. Ukuran:
Hipokotil: panjang 12-30 cm dan diameter 1,5-2 cm.
5) Ekologi : Merupakan jenis yang dominan pada hutan mangrove yang
tinggi dan merupakan ciri dari perkembangan tahap akhir dari hutan pantai,
serta tahap awal dalam transisi menjadi tipe vegetasi daratan. Tumbuh di
areal dengan salinitas rendah dan kering, serta tanah yang memiliki aerasi
yang baik. Jenis ini toleran terhadap daerah terlindung maupun yang
mendapat sinar matahari langsung. Mereka juga tumbuh pada tepi daratan
dari mangrove, sepanjang tambak serta sungai pasang surut dan payau.
Ditemukan di tepi pantai hanya jika terjadi erosi pada lahan di hadapannya.
Substrat-nya terdiri dari lumpur, pasir dan kadang-kadang tanah gambut
hitam. Kadang-kadang juga ditemukan di pinggir sungai yang kurang
terpengaruh air laut, hal tersebut dimungkinkan karena buahnya terbawa
arus air atau gelombang pasang. Regenerasinya seringkali hanya dalam
jumlah terbatas. Bunga dan buah terdapat sepanjang tahun. Bunga relatif
besar, memiliki kelopak bunga berwarna kemerahan, tergantung, dan
mengundang burung untuk melakukan penyerbukan.
6) Penyebaran : Dari Afrika Timur dan Madagaskar hingga Sri Lanka,
7) Manfaat : Bagian dalam hipokotil dimakan (manisan kandeka), dicampur
dengan gula. Kayunya yang berwarna merah digunakan sebagai kayu bakar
dan untuk membuat arang.
Gambar 2.4 Mangrove BruyguieraGymnorhiza
BAB III
METODE PENELITIAN
III. 1. Bahan Penelitian
1. Tanaman mangrove jenis Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan
Bruguiera gymnorrhiza umur 4 bulan.
2. Tanah taman dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1.
3. Air rawa belakang FTSP (aklimatisasi).
4. Limbah artificial.
5. Air mineral.
.
III. 2. Peralatan Penelitian
1. Bak plastik dengan volume 9,33 liter
III. 3. Prosedur Penelitian
1. Tanah taman dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, campur rata
lalu masukkan ke dalam bak plastik setinggi 16,5 cm.
2. Setelah itu tanam tumbuhan mangrove ke dalam bak.
3. Beri tanda pada bak setinggi 5 cm diatas permukaan tanah untuk
penambahan air rawa belakang FTSP. Lalu masukkan air rawa belakang
FTSP sampai ketinggian yang telah ditentukan.
4. Proses aklimatisasi sampai tanaman mangrove tumbuh tunas.
5. Setelah tumbuh tunas, lakukan penambahan konsentrasi logam berat
timbal (Pb) sebesar 50 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar 150 ppm.
6. Amati perubahan morfologi tumbuhan mangrove 1 minggu sekali.
7. Penyiraman dilakukan 2 minggu sekali dengan ketinggian air 5 cm diatas
permukaan tanah. Penyiraman menggunakan air mineral.
III. 4. Peubah
1. Jenis tanaman mangrove :
1) Avicennia marina
2) Rhizophora mucronata
3) Bruguiera gymnorrhiza
2. Limbah artificial :
1) Timbal (Pb)
2) Merkuri (Hg)
3. Pemaparan logam berat, 1 – 5 minggu.
III. 5. Tetapan
1. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) 50 ppm
III. 6. Kerangka Penelitian
III. 7. Prosedur Analisa Organolaptik
Setelah proses aklimatisasi selesai ditandai dengan tumbuhnya tunas,
maka dilakukan pengamatan morfologi tumbuhan mangrove mulai minggu
ke-1 sampai dengan minggu ke-5.
Judul
Kemampuan Tanaman Mangrove untuk Menyerap Logam Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb)
Persiapan Alat dan Bahan Studi Literatur
Proses Aklimatisasi
Analisa Hasil
Pembahasan Hasil
III. 8. Prosedur Analisa Laboratorium
1. Sampel akar yang telah diambil dari lokasi pengamatan dicuci untuk
menghilangkan lumpur yang melekat pada organ tanaman, bersama sedimen
kemudian dioven pada suhu ±101oC selama 3 jam untuk mendapatkan kadar
air 1%.
2. Setelah kering sampel dihaluskan hingga menjadi serbuk. Sampel tanaman
dihaluskan dengan menggunakan blender, sedangkan sampel sedimen
dihaluskan dengan cara digerus.
3. Serbuk sampel tanaman dan sedimen kemudian ditimbang sebanyak 5-8
gram.
4. Sampel didestruksi secara kimia. Sampel dimasukkan ke dalam beaker
glass pyrex ditambahkan 15 ml HCl pekat dan 5 ml HNO3 pekat dan mulut
beaker ditutup dengan kaca arloji.
5. Selanjutnya dilakukan pengenceran sampel dengan 50-100 ml aquades.
Kemudian shake larutan sampel ± 30 menit supaya homogen.
6. Larutan sampel tersebut diukur atau dimasukan ke alat Spektro Pharo 100.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
IV.1. Pengamatan Morfologi
Pengamatan dilakukan setelah proses aklimatisasi selesai, baik pada
kontrol maupun pada media tanam yang telah ditambahkan logam berat timbal
(Pb) sebesar 50 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar 150 ppm pada
mansing-masing bak tanaman mangrove jenis :
1. Avicennia Marina : pada bak kontrol mulai tumbuh tunas baru sebanyak 4
tunas pada minggu ke-2, pada minggu ke-4, terdapat 3 daun tua yang mulai
menguning. Menguningnya daun pada minggu ke-4 adalah wajar dikarenakan
usia daun yang sudah tua yang berada pada bagian paling bawah batang. Dan
pada minggu ke-5 selain tunas yang berkembang, tidak ada perkembangan
yang berarti.
Sedangkan pada masing-masing bak yang telah ditambahkan konsentrasi
logam berat mulai dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 hanya
terdapat tunas yang terus berkembang pada bak-1 sampai dengan bak-5. Mulai
terjadi gangguan pada tanaman berupa menguningnya beberapa daun dan
tampak layu, baik pada 3 sampai dengan 5. Di minggu ke-4, pada
bak-4 dan bak-5 jumlah daum yang menguning trus bertambah. Sampai pada
minggu ke-5 pertumbuhan terhenti, daun perlahan berubah warna menjadi
coklat dan akhirnya kering atau mati. Perubahan warna pada daun merupakan
akibat terjadinya gangguan terhadap proses pembentukan klorofil atau yang
dikenal dengan istilah klorosis. Jika pembentukkan klorofil terganggu, maka
proses fotosintesis juga akan terganggu, pada akhirnya akan mengganggu
pertumbuhan yang mengakibatkan kematian tanaman. Hal ini sangat bertolak
belakang pada kontrol karena pada kontrol tanaman tumbuh dengan normal
dengan adanya tunas yang terus berkembang.
2. Rhizophora Mucronata : pada bak kontrol, terjadi pertumbuhan tunas pada
minggu ke-1 muncul 2 tunas baru pada batang muda di sisi kanan dan kiri. Di
lanjutkan pada sampai dengan minggu ke-5 pertumbuhan batang muda
semakin berkembang.
Sedangkan pada masing-masing bak yang telah ditambahkan konsentrasi
logam, untuk minggu ke-1 mulai dari bak-1 sampai dengan bak-5 tidak ada
perkembangan yang berarti. Demikian pula yang terjadi pada minggu ke-2,
hanya pada bak-2 terdapat 1 daun menguning. Di minggu ke-3 pada bak-3
terdapat 1 daun menguning sedangkan pada bak ke-4 sampai dengan bak ke-5
mulai terjadi gangguan pada tanaman menjadi layu sampai pada minggu ke-4
terdapat 2 daun menguning di bak-5 diikuti pada minggu ke-5 tanaman tidak
mengalami perubahan. Hal semacam ini hampir sama dengan yang dialami
oleh tanaman mangrove jenis Avicennia Marina, pada kontrol tanaman tumbuh
dengan normal karena proses fotosintesis tetap berjalan. Sedangkan dari
minggu ke-3 tumbuhan sudah mulai layu, sampai dengan minggu ke-5 tidak
ada perubahan yang berarti dan akar tumbuhan mangrove terus menyerap dan
merupakan dampak dari toksik logam berat pada tumbuhan, yang
mengakibatkan terhambatnya proses foto sintesis pada tumbuhan.
3. Bruguiera Gimnorhiza : pada bak kontrol, terjadi pertumbuhan tunas pada
minggu ke-2 dan 1 daun menguning . Di minggu ke-3 sampai dengan minggu
ke-5 hanya terjadi tunas yang berkembang.
Sedangkan pada masing-masing bak yang telah ditambahkan konsentrasi
logam berat, pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 hanya terdapat
tunas yang mengembang. Minggu ke-5 di bak-5 mulai muncul tunas dan
terdapat 1 daun tua yang mulai menguning.
Bila dibandingkan dengan kontrol, perkembangan pada bak yang telah
ditambahkan konsentrasi logam berat lebih lambat dengan tunas yang mulai
tumbuh lagi pada minggu ke-5.
IV.2.Penyerapan Logam Berat Timbal (Pb) dan Logam Berat Merkuri
(Hg) pada Tanaman Mangrove
Tanaman mempunyai kemampuan mengakumulasi zat pencemar.
Mangrove merupakan tumbuhan tingkat tinggi di kawasan pantai yang dapat
berfungsi untuk menyerap bahan-bahan organik dan non-organik sehingga
dapat dijadikan bioindikator logam berat (Wittig 1993). Melalui akarnya,
vegetasi ini dapat menyerap logam-logam berat yang terdapat pada sedimen
maupun kolom air dan pangkal ranting dan daun muda pada ujung ranting
Tabel 4.1. Pengaruh Waktu Pemaparan dan Jenis Mangrove Terhadap Kadar Logam Berat pada Media Tanam dan Akar
Jenis Mangrove
Kadar Logam Berat Timbal (Pb) ppm Kadar Logam Berat Merkuri (Hg) ppm Hari-0
(Aklimatisasi) Minggu-5
Hari-0
(Aklimatisasi) Minggu-5
Media Media Akar Media Media Akar
Avicennia Marina 10,4 3,31 5,42 27,412 4,72 13,83
Rhizophora
Mucronata 10,4 2,92 5,19 27,412 7,61 13,82
Bruguiera Gimnorhiza 10,4 3,76 4,22 27,412 5,97 11,00
Sumber : Hasil Pengamatan
Pada tabel 4.1, media tanam telah mengandung kadar logam berat timbal
(Pb) sebesar 10,4 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar 27,412 dari hari-0
(Aklimatisasi). Setelah proses aklimatisasi selesai dengan ditandainya
pertumbuhan tunas maka penelitian berjalan dengan penambahan konsentrasi
logam berat timbal (Pb) sebesar 50 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar
150 ppm pada media tanam di minggu-1.
Pada tabel 4.1, kandungan logam berat yang terdapat pada
masing-masing bak telah jauh berkurang dengan jangka waktu 5 minggu. Akar
mangrove jenis Avicennia marina mampu mengakumulasi logam berat merkuri
(Hg) paling tinggi sebesar 13,83 ppm sedangkan untuk logam berat timbal (Pb)
sebesar 5,42 ppm. Hal tersebut membuktikan bahwa perlakuan yang diterapkan
pada tanaman membuat akar mangrove mampu menyerap logam berat yang
Gambar 4.1. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Media (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove
Dari gambar 4.1, mununjukan penurunan kadar logam berat merkuri (Hg)
pada media dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 dengan pemaparan
150 ppm, secara berturut-turut pada jenis mangrove Avicennia Marina sebesar
98,20 ppm, 57,98 ppm, 38,91 ppm, 28,83 ppm, 28,21 ppm; jenis mangrove
Rhizophora Mucronata sebesar 102,93 ppm, 48,02 ppm, 23,46 ppm, 11,72
ppm, 6,35 ppm; dan jenis mangrove Bruguiera Gymnorrhiza sebesar 118,44
ppm, 61,79 ppm, 42,66 ppm, 21,07 ppm, 10,09 ppm.
Dari hasil analisa mununjukan bahwa penurunan kandungn logam berat
merkuri (Hg) pada media yang paling rendah berada pada minggu ke-5 dengan
pemaparan 150 ppm secara berturut-turut pada masing-masing media tanam
yang ditanami jenis mangrove Rhizophora Mucronata, Bruguiera
Gymnorrhiza, dan Avicennia Marina dengan hasil berturut-turut sebesar 6,35
Ternyata perlakuan pada tanaman mangrove tersebut mampu
menurunkan kadar logam berat merkuri (Hg) pada masing-masing media
tanam.
Gambar 4.2. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Media (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove
Pada gambar 4.2 diatas tidak jauh beda dengan hasil kandungan logam
berat timbal (Pb) dalam media tanam, hal ini dikarenakan akar merupakan
organ tanaman yang kontak langsung dengan media tanam dan sekaligus
berfungsi menyerap unsur hara kemudian ditranslokasikan ke bagian organ
lain. Maka semakin lama pemaparan semakin banyak pula logam berat yang
diakumulasi oleh akar tumbuhan mangrove tersebut.
Dari gambar 4.2, mununjukan penurunan kadar logam berat timbal (Pb)
pada media dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 dengan pemaparan
50 ppm, secara berturut-turut pada jenis mangrove Avicennia Marina sebesar
29,58 ppm, 24,36 ppm, 15,35 ppm, 5,08 ppm, 4,16 ppm; jenis mangrove
Rhizophora Mucronata sebesar 30,26 ppm, 24,38 ppm, 17,52 ppm, 9,92 ppm,
5,01 ppm; dan jenis mangrove Bruguiera Gymnorrhiza sebesar 39,02 ppm,
30,92 ppm, 28,38 ppm, 19,58 ppm, 7,60 ppm.
Penurunan kadar logam berat timbal (Pb) pada media yang paling rendah
berada pada minggu ke-5 dengan pemaparan 50 ppm secara berturut-turut pada
masing-masing media tanam yang ditanami tumbuhan jenis mangrove
Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan Bruguiera gymnorrhiza dengan
hasil berturut-turut sebesar 4,16 ppm, 5,01 ppm, dan 7,60 ppm.
Gambar 4.3. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Akar (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove
Berdasarkan gambar 4.3, proses penyerapan logam berat merkuri (Hg)
pada akar tanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata dan Bruguiera
gymnorhiza mengalami peningkatan akumulasi dari minggu ke-1 sampai
dengan minggu ke-5 dengan hasil berturut-turut 37,07 ppm, 57,28 ppm, 80,24
ppm, 88,23 ppm, 92, 47 ppm; dan 15,58 ppm, 29,69 ppm, 48,49 ppm, 68,96
ppm, 80,44 ppm. Sedangkan pada tanaman mangrove jenis Avicennia marina
mengalami peningkatan akumulasi logam berat merkuri (Hg) dari minggu ke-1
sampai dengan minggu ke-3 secara berturut-turut sebesar 36,08 ppm, 67,19
ppm, 83,83 ppm. Sedangkan pada minggu ke-4 mengalami penurunan kadar
logam berat sebesar 7,89 ppm yaitu 75,95 ppm. Hal ini bisa terjadi dikarenakan
akar tanaman mangrove mengalami stres atau jenuh sehingga penyerapan
logam berat merkuri (Hg) tidak maksimal sedangkan transport tetap
berlangsung ke batang dan daun. Pada minggu ke-5 akumulasi logam berat
hanya meningkat menjadi 76,92 ppm. Peningkatan penyerapan logam berat
dari minggu ke-4 menuju minggu ke-5 sangat kecil, kemungkinan tanaman
telah terkena dampak toksik dari konsentrasi logam berat yang tinggi sehingga
mengganggu proses penyerapan pada akar.
Pada gambar 4.3, hasil analisa diatas menunjukan bahwa penyerapan
logam berat merkuri (Hg) pada akar mangrove yang tertinggi berada pada
pemaparan logam berat minggu ke-5 secara berturut-turut pada jenis mangrove
Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza, dan Avicennia marina dengan
hasil berturut-turut sebesar 92,47 ppm, 80,44 ppm, dan 76,92 ppm. Maka
tumbuhan mangrove yang mampu menyerap logam berat merkuri (Hg) paling
tinggi terdapat pada akar tumbuhan mangrove jenis Rhizophora mucronata
Gambar 4.4. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Media (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove
Berdasarkan gambar 4.4, kandungan logam berat timbal (Pb) yang
terakumulasi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 secara
berturut-turut pada jenis mangrove Avicennia Marina sebesar 11,84 ppm, 17,57 ppm,
27,51 ppm, 30,42 ppm, 31,45 ppm; jenis mangrove Rhizophora Mucronata
sebesar 10,86 ppm, 11,58 ppm, 22,61 ppm, 27,17 ppm, 29,65 ppm; dan jenis
mangrove Bruguiera Gymnorrhiza sebesar 5,20 ppm, 6,80 ppm, 10,66 ppm,
13,30 ppm, 17,04 ppm.
Pada gambar 4.4, hasil analisa diatas menunjukan bahwa penyerapan
logam berat timbal (Pb) pada akar mangrove yang tertinggi berada pada
pemaparan logam berat minggu ke-5 secara berturut-turut pada mangrove jenis
Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan Bruguiera gymnorrhiza dengan
hasil berturut-turut sebesar 31,45 ppm, 29,65 ppm, dan 17,04 ppm. Maka
tumbuhan mangrove yang menyerap logam berat timbal (Pb) paling tinggi
terdapat pada akar tumbuhan mangrove jenis Avicennia marina sebesar 31,45
ppm pada minggu ke-5.
IV.3. Pengolahan Data Statistik Analisa Regrasi Ganda
Data yang diolah dalam Statistik Analisa Regresi Ganda ini didapatkan
dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
Berikut hasil dari kandungan logam berat Pb pada media dan
Akumulasi Akar mangrove Avicennia Marina adalah sebagai berikut :
Descriptive Statistics
Mean
Std.
Deviation N
Waktu Pemaparan (minggu ke-) 3.00 1.581 5
Konsentrasi Logam Berat Pb pada Media 60.4000 .00000 5
Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada
Akar 23.7580 8.63071 5
Kandungan Logam Berat Pb pada Media Tanam 15.7060 11.33279 5
Tabel di atas menunjukan rata-rata waktu pemaparan sebesar 3.00
dengan standart atau batas kesalahan dalam penelitian data adalah 1.581;
rata-rata konsentrasi logam berat Pb pada media 60.4 dengan standart devisiansinya
adalah 0; rata-rata akumulasi penyarapan logam berat Pb pada akar 23.7580
dengan standart devisiansinya sebesar 8.63071; dan rata-rata kandungan logam
berat Pb pada media tanam 15.706 dengan standart devisiansinya sebesar
Tabel diatas menunjukkan metode yang digunakan adalah metode enter yaitu
dengan memasukkan atau memilih variabel dependen dalam persamaan.
Model Summaryb
a. Predictors: (Constant), Kandungan Logam Berat Pb pada Media Tanam, Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada Akar
b. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)
Untuk table di atas R menunjukkan hubungan antar variabel sebesar
0.978 sehinggan bisa dinyatakan hubungan yang terjadi cukup kuat. Sedangkan
R square adalah koefisien determinasi menunjukkan bahwa kandungan logam
berat pada media 0.95 atau 95% dan sisanya dipengaruhi oleh fariabel lain
sebesar 5%.
Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered
Variables
Removed Method
1 Kandungan Logam
Berat Pb pada Media Tanam, Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada Akara
. Enter
a. All requested variables entered.
ANOVAb
a. Predictors: (Constant), Kandungan Logam Berat Pb pada Media Tanam, Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada Akar
b. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)
Uji anova ditunjukkan untuk mengetahui variabel independent secara
keseluruhan terhadap variabel dipenden. Df menunjukkan derajat kebebasan
dengan nilai V1 = 2 dan V2 = 2 pada taraf sionifikasi 0.43. Nilai variabel
dipenden yang disesuaikan sebesar 0.915.
Coefficientsa
a. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)
Tabel ini untuk menguji signivikansi koefisien variabel pada model linier. B
menujukkan koefisien regresi Y = ax2 + bx + c artinya Y = 0.679x2 + 0.013 +
Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean
Std.
Deviation N
Predicted Value 1.08 4.56 3.00 1.547 5
Residual -.435 .435 .000 .326 5
Std. Predicted
Value -1.238 1.011 .000 1.000 5
Std. Residual -.942 .943 .000 .707 5
a. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)
Tabel ini merupakan tabel penyimpan harga residual untuk masing-masing
model dan menyimpan harga-harga prediksi untuk masing-masing model yang
dipilih.
Grafik diatas menunjukkan validitas data dan hasil penelitian yang
dilakukan adalah benar. Hal ini dapat dilihat dari posisis titik-titik yang
mendekati garis grafik. Dengan demikian data dan penelitian yang ada sudah
Correlations
Sig. (1-tailed) Waktu Pemaparan
(minggu ke-) . .000 .006 .002
N Waktu Pemaparan
Diperoleh nilai korelasi antara waktu pemaparan dan kandungan logam
berat Pb pada media tanam sebesar -0.978 untuk signivikansinya 0.002; nilai
korelasi antara waktu pemaparan dan kandungan logam berat Pb pada akar
0.954 untuk signivikansinya 0.006; dan nilai korelasi antara akumulasi
penyerapan logam berat Pb pada akar dan kandungan logam berat Pb pada
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Tanaman mangrove jenis Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan
Bruguiera gymnorrhiza mampu menyerap logam berat timbal (Pb) dan merkuri
(Hg).
2. Tanaman mangrove jenis Avicennia marina mampu menyerap logam berat
timbal (Pb) paling tinggi sebesar 31,45 ppm, sedangkan mangrove jenis
Rhizophora mucronata mampu menyerap logam berat merkuri (Hg) paling
tinggi sebesar 92,47 ppm terdapat pada minggu ke-5.
V.2. Saran
Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perlu pangamatan batang dan daun untuk penelitian salanjutnya.
2. Dengan terbuktinya tumbuhan mangrove jenis Avicennia Marina dan
Rhizophora Mucronata dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) dan
merkuri (Hg) paling tinggi, seharusnya konservasi mangrove jenis tersebut
lebih digalakkan pada perairan yang tercemar oleh logam berat.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2001, “Mangrove Jenis Api-api (Avicennia marina) Alternatif
Pengendalian Logam Berat Pesisir”, URL:http://www.terranet.com, 24
November 2009
Anonim, 2006, ”Pengaruh logam berat terhadap tumbuhan”,
URL:http://www.pdfqueen.com, 24 November 2009
Anonim, 2007, ”Dampak logam berat”, URL:http://www.Andiar_08.com, 24
November 2009
Anonim, 2009,“Akumulasi logam berat tembaga (Cu) dan timbal (Pb) pada
pohon avicennia marina di hutan
mangrove”URL:http://library.usu.ac.id, 23 Maret 2010
Anonim, 2009, ”Ekosistem mangrove”,
URLhttp://perikananunila.wordpress.com, 11 Juli 2010
Anonim, 2009, ”Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove”,
URL:http:// www. Acehpedia.org/, 24 November 2009
Anonim, 2009, ”Hutan bakau”, URL:http://id.Wikipedia.org, 24 November
2009
Anonim, 2010, ”Logam berat (heavy metal)”, URL:http://www.icempo.com,
16 Maret 2010
Firlianasari, F. 2002. Studi Literatur Dampak Merkuri Serta
Penanggulangannya. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Lingkungan. ITS.
Panjaitan, G.C. 2009. Akumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) dan Timbal (Pb)
pada Pohon Avicennia Marina Di Hitan Mangrove. Skripsi. Jurusan
Budaya Hutan. Universitas Sumatera Utara. Medan
Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No: