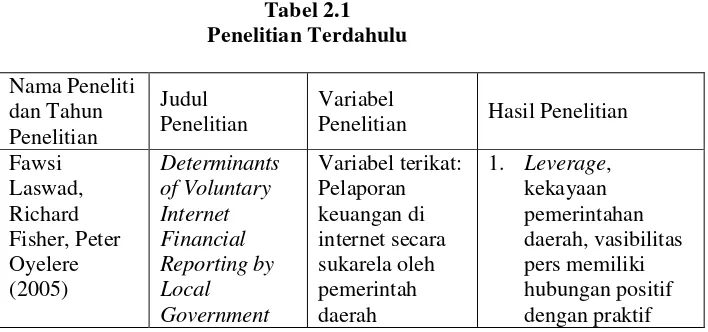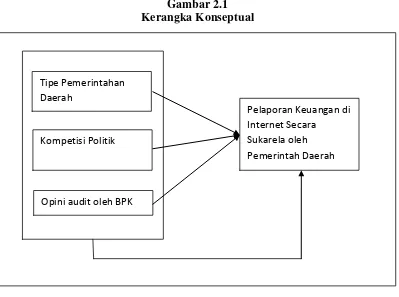BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1 Pemerintahan Daerah di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dituliskan bahwa pemerintahan
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia terbagi atas
pemerintahan daerah provinsi dimana setiap pemerintahan darah provinsi
dibagi lagi atas pemerintahan daerah kota dan pemerintahan daerah
kabupaten. Setiap pemerintahan daerah memiliki kepala daerah
masing-masing dan penyelenggaraannya diatur dalam undang-undang.
Yang termasuk ke dalam pemerintah daerah adalah kepala daerah
beserta perangkat daerah di dalamnya. Daerah provinsi dipimpin oleh
Gubernur, daerah kota dipimpin oleh Walikota, dan daerah kabupaten
dipimpin oleh Bupati. Kepala daerah berperan sebagai badan eksekutif.
Hal itu tertuang di dalam UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
menyusun dan menyampaikan anggaran untuk mendapatkan persetujuan,
kemudian melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
setelah mendapatkan persetujuan. Hal tersebut juga ditegaskan di dalam
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
pemegang kekuasaan pengelolaan keuanga daerah adalah kepala daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Semenjak UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
diberlakukan, pemilihan kepala daerah lebih bersifat demokrasi. Pilkada
dilakukan secara langsung dimana terbuka kesempatan bagi calon
independen/nonparpol untuk maju mengikuti pilkada. Proses penyaringan bakal calon dilaksanakan secara terbuka dengan mewajibkan tiap
parpol/gabungan parpol mengumumkan proses dan hasil penyeleksian
kepada masyarakat. Kewenangan politik yang dulu ada pada DPRD untuk
memilih kepala daerah kini telah diserahkan kepada rakyat untuk memilih
langsung dengan mekanisme yang telah diatur.
Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
dikatakan bahwa pemerintah daerah melaksanakan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk
melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang berdampak
Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan keberagaman
dan kekhususan daerah serta dilaksanakan secara adil dan selaras dengan
undang-undang.
2.1.2 Tipe Pemerintahan Daerah
Tipe pemerintahan daerah dalam penelitian ini terbagi atas
pemerintahan daerah provinsi dimana setiap pemerintahan darah provinsi
dibagi lagi atas pemerintahan daerah kota dan pemerintahan daerah
kabupaten. Daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur, daerah kota dipimpin
oleh Walikota, dan daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati. Kepala daerah
berperan sebagai badan eksekutif.
Dalam UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 14, kepala daerah menyusun dan
menyampaikan anggaran untuk mendapatkan persetujuan, kemudian
melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah
mendapatkan persetujuan. Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan, bahwa pemegang
kekuasaan pengelolaan keuanga daerah adalah kepala daerah yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.
Penduduk di pemerintah kabupaten pada umumnya melakukan
urbanisasi. Menurut Ingram (1984) dalam Laswad, dkk (2005), urbanisasi
sehingga kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk
memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan
wilayah metropolitan yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar
dibandingkan dengan wilayah desa yang memiliki jumlah penduduk relatif
kecil. Hal tersebut berarti di wilayah metropolitan yang memiliki jumlah
penduduk yang lebih besar akan meyebabkan tingkat pemantauan yang
lebih tinggi sebagai akibat dari terbentuknya koalisi hasil dari urbanisasi
yang terjadi. Oleh karena itu kepala pemerintahan daerah akan lebih
memilih untuk melakukan pelaporan keuangan di internet di wilayah
metropolitan yang memiliki jumlah penduduk yang relative besar
dibandingkan dengan di wilayah desa yang memiliki jumlah penduduk
yang relatif kecil.
2.1.3 Kompetisi Politik
Menurut Bardhan dan Yang (2004) kompetisi politik adalah
kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan
dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan politik
dan kepentingan masyarakat. Menurut Downs (1957), kompetisi politik
diartikan sebagai kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara
terbanyak dari pemilih untuk menjalankan suatu platform kebijakan yang layak dijalankan. Olson (2000) menunjukkan bahwa kompetisi politik
akan mempengaruhi cara pemerintah mengelola ekonomi. Kompetisi
politik akan mendorong penguasa untuk mengalokasikan sumberdaya ke
masyarakat. Semakin tinggi kompetisi yang dihadapi penguasa, maka
penguasa akan mengarahkan manfaat dari pengalokasian sumberdaya
kepada perwakilan masyarakat yang terpenting.
Semakin besar kompetisi politik suatu pemerintahan daerah maka
akan semakin besar kecenderungan kepala daerah untuk menyediakan
informasi (Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005) karena akan
menanggung biaya pengawasan yang lebih besar dari saingan politiknya.
Salah satu cara penyediaan informasi yang dapat dilakukan adalah
menggunakan internet sebagai media pelaporan keuangan. Oleh karena itu
daerah yang memiliki kompetisi politik yang tinggi akan memiliki
kecendrungan untuk melakukan pelaporan keuangan di internet sebagai
akibat pemantauan yang tinggi oleh para pesaing politiknya dibandingkan
dengan daerah yang memiliki kompetisi politik yang rendah.
2.1.4 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan
informasi keuangan. Pelaporan keuangan lebih luas dari pada laporan
keuangan (Bastian, 2006). Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses
akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan
disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial
Negara.
Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh febriyanty (2011),
dicantumkan bahwa informasi keuangan yang dibutuhkan berdasarkan
perencanaan dan penganggaran. Informasi tersebut dapat dilihat dari
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Dari semua peraturan dan ketentuan tentang pelaporan keuangan
daerah, tidak ada satupun yang mengatur mengenai media yang digunakan
untuk penyebaran informasi keuangan pemerintahan daerah. Meskipun
begitu, pemerintah daerah dapat menyediakan informasi keuangan oleh
karena pemerintah daerah beranggapan bahwa informasi tersebut dapat
berguna bagi pihak luar dan mengungkapkannya dengan sukarela. Bila
suatu pemerintahan daerah melakukan pelaporan keuangan di internet, hal
tersebut merupakan suatu bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan
secara sukarela, bukan karena untuk memenuhi tuntutan undang-undang
maupun peraturan yang lainnya.
APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintahan
daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Setiap
pemerintahan daerah berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan
laporan keuangan dan laporan kinerja guna pertanggungjawaban terhadap
pelaksanaan APBD. Di dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang keuangan daerah dijelaskan bahwa APBD terdiri atas
anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan
daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan
fungsi, dan jenis belanja. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit,
ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut
dalam peraturan daerah tentang APBD. Dalam hal perkiraan
surplus,ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah
tentang APBD.
Fungsi APBD sesuai dengan yang tertuang di dalam Permendagri
No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara,
yaitu :
1. Fungsi otorisasi, berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan
2. Fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada
tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran daerah menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketetentua yang yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa aggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran
dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perkonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran
6. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintahan daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.
Menurut Mardiasmo (2002), proses penyusunan anggaran memiliki
tujuan sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan
koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan
barang dan jasa publik dalam proses pemroritasan
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
4. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada
masyarakat luas
Sesuai dengan Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi
Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan
merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan
umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara
spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya, dengan :
1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan
prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk
memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang
berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang
berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan
keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
b. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh
DPR/DPRD.
Komponen-komponen yang terdapat di dalam satu set laporan
keuangan pokok adalah :
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi anggaran berisi ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya
dalam satu periode pelaporan.
b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah
mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu.
c. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam satu periode, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran,
neraca, dan laporan arus kas.
Sebagai dampak dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7
pemerintah, termasuk kepala daerah, untuk melaksanakan akuntabilitas
kinerja intansi pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan
pemerintahan yang bertanggung jawab, maka disusunlah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP berisi informasi tentang
uraian daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka
pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang
dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan. Laporan ini juga
memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan
hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan
dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.
Penyusunan LAKIP berpedoman kepada Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003. Dalam
penelitian Solikin (2006) dijelaskan bahwa pada keputusan tersebut
dijelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan
cara mencapai sasaran tersebut dalam bentuk uraian kebijakan dan
program. Dalam LAKIP terdapat dua formulir untuk mengukur kinerja,
yaitu formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir
Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPS).
LAKIP memiliki dua bagian akuntabilitas kinerja, yaitu
akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kinerja
meliputi evaluasi dan analisis kinerja kegiatan serta evaluasi dan analisis
sumber pembiayaan serta realisasi anggaran untuk membiayai program
dan kegiatan, termasuk penjelasan tentang efisiensi.
Selain Instruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 mengenai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP juga
memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1.5 Opini Audit oleh BPK
Pada awal perkembangannya auditing hanya dimaksudkan untuk
mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian
berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan
pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga
menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan.
Menurut Arens and Loebbecke (Auditing: An Integrated Approach, eight edition, 2000:9), Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan
melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah
ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan
independent.
mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan
dan kejadian ekonomi dengan tujuan umtuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.
Menurut William F. Meisser, Jr (Auditing and Assurance Service, A Systematic Approach, 2003:8) audit adalah proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan
kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut
dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.
Menurut Sukrisno Agoes (2004), ditinjau dari luasnya
pemeriksaan, maka
1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini
mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap
bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan
Orang yang melakukan audit disebut dengan auditor. Arens &
Loebbecke dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu yang diadaptasi
oleh Amir Abadi Jusuf menggolongkan auditor menjadi beberapa
golongan, yaitu :
1. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit
atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor
pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu :
a. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasa 23E
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.. ayat (2) Hasil
pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan
DPRD sesuai dengan kewenangannya. BPK merupakan badan
yang tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat
bersikap independen.
b. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan
oleh BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan
Pengawas Daerah.
2. Auditor Intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan
tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen
perusahaan tempat dimana ia bekerja.
3. Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsi
pengauditan atas Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan
yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan
kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba.
Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu KAP.
4. Auditor Pajak, Direktoral Jenderal Pajak yang berada dibawah
Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggungjawab atas
penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum
dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP di
lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak.
Hasil akhir dari audit adalah adanya laporan audit yang berupa
opini audit. Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007)
adalah laporan yang diberikan seorang akuntan public terdaftar sebagai
hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan
perusahaan.
Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini
audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang
menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau
aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran
melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan
kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang
diauditnya.
Opini audit menurut Standar Profesional Akuntan (PSA29) terbagi
atas 5 jenis, yaitu:
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan
sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan
kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak
terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk
laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:
a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan
auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia
dapaty memastikan kerja lapangan telah ditaati.
b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan
kerja.
c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan
pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian
pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki
d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material
uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang
tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara
memuaskan.
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
(Modified Unqualified Opinion)
Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang
tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu
dapat terjadi apabila:
a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor
independen lain.’
b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan
dibuat menyimpang dari SAK.
c. Laporan dipengaruhi oleh ketidak[pastian peristiwa masa yang
akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal
laporan audit.
d. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
e. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material
dalam penerapan prinsip akuntansi.
f. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan
wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/
kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari
pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:
a. Bukti kurang cukup
b. Adanya pembatasan ruang lingkup
c. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang
berlaku umum (SAK).
Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini
diberikan apabila:
1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan
lingkup audit yang material tetapi tidak m,empengaruhi laporan
keuangan secara keseluruhan.
2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari
prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi
tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak
4. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan
ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tyambahan paragraf untuk
menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan
dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.
5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion)
Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan
yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai
dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya
auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh
klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.
Sementara pada prakteknya dalam audit laporan keuangan pemda
opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak
Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan
yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Semakin tinggi penyimpangan dalam laporan keuangan pemda
akan mendorong pemda untuk menutupi informasi yang dimiliki, sehingga
tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi rendah (Handayani,
2.1.6 Pelaporan Keuangan di Internet
Pelaporan keuangan di internet merupakan bentuk pelaporan yang
dilakukan secara suakrela (voluntary disclosure). Terdapat tiga cara penyajian laporan keuangan melalui website, yaitu :
1. Membuat duplikat laporan keuangan yang sudah dicetak ke dalam
format electronic paper.
2. Mengkonversi laporan keuangan ke dalam format HTML
(Hypertext Markup Language)
3. Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui website
sehingga lebih mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan
daripada laporan keuangan dalam format cetak.
Menurut Styles dan Tennyson (2007), suatu cara yang mungkin
paling nyaman dan cost effective bagi pihak pemerintahan untuk menyebarkan informasi di zaman sekarang adalah dengan menggunakan
internet. Hal tersebut sudah menjadi perhatian dari Governance Finance Officers Associatiton (GFOA) di Amerika Serikat. GFOA meyakini banyak manfaat dari publikasi dengan menggunakan media internet, antara
lain:
1. Meningkatkan kepedulian terhadap dokumen. Pemerintah daerah akan
sangat peduli terhadap dokumen-dokumen daerah karena
sewaktu-waktu dokumen tersebut harus dapat dipublikasikan
yang penting bagi partisipasi stakeholders dalam proses penganggaran pemerintahan dan demonstrasi akuntabilitas keuangan(GFOA, 2003).
Internet menyediakan kesempatan yang relatif mudah dan cost effective untuk menyediakan informasi keuangan bagi semua stakeholder (Lavigne, 2002 dalam Styles dan Tennyson, 2007).
3. Merupakan alat analisis yang lebih mudah untuk diaplikasikan.
Informasi keuangan yang disediakan di internet dalam format
elektronik seperti berkas kertas kerja (spreadsheet) atau eXtensible Financial Reporting Markup Language (XFRML) memungkinkan pengguna untu lebih mudah dan lebih luas dalam menganalisis data
keuangan (Lymer, dkk 1999; Trites 1999; FASB,2000 dalam Styles
dan Tennyson, 2007).
4. Mencegah kelebihan pengungkapan dan menghemat biaya publikasi.
Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa informasi keuangan
yang dipublikasikan secara elektronik dapat menjangkau lebih banyak
pengguna namun tidak meningkatkan biaya cetak dan distribusi.
2.1.7 Teori Legitimasi
Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara
berkesinambungan mencari cara untuk meyakinkan bahwa organisasi
tersebut beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang ada
dalam masyarakat, dengan begitu organisasi tersebut berusaha meyakinkan
bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dipedulikan oleh
atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Asforth dan
Gibs, 1990 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Legitimasi organisasi dapat
dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan
sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (Ghozali
dan Chariri,2007).
Menurut Deegan (2000), teori legitimasi meyakinkan suatu
gagasan bahwa terdapat “kontrak sosial” antara orgasiasi dengan
lingkungan tempat organisasi beroperasi. Konsep “kontrak sosial”
digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang
seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan
masyarakat tersebut dapat bersifat eksplisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit
dari kontrak social tersebut adalah persyaratan legal, sementara bentuk
implicit dari kontrak social tersebut adalah harapan masyarakat yang tidak
tercantum dalam peraturan legal. Teori legitimasi menganjurkan organisasi
untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja organisasi tersebut dapat
diterima oleh masyarakat.
Demikian halnya dengan pemerintahan daerah. Dewasa ini, seiring
dengan adanya jaminan akan demokrasi pasca reformasi, masyarakat
menjadi semakin kritis dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk memiliki pemerintahan
yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah.
Seiring dengan harapan masyarakat yang berubah, pemerintah daerah juga
apabila dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan yang menjadi
perhatian (Deegan, 2000).
Untuk memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang
bersih, pemerintah daerah dapat melakukan pelaporan keuangan di internet
secara sukarela. Pelaporan keuangan di internet secara sukarela merupakan
suatu bentuk publikasi infrormasi keuangan yang mengandung nilai
akuntabilitas serta merupakan wujud transparansi atas pengelolaan
keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Cara ini dianggap tepat karena
menurut (Dowling dan Prefer dalam Deegan, 2000) strategi yang dapat
dilakukan untuk melegitimasi aktivitas suatu organisasi adalah dengan
strategi komunikasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hurst (1970)
dalam Deegan (2000) bahwa laporan akuntansi dapat menjadi alat
melegitimasi keberadaan suatu organisasi.
Menurut Deegan (2000), organisasi harus dapat beradaptasi dengan
harapan masyarakat jika ingin sukses. Dengan memenuhi harapan
masyarakat, aktivitas dan kinerja pemerintah daerah dapat diterima oleh
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan cenderung untuk
melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela dengan tujuan
untuk dapat memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan daerah
2.1.8 Teori Signalling
Teori signaling menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang
baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja
pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan
baik (Puspita dan Martani, 2012). Pemda akan berusaha melakukan
pelaporan keuangan di internet secara lebih optimal untuk menunjukkan
bahwa pemda telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat
(Puspita dan Martani, 2012). Masyarakat juga dapat dengan mudah dan
cepat mengakses informasi keuangan terkait penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi.
2.2 Penelitian Terdahulu
Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memeriksa pelaporan
keuangan di internet pada organisasi-organisasi laba, namun hanya sedikit
penelitian dengan topik yang sama yang dilakukan di institusi
pemerintahan (Laswad, dkk 2005 dan Styles dan Tennyson, 2007).
Berikut ini merupakan penelitian terdahulu :
Tabel 2.1
Penelitian Hasil Penelitian
Authorities Variabel bebas:
IFR. Tipe council berhubungan negative dengan praktif IFR. 2. Hubungan positif
antara praktik IFR dengan kompetisi politik dan ukuran tidak didukung.
2. Aksesbilitas data keuangan di kota serta kualitas pelaporan
1. Tipe pemerintahan daerah
internet secara
2. Kompetisi politik dan leverage tidak berpengaruh bahwa ukuran dan kekayaan
Variabel terikat Reporting Index Variabel bebas Size, Leverage, Capital
1. Size, Leverage, Capital Investment, Political
Competition berpengaruh positif, 2. Press Visibility
berpengaruh
1. Jumlah penduduk, tingkat investasi, kekayaan daerah dan press visibility berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah 2. Kompetisi politik
daerah, dan 3. Leverage tidak
berpengaruh terhadap
ketersediaan IKD 4. Ukuran pemerintah
dan kompleksitas berpengaruh positif signifikan terhadap aksesbilitas IKD 5. Leverage dan
pendapata perkapita berpengaruh negative terhadap aksesbilitas IKD 6. Rasio kemandirian
tidak berpengaruh 2. local government
government type
1. kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, leverage, dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif 2. tipe pemerintah
daerah dan opini audit tidak berpengaruh
2.3 Kerangka konseptual
Masyarakat sekarang ini lebih peka terhadap pemerintahan daerah
terutama pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat memiliki harapan akan suatu
pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang menandakan
terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Terdapat beberapa
sumber yang mengatakan manfaat internet apabila digunakan sebagai media
pelaporan keuangan. Menurut Bertot, dkk (2010), penggunaan internet dapat
menciptakan budaya transparansi yang juga akan mewujudkan akuntabilitas.
Pengungkapan secara sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet
dinilai efisien (Woldenberg, 2004 dalam Bertot, dkk 2010) dan efektif
meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari
tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dinilai dapat menjadi solusi atas harapan masyarakat akan terselenggaranya
pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Namun pada kenyataannya, hanya ada beberapa pemerintah daerah yang
secara sukarela memanfaatkan internet sebagai media dalam malakukan pelaporan
keuangannya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pemerintahan
daerah yang melakukan dan tidak melakukan pelaporan keuangan di internet
secara sukarela serta mengetahui karakteristik tertentu yang mempengaruhinya.
Sehingga, dapat dianalisis alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan
melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela
berhubung internet dinilai sebagai media yang efektif dan efisien dalam pelaporan
keuangan yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
daerah.
Penelitian ini menganalisis pengaruh tipe pemerintah daerah, kompetisi
politik, dan opini audit terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela
oleh pemerintah daerah. Penduduk di pemerintah kabupaten pada umumnya
melakukan urbanisasi. Menurut Ingram (1984) dalam Laswad, dkk (2005),
urbanisasi membantu pembentukan koalisi, yaitu gabungan pemilih individu,
sehingga kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk memberikan
informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan
yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah
desa yang memiliki jumlah penduduk relatif kecil. Ditambah lagi, pemakaian dan
akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut
banyak dipraktikkan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota
dibandingkan pemerintahan kabupaten. Dengan demikian, tipe pemerintahan
kabupaten mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara
sukarela oleh pemerintahan daerah.
Faktor terakhir dalam penelitian ini adalah kompetisi politik. Semakin
besar kompetisi politik suatu pemerintahan daerah maka akan semakin besar
kecenderungan kepala daerah untuk menyediakan informasi (Baber, 1983 dalam
Laswad, dkk 2005) karena akan menanggung biaya pengawasan yang lebih besar
dari saingan politiknya. Salah satu cara penyediaan informasi yang dapat
dilakukan adalah menggunakan internet sebagai media pelaporan keuangan.
Pemda yang mendapat opini WTP akan cenderung melakukan publikasi
laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan
keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, opini audit
selain WTP dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah
cenderung menutupi informasi keuangannya. Penelitian Handayani (2010)
menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan mempunyai hubungan negatif
signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Semakin tinggi tingkat penyimpangan,
maka pemda cenderung untuk menutupi informasi yang dimiliki, sehingga tingkat
pengungkapan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, opini audit berpengaruh
terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.
Dari uraian di atas, kerangka konseptual mengenai pengaruh ukuran
terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah
dapat digambarkan dalam satu model seperti berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
2.4 Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah Pemilih individu memiliki kemampuan yang terbatas dalam
mengawasi perilaku kepala daerah dan perangkatnya dibandingkan dengan
koalisi pemilih, yaitu kumpulan pemilih individu, yang memiliki
kemampuan lebih besar untuk melakukan pengawasan karena potensi
mereka dalam mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah yang
dilakukan melalui voting (Baber, 1983 dan Ingram, 1984 dalam Laswad,
dkk 2005). Macam-macam dari koalisi pemilih ialah koalisi partai, koalisi Tipe Pemerintahan
Daerah
Kompetisi Politik
Opini audit oleh BPK
Pelaporan Keuangan di Internet Secara
politik, koalisi pekerjaan, dan lainnya. Kepala daerah akan berusaha
mengakomodasi pengawasan yang dilakukan koalisi pemilih dengan cara
menyediakan informasi yang berguna dalam pemantauan dari tindakan
kepala daerah.
Menurut Ingram (1984) dalam Laswad, dkk (2005), urbanisasi
membantu pembentukan koalisi. Dengan demikian, kepala daerah di
daerah tujuan urbanisasi akan memiliki dorongan yang lebih besar dalam
melakukan pelaporan keuangan di internet secara suakrela guna
pemantauan secara proporsional dibandingkan dengan wilayah asal
urbanisasi. Tipe pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan provinsi,
pemerintahan kota, dan pemerintaha kabupaten umumnya memiliki
komposisi penduduk yang berbeda. Penduduk di pemerintahan kabupaten
umumnya melakukan urbanisasi sehingga komposisi penduduk di
pemerintahan kabupaten lebih homogen dibandingkan pemerintahan
provinsi dan pemerintahan kota. Ditambah lagi, berdasarkan laporan
kesenjangan telekomunikasi dan teknologi informasi di Amerika (Juli,
1999) yang dikeluarkan oleh Administrasi Informasi dan Telekomunikasi
Nasional setempat, yang dikutip dalam Laswad, dkk (2005), didapat fakta
bahwa pemakaian dan akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih
tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet
secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan di pemerintahan provinsi
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian
sebagai berikut :
H1 : Tipe pemerintahan kabupaten memiliki pengaruh terhadap
pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah
daerah secara parsial.
2.4.2 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah
Setelah dipilih, politisi biasanya mengabaikan janji-janji pemilu
yang dibuat pada masa sebelum pemilihan. Namun, perilaku ini mungkin
akan berkurang jika ada oposisi yang kuat untuk memantau kelompok
yang ada di pemerintah. Rival politik dalam hal ini akan meminta untuk
menginformasikan opini publik apaun terkait dengan penyimpangan dalam
tindakan pemerintah dari janji-janji pemilu yang dibuat. Oleh karena itu,
pihak oposisi disini berfungsi untuk menahan deviasi kepentingan antara
pemilih dan politikus (Zimmerman, 1997). Akibatnya pihak pemerintah
mungkin akan memilih kebijakan yang sesuai dengan janji ketika pemilu
jika mereka ingin dipilih kembali. Tentu saja dengan tingginya faktor ini
maka hal ini menunjukkan semakin besarnya tingkat persaingan politik
(Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005). Jika pemerintah ingin memenuhi
komitmennya maka pemerintah akan tertarik menggunakan semua media
pelaporan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat (Baber
dan Sen, 1984 dalam Laswad, dkk 2005). Internet menjadi media yang
2005). Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai
berikut :
H2 : Kompetisi politik berpengaruh terhadap pelaporan keuangan
di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara parsial.
2.4.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah
Pemda yang mendapat opini WTP akan cenderung melakukan
publikasi laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan sinyal
kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat
dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, opini audit selain WTP dapat
menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah cenderung
menutupi informasi keuangannya. Penelitian Handayani (2010)
menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan mempunyai hubungan negatif
signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Semakin tinggi tingkat
penyimpangan, maka pemda cenderung untuk menutupi informasi yang
dimiliki, sehingga tingkat pengungkapan menjadi lebih rendah. Maka
dapat disusun hipotesis sebagai berikut :
H3 : Opini audit berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di
2.4.4 Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, dan Opini Audit terhadap Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah
Dari penjelasan secara parsial masing-masing variabel yang telah
diuraikan diatas, maka diduga secara bersama-sama variabel yang diteliti
memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara
sukarela oleh pemerintahan daerah. Maka dapat disusun hipotesis sebagai
berikut :
H4 : Tipe Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, dan Opini
Audit berpengaruh secara simultan terhadap Pelaporan Keuangan