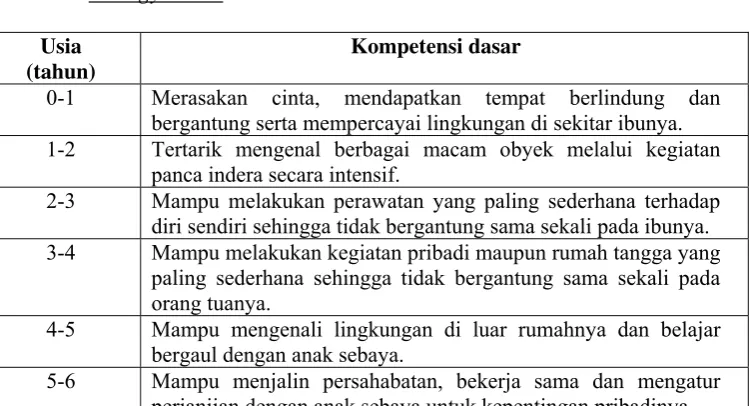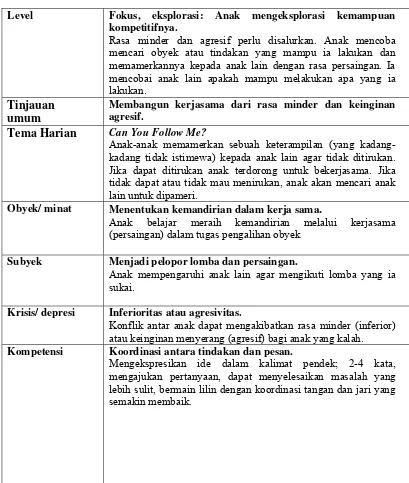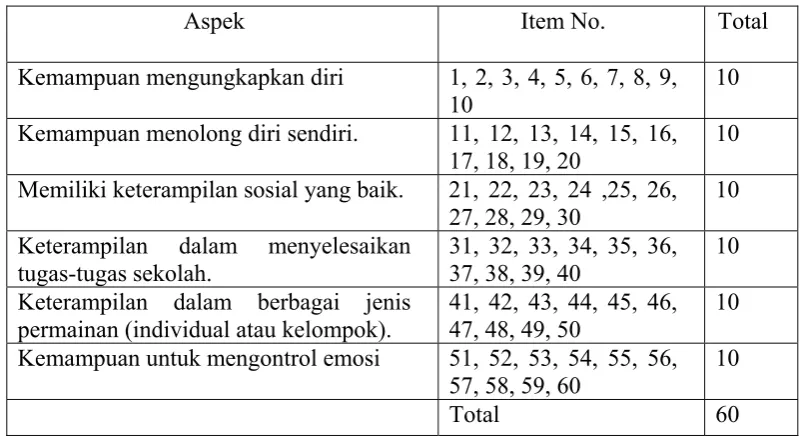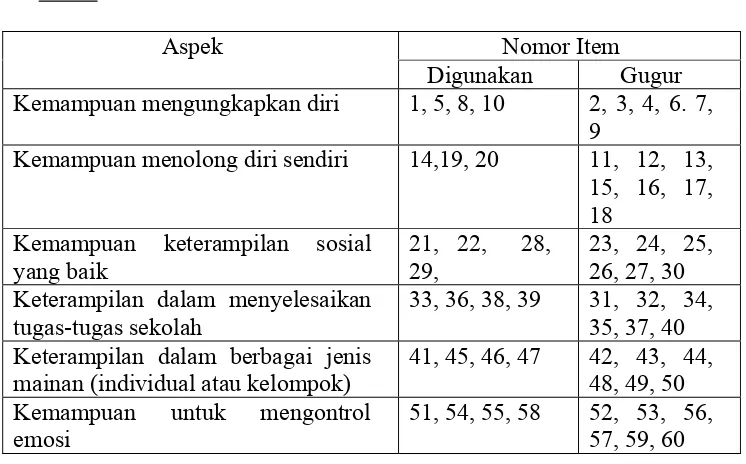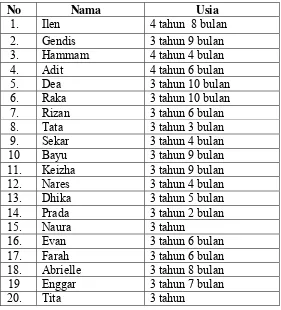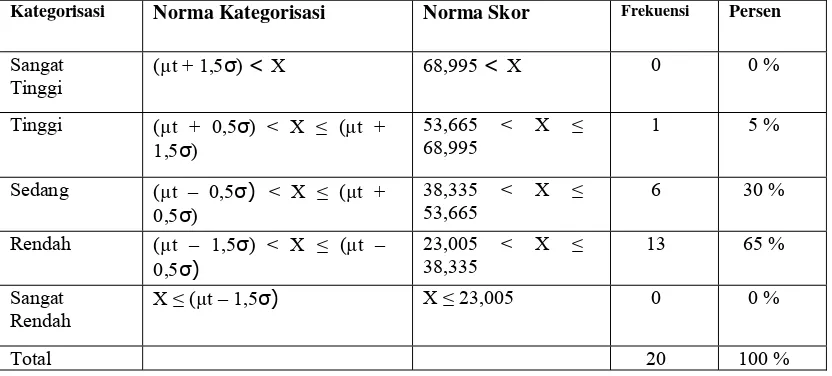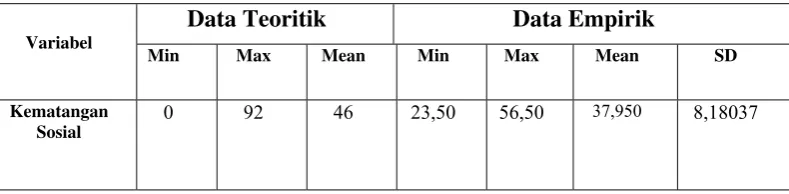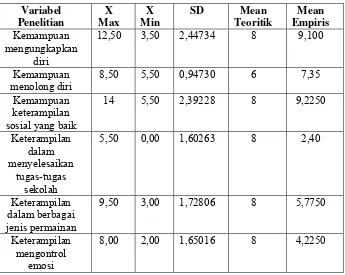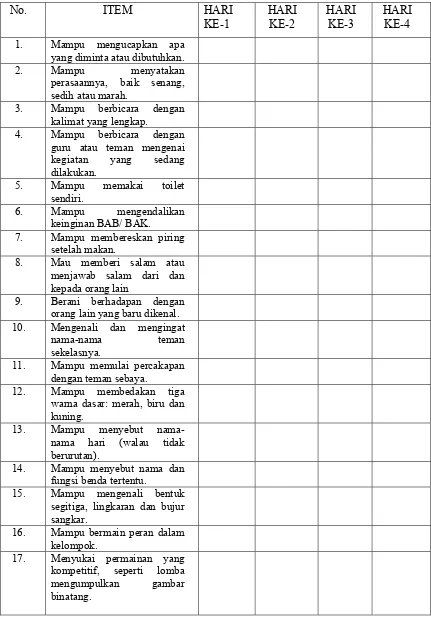STUDI DESKRIPTIF KEMATANGAN SOSIAL ANAK USIA
PRASEKOLAH DI
PLAYGROUP YOGYA KIDS
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi
Oleh : Ignatia Ria Natalia
009114043
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini
tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan
dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.
Yogyakarta, November 2006
Penulis
Matahari tak pernah padam…
Hanya dunialah yang berputar…
Kadang terang, kadang temaram…
ABSTRAK
Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids. Ignatia Ria Natalia
Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kematangan sosial anak usia prasekolah di Playgroup Yogya Kids di Yogyakarta. Kematangan sosial merupakan keadaan anak yang telah memiliki kesiapan untuk menyesuaikan diri pada peraturan serta norma yang ada dalam lingkungannya dan dipengaruhi oleh faktor belajar atau adaptasi sehingga dapat bergaul serta melibatkan diri di dalamnya.
Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah murid-murid Playgroup Yogya Kids sejumlah 20 orang dengan rentang usia 3 sampai lebih kurang 4,5 tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi yang menggunakan alat check list. Observasi dilakukan oleh 2 orang rater untuk mendapatkan hasil yang lebih obyektif. Untuk melihat konsistensi antara rater 1 dan rater 2 dilakukan uji korelasi dengan menggunakan metode Product Moment dari Pearson dan diperoleh hasil rxy=0,802 dengan p=0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada konsistensi antara kedua rater dalam mengamati perilaku anak-anak.
ABSTRACT
Social Maturity of Preschool Ages at Yogya Kids Playgroup Ignatia Ria Natalia
Faculty of Psychology University of Sanata Dharma
The aim of this research was to show the social maturity at Preschool ages at Yogya Kids Playgroup. Social maturity is a condition of children when they are ready to adapt rules exist in the community and able to get involve in the community activities.
The subject of this research were students of Yogya Kids Playgroup with ages range from 3 to approximately 4.5 years old. The method used for this research was descriptive with check list observation data gathering technique. The observation was done by 2 raters to get more objective result. The correlation technique was used to see the consistency of rater 1 and rater 2 was Pearson Product moment Correlation. It would get rxy=0.802 whits p=0.00. This would show us consistency of 2 raters in observasing children behavior.
The result of validity test on social maturity observational items indicated 37 items failed and 23 was used in the research with reliability coefficient
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat yang begitu
melimpah, pertolongan serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
Penulis skripsi berjudul
“
Studi Deskriptif Kematangan Sosial AnakUsia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids, disusun guna melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini
tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Bapak P. Eddy Suhartanto, S. Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma.
2. Ibu Lusia Pratidarmanastiti, M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan sabar membimbing serta
memberi masukan kepada penulis sampai diselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Y. Agung Santoso S. Psi dan Ibu Agnes Indar Etikawati, S. Psi., M. Si., Psi., selaku dosen penguji yang telah memberikan
dukungan dan masukan terhadap kemajuan penelitian saya.
4. Bapak FX. Mudji Trisnowibowo, dan Ibu Lucia Suratmiyati karena
telah menjadi donatur terbesar dalam sejarah pendidikanku, yang tak
pendidikanku dan tetap bangga pada diriku walaupun sering bertanya
“Kamu mau sekolah sampai kapan?” Pak, Bu ini hadiah terbesarku
untuk kalian.
5. Suamiku tercinta, Yoakim Adi Purnianto, yang sudah bersama
penulis selama 6,5 tahun. Terima kasih buat hari-hari indah yang kita
lalui bersama, terima kasih buat pengertian dan cintamu yang luar
biasa sehingga menjadikan penulis selalu bersemangat menggapai hari
depan.
6. Adikku terkasih, Marcellinus Previarinto Nugroho. Terima kasih
buat semua kelucuanmu, keceriaanmu bahkan kenakalanmu yang
membuatku lebih mau mengerti orang lain. Ingat Ri, hidup tak
selamanya indah.
7. Keluarga Yohanes Sutarto; Pakde, Bude, Mbak Yulin, Mas Antok,
Mbah Kakung & Mbah Putri terima kasih telah menjadi keluarga
penulis selama tinggal di Yogyakarta. Terima kasih juga atas segala
fasilitas, dorongan dan cinta kepada penulis.
8. Keluarga besar Yohanes Sunarto di Lembang, terima kasih atas
dukungan, keramahan dan pengertian yang diberikan kepada penulis.
Terima kasih juga telah menerima penulis sebagai anggota keluarga
baru.
9. Para penyemangat jiwa, SEMEDI… :
Putri (terima kasih buat SPSSnya!), Rini (terima kasih buat
lupa tujuan awal kita datang ke Yogya), Icha “Mamih”, Ulin, Vivi
(ayo, ditunggu undangannya). Terima kasih atas hari-hari yang
menakjubkan selama 6 tahun ini; ada tangis, tawa, haru, kekonyolan
dan semua hal aneh yang pernah kita lakukan bersama. Kalian bukan
hanya sahabatku, tapi juga penyemangat jiwaku…
10.Untuk Pangeran para SEMEDI; Ari “Ucup”, Mas Totok, Didi, Mas
Yudi, Jurgen (is that correct, Lin?), Dion, Puspo “Popo”. Terima kasih
sudah menemani Semedi selama berjuang di Yogya dan terima kasih
telah membuat para SEMEDI bahagia.
11.Sahabat para SEMEDI: Ette yang sweet dan Ellen yang ceria (terima
kasih sudah mau direpotkan ya Len), Meta (sudah kepala 2, harus lebih
dewasa lho..), Tessa yang ajaib dan Tante di Warung Rica-Rica, Ridez
juga Kenny, terima kasih untuk kasurnya.
12.Teman- teman kelas A angkatan 2000: Cyria, Ika (terima kasih atas
bantuannya selama ini, sukses terus, Ka!), Niken, Doni “Solo”, Doni
Maradona, Olla, Lintang, Ita, Monic, Anggit, Melanie, Hari, Andre,
Bintoro, Adri, Merdeka, Reni, Pipit, Linggar, Suster dan masih banyak
lagi. Terima kasih buat segala kenangan indah yang pernah kita jalani
bersama, kalian membuat hari-hariku penuh warna. Keep going on,
friends!
13.Teman-teman angkatan ’99: Mbak Onny, Mbak Rani, Mbak Anna,
terima kasih telah banyak membantuku dan membuatku merasa
14.Teman-teman angkatan ’98: Lumowah “Moa” Sebastianus (terima
kasih sudah pernah hadir dan memberi warna pada hidupku), Mas
Radix (maaf kalau salah menulis nama), Mas Dea, Mas Irfan “Ciu”,
Bang Martin, Mas Dili, Mas Lidi, Mbak Kian, Mas Kebo, Mas Anton
“Lampung” dan yang lainnya yang telah banyak membantu penulis
selama menempuh perkuliahan.
15.Teman-teman di TK & Playgroup Yogya Kids. Buat para rekan guru:
Mbak Ella (akhirnya.. S. Psi), Mbak Onny (tetap semangat, Mbak!),
Bu Mamik, Om Lono, Bu Ita (terima kasih buat pengalaman baru), Bu
Lita, dan Om Totok. Terima kasih telah mengajariku untuk menjadi
dewasa. Tidak lupa pula untuk Ibu Selly Sagita, terima kasih untuk
segala kemudahannya.
16. Mas Gandung, Mas Muji, Mas Doni dan Mbak Nanik yang telah
membantu kemudahan administrasi selama penulis menempuh
perkuliahan. Juga untuk special person in Psychology; Pak Gi’ yang
dengan ketulusannya telah membantu penulis dalam banyak hal.
17.Padi, sebagai sumber inspirasi hidup penulis. Terima kasih sudah
menjadi sobat yang paling setia dalam menemani penulis mengerjakan
skripsi, menghibur hati ketika kasih tak sampai, mengingatkan
penulis bahwa selalu ada mahadewi yang menerangi jiwa sehingga
18.Yogyaku, terima kasih atas segala keramahanmu, yang mampu
membantuku menjadi orang yang lebih memaknai hidup. Untukmu
Yogya, sungguh sebuah cinta tanpa akhir…
19.Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
terima kasih banyak atas semuanya.
Semoga Tuhan Yang Maha Kasih akan membalas budi baik anda
sekalian dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap agar skripsi ini
bermanfaat bagi pembaca yang berminat dan dapat juga sebagai bahan bacaan
untuk penelitian selanjutnya.
Akhir kata penulis terbuka atas semua kritik dan saran yang nantinya
akan semakin mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini.
Yogyakarta, November 2006
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL……… i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………. ii
HALAMAN PENGESAHAN………. iii
HALAMAN PERSEMBAHAN……….. iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA……….. v
ABSTRAK………... vi
ABSTRACK………. vii
KATA PENGANTAR……….. viii
DAFTAR ISI………. xiii
DAFTAR TABEL………. xvi
DAFTAR LAMPIRAN………. xvii
BAB I PENDAHULUAN……… 1
A. Latar belakang ……….. 1
B. Rumusan Masalah………. 5
C. Tujuan Penelitian………... 5
D. Manfaat Penelitian………. 6
BAB II LANDASAN TEORI………... 7
A. Anak prasekolah………. 7
1. Pengertian Kematangan Sosial……… 12
2. Tugas Perkembangan Anak Prasekolah……... 12
3. Kematangan Sosial Anak Prasekolah………... 14
4. Proses Perkembangan Kematangan Sosial Anak Prasekolah……… 15
5. Faktor yang Mempengaruhi Kematangan Sosial Anak 16 6. Aspek-aspek Kematangan Sosial Anak Prasekolah….. 17
C. Playgroup Yogya Kids………... 26
D. Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids……….. 30
E. Skema……….. 33
BAB III METODE PENELITIAN………... 34
A. Jenis Penelitian………. 34
B. Definisi Operasional………. 34
C. Subyek Penelitian………. 35
D. Metode dan Alat Pengumpul Data……… 35
E. Pertanggung Jawaban Mutu……….. 39
1. Validitas Isi………... 39
2. Seleksi Item………... 40
3. Reliabilitas Item Observasi……… 42
4. Korelasional Antar Rater………... 42
a. Uji Normalitas………. 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN………. 44
A. Orientasi Kancah Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian…….. 44
1. Orientasi Kancah Penelitian……….. 44
2. Pelaksanaan Penelitian……….. 45
B. Hasil Penelitian……….. 46
Deskripsi Data Penelitian……….. 46
C. Pembahasan………... 48
BAB V PENUTUP……… 52
A. Kesimpulan……… 52
B. Saran……….. 52
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Ringkasan Dasar Komptensi Anak………. 27
Tabel 2. Contoh Dasar Pengajaran Harian Playgroup Yogya Kids…….. 29
Tabel 3. Daftar perilaku aspek-aspek kematangan sosial………. 36
Tabel 4. Blue Print Check List Kematangan Sosial………. 39
Tabel 5. Butir yang digunakan dan gugur dalam Check List Kematangan Sosial……… 41
Tabel 6. Penyebaran butir-butir pengamatan setelah uji coba…………. 41
Tabel 7. Daftar Keterangan Subyek Penelitian……… 45
Tabel 8. Kategorisasi Hasil Penelitian………. 46
Tabel 9. Deskripsi Data Penelitian………... 47
Tabel 10. Perbandingan Hasil Deskripsi Data Penelitian………. 47
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
A. Check List Pengamatan Try Out……….. 56
B. Data Try Out………... 60
C. Alat Ukur Penelitian………... 80
D. Hasil Penelitian……… 83
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap awal tahun ajaran baru, banyak orang tua sibuk mendorong sang balita agar segera masuk sekolah. Ternyata masalah tidak berakhir setelah niatnya kesampaian, karena sang balita kok malah rewel dan nangis terus.. pengasuhnya harus kelihatan olehnya.. kalau tidak, bisa panik… Adapula yang ngadat nggak mau sekolah… Ada pula yang susah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mojok terus dan membisu, kalau didekati guru malah ketakutan… (Rini, 2002)
Banyak orang tua yang bingung menghadapi perubahan sikap
anaknya yang tiba-tiba mogok tidak mau berangkat ke sekolah dengan
berbagai alasan, mulai dari sakit perut, sakit kepala, sakit kaki dan seribu
alasan lainnya. Bagi orang tua yang anaknya masih ada di usia prasekolah,
keadaan ini tentu membuat mereka pusing karena menimbulkan
kebingungan apakah alasan tersebut benar atau hanya dibuat-buat. Orang tua
dihadapkan pada dua pilihan; memaksa anak untuk tetap berangkat sekolah
tapi mereka juga cemas bila nanti anaknya stress, atau tidak memaksa
berangkat sekolah tetapi bagaimana dengan penanaman disiplin sehingga
mereka bingung untuk menentukan sikap (Rini, 2002).
Sesuai dengan kemampuan berdasarkan tahap perkembangan anak,
usia 3-5 tahun sebenarnya merupakan usia yang tepat memasukkan anak ke
playgroup atau TK namun sering kali banyak anak belum mampu
melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungan barunya. Setiap anak
orang tua ketika sekolah namun ada anak yang belum siap. Masalah ini
merupakan masalah yang biasa dialami oleh para orang tua yang akan
memasukkan anaknya ke TK, walaupun hanya sekitar kurang lebih 5-10
persen dari anak-anak usia tersebut yang benar-benar memiliki masalah
penyesuaian diri dengan sekolahnya yang baru setiap tahunnya (Lubis,
2002).
Penyesuaian sosial yang dilakukan anak prasekolah, tidak lagi
terbatas di lingkungan rumah, melainkan juga saat anak di sekolah. Sesuai
tahap perkembangannya, fungsi sekolah taman kanak-kanak adalah untuk
mengembangkan kemampuan sosial dan kemandirian serta
memperkenalkan konsep dasar seperti warna dan bentuk pada anak. Hal
mendasar yang harus dipersiapkan agar anak dapat melakukan penyesuaian
sosial dengan baik di sekolah ialah kematangan fisik, sosial, mental dan
emosi. Khusus mengenai kematangan sosial dapat dilihat dari sikap anak
bersosialisasi dengan lingkungan baru serta kemandirian melakukan tugas
yang diberikan oleh guru (Hurlock, 1991).
Mulai usia prasekolah, seseorang sudah mulai keluar dari lingkungan
keluarga, karena pada saat ini anak sudah mulai mengadakan kontak sosial
yang sebenarnya dan mengadakan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial
menentukan bagaimana seorang anak akan diterima di lingkungannya dan
mempengaruhi pembentukan konsep diri karena pola perilaku dan sikap
yang dibentuk pada masa awal kehidupan cenderung menetap.
akhir masa sekolah ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial (Hurlock,
1991).
Anak-anak melepaskan diri dari keluarga, ia makin mendekatkan diri
pada orang-orang lain di samping anggota keluarga. Meluasnya lingkungan
sosial bagi anak menyebabkan anak menjumpai pengaruh-pengaruh yang
ada di luar pengawasan orang tua. Ia bergaul dengan teman-teman, dan ia
mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses emansipasi (Monks &
Knoers, 2001). Kebutuhan akan perluasan dunia pergaulan membawa anak
pada peningkatan hubungan dengan teman sebaya. Pemusatan perhatian
terhadap keluarga berkembang ke arah perluasan pergaulan di luar rumah
(Sadarjoen, 2002).
Pada usia antara 3 dan 5 tahun, anak-anak berkembang dari
pemikiran egosentrik ke kepasitas untuk bergaul dengan teman sebayanya.
Kelas playgroup, kelompok bermain atau bahkan taman kanak-kanak akan
memberikan kesempatan anak untuk meluaskan hubungan sosial (Sylva &
Lunt, 1988).
Anak yang berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik di
kelas prasekolah mempunyai kemungkinan yang jauh lebih baik untuk dapat
melakukan penyesuaian di tingkat berikutnya (Hurlock, 1991). Pada masa
ini sejumlah hubungan yang dilakukan anak dengan anak-anak lain
meningkat dan ini akan menentukan gerak perkembangan sosial mereka.
Anak yang mengikuti pendidikan prasekolah melakukan penyesuaian sosial
pendidikan prasekolah. Alasannya, mereka dipersiapkan secara lebih baik
untuk melakukan partisipasi dalam kelompok dibandingkan dengan anak
lain yang aktivitas sosialnya terbatas dengan anggota keluarga dan
anak-anak dari lingkungan tetangga terdekat saja (Hurlock, 1991).
Hal yang terpenting dalam perkembangan anak antara umur 2 sampai
3 tahun ialah perkembangan sikap sosialnya. Sikap sosial secara umum
adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Sekitar usia 2
atau 3 tahun anak sudah mulai membentuk masyarakat kecil terdiri dari 2
atau 3 orang. Mereka bermain bersama-sama walaupun kelompok itu hanya
dapat bertahan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan semacam
itu anak sudah mulai menghubungkan dirinya dengan suatu masyarakat yang
baru, di dalamnya mulai terjadi perkembangan baru yaitu perkembangan
sosial.
Teman-teman sebaya dalam perkembangan sosial seseorang
sangatlah penting. Hartup (dalam Santrock, 2002) mengatakan bahwa teman
sebaya (peers) ialah anak-anak yang tingkat usia dan kematangannya kurang
lebih sama. Selain itu, pada perkembangan sosial, bermain bersama teman
sebaya membuat kelompok permainan dan berkompetisi antar kelompok
dapat meningkatkan sosialiasi anak
Kematangan sosial pada diri setiap individu sangat penting dalam
perkembangan sosial manusia karena hal ini terkait dengan keberhasilan
bertahan hidup. Sosialisasi dipupuk justru melalui kesempatan bermain
bersama teman sebaya dalam masa kanak-kanak.
Yogya Kids adalah suatu lembaga pendidikan prasekolah yang
memiliki metode pengajaran yang unik yaitu Natural Growth Curriculum
yang membuat siswa lebih aktif untuk belajar mandiri dengan menekankan
keterampilan sosial anak prasekolah di awal-awal pemebelajarannya.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana
kematangan sosial pada anak usia prasekolah khususnya di Playgrup Yogya
Kids di Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana kematangan sosial pada anak usia prasekolah saat belajar
di playgroup, yaitu Playgroup Yogya Kids di Yogyakarta.
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
kematangan sosial pada anak usia prasekolah saat belajar di Playgroup
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Di bidang Psikologi Perkembangan, penelitian ini bermanfaat untuk
menambah kajian secara empirik tentang kematangan sosial anak usia
prasekolah dalam lingkungan sosialnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi orang tua
Memberi gambaran atau pengetahuan kepada orang tua bahwa
untuk mencapai kesiapan sekolah, para anak usia prasekolah ini
tidak hanya dibekali dengan kemampuan baca-tulis, tetapi ada hal
yang juga penting yaitu kematangan sosial sehingga anak berhasil
melakukan penyesuaian-penyesuaian sosial yang kelak diperlukan
dalam perkembangan kehidupannya.
b. Bagi para guru taman kanak-kanak & playgroup
Memberi pengetahuan yang nyata bagaimana kematangan sosial
yang terjadi pada diri anak-anak didik mereka karena pada masa
prasekolah ini, anak-anak lebih banyak bersosialisasi dengan
lingkungan sekolah mereka. Kemudian dengan adanya
pengetahuan ini diharapkan para guru (bekerja sama dengan orang
tua) bisa mendampingi anak-anak yang mungkin memiliki masalah
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Anak Prasekolah
Hurlock (1991) menyebutkan bahwa para pendidik menyebut
tahun-tahun awal pendidikan di masa kanak-kanak sebagai usia prasekolah. Anak
yang mengikuti taman kanak-kanak juga dinamakan anak-anak prasekolah.
Awal masa kanak-kanak, baik di rumah maupun di lingkungan prasekolah
merupakan masa persiapan.
Berdasarkan tahap perkembangan psikososial menurut Erikson
(dalam Hall & Lindzey, 1993) anak usia prasekolah ini berada pada tahap
Inisiatif versus Rasa Bersalah. Inisiatif bersama-sama dengan otonomi
memberikan suatu kualitas sifat mengejar, merencanakan sesuatu dan meraih
tujuan-tujuan. Bahaya dari tahap ini adalah perasaan bersalah karena
terlampau bergairah memikirkan tujuan, termasuk fantasi genital. Tujuan
adalah nilai yang menonjol pada tahap perkembangan ini. Kegiatan utama
anak dalam tahap ini adalah bermain dan tujuan tumbuh dari kegiatan
bermainnya, eksplorasi-eksplorasinya, usaha-usaha dan
kegagalan-kegagalannya serta eksperimentasinya dengan alat-alat permainannya. Masa
bermain ini bercirikan ritualisasi dramatik. Anak secara aktif berpartisipasi
dalam kegiatan bermain, memakai pakaian, meniru kepribadian-kepribadian
orang dewasa dan berpuara-pura menjadi apa saja dari seekor anjing sampai
unik, dan anak-anak kecil paling baik belajar melalui pengalaman tangan
pertama (langsung) dengan manusia dan benda-benda. Kegiatan bermain
sangat penting dalam perkembangan total anak (Santrock, 2002).
Secara umum, menurut Piaget (dalam Santrock, 2002), anak
prasekolah berada pada tahap praoperasional, yaitu; anak-anak berada pada
tahap kemampuan awal untuk merekonstruksi pada tingkat pemikiran apa
yang telah dilakukan di dalam perilaku. Anak-anak juga masih berada pada
tahap subtahap fungsi simbolis yaitu; pemikiran praoperasional yang terjadi
kira-kira pada usia 2-4 tahun. Pada subtahap ini, anak membayangkan secara
mental suatu obyek yang tidak ada. Kemampuan berpikir simbolis semacam
itu disebut fungsi simbolisdan kemampuan itu mengembangkan secara cepat
dunia mental anak.
Tahap praoperasional ini ditegaskan kembali oleh Monks (2001)
yang menurutnya, berdasarkan perkembangan kognitif, anak usia prasekolah
juga berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak mulai
melakukan penggunaan bahasa yang sistematis, permainan simbol, imitasi
(tidak langsung) serta bayangan dalam mental. Semua proses ini
menunjukkan bahwa anak sudah mampu untuk melakukan tingkah laku
simbolis. Anak tidak lagi mereaksi begitu saja terhadap stimulus-stimulus
melainkan nampak ada suatu aktivitas internal, cara berpikir
praoperasionalnya pun masih sangat egosentris. Anak belum mampu (secara
persepsual, emosional-motivasional dan konsepsual) untuk mengambil
sana ada 3 bendera; berwarna merah, putih dan biru berjajaran. Bila anak
diminta untuk menyebutkan urutan mobil tadi dari sudut pandangan orang
lain yang berdiri di seberang sebaliknya, maka ia akan menjawab dari sudut
persepektifnya sendiri.
Dari anak umur 2 sampai 6 tahun, anak belajar melakukan hubungan
sosial dan bergaul dengan orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan
anak-anak yang umurnya sebaya. Mereka belajar menyesuaikan diri dan
bekerja sama dalam kegiatan bermain. Studi lanjutan tentang kelompok anak
melaporkan bahwa sikap dan perilaku sosial yang terbentuk pada usia dini
biasanya menetap dan hanya mengalami sedikit perubahan (Hurlock, 1991).
Menurut Hurlock (1991) masa kanak-kanak awal sering disebut “usia
prageng” (pregang age). Pada masa ini sejumlah hubungan yang dilakukan
anak dengan anak-anak lain meningkat dan ini sebagian menentukan
bagaimana gerak maju dan perkembangan sosial mereka. Anak-anak yang
mengikuti pendidikan prasekolah; misalnya pendidikan untuk anak sebelum
taman kanak-kanak (nursery school), pusat pengasuhan anak pada siang hari
(day care centre), atau taman kanak-kanak (kindergarten), biasanya
mempunyai sejumlah besar hubungan sosial yang telah ditentukan dengan
anak-anak yang umurnya sebaya. Anak yang mengikuti pendidikan
prasekolah melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik dibandingkan
anak-anak lain yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah. Alasannya
adalah mereka dipersiapkan secara lebih baik untuk melakukan partisipasi
sosialnya terbatas dengan anggota keluarga dan anak-anak dari lingkungan
tetangga terdekat.
Berikut ini beberapa karakteristik perilaku dari anak prasekolah
(Santrock, 2002):
a. Memiliki pemikiran yang lebih simbolis daripada pemikiran
sensorimotorik. Anak prasekolah masih memiliki pemikiran dengan
membayangkan secara mental suatu obyek yang tidak ada.
b. Egosentrisme; ketidakmampuan membedakan perspektifnya sendiri
dengan pemikiran atau perspektif orang lain meski anak menyadari
bahwa orang lain pun memiliki perasaannya sendiri, namun
egosentrisme anak usia 3 tahun amat kuat. Anak berpikir bahwa ialah
“pusat dunia”, bahwa semua hal di dunia ini tersedia untuknya, semua
ada untuk memenuhi kebutuhannya. Kuatnya egosentrisme ini juga
mempengaruhi perilaku anak saat bermain. Saat bermain, anak enggan
bila mainannya dipinjam, juga menolak mengembalikan pinjaman. Hal
ini sangat wajar bila kemudian kegiatan bermain bersama kerap diwarnai
konflik (perselisihan).
c. Anak usia 3 sampai 5 tahun sering menanyakan pertanyaan. Pertanyaan
–pertanyaan mereka memberi petunjuk akan perkembangan mental
mereka dan mencerminkan rasa ingin tahu intelektual. Meluapnya rasa
ingin tahu; secara alamiah, anak prasekolah memiliki rasa ingin tahu
yang amat besar. Rasa ingin tahunya meliputi beragam bidang, termasuk
manakah asal bayi atau sering kali anak sedang “menyelidiki alat
genitalnya”, seringkali juga anak banyak bertanya “Kenapa?” atau “Ada
apa?”
d. Anak prasekolah lebih bersifat intuitif daripada logis. Hal ini berkaitan
dengan dunia imajinasi mereka yang kaya. Dunia imajinasi yang kaya;
pada anak prasekolah, imajinasi banyak mewarnai perilaku mereka.
Anak pun masih sulit membedakan antara imajinasi dan realitas. Lihat
saja, tak jarang ia ia sibuk menceritakan “pengalaman” yang sebetulnya
hanya khayalannya. Itu semua membuat anak tampak sebagai sosok
yang suka melebih-lebihkan cerita. Padahal jika ditelusuri, penyebabnya
hanyalah ketidak mampuannya membedakan antara realitas dan
kahyalan. Khayalan atau imajinasi memamng memiliki fungsi penting
dalam kehidupan anak. Imajinsi merupakan alat untuk mengeksplorasi
dunia, alat untuk bereksperimen dengan pengalaman dan perasaan
mereka. Pada saat usia prasekolah, beberapa kasus bisa terjadi pada
anak-anak, yaitu anak-anak yang memiliki teman imajiner. Hal ini wajar
terjadi karena pada teman imajiner anak bisa mencurahkan berbegai
perasaannya, sekadar berbagi ketakutan, kecemasan, kebahagiaan atau
kekesalan sehingga memberi kesempatan berkembangnya kematangan
emosi anak.
e. Ketidakmampuan untuk mengaitkan dalam operasi; tidak dapat
mengubah tindakan secara mental; kurangnya keterampilan dalam
B. Kematangan Sosial Anak Prasekolah 1. Pengertian Kematangan Sosial
Kematangan sosial (Social Maturity) adalah derajat di mana
individu mencapai kemerdekaan dirinya dari pengaturan orang tuanya
dan dari orang dewasa lainnya (Kartono & Gulo, 1987). Schnneiders
(dalam Gunarsa, 2003) mengatakan kematangan merupakan dasar
perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi tingkah laku. Ada
pun yang dimaksud dengan kematangan ialah keadaan pada tahap-tahap
perkembangan yang sesuai dengan keadaan atau norma umum pada
tingkatan perkembangan seseorang. Kematangan dalam hal ini termasuk
kematangan fisik, emosi dan intelektual.
Bhatia (dalam Indrawan, 2000) menjelaskan bahwa kematangan
sosial memiliki 2 pengertian yaitu:
a. Kesadaran sosial yang dilandasi oleh sikap yang mengerti,
memahami, menghormati kebiasaan atau nilai masyarakat serta
menampilkan dirinya sebagai anggota masyarakat tersebut.
b. Berkembangnya pola tingkah laku merupakan sikap kebiasaan
yang membantu anak dalam kehidupan kelompok serta dalam
menciptakan kesejahteraan kelompok.
2.
Tugas Perkembangan Anak PrasekolahPada saat usia prasekolah, anak senang melakukan berbagai
gerakan motorik disertai dengan perkembangan fisik dan kognitif. Pada
usia ini anak lebih banyak melakukan gerakan motorik kasar dan
motorik halusnya seperti berlari, melompat, menulis, menggunakan
berbagai alat seperti gunting atau menyusun suatu barang menjadi suatu
bentuk tertentu. Anak juga belajar menggunakan sendok pada saat
makan, belajar mandi dan memakai baju sendiri. Pada usia ini anak telah
dapat mengontrol diri sendiri saat harus ke kamar mandi untuk buang air.
Anak mulai mandiri dan dapat merawat diri sendiri. Anak usia
prasekolah senang diperhatikan oleh setiap orang dan menunjukkan
kegembiraan bila telah berhasil melakukan sesuatu. Anak bangga
menunjukkan apa yang telah dilakukan untuk menerima perhatian dan
pengakuan orang lain. Hal ini merupakan salah satu cara menstimulasi
anak mengembangkan kreatifitasnya (Pikunas dalam Anggraini, B. D.
2003).
Sejalan dengan perkembangan fisiknya, perkembangan bahasa
anak mulai bertambah, anak mulai mampu menghafal nama-nama benda,
nama-nama orang, lagu-lagu dan anak senang mengajukan berbagai
pertanyaan terutama yang berhubungan dengan konsep. Menurut Piaget
(dalam Monks dkk., 2001) anak prasekolah memasuki stadium
praoperasional dimulai dengan penguasaan bahasa yang sistematis,
permainan simbolis serta imitasi. Ia mampu untuk menirukan tingkah
laku yang dilihatnya (imitasi) dan apa yang dilihat sehari sebelumnya
Bandura dalam teori Belajar Sosial (dalam Hetherington & Parke,
1976; Jersild, 1968) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi
pembentukan pola perilaku anak yang cenderung menetap adalah imitasi
terhadap model. Model dalam hal ini perilaku, sikap serta stimulus yang
dilihat anak dari lingkungan terutama orang-orang yang berada di dekat
si anak. Perilaku yang terbentuk cenderung menguat dengan adanya
reinforcement baik yang disadari atau pun tidak dari lingkungan.
3.
Kematangan Sosial Anak PrasekolahKematangan sosial anak terkait dengan perkembangan anak
secara umum dan perkembangan perilaku sosial secara khusus. Oleh
karena itu kematangan atau kemasakan sosial merupakan keadaan anak
yang telah memiliki kesiapan untuk menyesuaikan diri pada peraturan
serta norma yang ada dalam lingkungannya dan dipengaruhi faktor
belajar atau adaptasi sehingga dapat bergaul serta melibatkan diri di
dalamnya. Perilaku sosial anak berkembang bersama dengan
kematangan hereditas dan pengaruh belajar yang bertahap. Dengan
demikian kematangan sosial anak tidak terlepas dari tahap-tahap
perkembangannya.
Doll (dalam Anastasi,1976) mendefinisikan kematangan sosial
sebagai kinerja yang menunjukkan perkembangan kemampuan dalam
memelihara diri sendiri dan kemampuan berpartisipasi dalam
dewasa. Kematangan sosial juga berkaitan dengan kesiapan anak untuk
terjun dalam kehidupan sosial dengan orang lain yang bisa diamati
dalam bentuk-bentuk ketrampilan yang dikuasai dan dikembangkan
sehingga akan membantu kemandirian sosial kelak.
4. Proses Perkembangan Kematangan Sosial Anak Prasekolah
Berkaitan dengan tugas perkembangan anak, secara sosial anak juga mulai mengalami perubahan yang cukup pesat. Mulai usia
prasekolah, interaksi anak tidak hanya terbatas pada ibu atau pun
keluarganya tetapi mulai terlibat dengan teman sebaya (peer) dan guru di
sekolah. Hal ini berarti anak harus mampu menyelesaikan tugas
perkembangan pada usianya dengan mulai mengembangkan sikap
menghargai, membantu orang lain, bekerja sama, menunggu giliran untuk
suatu aktivitas (Margolin, 1982). Anak juga mulai belajar
mengungkapkan perasaan dalam perilaku yang bisa diterima secara sosial,
memilih kegiatan dan tugas serta dapat menyelesaikan tugas tersebut
dapat mengontrol emosi, tidak mengalami kesulitan untuk berpisah dalam
waktu tertentu dengan orang tua, mampu menerima dan mengerti setiap
tuntutan dari lingkungan terutama di sekolah (Hurlock, 1991), mampu
mandiri dan merawat diri, mampu mengkoordinasikan gerakan kaki dan
motorik tangan, mata dan kaki sehingga dapat melakukan aktivitas dan
5. Faktor yang Mempengaruhi Kematangan Sosial Anak
Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan sosial menurut
Hurlock (1991) adalah:
a.
FisikFisik seorang anak mempengaruhi berperilaku, yang sehat tanpa cacat
akan membuat anak lebih mampu merespon stimulus yang diberi
lingkungan. Fisik yang sehat juga mempengaruhi pandangan anak
terhadap dirinya, anak yang merasa berbeda dibanding teman-temannya
cenderung menutup diri. Perkembangan fisik juga mempengaruhi
perkembangan lain.
b.
IntelegensiIntelegensi di atas rata-rata memungkinkan anak melakukan imitasi atau
stimulus pada lingkungan yang akan terinternalisasi dalam diri anak.
Penelitian Oden (Monks, Knoers & Haditono, 1988) mengungkapakan
bahwa anak-anak dengan intelegensi tinggi mempunyai prestasi yang
baik, lebih ulet, lebih bermotivasi untuk dapat berprestasi sebagai yang
paling baik kemudian anak-anak ini lebih baik dalam melakukan
penyesuaian sosial dan rata-rata psikis mereka juga lebih sehat.
c.
KeluargaKeluarga merupakan perantara ang sangat penting dalam membantu
perkembangan sosialisasi anak (Hetherington & Parke, 1999). Jika
lingkungan rumah secara keseluruhan memupuk perkembangan sosial
Bhatia (dalam Indrawan, 2000) berpendapat bahwa tingkah laku sosial
dan sikap anak terhadap orang lain dipengaruhi oleh pengalaman
belajarnya yang didapatkan pada tahap-tahap awal pembentukan pribadi.
Keluarga dalam hal ini juga termasuk sistem dan kebiasaan yang
berkembang.
d.
Lingkungan sosialLingkungan tempat anak bersosialisasi merupakan media anak
melakukan imitasi berperilaku dan bersikap. Anak usia prasekolah
memasuki stadium praopersional, anak masih belum mampu untuk
memahami segala sesuatu menurut cara berpikirnya sendiri. Sehingga
pada usia ini anak melakukan imitasi pada lingkungannya (Piaget dalam
Monks, Knoers dan Haditono, 1988). Lingkungan sekitar rumah dalam
hal ini adalah yang di luar keluarga yaitu sekolah, teman sebaya bahkan
televisi.
e.
GuruPerlakukan dan sikap guru pada anak di sekolah termasuk peraturan
yang berlaku di sekolah mempengaruhi sikap sosial anak untuk
beradaptasi dengan lingkungan di luar rumah.
6. Aspek-aspek Kematangan Sosial Anak Prasekolah
Doll (dalam Anastasi, 1976) mengatakan bahwa kematangan
a. Self-help
Self-help adalah kemampuan membantu diri sendiri dalam hal
umum seperti kemampuan menghindari bahaya sederhana,
mengurus diri sendiri di toilet, mengambil makanan tanpa
bantuan, mampu berpakaian sendiri, mandi dan tidur tanpa
bantuan merupakan kemampuan yang harus dikuasai anak usia
prasekolah sehingga anak dapat mandiri untuk melakukan
sesuatu bagi diri sendiri terutama di sekolah (Ilg dan Gussel,
1977).
b. Self-direction
Self direction adalah kemampuan untuk mengerahkan dan
memimpin diri sendiri seperti berbelanja yang ringan-ringan
tanpa pengawasan pada siang hari.
c. Occupation
Occupation adalah kemampuan untuk membantu berupa
pekerjaan rumah tangga yang ringan, menggunakan pensil dan
spidol untuk menggambar dan menggunakan alat-alat
perlengkapan. Seorang anak, agar dapat menjadi anggota
kelompok sosial yang diterima di dalam keluarga, sekolah dan
teman sebaya, anak harus menjadi anggota yang kooperatif
d. Locomotion
Daya penggerak pada anak (locomotion) untuk bepergian seperti
main atau pergi ke rumah tetangga tanpa pengawasan, ke sekolah
tanpa diantar, keliling kompleks perumahan dengan bebas.
Bepergian tanpa diawasi orang dewasa menunjukkan tanggung
jawab dan kemandirian yang dimiliki anak.
e. Communication
Communication adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan
dan menerima apa yang dipikirkan, diinginkan dan dirasakan.
f. Social relation
Anak usia prasekolah (3-5 tahun) tidak lagi berorientasi pada diri
sendiri melainkan harus dapat berinteraksi dengan orang lain.
Berinteraksi menekankan pada hubungan timbal balik, anak tidak
hanya menuntut orang lain memahami dirinya tetapi anak juga
harus dapat memahami dan mematuhi standar norma yang
berlaku dalam lingkungannya di rumah atau pun di sekolah.
Kemampuan anak mengadakan hubungan sosial (social relation)
seperti turut serta dalam permainan perlombaan, “main
sandiwara”. Keterampilan ini melihat sejauh mana anak dapat
terlibat dalam kehidupan sosialnya. Kematangan sosial yang
dicapai anak usia taman kanak-kanak mungkin berbeda satu sama
lain. Apabila anak telah menguasai 6 ketrampilan di atas dengan
kematangan sosial yang tinggi. Anak yang kematangan sosialnya
tinggi umumnya dapat melakukan penyesuaian sosial lebih baik
dari anak yang kematangan sosialnya rendah (Hurlock, 1991).
Kematangan sosial anak juga bervariasi menurut tingkat
perkembangan perilaku sosialnya. Perkembangan perilaku sosial dapat
disimpulkan bahwa hal ini akan bermuara pada aspek organisasi perilaku
sosial (sosialisasi) saja. Aspek kompetensi sosial adalah sebagian dari
aspek sosialisasi, hal ini menjelaskan kekuatan motivasi dan
keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatur perilaku
sosial. Kaitan yang sangat erat antara perilaku attachment dan
kompetensi anak (Sroufe, 1978), menampakkan bahwa kompetensi
sosial merupakan fasilitas untuk organisasi perilaku sosial. Dengan kata
lain aspek sosialisasi atau aspek organisasi perilaku sosial merupakan
puncak dari kedua aspek lainnya. Dalam konsep ini aspek-aspek yang
juga digunakan untuk mengamati kematangan sosial (Fitzgerald et al.,
1982):
a. Dependensi
Item ini meliputi empat macam ketrampilan: self help skills, social help
skills, school skills dan play skills. Self help skills adalah keterampilan
dalam menolong diri sendiri yang menunujukkan taraf kemampuan anak
untuk semakin bergantung pada dirinya sendiri dan kemerdekaan dari
bantuan orang lain. Social help skills adalah keterampilan yang
dalam keluarga. School skills adalah keterampilan dalam menyelesaikan
tugas-tugas sekolah baik akademik maupun non akademik. Play skills
adalah keterampilan dalam berbagai jenis permainan yang sesuai dengan
tingkat perkembangannya. Dari deskripsi di atas nampak bahwa
dependensi sangat terkait dengan perilaku attachment sehingga
faktor-faktor pembentuk pola perilaku attachment itu adalah komposisi
keluarga. Anak yang dependen cenderung banyak meminta tolong
kepada orang lain. Ia senang menempel, meminta digandeng dan
meminta perhatian pada orang lain. Ia kurang berinisiatif, tidak mampu
mengatasi hambatan lingkungan dan tidak menuntaskan kegiatannya. Ia
tidak merasa puas dalam pekerjaannya. Sebaliknya anak independen
mampu melaksanakan tugas rutinnya sendiri. Ia juga mampu berpakaian
dan makan sendiri dan ia terdorong untuk bergabung dengan
kelompoknya. Doll (dalam Medinnus, 1976) menyusun item-item
kematangan sosial berdasarkan Vineland Maturity Scale. Item-item itu
dikembangkan untuk mengukur Social Quotient (SQ) anak. Item-item
untuk anak prasekolah adalah:
1. Mampu melakukan kegiatan toilet sendiri
2. Mampu mencuci muka sendiri
3. Mampu menjalin hubungan dengan orang baru
4. Mampu berpakaian sendiri kecuali dasi
5. Mampu menggunakan pensil dan krayon untuk menggambar
b. Partisipasi Sosial
Partisipasi sosial terutama diamati berdasarkan partisipasi anak bersama
peernya. Parten (1932, dalam Monks, Knoers & Haditono, 2001)
meninjau permainan anak dari sudut tingkah laku sosial anak; Parten
menyusun kategori-kategori permainan berdasarkan besarnya
keterlibatan sosial. Kategori-kategori yang digunakan untuk melihat
partisipasi sosial anak adalah sebagai berikut:
1. Paralel Play
Anak bermain secara bebas tetapi aktivitas yang ia pilih adalah
aktivitas yang secara alamiah akan menempatkan dia dalam
golongan anak-anak lain. Ia memainkan mainan-mainan yang
menyerupai mainan yang dipakai anak-anak lain di sekitarnya.
Tetapi ia memainkan mainan itu menurut adanya ia lihat dan tidak
mencoba mempengaruhi aktivitas anak-anak di sekitarnya. Jadi ia
hanya bermain di sebelah anak-anak lain dan tidak bersama
ana-anak lain.
2. Associative Play
Anak bermain bersama anak-anak lain. Terjadi pinjam-meminjam
alat/ bahan permainan; silih berganti dengan sedikit usaha untuk
mengontrol alat/ bahan permainan mana yang sedang digunakan
atau tidak digunakan anak lain. Aktivitasnya serba sama kalau
bukan identik. Belum ada pembagian kerja dan pengaturan
sendiri dan tidak menjadikan minatnya sebagai bagian dari
kelompok.
3. Cooperative Play atau Organized Supplementary Play
Anak bermain dalam sebuah kelompok yang dibentuk dan
diorganisir untuk tujaun-tujuan tertentu, misalnya untuk membuat
suatu barang, mencapai tujuan persaingan, mendramakan situasi
hidup orang dewasa atau memainkan permainan formal. Kontrol
terhadap situasi kelompok berada di tangan satu atau dua anggota,
yang mengarahkan aktivitas anak lain. Tujuan maupun sarana yang
digunakan memerlukan pembagian kerja, pembagian peran yang
berbeda-beda dan organisasi aktivitas sehingga usaha dari seorang
anak dilengkapi oleh usaha dari anak lain.
c. Kontrol Emosi
Pengontrolan emosi yang efektif menghasilkan penerimaan sosial.
Indikasi adanya penerimaan sosial dapat dilihat dari kesesuaian tingkah
laku anak terhadap norma kelompok, kemampuan adaptasi dengan
kelompok, keterlibatan anak dan penerimaan dari kelompoknya serta
perasaan puas dan bahagia berada dalam kelompok. Pola umum emosi
anak-anak yaitu; kemarahan, ketakutan, rasa malu, kecanggungan,
kekhawatiran dan kecemasan. Anak yang pemalu dan canggung
(Hurlock, 1991), hanya memberi sedikit kontribusi pada kelompok.
Umumnya mereka bukan tidak disukai tetapi dipandang rendah dan
kurangnya pengalaman belajar dalam segi hubungan sosial. Anak yang
pemalu, takut bicara dengan orang lain sehingga orang lain juga tidak
berbicara dengan mereka, hal ini mendorong mereka menjadi terikat
kepada diri sendiri. Syarat utama penerimaan sosial pada anak-anak
adalah kematangan sosial sebagaimana didefinisikan oleh kelompok
anak itu berada. Penerimaan sosial berkaitan dengan popularitas anak
dalam kelompoknya. Adapun ciri-ciri perilaku tidak populer menurut
Koch (dalam Medinnus & Johnson, 1969) adalah sebagai berikut:
1. Cenderung bermain sendiri
2. Menolak atau mengabaikan permintaan anak lain
3. Menyerang anak lain
4. Melarikan diri dari keadaan yang tidak diharapkan
5. Membuang-buang waktu
Penerimaan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kematangan sosial
melainkan juga jenis kelamin dan kelas sosial. Oleh karena itu dalam
mengamati kematangan sosial anak yang didasarkan pada penerimaan
sosial, variabel jenis kelamin dan kelas sosial sebisa mungkin
disingkirkan. Lagipula, istilah peer group mengimplikasikan keadaan di
mana seorang anak dinilai oleh lingkungan sebayanya. Menurut Hurlock
(1991) penerimaan sosial berarti dipilih sebagai teman untuk suatu
aktivitas dalam kelompok di mana seseorang menjadi anggota. Ini
dalam kelompok sosial dan menunjukkan derajat rasa suka anggota
kelompok yang lain untuk bekerja atau bermain dengannya.
Maka, dari beberapa aspek kematangan sosial yang sudah
dipaparkan di bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa
kematangan sosial anak usia prasekolah adalah kemampuan anak usia
prasekolah dalam menjalin relasi dengan orang lain yang nampak dari :
a. Kemampuan mengungkapkan diri; misalnya berani meminta sesuatu,
mengekpresikan rasa senang, sedih atau marah dengan jelas, mulai
bertanya “apa?”, “kenapa?”, “siapa?”.
b. Mampu menolong dirinya sendiri; yaitu memakai sepatu sendiri, bisa
memakai celana atau kaus sendiri; bisa memakai kaus kaki sendiri, pergi
ke toilet sendiri, mampu mencuci muka atau tangan sendiri, makan
sendiri.
c. Memiliki keterampilan sosial yang baik; perilaku ini dapat dilihat dari
kemauan anak menjawab atau memberi salam kepada orang lain,
berkenalan dengan teman baru dan tidak malu berhadapan dengan orang
lain tanpa didampingi figur lekatnya (dalam hal ini pengasuh atau orang
tua), kemampuan empatik atau mau menolong teman.
d. Memiliki keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, baik
akademis maupun non akademis; misalnya mampu memegang pensil
dengan benar, mampu menggambar dengan pensil atau crayon, mampu
e. Memiliki keterampilan dalam berbagai jenis permainan yang sesuai
dengan tingkat perkembangannya. Kemampuan anak dalam hal ini
dilihat dari jenis permainan yang dipilih, apakah cenderung permainan
individual atau kelompok, mampu bermain secara kooperatif, bermain
peran atau bahkan permainan kompetitif.
f. Memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi; problem solving dengan
anak lain ketika terjadi konflik, mau berbagi mainan dengan teman, tidak
memukul teman ketika terjadi konflik, tidak mudah menangis dalam
situasi sulit atau gagal dalam melakukan suatu pekerjaan
C. Playgroup Yogya Kids
Playgroup Yogya Kids adalah lembaga pendidikan anak
prasekolah dengan memakai sistem bilingual (Bahasa Inggris dan Indonesia)
untuk meningkatkan dan menstimulasi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Keterampilan bersosialisasi dan kemandirian
b. Keterampilan berbahasa dan kesiapan baca-tulis
c. Keterampilan emosi
d. Kesiapan numerik dan spasial
e. Psikomotorik
f. Kreativitas
Anak-anak playgroup ini belajar sambil bermain dalam suasana
Kurikulum yang digunakan adalah Natural Growth Curriculum
(Kurikulum Pertumbuhan Alamiah). Kurikulum alamaiah berarti kurikulum
sehari-hari. Kegiatan belajar, baik isi maupun caranya, sama dengan
kegiatan anak sehari-hari. Kegiatan yang biasanya suka dilakukan anak pada
umur tertentu akan dialami juga di sekolah. Bagi anak, sekolah tidak jauh
berbeda dengan kegiatan sehari-hari. Bedanya, di sekolah kegiatan itu lebih
terjadwal, disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Selain itu kegiatan
di sekolah juga dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan latar budaya
manapun di dunia (Dasar Kurikulum Yogya Kids, 2005/2006). Tujuan dari
kurikulum ini adalah menyiapkan anak mengikuti kurikulum pendidikan
dasar yang berbasis kompetensi. Inti dari kaurikulum berbasis kompetensi
hanyalah memindahkan fokus; dari materi belajar menjadi taraf belajar.
Kurikulum Yogya Kids terdiri atas beberapa grade yang didasarkan pada
kompetensi anak. Kompetensi tersebut diringkas menjadi:
Tabel 1. Ringkasan Dasar Kompetensi Anak yang diberlakukan
di Yogya Kids
Usia (tahun)
Kompetensi dasar
0-1 Merasakan cinta, mendapatkan tempat berlindung dan bergantung serta mempercayai lingkungan di sekitar ibunya. 1-2 Tertarik mengenal berbagai macam obyek melalui kegiatan
panca indera secara intensif.
2-3 Mampu melakukan perawatan yang paling sederhana terhadap diri sendiri sehingga tidak bergantung sama sekali pada ibunya. 3-4 Mampu melakukan kegiatan pribadi maupun rumah tangga yang
paling sederhana sehingga tidak bergantung sama sekali pada orang tuanya.
4-5 Mampu mengenali lingkungan di luar rumahnya dan belajar bergaul dengan anak sebaya.
Kelebihan dari metode Natural Growth Curriculum ini adalah:
a. Home away school
Sistem belajarnya membuat kegiatan sekolah menyerupai
kegiatan anak sehari-hari sehingga anak bisa
mengulanginya di rumah.
b. Smart and Fun
Target akademik ditekankan tetapi metodenya harus
dengan cara bermain (kegiatan dan temanya disukai
semua anak).
c. Adil Budaya
Pendidikan dapat diikuti anak dari semua latar budaya
dunia. Anak menjadi toleran dan memahami
prinsip-prinsip universal.
d. Karakter
Anak dididik agar semakin mandiri, berminat sosial dan
mencintai Pencipta-Nya. Diharapkan kelak, anak tidak
mudah terombang-ambing.
(Understanding The Curriculum Yogya Kids, 2005).
Anak-anak di sekolah ini memang telah dilatih untuk mandiri
pada usia dini. Motto yang digunakan sekolah ini adalah “I Can Do It All
By My Self”. Anak-anak playgroup ini rata-rata tidak lagi ditemani oleh ibu
atau pengasuh serta diajarkan untuk mampu menolong diri sendiri seperti
disusun berdasarkan tema besar dirangkum dalam kegiatan mingguan dan
dijabarkan dalam pelaksanaan tema harian. Misalnya Tema minggu ini
adalah “Eksplorasi Kemampuan Kompetitif” (kurikulum mingguan
Playgroup Yogya Kids, 2005/2006). Berikut ini adalah dasar pengajaran
harian:
Tabel 2. Contoh dasar pengajaran harian Playgroup Yogya Kids
Level Fokus, eksplorasi: Anak mengeksplorasi kemampuan kompetitifnya.
Rasa minder dan agresif perlu disalurkan. Anak mencoba mencari obyek atau tindakan yang mampu ia lakukan dan memamerkannya kepada anak lain dengan rasa persaingan. Ia mencobai anak lain apakah mampu melakukan apa yang ia lakukan.
Tinjauan umum
Membangun kerjasama dari rasa minder dan keinginan agresif.
Tema Harian Can You Follow Me?
Anak-anak memamerkan sebuah keterampilan (yang kadang-kadang tidak istimewa) kepada anak lain agar tidak ditirukan. Jika dapat ditirukan anak terdorong untuk bekerjasama. Jika tidak dapat atau tidak mau menirukan, anak akan mencari anak lain untuk dipameri.
Obyek/ minat Menentukan kemandirian dalam kerja sama.
Anak belajar meraih kemandirian melalui kerjasama (persaingan) dalam tugas pengalihan obyek
Subyek Menjadi pelopor lomba dan persaingan.
Anak mempengaruhi anak lain agar mengikuti lomba yang ia sukai.
Krisis/ depresi Inferioritas atau agresivitas.
Konflik antar anak dapat mengakibatkan rasa minder (inferior) atau keinginan menyerang (agresif) bagi anak yang kalah.
Kompetensi Koordinasi antara tindakan dan pesan.
Pengasuhan “Hai lihat, si A bisa!”
Pengasuhan sebaiknya diarahkan pada keterampilan otot halus yang berhubungan dengan alat-alat (meskipun tidak harus menulis). Urutkan pengajaran sebagai berikut:
a. Pamerkan pada semua anak sebuah keterampilan
b. Dorong anak agar menirukan, awasi bila ada anak yang mampu
c. Jika ada satu anak yang mampu atau mau menirukan, katakan “Hai, lihat si A bisa!” untuk menumbuhkan rasa persaingan
d. Pamerkan keterampilan yang lain, yang lebih sulit
e. Beri kesempatan anak bila ingin memamerkan keterampilannya di hadapan anak lain
Setting Reaksi buruk dalam persaingan.
Dalam kehidupan sehari-hari, persaingan anatar anak tidak selalu berjalan mulus. Kecurangan, kecelakaan atau kegaduhan seringkali tidak dikehendaki oleh pihak yang kalah, korban atau kepentingan orang tua. Dalam hal ini, anak menerima peringatan dan petuah mengenai pentingnya berbagi. Sebenarnya pengertian akan pentingnya berbagi diperoleh anak pertama kali dari reaksi buruk/ protes anak lain yang menjadi korbannya.
D. Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids
Anak berusia 3 tahun yang pergi dari rumahnya untuk memasuki sekolah
atau kelompok bermain dihadapkan dengan dunia sosial baru dengan orang
dewasa dan anak-anak lain. Hal ini mungkin kontak pertamanya dengan anak
lain yang seusia dengannya yang sekarang mulai memainkan peran penting
dalam kehidupannya (Silva & Lunt, 1988). Anak-anak prasekolah, khususnya
dalam hal ini anak-anak Playgroup Yogya Kids diharapkan memiliki
kematangan sosial sebagai tugas perkembangan yang harus dilewati dalam tahap
perkembangan kehidupannya. Anak-anak prasekolah di Playgroup Yogya Kids
belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosialnya terutama sekolah
dikatakan Dowling (dalam Silva & Lunt, 1988) bahwa kesempatan untuk
mengembangkan kemandirian harus diutamakan dalam setiap bidang
pengasuhan anak; pengaturan mengambil susu sendiri memberi kesempatan
kepada anak untuk menuang susu sendiri dan memutuskan seberapa banyak
yang dapat ia minum; tempat buang air yang tepat berarti si anak dapat pergi
buang air pada saat dan kapan saja ia inginkan; pilihan untuk bernain di dalam
atau di luar dengan berbagai sarana; untuk mengikuti atau tidak mengikuti acara
mendengarkan cerita dan memilih teman bermain. Semua itu merupakan awal
pengambilan keputusan untuk kehidupan. Anak yang mampu membuat
keputusan dan bertindak inisiatif sendiri akan cepat bertumbuh dengan penuh
percaya diri. Playgroup Yogya Kids pun membantu murid-muridnya dalam
mencapai kematangan sosial dengan Natural Growth Curriculum yang
menekankan pada semboyan belajar “semua bisa saya lakukan sendiri” (All I
Can Do It by Myself) untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan menurut
Yogya Kids yaitu;
a. Keterampilan bersosialisasi dan kemandirian
b. Keterampilan berbahasa dan kesiapan baca-tulis
c. Keterampilan emosi
d. Kesiapan numerik dan spasial
e. Psikomotorik
f. Kreativitas
Hal ini sesuai dengan aspek-aspek perkembangan secara umum
a. Keterampilan mengungkapkan diri yang mencakup
keterampilan berbahasa
b. Kemampuan menolong diri yang mencakup kemandirian
c. Keterampilan sosial yang mencakup keterampilan
bersosialisasi
d. Keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah
yang mencakup kesiapan baca-tulis, kesiapan numerik
dan spasial
e. Keterampilan dalam berbagai jenis permainan yang
mencakup kreativitas dan psikomotorik
f. Kemampuan mengontrol emosi yang mencakup
keterampilan emosi.
Playgroup Yogya Kids juga memperhatikan kebutuhan pribadi setiap
anak dalam mencapai kematangan sosial dengan memperhatikan faktor-faktor
yang mempengaruhi kematangan sosial anak yaitu; fisik, intelegensi, keluarga,
lingkungan sosial dan guru. Anak-anak yang memiliki kebutuhan fisik khusus
misalnya, akan dilatih psikomotoriknya atau dibimbing secara personal untuk
bisa mengikuti kegiatan yang ada. Guru juga tetap bekerja sama dengan orang
tua dalam memantau perkembangan anak setiap hari melalui laporan harian dan
menerima konsultasi perkembangan anak-anak dididiknya. Oleh karena itu,
dengan berbagai sarana dan fasilitas yang ada, anak-anak prasekolah diharapkan
anak sehingga akhirnya anak-anak tersebut memiliki kematangan sosial selama
mereka belajar di Playgroup Yogya Kids.
E. Skema
Anak Prasekolah di Playgroup Yogya Kids
Kematangan sosial sebagai tugas perkembangan
Faktor-faktor kematangan sosial anak prasekolah
Metode pembelajaran dengan Natural Growth
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu laporan
mengenai gejala yang diamati, tanpa satu usaha pun untuk
mengindentifikasikan kaitan sebab-musababnya (Chaplin, 2006). Penelitian
deskriptif dilakukan dengan menyajikan data, menganalisis, serta
menginterpretasi (Narbuko & Achmadi, 1991). Penelitian ini juga bertujuan
melihat lebih dalam, secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan
sifat populasi, dalam hal ini bagaimana kematangan sosial yang terjadi pada
anak usia prasekolah dengan menggunakan metode kuantitatif (terukur).
B. Definisi Operasional
Kematangan Sosial Anak Prasekolah
Kematangan Sosial adalah suatu keadaan di mana sesorang sudah
mampu memahami apa keinginannya tanpa dibatasi oleh kehendak orang
lain (mampu memerdekakan dirinya sendiri). Kematangan sosial pada
penelitian ini lebih ditujukan pada kematangan sosial yang terjadi pada
anak-anak, yaitu kemampuan mengungkapkan diri, kemampuan menolong
diri sendiri, memiliki keterampilan sosial yang baik, keterampilan dalam
menyelesaikan tugas-tugas sekolah, keterampilan dalam berbagai jenis
C. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah anak-anak usia prasekolah
(playgroup), dengan usia 3 tahun sampai anak usia lebih kurang 4,5 tahun.
Anak-anak ini tidak bedakan menurut jenis kelaminnya karena dalam hal ini
tidak ada pengkategorian subyek berdasarkan jenis kelamin.
Subyek penelitian dipilih secara purposive sampling yaitu pemilihan
sekelompok subyek didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang
dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat
populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 1986). Dalam hal ini,
subyek penelitian yang dipilih, telah bersekolah di Yogya Kids, minimal
selama 3 bulan sehingga subyek sudah melakukan adaptasi sosial dengan
peers dan lingkungan sekolahnya.
D. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik
gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Achmadi, 1991). Observasi dilakukan
dalam jangka waktu yang terbatas karena yang ingin diungkap dalam
observasi ini hanyalah fenomena spesifik yang berlangsung pada saat-saat
tertentu saja. Alat pengambilan yang digunakan dalam teknik observasi ini
adalah check list. Chek list adalah suatu daftar yang berisi nama-nama
mensistematiskan catatan observasi (Narbuko dan Achmadi, 1991). Berikut
ini adalah pernyataan indikator kematangan sosial yang disusun berdasarkan
Indian Association For Preschool Education, Sue Bradekamp and Carol
Copple, EDT dan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia Dirjen Pendidikan
Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional 2002.
Tabel 3. Daftar Perilaku aspek-aspek kematangan sosial
No. Aspek Perilaku Item
1. Kemampuan mengungkapkan diri
a. Mampu mengucapkan apa yang diminta atau dibutuhkan.
b. Mampu bertanya “apa?” atau “kenapa?” c. Berani menyanyi sendiri di depan kelas. d. Mampu berkata “tidak mau” atau “tidak bisa”
e. Mampu menyatakan perasaannya, baik senang, sedih atau marah.
f. Mampu mnyebutkan nama lengkap
g. Mampu berbicara dengan ucapan yang jelas. h. Mampu berbicara dengan kalimat yang lengkap. i. Mampu menjawab pertanyaan sederhana dengan benar. j. Mampu berbicara dengan guru atau teman mengenai
kegiatan yang sedang dilakukan.
2. Kemampuan menolong diri sendiri.
a. Mampu memakai sepatu sendiri.
b. Mampu memakai atau melepas kaus atau celana sendiri.
c. Mampu memakai kaus kaki sendiri. d. Mampu memakai toilet sendiri. e. Mampu makan sendiri.
f. Mampu membedakan bagian depan atau belakang baju. g. Mampu menggosok gigi dengan benar.
h. Mampu mencuci dan mengeringkan muka serta tangan.
3. Memiliki keterampilan sosial yang baik.
a. Mau memberi salam atau menjawab salam dari dan kepada orang lain.
b. Berani berhadapan dengan orang lain yang baru dikenal.
c. Mau menyebut nama ketika berkenalan dengan orang lain.
d. Mau bermain bersama teman tanpa didampingi pengasuh.
e. Mampu menjalin relasi dengan teman-teman baru. f. Kemauan untuk menolong teman.
g. Mampu menyapa teman-temannya terlebih dahulu. h. Mengenali dan mengingat nama-nama teman sekelasnya.
i. Mampu memulai percakapan dengan teman sebaya. j. Menunjukkan minat terhadap teman sebaya.
4. Keterampilan dalam
menyelesaikan tugas-tugas sekolah.
a. Mampu menggambar dengan pensil warna atau crayon.
b. Memahami satu atau dua perintah sederhana dari guru. c. Mampu membedakan tiga warna dasar: merah, biru
dan kuning.
d. Mampu memgang pensil dengan benar. e. Mampu menempel atau mengelem.
f. Mampu menyebut nama-nama hari (walau tidak berurutan).
g. Mampu mengenali nama-nama bagian tubuh. h. Mampu menyebut nama dan fungsi benda tertentu. i. Mampu mengenali bentuk segitiga, lingkaran, dan
bujur sangkar.
j. Mampu mengembalikan alat-alat permainan setelah selesai bermain.
a. Mampu bermain peran dalam kelompok.
b.Mampu mendengarkan cerita pada saat telling story. c. Menunjukkan kerja sama ketika bermain.
d. Mampu melakukan berbagai jenis permainan yang variatif.
e. Menyukai permainan yang kompetitif, seperti lomba mengumpulkan gambar binatang.
f. Mau bermain secara aktif menggerakkan anggota tubuh seperti menirukan gerakan katak yang sedang melompat.
g. Mampu bermain pasir bersama teman-teman.
h. Mampu menyusun balok menjadi suatu bentuk tertentu, misalnya robot atau pesawat terbang.
i. Kemampuan bermain menyortir warna manik-manik sesuai dengan yang diperintahkan guru.
6. Kemampuan untuk mengontrol emosi
a. Mau berbagi mainan dengan teman.
b. Sudah mampu mengerti konsep antri dan bergiliran. c. Mampu menunjukkan simpati terhadap teman. d. Mau meminta maaf saat berbuat salah.
e. Mampu menunjukkan simpati dan perhatian terhadap teman yang lebih muda.
f. Mampu mengatasi rasa marah dengan cepat.
g. Mau membantu pekerjaan orang dewasa (seperti mengangkat kursi kelas atau matras).
h. Mampu meminta persetujuan dari teman. i. Mampu memberi dorongan kepada teman. j. Mau memaafkan teman yang berbuat salah.
Observasi dilaksanakan selama 4 kali atau 4 hari untuk
masing-masing anak. Jumlah keseluruhan subyek adalah 20 orang dan dibagi dalam
2 kelas, masing-masing kelas berjumlah 10 orang anak. Dalam 1 minggu,
anak dibagi dalam 2 kelas. Kelas B1 berjumlah 10 orang dan masuk kelas
setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada pk. 07.30-pk. 09.30, sedangkan
kelas B2 masuk pada hari yang sama namun pada jam yang berbeda yaitu
pk.10.00-pk.12.00. Pengambilan data hanya 4 kali karena pada hari-hari
tertentu, beberapa siswa tidak masuk kelas sehingga peneliti hanya dapat
mencatat data ketika semua anak masuk kelas. Cara kerja observasi ini
adalah 1 kelas yang terdiri dari 10 orang anak, masing-masing anak akan
diamati oleh 2 orang observer. Check list akan dipegang oleh observer untuk
melihat perilaku tampak atau tidak saat pelajaran berlangsung kemudian
perolehan data masing-masing subyek dapat dicross check antara observer 1
dengan observer 2. Hal ini dimaksudkan untuk melihat konsistensi
perolehan data kedua observer. Cara pemberian skornya adalah berikut:
a. Setiap observer memberi skor 1 (satu) pada setiap perilaku yang tampak.
Kriteria yang dipakai dalam check list ini adalah semakin tinggi
skor yang diperoleh pada setiap item, maka dapat dikatakan subyek memiliki
tingkat kematangan sosial yang tinggi pula.
Sebelum menyusun lembar check list kematangan sosial anak,
peneliti terlebih dahulu membuat blue print berdasarkan pada aspek-aspek
kematangan sosial di atas. Pembuatan blue print bertujuan sebagai acuan
pembuatan item-item pernyataan yang akan mewakili berbagai aspek
kematangan sosial yang akan disusun.
Tabel 4. Blue PrintCheck List Kematangan Sosial
Aspek Item No. Total
Kemampuan mengungkapkan diri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10
Kemampuan menolong diri sendiri. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
10
Memiliki keterampilan sosial yang baik. 21, 22, 23, 24 ,25, 26, 27, 28, 29, 30
10
Keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
10
Keterampilan dalam berbagai jenis permainan (individual atau kelompok).
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
10
Kemampuan untuk mengontrol emosi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
10
Total 60
F. Pertanggung jawaban Mutu 1. Validitas Isi
Validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam
melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat
menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai
dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.
Validitas yang digunakan oleh peneliti adalah validitas isi yaitu
validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis
yang rasional atau professional judgment. Validitas ini ditujukan untuk
melihat sejauh mana item-item dalam tes mencakup keseluruhan
kawasan isi obyek yang hendak diukur. Validitas isi tidak menggunakan
analisis dengan perhitungan statistik apapun. (Azwar, 1997).
2. Seleksi Item
Seleksi item diambil dari hasil uji coba yang sudah dilakukan
pada subyek yang memiliki karakteristik yang setara dengan subyek
yang akan diteliti. Item-item tersebut dievaluasi dengan analisis butir
dengan menggunakan parameter daya beda item yang berupa koefisien
korelasi item total yang memperlihatkan adanya kesesuaian fungsi item
dalam check list mengungkap kematangan sosial.
Berdasarkan data hasil uji coba terhadap 10 subyek dengan
menggunakan 60 item, prosedur analisis item dilakukan dengan
menggunakan koefisien korelasi Pearson dari program komputer SPSS
for windows versi 12. Berikut ini adalah distribusi item check list setelah