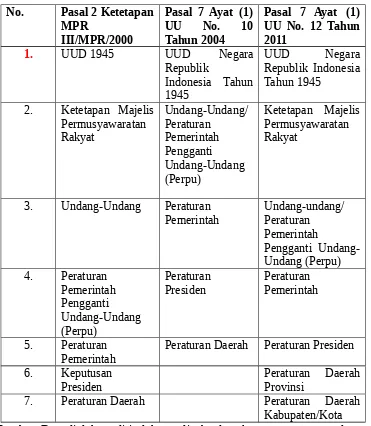KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMABGA CONSTITUTIONAL REVIEW
TERKAIT PUTUSAN MK NO. 138/PUU-VII/2009
ABSTARKSI:
Constitutional review diartikan sebagai pengujian konstitusionalitas dengan batu ujiannya adalah konstitusi atau UUD. Mahkamah Konstitusi di Indonesia menjadi lembaga peradilan konstitusi dan
juga dikenal sebagai lembaga penjaga konstitusi (guardian constitution). Kewenangan yang diberikan secara langsung dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ( UUD NRI 1945) yang mana objek pengujian berupa undang-undang dengan batu uji UUD NRI
1945. Tetapi ketika putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dikeluarkan teradapat kewenangan baru dari
Mahkamah Konstitusi terkait sebagai lembaga constitutional review yakni dapat melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD NRI 1945. Dalam
hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi, menuangkan penafsirannya di
dalam putusan tersebut membuka kewenangan barunya tersebut dengan ada alasan berbeda serta
pendapat berbeda yang masing-masing datang dari hakim konstitusi Mahfud MD dan Muhammad
Alim. Melalui Putusan MK No. 138/PU-VII/2009 memberikan perkembangan pengujian
perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), telah
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak empat kali sejak 1999
hingga tahun 2002. UUD NRI 1945 telah menghasilkan perubahan-perubahan substansial
bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Pemikiran yang dapat diterima atas perubahan UUD NRI 1945 yakni untuk
menghilangkan struktur ketatanegaraan yang selama itu bertumpu pada kekuasaan tertinggi di
tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi sepenuhnya
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, tetapi disebar di masing-masing lembaga negara
menurut fungsinya yang dimuat dalam UUD NRI 1945, mempertegas sistem presidensiil atau
tentang kehidupan bernegara yang demokratis, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat,
penghormatan terhadap HAM, dan otonomi daerah sehingga tercipta praktik penyelenggaraan
negara yang sesuai degan pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945. Bersamaan dengan
perubahan-perubahan tersebut, beberapa lembaga negara baru pun dibentuk, diantaranya
Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satunya perubahan (amandemen) ketiga, tahun 2001 UUD NRI 1945 yakni
adanya perkembangan yang lebih maju dalam politik hukum kekuasaan kehakiman. Pasal 24
ayat (1) UUD NRI 1945 Perubahan merupakan pasal yang memberikan perlindungan
konstitusional independensi kekuasaan kehakiman. Secara eksplisit Pasal ini menyatakan
bahwa ‘Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’. Kekuasan kehakiman yang tersebut
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan
demikian Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kekuasaan kehakiman di samping
Mahkamah Agung (MA) yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan
politik.
Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak
melakukan uji materi (judicial review, atau secara lebih spesifik melakukan constitutional
review) UU terhadap UUD NRI 1945. MK juga mempunyai tugas khusus lain, yaitu memutus
pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD
NRI 1945 sehingga mereka dapat diproses untuk diberhentikan; memutus pembubaran parpol
dan memutus sengketa hasil Pemilu. Sementara MA mengadili perkara-perkara konvensional
ditambah dengan hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap
peraturan perundang-undang lainnya.1 Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, MK
1 Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, h.
menganut prinsip “check and balences” yang menempatkan semua lembaga negara dalam
kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan
memberi kesempatan untuk dapat saling mengkoreksi kinerja antarlembaga negara.2
Dengan adanya MK semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD
NRI 1945 dapat dimintakan judicial review (pengujian yudisial) untuk dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Dapat dikemukakan bahwa MK telah tampil sebagai lembaga negara yang
independen dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan yang sangat mendukung
bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. 3
Permasalahan yang serius dalam kajian kali ini adalah untuk pertama kalinya
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengadili uji materi Perpu, yaitu Perpu No. 4 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Sudah secara eksplisit UUD NRI 1945 memberikan kewenangan
kepada MK seperti yang telah disebutkan, Undang-undang yang menjadi objek pengujian
MK. Dalam perkara pengujian Perpu tersebut merupakan usaha Perhimpunan Advokat
Indonesia Pengawal Konsitusi, sebanyak 13 Pengacara sebagai Pemohon, mempersoalkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4 Tahun 2009 sebagai salah
satu dasar pengangkatan tiga pimpinan KPK sementara. Di dalam pokok perkara para
Pemohon menyebutkan untuk pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 terhadap Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945. Pada pengujian Perpu ini Mahkamah Konstitusi telah menentukan sikap
bersama yang mana sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa mengenai
keberwenangan dari MK untuk memeriksa perkara a quo, yaitu apakah para hakim konstitusi
menganggap dirinya memang berwenang untuk memeriksa perkara atau tidak dan mengenai
legal standing pemohon. Usaha Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (PAIP) Konsitusi
2 Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia, cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.168.
3 Mohammad Fajrul Falaakh dkk, 2008, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu
yang mempersoalkan Perppu No 4 Tahun 2009 memang telah kandas. Karena pada amar
putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Pasalnya, PAIP-Konstitusi dinilai tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum
untuk mempersoalkan Perppu tersebut.
Terjadi suatu kekosongan norma dalam kasus ini, sudah jelas Mahkamah
Konstitusi diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang, apakah bertentangan atau
tidak dengan UUD NRI 1945. Sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan
perundang-undang di bawah perundang-undang-perundang-undang terhadap perundang-undang-perundang-undang. Pengujian suatu Perpu sama
sekali tidak ada yang menyebutkan secara jelas atau eksplisit dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hingga pada akhirnya
pertimbangan-pertimbangan dari para Hakim Konstitusi di dalam putusan 138/PUU-VII/2009, Mahkmah
Konstitusi melakukan penafsiran yang menambah ketentuan kewenangan Mahkamah
Konstitusi tidak hanya berwenangan menguji undang-undang tetapi dapat pula menguji Perpu
terhadap UUD NRI 1945.
Menarik kemudian untuk mengetahui aturan normatifnya Perpu, Perpu adalah
suatu peraturan yang bersifat sementara yang lahir hanya untuk mengatasi keadaan “hal
ikhwal kegentingan yang memaksa”. Karena sifatnya yang sementara itulah Perpu perlu diuji
melalui mekanisme legislative review. Pengujian legislative review ini dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. Perpu yang di tolak oleh DPR maka akan batal atau sudah tidak bisa
menjadi landasan hukum kembali, namun bagi Perpu yang diterima maka akan menjadi UU.4 Sebelum ditetapkan perubahan atas Pasal 24 UUD NRI 1945 pernah dikeluarkan
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 berisi hierarki peraturan perundang-undangan yang
menempatkan Perpu di bawah UU dan karenaya dapat dilakukan uji materi atasnya oleh
Mahkamah Agung.5 Kemudian di dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (saat pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 masih
4 Zaid Mushafi, 2010, Pengujian Perpu JPSK oleh Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 18 Maret
2011, URL: http://mushafi27.blogspot.com/search/label/Mahkamah%20Konstitusi, h. 1.
berlaku), yang disebut sebagai perturan perundang-undangan mencakup bentuk-bentuk yang
hirarkis di mana urutan 2 (dua) setelah UUD NRI 1945 yakni undang-undang/Perpu.
Sedangkan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) menempatkan Undang-undang/Perpu pada urutan 3 (tiga)
di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan dan UUD Negara Republik Indonesia.
Akan tetapi, jika urutan di bawah undang-undang, timbul masalah hukum yang
menyulitkan karena Perpu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Padahal, perpu
itu justru diperlukan untuk maksud yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang
ada. Oleh karena itu, tidak dapat tidak, kedudukannya memang sudah seharusnya sederajat
dengan undang-undang, tetapi namanya Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah
sebagai Pengganti Undang-undang yang disingkat dengan PERPU atau kadang-kadang
disingkat PERPPU.6
Lihat ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 bahwa, Perpu itu hanya bentuk peraturan
yang bersifat sementara, yaitu sampai persidangan DPR berikutnya melalui mana pemerintah
dapat mengajukan Perpu itu untuk mendapat persetujuan DPR. Jika Perpu itu telah mendapat
persetujuan DPR sebagaimana mestinya, maka dengan sendirinya bentuknya akan berubah
menjadi Undang-Undang, sedangkan jika tidak mendapat persetujuan Perpu itu harus dicabut. Dibukanya kewenangan MK menguji Perpu ini tidak diambil secara bulat. Hakim
Konstitusi Muhammad Alim menegaskan:
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan kewenangan MK untuk 'menguji undang-undang terhadap UUD pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas menguji Undang Undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perppu, menurut saya dilaksanakan tidak menurut UUD, melainkan dilaksanakan menyimpang dari UUD.7
6 Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta,
(selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I) h. 33.
7 Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi, 2010, Judicial Review Perpu oleh MK,
Uji materi yang diajukan Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi itu
memang diakhiri dengan amar putusannya MK bahwa tidak dapat diterima. Sebab, pemohon
dianggap tak memiliki kedudukan hukum. Bagaimanapun juga bahwa pengujian Perpu untuk
petama kalinya tersebut telah dikeluarkan putusan MK, yang mana MK berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan yang bersifat final. Namun terlepas dari dalam
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit dikatakan bahwa MK
dapat menguji Perpu dan soal benar atau salah putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum
tetap itu mengikat dan karenanya harus diikuti atau dilaksanakan.
PEMBAHASAN:
1. Constitutional Review
Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri
dari perkataan pengujian dan peraturan perundang-undangan. Pengujian berasal dari
akar kata uji yang memiliki arti perobaan untuk mengetahi mutu sesuatu, sehingga
‘pengujian’ diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengujian.8 Sedangkan
peraturan perundang-undangan dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Terlihat dari pengertian tersebut
yang penting ada 2 hal yakni berkaitan dengan siapa (subjek) yakni siapa yang
diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pengujian peraturan
perundang-undangan dan apa (objek) yakni objek norma hukum yang akan dilakukan
pengujiannya.
8 Zainal Arifin Hoesein, 2009, Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian
Dalam bahasa Belanda ada dikenal toetsingrecht: Toet’sen, toetste, h getoets
yang masng-masing mempunyai arti menguji kadar nilai (dengan batu ujian atau
jarum uji); mencoba; menyelidiki kebenarannya (keaslian atau kemurniannya).9 Tentu
itu memperjelas bahwa toetsingrecht merupakan suatu proses untuk melakukan
pengujian atau menguji dan secara harfiah diartikan sebagai kewenangan untuk
menguji. Pengertian dari toetsingrecht jika dibandingkan dengan judicial review lebih
luas. Lihat pada subyek atau siapa yang diberikan kewenangan untuk melakukan
pengujian tentu toetsingrecht dapat diberikan kepada lembaga yudisial, eksekutif dan
legislatif. Jika diberikan kepada lembaga yudisial dengan demikian disebut sebagai
judicial review.Artinya adalah pengertian dari toetsingrecht dalam perspektif judicial
review dapat diartikan sebagai toetsingrecht dalam arti sempit atau uji judicial yang
subyeknya tertentu dan dapat mencakup pengertian luasnya yakni tidak saja menguji
atau menyangkut segi-segi konstitusionalitas obyek yang diuji, melainkan
menyangkut pula segi-segi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di
bawah UU.
Constitutional review atau pengujian konstitusional harus pula dibedakan
dengan judicial review, antara keduanya pun terletak perbedaan yakni dari segi
subyeknya atau siapa yang berwenangan melakukan pengujian dari constitutional
review tentu lebih luas dibandingkan dengan judicial review yang kewenangannya
diberikan kepada lembaga yudisial. Constitutional review selain hakim dapat pula
dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga
mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Dari segi obyeknya,
judicial review mencakup soal legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU,
9 S. Wojowasito, 2003, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT Ichtiar Baru Vn Hoeve, Jakarta, h.
sedangkan constitutional review hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya,
yaitu terhadap UUD.10
Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa, apabila norma yang diuji
itu menggunakan undang-undang sebagai batu ujian, misalnya Mahkamah Agung
menurut Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 berwenang mengui peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undnag terhadap undang-undang, pengujian semacam itu
tidak dapat disebut sebagai constitutional review, melainkan judicial review on the
legality of regulation. Di samping itu, harus dibedakan pula kualifikasi dari norma
hukum yang diuji. Jika normanya bersifat umum dan abstrak (general and abstract),
berarti norma yang diuji itu adalah produk regeling, dan hal ini termasuk wilayah
kerja pengujian dalam konteks hukum tata negara. Akan tetapi, kalau norma hukum
yang diuji itu bersifat kongkret dan individual, maka judicial review semacam itu
termasuk lingkup peradilan tata usaha negara.11
Di setiap negara, konsep-konsep judicial review itu sendiri berbeda-beda
cakupan pengertiannya satu sama lain. Oleh karena itu, pengertian istilah-istilah itu
juga tidak boleh diidentikkan antara di satu negara dengan negara lainnya.
Perkemabgan pengujian konstitusisionalitas semakin luas seiring dengan tradisi
menganut konsep konstitusi sebagai ukuran penyelenggaraan kegian bernegara di
dunia, seingga sangat diperlukanlah adanya pengujian kosntitusionalitas tersebut
dalam rangka melindungi dan mengawal pelaksaan hukum dan konstitusi dalam
praktik sehari-hari di tiap negara-negara yang menganutnya.
Di beberapa negara pembentukan Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang
menjalankan fungsi sebagai atau seperti Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah
Agung, yang pada prinsipnya dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:
a. Negara yang mengikut pola Jerma, yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung;
10 Jimly Asshiddiqie, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Sinar
Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II) h. 2.
b. Negara yang mengikuti pola Prancis yang tidak menyebutkan dengan istialh court (pengadilan), tetapi hanya dewan, yaitu couseil constitutionnel (constitutional council), misalnya Aljazzair;
c. Negara yang mengikuti pola Belgi, yaitu constitutional arbitrage (arbitrasi konstitusional).12
Penempatan pengaturan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di
dalam UUD NRI 1945 menjadi sangat penting dan strategis karena hal ini tentu
berkaitan dalam hal pertama penjamian berfungsinya sistem demokrasi dalam
hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang legislatif, eksekutif dan
yudikatif dan kedua untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan
kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang
dijaimn dalam UUD NRI 1945.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di dasarkan pada ketentuan UUD
Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 24C ayat (1) sebagai berikut:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
dan pengaturan lebih lanjut pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat
dilihat di dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8
Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara
Pengujian Undang-undang (PMK No. 06/PMK/2005).
2. Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Pengujian Perpu
Objek pengujian peraturan undangan adalah peraturan
perundang-udnangan yang bersifat mengatur (regeling)13, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “peraturan
perudnang-undangan adalah praturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan.”
Berikut akan ditunjukkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undang di
Indonesia:
Tabel 1
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undang Indonesia yang pernah dan sekarang berlaku
No. Pasal 2 Ketetapan MPR
III/MPR/2000
Pasal 7 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004
Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011
1. UUD 1945 UUD Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945
UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang Peraturan
Pemerintah Undang-undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Peraturan Presiden
6. Keputusan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber: Data diolah sendiri oleh penulis, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.
Pahan hierarki norma tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum yang rendah
tinggi. Sifat betentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya
laku hukum itu. sebaliknya. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya,
semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya. Sebaliknya semakin
rendah peringkatnya, maka semakin nyata sifat norma yang dikandungnya. Menjaga
posisi konstitusi sebagai hukum dasar, sangat diperlukannya suatu instrumen hukum
yang memberikan kekuasaan tertentu untuk menilai dan menetapkan bahwa apakah
suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dari materi
muatannya bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI
1945. Dapat melakukan pengujian secara formal dan/atau pengujian materiil14 dari
suatu undang-undang terhadap UUD. Undang-undang sebagai peraturan yang bersifat
mengatur atau (regelings) dan merupakan salah satu bentuk peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 20 UUD Negera Republik Indonesia 1945
memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk
undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah dan di dalam Pasal 5
ayat (1) Presiden diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada
DPR. Serta di dalam ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada DPR rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Undang-undang
14 Pasal 4 Ayat (2) PMK No.6/PMK2005 “pengujian materiil adalah pengujian undang-undang
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan persetujuan bersama Presiden”.
Setelah dikeluarkannya putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 MK tak hanya
dapat menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat pula melakukan
pengujin suatu Perpu terhadap UUD NRI 1945. Tidak adanya frasa kata “pengujian
Perpu” dalam penjabaran kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat
(1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran-penafsiran
secara sistematis, gramatikal, historis/ sejarah dan teleologis atau sosiologis dengan
tidak melepas tafsiran dari alasan dan pendapat berbeda yang terdapat dalam putusan
138/PUU-VII/2009. Pengaturan penemuan hukum di Indonesia memang tidak secara
tegas diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, menentukan kewenangan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan
dalam memeriksa dan mengadili perkara atau kasus konkret. Pasal 5 ayat (1) UU
Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) menentukan bahwa “Hakim dan
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadillan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan apa yang telah disebutkan
dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dilihat hal itu menunjukkan bahwa
Hakim Indonesia haruslah berfikir yuridis secara sistematis-problematik.
Lebih lanjut pendapat dari H. Mucshin dapat dipahami bahwa mengenai
legitimasi penemuan hukum oleh hakim Indonesia yang disebut pula dasar hukum
penemuan hukum oleh hakim ada tiga dasar, mencakup: (1) asas ius curia novit
(hakim yang paling tahu hukum); (2) asas hakim mengisi kekosongan hukum; dan (3)
asas hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.15 Seperti
yang telah dijabarkan diatas bahwa terlihat metode yang dilakukan dalam
pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dikatakan mengacu pada
15 I Dewa Gede Atmadja, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal
metode penemuan hukum yang memiliki beberapa teknik interpretasi atau penafsiran
tetap mengembalikkan pada original intens dalam UUD NRI 1945. Serta dengan
suatu interpretasi yang dikatakan ekstensif atau penafsiran secara luas dan melakukan
suatu konstruksi hukum dengan tiga jenis metode yang salah satunya adalah dengan
melakukan suatu analogi16. Bahkan lebih jauh lagi penafsiran dari para hakim MK
yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja menjadi suatu
pelaksanaan mengubah beberapa ketentuan dalam UUD NRI 1945. Yang dilakukan
oleh Hakim Konstitusi ini di dalam bidang Hukum Tata Negara ada dikenal judicial
interpretation17 (penafsiran oleh hakim), dapat berfungsi sebagai metode perubahan
konstitusi dalam arti menambah, mengurangi atau memperbaiki makna yang terdapat
dalam suatu teks UUD. Karena sebagai lembaga constitutional review, Mahkamah
Konstitusi dalam melakukan penilaian terhadap sebuah undang-undang, agar
bersesuai dengan UUD NRI 1945, harus memaknai serta menafsirkan UUD NRI 1945
itu sendiri.
Seperti putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai uji konstitusionalitas
UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah
Konstitusi menafsirkan bahwa para Hakim Konstitusi tidak termasuk makna hakim
yang terdapat di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Menurut Mahkamah
Konstitusi Hakim Agung merupakan bagian dari Pasal 24B UUD NRI 1945, bunyi
Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945 secara tidak langsung setelah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi: “Komisi Yudisial berisfat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
16 “Analogi, suatu bentuk penalaran yang dapat dikatakan dengan memperluas berlakunya suatu
pasal dari aturan hukum atau UU terhadap peristiwa hukum yang eksplisit (jelas-jelas) tidak disebut dalam aturan hukum dimaksud”. Lihat: Ibid, h. 48.
17 K.C Wheare mengemukakan bahwa perubahan undang-undang dasar melalui penafsiran secara
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marabat, serta
perilaku hakim, kecuali Hakim Konstitusi”. Dengan demikian, Putusan MK No.
138/PUU-VII/2009 secara tidak langsung membuat Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI
1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat fisnal untuk menguji undang-undang/perpu terhadap
undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lemabga negara yang
kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Pengaturan Perpu di dalam UUD NRI 1945 yakni Pasal 22 ayat (1) yang
berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dalam Pasal 22 ayat (2)
dinyatakan, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikut”, dan ayat (3)-nya menentukan, “Jika tidak
mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Pasal 1 angka 4
UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Di dalam hierarki peraturan
perundang-undangan yang berlaku sekarang (UU No. 12 Tahun 2011) dan atau pada saat
pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 diajukan (UU No. 10 Tahun 2004) sama-sama
mempertahankan posisi Perpu itu sama atau sederajat dengan Undang-undang. itu pun
dijadikan alasan pengajuan pengujian Perpu kepada MK oleh para Pemohon yang
terdiri dari 13 advokat. Kedudukan yang sama dengan UU karena Perpu secara materi
muatan sama dengan undang-undang (lihat Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2012)18. Pasal
18 Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 “Materi muatan Perpu adalah sama dengan materi muatan
22 berada dalam ranah pengaturan, yang berisi norma pengecualian atas fungsi
kekuasaan legslatif. Artinya adalah Presiden menetapkan Perpu itu berpandangan
adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang harus segera mungkin diselesaikan
tanpa memerlukan waktu panjang atas proses pembentukan suatu undang-undang
secara konstitusional. Suatu Perpu melahirkan norma hukum di mana norma tersebut
tergantung dari persetujuan DPR apakah akan menerima atau menolak norma hukum
tersebut akan tetapi pada renggang waktu sebelum diajukannya kepada DPR tersebut
Perpu masih menimbulkan norma hukum yang materi muatannya sama dengan
undang-undang begitu pula dengan fungsinya sama dengan undang-undang. Namun,
dengan pandangan subyektif Presiden dalam menetapkan Perpu itu jangan sampai
Presiden menetapkannya dengan sewenangan-wenang hingga misalnya menimbulkan
korban ketidakadilan yang sangat serius.
Jika Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan atau
menjalankan undang-undang, ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah tersebut
berkedudukan lebih rendah dari undang-undang. Pihak lain, Perpu ditetapkan oleh
Presiden dengan syarat apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Di samping itu,
Peraturan Pemerintah ini dengan tegas dikatakan sebagai Pengganti Undang-undang.
Ini berarti, bahwa Perpu sederajat dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat
menarik kesimpulan, bahwa meskipun kedua peraturan di atas ditetapkan oleh
Presiden akan tetapi antara keduanya tidak sederajat19, sehingga Mahkamah Agung
tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Perpu, dan hanya berwenang
untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menyatakan
bahwa aturan normatif Perpu di dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, haruslah dilihat
secara keseluruhan dari Perubahan I hingga IV. Mahkamah Konstitusi menemukan
bahwa Pasal 22 terletak di dalam Bab VII UUD NRI 1945 tentang DPR, hal tersebut
menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 22 erat hubungannya dengan kewenangan DPR
dalam pembuatan undang-undang. Mahkamah Konstitusi pun membedakan antara
Peraturan Pemerintah (Pasal 5 Aayat (2) UUD NRI 1945) dengan Perpu (Pasal 22).
Karena Perpu diatur di dalam Bab tentang DPR dan DPR adalah lembaga pembentuk
udnang-undang maka materi muatan dari Perpu itu seudah seharusnya adalah materi
muatannya yang menurut UUD diatur dengan undang-undang, bukan materi muatan
yang melaksanakan undang-undang (Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945).
Mengenai kegentingan yang memkasa dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI
1945 perlu juga membedakan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI 1945.
Mahkamah Konstitusi menyatakan benar bahwa keadaan bahaya dapat pula
menyebabkan pembentukan suatu Undang-undang secara biasa atau normal tidak
dapat dilaksanakan. Namun, keadaan bahayalah bukanlah satu-satunya keadaan yang
menyebabkan timbulnya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945.
Sesuatu yang membahayakan tentu selalu memiliki sifat yang menimbulkan
kegentingan yang memaksa, tetapi segala hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak
selalu membahayakan. Artinya adalah kegentingan yang memaksa mempunyai
cakupan yang lebih luas dibandingkan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI
1945. Dalam keadaan bahaya menurut Pasal 12, Presiden dapat menetapkan Perpu
kapan saja diperlukan, tetapi penetapan Perpu oleh Presiden itu tidak selalu harus
berarti ada keadaan bahaya lebih dulu. Artinya dalam kondisi negara dalam keadaan
normal pun, apabila memang memenuhi syarat, Presiden dapat saja menetapkan suatu
Perpu.20 Lebih lanjut pendapat dari Jimly Asshiddiqie dalam buku Hukum Tata
Negara Darurat. Beliau menyatakan bahwa:
20 Jimly Asshiddiqie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Ketentuan mengenai keadaan bahaya yang ditentukan dalam Pasal 12 jelas lebih menekankan sifat bahaya yang mengancam (dengerous threat), sedangkan kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Di satu pihak ada unsur resonable necessity, tetapi di pihak lain terhadap kendala limited time. Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting yang secara bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu:
1. Unsur ancaman yang membahayakan (dengerous threat);
2. Unsur kebutuhan yang mengharuskan (resonable necessity); dan 3. Unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.21
Mahkamah Konstitusi pun menyatakan bahwa Perpu itu diperlukan apabila 1)
adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum
secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut
belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak
memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat
undang-undang secara prosedur konstitusi atau biasa karena akan memerlukan waktu
yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum
untuk diselesaikan. atas pernyataan tersebut di atas kesimpulan yang dapat diterima
adalah frasa “Presiden berhak” memang terkesan bahwa pembuatan Perpu itu menjadi
sangat subjektif karena menjadi hak dan sepenuhnya penilaian dari Presiden. Namun
bukan berarti bahwa secara absolut tergantung pada penilian subjektif Presiden.
Karenanya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penilaian subjektif Presiden
harus didasarkan pula pada keadaan yang objektif yaitu adanya 3 (tiga) syarat sebagai
parameter adanya kegentingan yang memaksa.
Terakhir pada pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru Perpu akan
melahirkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, (c) akibat hukum baru.
Norma hukum baru lahir begitu Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut
sangat bergantung kepada DPR apakah akan menolak atau menerima Perpu. Namun
meski DPR akan menjadi penentu diterima tidaknya Perpu, sebelum dibahas oleh
DPR norma yang menjadi kandungan Perpu sah dan berlaku sebagai UU. Karena
kekuatan mengikatnya sama dengan UU itulah maka Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas
Perpu sebelum Perpu itu ditolak atau disetujui oleh DPR sebagai UU. Mahkamah
Konstitusi juga berwenang menguji konstitusionalitas Perpu setelah adanya
persetujuan DPR atas Perpu tersebut karena Perpu telah menjadi UU.
Perlu pula untuk mengetahui alasan berbeda (concurrent opinion22) di dalam
Putusan No. 138/PUU-VII/2009 karena alasan berbeda tidak akan terlepas dari
putusan hakim yang telah dijatuhkan, berikut alasan berbeda di dalam Putusan MK
No. 138/PUU-VII/2009 yang berasal dari Mahfud MD yang pada akhirnya Perpu
dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945:
1. Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.
2. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat
22 “jika pendapat berbeda itu mempunyai kesimpulan pada amar putusan yang sama, tetapi alasan
diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. 3. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan,
sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.
4. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.
Alasan berbeda dari Hakim Konstitusi Mahfud MD memberikan peranan
penting dalam penetapan kewenangan Mahkamha Konstitusi dapat melakuan
pengujian Perpu terhadap UUD NRI 1945. Pandangan atau tafsiran yang penuh
dengan tafsir teleologis23 atau sosiologis24, membuka kewenangan baru atau mengisi
kekosongan hukum yang terjadi dalam praktik ketata negaraan.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam surat kabar KOMPAS
menyatakan, sebagai berikut:
23 “Penafsiran ini difokuskan penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan
jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruh interpretasi.... juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatn aktual.” Lihat: Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretarait Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarata (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie IV), h. 296-297.
24 “Menurut Utrect, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penfsiran sosiologis
Perpu menjadi fasilitas efektif bagi Presiden untuk mengubah undang-undang sesuai dengan kepentingan jangka pendeknya. Perpu bisa dipakai semena-mena, semau-maunya Presiden. Kapan saja, ia bisa melanggar undang-undang dengan Perpu. Ketentuan ini sangat berbahaya, Perpu akhirnya berpotensi disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Misalnya Presiden butuh melakukan sesuatu hal dalam jangka satu bulan ke depan, tetapi UU tak mengizinkan, Perpu menjadi jalan paling efektif meski kemudian ditolak DPR.25
Jika korban yang hak atau kewenangan konstitusionalnya nyata-nyata memang
dirugikan oleh berlakunya Perpu itu mengajukan permohonan perkara pengujian
kepada Mahkamah Konstitui, maka tidak ada alasan bagi lembaga pengawal
konstitusi ini kecuali memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian
konstituisonalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu atau
Perppu) itu sebagai undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin) dengan
cara yang sebaik-baiknya menurut UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.26 Tetap meyakini bahwa munculnya peradilan konstitusi
dipahami sebagai mekanisme pengendalian kebijakan negara yang diwujudkan serta
dilaksanakan oleh produk peraturan perundang-undangan itu sendiri (UU/ Perpu). Terdapat pula perbedaan pendapat (dissenting opinion27) dari salah satu hakim
konstitusi yakni Muhammad Alim:
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap UUD.” Pada waktu dirumuskannya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dilakukan pada Perubahan Ketiga (2001), tetapi hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” (tanpa menyebut perppu), dan tata urutan perundang-undangan Indonesia yang dipakai adalah menurut Tap MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
25 Susana Rita K, “Dari KPK, Cegah Inflansi Perpu Untuk Lima Tahun ke Depan”, Kompas, Selasa,
29 September 2009, h. 5.
26 Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat
Jimly Asshidiiqie V) h. 62.
27 ”pertanggungjawaban hakim secara individual lebih tinggi dibandingkan pertanggungjawaban
Urutan Perundang-Undangan adalah: UUD 1945; Tap MPR; Undang-Undang; Perppu, dst.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD”. Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat,
harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Pasal Pelaksanaan pengujian
hukum oleh kekuasaan kehakiman dilakukan karena terdapat potensi bahwa produk
hukum (undang-undang) dapat saja bermuatan hal-hal yang bertentangan atau
bersebrangan dengan jiwa hukum dasar. Sehingga hukum (undang-undang) sebagai
suatu tata nilai seyogyianya dikendalikan oleh UUD NRI 1945 tetapi jika secara
teoritis karena undang-undang merupakan produk legislasi itu dihasilkan oleh
lembaga politik, sehingga dapat saja substansinya sarat akan pesan-pesan jangka
pendek kekuasaan belaka.
Perkembangan pengujian peraturan perundang-undangan yang maju dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi ini, menunjukkan peranan yang penting dari adanya
Mahkamah Konstitusi di suatu negara yang menganut atau merupakan negara hukum.
jangan sampai dalam setiap detiknya ada peraturan perundang-undangan (UU &
Perpu) itu melanggar ketentuan dasar di dalam UUD NRI 1945. Pengujian Perpu
adalah hal baru maka Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pelaksanaan
kewenangan menguji Perpu mengacu kepada bagaimana pengaturan pengujian
undang-undang di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang. Mahkamah Konstitusi
hanyalah dapat membatalkan segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh organ
pembentuk UU dan Perpu, dengan satu syarat jika dinilai bertentangan dengan
bahwa DPR dan Pemerinah sebagai pembuat norma sedangkan Mahkamah Konstitusi
sebagai penghapus atau pembatal norma.
PENUTUP
Mahkamah Konstitusi tampil sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan
secara langsung oleh UUD NRI 1945 (Pasal 24C Ayat (1)). Salah satu kewenangannya
adalah sebagai lembaga penguji kosntitusionalitas atau constitutional review. Obyek
pengujian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Undang-undang dan Perpu
terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum atas
permohonan pengujian Perpu pertama kali yang diajukan dan menjadi perluasan bunyi
frasa “pengujian undang-undang” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia. Hal ini menjadi perkembangan baru dalam bidang pengujian peraturan
perundang-undangan terutama yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA
(1) BUKU
Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, 1983, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
I Dewa Gede Atmadja, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning and Legal Argumentation an Introduction),BaliAga, Denpasar.
_______, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarata.
_______, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
_______, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
_______, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
Mohamad Fajrul Falaakh, 2008, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi,Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
S. Wojowasito, 2003, Kamus Umum-Belanda Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Sri Soemantri, 1986, Hak Menguji Material Di Indonesia, Alumni, Bandung.
Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2011, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarata.
Zainal Arifin Hoesein, 2009, Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Rajawali Pers, Jakarta.
(2) ARTIKEL
Susana Rita K, “Dari KPK, Cegah Inflasi Perpu untuk Lima Tahun ke Depan”, Kompas, 29 September 2009.
Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal, 2010, Judicial Review Perpu oleh MK,
diakses tanggal 17 Maret 2011, URL: