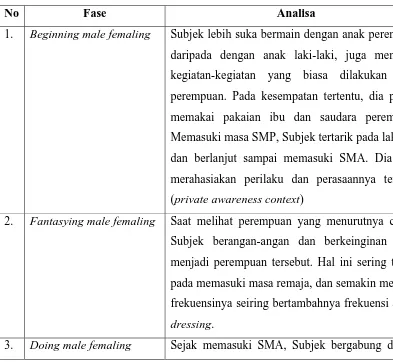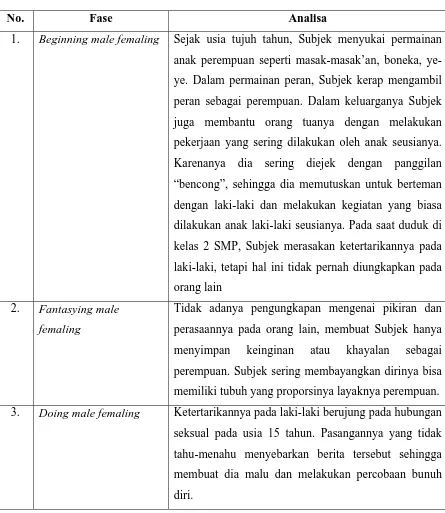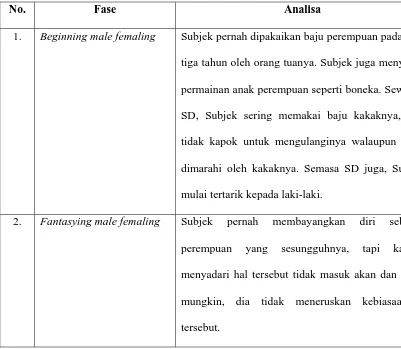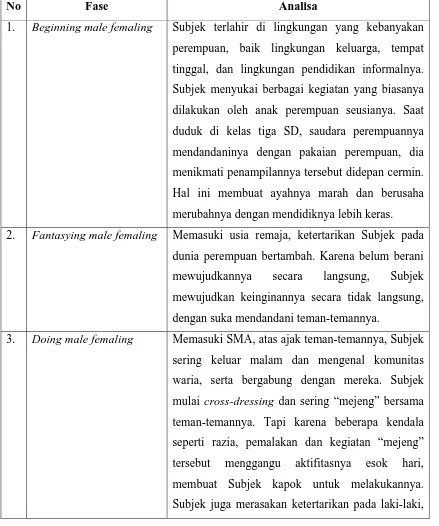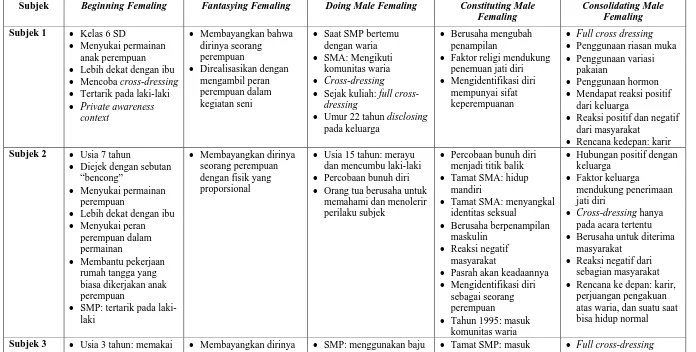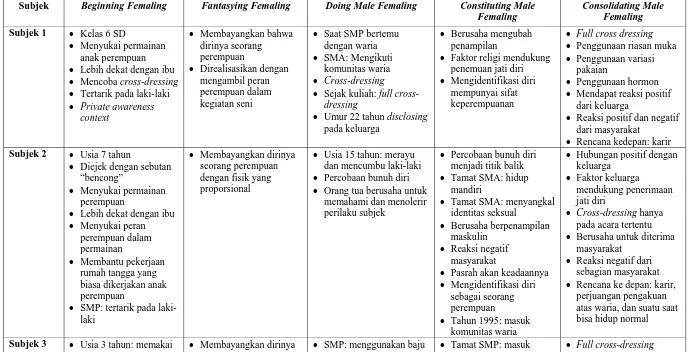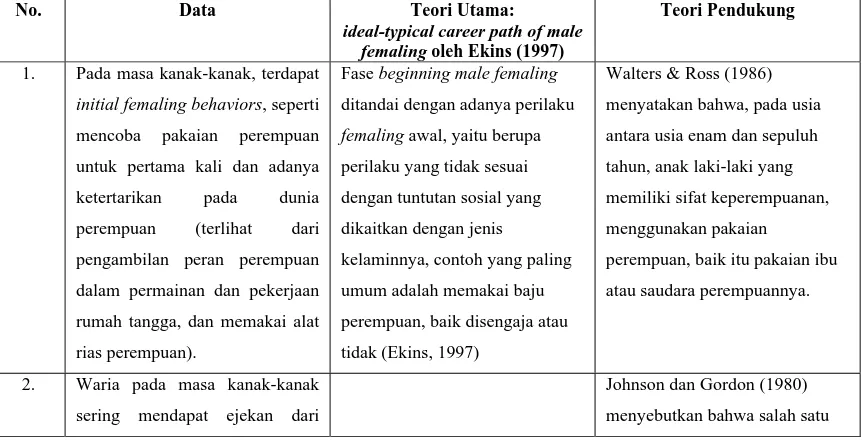IDEAL-TYPICAL CAREER PATH OF MALE FEMALING
PADA WARIA
SKRIPSI
Guna memenuhi persyaratan
Ujian Sarjana Psikologi
Oleh:
NAOMI ELISABETH LUMBANTOBING
031301058
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan
anugrahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrpsi ini. Skripsi yang
berjudul, “Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Waria”, merupakan
tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan.
Proses pelaksanaan penelitian ini membantu penulis untuk belajar lebih
dalam mengenai waria, khususnya fase-fase “menjadi waria” (ideal-typical career
path of male femaling) pada waria. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan, serta masukan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K), selaku Rektor
Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak dr. Chairul Yoel, Sp. A (K), selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Irmawati, Psikolog, selaku dosen pembimbing. Penulis
mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan semangat
yang diberikan, selama penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Rika Eliana, M.Psi dan Ibu Arliza J. Lubis, yang telah bersedia
menjadi penguji sekaligus pembimbing dalam menyempurnakan skripsi
5. Ibu Dra. Sri Mulyani Nasution, selaku dosen penasehat akademik penulis,
yang selalu sabar memberi dukungan dan arahan selama masa perkuliahan
penulis berlangsung.
6. Kedua orang tua penulis, T. Lumbantobing dan T Siahaan, buat seluruh
doa dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, Daniel, Bertha,
Christine dan Simon yang telah memberi dukungan dan doa yang tak
berkesudahan dalam hidup penulis.
7. Kelima partisipan yaitu, Kak Wenny, Kak Ilo, Dara, Kak Deri dan Intan
atas kesediannya menjadi partispan dalam skripsi ini.
8. Tari, Nda, Melda, Cory, Sondang, Titin, Nouva, Jay, Devi, Astri, Rospit,
Reni, atas seluruh dukungan dan dorongan semangat. Kepada Kak Vey,
Kak Devi, Kak Tika, Kak Ganda, atas seluruh bantuannya dalam
penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman penulis dan pihak lain, yang mendukung penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
Sebagai manusia yang masih dalam proses belajar, penulis menyadari
kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.
Medan, April 2008
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ... v
BAB I PENDAHULUAN I.A. Latar Belakang Masalah ... 1
I.B. Perumusan Masalah ... 8
I.C. Tujuan Penelitian ... 9
I.D. Manfaat penelitian ... 9
I.E. Sistematika Penulisan ... 9
BAB II LANDASAN TEORI II.A. Waria II.A.1. Pengertian Waria ... 11
II.A.2. Kriteria Diagnostik Waria ... 12
II.A.3. Etiologi Waria... 13
II.B. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling ... 16
BAB III METODE PENELITIAN III.A. Pendekatan Kualitatif ... 21
III.B. Metode Pengumpulan Data ... 22
III.B.1. Wawancara ... 23
III.B.2. Observasi ... 23
III.C. Alat Bantu Pengumpul Data ... 24
III.D. Subjek Penelitian ... 25
III.D.1. Kriteria Subjek Penelitian ... 25
III.D.2. Jumlah Subjek Penelitian ... 26
III.D.3. Prosedur Pengambilan Subjek Penelitian ... 27
BAB IV ANALISIS DATA
IV.A. Analsis Data Subjek 1
IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 1 ... 29
IV.A.2. Data Observasi Subjek 1 ... 31
IV.A.3. Data Wawancara Subjek 1 ... 34
IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling
pada Subjek 1 ... 49
IV.B. Analsis Data Subjek 2
IV.B.1. Gambaran Umum Subjek 2 ... 55
IV.B.2. Data Observasi Subjek 2 ... 57
IV.B.3. Data Wawancara Subjek 2 ... 59
IV.B.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling
pada Subjek 2 ... 74
IV.C. Analsis Data Subjek 3
IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 3 ... 81
IV.A.2. Data Observasi Subjek 3 ... 83
IV.A.3. Data Wawancara Subjek 3 ... 85
IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling
pada Subjek 3 ... 94
IV.D. Analsis Data Subjek 4
IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 4 ... 100
IV.A.2. Data Observasi Subjek 4 ... 102
IV.A.3. Data Wawancara Subjek 4 ... 104
IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling
pada Subjek 4 ... 117
IV.E. Analsis Data Subjek 5
IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 5 ... 124
IV.A.2. Data Observasi Subjek 5 ... 126
IV.A.3. Data Wawancara Subjek 5 ... 128
IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling
BAB V KESIMPULAN, DISKUSI, DAN SARAN
V.A. Kesimpulan ... 150
V.B. Diskusi ... 160
V.C. Saran ... 174
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Gambaran Umum Subjek 1 ... 29
Tabel 2. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 1 ... 53
Tabel 3. Gambaran Umum Subjek 2 ... 55
Tabel 4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 2 ... 78
Tabel 5. Gambaran Umum Subjek 3 ... 81
Tabel 6. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 3 ... 98
Tabel 7. Gambaran Umum Subjek 4 ... 100
Tabel 8. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 4 ... 122
Tabel 9. Gambaran Umum Subjek 5 ... 124
Tabel 10. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 5 ... 148
Tabel 11. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian ... 157
BAB I
PENDAHULUAN
I.A. Latar Belakang Masalah
Dunia waria, wadam atau banci, merupakan bentuk kehidupan yang unik
bagi banyak orang. Secara fisik mereka adalah laki-laki normal, memiliki kelamin
yang normal, namun mereka merasa dirinya perempuan, dan berpenampilan tidak
ubahnya seperti kaum perempuan lainnya (Koeswinarno, 2004). Menurut data
Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri,
jumlah waria di Indonesia tahun 2005 lalu, mencapai 400.000 jiwa. Jumlah ini
masih berupa fenomena gunung es, karena masih banyak waria yang belum
masuk dalam hitungan, dan disinyalir angka ini akan terus bertambah setiap
tahunnya (Sujatmiko dalam Tempointeraktif, 2005).
Sebagai individu maupun mahluk sosial, waria berusaha untuk mendapat
bagian dalam berbagai ruang sosial (Koeswinarno, 2004). Berbagai cara mereka
lalui untuk mendapat pengakuan atas keberadaan mereka, diantaranya adalah
munculnya penyelenggaraan kontes Miss Waria, baik di tingkat daerah maupun
nasional dan munculnya berbagai figur waria ke permukaan, baik melalui keahlian
dan kecerdasan mereka. Munculnya berbagai figur waria ke permukaan
merupakan langkah awal usaha untuk diterima di masyarakat. Baik melalui
keahlian, kecerdasan dan lain sebagainya. Sebut saja Merlyn Sopjan, seorang
penulis buku ”Jangan Lihat Kelaminku”. Waria lulusan Institut Teknologi
Malang mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tahun 2003.
Waria cantik kelahiran Kediri ini bahkan dianugerahi gelar Doktor HC dari
Northern California Global University Amerika karena keterlibatannya sebagai
aktivis sosial HIV/AIDS. Ketua Ikatan Waria Malang ini pernah menyandang
gelar Ratu Waria Indonesia 1995 (Suara Merdeka dalam STUDIA, 2006). Megie
Megawatie, adalah waria yang berjuang keras agar kaumnya tidak terpinggirkan,
yaitu melalui kontes waria. Selain itu, ada Shunniyah R.H, waria berkerudung,
yang menulis buku”Jangan Lepas Jilbabku.” Dia adalah alumni Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan sosial politik dengan predikat Cum Laude,
yang menyelesaikan bangku kuliah dalam waktu hanya 3 tahun 40 hari
(Muslichan, Wiramada, & Galih dalam Indosiar ”Hitam Putih”, 2006).
Namun, sampai saat ini, waria masih mendapat perlakuan yang negatif
dari berbagai pihak. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki
pemahaman atau konsep yang salah mengenai kaum minoritas ini (Yash, 2003).
Dalam masyarakat, sebagian besar waria dikenal keberadaannya karena mereka
kerap beraksi menghentikan kendaraan yang melintas di sejumlah pinggir jalan
Jakarta, seperti di kawasan Menteng Jakarta Pusat yang mereka sebut ”teli” atau
”taman lawang”, kawasan Jalan Brawijaya Jakarta Selatan, serta ”kawasan
boker”, Jalan Raya Bogor. Mereka-mereka inilah sebagai penjaja kenikmatan
untuk mengumpulkan rupiah (Muslichan, Wiramada, & Galih dalam Indosiar
”Hitam Putih”, 2006). Konstruksi sosial masyarakat selama ini terbiasa melihat
kehidupan waria yang selalu identik dengan dunia pelacuran atau prostitusi.
penolakan terhadap keberadaan waria (Nadia, 2005). Begitu juga dari segi religi,
secara umum agama-agama besar yang ada di Indonesia menolak keberadaan
mereka (STUDIA, 2006).
Kemala Atmojo (1986 dalam Nadia, 2005) menjelaskan bahwa, waria
adalah fenomena transseksualitas. Melalui pengamatan yang dilakukan,
diasumsikan bahwa sebagian besar dari mereka merupakan transseksual. Istilah
waria memang ditunjukkan untuk seorang transseksual (seseorang yang memiliki
fisik yang berbeda dengan keadaan jiwanya). Ma’shum & Tyas (dalam Kompas,
2004) memberikan pengertian sederhana mengenai waria. Waria secara fisik ingin
berpenampilan seperti wanita, dan secara psikologis dia mengidentifikasikan
dirinya sebagai wanita, namun secara biologis adalah pria dengan organ
reproduksi pria. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata waria
menggantikan transseksual atau gender identity disorder, karena sebutan waria ini
merupakan representasi bahasa Indonesia (waria/wanita-pria) dan lebih mudah
dikenali dan dipahami oleh masyarakat secara umum.
Berdasarkan referensi klinis, terlihat bahwa laki-laki memiliki frekuensi
enam kali lebih tinggi dari wanita menjadi transsexual (Zucker et al. dalam
Davidson, Neale & Kring, 2004). Masih dalam buku yang sama, berdasarkan data
American Psychiatric Association menyatakan prevalensi gangguan ini berbeda tajam, satu di antara 30.000 laki-laki, dan satu di antara 100.000-150.000
perempuan mengalami gangguan ini.
Pembentukan “waria” tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan proses
kebiasaan-kebiasaan pada masa anak-anak ketika mereka dibesarkan di dalam keluarga, yang
kemudian mendapat penegasan pada masa remaja, yang menjadi penyumbang
terciptanya waria. Tidak satu pun waria yang “menjadi waria” karena proses
mendadak (Nadia, 2005). Hidup sebagai waria adalah hasil akhir dari akumulasi
masalah-masalah yang dihadapi semasa proses “menjadi waria”, yang
berlangsung dari masa anak-anak hingga ia mencapai dewasa (Koeswinarno,
2004).
Contohnya adalah bernama Shika (dalam Koeswinarno, 2004), seorang
waria yang dibesarkan dalam keluarga Jawa yang sangat kental dan ketat.
Menurut pengakuannya, sejak kecil penampilannya sudah berbeda dibandingkan
dengan teman-teman laki-laki sebayanya. Shika masih ingat ketika ibunya hendak
pergi ke pasar Beringharjo, ia justru memesan kepada ibunya perlengkapan
permainan anak perempuan, bukan peralatan permainan anak laki-laki.
Peristiwa-peristiwa demikian ini terjadi berulang kali dan di luar kesadaran orang tua
terhadap perilaku anaknya. Tanda-tanda berbeda tersebut jarang disadari oleh
orang tua mereka, sehingga ketika perilaku itu menjadi perilaku yang menetap
pada masa menginjak remaja, baru orang tua menyadari ada yang berbeda dengan
anaknya. Sopjan (2005) mengalami hal yang serupa, dalam bukunya yang
berjudul “Jangan Lihat Kelaminku, Suara Hati Seorang Waria”, mantan ratu waria
ini mengungkapkan, sejak kecil dia sudah merasa ada yang berbeda dengan
dirinya. Terlihat dari tokoh pahlawan yang disukainya yang berjenis kelamin
disadari ibunya saat dia berusia 18 tahun, surat cintanya pada “cowok”nya dibaca
oleh kakak perempuannya.
“saat gue usia 18, ibu gue tahu bahwa gue lain. Gara-gara surat buat cowok gue yang gue simpan di lemari terbaca kakak perempuan gue. Gue inget banget, sepulang sekolah ibu gue masuk ke kamar gue dengan raut wajah yang gue gak bisa lukiskan”
Dalam proses menjadi waria, individu mengalami masa dimana individu
melakukan cross dressing (menggunakan pakaian lawan jenisnya) secara
sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan secara rahasia, karena ada ketakutan akan
terbongkarnya perilaku mereka, dan adanya pertimbangan akan konsekuensi yang
diterimanya jika perilakunya terbongkar (Ekins, 1997). Kejadian ini dialami oleh
seorang waria (Koeswinarno, 2004) yang tidak disebutkan namanya untuk alasan
kerahasiaan.
“Ketika SMP, saya sering bercermin, memakai pakaian perempuan milik kakak saya dengan cara sembunyi-sembunyi di kamar. Sambil bergaya dan bicara sendirian, saya merasa ada hal yang tidak sama dengan fisik saya. Sering pula saya mencuri lipstik milik kakak perempuan saya atau ibu saya, sampai-sampai pernah suatu ketika ketahuan bapak. Habislah saya.
Saya dimarahi habis-habisan. Meskipun tidak sampai memukul, tetapi kemarahan ayah saya itu benar-benar menunjukkan ketidaksenangan kepada saya”
Seiring dengan adanya kesadaran bahwa waria memiliki orientasi
seksualnya berbeda, yang mungkin diketahuinya dari ulasan atau artikel dari
majalah atau telah bertemu dengan waria lainnya, terdapat keinginan dan usaha
yang semakin kuat untuk melakukan cross-dressing (Walters & Ross, 1986).
Selain memakai pakaian perempuan, mereka juga memakai kosmetik, dan juga
dan bahkan merubah suaranya menyerupai warna suara perempuan (Koeswinarno,
2004). Tidak hanya mengubah penampilannya, waria juga berusaha mengubah
fisik mereka dengan berbagai cara. Baik melalui operasi payudara, bibir (Nadia,
2005), dan melakukan usaha manipulasi hormon (DSM-IV-TR, 2004). Untuk
mengukuhkan diri sebagai perempuan, beberapa waria melakukan tindakan medis
yang ekstrim, yaitu operasi penggantian kelamin, seperti yang dilakukan oleh
Dorce Gamalama, seorang entertainer terkenal di Indonesia. Dorce (dalam
Gamalama & Gunawan, 2005) melakukan operasi penggantian kelamin di rumah
sakit Dr. Soetomo Surabaya. Setelah itu, dia juga mengurus pengubahan jenis
kelaminnya secara hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dikabulkan pada
tahun 1986.
Peran keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
perkembangan waria. Seorang waria yang dilahirkan dalam keluarga yang
baik-baik, taat beragama, berpendidikan, ditambah dengan keberadaan orang tua yang
pada akhirnya menerima keberadaan mereka secara otomatis akan mempunyai
pengaruh yang baik bagi perkembangan waria. Karena, jika keluarga sudah
menerima keberadaan mereka, maka dukungan, baik itu secara moril atau pun
materiil akan mereka dapatkan. Kemungkinan untuk dapat diterima oleh
masyarakat dengan baik akan semakin tinggi pula. Di Indonesia secara umum,
hadirnya seorang waria tidak pernah dikehendaki oleh keluarganya. Dalam
banyak kasus, banyak waria yang akhirnya pergi meninggalkan rumah dan
laki-laki pada umumnya. Tidak banyak waria yang diterima dengan baik oleh
keluarganya (Nadia, 2005).
Selain keluarga, masyarakat juga berperan penting dalam proses “menjadi
waria”. Yash (2003) mengemukakan, bahwa pandangan masyarakat memberi
pengaruh besar pada proses pencapaian eksistensi seorang waria. Masyarakat
Indonesia saat ini memiliki pemahaman yang salah terhadap waria dikarenakan
minimnya sumber informasi yang layak mengenai waria. Koeswinarno (2004)
menambahkan, tekanan-tekanan dari masyarakat muncul lebih kompleks
dibandingkan tekanan yang ada dalam keluarga. Pandangan bahwa dunia waria
identik dengan pelacuran, melahirkan rekasi negatif dari masyarakat pada waria.
Waria kerap dikucilkan, dicemooh, diprotes, dan ditekan dengan aturan yang ketat
oleh lingkungan.
Proses “menjadi waria” yang dikemukakan di atas, mempunyai konsep
yang selaras dengan konsep male femaling yang dikemukakan oleh Ekins. Ekins
(1997), mengartikan male femaling sebagai sebuah proses sosial yang terdiri dari
sekumpulan fase, dimana individu yang secara genetik merupakan laki-laki,
menjadi “perempuan” dengan berbagai cara, mengadopsi pikiran, perasaan, sikap,
perilaku, perlengkapan dan atribut perempuan. Fase-fase tersebut terlihat jelas
dalam ideal-typical career path of male femaling. Terdapat lima fase yaitu:
akan diri sendiri), dan consolidating male femaling (fase kesadaran diri dan
penetapan rencana ke depan mengenai hidup dan identitas diri).
Teori ideal-typical career path of male femaling didasarkan pada penelitian Ekins yang dilakukan selama hampir 17 tahun, terhadap ribuan waria di
berbagai kota di Ingris. Menurut Ekins, fase-fase ini merupakan fase yang “ideal”,
sehingga tidak semua waria menjalani setiap fase, dan setiap waria menjalani
proses male femaling dengan cara berbeda-beda. Perlakuan yang diterima dari
lingkungan sekitar (keluarga dan masyarakat) pada setiap fase memberi pengaruh
yang cukup besar pada proses male femaling. Di samping itu akses informasi dan
teknologi juga mempengaruhi proses ini (dalam Ekins, 1997).
Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa setiap waria menjalani
male femaling dengan cara yang berbeda-beda. Proses tersebut dipengaruhi oleh lingkungan (keluarga dan masyarakat) dan akses waria pada bidang informasi dan
teknologi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses
menjadi waria dengan menggunakan teori ideal-typical career path of male
femaling yang dikemukakan oleh Ekins sebagai pedoman.
I.B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti
tertarik untuk mengetahui “bagaimana ideal-typical career path of male femaling
I.C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai
fase-fase ideal-typical career path of male femaling pada waria, dengan melihat
secara spesifik setiap fase yang dilalui oleh waria.
I.D. Manfaat Penelitian
I.D.1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu psikologi,
khususnya psikologi sosial mengenai ideal-typical career path of male
femaling pada waria.
b. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin
mengadakan penelitian-penelitian lanjutan mengenai waria, terutama yang
berkaitan dengan male femaling pada waria.
I.D.2. Manfaat praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: sebagai bahan referensi atau
acuan bagi kalangan yang tertarik dan terlibat dalam kehidupan waria.
I.E. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab,
dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematika
BAB I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian,
perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan.
BAB II : Landasan Teori
Bab ini memuat tinjauan teoritis yang menjadi acuan dalam
pembahasan masalah. Teori-teori yang dimuat adalah teori mengenai
pengertia waria, kriteria diagnostik waria, etiologi waria, dan teori
ideal-typical career path of male femaling. BAB III : Metodologi Penelitian
Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif, metode
pengumpulan data, alat bantu pengumpul data, subjek penelitian, serta
prosedur analisis data.
BAB IV : Analisis Data
Bab ini menguraikan analisis data dari hasil dari data utama berupa
data wawancara dan data tambahan berupa data observasi yang
dilakukan terhadap subjek penelitian.
BAB V : Kesimpulan, Diskusi dan Saran
Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, di dalamnya dibahas
kesimpulan, diskusi dan saran dari hasil penelitian yang telah
BAB II
LANDASAN TEORI
II.A. Waria
II.A.1. Pengertian Waria
Nadia (2005), mendefinisikan waria sebagai individu yang sejak lahir
memiliki jenis kelamin laki-laki, akan tetapi dalam proses berikutnya menolak
bahwa dirinya seorang laki-laki. Maka waria melakukan berbagai usaha untuk
menjadi perempuan, baik dari sikap, perilaku dan penampilannya. Selanjutnya
dikemukakan bahwa kebanyakan waria berada pada posisi transseksual. Sejak
lahir waria secara fisik berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi dalam proses
berikutnya ada keinginan untuk diterima sebagai jenis kelamin yang berbeda. Hal
ini sesuai dengan pendapat Koeswinarno (2004) yang menyatakan bahwa, dalam
konteks psikologis waria termasuk transseksual, yakni individu yang secara fisik
memiliki jenis kelamin yang jelas, namun secara psikis cenderung untuk
menampilkan diri sebagai lawan jenis.
Dilihat dari arti transseksual sendiri, Yash (2003) mengartikan
transseksual sebagai masalah indentitas jenis kelamin, kesadaran mental yang
dimiliki individu tentang jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Dimana
identitas jenis kelamin yang dimiliki seorang transseksual ini berlawanan dengan
jenis kelamin yang ”dikenakan” kepadanya berdasarkan genital fisiknya.
Pengertian yang lebih sederhana dikemukakan oleh Devault & Lyarber (2005),
cocok. Seorang transseksual merasa terjebak dalam tubuh dan anatomi seksual
yang salah. Walters & Ross (1986) menyebutkan bahwa, transseksual berusaha
untuk diterima menjadi anggota dari kelompok jenis kelamin yang berbeda.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat
disimpulkan bahwa waria adalah individu yang merasa identitas jenis kelaminnya
berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya secara fisik, dimana ia berusaha
untuk diterima sebagai anggota jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin
yang dimilikinya secara fisik.
II.A.2. Kriteria Diagnostik Waria
Seperti yang dijelaskan dalam pengertian waria di atas, disimpulkan
bahwa waria berada pada posisi transseksual yang secara klinis sering dikaitkan
dengan gender identity disorder (gangguan identitas gender). Dalam DSM IV-TR
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 2000), kriteria diagnostik
untuk gangguan identitas gender adalah:
Kriteria A : Identifikasi cross-gender yang kuat dan tetap (tidak termasuk di
dalamnya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sosial
dengan menjadi anggota jenis kelamin yang berbeda).
Pada remaja dan orang dewasa, gangguan ini dimanifestasikan
dengan simptom seperti: keinginan tetap untuk menjadi anggota
jenis kelamin yang berbeda, sering mengaku sebagai anggota dari
jenis kelamin yang berbeda, keinginan untuk hidup dan
atau keyakinan bahwa dia mempunyai perasaan dan reaksi khas
yang terdapat pada jenis kelamin yang berbeda.
Kriteria B : Secara menetap merasa tidak nyaman dengan ketidakcocokan
jenis kelaminnya dengan peran jenis kelamin yang timbul.
Pada remaja dan orang dewasa, gangguan ini dimanifestasikan
dengan simptom seperti mengubah karakteristik seksual primer
dan sekundernya (dengan cara menambah hormon, operasi, dan
prosedur lainnya) serta berkeyakinan bahwa dia dilahirkan
dengan jenis kelamin yang salah.
Kriteria C : Gangguan ini tidak berhubungan dengan kondisi interseks yang
fisikal
Kriteria D : Gangguan ini menyebabkan disstres klinis atau gangguan fungsi
sosial, pekerjaan dan area penting lainnya.
II.A.3. Etiologi Waria
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, waria adalah kaum transseksual,
yakni individu yang merasa identitas jenis kelaminnya berbeda dengan jenis
kelamin yang dimilikinya secara fisik, dimana ia berusaha untuk diterima sebagai
anggota jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin yang dimilikinya secara
fisik. Yash (2003) mengelompokkan teori-teori yang menjelaskan sebab-sebab
a. Teori Bawaan
1) Pengaruh Genetika
Walter & Ross (1986) menyatakan terdapat studi genetik pada
transseksual yang didalamnya terdapat keabnormalan kromosom.
Tapi belum terdapat penjelasan yang kuat mengenai penemuan ini.
Nadia (2005) menyimpulkan bahwa jika seorang bayi biasanya
lahir dengan kromosom yang seimbang yaitu XX dan XY. Maka
pada waria, kromosom tersebut tidak seimbang (XXY). Hal ini
menimbulkan lahirnya seorang laki-laki dengan ciri
keperempuanan yang lebih melekat.
2) Hormonal
Gender confusion akan terjadi ketika otak memproduksi hormon secara abnormal. Identitas gender tidak hanya bergantung pada
hormon yang tepat, tetapi juga bergantung pada level hormon yang
tepat. Gender sebuah janin adalah sesuatu yang dapat diubah oleh
apapun yang mengubah keseimbangan hormonal dalam suplai
darah janin, dimana sebuah ketidakseimbangan kecil dapat
menyebabkan kaburnya atau berpindahnya garis antar gender.
3) Kondisi otak
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zhou JN, Hofman MA,
Gooren L.J, Swaab DF (1995, dalam Yash, 2003), ditemukan
bahwa sebuah area otak yang dikenal dengan nama central region
pada laki-laki daripada perempuan. BTSc dari enam transseksual
laki-laki ke perempuan sama kecilnya dengan BTSc pda
perempuan, sekitar separuh dari volume BTSc pada laki-laki lain.
Jadi, otak transseksual tampaknya sesuai dengan pengakuan
mereka bahwa mereka perempuan.
4) Jumlah Neuron
Dari penelitian yang dilakukan oleh FPM Krujver, J-N Zhou, CW
Pool, MA Hofman, LJG Gooren dan Dick F Swaab (dalam Yash
2003), didapatkan hasil bahwa laki-laki memiliki hampir dua kali
jumlah somatostatin neuron dibandingkan perempuan. Jumlah
neuron di dalam BRSc transseksual laki-laki ke perempuan sama dengan jumlah neuron di dalam BTSc perempuan. Sebaliknya,
jumlah neuron pada transseksual perempuan ke laki-laki berada
pada rentang jumlah neuron pada laki-laki.
b. Teori Lingkungan
Berdasarkan teori assignment, keadaan seks/gender anak pada saat
dibesarkan dan konsistensi yang mengikutinya adalah ”peramal” terbaik
dari identitas gendernya di masa depan. Sadocks & Sadocks
mengemukakan bahwa pembentukan identitas gender dipengaruhi oleh
interaksi temperamen anak dan kualitas dan sikap dari orang tua. Kualitas
hubungan ibu-anak pada tahun-tahun pertama adalah penentu identitas
gender anak. Selama periode ini, ibu biasanya memfasilitasi kesadaran,
perempuan atau anak laki-laki. Ibu yang mengalami masalah dengan
kemarahan dapat menghasilkan masalah identitas gender anak. Anak yang
ditolak atau diabaikan dapat menanamkan keyakinan bahwa mereka akan
lebih dihargai jika mereka mengadaptasi identitas gender yang berbeda.
c. Zat-Zat Kimia/Polutan
Penyebab kondisi transseksual adalah karena zat kimia seperti beberapa
jenis obat yang diberikan pada perempuan hamil (yang paling dikenal
adalah diethylstilboestrol) atau kontraseptif oral yang dikonsumsi setelah
pembentukan, kadang menyebabkan kondisi transseksual karena
mengganggu proses hormonal.
Terdapat juga bukti-bukti yang terus bertambah tentang sejumlah polutan
yang memberikan efek yang sama. Khususnya substansi-substansi seperti
polychlorobiphenyl dan dibenzodioxin.
II.B. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling
Ekins (1997), mengartikan male femaling sebagai sebuah proses sosial
yang terdiri dari sekumpulan fase, dimana individu yang secara genetik
merupakan laki-laki, menjadi “perempuan” dengan berbagai cara, mengadopsi
pikiran, perasaan, sikap, perilaku, perlengkapan dan atribut perempuan. Fase-fase
ini merupakan fase “ideal”, sehingga tidak semua waria menjalani setiap fase, dan
tidak semua waria memiliki fase male femaling yang sama. Terdapat lima fase
1. Beginning Male Femaling
Menurut pandangan kotemporer barat, terlihat jelas bahwa ada dua
pemisahan yang jelas mengenai gender. Apa yang disebut oleh
ethnomethodologis natural attitude mengenai gender, adalah bahwa semua
manusia termasuk salah satu di antara dua kategori sosial yang ditentukan
permanen berdasarkan karakter biologis (naturally given). Selanjutnya,
yang terakhir disebut dengan “sex” dan yang pertama disebut “gender”
(Stoller, 1986). Kesesuaian antara sex dan gender sangat diharapkan.
Beginning merujuk pada asal, sumber atau bagian pertama. Fase ini fokus pada perilaku femaling awal (initial femaling behaviors) yang merupakan
perilaku awal individu yang tidak sesuai dengan tuntutan sosial atas jenis
kelaminnya. Kasus yang sering muncul adalah adanya cross-dressing
(individu menggunakan pakaian lawan jenisnya, dalam penelitian ini
laki-laki menggunakan baju perempuan), baik karena direncanakan, atau
karena adanya kesempatan.
Pada fase awal ini, individu kemudian berkonfrontasi dengan berbagai
masalah. Individu berkeinginan untuk terlihat sebagai perempuan, tetapi
tidak berkeinginan untuk mengungkapkannya kepada orang lain.
Kebanyakan individu merahasiakan kegiatan femaling dan perasaan
mereka (private awareness context), baik dengan merencanakan tehnik
dan strategi dalam mempertahankan private awareness contextnya.
Terdapat banyak ketakutan akan peluang terbongkarnya perilaku mereka,
jika perilakunya terbongkar. Kejadian awal ini dapat terjadi di masa
kanak-kanak, remaja atau masa dewasa.
2. Fantasying Male Femaling
Di tahap ini ditekankan mengenai pikiran dan fantasi. Fantasi tersebut
bervariasi, mungkin mempunyai skenario tertentu, diadaptasi dari kejadian
nyata, inovasi atau imajinasi. Fantasi seperti menjadi perempuan,
berbelanja dengan ibu di toko mainan anak perempuan, terbangun di pagi
hari sebagai perempuan, dan lain-lain.
Pada fase ini, individu tidak menekankan atau berkeinginan untuk tampil
di publik sebagai perempuan atau mengungkapkannya kepada orang lain.
Dalam kejadian lainnya, fantasy femaling berkaitan dengan penggunaan
alat yang berasal dari dunia perempuan, seperti membaca novel romantis,
dan membayangkan diri sebagai tokoh perempuan dalam novel tersebut.
3. Doing Male Femaling
Fakta bahwa male femaling masih dianggap sebagai penyimpangan,
memberi banyak kemungkinan tidak berkembangnya individu dari fase
beginning dan fantasying. Keinginan untuk menjadi perempuan diikuti dengan ketakutan bahwa dia akan dipermalukan, ditolak, dicemoohkan
oleh orang-orang disekitarnya.
Fase doing male femaling terjadi setiap kali subjek mengadopsi pikiran,
perasaan, sikap dan perilaku perempuan. Ditandai dengan cross-dressing
yang lebih serius dan tindakan untuk mencapai fantasi (yang ada pada fase
ketakutan bahwa dia akan dipermalukan, ditolak dan dicemooh oleh
orang-orang di sekitarnya. Sehingga pada tahap ini, individu berusaha
merahasiakannya dengan menyusun rencana atau strategi untuk
cross-dressing secara aman (masked awareness context).
Dalam fase ini terdapat 4 tipe dari doing femaling, yaitu solitary doing,
solo doing, dyadic doing, dan group doing. Solitary doing dan solo doing
memiliki kecenderungan yang sangat kecil untuk mengungkapkan diri
pada orang lain (disclose).
4. Constituting Male Femaling
Fase ini menandai periode dimana individu mulai menetapkan makna dari
keberadaannya dengan cara yang serius dan kontinu. Seiring dengan
meningkatnya pengalaman dan aktivitas femaling, banyak dari individu
yang mencoba mencari penjelasan yang lebih serius akan diri mereka
sendiri.
Terdapat beberapa kemungkinan, mencari petunjuk profesional berupa
bantuan untuk sembuh atau perawatan. Walaupun jarang, ada beberapa
individu yang kemudian membentuk definisi sendiri mengenai situasi yang
dialaminya berdasarkan referensi media biasa, tanpa mencari rujukannya
dalam literatur. Pada fase ini, individu melakukan tindakan ‘penamaan’
atas diri mereka.
Constituting femaling ini terjadi dalam berbagai cara dan kondisi, ada yang secara personal dan yang secara publik (umum), dengan konteks kesadaran
berbeda-beda. Tahap constituting femaling ini dapat terjadi di sebuah komunitas
tertentu, seperti komunitas waria.
5. Consolidating Male Femaling
Fase ini menandai tahap dimana terjadi pemahaman dan penetapan atas
diri dan dunianya. Pada fase ini mereka meyadari diri mereka sepenuhnya
dan mulai membuat rencana ke depan mengenai hidup mereka dan
identitas mereka. Pada tahap ini individu mengidentifikasi dirinya sebagai
waria dan melakukan berbagai cara untuk mengubah fisiknya. Individu
mulai berani mengekspresikan dirinya sendiri, berani memakai pakaian
perempuan, melakukan operasi atau penyuntikan hormon, dan lain-lain.
Individu berkeinginan untuk terlihat dan berperilaku seperti perempuan
BAB III
METODE PENELITIAN
III.A. Pendekatan Kualitatif
Metode penelitian merupakan unsur terpenting dalam penelitian ilmiah
karena metode yang digunakan dalam penelitian dapat menentukan apakah
penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (Hadi, 2000). Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif.
Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000), metode penelitian
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Pendekatan ini juga digunakan untuk menggambarkan dan menjawab
pertanyaan seputar subjek penelitian beserta konteksnya. Poerwandari (2001)
menyatakan bahwa salah satu tujuan penting penelitian kualitatif adalah
diperolehnya pemahaman yang menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang
diteliti, sebagian besar aspek psikologis manusia juga sangat sulit direduksi dalam
bentuk elemen dan angka sehingga akan lebih ‘etis’ dan konstektual bila diteliti
dalam seting alamiah. Artinya tidak cukup mencari “what” dan “how much”,
tetapi perlu juga memahaminya (why dan how) dalam konteksnya.
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus.
Poerwandari (2001), menyatakan studi kasus sangat bermanfaat ketika peneliti
dengan karakteristik tertentu, ataupun situasi unik secara mendalam, sehingga
dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan terintegrasi mengenai keterkaitan
berbagai fakta dan dimensi dari suatu kasus utuh.
Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep
ideal-typical career path of male femaling yang dikemukakan Ekins (1997), yang merupakan sebuah proses sosial yang terdiri dari sekumpulan fase, dimana
individu yang secara genetik merupakan laki-laki, menjadi “perempuan” dengan
berbagai cara, mengadopsi pikiran, perasaan, sikap, perilaku, perlengkapan dan
atribut perempuan. Dimulai dari fase beginning male femaling (fase terjadinya
perilaku femaling awal) hingga fase consolidating male femaling (adanya identitas
yang utuh). Peneliti ingin memperoleh data deskriptif serta pemahaman yang
menyeluruh dan utuh mengenai proses ideal-typical career path of male femaling
pada waria untuk menjawab pertanyaan “how” atau bagaimana proses ini terjadi
pada waria yang akan diteliti.
III.B. Metode Pengumpulan Data
Lofland & Lofland (dalam Moleong, 2002) menyatakan, bahwa sumber
utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan
tindakan ini dapat dicatat melalui perekaman suara atau melalui catatan tertulis.
Pencatatan sumber data utama dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi
III.B.1. Wawancara
Rahayu & Ardani (2004) menyatakan, pengumpulan data kualitatif melalui
wawancara bertujuan untuk memperoh informasi yang digunakan untuk
mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena yang diteliti. Informasi tersebut
bersifat mendalam dan individual. Hal ini sesuai dengan pernyataan Banister, dkk.
(dalam Poerwandari, 2001) yang menyatakan bahwa, wawancara kualitatif
dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang
makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang
diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut.
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini sifatnya tidak terstruktur
memberi kesempatan pada subjek untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan
dan perasaannya dengan bebas (Nasution, 1996).
Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (in depth
interview). Wawancara mendalam adalah wawancara yang tetap menggunakan pedoman wawancara, namun fungsinya tidak seketat wawancara terstruktur.
Pedoman wawancara berfungsi semata-mata untuk memuat pokok-pokok
pertanyaan yang akan diajukan yaitu open-ended questions
(pertanyaan-pertanyaan terbuka), yang bertujuan menjaga agar arah wawancara tetap sesuai
dengan tujuan penelitian (Poerwandari, 2001).
III.B.2. Observasi
Minauli (2002) menyatakan, metode observasi dan wawancara memiliki
terpenting dalam metode wawancara. Mengobservasi aspek-aspek nonverbal
selama melakukan wawancara akan sangat bermanfaat terutama pada saat
menggali dan melihat sinkronisasi antara apa yang dikatakan sunjek (bahasa
verbal) dengan apa yang secara tersirat sebenarnya ingin disampaikannya (bahasa
nonverbal). Oleh karena itu, observasi menjadi metode pengumpulan data yang
esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan menggunakan pendekatan
kualitatif (Patton dalam Poerwandari, 2001).
III.C Alat bantu Pengumpul Data
Alat bantu pengumpul data dalam penelitian ini digunakan pada saat
melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu menggunakan peralatan
bantu sebagai berikut:
1. Alat perekam (voice recorder).
Poerwandari (2001) menyatakan, sedapat mungkin wawancara perlu
direkam dan dibuat transkipnya secara verbatim (kata demi kata), sehingga
tidak bijaksana bila peneliti hanya mengandalkan ingatan. Untuk tujuan
tersebut, perlu digunakan alat perekam agar peneliti mudah mengulang
kembali rekaman wawancara dan dapat menghubungi subjek kembali
apabila masih ada hal yang belum lengkap atau belum jelas. Dengan
adanya alat perekam ini, hasil wawancara yang direkam juga merupakan
data yang utuh karena sesuai dengan apa yang disampaikan subjek dalam
2. Pedoman Umum Wawancara.
Pedaman umum wawancara memuat isu-isu yang berkaitan dengan tema
penelitian tanpa menentukan urutan pertanyaan karena akan disesuaikan
dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. Pedoman ini
digunakan untuk mengingatkan sekaligus sebagai daftar pengecek bahwa
semua aspek yang relevan telah dibahas atau ditanyakan. Hal ini
dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari
tujuan penelitian. Selain itu, pedoman wawancara berfungsi sebagai alat
bantu untuk mengkategorikan jawaban sehingga memudahkan peneliti
pada tahap analisis data (Poerwandari, 2001).
3. Lembar observasi dan Catatan subjek.
Lembar observasi dan catatan subjek digunakan untuk mempermudah
proses observasi yang dilakukan. Observasi dilakukan seiring dengan
wawancara. Lembar observasi dan catatan subjek antar lain memuat
tentang penampilan fisik subjek, setting wawancara, suasana lingkungan,
sikap dan reaksi subjek, serta hal-hal yang menarik maupun mengganggu
dalam pelaksanaan wawancara.
III.D. Subjek Penelitian
III.D.1. Kriteria Subjek Penelitian
Kriteria yang digunakan untuk memilih subjek penelitian adalah sebagai
Waria (transseksual male-to-female), yakni individu yang mengakui dan
menyadari bahwa dirinya memiliki jenis kelamin laki-laki, tetapi secara psikis
cenderung menampilkan dirinya sebagai seorang perempuan.
III.D.2. Jumlah Subjek Penelitian
Prosedur penentuan subjek dalam penelitian kualitatif menurut Sarankatos
memiliki karakterisitik berikut ini yaitu: tidak ditentukan secara kaku sejak awal
tetapi dapat berubah, baik dalam hal jumlah maupun karakteristik subjek sesuai
dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian. Yang kedua,
tidak diarahkan pada keterwakilan melainkan pada kecocokan konteks. Ketiga,
subjek tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kasus-kasus
tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian. Miles & Huberman juga
menyatakan bahwa, penelitian kualitatif sedikit banyak dapat dianalogikan dengan
pekerjaan detektif yang harus mendapatkan gambaran tentang fenomena yang
dicarinya (dalam Poerwandari, 2001).
Jumlah subjek dalam penelitian ini direncanakan berjumlah tiga sampai
lima orang. Hal ini mengacu pada alasan kesulitan untuk mendapatkan subjek
penelitian yang sesuai dengan kriteria dan bersedia untuk dijadikan subjek
penelitian. Di samping itu terdapat juga pertimbangan kesanggupan peneliti dalam
III.D.3. Prosedur Pengambilan Subjek Penelitian
Penelitian in menggunakan prosedur pengambilan subjek dengan tehnik
sampling purposif, yaitu pengambilan sampel purposif yang terstratifikasi
(stratified purposeful sampling). Penelitian kualitatif fokus pada kedalaman kasus
dari beberapa subjek penelitian yang dipilih berdasarkan tujuan tertentu
(purposefully) (dalam Patton,1990).
III.E. Prosedur Analisis Data
Pengolahan dan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data,
koding, analisis dan terakhir adalah interpretasi (Poerwandari, 2001).
1. Organisasi Data
Data kualitatif sangat banyak dan beragam, sehingga perlu untuk
diorganisasikan secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Highlen &
Finley (dalam Peorwandari, 2001) menyatakan bahwa organisasi data yang
sistematis memungkinkan peneliti untuk memperoleh kualitas data yang baik,
mendokumetasikan analisis yang dilakukan serta menyimpan data dan analisis
yang berkaitan dalam penyelesaian penelitian. Hal-hal yang penting untuk
disimpan dan diorganisasikan adalah data mentah (catatan lapangan, kaset
hasil rekaman), data yang telah dibubuhi kode spesifik dan dokumentasi
umum yang kronologis mengenai pengumpulan data dan langkah analisis.
2. Koding dan Aanalisis
Langkah penting pertama sebelum analisis dilakukan adalah menambahkan
dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun transkrip verbatim (kata demi
kata) atau catatan lapangan sedimikian rupa, sehingga ada kolom yang lebih
besar disebelah kanan transkrip tersebut. Kemudian memberi penomoran
secara berurutan dan kontinu pada baris-baris ktranskrip tersebut. Selanjutnya
peneliti memberikan nama untuk msaing-masing berkas dengan kode tertentu.
3. Interpretasi Data
Kuale (dalam Poerwandari, 2001) menyatakan bahwa interpretasi mengacu
pada upaya memahami dan secara lebih ekstensif sekaligus mendalam peneliti
memiliki perspektif tersebut. Peneliti beranjak melalui apa yang secara
langsung dikatakan oleh subjek, untuk mengembangkan struktur-struktur dan
hubungan-hubungan bermakna yang tidak segera ditampilkan dalam data
mentah. Proses interpretasi memerlukan distansi (upaya mengambil jarak) dari
data, dicapai melalui langkah-langkah metodis dan teoritis yang jelas, serta
BAB IV
ANALISA DATA
IV.A. Analisis Data Subjek 1
IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 1
Tabel 1.
Gambaran Umum Subjek 1
Nama samaran Wenny
Usia 58 tahun
Agama Kristen
Suku Batak
Pendidikan terakhir Diploma (D3) Sekretaris
Pekerjaan Wiraswasta (Salon)
Status Belum menikah
Alamat Medan
Deskripsi Data Subjek 1
Dilahirkan di Siantar, 58 tahun yang lalu, Subjek merupakan anak ke
empat dari lima bersaudara. Dia merupakan anak laki-laki pertama di
keluarganya, memiliki tiga orang saudara perempuan, dan seorang adik laki-laki.
Subjek lahir dari keluarga bersuku Batak Toba, ayah dan ibunya sama-sama
bersuku Batak Toba. Semasa SD, Subjek tinggal bersama keluarganya di
Ambarita, kemudian memasuki SMP, mereka sekeluarga bermukim di Siantar.
Sejak masa prasekolah, Subjek sudah menyukai dunia anak perempuan, di
antaranya lebih menyukai bermain dengan perempuan dan melakukan permainan
saat orang tuanya tidak di rumah, dia pernah mencoba pakaian ibunya, dan
berjalan bak seorang peragawati.
Subjek tertarik pada laki-laki saat duduk di bangku SMP, tapi dia
kemudian merasakan cinta yang sesungguhnya saat dia memasuki SMA. Saat
SMA pula, dia mulai mengenal komunitas waria, dia sering keluar malam dan
“nongkrong” dengan komunitasnya tersebut. Hal ini tidak diketahui oleh orang
tuanya, berbagai alasan digunakan untuk bisa keluar malam dan tetap
menyembunyikan kegiatannya dengan komunitasnya.
Subjek meneruskan pendidikannya ke jenjang D3 di Medan. Jauh dari
pengawasan orang tua dan keluarga membuatnya lebih berani untuk
berpenampilan layaknya seorang wanita. Walaupun demikian, dia mengaku sudah
berusaha untuk mengubah perilakunya tersebut, seperti mencoba berpacaran
dengan perempuan, dan berpenampilan dan berteman dengan laki-laki, tetapi hal
tersebut tidak berhasil.
Setelah menamatkan pendidikan D3-nya, Subjek kemudian merantau ke
luar Medan, seperti Jawa dan Banda Aceh. Beberapa pekerjaan dilakoninya, baik
sebagai pegawai swasta, penyanyi, pemain sandiwara dan sebagai pegawai sebuah
bank di Banda Aceh. Saat bekerja di bar sebagai pelayan dan penyanyi di Jakarta,
dia berpakaian ala perempuan. Dia juga mengirimkan fotonya berpakaian
perempuan pada keluarganya. Keluarganya yang sempat tidak mengetahui
kabarnya selama hampir lima tahun, dan mengira bahwa dia sudah meninggal
dalam sebuah kecelakaan sesuai dengan pemberitaan sebuah media, merasa
keluarganya, Subjek pulang ke Medan, keluarganya menerima perubahan yang
terjadi pada dirinya.
Sekarang Subjek aktif di kegiatan gereja dan lingkungannya. Dia tetap
tampil dengan dandanan seorang perempuan, ini ditetapkannya setelah dia
mempunyai penghasilan sendiri, didukung pengetahuan agama yang
mendukungnya untuk menerima dirinya apa adanya dan tetap berbuat baik.
Kedekatannya dengan keluarga tetap terjalin, saat ini dia tinggal dengan keluarga
adiknya dan aktif mengikuti kegiatan ibadah dan arisan keluarga besar marganya.
Pekerjaan yang digelutinya sekarang, adalah di bidang kecantikan. Setelah
menghabiskan lebih dari lima tahun belajar tata rias di beberapa salon, dia
menjadi karyawan salon di beberapa salon. Setelah kenyang dengan pengalaman,
tahun 1990, Subjek membuka salon pertamanya, tapi karena ketidakcocokan
dengan sang pemilik rumah, dia kemudian pindah dan membuka usaha salon di
daerah Menteng sekitar tahun 1992.
IV.A.2. Data Observasi Subjek I
Bulan Januari akhir 2007, peneliti berkenalan dengan Subjek di salonnya
yang terletak di daerah Menteng. Saat mengemukakan maksud dan tujuan peneliti,
dia bersedia membantu sebagai partisipan dalam penelitian peneliti, kemudian
peneliti memberikan informasi mengenai hak-hak privasi dan penggunaan data
wawancara yang nantinya didapat. Untuk mengakrabkan diri, peneliti sempat
potong rambut di salon Subjek, sambil bercerita tentang berbagai hal, terutama
Wawancara pertama, diadakan di salon Subjek pada hari Rabu, tanggal 11
Juli 2007, pukul 15.30-17.30 WIB. Pemilihan tempat merupakan kehendak Subjek
sendiri karena dia menjalankan salonnya sendiri. Keadaannya memang tidak
begitu nyaman untuk melakukan wawancara, karena salon Subjek berada di depan
jalan raya yang ramai dilintasi oleh kendaraan dan pada saat itu listrik padam,
sehingga ruangan panas dan suara genset di luar ruangan menambah suara bising.
Saat itu, Subjek menggunakan daster berwarna krem, dan rambutnya dikucir ke
belakang. Karena udara yang panas, sesekali Subjek mengipas-ngipas muka dan
badannya dengan selembar koran, terkadang dia mengangkat kedua kakinya ke
atas kursi dan beberapa saat kemudian menurunkannya kembali. Sebelum
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, peneliti berbasa-basi sejenak, dan setelah
peneliti merasa Subjek sudah cukup nyaman dengan keberadaan peneliti, peneliti
memulai wawancara. Subjek terlihat santai menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh peneliti, dengan suara khas dan cepat yang terkadang
membuat peneliti kewalahan mencerna perkataan Subjek. Saat menjawab
pertanyaan yang berhubungan dengan kejadian dimana Subjek mendapat reaksi
negatif dari orang lain, suara Subjek berubah menjadi lebih keras dan tegas,
kakinya yang semula disilangkan di atas kursi diturunkan, badannya mencondong
ke depan. Saat wawancara, pelanggannya datang, wawancara kemudian ditunda
dan dilanjutkan kembali setelah Subjek selesai melayani pelanggan tersebut.
Wawancara kedua, diadakan di tempat yang sama, yaitu di salon Subjek
pada hari Senin, 30 Juli 2007, pukul 14.45-16.00 WIB, untuk melengkapi data
saat dia sedang berbicara dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya.
Dari seberang jalan, Subjek sudah mengenali peneliti dan melambaikan tangannya
ke arah peneliti, kemudian setelah peneliti menyeberang, Subjek mengajak
peneliti masuk. Penampilan Subjek terlihat simpel, dia mengenakan celana pendek
warna krem dengan tank top berwarna senada. Tidak nampak polesan make-up di
wajahnya, rambutnya yang pendek dikucir dan diikat ke belakang, tampilannya
sederhana dan ramah. Sebelum wawancara dimulai, Subjek memakan sepotong
kue yang dibawa oleh peneliti dan bercerita mengenai keponakannya yang juga
sering membawa kue. Subjek sesekali menanyakan mengenai keluarga dan studi
peneliti, kemudian peneliti menceritakan sekilas mengenai studi, keluarga dan
rencana pulang kampung. Saat wawancara berlangsung, Subjek duduk di kursi di
depan peneliti, kakinya disilangkan, tangan kanannya diletakkan di atas lututnya
dan tangan kirinya memegang rambutnya, dan terkadang digunakan untuk
memperbaiki rambutnya beberapa kali.
Wawancara yang merupakan ketigakalinya ini diadakan pada hari Kamis,
tanggal 22 November 2007, mulai pukul 13.00-14.50 WIB. Seperti penampilan
sebelumnya, Subjek menggunakan tank top dan celana pendek, tapi ada yang
berbeda dengan rambutnya, terlihat lebih lurus, rapi dan di hi-lite (diwarnai),
ternyata Subjek baru menjalani perawatan rambut smoothing. Salonnya terlihat
ramai, ada empat orang anak perempuan yang menurut penuturan Subjek
merupakan asistennya yang juga belajar di salonnya. Terdapat beberapa
perubahan pada salonnya, yaitu penggantian keramik lantai, adanya papan
salonnya. Dia menceritakan bahwa saat lebaran, dia mendapatkan penghasilan
yang lumayan besar dan dengan uang tersebut dia dapat memperbaiki salonnya.
Wajah Subjek terlihat lebih ceria dari sebelumnya, dan lebih sering tersenyum
sambil menceritakan perkembangan salonnya. Saat wawancara, Subjek
menyisipkan cerita keberhasilan usaha salonnya pada peneliti. Bahkan setelah
wawancara usai, Subjek beberapa kali menceritakan cerita keberhasilan usaha
salonnya sekarang. Selama menjawab pertanyaan, Subjek sering memperbaiki
rambutnya yang ringan tertiup angin, kakinya disilangkan serta tangannya
terkadang diayunkan saat menjawab beberapa pertanyaan. Setelah wawancara
selesai, saat peneliti memandang ke sekeliling salon, ternyata foto Subjek saat
menjadi Miss Waria Sumatera Utara telah dipajang, berderet dengan foto-foto lain
saat Subjek menerima berbagai penghargaan dalam bidang kecantikan dan
kejuaraan.
IV.A.3. Data Wawancara Subjek I
a. Beginning Male Femaling
Sejak masa prasekolah, Subjek mengakui kalau dia sudah berperilaku
seperti anak perempuan dan dia menyadarinya saat masih duduk di bangku SD,
sekitar umur 12 tahun.
“Aku sejak dari ini mm.., dari SD, ..dari SD aku, sebelum sekolah pun saya da nampak kayak-kayak perempuan-perempuan gitu...kalo gak salah saya, umur 12 tahun saya da nampak gejala. Dari SD-SD la, mau masuk SMP gitu, uda kentara kali lah, uda nampak.”
Saat bermain, Subjek lebih memilih untuk bermain dengan anak
perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki.
“Sama perempuan, tapi di sana misalkan kumpulan laki-laki sekalian bermain, saya gabung sama perempuan”.
(S1.W3/b.195-197/hal.7).
Menghabiskan waktu bermain dengan anak perempuan membuatnya akrab
dengan permainan-permainan dan kegiatan-kegiatan anak perempuan pada
umumnya. Subjek melakukan kegiatan seperti mencuci piring, menjahit, main
boneka, menari, main pecal-pecalan dan kegiatan lain yang identik dengan
kegiatan yang biasa dilakukan anak perempuan. Bahkan saat perayaan
kemerdekaan, 17 Agustus, dia mengikuti kegiatan seperti menari dan pada saat
karnaval, dia memakai baju perempuan.
“Dari sebelum SD, saya uda ada pekerjaan perempuan, kewanitaan-kewanitaan saya da ada. Cuci piring, ngapel, jahit-menjahit, main-mainan kelereng-kelereng, main anak-anakan, main boneka-boneka sudah, joget-joget, nari-nari. Kalo sudah 17 Agustusan itu, saya da sering nari-nari gitu. Kalo ada-ada karnaval gitu da suka dibuat pake baju perempuan kan... Anak-anakan, trus main pecel-pecelan gitu.”
(S1.W1/b.18-27, 85-86/hal.1, 2).
Sewaktu kelas enam SD, Subjek menyukai permainan lain, seperti jinjing
bakul, dan pada saat tersebut dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang anak
perempuan
“Oooo...iya pernahlah waktu kelas-kelas enam la itu saya rasa. Saya kan dulu apa, sering main kain-kain jingjing bakul kan, ya iya la, saya kan perempuan, pernah itu mau omongan gitu memang pernah.”
(S1.W2/b.280-285/hal.7).
Hal ini tidak luput dari perhatian saudara-saudaranya dan orang tuanya,
seorang anak laki-laki, dia tidak boleh berbuat demikian. Ibunya memaklumi hal
tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu Subjek masih anak-anak.
“Eee, dilarang, gak dilarang, dilarang sih enggak. Cuman ya dikasi ingat, dikasi ingat gitu aja. ‘Jangan gitu la’ katanya, ‘Kau kan laki-laki’, itu katanya. Tapi dibiarkan saja, datang mamak saya, ‘Uda la gak papa, gitu aja, namanya anak-anak’, itu katanya.”
(S1.W1/b.99-105/hal.3).
Begitu juga dengan ayah dan saudara perempuannya, mereka hanya
menyatakan keheranan mereka atas kesukaan Subjek terhadap barang-barang
yang disukai anak perempuan.
Ya dari kecil, mereka sudah tahu, tidak pala mau dilarang, tidak pala mau di apa gitu. Cuman ayah, kakak saya bilang, “Kau kok kayak perempuan, suka kali kau barang-barang ke gitu”, katanya, itu aja.
(S1.W3/b.156-160/hal.4).
Pada kesempatan lain, Subjek berani memakai pakaian-pakaian ibu dan
saudara perempuannya secara sembunyi-sembunyi atau bersama teman-temannya
perempuan. dia memakai kebaya, kain sarung, sanggul dan sepatu serta
menyobanya di depan kaca.
“Iya..pake-pake kebaya, kain sarung, pake-pake sanggul gitu...Iya, nyoba di depan kaca...Baju kakak saya, baju mamak saya, tapi kalo sepatu kakak saya pernah, baju mamak saya sepatu kakak saya la. Jalan-jalan kek gini-gini di ruangan gitu...Ga ada orang yang lihat, apa la, kadang-kadang bermain sama-sama perempuan la.”
(S1.W2/b.325-326, 328, 334-337, 339-341/hal.7, 8).
Setelah mengerti perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Subjek
menyadari bahwa dia merasa dirinya adalah seorang perempuan. Tingkah lakunya
yang cenderung seperti perempuan semakin bertambah seiring pertambahan
usianya, bahkan dia mulai tertarik terhadap laki-laki.
perempuan, trus itu di SD belum ada terasa, cuman tingkah laku da tingkah laku perempuan, ha.. di SMP, di SMP, udahlah, uda jadi, uda jadi tapi blum pas, blum pas, jadi di SMU, baru uda mulai. Kita uda mengenal cinta dan kasih sayang, itulah perhatian, rasa sama cowok gitu.”
(S1.W3/b.108-119/hal.3).
Keterarikan terhadap laki-laki tersebut dirasakannya sejak kelas tiga SMP
hingga duduk di bangku SMA.
“Di SMP uda terasa la, uda pernah di..diapala, diajak-ajak bercinta gitu, tapi gak sampai kencan. Cuma ada sayang gitu, ada cinta la gitu, beda la beda. Dari SMP saya uda itu di kelas tiga. Uda mau masuk di SMU, tapi waktu di SMUnya ya uda, kita uda.”
(S1.W1/b.50-56/hal.2 ).
Ketertarikan tersebut berupa rasa sayang dan perhatian terhadap laki-laki,
Subjek merasa sebagai seorang perempuan yang dicintai oleh laki-laki.
“Berbedalah. Berbeda, terasa sayang sama laki-laki itu, ada rasa perhatian, ada apa gitu”
(S1.W3/b122-124/hal.3).
“... diri ini merasakan perempuan, merasa dicintai, namun laki-laki, saya tidak tahu, tapi namun dia ada sayang gitu...”
(S1.W1/b.68-71/hal.2).
b. Fantasying Male Femaling
Subjek pernah membayangkan dirinya seperti perempuan, hal ini biasanya
terjadi ketika dia melihat perempuan yang cantik, dia akan bertanya pada dirinya
sendiri apa bisa dia seperti perempuan tersebut
“.Ya...pernah...pernah, itu tentu ada, ada...ya perasaan kita itu kaya perasaan perempuan la. Kalo ada lihat ada perempuan cantik ya, ‘apa bisa saya kayak perempuan itu?’, begitu.”
Keinginannya untuk menjadi secantik perempuan yang dilihatnya, dia
tuangkan dengan mengikuti sandiwara-sandiwara dan mengambil peran sebagai
seorang perempuan.
“Ya kalo ada nengok perempuan yang cantik gitu kan? Maunya saya bisa secantik itu, kek menonton-nonton kita di TV, dengar-dengar sandiwara, ha, karena saya dulu pernah ikut-ikut sandiwara, ha, jadi saya itu selalu ikut-ikut jadi sebagai wanita la.”
(S1.W3/b.175-180/hal.4).
Selain itu, Subjek juga pernah mengikuti opera-opera, yang juga banyak
diikuti oleh waria-waria. Dalam opera tersebut Subjek 1 mengambil peran sebagai
perempuan.
“....apalagi pada opera itu pada umumnya orang waria-waria kebanyakan. Jadi peranan kalo agak tua jadi sebagai mamak, karena hari itu masuk umur-umur 20, aku sebagi anak gadis, sebagai gadis nakal, gitu-gitu la. Banyaklah peranan saya di situ.”
(S1.W2/b.369-375/hal.8).
c. Doing Male Femaling
Subjek mengenal waria sejak dari SD, saat SMP dia memiliki teman yang
juga memiliki kecenderungan untuk menjadi perempuan.
“Saya dari SMP, dari SD pun saya uda ada kenal, uda ada teman, tapi saya gak mau pala terjun. Hanya sekedar gitu, ya karena masih sekolah, jadi karena masih sekolah gitu gak...Di SMP saya, saya uda ada teman-teman saya, dua di antara kami, dua tiga di lingkungan itu...”
(S1.W1/b.334-342/hal.8).
Memasuki SMA, bersama teman-teman sekelasnya, Subjek mulai sering
keluar malam dan bergabung dengan komunitas waria.
“Sebelum SMA uda pernah-pernah juga. Sesudah SMA, waktu SMA ya sudah sering la keluar-keluar malam, uda gabung-gabung... Sama teman-teman. Ha...itu la teman-teman sekelas, marga Tarigan, marga Sinaga, marga Situmorang”
Bersama komunitas waria, Subjek diajak untuk berpenampilan seperti
perempuan, pakaian yang dipakai biasanya adalah pakaian ibu, saudara
perempuan, atau pakaian perempuan yang dibeli sendiri. Kemudian mereka pergi
“mejeng” ke berbagai tempat hiburan, seperti restoran, kafe, bar, taman hiburan,
kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
“...Uda SMA la, uda gabung dengan kawan. Kita uda mengenal dua tiga orang. Kadang-kadang kita malam-malam uda diajak kita dandan di tempat orang, ada spesial warung di situ. Kita uda membeli baju...ambil baju kakak kita ato mamak kita. Kita uda pakaian, nanti pagi uda ganti lagi seperti biasa, jangan sampai ketahuan sama keluarga begitu. Tapi namun kalau saya begitu dulu, cari uang tak pernah, blum pernah..tidak pernah. Cuma kalo kerja-kerja di diskotik ya..iya pernah...nyanyi-nyanyi di bar, di restoran pake baju perempuan. Dari jam sekian kita uda bangun, dandan, ntar kita uda pergi saja, kayak di taman Ria, kita ikut gabung kan dengan orang-orang, grup-grup, itu grup band.”
(S1.W1/b.219-237/hal.5-6)
“Iya ada...itu ada teman kita. Kita bergabung dengan kakak kelas kita, sama yang uda senior-senior kita, kita bergabung, mereka itu uda ada baju tersedia, sepatu tersedia. Tapi terkadang masalah selop takut gak pas, kita ambil selop mamak kita, ato kakak kita gitu, lalu kita jalan-jalan... Kalo masalah bedak-bedak, baju dari mereka. Jadi nanti ada warung di situ, nanti di situ la kita gabung, ada kafenya. Jadi nanti kan, kita satu persatu dipanggil nyanyi gitu, pake baju perempuan, joget-joget, melayang-melayang gitu. Apala...gitu...orang-orang dunia yang ada, supir-supir yang mabukla, namanya kafe, duduk di situ la dulu, mejeng di Siantar.”
(S1.W2/b.186-193, 195-204/hal.5)
Subjek pulang ke rumah sekitar pukul satu sampai dua pagi, melalui pintu
belakang dan terkadang harus memanjat.
“Pergi gitu aja uda, cuman sampai pagi sih enggak, paling la kadang-kadang jam satu malam, jam dua malam ke rumah, masuk pintu belakang la gitu, ya kadang manjat la.”
(S1.W2/b.173-177/hal.4)
Kebiasaan Subjek keluar malam mendapat larangan dari keluarganya,
tetapi larangan tersebut tidak membuatnya kapok untuk keluar malam.
tahu saya begituan, cuman da tau gerak-gerik saya itu da tau saya keperempuanan.”
(S1.W2/b.165-169, 180-182/hal.4).
Setamat SMA, Subjek merantau ke Medan dan kuliah di sana. Setelah jauh
dari orang tua, dia sering berpenampilan seperti perempuan, dan sering mengikuti
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia kecantikan bersama-sama
temannya sesama waria.
“Di medan ini, saya kuliah di Darma Agung, di ASMI.” (S1.W2/b.631-632/hal.14)
“Tapi yang terjun kali, sesudah tamat SMAla, kita harus tamatkan dulu SMA kita ini baru sesudah tamat kita SMA, sesudah mahasiswa baru kita sering-sering pakai pakaian baju perempuan malam hari, kadang nonton gitu kan, main-main gitu... Uda tamat, uda mahasiswa saya kadang-kadang mau ada acara gitu di hotel Danau Toba, ada ini... dari salon, jadi kita dandan, pake baju perempuan bersama-sama teman.” (S1.W1/b.194-198, 334-349/hal.5, 8)
Selain memperkenalkannya ke dunia kecantikan atau salon,
teman-temannya sesama waria juga mengajaknya mengikuti berbagai kegiatan seperti
menari, menyanyi, dan mengikuti berbagai acara, seperti acara mode dan
sandiwara.
“Dari teman la. Jadi kita terjun ke salon, lagi, kawan itu la yang mengajari kita terjun ke salon, gabung, trus nanti ada acara nonton sandiwara atau fashion show, kita uda ikut menari-menari, ia...nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya itu la menjadi-jadi menjadi la. Ya kita tidak mau lagi biasa-biasa, bergabung dengan masyarakat biasa. Kita harus dipandang orang la...kita...kita kek ada kelebihan ada keanehan gitu la. (S1.W1/b.726-736/hal.16).
Saat berumur sekitar 22 tahun, Subjek mengirimkan fotonya yang sedang
menggunakan baju perempuan kepada keluarganya.
“Ooo, keluarga itu tahu, waktu saya merantau dulu, saya kirim foto dengan pake baju perempuan, saya lagi nyanyi... Kira-kira itu uda 22 tahun...22 tahun”
Keluarganya tidak berkomentar banyak, tetapi Subjek menyadari bahwa
keluarganya sedih.
“Tidak banyak komentar cuman ya sedih, ya sedih tapi tidak terkatakan apalagi mamak saya dulu..saya itu tamat SMA uda langsung merantau dulu,...gitu. Adek-adek saya pun ga marah.”
(S1.W1/b.248-253/hal.6).
Subjek tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh
komunitas waria, seperti gebyar waria yang merupakan ajang berkumpul waria
yang dilakukan setahun sekali, juga perlombaan-perlombaan seperti lomba
fashion, olahraga, masak, dan lain-lain.
“..sering gabung setahun sekali, kita buat hari apa...apa namanya...reuni. ketemu wajah-wajah, dibuata lomba-lomba, masak, volli, basket, kek gitu kan. Lomba masak, basket, ini baru salon, baru sebulan itu nanti. Kek gitu, lomba basket, model, jahit, tapi apala...baru nanti acara puncaknya. Dibuatla malam gebyar...baru dibuatla....kita buat-buat model...la.... , gabung itu nanti untuk internasional dengan nasional..ha... yang dari bali, dari Yunani, Brunei, Hongkong, ada gitu kan...ha...Piliphina gabung la itu nanti, dibuatla model..ha...dibuat terima tamu, adala sponsor, adalah sponsornya....”
(S1.W1/b.745-761/hal.16-17).
Sekarang ini, Subjek tergabung dalam eskada grup dan perwakom, yaitu
komunitas waria yang terdapat di Medan. Dia juga pernah menjadi ratu waria se
Sumatera Utara.
”Macam apa...em...eskada grup...eskada grup...trus dibuat lagi ini...perwakom, perkumpulan waria kota medan dan sekitarnya, ada kita.. Saya ee..pernah ikut peserta...itu piagamanya... Itu piagamnya dan ada lagi saya, waktu foto, ada foto saya waktu saya apa, waktu saya masuk ratu. Saya pernah ratu Sumatera Utara.”
(S1.W1/763-767, 769-772/hal. 17).
d. Constituting Male Femaling
Melihat perilakunya yang seperti perempuan, orang-orang di sekitar
menyuruhnya berobat ke dukun, bergabung dengan laki-laki. Subjek menuruti
beberapa saran tersebut, tetapi dia mengaku bahwa dia tidak bisa mengubah
perilakunya yang seperti perempuan tersebut.
“Kalo orang lain ee...kenapa kamu? Bisa kok diobati, bisa kok diapai, bisa diapai, ada yang mau suruh dibawa ke dukun, ada yang suruh macam-macam, ada suruh kita bergabung sama laki-laki yang begitu...tapi kita ya....diri sendiri la...kita percaya diri sendiri aja, kita pun bukan suka begini, iya kan? Semua pun kadang-kadang kita coba dulu, waktu kita semasa dulu masih mahasiswa, ...apa..uda tau memang itu salah tapi tidak bisa memang, kita uda coba. Kita coba kok berpakaian jantan tapi tidak menerima, berontak, ha gitu.”
(S1.W1/b.394-407/hal.9).
Usaha-usaha yang dilakukannya beragam, mulai dari mencoba tampil
lebih maskulin dengan memanjangkan kumis, menjalin hubungan dengan
perempuan, bahkan mencoba tidur dengan teman perempuan. Tetapi hal-hal
tersebut tidak berhasil, dia merasa seperti orang lain ketika melakukan berbagai
usaha tersebut di atas.
“Saya panjangi kumis, kumis pun tak tumbuh, saya coba pacaran sama perempuan, perempuan pun tak mau, menolak hati pun, tidak menerima, menolak begitu lah. Tapi sekedar teman-teman dulu, sekedar cerita-cerita ya tidur sama perempuan kita juga sudah, teman-teman gitu uda anggap teman gitu, satu ranjang gitu, sudah. Tapi gak ada apa-apa. Kita kayak ga seperti diri kita sendiri... Uda berusaha ha...Tapi ya tidur sama pacar kita temani, kita sukai, ya ada la untuk rasa cemburu, rasa cinta, ada memang, ada, iya kan.”
(S1.W1/413-423, 425-428/hal.9, 10).
Subjek mengakui, bahwa dia sulit melepaskan dirinya dari dunia
perempuan terutama tampil dengan tampilan perempuan. Apalagi sekarang dia
bekerja di dunia kecantikan yang semakin memperberat dirinya untuk
melepaskannya.