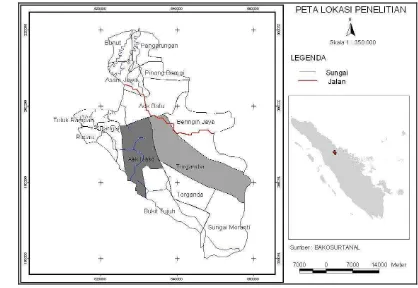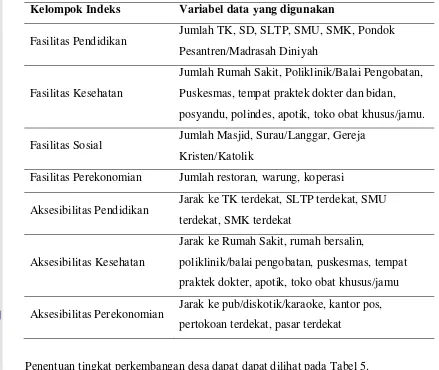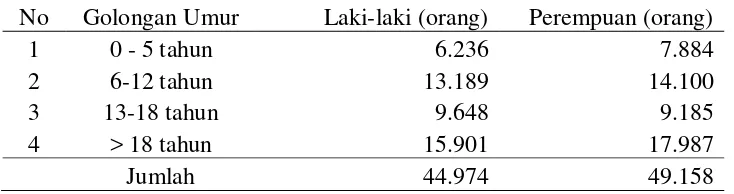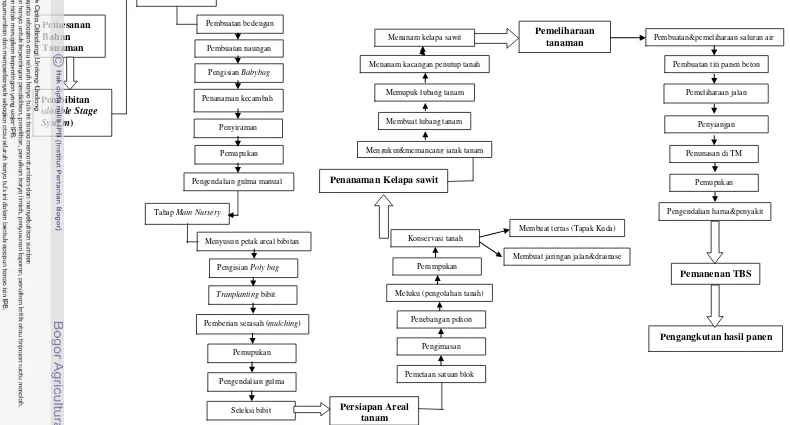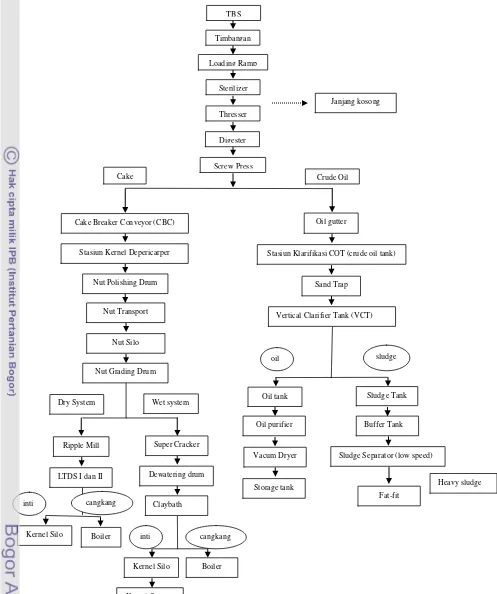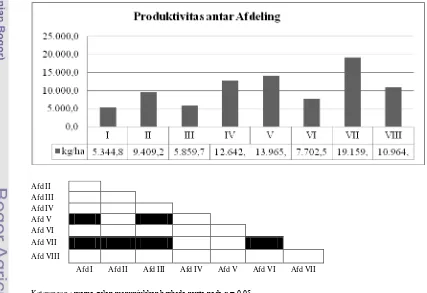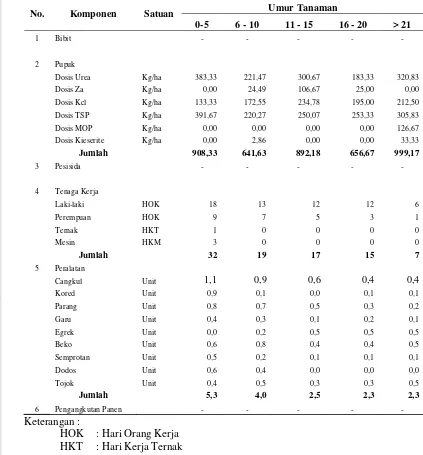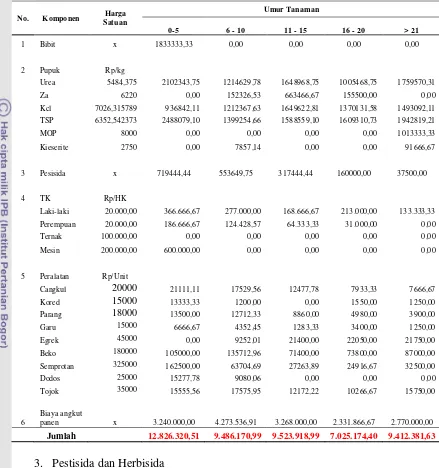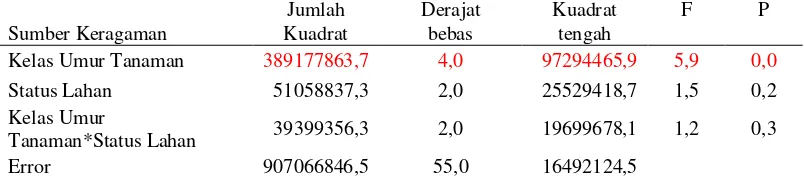ANALISIS PENGELOLAAN KEBUN DAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT SERTA HUBUNGANNYA DENGAN HIRARKI DESA-DESA DI
KECAMATAN TORGAMBA, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA
Oleh :
Onie Suwartika
A14063310
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN
FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
iv
RINGKASAN
ONIE SUWARTIKA. Analisis Pengelolaan Kebun dan Produktivitas Kelapa Sawit serta Hubungannya dengan Hirarki Desa-desa di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. (Dibimbing oleh (SANTUN R.P SITORUS dan DYAH RETNO PANUJU).
Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang dewasa ini sangat
diminati untuk dikelola atau ditanam, baik oleh BUMN, perkebunan swasta
maupun petani (perkebunan rakyat). Produktivitas kelapa sawit perlu diketahui
agar dapat disusun suatu sistem pengelolaan perkebunan dengan tingkat
produktivitas yang tinggi sehingga mampu bersaing di pasar dunia serta dapat
meningkatkan tingkat perkembangan desa-desa di sekitar areal perkebunan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kebun dan pengolahan
Tandan Buah Segar (TBS) serta tingkat produktivitas kelapa sawit di kebun inti
dan plasma, mengetahui struktur biaya usahatani antar kelas umur tanaman di
kebun plasma dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit,
serta mengetahui hirarki perkembangan desa-desa.
Pengelolaan kebun dan pengolahan TBS di PT. Perkebunan Nusantara-III
Kebun Torgamba dari proses Pembibitan sampai pengangkutan hasil panen sudah
baik karena telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan.
Namun, semangat atau etos kerja pekerja kebun tergolong masih kurang baik
terutama dari masyarakat lokal, dilihat antara lain dari kurangnya disiplin jam
masuk dan pulang kerja serta keseriusan dalam bekerja.
Tingkat produktivitas kelapa sawit antar Afdeling di kebun inti berbeda
nyata. Produktivitas tertinggi terdapat pada Afdeling VII sedangkan produktivitas
terendah terdapat pada Afdeling I. Umur tanaman 27 tahun menghasilkan
produktivitas tertinggi sedangkan umur tanaman 3 tahun menghasilkan
produktivitas terendah. Produktivitas kelapa sawit di kebun inti lebih tinggi
dibandingkan dengan produktivitas kelapa sawit di kebun plasma.
Pada status kepemilikan lahan yang sama yaitu lahan milik sendiri di
kebun plasma, produktivitas tanaman umur 6-10 tahun dan 11-15 tahun berbeda
nyata dengan produktivitas tanaman umur > 21 tahun, produktivitas tanaman pada
kelompok umur 0-5 tahun berbeda nyata dengan produktivitas tanaman umur
v
berbeda menghasilkan produktivitas yang berbeda pula. Produktivitas tanaman
umur 11-15 tahun yang dikelola di lahan sewa lebih tinggi (16 ton/ha)
dibandingkan dengan produktivitas tanaman umur 11-15 tahun di lahan milik
sendiri (15 ton/ha) dan lahan garap (8 ton/ha).
Penggunaan input usahatani dengan biaya usahatani tertinggi adalah pada
kelas umur tanaman 0-5 tahun. Semakin meningkat umur tanaman maka biaya
usahatani yang dibutuhkan semakin rendah. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata
terhadap produktivitas kelapa sawit di kebun plasma adalah pendidikan petani,
teknik pemupukan, umur tanaman dan bibit, pekerjaan sampingan dan status
kepemilikan lahan.
Berdasarkan hasil analisis skalogram tahun 2003 dan 2008, dalam kurun
waktu 5 tahun, beberapa desa di Kecamatan Torgamba telah mengalami
perubahan hirarki baik berupa peningkatan atau penurunan dan sebagian lagi
tetap. Desa yang mengalami peningkatan perkembangan ada 2 yaitu desa Asam
Jawa dan desa Torgamba. Desa yang mengalami penurunan perkembangan ada 4
yaitu desa Beringin Jaya, Bangai, Rasau, dan Aek Raso. Sisanya ada 8 desa yang
tidak mengalami perubahan perkembangan (hirarki tetap), yaitu desa Aek Batu,
Bunut, Pinang Dame, Bukit Tujuh, Pangarungan, Teluk Rampah, Sungai Meranti,
vi
SUMMARY
ONIE SUWARTIKA. An Analysis of Management and Productivity of Oil Palm Plantation and Its Relation to the Villages Hierarchies in the Torgamba District, South Labuhanbatu Regency, North Sumatera Province. (Under Supervision of
SANTUN R.P SITORUS and DYAH RETNO PANUJU).
Oil palm is currently in great demand to be managed or planted, either by
the state-owned, private estates or farmers (smallholders). Oil palm productivity
should be known to set up an effective management system for plantations with
high productivity level so it will be able to compete in world markets and could
lift up development of rural areas around the plantation. This research aims to
understand the management of plantation and processing of fresh fruit bunches
(FFB), to determine the level of productivity of oil palm in the nucleus and
plasma, to know the cost structure of farming among age classes of plants in
plasma estate and the factors affecting productivity of oil palm, and to know the
hierarchy of villages development.
Plantation management and processing of FFB in the PT. Perkebunan
Nusantara III Torgamba estate from nursery process up to process to transport the
harvest are good because they have followed the Standard Operating Procedure
(SOP) of the company. However, the work spirit or ethos of plantation workers
was still not good, especially local communities, is indicated among others from
lack of discipline both in implementing working hours and in seriousness during
the work.
The productivity level of oil palm in the nucleus among Afdeling
significantly different, the highest productivity found in Afdeling VII while the
lowest productivity in Afdeling I. In terms of age of plants, plants with age of 27
years produce the highest productivity whereas the 3-year old plant, produce the
lowest productivity. Productivity of oil palm in the nucleus is higher than the
productivity of oil palm in the plasma.
Similarly, in terms of land ownership status, land owned by farmer himself
in plasma plantation, crop productivity of plants age 6-10 years and 11-15 years
significantly different from the productivity of plants age > 21 years. Crop
productivity of plants in 0-5 years age group significantly different with crop
vii
land tenure produce different productivity. Crop productivity of plants age 11-15
years who are managed in renting land is higher (16 tons/ha) compared with the
productivity of plants age 11-15 years on land owned by farmer himself (15
tons/ha) and land working on (8 ton/ha).
The highest cost of farm inputs is in a class of plant age of 0-5 years. The
more age of the plant, the lower the costs of farming required. Factors affecting
significantly on productivity of oil palm on plasma are education of farmers,
fertilization technique, age of plants and seeds, supporting job and status of land
ownership.
The scalogram analysis in 2003 and 2008 show that within a period of 5
years, several villages in the Torgamba district has changes their hierarchies,
either increase, or decrease but the others still remain. Two Villages increased
their development hierarchies those are Asam Jawa and Torgamba villages. Four
Village has decreased their development hierarchies, those are Beringin Jaya,
Bangai, Rasau, and Aek Raso villages. The rest 8 villages have the same
hierarchies level (fixed hierarchy), namely Aek Batu, Bunut, Pinang Dame, Bukit
ii
ANALISIS PENGELOLAAN KEBUN DAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT SERTA HUBUNGANNYA DENGAN HIRARKI DESA-DESA DI
KECAMATAN TORGAMBA, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA
Oleh : Onie Suwartika
A14063310
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar SARJANA PERTANIAN
pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN
FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
iii
LEMBAR PENGESAHAN
Judul : Analisis Pengelolaan Kebun dan Produktivitas Kelapa Sawit serta Hubungannya dengan Hirarki Desa-desa di Kecamatan Torgamba,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi
Sumatera Utara
Nama Mahasiswa : Onie Suwartika
Nomor Pokok : A14063310
Disetujui,
Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,
Prof. Dr. Ir. Santun R.P. Sitorus Dyah Retno Panuju SP. M.Si
NIP 19490721 197302 1 001 NIP 19710412 199702 2 005
Diketahui,
Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc
NIP. 19621113 198703 1 003
viii
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Torgamba, Sumatera Utara pada tanggal 25 Agustus
1987, dari pasangan Bapak Kliwon dan Ibu Sri Taviv Handayani, sebagai anak ke
dua dari tiga bersaudara.
Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari TK Sri Melati Torgamba
tahun 1992. Dua tahun setelah itu, penulis mengenyam pendidikan di SD TPI
(Taman Pendidikan Islam) Torgamba dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun yang
sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Swasta YPTG (Yayasan
Perguruan Torgamba), yang kemudian dilanjutkan di SMA Negri 1 Rantau
Selatan dan lulus tahun 2006. Melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB)
penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Program Studi Manajemen
Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian tahun 2006.
Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mendapatkan kesempatan
menjadi anggota dalam kepengurusan HIMLAB (Himpunan Mahasiswa Labuhan
Batu) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Faperta serta beberapa
kegiatan kepanitiaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT). Penulis juga
berpartisipasi menjadi asisten praktikum Perencanaan Pengembangan Wilayah
dan Perencanaan Tata Ruang dan Penatagunaan Lahan. Selain itu, penulis juga
menjalani kegiatan tambahan di luar kuliah, yaitu mengajar les private untuk murid SLTP.
ix
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul
”Analisis Pengelolaan Kebun dan Produktivitas Kelapa Sawit serta Hubungannya dengan Hirarki Desa-desa Di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara”. Kegiatan penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana di Departemen Ilmu
Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr Ir Santun R.P. Sitorus dan Ibu Dyah Retno Panuju SP.
M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 1 dan 2, yang telah banyak
bersabar dalam membimbing serta memberikan saran dalam pelaksanaan
penelitian dan penyusunan skripsi ini,
2. Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya baik itu dalam bentuk
moril dan materil, memberikan do’a serta motivasi,
3. Kakak-kakak tersayang (Safitri Rahayu dan Heri Azhari) yang selalu
menjadi penyemangat hidup dan telah banyak membantu selama magang,
4. Kakanda Surya Hoirul Ahsan Dalimunthe yang selalu memberikan
kebahagiaan tulus hingga hati ini tetap tenang dan tegar,
5. Yunda Sirri Hidayani beserta keluarga yang telah membantu
memperlancar pengambilan data selama penelitian di lapang,
6. Ibu Asdar, Mbak Emma dan Mbak Dian yang telah banyak membantu
dalam penyediaan data, dan atas saran dan motivasinya,
7. Sahabatku Ivong Verawaty dan Agatha Septiana yang selalu menemani
dalam suka dan duka,
8. Teman-teman Bangwilers 43 (Sony Nugroho, Mila Mulyani, Intan
Laksmita Sari, Ratri Ariani, Haqu) serta teman-teman MSL 43 (Arin,
Manda, Nahrul, luluk, dll) penulis ucapkan terima kasih untuk
kebersamaan kita dan salam ”VIVA SOIL”,
9. Teman-teman kosan Siti Mawaddah, Pratiwi Eka Puspita, Mahmudah,
x
Fauziah, mbk Malya dan Mbak Suhesti Roza yang telah mendengarkan
semua perasaan yang dirasa saat penyusunan skripsi ini, I love you all.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu
hingga penyusunan skripsi ini selesai.
Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis
mengharapkan saran yang berguna dan membangun untuk penyempurnaannya.
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.
Bogor, Juli 2011
xi
2.4 Produktivitas Kelapa Sawit antara Perkebunan Inti dengan Plasma. 13
2.5 Konsep Usahatani ... 14
3.4.1 Analisis Pengelolaan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kebun Torgamba ... 20
3.4.2 Teknik Analisis Data Menggunakan Statistik Uji-T ... 21
3.4.3 Analisis Ragam (ANOVA) Uji Lanjut Metode Tukey ... 22
xii
V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31
5.1 Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dan Pengolahan Tandan Buah Segar di PTPN-III Kebun Torgamba... 31
5.1.1 Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit ... 31
5.1.2 Pengolahan Tandan Buah Segar ... 34
5.2 Produktivitas Kelapa Sawit di Kebun Inti dan Plasma ... 35
5.2.1 Tingkat Produktivitas antar Afdeling dan Umur Tanaman di Kebun Inti ... 35
5.2.2 Perbandingan Tingkat Produktivitas antara Kebun Inti dan Plasma menurut Kelas Umur Tanaman ... 38
5.3 Struktur Biaya Usahatani Menurut Kelas Umur Tanaman di Kebun Plasma ... 40
5.4 Perbandingan Produktivitas Menurut Kelas Umur Tanaman dan Status Kepemilikan Lahan ... 45
5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Usahatani Sawit di Kebun Plasma ... 48
5.6 Hirarki/Tingkat Perkembangan Desa-desa di Kecamatan Torgamba 55
VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 60
6.1. Kesimpulan ... 60
6.2. Saran ... 61
DAFTAR PUSTAKA ... 62
xiii
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
Teks
1. Perbandingan Produktivitas Kelapa Sawit di Kalimantan dan
Sumatera terhadap standar kelas kesesuaian lahan S-3 ... 13
2. Produktivitas Kelapa Sawit pada Kebun Inti dan Plasma di Kalimantan Timur dan Sumatera Utara ... 14
3. Jumlah responden pada masing-masing KUD ... 20
4. Variabel-variabel yang digunakan dalam Analisis Skalogram... 27
5. Nilai Selang Hirarki Pusat Pelayanan ... 27
6. Luas Areal Kebun pada 3 KUD ... 28
7. Komposisi Penduduk menurut Golongan Umur ... 30
8. Komposisi Jenis Mata Pencaharian Golongan Umur di atas 18 Tahun .. 30
9. Rekapitulasi Penggunaan Input Usahatani Kelapa Sawit di Kebun Plasma ... 41
10. Rekapitulasi Struktur Biaya Usahatani (Rp) ... 42
11. Tabel ANOVA ... 45
12. Hasil Perhitungan Uji Tukey ... 46
13. Akar Ciri Komponen-komponen Utama ... 49
14. Nilai Kumulatif Akar Ciri Hasil Analisis Faktor ... 49
15. Nilai Factor Loading Analisis Komponen Utama ... 50
16. Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Produktivitas sebagai Fungsi Tujuan ... 51
17. Persamaan Hasil Analisis Regresi Berdasarkan Karakteristik Responden ... 52
18. IPD dan Hirarki Desa-desa di Kecamatan Torgamba Tahun 2003 dan 2008 ... 56
19. Keterkaitan Produktivitas Kelapa Sawit dengan Hirarki Desa ... 58
xiv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
Teks
1. Peta Lokasi Penelitian ... 19
2. Diagram Alir Proses Pengelolaan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Torgamba ... 32
3. Diagram Alir Pengolahan TBS di Pabrik Kelapa Sawit Torgamba ... 33
4. Tingkat Produktivitas antar Afdeling di Kebun Inti ... 36
5. Tingkat Produktivitas antar Umur Tanaman di Kebun Inti ... 37
6. Perbandingan Nilai Tengah Produktivitas antar Kelas Umur Tanaman . 39
7. Box Plots Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit pada Berbagai Umur Tanaman di Lahan (a) Inti dan (b) Plasma ... 39
8. Grafik Jumlah Biaya Usahatani per hektar Menurut Kelas Umur Tanaman ... 44
9. Grafik Produktivitas Kelapa Sawit antar Status Kepemilikan Lahan pada Kelompok Umur Tanaman 11-15 Tahun ... 48
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
Teks
1. Nilai PC scores Hasil PCA ... 64 2. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2003 ... 67
3. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2008 ... 68
4. Produktivitas Kelapa Sawit Menurut Umur Tanaman dan Afdelingnya
di Kebun Torgamba ... 69
I. PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang
Perluasan areal perkebunan kelapa sawit terus berlanjut akibat
meningkatnya harga minyak bumi sehingga peran minyak nabati meningkat
sebagai energi alternatif. Sampai saat ini, penanaman kelapa sawit telah
berkembang di 16 provinsi. Sebagian besar areal kelapa sawit tersebut terdapat di
provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat
berturut-turut sebesar 21,7%, 20,6%, 10% dan 9,6% dari total areal kelapa sawit di
Indonesia (Ditjenbun, 1998).
Salah satu peran dari Industri kelapa sawit adalah memberikan lapangan
kerja sekitar 3,5 juta Kepala Keluarga (KK) mulai dari on-farm sampai off-farm. Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga
kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara
positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta
lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa
yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan
pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang
(backward linkages). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang,
perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama
proses tersebut. Sementara itu, pada kegiatan pascapanen dan proses pengolahan
akan mempunyai keterkaitan ke depan (foreward linkages). Proses foreward
linkages yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang
memproduksi alat produksi pertanian (Syahza, 2007). Semua aktivitas ini akan
meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya serta
berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang
jasa dan perdagangan. Selain itu, pembangunan industri tersebut juga harus
mampu memakmurkan rakyat pekebun dan mendorong pembangunan wilayah
perdesaan.
2
Pada umumnya, sebagian besar wilayah perkebunan sawit dikembangkan
dengan membuka lahan baru (ekstensifikasi pertanian) atau belum diusahakan
sebelumnya. Dengan adanya pembukaan lahan untuk ekstensifikasi pertanian
mengakibatkan perubahan yang luar biasa pada sistem tataan atau hidrologi, erosi,
iklim mikro, dan produksi biomassa. Perubahan hutan menjadi perkebunan
monokultur kelapa sawit akan menimbulkan masalah segera setelah pembukaan
lahan seperti daur hara pada sistem siklus tertutup menjadi terputus oleh adanya
perubahan tegakan biomassa. Penurunan produksi biomassa akan menurunkan
produktivitas tanah bila tidak ada tindakan konservasi tanah dan penerapan kultur
teknis yang baik. Penurunan produktivitas ini diakibatkan oleh menurunnya rezim
kelembaban tanah, meningkatnya erosi, dan menurunnya kualitas fisik dan kimia
tanah (Barchia, 2009).
Oleh sebab itu, tingkat produktivitas kelapa sawit perlu diketahui agar
dapat dibentuk sebuah sistem perkebunan kelapa sawit dengan tingkat
produktivitas yang tinggi sehingga tetap mampu bersaing di pasar dunia.
Keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak saja ditentukan oleh
potensi lahan dan ketersediaannya, tetapi juga ditentukan oleh kelengkapan sarana
dan prasarana, pelayanan, aksesibilitas dan transportasi, kependudukan, tenaga
kerja serta kelembagaan. Untuk itu, diperlukan juga pendekatan wilayah yang
berkenaan dengan struktur pusat-pusat kegiatan dan pelayanan dalam suatu sistem
hirarki sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan perdesaan di sekitar areal
perkebunan.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui pengelolaan kebun dan pengolahan tandan buah segar (TBS)
2. Mengetahui perbandingan tingkat produktivitas kelapa sawit di kebun inti
dan plasma
3. Mengetahui struktur biaya usahatani antar kelas umur tanaman dan tingkat
produktivitas menurut kelas umur dan status kepemilikan lahan di kebun
3
4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit
di kebun plasma
5. Mengetahui hirarki/tingkat perkembangan desa-desa di kecamatan
4
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Ekofisiologi Tanaman Kelapa Sawit
Dalam konteks ekofisiologi, faktor lingkungan yang dominan
mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit adalah faktor iklim dan
keadaan tanah. Faktor iklim meliputi intensitas sinar matahari, temperatur, curah
hujan, dan kelembaban udara, sedangkan syarat tanah meliputi sifat fisik dan
berkisar antara 1500 – 2500 mm dengan penyebaran merata sepanjang tahun dan
tidak terdapat bulan kering yang nyata. Adanya bulan kering lebih dari dua bulan
berturut – turut akan memberikan pengaruh terhadap penurunan produksi pada tahun – tahun berikutnya. Bulan kering > 3 bulan sudah merupakan pembatas berat untuk kelapa sawit, begitu juga defisit air > 400 mm per tahunnya sudah
merupakan pembatas berat. Lama penyinaran matahari tidak boleh kurang dari 5 –
7 jam per hari dan kelembaban nisbi yang diinginkan berkisar 50 – 90% atau optimalnya pada kelembaban 80%.
2.1.2. Tanah
Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh secara baik pada berbagai jenis tanah,
seperti Podsolik (Ultisol), Latosol, Hidromorfik Kelabu, Regosol, Andosol, dan
tanah Alluvial (Fauzi et al., 2003) bahkan pada tanah gambut dengan syarat ketebalan gambut yang dapat ditoleransi mencapai 150 cm (Pahan, 2008). Namun
kemampuan produksi pada jenis tanah tersebut tidak sama. Ada dua sifat tanah
dan lingkungan yang menentukan baik tidaknya tanah sebagai media tumbuh :
1. Sifat fisik Tanah
Beberapa hal yang menentukan sifat tanah adalah tekstur, struktur,
konsistensi, kemiringan tanah, permeabilitas, ketebalan lapisan tanah dan
kedalaman permukaan air tanah. Beberapa kesesuaian sifat fisik tanah untuk
5
a) Mempunyai solum yang tebal sekitar 80 cm. Walaupun kenyataan bahwa
penyebaran akar kelapa sawit yang terbanyak dijumpai sampai kedalaman
60 cm, namun ujung akar masih mencapai kedalaman 90 cm atau lebih,
sehingga dibutuhkan untuk perkembangan akar yang baik. Kedalaman
efektif yang ideal adalah minimum 100 cm.
b) Lapisan tanah yang keras atau padas dengan tingkat kekerasan >3,0
kg/cm2 pada kedalaman <50 cm merupakan pembatas berat bagi kelapa
sawit.
c) Tekstur yang ideal adalah pada kisaran liat berpasir, lempung liat berpasir,
lempung berdebu, lempung dan lempung liat berdebu. Tanah dengan
tekstur pasir kasar dan liat berat yang masif merupakan pembatas berat
untuk kelapa sawit.
d) Perkembangan struktur yang kuat, konsistensi gembur sampai agak teguh
dengan permeabilitas yang sedang sampai baik.
e) Permukaan air harus berada di bawah 80 cm dan semakin dalam semakin
baik.
f) Tanah yang kurang cocok adalah tanah pantai berpasir dan tanah gambut
tebal.
Topografi yang cukup baik untuk kelapa sawit adalah kemiringan 0 – 15%
(datar-berombak). Hal ini memudahkan pengangkutan buah dari areal ke pabrik.
Areal dengan kemiringan > 15% (berbukit-curam) masih mungkin ditanami, tetapi
perlu dibuat teras, karena akan menyulitkan panen serta pengangkutan tandan
buah segar (TBS) ke pabrik (Adiwiganda et al., 1997). Selain itu, tanah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% juga beresiko besar mengalami erosi permukaan
cukup berat. Topografi lahan yang tidak disertai dengan penerapan konservasi
tanah yang standar (teras individu/kontur) berpengaruh terhadap produksi kelapa
sawit dan penggunaan tenaga panen.
Berdasarkan hasil penelitian Dja'far et al. (2001), perbedaan produksi areal yang bertopografi berombak dengan lahan yang berbukit bisa mencapai 3,96
tonTBS/ha/tahun (28,84%). Pada daerah berbukit walaupun pemakaian tenaga
panen lebih banyak 9,11 % dibandingkan dengan daerah berombak tetapi produksi
6
dipanen serta kehilangan brondolan mencapai 51,36%. Hasil analisis
menunjukkan pengaruh topografi lahan terhadap produksi adalah sebesar 14,56 %
dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti penerapan kultur teknis, sumber
daya manusia, kesuburan lahan dan varietas tanaman.
Bentuk wilayah kebun kelapa sawit plasma di Sei Pagar umumnya datar
dengan kemiringan 0-3% dan hanya sebagian kecil saja wilayah dengan
kemiringan 3-5%. Vegetasi yang menutupi permukaan tanah di seluruh areal
perkebunan terdiri atas rumput-rumputan alami, pakis resam, lumut-lumutan, dan
tumbuhan perdu pendek lainnya. Di antara dua barisan pohon kelapa sawit
terdapat tumpukan pelepah dahan dan daun kelapa sawit hasil pangkasan.
Tumpukan material tersebut berfungsi sebagai penyangga atau penghalang
hanyutnya tanah oleh aliran permukaan, sebagai mulsa untuk mencegah gulma
dan menjaga suhu tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, erosivitas hujan (R)
untuk lokasi perkebunan plasma Sei Pagar diperkirakan sebesar 1,750 dengan
erodibilitas tanah (K) berkisar antara 0,265-0,345 serta nilai faktor penutupan
tanaman dan konservasi tanah (CP) diasumsikan sebesar 0,01. Prediksi erosi tanah
pada bentuk wilayah di lahan perkebunan tersebut menunjukkan bahwa besarnya
erosi berkisar antara 1,322-3,423 t/ha/tahun, jauh di bawah erosi yang masih dapat
diabaikan (tolerable soil loss, TSL) dengan nilai sekitar 15 t/ha/tahun (Wigena et al., 2009).
2. Sifat Kimia Tanah
Sifat kimia tanah mempunyai arti penting dalam menentukan kelas
kesuburan tanah dan dosis pemupukan. Namun, menurut Adiwiganda et al. (1995)
sifat kimia tidak terlalu diperhitungkan dalam plotting areal sawit karena kesuburan kimia tanah secara umum dapat dikendalikan melalui pemupukan yang
rasional. Beberapa sifat kimia tanah yang dipakai sebagai pedoman untuk tanaman
kelapa sawit adalah :
a) Kemasaman (pH) yang diinginkan berkisar antara 4,0-6,0, sedangkan pH
optimumnya 5,0 - 5,5. Kemasaman (pH) <3,5 dan >7,0 adalah pembatas
berat bagi kelapa sawit (Adiwiganda et al., 1997).
7
c) Daya tukar Mg dan K berada pada batas normal, yaitu Mg 0,4 – 10 me/100
gram, sedangkan K 0,15 – 1,20 me/100 gram.
Berhubung tanaman kelapa sawit dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah,
maka tanaman ini termasuk tanaman yang relatif mudah dibudidayakan. Keadaan
demikian menyebabkan tanaman kelapa sawit dapat beradaptasi dengan sifat
kimia tanah yang ekstrem sekalipun, dengan catatan ketinggian lahan tidak lebih
dari 500 meter di atas permukaan laut (Fauzi et al., 2003). Menurut Sastrosayono
(2006), yang penting tanaman tidak kekurangan air pada musin kemarau dan tidak
tergenang pada musim hujan (drainase baik). Di lahan-lahan yang permukaan air
tanahnya tinggi atau tergenang, akar akan busuk. Selain itu, pertumbuhan batang
dan daunnya tidak mengindikasikan pertumbuhan tanaman yang baik.
2.2. Kultur Teknis Kelapa Sawit 2.2.1. Pembibitan
Secara garis besar, menurut Setyamidjaja (2006) teknik budidaya tanaman
kelapa sawit meliputi pengadaan bibit, pembukaan lahan, pembuatan rancangan
kebun, penanaman bibit kelapa sawit, penanaman tanaman penutup tanah,
pemeliharaan tanaman, dan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM).
Pembibitan merupakan kegiatan awal di lapangan yang bertujuan untuk
mempersiapkan bibit siap tanam. Pemilihan lokasi pembibitan harus memenuhi
beberapa persyaratan, antara lain adalah pada areal datar atau bila tidak datar
sebaiknya dibuat teras, dekat dengan sumber air, berada di tengah-tengah areal
yang akan ditanami, bebas dari gangguan hewan liar maupun piaraan, dan mudah
dikunjungi serta diawasi.
Sistem pembibitan kelapa sawit yang digunakan dalam perkebunan kelapa
sawit terdiri dari dua macam sistem, yaitu (1) single stage system (sistem pembibitan satu tahap) dan (2) double stage system (sistem pembibitan dua tahap). Pembibitan satu tahap artinya penanaman kecambah langsung pada pembibitan
utama tanpa tahap pembibitan awal, sedangkan pada sistem pembibitan dua tahap
terdapat dua tahapan, yaitu tahap pembibitan awal (pre nursery) dan tahap pembibitan utama (main nursery).
Pemeliharaan persemaian (pre nursery) dan pemeliharaan pembibitan
8
penyiraman, penyiangan gulma, pemupukan, penanggulangan hama dan penyakit,
serta semai/bibit. Menurut Pahan (2008), Perawatan yang baik akan
meningkaatkan vigor bibit yang nantinya akan berdampak pada peningkatan
produksi pada tahun pertama menghasilkan (TM-1). Secara umum, karakter yang
menyimpang pada tanaman kelapa sawit dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis,
yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk anak daun (leaflet), dan kelainan daya pertumbuhan.
2.2.2. Pembukaan Lahan
Cara pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit disesuaikan dengan
kondisi lahan yang tersedia, yaitu:
1. Bukaan baru (new planting) pada hutan primer, hutan sekunder, semak
belukar atau areal yang ditumbuhi lalang
2. Konversi, yaitu penanaman pada areal yang sebelumnya ditanami dengan
tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, atau komoditas tanaman
perkebunan lainnya.
3. Bukaan ulangan (replanting), yaitu areal yang sebelumnya telah ditanami kelapa sawit.
Luas lahan perkebunan kelapa sawit berkisar antara 6.000 – 12.000 hektar
sudah sesuai dengan kapasitas pabrik yang dibangun untuk pengolahan hasilnya.
Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan secara mekanis,
kimia, atau manual (Setyamidjaja, 2006). Tahapan pekerjaan yang dilakukan
dalam pembukaan lahan kelapa sawit meliputi babat pendahuluan, menumbang,
merencek (memotong cabang dan ranting kayu), serta merumpuk (menumpuk
hasil tebangan).
2.2.3. Rancangan Kebun
Setelah pembukaan lahan selesai, langkah selanjutnya adalah membuat
rancangan untuk menetapkan lokasi-lokasi emplasement (kantor dan pabrik),
perumahan (pondok-pondok) bagi karyawan dan pekerja kebun, jalan-jalan kebun,
jembatan dan sebagainya. Rancangan kebun yang penting adalah jaringan jalan
dan jembatan, karena sangat diperlukan untuk kegiatan rutin di kebun dan
9
kelapa sawit diberi nama sesuai dengan kepentingannya dan dikenal beberapa
jalan sebagai berikut :
1. Jalan utama, yaitu jalan yang menghubungkan afdeling dengan emplasement,
afdeling dengan afdeling, dan keluar kebun/emplasement.
2. Jalan pengangkutan hasil atau jalan produksi, yaitu jalan yang digunakan
dalam pengangkutan hasil dari kebun ke pabrik. Tempat pengumpulan hasil
(TPH) berada pada jalan ini.
3. Jalan kontrol, yaitu jalan yang berfungsi sebagai batas blok atau batas
pinggiran kebun, untuk memudahkan pelaksanaan pengontrolan (pengawasan)
kebun oleh pimpinan kebun (Administratur, Asisten Kepala, Asisten, dll.).
2.2.4. Penanaman Tanaman Penutup Tanah
Tanaman penutup tanah adalah tanaman kacangan (legume cover crops,
LCC) yang ditanam untuk menutupi tanah yang terbuka di antara kelapa sawit karena belum terbentuk tajuk yang dapat menutup permukaan tanah. Jenis-jenis
tanaman kacangan penutup tanah yang umum ditanam di perkebunan kelapa sawit
adalah Calopogonium caeruleum, Calopogonium mucunoides, Pueraria javanica,
Pueraria phaseoloides, Centrocema pubescens, Psophocarphus palustries, dan Mucuna cochinchinensis (Setyamidjaja, 2006)
Menurut Pahan (2008), manfaat kacang-kacangan dalam pengusahaan
tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut :
a. Menambah bahan organik sehingga memperbaiki struktur tanah
b. Memperbaiki status hara tanah, terutama nitrogen
c. Memperbaiki sifat-sifat tanah akibat pembakaran (pembukaan lahan)
d. Melindungi permukaan tanah dan mengurangi bahaya erosi, terutama pada
tanah yang curam
e. Mengurangi biaya pengendalian gulma
f. Mendorong pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi
2.2.5. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan
Tanaman belum menghasilkan (TBM) adalah tanaman kelapa sawit yang
berada pada umur mulai ditanam hingga berumur kurang lebih 2,5 – 3 tahun. Beberapa kegiatan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang penting
10
1. Penyulaman
Penyulaman (menyisip) adalah mengganti tanaman yang mati, rusak berat,
atau tumbuh abnormal dengan bibit yang baru.
2. Pembuatan dan pemeliharaan piringan
Piringan atau bokoran (circle weeding) adalah lingkungan di sekitar individu tanaman yang dijaga agar selalu dalam keadaan bersih, pada
radius antara 1,0 – 1,5 m dari pokok kelapa sawit. Pemeliharaan piringan
yang penting adalah penyiangan gulma yang tumbuh pada piringan dengan
cara dikored, dibabat, atau disemprot dengan herbisida.
3. Pemeliharaan tanaman kacangan penutup tanah
Adapun pemeliharaan tanaman kacangan penutup tanah (legume cover
crops, LCC) adalah sebagai berikut :
a. Membuang gulma yang tumbuh di antara kacangan baik gulma yang
menghindarkan kekurangan B (Boron deficiency) karena kekurangan
Boron dapat mengakibatkan kematian pada tanaman kelapa sawit muda.
Sementara itu, kekurangan unsur N, P, K, dan Mg hanya akan
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman sehingga tanaman akan
tumbuh lambat dan kerdil, tetapi tidak sampai mematikan. Jenis-jenis
pupuk yang digunakan adalah Urea atau ZA (N), Rock Phosphate (P),
Muriate of Potash (K), Kieserite (Mg), dan Borax (B).
5. Pemangkasan daun
Tujuan pemangkasan daun adalah untuk memperoleh pokok yang bersih,
jumlah daun yang optimal dalam satu pohon, dan memudahkan pekerjaan
panenan bila tanaman sudah berproduksi.
11
6. Kastrasi bunga
Kastrasi adalah pemotongan atau pembuangan bunga jantan dan bunga
betina yang masih muda yang telah tumbuh pada tanaman yang berumur
12 – 20 bulan. Kastrasi berlangsung hingga 6 bulan sebelum panen yang pertama dimulai. Tujuan kastrasi bunga adalah :
a. Untuk merangsang pertumbuhan vegetatif dan menghemat penggunaan
unsur hara dan air, terutama bagi daerah yang curah hujannya relatif
rendah.
b. Menciptakan keadaan tanaman lebih bersih sehingga mengurangi
kemungkinan terjadinya gangguan hama (tikus, tupai) dan
berjangkitnya penyakit Marasmius sp..
c. Memudahkan pelaksanaan penyerbukan buatan karena keadaan
mahkota tanaman lebih bersih.
Rotasi pelaksanaan kastrasi adalah sebulan sekali dan pemotongan bunga
yang dimaksud menggunakan dodos atau IRHO tools.
7. Penyerbukan bantuan
8. Pengendalian hama dan penyakit
Beberapa hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman muda (TBM)
adalah jenis serangga, misalnya kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros), kumbang (Apogonia sp.), belalang (Valanga sp.), dan ulat perusak daun. Beberapa kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) adalah
pengendalian gulma, pemupukan, penjarangan, pemeliharaan jalan, serta
pengendalian hama dan penyakit. Upaya pengendalian gulma telah dilaksanakan
dengan menanami tanaman kacangan penutup tanah di antara tanaman kelapa
sawit (gawangan) dan membuat piringan di sekeliling tiap individu tanaman.
2.3. Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit
Produktivitas tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh iklim, jenis tanah,
serta kegiatan kultur teknis. Kegiatan kultur teknis mencakup pemupukan,
pengendalian hama dan penyakit, penunasan dan kegiatan panen. Perkebunan
kelapa sawit di Indonesia 60% tanahnya merupakan tanah Ultisols memiliki
kualitas yang rendah dimana pH tanah < 5, KTK tanah rendah, <15 me/100g,
12
sangat tinggi (Adiwiganda et al., 1997). Produktivitas tanah Ultisols yang rendah ini harus diiringi dengan pemupukan yang berimbang untuk mendapat hasil yang
optimum. Bila tidak dilakukan perbaikan kesuburan tanahnya, produksi tanaman
yang diusahakan pada tanah tropika ini sangat rendah.
Pemupukan yang berimbang perlu dilakukan sehubungan dengan tingkat
kesuburan dan produksi yang rendah sehingga produktivitas tanah tropika dapat
ditingkatkan. Prinsip pemupukan berimbang bertujuan untuk mencapai
pemupukan yang efektif dan efisien. Konsep pemupukan berimbang harus
diterapkan berdasarkan status hara tanah dan kebutuhan hara tanaman.
Pemupukan berimbang adalah upaya untuk meningkatkan mutu intensifikasi
dengan menambah jenis dan takaran pupuk. Dosis pupuk yang berimbang dibuat
atas dasar beberapa pertimbangan antara lain; 1) jumlah hara yang terangkut oleh
hasil panen, 2) jumlah hara yang terimmobilisasi dalam batang, cabang,
pelepah/daun, 3) jumlah hara yang dikembalikan ke dalam tanah, 4) jumlah hara
yang terfiksasi dan hilang dalam tanah, dan 5) jumlah hara yang tersedia dalam
tanah.
Pemupukan perlu dilakukan secara rasional sesuai dengan kebutuhan
tanaman, kemampuan tanah menyediakan unsur-unsur hara, sifat-sifat tanah, dan
pengelolaan oleh petani. Kelebihan pemberian pupuk selain merupakan
pemborosan, juga mengganggu keseimbangan unsur-unsur hara dalam tanah,
sedangkan pemberian terlalu sedikit tidak akan memberikan produksi yang
optimal. Seperti terlihat bahwa produktivitas tanaman kelapa sawit pada umur 3 –
13 tahun dari beberapa wilayah, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Sumatera Utara dan Riau masih di bawah produktivitas baku lahan kelas
kesesuaian lahan S-3 (Tabel 1). Persentase total produksi rata-rata di Kalimantan
baru sekitar 60 persen, dan di Sumatera baru mencapai 70 persen dari potensi
produksi baku lahan kelas S-3. Produksi standar kelas kesesuaian lahan S-3 untuk
13
Tabel 1. Perbandingan Produktivitas Kelapa Sawit di Kalimantan dan Sumatera terhadap standar kelas kesesuaian lahan S-3
Wilayah Total Produksi (3 - 13 tahun) Perbandingan Produksi terhadap
(Ton TBS/ha) Standar S-3 (%)
Kalimantan Barat 138,1 60,8
Kalimantan Timur 141,8 62,5
Rata-rata 140,2 61,8
Sumatera Utara 174,4 76,9
Riau 142,8 62,9
Rata-rata 158,6 69,9
Sumber:Poeloengan, et al., 2001 dalam Barchia (2009)
Produktivitas tandan buah kelapa sawit dapat diperhitungkan dari
komponen-komponennya, yaitu jumlah tandan dan rata-rata berat tandan.
Rata-rata berat tandan akan meningkat sejalan dengan umur tanaman, sedangkan
jumlah tandan akan menurun dengan semakin bertambahnya umur tanaman
(Siregar, 1998). Pada keadaan normal, tandan buah kelapa sawit dapat mencapai
matang panen untuk pertama kalinya setelah tanaman berumur 3-4 tahun di
lapangan. Produktivitas tandan kelapa sawit meningkat dengan cepat dan
mencapai maksimum pada umur tanaman 8-12 tahun, kemudian menurun secara
perlahan-lahan dengan tanaman yang makin tua hingga umur ekonomis 25 tahun
(Corley, 1976 dalam Siregar, 2003).
2.4. Produktivitas Kelapa Sawit antara Perkebunan Inti dengan Plasma
Produktivitas kelapa sawit pada tanah tropika yang dikelola oleh
perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang dikelola oleh petani.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, teknologi, tenaga, dan modal
dari petani yang mengusahakan tanaman tersebut. Hasil kelapa sawit yang senjang
antara produktivitas di perkebunan inti yang dikelola langsung oleh perusahaan
perkebunan swasta besar dan plasma yang dikelola oleh petani terlihat nyata dari
kebun kelapa sawit di Sumatera Utara seperti disajikan pada Tabel 2.
Produktivitas puncak kebun sawit dicapai pada tahun ke-9 umur tanaman, pada
perkebunan inti dengan hasil dapat mencapai 27,6 ton TBS/ha/tahun, sedangkan
pada kebun plasma hanya berproduksi 13,6 ton TBS/ha/tahun, atau sekitar 50%
14
Rendahnya produktivitas pada kebun plasma disebabkan oleh kualitas
sumberdaya petani plasma dan kemampuan swadayanya yang rendah.
Pengelolaan tanah tropika untuk perkebunan kelapa sawit di tingkat plasma
dihadapkan pada permasalahan adopsi teknologi yang tidak baku teknis karena
keterbatasan pengetahuan dan daya beli sarana produksi yang rendah.
2.5. Konsep Usahatani
Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari
bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan
efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.
Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya
yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila
pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi
15
informasi tentang keragaan suatu usaha tani yang dilihat dari berbagai aspek.
Telaah seperti ini (kajian berbagai aspek) sangat penting karena tiap macam tipe
usahatani pada tiap macam skala usaha dan pada tiap lokasi tertentu berbeda satu
sama lain; karena hal tersebut memang ada perbedaan dalam karakteristik yang
dipunyai pada usahatani yang bersangkutan (Soekartawi, 1995).
Analisis struktur biaya usahatani menurut Soekartawi (1995), biasanya
sering dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) Analisis finansial, dan (b) Analisis
ekonomi. Dalam analisis finansial, data biaya yang dipakai adalah data riil yang
sebenarnya dikeluarkan. Misalnya jumlah tenaga kerja yang dipakai 100 HKSP
(Hari Kerja Setara Pria) dengan upah Rp 3.000/hari; maka biaya tenaga kerja
adalah 100 × Rp 3.000 = Rp 300.000. Bila diantara 100 HKSP tersebut, 25 HKSP
diantaranya adalah tenaga dalam keluarga, maka nilai upah yang dihitung hanya
upah tenaga kerja yang menyewa saja sebesar 75 HKSP tersebut.
Dalam analisis ekonomi, data upah yang dipakai adalah upah menurut
ukuran harga bayangan (shadow price). Upah tenaga kerja di Jawa yang jumlah penduduknya berlebihan ini memungkinkan upah tenaga kerja riil lebih kecil
daripada upah menurut ukuran perhitungan harga bayangan. Mungkin upah
tersebut bernilai Rp 5.000/hari. Bila demikian, biaya untuk 100 HKSP menjadi
100 × Rp 5.000 = Rp 500.000.
Rodjak (2002) mengemukakan bahwa usahatani adalah organisasi dari
alam, kerja, modal yang ditujukan pada produksi di lapangan pertanian.
Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat unsur pokok dalam usahatani yang
saling terkait dalam pengelolaannya, yakni lahan, tenaga kerja, modal, dan
manajemen.
1. Lahan merupakan faktor produksi utama dalam usahatani yang memiliki sifat-sifat khusus, yaitu masih relatif luas, tidak dapat dipisah-pisahkan
dan sangat membutuhkan perawatan (pemupukan). Lahan sebagai faktor
produksi usahatani mengandung pengertian bahwa lahan tersebut harus
dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya (modal, tenaga kerja, dan
keterampilan) sehingga dapat menghasilkan produk yang berupa tanaman
atau ternak. Lahan pada usahatani dapat berupa lahan pekarangan, tegalan,
16
2. Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja sebagai faktor produksi mengandung arti bahwa
tenaga kerja tersebut merupakan sub-sistem produksi, artinya apabila
faktor tenaga kerja tidak ada, maka produksi suatu barang/tanaman dan
ternak tidak akan terjadi atau sistem produksi tidak akan berjalan. Besar
kecilnya peranan tenaga kerja terhadap hasil produksi usahatani akan
dipengaruhi oleh keterampilan tenga kerja yang tercermin oleh tingkat
produktivitasnya. Tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh
jenis kelamin, umur, pengalaman kerja, kesehatan, alat bantu yang
diberikan, serta tingkat upah dan waktu bekerja. Berdasarkan sumbernya,
tenaga kerja berasal dari dalam dan luar rumah tangga (keluarga).
Kebutuhan tenaga kerja dipengaruhi oleh jenis komoditas, jenis tanah yang
diolah, intensitas pengolahan, pola tanam yang dilakukan, keadaan sistem
pengairan, dan tekhnologi. Ada beberapa sistem upah tenaga kerja dalam
usahatani, yaitu sistem upah harian tidak tetap, sistem upah harian tetap,
sistem upah borongan, dan sistem upah kontrak. Konversi tenaga kerja
untuk pria : wanita : anak adalah 1 : 0,8 : 0,5
3. Modal merupakan faktor produksi ketiga yang diartikan sebagai barang ekonomi, artinya bahwa modal merupakan sebagian dari hasil produksi,
yang disisihkan untuk dipergunakan dalam proses produksi selanjutnya.
Modal dapat berupa lahan, bangunan, peralatan, mesin, tanaman
(benih/bibit), stok produksi dan uang tunai. Menurut sifatnya, modal
dibedakan atas :
- Modal tetap, yaitu modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali produksi. Yang termasuk modal tetap diantaranya adalah lahan usaha
yang dimiliki, bangunan, traktor dan bajak, tanaman budidaya, ternak,
alat pembasmi hama dan penyakit.
- Modal tidak tetap atau modal lancar, yaitu modal yang habis digunakan
dalam satu kali produksi perlengkapan, uang tunai, benih, dan piutang.
4. Manajemen usahatani merupakan kemampuan petani dalam menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan faktor-faktor
17
manajemen dalam proses produksi akan tercermin dalam kualitas hasil
usahatani yang diperoleh. Hal ini akan terlihat bahwa apabila suatu
usahatani dikelola oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan keterampilan
yang tinggi, maka akan diperoleh hasil usahatani yang mempunyai kualitas
yang tinggi denagn penggunaan faktor produksi yang efektif dan efisien.
Dengan demikian, keberhasilan usahatani dapat diukur dari produktivitas
yang tinggi dan ditentukan oleh pengelolaan yang baik dari setiap
faktor-faktor produksi tersebut. Hal-hal yang menyebabkan petani sering kurang
berhasil dalam mengelola usahatani adalah;
- Pengetahuan cara produksi (teknologi) yang kurang
- Tidak memiliki akses pada sumber-sumber permodalan
- Kurangnya informasi tentang kondisi pasar
- Belum mampu mengetahui perubahan ekonomi, politik, dan sosial
budaya.
2.6. Perkembangan Wilayah
Konsep perkembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu
daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial,
ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehateraan masyarakat. Pengaruh globalisasi,
pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika
spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan
hingga perdesaan. Pengembangan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang
dilakukan suatu wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya.
Jadi pengembangan wilayah harus dipandang sebagai sutau proses yang memiliki
keterkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya perkembangan tersebut serta dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan
seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan
mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap
pembangunan ke tahap pembangunan selanjutnya (Sitorus, 2006).
Pengembangan perdesaan merupakan suatu pendekatan bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sistem usaha pertanian yang
mengubah struktur kegiatan ekonomi dari yang bercorak subsisten ke modern,
18
wilayah merupakan suatu pendekatan pengarahan proses transformasi ekonomi,
sosial, dan lingkungan ke dalam tatanan ruang berdasarkan pada pengembangan
interaksi ekonomi antar regional, penyediaan infrastruktur dan pengembangan
kawasan permukiman dengan mempertimbangakan pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan
masyarakat. Secara sederhana konsep pengembangan wilayah perlu dilakukan
dalam perencanaan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan
memperkuat masyarakat di lapisan bawah agar dapat mempengaruhi pasar secara
berkelanjutan.
Berdasarkan konsep wilayah nodal, pusat atau hinterland suatu wilayah dapat ditentukan dari kelengkapan fungsi pelayanan suatu wilayah. Secara teknis
hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah dan jenis fasilitas
umum, industri, dan jumlah penduduknya. Unit wilayah yang mempunyai jumlah
dan jenis fasilitas umum, industri, dan jumlah penduduk dengan kuantitas dan
kualitas yang secara relatif paling lengkap dibandingkan dengan unit wilayah lain
akan menjadi pusat atau mempunyai hirarki lebih tinggi. Sebaliknya, jika suatu
wilayah mempunyai jumlah dan jenis fasilitas umum, industri, dan jumlah
penduduk dengan kuantitas dan kualitas paling rendah merupakan wilayah
hinterland dari unit wilayah yang lain (Rustiadi et al., 2009). Secara teoritis, hierarki wilayah sebenarnya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan wilayah
secara totalitas yang tidak terbatas ditunjukkan oleh kapasitas infrastruktur
fisiknya saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia serta
kapasitas perekonomiannya. Dalam perencanaan tata ruang hierarki dapat
ditentukan dengan teknik skalogram. Oleh karena itu, dalam penyusunan suatu
hirarki dapat ditentukan jumlah jenis sarana. Hirarki dari pusat pelayanan yang
lebih tinggi memiliki jumlah dan jenis sarana pelayanan yang lebih banyak dan
19
III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian di lapangan dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari
hingga April 2010. Lokasi penelitian adalah areal perkebunan inti dan plasma
milik PT. Perkebunan Nusantara-III yang berada di Desa Torgamba dan Desa
Aek-Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi
Sumatera Utara (Gambar 1). Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja
(purposive), dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu daerah perkebunan dengan budidaya tanaman kelapa sawit. Analisis data
dilakukan di Laboratorium Perencanaan Pengembangan Wilayah, Departemen
Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
3.2. Jenis Data, Sumber Data dan Alat Penelitian
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani menggunakan
kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari
20
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dari Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008, Laporan Bidang Tanaman dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Perkebunan Nusantara-III dari kantor
Kebun Torgamba, serta data Potensi Desa (PODES) Kecamatan Torgamba tahun
2003 dan 2008 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peralatan yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi seperangkat komputer dengan perangkat
lunak (software) yang terdiri dari Arc View 3.3 untuk koreksi geometrik dan pengolahan peta, Microsoft Office Excel dan Statistica 7.0 untuk pengolahan data.
3.3. Metode Pemilihan Responden
Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode acak
sederhana. Penarikan contoh didasarkan pada jumlah responden sebesar 3.249
responden dan tersebar ke dalam tiga daerah KUD, yaitu KUD Aek Raso, KUD
Aek Torop, dan KUD Batu Ajo. Metode ini dirasa yang paling tepat dan setiap
sampel dari populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan responden.
Selanjutnya setiap sampel dari populasi yang dijadikan responden dipilih secara
acak.
Berhubung jumlah petani di plasma relatif banyak dan kondisinya relatif
seragam, maka jumlah responden yang diwawancara dipertimbangkan cukup 2%
saja dari jumlah petani pada tiga KUD yang ada. Jumlah responden pada
masing-masing KUD tertera pada Tabel 3. Umur tanaman, status kepemilikan lahan, dan
luas lahan yang diusahakan petani menjadi sumber keragaman utama
produktivitas yang dipertimbangkan.
Tabel 3. Jumlah responden pada masing-masing KUD
Nama KUD Jumlah KK Proporsi responden Responden yang diwawancara
KUD Aek Raso 1.749 1.749×2% 34
21
mengetahui mekanisme pengelolaan kebun dan pengolahan TBS secara langsung
di lokasi penelitian. Dalam melaksanakan kegiatan magang tersebut digunakan
beberapa metode pendekatan, yaitu :
1. Metode Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan sebenarnya yang terjadi
di lapang. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa aspek penting terkait
pengelolaan perkebunan kelapa sawit, antara lain pembibitan, pemupukan,
pemeliharaan jalan, panen, dan sebagainya.
2. Metode Wawancara
Dalam metode ini, dilakukan dialog dan proses komunikasi langsung
dengan pihak terkait yang ada di lapangan serta pihak yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan di lapangan dan bertanggung jawab terhadap semua masalah
teknis di lapangan.
3. Studi Pustaka
Dalam studi kepustakaan ini, data dikumpulkan dengan mempelajari
berbagai literatur dari buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.
4. Dokumentasi
Selama melaksanakan kegiatan di lapangan mahasiswa menggunakan foto
atau gambar untuk memperkuat isi tulisan yang disusun.
3.4.2. Teknik Analisis Data Menggunakan Statistik Uji-t
Analisis ini dilakukan untuk membandingkan tingkat produktivitas antar
afdeling dan tingkat produktivitas antar kelas umur tanaman di kebun Inti. Untuk
menguji parameter dugaan dari masing-masing peubah apakah secara terpisah
peubah ke-n berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebasnya digunakan uji
statistik-t (Gujarati, 1995).
Statistik uji yang digunakan dalam uji-t:
t-hitung = , derajat bebas (n-k)
Dimana :
Se(bi) = standar deviasi untuk parameter ke-n
22
Jika thitung > ttabel, (α/2; n-k) maka tolak H0, artinya peubah yang diuji berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel tak bebas pada taraf α persen.
Jika thitung < ttabel, (α/2; n-k) maka terima H0, artinya peubah yang diuji tidak
berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas pada taraf α persen.
3.4.3. Analisis Ragam (ANOVA) dan Uji Lanjut Metode Tukey
Pengujian ragam (Analysis of Variance), dilakukan untuk menarik
kesimpulan menerima atau menolak hipotesis. Jika hipotesis ditolak berarti
variabel-variabel yang diuji memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam statistik,
teknik Uji lanjut digunakan untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki
perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini digunakan metode Tukey dengan
pertimbangan metode tersebut relatif sensitif terhadap pengaruh perubahan
variabel penjelas terhadap produktivitas sampai tingkat kepercayaan 70%.
Analisis ragam dilakukan berdasarkan desain faktorial dengan perlakuan umur
tanaman dan status kepemilikan lahan. Umur tanaman dibagi atas 5 kelas yaitu
(0-5) tahun, (6-10) tahun, (11-1(0-5) tahun, (16-20) tahun, dan >21 tahun. Status
kepemilikan terdiri dari 3 kelas yaitu garap, sewa, dan milik sendiri.
Pada metode Tukey, semua perbandingan perlakuan yang mungkin,
ditetapkan kesalahannya sebesar α. Besaran α ditetapkan yaitu sebesar 5%. Apabila t-hitung yang diperoleh lebih besar dari pada nilai t-tabel pada taraf nyata
5%, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara peubah yang diamati dan
demikian juga sebaliknya.
3.4.4. Analisis Faktor (Factor Analysis) dan Regresi Berganda (Multiple Regression)
Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat produktivitas kelapa sawit adalah dengan Analisis Faktor
(Factor Analysis) kemudian dilanjutkan dengan Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis).
Analisis Faktor (Factor Analysis)
Analisis Faktor (Factor Analysis atau FA) merupakan salah satu teknik analisis yang dapat menciptakan variabel baru sebagai pengganti variabel-variabel
23
Tujuan analisis faktor adalah untuk menemukan suatu variabel-variabel baru,
yang disebut komponen utama, yang dapat mewakili variabel-variabel indikator
asal. Pada penelitian ini, analisis faktor dilakukan karena potensi multikolinearitas
cukup besar jika seluruh variabel asal terkait input produksi pertanian
diikutsertakan dalam regresi berganda, sementara seluruh variabel input usahatani tersebut diharapkan masuk dalam permodelan.
Variabel-variabel indikator asal yang digunakan dalam analisis faktor
adalah:
X8 : Pemupukan rutin, merupakan jadwal pemupukan yang dilakukan oleh
petani apakah rutin atau tidak rutin. Dalam perhitungan dijadikan peubah
boneka (dummy). Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif (nominal). Bagi petani yang
melakukan pemupukan rutin diberi nilai 1 sedangkan yang tidak rutin
diberi nilai nol.
Analisis faktor terhadap data tersebut dilakukan beberapa kali hingga
diperoleh hasil terbaik, yaitu: PC scores dengan nilai akar ciri (eigenvalues) di atas 70%; nilai akar ciri lebih besar dari 1; dan korelasi antar variabel-variabel
asal dengan faktor-faktor baru pada factor loading dapat diinterpretasikan secara logis. Output data hasil analisis komponen utama umumnya memiliki variabel-variabel baru (faktor) yang lebih sedikit dan orthogonal, dengan nilai ragam
(variance) yang relatif sama. Hasil analisis komponen utama adalah sebagai berikut:
a)
Nilai akar ciri (eigenvalues), yaitu nilai yang menggambarkan keragaman datapada variabel-variabel baru (faktor utama). Dengan kata lain, faktor utama
24
mewakili variabel-variabel asal sebesar nilai akar ciri tadi. Persamaan untuk
memperoleh nilai akar ciri (eigenvalues) adalah:
[
y
y +λ
(1
–
a
1a
1)] = [a
1Sa
1 +λ
1(1
–
a
1a
1)]
b) Tabel kumulatif akar ciri (communalities), yaitu tabel yang menunjukkan besarnya nilai keragaman/keterwakilan data masing-masing variabel atau
peubah asal terhadap faktor-faktor utama yang diperoleh.
c) Nilai pembobot (eigenvector) atau disebut sebagai PC loadings (factor loadings). Vektor pembobot adalah parameter yang menggambarkan hubungan (peran) setiap variabel dengan faktor ke-i.
Nilai loadings diperoleh dari persamaan berikut:
r
1= a
1λ
1 ,Dimana :
λ1 : akar ciri (eigenvalues) komponen utama ke-1
r1 : nilai loadings ke-i
a1 : Nilai vektor pembobot utama ke-1
Jadi, loadings menunjukkan besarnya nilai korelasi antara variabel asal
dengan komponen utama ke-i yang diinterpretasikan berdasarkan marked
loading > 0,7. Nilai yang berkorelasi positif menyatakan bahwa faktor utama ke-i berbanding lurus dengan variabel penjelas. Sebaliknya, nilai dengan korelasi negatif menyatakan bahwa faktor utama ke-i berbanding terbalik
dengan variabel penjelas. Nyata tidaknya korelasi antar komponen utama ke-i
terhadap peubah asal dapat diuji dengan persamaan berikut:
t = r
,Dimana :
t : nilai t pada taraf nyata yang diinginkan n : contoh data yang dianalisis
r : nilai korelasi
d) Tabel PC scores (factor scores), yaitu tabel yang menyajikan nilai-nilai berupa besarnya titik-titik data baru hasil analisis faktor. Faktor inilah yang
digunakan jika terdapat analisis lanjutan. Factor analysis (FA) dapat
25
antara dapat menghilangkan multikolinearitas data dan menyederhanakan satu
set data dengan variabel besar. FA sebagai analisis akhir berfungsi dalam
pengelompokkan variabel-variabel penting dari satu kelompok variabel
penduga pada suatu fenomena sekaligus pemahaman akan struktur dan
hubungan antar variabel.
Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis)
Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
produktivitas kelapa sawit di kebun plasma, maka dilakukan analisis regresi
berganda dengan metode forward stepwise. Prinsip dasar metode forward
stepwise adalah mengurangi banyaknya peubah di dalam fungsi tujuan dengan cara menyisipkan peubah penjelas satu per satu hingga diperoleh persamaan
regresi yang paling baik.
Pada penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan
model persamaan yang menjelaskan hubungan antara produktivitas sebagai
variabel tujuan (dependent variable) dan faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat produktivitas sebagai variabel penduga/penjelas (explanatory variable). Variabel-variabel penduganya adalah sebagai berikut:
X1 :Pengalaman petani (tahun)
X2 :Pendidikan petani (tahun)
Faktor-1 : Pestisida, tenaga kerja, peralatan, penen
Faktor-2 : Teknik pemupukan
Faktor-3 : Umur tanaman dan bibit
d1 : Pekerjaan sampingan
Berdasarkan hasil kuesioner, ada petani yang memiliki pekerjaan sampingan
selain usahatani kelapa sawit dan ada yang tidak (usahatani kelapa sawit
menjadi prioritas utama). Untuk memudahkan perhitungan, bagi petani yang
memiliki pekerjaan sampingan diberi nilai 1 sedangkan yang lainnya diberi
nilai nol. Ini disebut sebagai peubah boneka (dummy).
d2 : Status kepemilikan lahan, dalam perhitungan juga dijadikan
26
Secara umum, hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat
dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :
Y = β0+ β1X1+ β2X2+ ….. + βnXn
Dimana : Y : Fungsi tujuan/peubah yang diduga (dependent variable)
β0 : Nilai konstanta/koefisien fungsi regresi (intercept),
Diasumsikan nilai intercept sama dengan 0
βn : Nilai konstanta/koefisien variabel penjelas fungsi regresi
X : Variabel penjelas/variabel yang diduga (independent variable) Ukuran kebaikan model regresi dapat dilihat dari beberapa parameter,
diantaranya yang paling banyak dinilai adalah koefisien determinasi (R2) dan galat
baku (standar error, SE). Model terbaik akan memiliki R2 mendekati 1 dan SE
terkecil (Drapper&Smith, 1992). Selanjutnya pengujian untuk menilai variabel
disebut berpengaruh nyata secara statistik jika teruji penting pada selang
kepercayaan 85-95% (0,05<p-level<0,1). Variabel disebut berpengaruh sangat nyata secara statistik jika variabel tersebut teruji penting pada selang kepercayaan
>95% (p-level<0,05).
3.4.5. Analisis Skalogram
Analisis skalogram digunakan untuk menetapkan indeks hirarki desa-desa
di Kecamatan Torgamba berdasarkan jumlah unit dan jenis fasilitas pelayanan
yang dimiliki masing-masing desa serta jarak ke fasilitas tersebut. Menurut
Rustiadi et al. (2009), model untuk menentukan Indeks Perkembangan Desa (IPD)
adalah :
IPDj = I’ ij, Dimana : I’ ij = Iij– I i min
SDi
IPD = Indeks perkembangan desa ke-j
Iij = Nilai (skor) indeks perkembangan ke-i terkoreksi (standarisasi) desa ke-j
27
Sdi = Standar deviasi indeks perkembangan ke-i
Iij adalah data berupa jumlah unit fasilitas j terpilih yang ada di desa ke-i.
Khusus beberapa fasilitas dengan data berupa aksesibilitas (jarak ke lokasi
fasilitas) digunakan formula sebagai berikut: Iij = untuk Xij = 0, (artinya
fasilitas j berada di desa ke-i), maka: Iij = , Dimana Xij min adalah Xij
terendah selain nol (Xij tidak sama dengan nol).
Variabel data yang digunakan dalam analisis ini tertera pada Tabel 4.
Tabel 4. Variabel-variabel yang Digunakan dalam Analisis Skalogram
Kelompok Indeks Variabel data yang digunakan
Fasilitas Pendidikan Jumlah TK, SD, SLTP, SMU, SMK, Pondok
Pesantren/Madrasah Diniyah
Fasilitas Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit, Poliklinik/Balai Pengobatan,
Puskesmas, tempat praktek dokter dan bidan,
posyandu, polindes, apotik, toko obat khusus/jamu.
Fasilitas Sosial Jumlah Masjid, Surau/Langgar, Gereja
Kristen/Katolik
Fasilitas Perekonomian Jumlah restoran, warung, koperasi
Aksesibilitas Pendidikan Jarak ke TK terdekat, SLTP terdekat, SMU
terdekat, SMK terdekat
Aksesibilitas Kesehatan
Jarak ke Rumah Sakit, rumah bersalin,
poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, tempat
praktek dokter, apotik, toko obat khusus/jamu
Aksesibilitas Perekonomian Jarak ke pub/diskotik/karaoke, kantor pos,
pertokoan terdekat, pasar terdekat
Penentuan tingkat perkembangan desa dapat dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Nilai Selang Hirarki Pusat Pelayanan
No. Nilai Selang (x) Kelas Hirarki Tingkat Hirarki
1 x ≥ (rataan IPD + Stdev IPD) I Tinggi
2 rataan IPD < x < Stdev IPD II Sedang