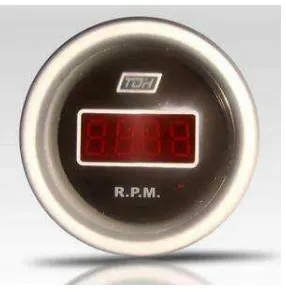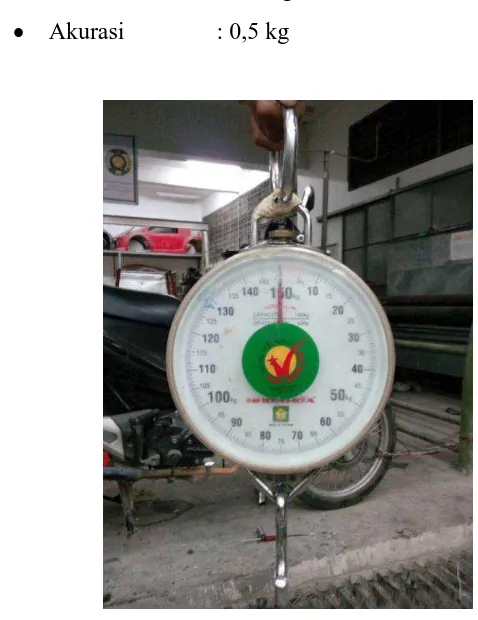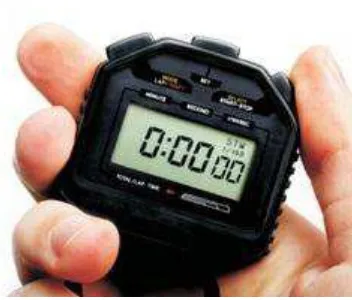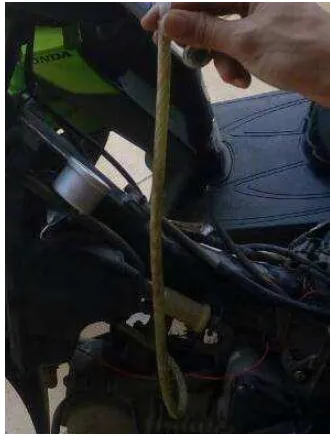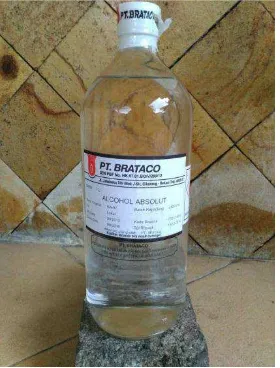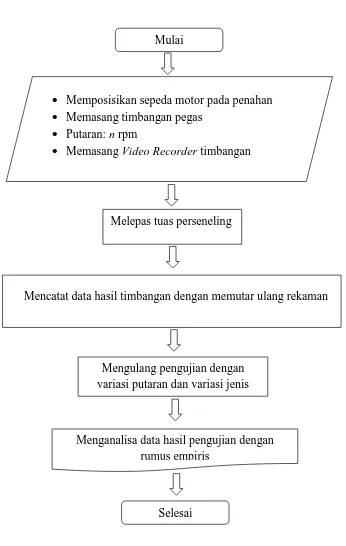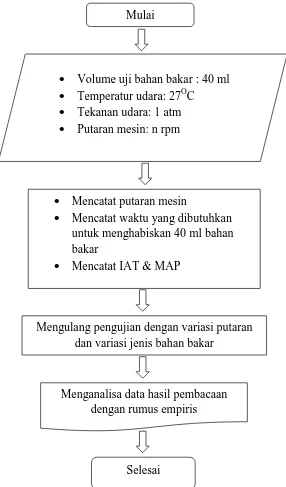DATA HASIL PENGUJIAN
1. Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar Pertalite
HHV (kJ/kg) 47794.24 47794.24 46323.65 48529.54 47058.94
Gasohol 5%
HHV (kJ/kg) 42647.17 44853.06 44853.06 47058.94 44117.76
Gasohol 10%
Gasohol 15%
HHV (kJ/kg) 41911.87 41911.87 44853.06 43382.46 45588.35
Gasohol 10%
Gasohol 5%
RPM m (kg) F (N) T.roda (Nm) T.mesin (Nm) Daya (W)
8000.00 37.80 370.70 80.04 8.31 6959.09
7000.00 39.40 386.40 83.42 8.66 6346.95
6000.00 42.10 412.87 89.14 9.26 5813.05
5000.00 42.80 419.74 90.62 9.41 4924.76
4000.00 42.60 417.78 90.20 9.37 3921.39
3000.00 41.80 409.93 88.50 9.19 2885.81
2000.00 40.80 400.13 86.39 8.97 1877.85
Gasohol 10%
RPM m (kg) F (N) T.roda (Nm) T.mesin (Nm) Daya (W)
8000.00 38.00 372.67 80.46 8.35 6995.91
7000.00 39.80 390.32 84.27 8.75 6411.39
6000.00 42.00 411.89 88.93 9.23 5799.25
5000.00 42.60 417.78 90.20 9.37 4901.74
4000.00 42.40 415.82 89.77 9.32 3902.98
3000.00 41.60 407.97 88.08 9.15 2872.01
2000.00 41.00 402.09 86.81 9.01 1887.06
Gasohol 15%
RPM m (kg) F (N) T.roda (Nm) T.mesin (Nm) Daya (W)
8000.00 37.60 368.74 79.61 8.27 6922.27
7000.00 39.40 386.40 83.42 8.66 6346.95
6000.00 42.20 413.86 89.35 9.28 5826.86
5000.00 42.40 415.82 89.77 9.32 4878.73
4000.00 42.10 412.87 89.14 9.26 3875.37
3000.00 41.60 407.97 88.08 9.15 2872.01
4. Tekanan Udara Masuk (Pi) dan Suhu Udara Masuk (Ti) Pertalite
Suhu Lingkungan (Ta) = 31°C
RPM
Pi (kPa)
I II III IV V Rata-rata
1000 70.00 68.00 69.00 70.00 70.00 69.40 2000 70.00 69.00 70.00 70.00 70.00 69.80 3000 70.00 70.00 70.00 69.00 70.00 69.80 4000 71.00 70.00 70.00 71.00 70.00 70.40 5000 73.00 72.00 72.00 73.00 73.00 72.60 6000 74.00 73.00 74.00 73.00 74.00 73.60 7000 76.00 76.00 77.00 77.00 75.00 76.20 8000 81.00 82.00 83.00 82.00 81.00 81.80
RPM
Ti (°C)
I II III IV V Rata-rata
Gasohol 5%
Suhu Lingkungan (Ta) = 31°C
RPM Pi (kPa)
I II III IV V Rata-rata
1000 71.00 71.00 71.00 70.00 70.00 70.60 2000 71.00 71.00 71.00 71.00 72.00 71.20 3000 71.00 72.00 72.00 71.00 72.00 71.60 4000 72.00 72.00 72.00 71.00 71.00 71.60 5000 74.00 74.00 72.00 74.00 73.00 73.40 6000 74.00 74.00 74.00 75.00 74.00 74.20 7000 76.00 77.00 77.00 76.00 76.00 76.40 8000 82.00 81.00 82.00 83.00 82.00 82.00
RPM Ti (°C)
I II III IV V Rata-rata
Gasohol 10%
Suhu Lingkungan (Ta) = 33°C
RPM Pi (kPa)
I II III IV V Rata-rata
1000 71.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.20 2000 71.00 71.00 70.00 70.00 71.00 70.60 3000 72.00 71.00 71.00 72.00 72.00 71.60 4000 73.00 72.00 74.00 73.00 72.00 72.80 5000 74.00 73.00 74.00 73.00 73.00 73.40 6000 74.00 73.00 74.00 74.00 75.00 74.00 7000 77.00 76.00 77.00 76.00 77.00 76.60 8000 82.00 82.00 83.00 83.00 83.00 82.60
RPM Ti (°C)
I II III IV V Rata-rata
Gasohol 15%
Suhu Lingkungan (Ta) = 31°C
RPM Pi (kPa)
I II III IV V Rata-rata
1000 72.00 70.00 69.00 70.00 70.00 70.20 2000 72.00 72.00 70.00 70.00 70.00 70.80 3000 72.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.40 4000 73.00 72.00 70.00 70.00 70.00 71.00 5000 73.00 72.00 72.00 73.00 73.00 72.60 6000 75.00 73.00 74.00 73.00 74.00 73.80 7000 76.00 76.00 77.00 77.00 75.00 76.20 8000 81.00 81.00 82.00 82.00 81.00 81.40
RPM Ti (°C)
I II III IV V Rata-rata
DAFTAR PUSTAKA
1. Kristanto, Philip. 2015. Motor Bakar Torak (Teori dan Aplikasinya). Yogyakarta :
Penerbit ANDI.
2. Anonim. 2014. Mesin Pembakaran Luar Turbin Gas.
http://schoolworkhelper.net/engine-function-type-overview/. Diakses 25
Desember 2015.
3. Kurniasih. 2015. Empat Fakta BBM Pertalite.
http://economy.okezone.com/read/2015/04/23/19/1139089/empat-fakta-bbm-pertalite-produk-baru-pertamina). Diakses 28 Desember 2015.
4. Purponegoro, Wianda. 2015. Pertalite. http://www.pertamina.com. Diakses 25
Desember 2015.
5. Ambarita, Himsar. 2013. Aplikasi Siklus Termodinamika. Edisi Pertama. Medan:
Penerbit Universitas Sumatera Utara.
6. Heywod, Jhon B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw Hill Book
Company, New York, 1988
7. B.Tech Mechanical. Elements of Mechanical Engineering Unit-3.
http://image.slidesharecdn.com/unit4bmei-150317013010-conversion-gate01/95/unit-4-bme-ic-engine-37-638.jpg?cb=1426555843. Diakses 29
Desember 2015.
8. Rangkuti, Chalilullah. 1996. Panduan Praktikum Bom Kalorimeter. Laboratorium
Motor Bakar Teknik Mesin USU. Medan.
9. Crouse, William H. 1976. Automotive Mechanics, Seventh Edition. McGraw-Hill
Book Company.
10.Anonim. 2012. Sejarah Pemanfaatan Bioetanol.
http://www.indobioethanol.com/sumber_lain.php. Diakses 27 Desember 2015.
11.Gusmailina. 2010. Prospek Bioetanol Sebagai Pengganti Minyak Tanah.
http://www.indobioethanol.com/sumber_lain. (Pusat Litbang Hasil Hutan, Bogor).
12.Pulkrabek, Willard W. 1997. Engineering Fundamentals of the Internal
Combustion Engine. New Jersey: Penerbit Prentice Hall.
13.Arismunandar, Wiranto. Penggerak Mula Motor Bakar Torak. Edisi kelima.
Penerbit : ITB Bandung,1988
14.Susilo, Bambang dkk. 2013. Uji Performansi Motor Bakar (On Chasis)
Menggunakan Campuran Premium dan Etanol.
15.Wiratmaja, I Gede. 2010. UjiAnalisa Unjuk Kerja Motor Bensin Akibat
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Penelitian
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penelitian ini dilakukan dengan
metode eksperimental. Metode ini ialah metode yang dipakai untuk menguji
pengaruh dari suatu perlakuan atau desain baru dengan cara membandingkan
dengan desain lain tanpa perlakuan baru (kondisi awal desain) sebagai
pembanding pada hasil penelitian.
Pada pengujian ini, kondisi awal pengujian yaitu saat pengujian
menggunakan bahan bakar pertalite tanpa dicampur dan hasilnya akan
dibandingkan dengan pengujian berbahan bakar campuran pertalite-bioetanol
(gasohol) dengan kadar etanol 5%, 10%, dan 15%, sehingga perbedaan setiap
peformansi akan dapat diketahui.
Terdapat 3 variabel dalam uji eksperimental ini yaitu variabel bebas,
variabel terikat dan variabel kontrol. Pembagian variabel tersebut antara lain:
a. Variabel bebas : 4 jenis bahan bakar
b. Variabel kontrol : putaran mesin (1000 rpm, 2000 rpm, 3000 rpm, 4000 rpm,
5000 rpm, 6000 rpm, 7000 rpm, 8000 rpm)
c. Variabel terikat : Performansi motor bakar setiap bahan bakar.
3.2 Waktu dan Tempat
3.2.1 Pengujian Konsumsi Bahan Bakar
Dilakukan di Jl. Deli Kesuma No.27 Medan Sumatera Utara selama 2
Gambar 3.1 Pengujian konsumsi bahan bakar
3.2.2 Pengujian Torsi
Dilakukan di Laboratorium Teknologi Mekanik Departemen Teknik
Mesin Universitas Sumatera Utara selama 3 minggu.
Gambar 3.2 Pengujian torsi
3.2.3 Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar
Dilakukan di Laboratorium Motor Bakar Departemen Teknik Mesin
Gambar 3.3 Pengujian nilai kalor bahan bakar
3.3 Alat dan Bahan
3.3.1 Alat
Alat yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Bom Kalori Meter
Bom kalori meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah
kalor (nilai kalori) yang dibebaskan pada pembakaran sempurna (O2 berlebih) pada suatu senyawa bahan makanan atau bahan bakar.
2. Mesin
Mesin yang digunakan yaitu mesin otto 4 langkah, yaitu mesin sepeda
Gambar 3.4 Mesin Honda Supra-X 125
Spesifikasi:
a. Mesin :
Mesin : 4 langkah SOHC
Volume langkah : 124,8 cc
Diameter x langkah : 52,4 x 57,9 mm Perbandingan kompresi : 9:1
Sistem pemasukan : Karburator
Sistem pengapian : Full transistorized Daya maksimum : 9,63 PS / 7500 rpm Torsi maksimum : 1,03 kgf.m / 4000 rpm Kapasitas pelumas mesin : 0,7 Liter
Tipe starter : Pedal dan elektrik Sistem pendingin : Pendingin udara
Kopling : Ganda, sentrifugal, tipe basah
Busi : NGK CPR6EA-9
b. Transmisi :
Speed 2 = 31/20
Speed 3 = 23/20
Speed 4 = 26/24
3. Tabung ukur
Tabung ukur digunakan untuk mengukur jumlah bahan bakar yang
terpakai pada saat pengujian konsumsi bahan bakar.
Spesifikasi :
Kapasitas : 60 ml Akurasi : 1 ml
Gambar 3.5 Tabung ukur
4. Tachometer
Tachometer merupakan alat untuk mengukur jumlah putaran yang
akan dihasilkan mesin.
GAMBAR
Spesifikasi:
Display Counts : 9999 counts LCD
Range rpm : 5 to 9999
Ft/min : 0.2 to 6560
M/min : 0.05 to 1999.9
Basic Accuracy : ± 0.05% ±1d
Gambar 3.6 Tachometer
5. Timbangan Digital
Timbangan digital digunakan untuk mengukur massa dari bahan
bakar yang akan diuji.
Gambar 3.7 Timbangan digital
6. Timbangan pegas
Timbagan pegas ini digunakan sebagai alat untuk mengukur daya
dan torsi pada roda belakang motor sebagaimana halnya dyno test
yang sering digunakan untuk mengetahui torsi dan daya kendaraan.
Namun, pada pengujian ini, data yang ditunjukkan oleh timbangan
pegas akan diolah kembali mengunakan rumus, karena daya yang
didapat merupakan data pada roda, belum dikonversikan secara
langsung pada data mesin yang sebenarnya sebagaimana halnya pada
Data yang didapat pada timbangan ini, nantinya akan digunakan
untuk mengetahui performansi mesin sebagai pertimbangan pada hasil
pengujian.
Sepsifikasi :
Beban maksimal : 150 kg Akurasi : 0,5 kg
Gambar 3.8 Timbangan pegas
7. Stopwatch
Stopwatch digunakan untuk menghitung lama waktu yang
dibutuhkan untuk menghabiskan 30 gram bahan bakar dari setiap
Gambar 3.9 Digital stopwatch
8. HiDS HD-30
HiDS adalah alat yang mampu berkomunikasi dengan Engine
Control Mobile (ECM), data-data berupa sinyal dari ECM dan ditampilkan pada layar dalam bentuk besaran-besaran fisika
seperti:
Suhu ditampilkan dalam °C Tekanan ditampilkan dalam kPa Spesifikasi
Dimensi : 122 x 82 x 33 mm Tegangan : 8 – 15 Volt DC Arus : 100 – 150 mA
Gambar 3.10 HiDS HD-30
Selang digunakan untuk menghubungkan tabung ukur dengan
karburator sebagau wadah tempat aliran bahan bakar menuju
karburator.
Gambar 3.11 Selang bahan bakar
3.3.2 Bahan
Bahan yang menjadi objek pengujian ini adalah sebagai berikut :
1. Bahan bakar pertalite.
Pertalite adalah jenis bahan bakar yang baru diperkenalkan pemerintah di
tahun 2015. Pertalite cocok untuk mesin kendaraan saat ini karena
Gambar 3.12 Bahan bakar Pertalite
2. Bahan bakar campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%
3. Bahan bakar campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 10%
4. Bahan bakar campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 15%.
Gambar 3.13 Bioetanol absolut (kadar 99%)
3.4 Metode Pengumpulan Data
Data yang dipergunakan dalam pengujian ini meliputi :
1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari pengukuran
dan pembacaan pada unit instrumentasi dan alat ukur pada
masing-masing pengujian.
2. Data sekunder, merupakan data tentang karakteristik bahan bakar yang
3.5 Metode Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari hasil pengujian diolah menggunakan rumus yang
ada kemudian hasil dari perhitungan diajukan dalam bentuk tabulasi dan grafik.
3.6 Pengamatan dan Tahap Pengujian
Parameter yang akan ditinjau dalam pengujian ini adalah :
1. Torsi motor (T)
2. Daya motor (N)
3. Konsumsi bahan bakar spesifik (SFC)
4. Rasio udara bahan bakar (AFR)
5. Efisiensi termal
6. Efisiensi volumetris
Pengujian dilakukan dengan melalui empat bagian, yaitu :
1. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar pertalite dengan
variasi putaran motor.
2. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar campuran
pertalite-bioetanol (gasohol) 5% dengan variasi putaran motor.
3. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar campuran
pertalite-bioetanol (gasohol) 10% dengan variasi putaran motor.
4. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar campuran
pertalite-bioetanol (gasohol) 15% dengan variasi putaran motor.
3.7 Prosedur Pengujian Performansi Mesin
Adapun prosedur pengujian performansi mesin dilakukan dengan cara
sebagai baerikut :
1. Pemeriksaan kondisi motor secara umum dan pemeriksaan sambungan
selang ke karburator.
2. Mengikat sepeda motor pada tiang tahanan.
4. Memastikan angka pada timbangan sudah tepat pada angka 0 kg dan
mengikatkan salah satu ujungnya pada roda belakang dan ujung yang lain
pada tiang penahan.
5. Memposisikan gigi transmisi pada posisi gigi ketiga. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan agar hasil pengujian masih dalam skala alat uji yang
digunakan.
6. Start mesin dengan starter sambil menekan kopling.
7. Atur variasi putaran mesin dengan melihat angka yang ditampilkan
tachometer dengan memutar tuas kecepatan dan memastikan putaran
mesin sudah konstan.
8. Merekam hasil pengujian pada timbangan pegas dengan video kamera.
9. Melepaskan kopling sehingga timbangan tertarik oleh roda belakang
hingga mesin berhenti pada beban maksimal.
10.Dilakukan sebanyak lima kali pengujian untuk setiap putaran yang
ditentukan.
11.Memutar kembali rekaman video dan mencatat massa yang terlihat pada
timbangan.
12.Mengulang pengujian menggunakan variasi putaran pengujian.
Gambar 3.14 Diagram alir performansi motor bakar
3.8 Prosedur Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Spesifik
Sebelum pengujian dilakukan, terlebih dahulu memasang alat yang akan
dignakan, diantaranya :
Mulai
Memposisikan sepeda motor pada penahan Memasang timbangan pegas
Putaran: n rpm
Memasang Video Recorder timbangan
Melepas tuas perseneling
Mencatat data hasil timbangan dengan memutar ulang rekaman
Mengulang pengujian dengan variasi putaran dan variasi jenis
Menganalisa data hasil pengujian dengan rumus empiris
1. Menghubungkan tabung ukur dengan karburator dengan selang
2. Menghubungkan HiDS HD-30 dengan motor melalui connector pada
bagian depan sepeda motor.
3. Memasukkan bahan bakar ke dalam tabung ukur dan menghilangkan
gelembung udara pada selang dengan menunggu sesaat setelah menuang
bahan bakar.
4. Memberikan tanda pada tabung ukur. Tanda ini digunakan sebagai titik
acuan untuk memulai perhitungan waktu dengan stopwatch dan
pengukuran konsumsi bahan bakar.
Adapun prosedur pengujian konsumsi bahan bakar spesifik dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengisi bahan bakar ke dalam tabung bertekanan sebanyak 50 ml.
2. Menghidupkan mesin dengan starter.
3. Memilih program pada HiDS HD-30 untuk jenis kendaraan yaitu
Supra-X 125
4. Menentukan putaran mesin yang ditampilkan tachometer dengan
memutar alat bukaan gas pada karburator.
5. Memulai stopwatch pada saat bahan bakar telah melalui tanda yang
diberikan pada tabung ukur.
6. Mematikan stopwatch dan motor pada aetiap 10 ml bahan bakar
yang habis.
7. Membaca waktu yang ditampilkan pada stopwatch.
8. Mencatat hasil pengujian dan mengulanginya sebanyak lima kali
Gambar 3.15 Pengujian konsumsi bahan bakar spesifik
Gambar 3.16 Diagram alir pengujian konsumsi 40 ml bahan bakar
3.9 Prosedur Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar
Alat yang digunakan dalam pengukuran nilai kalor bahan bakar ini adalah
Bom Kalorimeter.
Mulai
Volume uji bahan bakar : 40 ml Temperatur udara: 27OC
Tekanan udara: 1 atm Putaran mesin: n rpm
Mencatat putaran mesin
Mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 40 ml bahan bakar
Mencatat IAT & MAP
Mengulang pengujian dengan variasi putaran dan variasi jenis bahan bakar
Menganalisa data hasil pembacaan dengan rumus empiris
Gambar 3.17 Bom kalorimeter
Peralatan yang digunakan meliputi:
Kalorimeter, sebagai tempat air pendingin dan tabung bom Tabung bom, sebagai tempat pembakaran bahan bakar yang diuji Tabung gas oksigen
Alat ukur tekanan gas oksigen, untuk mengukur jumlah oksigen yang dimasukkan ke dalam tabung bom.
Termometer, dengan akurasi pembacaan skala 0.01°C
Elektromotor yang dilengkapi pengaduk untuk mengaduk air pendingin Split, untuk menentukan jumlah volume bahan bakar
Pengatur penyalaan (skalar), untuk menghubungkan arus listrik ke tangkai penyala pada tabung bom
Cawan, untuk tempat bahan bakar di dalam taung bom
Pinset, untuk memasang busur nyala pada tangkai dan cawan pada dudukannya
Adapun tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Mengisi cawan bahan bakar dengan bahan bakar yang akan diuji.
2. Menggulung dan memasang kawat penyala pada tangkai penyala yang ada
3. Menempatkan cawan yang berisi bahan bakar pada ujung tangkai penyala
serta mengatur posisi kawat penyala agar berada tepat diatas permukaan
bahan bakar yang berada di dalam cawan dengan menggunakan pinset.
4. Meletakkan tutup bom yang telah dipasangi kawat penyala dan cawan berisi bahan bakar pada tabungnya serta dikunci dengan ring “O” sampai rapat.
5. Mengisi bom dengan oksigen (30 bar).
6. Mengisi tabung kalorimeter dengan air pendingin sebanyak 1250 ml.
7. Menempatkan bom yang telah terpasang ke dalam tabung calorimeter.
8. Menghubungkan tangkai penyala penutup bom ke kabel sumber arus
listrik.
9. Menutup calorimeter dengan penutupnya yang telah dilengkapi dengan
pengaduk.
10.Menghubungkan dan mengatur posisi pengaduk pada electromotor.
11.Menempatkan termometer melalui lubang pada tutup calorimeter.
12.Menghidupkan elektromotor selama lima menit kemudian membaca dan
mencatat temperatur air pendingin pada termometer.
13.Menyalakan kawat penyala dengan menekan saklar.
14.Memastikan kawat penyala telah menyala dan putus dengan
memperhatikan lampu indikator selama elektromotor terus bekerja.
15.Membaca dan mencatat kembali temperatur air pendingin setelah lima
menit dari penyalaan berlangsung
16.Mematikan elektromotor pengaduk dan mempersiapkan peralatan untuk
pengujian berikutnya.
17.Mengulang pengujian sebanyak lima kali berturut-turut.
Gambar 3.18 Diagram alir pengujian nilai kalor bahan bakar Mulai
Berat sampel bahan bakar 0,2 gram Volume air pendingin 1250 ml Tekanan oksigen 30 Bar
Melakukan pengadukan terhadap air pendingin selama 5 menit
Mencatat temperatur air pendingin T1(OC)
Menyalakan bahan bakar
Menghitung HHV bahan bakar: HHV = (T2– T1– Tkp) x Cv x 1000
Melanjutkan pengadukan terhadap air pendingin selama 5 menit
Mencatat temperatur air pendingin T (OC)
Mengulang pengujian dengan variasi jenis bahan bakar
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Data Hasil Penelitian
Mesin Supra-X 125 yang akan digunakan sebagai alat uji merupakan mesin yang
dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin. Mesin ini merupakan mesin yang
menggunakan karburator sebagai alat pencampur bahan bakar dengan udara. Data
lengkap hasil pengujian bahan bakar pertalite, gasohol 5%, 10%, dan 15% dapat
dilihat pada lampiran.
4.1.1 Spesifikasi Data Alat dan Bahan Pengujian
Untuk menghitung unjuk kerja mesin diperlukan data-data seperti data pada mesin
uji, data alat yang digunakan pada mesin uji, dan data bahan bakar yang diuji. Data ini
nantinya akan digunakan dalam perhitungan performansi mesin. Data spesifikasi alat
sebagai berikut :
4.1.1.1 Data Motor
Mesin yang digunakan dalam pengujian ini adalah mesin Honda Supra-X 125
dengan data sebagai berikut :
Jumlah silinder : 1 silinder Diameter silinder (B) : 52,4 mm
Langkah (S) : 57,9 mm
Rasio kompresi : 9:1 Volume langkah : 124,8 cc Diameter roda : 17 inchi Rasio gigi speed ketiga : 23/20
4.1.1.2 Data Bahan Bakar
Dalam pengujian ini, bahan bakar yang digunakan yaitu bahan bakar pertalite,
dilakukan pengujian bom calorimeter di Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin
Universitas Sumatera Utara, dengan menggunakan persamaan 2.10 diperoleh nilai
kalor atas bahan bakar (HHV) dan nilai kalor bahan bakar bawah (LHV) seperti
tertera pada tabel 4.1 – 4.4.
Tabel 4.1 Pengujian nilai kalor bahan bakar pertalite
PERTALITE
Tabel 4.2 Pengujian nilai kalor bahan bakar gasohol 5%
E5
Tabel 4.3 Pengujian nilai kalor bahan bakar gasohol 10%
E10
Tabel 4.4 Pengujian nilai kalor bahan bakar gasohol 15%
4.2 Pengujian Performansi Mesin Otto
Data yang diperoleh dari pembacaan langsung alat uji mesin Supra-X 125 melalui
unit instrumentasi dan perlengkapan yang digunakan pada saat pengujian antara lain : Putaran (rpm) melalui pembacaan tachometer
Masa tarik melalui pembacaan timbangan pegas
Konsumsi bahan bakar melalui pengukuran dengan tabung ukur Massa bahan bakar melalui pembacaan timbangan digital
4.2.1 Final Ratio
Final ratio merupakan perkalian perbandingan roda gigi yang dimulai dari roda
gigi pada gigi tarik roda belakang, roda gigi pada transmisi (pada pengujian ini
ditetapkan pada gigi ketiga), dan roda gigi poros engkol yang menyalurkan putaran
dari poros utama transmisi ke poros engkol. Adapun perbandingan rasio yang didapat
adalah :
Perbandingan rasio pada roda belakang yaitu : Jumlah gigi tarik roda belakang : 35
Jumlah gigi tarik poros transmisi : 14
Maka didapat perbandingan rasio gear sebesar : 39/14 = 2,5 Perbandingan rasio gear ketiga pada transmisi yaitu :
Jumlah gear gigi ketiga : 23
Jumlah gear poros utama transmisi : 20
Maka didapat perbandingan rasio gear sebesar : 23/20 = 1,15 Perbandingan rasio antara transmisi dengan poros engkol yaitu :
Jumlah gear poros kopling : 67
Jumlah gear poros engkol : 20
Maka didapat perbandingan rasio gear sebesar : 67/20 = 3,35
Jadi untuk perbandingan rasio keseluruhan (final ratio) dapat diketahui dengan
mengalikan ketiga perbandingan rasio di atas, yaitu :
Jadi, final rasio gear pada pengujian ini adalah 9.63
4.2.2 Torsi
Besarnya torsi yang dihasilkan oleh mesin pada poros roda dapat dihitung dari
massa yang tertarik pada timbangan pegas. Besarnya torsi yang dihasilkan pada setiap
pengujian untuk setiap variasi putaran mesin dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan 2.1, 2.2, dan 2.3.
Maka torsi setiap bahan bakar dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5 Nilai torsi setiap bahan bakar
RPM
Perbandingan torsi dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar pertalite,
gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.
Gambar 4.1 Grafik Torsi vs Putaran 8.2
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Dari gambar diatas dapat disimpulkan :
1. Torsi terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 15% pada
putaran mesin 8000 rpm yaitu sebesar 8,27 Nm.
2. Torsi tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite pada putaran
5000 rpm yaitu sebesar 9,41 Nm.
3. Penambahan bioetanol cenderung menurunkan nilai torsi yang dihasilkan pada
4000 rpm hingga 5000 rpm. Hal ini dikarenakan rasio kompresi mesin yang
rendah sehingga pembakaran menggunakan gasohol tidak optimal.
4.2.3. Daya
Dari data torsi yang diperoleh di atas, maka daya dapat diperoleh dengan
menggunakan persamaan 2.4
Maka daya setiap bahan bakar dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.
Tabel 4.6 Besarnya daya pada setiap bahan bakar
RPM
DAYA (W)
E5 E10 E15 PERTALITE
8000 6959.09 6995.91 6922.27 7036.30 7000 6346.95 6411.39 6443.61 6382.41 6000 5813.05 5799.25 5826.86 5829.82 5000 4924.76 4901.74 4878.73 4950.28 4000 3921.39 3902.98 3875.37 3941.80 3000 2885.81 2872.01 2872.01 2914.91 2000 1877.85 1887.06 1859.44 1897.22
Perbandingan daya dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar pertalite,
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Daya vs Putaran pada setiap bahan bakar
Dari gambar diatas dapat disimpulkan :
1. Daya terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 15% pada
putaran mesin 2000 rpm yaitu sebesar 1859,44 W.
2. Daya tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite pada putaran
8000 rpm yaitu sebesar 7036,30 W.
3. Dari grafik dapat dilihat bahwa garis dari setiap bahan bakar saling
berhimpitan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan bioetanol tidak terlalu
mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh mesin.
4.2.4 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (SFC)
Konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) dari masing-masing pengujian pada setiap
putaran dihitung dengan menggunakan persamaan 2.5 dan 2.6. Berikut hasil
perhitungan laju aliran bahan bakar yang diperoleh dari persamaan 2.5
1. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar pertalite
Tabel 4.7 Hasil pengujian ̇ bahan bakar pertalite
RPM
0 2000 4000 6000 8000 10000
6000 76.07 77.01 75.48 74.32 75.88 75.75 1412.40
2. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar gasohol 5%
Tabel 4.8 Hasil pengujian ̇ bahan bakar gasohol 5%
RPM
3. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar gasohol 10%
Tabel 4.9 Hasil pengujian ̇ bahan bakar gasohol 10%
4. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar gasohol 15%
Tabel 4.10 Hasil pengujian ̇ bahan bakar gasohol 15%
RPM
Dengan menggunakan persamaan 2.6, maka SFC setiap bahan bakar dapat dilihat
pada tabel 4.15 berikut.
Tabel 4.11 Nilai SFC pada setiap bahan bakar
RPM
Perbandingan nilai SFC dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar
pertalite, gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.3
Gambar 4.3 Grafik SFC vs Putaran pada setiap bahan bakar
Dari gambar diatas dapat disimpulkan :
1. SFC terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 10% pada
putaran mesin 3000 rpm yaitu sebesar 213,23 gr/kWh.
2. SFC tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite pada putaran
8000 rpm yaitu sebesar 342,58 gr/kWh.
3. Pada putaran diatas 7000 rpm terlihat bahwa bahan bakar pertalite memiliki
SFC tertinggi dibandingkan dengan bahan bakar gasohol. Hal ini disebabkan
nilai kalor (LHV) pertalite yang lebih tinggi sehingga lebih mudah terbakar.
4.2.5 Efisiensi Thermal
Efisiensi thermal merupakan perbandingan antara daya keluaran aktual terhadap
laju panas rata-rata yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar.
Efisiensi thermal dari masing-masing pengujian pada tiap variasi putaran dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan 2.14
Maka efisiensi thermal setiap bahan bakar dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 150
0 2000 4000 6000 8000 10000
Tabel 4.12 Nilai Efisiensi Thermal pada setiap bahan bakar
Perbandingan Efisiensi Thermal dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar
pertalite, gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.4
berikut.
Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Efisiensi thermal vs Putaran
Dari gambar diatas dapat disimpulkan :
1. Efisiensi thermal terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite
pada putaran mesin 8000 rpm yaitu 23,74%.
2. Efisiensi thermal tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol
10% pada putaran 3000 rpm yaitu 41.01%. 0
0 2000 4000 6000 8000 10000
3. Nilai Efisiensi thermal untuk variasi gasohol yang tidak konsisten pada setiap
putaran disebabkan oleh suhu lingkungan yang berbeda pada saat pengujian.
Suhu lingkungan mempengaruhi laju konsumsi bahan bakar sehingga efisiensi
thermal juga terpengaruh.
4.2.6 Rasio Udara Bahan Bakar
Rasio udara bahan bakar (AFR) dari masing-masing pengujian pada tiap variasi
beban dan putaran dapat dihitung menggunakan persamaan 2.7.
Dari alat sensor HiDS HD-30, diperoleh tekanan (Pi) dan suhu (Ti) yang berbeda pada setiap putaran mesin, data ini dapat dilihat pada lampiran.
Dengan menggunakan persamaan 2.8 dan 2.9, maka laju aliran udara setiap bahan
bakar dapat diperoleh.
Tabel 4.13 Nilai ma pada setiap bahan bakar
RPM
ma (kg/cyl-cycle)
E5 E10 E15 PERT
8000 0.000131435 0.000131964 0.000130388 0.000130943 7000 0.000122379 0.000122139 0.000121978 0.000122138 6000 0.000118777 0.000117993 0.000118059 0.000117894 5000 0.000117496 0.000117113 0.000115912 0.000116292 4000 0.000114615 0.00011608 0.00011321 0.000112253 3000 0.000114615 0.000114167 0.000112253 0.000111296 2000 0.0001139 0.000112499 0.000112965 0.000111296
Maka AFR untuk setiap variasi putaran pada setiap bahan bakar dapat dilihat pada
tabel 4.18 berikut.
Tabel 4.14 Nilai AFR pada setiap bahan bakar
Perbandingan AFR dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar pertalite,
gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.
Gambar 4.5 Grafik AFR vs Putaran pada setiap bahan bakar
Dari gambar diatas dapat disimpulkan :
1. AFR terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 5% pada
putaran mesin 2000 rpm yaitu sebesar 12,55.
2. AFR tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 10% pada
putaran 6000 rpm yaitu sebesar 16,95.
4.2.7 Efisiensi Volumetris
Untuk menghitung efisiensi volumetris digunakan persamaan 2.12. Maka
efisiensi volumetris untuk setiap variasi putaran pada setiap bahan bakar dapat dilihat
pada tabel 4.15 berikut.
Tabel 4.15 Efisiensi volumetris pada setiap bahan bakar
RPM
0 2000 4000 6000 8000 10000
Perbandingan efisiensi volumetris dengan putaran mesin menggunakan bahan
bakar pertalite, gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15%.dapat dilihat pada tabel
4.6 berikut.
Gambar 4.6 Grafik Efisiensi volumetris vs Putaran pada setiap bahan bakar.
Dari gambar diatas dapat disimpulkan :
1. Efisiensi volumetris terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar
pertalite pada putaran mesin 2000 dan 3000 rpm yaitu 76,79%.
2. Efisiensi volumetris tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar
gasohol 10% pada putaran 8000 rpm yaitu 91,65%. 74
0 2000 4000 6000 8000 10000
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Secara umum, nilai kalor bahan bakar (LHV), torsi, daya, dan konsumsi bahan
bakar spesifik (SFC) gasohol mengalami penurunan dibandingkan dengan
pertalite. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
Nilai kalor bahan bakar (LHV) yang diperoleh dari hasil pengujian bom kalorimeter dengan bahan bakar pertalite sebesar 44260,12 kJ/kg, gasohol
5% sebesar 41466 kJ/kg, gasohol 10% sebesar 41171,88 kJ/kg, dan
gasohol 10% sebesar 40289,52 kJ/kg. Pembakaran pertalite lebih baik
karena nilai kalornya lebih tinggi daripada gasohol. Sehingga nilai torsi
dan daya juga lebih besar. Akan tetapi, dalam hal konsumsi bahan bakar,
pertalite lebih boros.
Torsi rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite sebesar 9,08 Nm, bahan bakar
gasohol 5% sebesar 9,02 Nm, bahan bakar gasohol 10% sebesar 9,03 Nm,
dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 8,97 Nm.
Daya rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite sebesar 4707,53 W, bahan
bakar gasohol 5% sebesar 4675,56 W, bahan bakar gasohol 10% sebesar
4681,48 W, dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 4654,52 W.
Konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite
sebesar 256,86 gr/kWh, bahan bakar gasohol 5% sebesar 249,49 gr/kWh,
bahan bakar gasohol 10% sebesar 248,65 gr/kWh, dan bahan bakar
2. Secara umum, efisiensi thermal, Air Fuel Ratio (AFR), dan efisiensi
volumetris gasohol mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertalite.
Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
Efisiensi thermal rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite adalah sebesar
32,27%, bahan bakar gasohol 5% sebesar 35,18%, bahan bakar gasohol
10% sebesar 35,87%, dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 37,06%. Air Fuel Ratio (AFR) rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari
hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite adalah sebesar
14,59; bahan bakar gasohol 5% sebesar 15,28; bahan bakar gasohol 10%
sebesar 15,38; dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 15,56.
Efisiensi volumetris rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite adalah sebesar
81,03%; bahan bakar gasohol 5% sebesar 82,13%; bahan bakar gasohol
10% sebesar 82,54%; dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 81,30%.
5.2 Saran
1. Melengkapi alat ukur pengujian untuk memperoleh hasil pengujian yang lebih
akurat
2. Menggunakan variasi putaran yang lebih spesifik untuk meningkatkan
ketelitian pengujian.
3. Melakukan modifikasi pada mesin seperti penggunaan blower untuk
mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik.
4. Melakukan pengujian emisi gas buang agar dampak terhadap lingkungan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Motor Bakar
Motor bakar pembakaran dalam (Internal Combustion Engine)
merupakan pesawat kalori yang merubah energi kimia dari bahan bakar menjadi
energi mekanis. Energi kimia dari bahan bakar yang becampur dengan udara
diubah terlebih dahulu menjadi energi termal melalui pembakaran atau oksidasi,
sehingga temperatur dan tekanan gas pembakaran di dalam silinder meningkat.
Gas bertekanan tinggi di dalam silinder berekspansi dan mendorong torak
bergerak translasi dan menghasilkan gerak rotasi poros engkol sebagai keluaran
mekanis motor. Demikian pula sebaliknya, gerak rotasi poros engkol akan
menghasilkan gerak translasi pada torak sehingga terjadi gerak bolak-balik torak
di dalam silinder. Disebut motor pembakaran dalam karena proses pembakaran
bahan bakar berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri.
Motor pembakaran dalam banyak digunakan dalam berbagai aktivitas
manusia, baik sebagai motor penggerak untuk pompa air, generator, mesin
pemotong rumput, maupun sebagai sarana transportasi untuk menunjang mobilitas
manusia dan barang.[1 Hal 1]
Motor bakar pembakaran luar (External Combustion Engine) adalah proses
pembakaran bahan bakar yang terjadi diluar dari motor itu sendiri. Di dalam
motor pembakaran luar, bahan bakar dibakar diruang bakar tersendir dan
memanfaatkan air untuk dipanaskan menjadi uap, sehingga uap bertekanan yang
dihasilkan digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin ataupun mendorong torak
sehingga terjadi gerak translasi. Jadi motor tidak digerakkan oleh gas yang
terbakar, akan tetapi digerakkan oleh uap air. Jenis dari ECE (External
Combustion Engine) adalah turbin uap, turbin gas, mesin uap, mesin stirling. Kelebihan motor pembakaran dalam adalah mesin yang lebih sederhana,
motor pembakaran luar adalah dapat digunakan bahan bakar berkualitas rendah
baik bahan bakar padat, cair dan gas, kapasitas lebih besar. Motor pembakaran
luar identik dengan bahan bakar padat seperti batubara.[2]
Gambar 2.1 Proses Pembakaran Luar (kanan) dan Proses Pembakaran Dalam
(kiri) [2]
2.2 Bahan Bakar Bensin
Hidrokarbon (HC) merupakan senyawa di mana setiap molekulnya hanya
mengandung hidrogen dan karbon yang dapat dibakar (dioksidasi), membentuk air
(H2O) atau karbondioksida (CO2). Bahan bakar hidrokarbon mempunyai variasi berat karbon dari 83% sampai 87% dan berat hidrogen dari 11% sampai 14%.
Pada umumnya bobot molekular komponen yang lebih besar mempunyai
temperatur didih lebih tinggi.
Bahan bakar bensin (gasoline) merupakan campuran senyawa hidrokarbon
cair yang sangat mudah menguap. Bensin terdiri dari parafin, naptalene, aromatik,
dan olefin, bersama-sama dengan beberapa senyawa organik lain dan kontaminan.
Struktur molekulnya dari C4– C9.
Angka Oktan Riset/Research Octane Number (RON) adalah karakteristik
menyala sendiri. Peringkat oktan didasarkan pada ukuran kemampuan bahan
bakar menahan detonasi. Semakin tinggi peringkat oktan, semakin kecil
kemungkinan untuk menghasilkan ledakan dini (pre-ignition). Kecenderungan
penyalaan dini menimbulkan gejala ketukan (knocking). Motor dengan rasio
kompresi rendah dapat menggunakan bahan bakar dengan angka oktan lebih
rendah, tetapi motor kompresi tinggi harus menggunakan bahan bakar oktan
tinggi untuk menghindari pengapian sendiri dan ketukan.[1 Hal 70-71]
Pertalite adalah salah satu jenis bahan bakar bensin yang dikeluarkan
Pertamina pada Mei 2015. Pertamina mengklaim Pertalite memiliki Research
Octane Number (RON) 90. Artinya lebih baik dibandingkan Premium yang memiliki nilai oktan 88. Pertamina meluncurkan Pertalite untuk memenuhi Surat
Keputusan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
313 Tahun 2013 tentang spesifikasi BBM RON 90.[3]
Berdasarkan keputusan Dirjen Migas No.313.K/10/DJM.T/2013:
Tabel 2.2 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenis Bensin 90 (Pertalite)
Titik didih akhir
Sumber: (Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)
Pertalite membuat pembakaran pada mesin kendaraan dengan teknologi
terkini lebih baik dibandingkan dengan premium yang memiliki RON 88.
Keunggulan pertalite adalah:
1. Durability, pertalite dapat dikategorikan sebagai bahan bakar kendaraan yang memenuhi syarat dasar durability/ketahanan, dimana bbm ini tidak
akan menimbulkan gangguan serta kerusakan mesin, karena kandungan
oktan 90 lebih sesuai dengan perbandingan kompresi kebanyakan
kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia.
2. Fuel Economy, kesesuaian oktan 90 Pertalite dengan perbandingan kompresi kebanyakan kendaraan beroperasi sesuai dengan
rancangannya. Perbandingan Air Fuel Ratio yang lebih tinggi dengan
konsumsi bahan bakar menjadikan kinerja mesin lebih optimal dan
efisien untuk menempuh jarak lebih jauh karena perbandingan biaya
dengan operasi bahan bakar dalam (Rupiah/kilometer) akan lebih
hemat.
mesin yang jauh lebih baik dibandingkan ketika menggunakan oktan
88. Hasilnya adalah torsi mesin lebih tinggi dan kecepatan meningkat.[4]
2.3 Motor Bakar Bensin
Motor bakar bensin dikenal dengan motor bakar siklus Otto. Siklus otto
pertama sekali dikembangkan oleh seorang insinyur berkebangsaan Jerman
bernama Nikolaus A. Otto pada tahun 1837.[5 Hal 42]
Pada motor bakar bensin, campuran udara bahan bakar dinyalakan oleh
percikan bunga api listrik diantara kedua elektrode busi sehingga motor bensin
juga dikenal sebagai motor pengapian percik (Spark ignition Engines). Busi
mempunyai fungsi untuk penghasil loncatan api yang akan menyalakan gas dari
campuran bahan bakar dan udara. Karburator dan injektor mempunyai fungsi
yang sama antara lain untuk melakukan percampuran serta pengabutan udara
dengan bahan bakar yang akan dibakar di dalam ruang bakar. Terdapat beberapa
jenis mesin otto berdasarkan banyak langkahnya antara lain siklus Otto 2 langkah,
siklus Otto 4 langkah, siklus Otto 6 langkah. Siklus Otto 2 langkah dan 4 langkah
banyak digunakan pada kendaraan yang beredar sebagai transportasi.[1 Hal 2-3]
2.3.1 Siklus Otto Ideal
Dalam siklus ini, terjadi penyalaan bunga api dengan menggunakan busi
(spark ignition) yang akan membakar campuran bahan bakar dengan udara setelah
melewati proses pengabutan yang dilakukan oleh karburator atau injektor. Siklus
Otto ideal memiliki 4 langkah disebut juga mesin 4-langkah (four stroke engine).
Gambar 2.2 Pembagian Langkah pada Siklus Otto [6 Hal 10]
Langkah-langkah yang terjadi pada motor bensin siklus Otto ideal adalah
sebagai berikut:
1. Langkah hisap
Diawali dengan posisi torak di TMA dan berakhir dengan posisi torak
di TMB, yang mana menghisap campuran bahan bakar dengan udara ke
dalam silinder. Untuk meningkatkan massa campuran yang dihisap,
katup masuk terbuka sesaat sebelum langkah hisap dimulai dan
menutup setelah berakhirnya langkah tersebut.
2. Langkah kompresi
Ketika kedua katup tertutup di mana campuran di dalam silinder
dimampatkan dan volumenya diperkecil. Menjelang akhir langkah
kompresi, pembakaran diaktifkan dan tekanan silinder naik dengan
cepat.
3. Langkah ekspansi
Diawali dengan posisi torak di TMA dan berakhir di TMB ketika
temperatur dan tekanan gas yang tinggi mendorong torak ke bawah dan
memaksa poros engkol untuk berputar. Ketika torak mendekati TMB,
katup buang terbuka untuk mengawali proses buang dan tekanan
4. Langkah buang
Di mana sisa gas yang dibakar keluar dari silinder ketika torak bergerak
ke arah TMA. Ketika torak mendekati TMA, katup masukan akan
terbuka. Sesaat setelah TMA, katup buang menutup dan siklus dimulai
lagi.[1 Hal 10-11]
Dalam kondisi ideal siklus Otto dibatasi dua garis isentropik dan dua garis
isovolume. Gambar 2.3 akan menjelaskan diagram siklus otto ideal.
Gambar 2.3 Diagram P-v dan Diagram T-s Siklus otto Ideal [7]
2.4 Unjuk Kerja Motor Bakar Bensin
Performansi dapat disebut juga sebagai unjuk kerja dari motor bakar bensin.
Beberapa hal yang mempengaruhi performansi motor bakar bensin antara lain
seperti rasio udara dan bahan bakar, dan rasio kompresi dari volume silinder
ruang bakar. Kedua hal tersebut saling berpengaruh dengan peningkatan unjuk
kerja mesin, efisiensi mesin dan emisi dari gas buang mesin motor bakar bensin.
2.4.1 Torsi Poros
Perkalian antara gaya dengan jarak dapat disebut sebagai Torsi. Disaat
proses pembakaran pada ruang bakar, dimana piston akan bergerak translasi dan
poros engkol yang menghubungkan piston dengan batang piston akan merubah
perhitungan gaya tarik yang terjadi pada roda dengan menggunakan persamaan
2.1.
………...2.1 Dimana : F = Gaya (N)
g = Percepatan gravitasi (9,8 m/s2) m = Massa (kg)
Untuk menghitung torsi pada roda, dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan 2.2.
………...2.2 Dimana : Troda = Torsi pada roda (Nm)
r = jari-jari roda = ½ diameter roda
Torsi pada mesin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.3.
………...………..2.3
Dimana : Tmesin = Torsi mesin (Nm)
2.4.2 Daya Poros
Kerja mesin selama waktu tertentu dapat disebut sebagai daya. Besarnya
poros engkol yang bekerja dengan pembebanan merupakan daya poros. Daya
poros berasal dari langkah kerja disaat campuran udara dan bahan bakar meledak
dan menyebabkan piston mengalami dorongan yang menghasilkan kerja pada
poros engkol yang mengubah gerak translasi menjadi gerak rotasi. Prestasi mesin
motor bakar ditentukan oleh daya poros yang telah dibebankan akibat gesekan
seperti pada torak, dinding silinder, poros, dan bantalan. Frekuensi putaran motor
atau disebut dengan RPM (Revolution per Minute) mempengaruhi besarnya daya
poros dimana semakin banyak putaran poros yang terjadi maka semakin besar
daya poros tersebut. Daya poros dapat dicari dengan persamaan 2.4.[12]
Dimana : T = Torsi (Nm)
2.4.3 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (Specific Fuel Consumption)
Konsumsi bahan bakar spesifik adalah parameter unjuk kerja mesin yang
berhubungan langsung dengan nilai ekonomis sebuah mesin, karena dengan
mengetahui hal ini dapat dihitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sejumlah daya dalam selang waktu tertentu. SFC dapat dicari
dengan menggunakan persamaan 2.5.
̇ ………2.5
Dimana : Sfc = konsumsi bahan bakar spesifik (gr/kW.h) ̇ = laju aliran bahan bakar (gr/jam)
P = Daya (W)
Besarnya laju aliran masssa bahan bakar dihitung dengan persamaan 2.6.
̇
……….2.6
Dimana : = massa jenis bahan bakar (kg/m3)
V = volume bahan bakar yang habis terpakai (m3) = waktu untuk menghabiskan bahan bakar (s)
2.4.4 Air Fuel Ratio (AFR)
Perbandingan udara dan bahan bakar yang masuk kedalam ruang bakar
adalah AFR yang didapat dengan menggunakan persamaan 2.7 – 2.11.[13]
̇ ̇ ………2.7
Dimana : = massa udara di dalam silinder per siklus (kg/cyl-cycle)
= massa udara di dalam silinder per siklus (kg/cyl-cycle)
̇ = laju aliran udara di dalam mesin (gr/jam) ̇ = laju aliran bahan bakar di dalam mesin (gr/jam)
………..2.9
………..2.10
……….2.11
Dimana : ̇ = laju aliran udara (gr/jam)
= laju aliran udara per siklus (kg/cyl-cycle)
= tekanan udara masuk silinder (1atm = 100 kPa)
= volume langkah (m3) = volume langkah (m3)
= konstanta udara (0,287 kJ/kg.K)
= temperature udara masuk silinder (K)
= bore (m)
= stroke (m)
= rasio kompresi
2.4.5 Efisiensi Volumetris
Jika sebuah mesin empat langkah dapat menghisap udara pada kondisi
isapnya sebanyak volume langkah toraknya untuk setiap langkah isapnya, maka
proses ini ideal. Tetapi dalam kondisi aktual dimana massa udara yang dapat
dialirkan selalu lebih sedikit dari perhitungan teoritis. Hal tersebut terjadi akibat
efek pemanasan yang mengurangi kerapatan udara ketika memasuki silender
mesin. Efisiensi Volumetris dapat dicari dengan persamaan 2.12 dan 2.13.
………...
2.12
………..………
2.13
Dimana :
=
efisiensi volumetris (%)= massa udara dalam silinder per siklus (kg/cyl-cycle)
= volume langkah (m3) = densitas udara (kg/m3)
2.4.6 Efisiensi Thermal
Kerja berguna yang dihasilkan selalu lebih kecil dari pada energi yang
dibangkitkan piston karena sejumlah energi hilang akibat adanya rugi-rugi
mekanis seperti gesekan, kerja pompa oli dan pompa pendingin, dan panas yang
terbuang. Maka Efisiensi Thermal dapat dicari dengan persamaan 2.14.
̇ ...2.14
Dimana : LHV = Nilai kalor bawah bahan bakar (kJ/kg)
2.5 Nilai Kalor Bahan Bakar
Reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen dari udara
menghasilkan panas. Besarnya panas yang ditimbulkan jika satu satuan bahan
bakar dibakar sempurna disebut nilai kalor bahan bakar (Caloric Value, CV).
Berdasarkan asumsi ikut tidaknya panas laten pengembunan uap air dihitung
sebagai bagian dari nilai kalor suatu bahan bakar, maka nilai kalor bahan bakar
dapat dibedakan menjadi nilai kalor atas dan nilai kalor bawah.
Nilai kalor atas (High Heating Value, HHV), merupakan nilai kalor
yang diperoleh secara eksperimen dengan menggunakan bom kalorimeter dimana
hasil pembakaran bahan bakar didinginkan sampai suhu kamar sehingga sabagian
besar uap air yang terbentuk dari pembakaran hydrogen mengembun dan
melepaskan panas latennya. Secara teoritis, besarnya nilai kalor atas (HHV) dapat
dihitung bila diketahui komposisi bahan bakarnya dengan menggunakan
persamaan 2.15.[8 Hal 3]
( ) ... 2.15
Dimana : HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)
Cv = Panas jenis bom kalorimeter (73529,6 kJ/kg oC)
Dan nilai kalor bawah dapat dihitung dengan persamaan 2.16.
LHV = HHV –3240 ... 2.16
Dimana : LHV = Nilai kalor bawah (kJ/kg)
HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)
Jika diketahui komposisi bahan bakar maka besarnya nilai kalor atas
dapat dihitung juga dengan menggunakan persamaan Dulong.[9 Hal 43]
...
2.17Dimana : HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)
C = Persentase karbon dalam bahan bakar
H2 = Persentase hydrogen dalam bahan bakar O2 = Persentase oksigen dalam bahan bakar S = Persentase sulfur dalam bahan bakar
Nilai kalor bawah (Low Heating Value, LHV), merupakan nilai kalor
bahan bakar tanpa panas laten yang berasal dari pengembunan uap air. Umumnya
kandungan hidrogen dalam bahan bakar cair berkisar 15% yang berarti setiap satu
satuan bahan bakar 0,15 bagian merupakan hidrogen. Pada proses pembakaran
sempurna, air yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar adalah setengah dari
jumlah mol hidrogen.
Selain berasal dari pembakaran hidrogen, uap air yang terbentuk pada
proses pembakaran dapat pula berasal dari kandungan air yang memang sudah ada
di dalam bahan bakar. Panas laten pengkondisian uap air pada tekanan parsial 20
kN/m2 (tekanan yang umum timbul pada gas buang) adalah sebesar 2400 kJ/kg, sehingga besarnya nilai kalor bawah (LHV) dapat dihitung berdasarkan
persamaan 2.18.[9 Hal 44]
Dimana : LHV = Nilai Kalor Bawah (kJ/kg)
M = Persentase kandungan air dalam bahan bakar
Dalam perhitungan efisiensi panas dari motor bakar dapat menggunakan
nilai kalor bawah (LHV) dengan asumsi pada suhu tinggi saat gas buang
meninggalkan mesin tidak terjadi pengembunan uap air. Namun dapat juga
menggunakan nilai kalor atas (HHV) karena nilai tersebut umumnya lebih cepat
tersedia. Peraturan pengujian berdasarkan ASME (American of Mechanical
Engineers) menentukan penggunaan nilai kalor atas (HHV), sedangkan peraturan SAE (Society of Automotive Engineers) menetukan penggunaan nilai kalor bawah
(LHV).
2.6 Sejarah Bioetanol
Bioetanol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan
pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan
keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa
minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa Neolitik.
Campuran dari Bioetanol yang mendekati kemurnian untuk pertama kali
ditemukan oleh Kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada
masa Kalifah Abbasid dengan peneliti yang terkenal waktu itu adalah Jabir ibn
Hayyan (Geber), Al-Kindi (Alkindus) dan al-Razi (Rhazes). Catatan yang disusun
oleh Jabir ibn Hayyan (721-815) menyebutkan bahwa uap dari wine yang
mendidih mudah terbakar. Al-Kindi (801-873) dengan tegas menjelaskan tentang
proses distilasi wine. Sedangkan Bioetanol absolut didapatkan pada tahun 1796
oleh Johann Tobias Lowitz, dengan menggunakan distilasi saringan arang.
Antoine Lavoisier menggambarkan bahwa bioetanol adalah senyawa yang
terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Nicolas-Théodore
de Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian
(1858), Archibald Scott Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan
demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan
Inggris oleh Henry Hennel dan S.G.Serullas di Perancis. Michael Faraday
membuat etanol dengan menggunakan hidrasi katalis asam pada etilen pada tahun
1982 yang digunakan pada proses produksi etanol sintetis hingga saat ini.
Pada tahun 1840 etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika Serikat,
pada tahun 1880-an Henry Ford membuat mobil quadrycycle dan sejak tahun
1908 mobil Ford model T telah dapat menggunakan bioetanol sebagai bahan
bakarnya. Namun pada tahun 1920an bahan bakar dari petroleum yang harganya
lebih murah telah menjadi dominan menyebabkan etanol kurang mendapatkan
perhatian. Akhir-akhir ini, dengan meningkatnya harga minyak bumi, bioetanol
kembali mendapatkan perhatian dan telah menjadi alternatif energi yang terus
dikembangkan.[10]
2.6.1 Bioetanol
Alkohol adalah bahan bakar dari jenis oksigenant. Molekul alkohol
memiliki satu atau lebih oksigen yang memberikan kontribusi untuk pembakaran.
Alkohol dinamai sesuai molekul dasar dari hidrokarbon turunannya, misalnya
metanol atau metil alkohol (CH3OH), etanol atau etil alkohol (C2H5OH), propanol (C3H7OH), butanol (C4H9OH). Secara teoritis, setiap molekul organik dari jenis alkohol dapat digunakam sebagai bahan bakar.
Penggunaan etanol sebagai bahan bakar mobil selama bertahun-tahun telah
dilakukan di berbagai negara di dunia. Brazil adalah pemakai yang terkemuka, di
mana pada tahun 1900-an, 4,5 juta kendaraan dioperasikan dengan bahan bakar
93% etanol. Selama beberapa tahun, gasohol (gasoline-alcohol) telah tersedia
pada stasiun pompa bahan bakar di Brazil.
Gasohol merupakan campuran 90% bensin dan 10% etanol. Dua
kombinasi campuran yang umum adalah E85 (85% etanol) dan E10 (10% etanol).
E85 pada dasarnya suatu bahan bakar alkohol dengan 15% bensin ditambahkan
untuk meniadakan sebagian permasalahan dalam penggunaan alkohol murni yaitu
start dingin, tangki mudah terbakar, dan lain-lain. E10 mengurangi penggunaan
bensin dengan tanpa memerlukan modifikasi motor mobil. Motor berbahan bakar
Bioetanol merupakan bahan bakar dari tumbuhan yang memiliki sifat
menyerupai minyak premium (Khairani,2007). Bioetanol adalah etanol yang
dihasilkan dari fermentasi glukosa (gula) yang dilanjutkan dengan proses distilasi.
Proses distilasi dapat menghasilkan etanol dengan kadar 95% volume, untuk
digunakan sebagai bahan bakar (biofuel) perlu lebih dimurnikan lagi hingga
mencapai 99 % yang lazim disebut fuel grade etanol (Damianus,2010).
Bahan baku pembuatan bioetanol dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :
1. Bahan sukrosa
Bahan-bahan yang termasuk kedalam kelompok ini antara lain nira, tebu, nira
nipati, nira sargum manis, nira kelapa, nila aren, dan sari buah mete.
2. Bahan berpati
Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah bahan-bahan yang
mengandung pati. Bahan tersebut antara lain, tepung-tepung ubi ganyong,
jagung, sagu, bonggol pisang, ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain.
3. Bahan berselulosa
Bahan berselulosa (lignoselulosa) artinya adalah bahan tanaman yang
mengandung selulosa (serat), antara lain kayu, jerami, batang pisang, dan
lain-lain.
Bioetanol jika dilihat dari segi bahan baku, maka proses pembuatan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Motor bakar torak merupakan mesin dengan sistem pembakaran dalam
atau Internal Combustion Engine di mana pada saat sekarang ini banyak
digunakan untuk berbagai keperluan terutama di bidang transportasi. Peranannya
di bidang transportasi sangatlah besar karena hampir semua kendaraan terutama
yang beroperasi di darat menggunakan motor bakar torak sebagai penggeraknya.
Penggunaan motor bakar yang besar ini disebabkan oleh banyak pekerjaan yang
dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat dengan bantuan motor bakar.
Sementara itu harga minyak bumi dunia yang terus meningkat dan diikuti
dengan meningkatnya kebutuhan bahan bakar fosil serta isu lingkungan global
yang menuntut tingkat kualitas lingkungan yang lebih baik, mendorong
pemerintah diharuskan mengambil kebijakan baik jangka pendek, menengah,
maupun jangka panjang. Saat ini konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia
mencapai 9,4 juta Kiloliter hingga Agustus 2015. Angka ini tergolong besar
karena nilainya bekisar 137 trilyun rupiah, terlebih lagi ditengarai banyak
dinikmati oleh golongan menengah ke atas. (BPH Migas,2015). Dalam jangka
pendek Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM subsidi yaitu bagi
pemilik kendaraan berkapasitas 1500cc ke atas disarankan menggunakan BBM
nonsubsidi seperti Pertalite dan Pertamax. Meskipun saat ini telah mulai
dikembangkan mobil listrik sebagai kendaraan yang paling ramah lingkungan
namun permasalahan mengenai baterai penyimpanan yang tahan lama belum bisa
teratasi serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan isi ulang masih cukup lama
sehingga menjadi kendala. Demikian halnya dengan konversi ke BBG yang masih
terkendala dengan infrastruktur. Sehingga sampai saat ini pilihan pada bahan
bakar minyak masih lebih tinggi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji
Mulai abad ke-21dunia mulai memikirkan energi alternatif yang dapat
digunakan untuk motor diesel ataupun motor otto. Salah satu bahan bakar
alternatif yang dikembangkan adalah bahan bakar alkohol. Alkohol adalah salah
satu jenis hidrokarbon yang salah satu atom hidrogennya diganti dengan hydroxyl
radical OH. Jeni-jenis alkohol sebagai berikut, (Pulkrabek, 2004) a. Metil alkohol (metanol), CH3OH
b. Etil alkohol (etanol), C2H5OH c. Propil alkohol (propanol), C3H7OH
Jenis alkohol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar adalah metanol
dan etanol. Penelitian mengenai bahan bakar alternatif ini sudah banyak
dilakukan.
Disekitar kita banyak sekali bahan yang memiliki potensi untuk dijadikan
bioetanol sebagai energi alternatif terutama untuk kebutuhan bahan bakar alat
transportasi. Banyak hasil pertanian di Indonesia yang memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai bioetanol. Metanol dan etanol yang diproses secara
fermentasi dari tanaman tebu, jagung, nenas, umbi-umbian, dan masih banyak
lagi. Namun, semua sumber daya hayati ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dari berbagai penelitian yang telah banyak dilakukan, penggunaan
bioetanol sebagai bahan alternatif memberikan dampak yang positif dari sisi
penghematan bahan bakar. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji
pengaruh penambahan bioetanol pada bahan bakar jenis pertalite. Hal ini karena
pertalite merupakan bahan bakar yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan
perkembangan otomotif. Pertalite memiliki oktan yang lumayan tinggi dan sisi
fisik bahan bakar pertalite memiliki stabilitas oksidasi yang lebih tinggi dan
kandungan oksin, aromatik, dan benzenanya tidak dibatasi. Hasilnya pembakaran
bahan bakar pertalite lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan
teknologi otomotif, maka angka oktan bahan bakar harus disesuaikan, sementara
itu pertalite memilki RON (Research Octane Number) 90. Di samping itu bahan
1.2Tujuan Pengujian
1. Untuk mengetahui nilai kalor bahan bakar pertalite, campuran
pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.
2. Untuk mengetahui perbandingan torsi motor bakar bensin menggunakan
pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.
3. Untuk mengetahui perbandingan daya motor bakar bensin menggunakan
pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.
4. Untuk mengetahui perbandingan konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) motor
bakar bensin menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol)
5%, 10%, dan 15%.
5. Untuk mengetahui perbandingan efisiensi termal motor bakar bensin
menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan
15%.
6. Untuk mengetahui perbandingan AFR (Air Fuel Ratio) motor bakar bensin
menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan
15%.
7. Untuk mengetahui perbandingan efisiensi volumetris motor bakar bensin
menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan
15%.
1.3Batasan Masalah
1. Bahan bakar yang digunakan dalam percobaan ini adalah bahan bakar
pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.
2. Alat uji yang digunakan untuk menghitung nilai kalor bahan bakar adalah bom
kalorimeter
3. Performansi mesin yang diteliti berupa daya, torsi, SFC, Efisiensi termal, rasio
udara-bahan bakar (AFR), dan efisiensi volumetris.
4. Mesin uji yang digunakan adalah mesin otto 4 langkah 1 silinder kapasitas
1.4Metodologi Penulisan
Metodologi penulisan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
a. Studi literature, berupa studi kepustakaan, kajian dari buku-buku dan
jurnal-jurnal terkait.
b. Browsing internet, berupa studi artikel-artikel, gambar-gambar dan buku
elektronik, serta data-data lain yang berhubungan.
c. Metode studi lapangan, yaitu dengan mengambil data dari hasil pengujian
yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik.
d. Diskusi, berupa tanya jawab dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh
Departemen Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara.
1.5Sistematika Penulisan
Agar penyusunan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan
mempermudah pembaca memahami tulisan ini, maka dilakukan pembagian bab
berdasarkan isinya.
Pada bab I pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, batasan masalah,
metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan pustaka,
yaitu berisi landasan teori yang diperoleh dari litelatur untuk mendukung
pengujian. Bab III metodologi penelitian, yaitu berisi metode yang akan
digunakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Pada bab ini juga akan dibahas
mengenai langkah-langkah pengujian, pengolahan dan analisa data yang akan
digunakan untuk menyelesaikan teori dari topic yang akan diangkat. Bab IV
analisa data dan pembahasan, pada bab ini akan dianalisa dan dibahas mengenai
data-data yang diperoleh dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Bab V berisi
kesimpulan dan saran dari hasil pengujian. Kemudian daftar pustaka dan
ABSTRAK
Bahan bakar gasohol diuji pada mesin Supra-X 125cc untuk mengetahui
perbandingan unjuk kerja mesin dengan menggunakan bahan bakar bensin jenis
pertalite. Prosedur pengujian dibagi dua tahap yaitu, pengujian nilai kalor bahan
bakar dan pengujian unjuk kerja mesin. Hasil pengujian nilai kalor bahan bakar
diperoleh nilai kalor pertalite 44260,12 kJ/kg; gasohol 5% 41466 kJ/kg; gasohol
10% 41171,88 kJ/kg; dan gasohol 15% 40289,52 kJ/kg. Hasil pengujian unjuk
kerja diperoleh torsi dan daya rata-rata tertinggi pada bahan bakar pertalite sebesar
9,08 Nm dan 4707,53 W. Konsumsi bahan bakar spesifik terendah pada bahan
bakar gasohol 15% yaitu 242,4 gr/kW.h.
ABSTRACT
Gasohol fuels tested on Supra-X 125cc engine to compare the performance of the
engine using gasoline fuel types pertalite. The testing procedure is divided into
two stages, testing the calorific value of the fuel and engine performance testing.
The test results obtained calorific value fuel heating value pertalite 44260.12
kJ/kg; gasohol 5% 41 466 kJ/kg; gasohol 10% 41171.88 kJ/kg; and gasohol 15%
40289.52 kJ/kg. The test results obtained torque and power performance highest
average fuel pertalite of 9.08 Nm and 4707.53 W. Lowest specific fuel
consumption in the fuel gasohol 15% is 242.4 g/kWh.
UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN
BIOETANOL PADA BAHAN BAKAR PERTALITE
TERHADAP UNJUK KERJA MOTOR BAKAR BENSIN
Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
M. HAFIZ PRATAMA
NIM. 110401104DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN