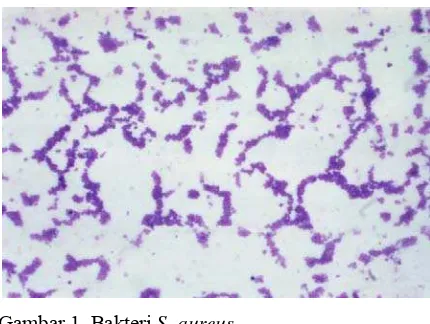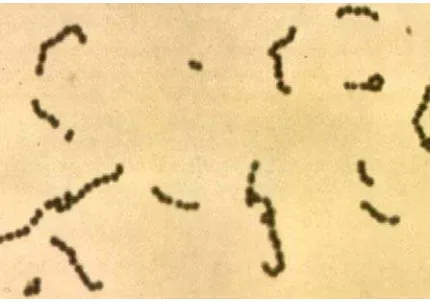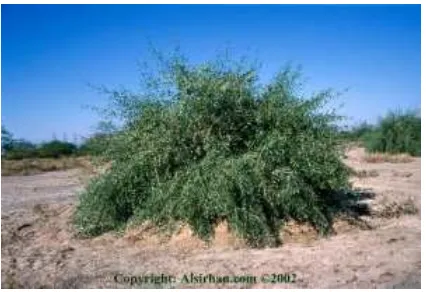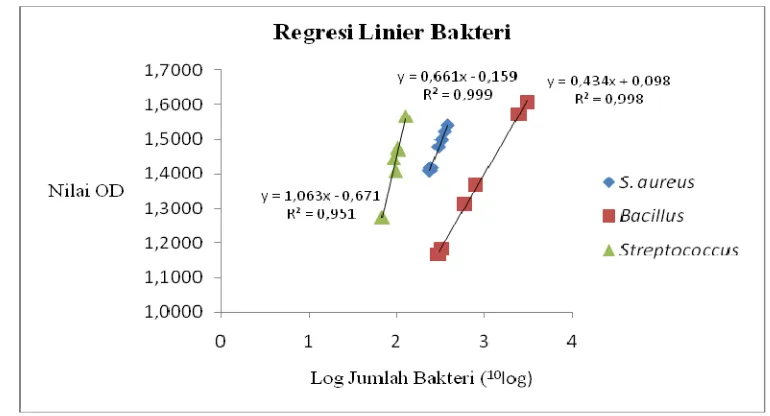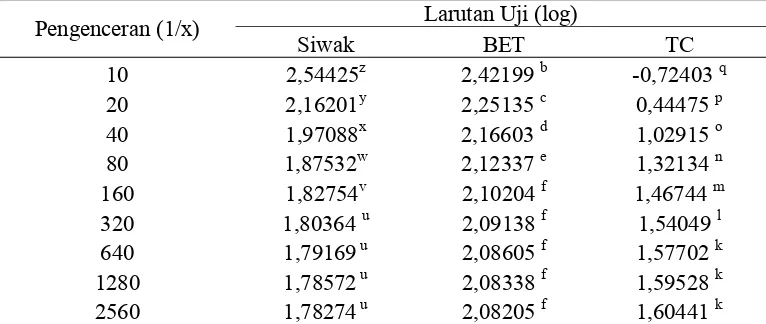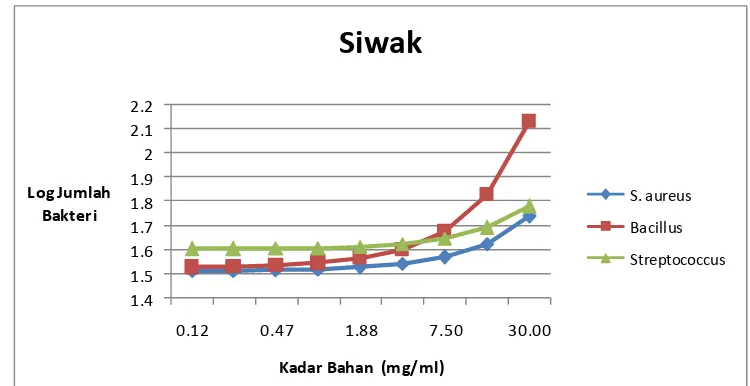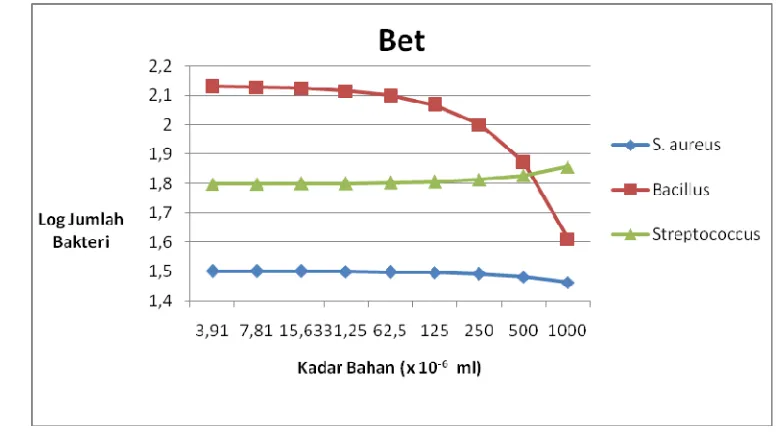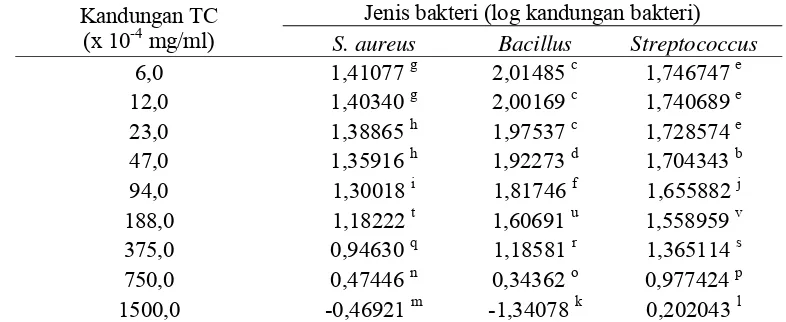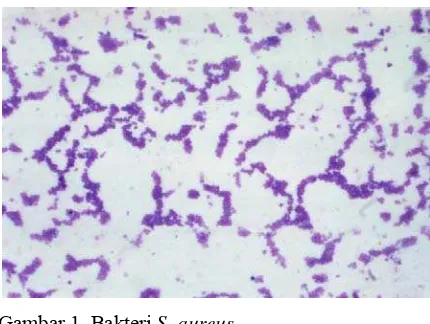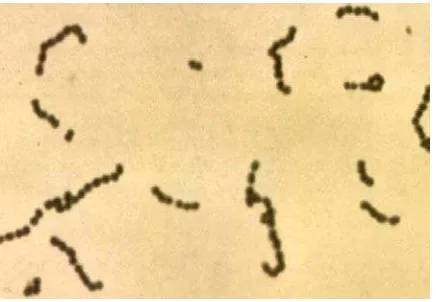TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI MULUT
IRAL PREPINIDA
B04062431
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi.
Bogor, Februari 2011
Iral Prepinida
IRAL PREPINIDA. Comparative Inhibition Activity of Extracts Siwak (Salvadora persica) With Mouthwash Commercial Against Oral Bacteria. Supervised by EKO S. PRIBADI and HUDA S. DARUSMAN.
The research aimed to find out antibiotic properties of siwak extraction
solution and compared it to commercial mouthwash solution. The siwak
extraction solution showed poor inhibition activity to isolated mouth bacteria than
BET and TC mouthwash solution, respectively. The TC mouthwash solution
showed more effective to inhibited the bacteria than BET mouthwash solution
and siwak extraction solution.
Keywords : Siwak, commercial mouthwash solution, antibiotic property, mouth
IRAL PREPINIDA. Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora
persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut. Dibimbing oleh EKO S. PRIBADI dan HUDA S. DARUSMAN.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol kayu siwak terhadap bakteri-bakteri mulut dan membandingkannya dengan daya hambat yang dimiliki larutan kumur komersil yang ada saat ini. Hasil akhir ekstraksi kayu siwak didapatkan larutan ekstraksi dengan kadar 200 dan 300 mg/ml. Dari penelitian ini, hasil ekstraksi dengan kandungan 300 mg/ml tidak memiliki daya hambat yang baik terhadap bakteri-bakteri mulut yang diisolasi. Daya hambat yang dimiliki oleh larutan kumur komersil BET dan TC masih lebih baik dibandingkan ekstrak kayu siwak. Larutan kumur TC memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kedua larutan lainnya.
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI MULUT
IRAL PREPINIDA
B04062431
Skripsi
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan
Institut Pertanian Bogor
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Bakteri Mulut Nama Mahasiswa : Iral Prepinida
NIM : B04062431
Menyetujui,
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. drh. Eko S. Pribadi, MS. drh. Huda S. Darusman, M.Si. NIP.19640605.199103.1.006 NIP.19790622.200501.1.001
Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB
Dr. Nastiti Kusumorini NIP.19621205.198703.2.001
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut“. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Keluarga tercinta : Bapak dan Ibu serta Saudara-saudara Saya (Khalifian, Wika, Ike, Ryqaw, dan Izza) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do’a kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. drh. Eko Sugeng Pribadi, M.S. dan Bapak drh. Huda Sholahuddin Darusman, M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, arahan, bantuan, dan saran yang diberikan kepada penulis. 3. Bapak drh. H. Abdul Gani Amri Siregar, M.S. sebagai dosen penguji
seminar atas kritik dan saran yang membangun yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Agus Soemantri, S.Si., Ibu Roselyn Saferina, A.Md., dan Bapak Ifan atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian di laboratorium Bakteriologi FKH-IPB.
5. Bapak drh. Usamah Afiff, M.Sc. sebagai dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan bantuannya.
6. Bapak Dr. Ir. Bonny P. W. Soekarno, M.S., mantan Kepala BPA TPB-IPB atas bimbingan dan bantuannya.
7. Bapak Dr. Ir. Irmansyah, M.Si., sebagai Kepala BPA TPB-IPB atas bimbingan dan bantuannya.
8. Seluruh dosen, pegawai, dan staf Tata Usaha FKH-IPB.
11.Teman-teman FKH’43 Aesculapius atas bantuan dan kerjasamanya. 12.Semua pihak yang telah membantu penulis selama kuliah di S1 FKH-IPB.
“Tiada gading yang tak retak”, begitu juga skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon ma’af jika masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat.
Bogor, Februari 2011
Penulis dilahirkan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 23 Maret 1989. Penulis merupakan anak sulung dari enam bersaudara, buah hati dari Ayahanda Zulkifli, S.Pt. dan Ibunda Meriyanah. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK An-Nahl Tanjung Enim pada tahun 1994 dan lulus tahun 1995. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 26 Tanjung Enim dan lulus pada tahun 2000. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Tanjung Enim dan lulus pada tahun 2003. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Muara Enim dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan pada tahun berikutnya penulis memilih Fakultas Kedokteran Hewan sebagai Jurusan di Institut Pertanian Bogor.
Halaman
Daftar Tabel ... x
Daftar Gambar ... xi
Pendahuluan Latar Belakang ... 1
Perumusan Masalah ... 2
Tujuan Penelitian ... 2
Hipotesis ... 2
Tinjauan Pustaka Mikroba Mulut ... 3
Kayu Siwak ... 6
Klasifikasi Tanaman Siwak (Salvadora persica) ... 7
Morfologi dan Habitat Tanaman Siwak (Salvadora persica) ... 8
Manfaat dan Kandungan Aktif ... 9
Metode Penelitian Waktu dan Tempat Penelitian ... 11
Bahan Penelitian ... 11
Media dan Reagen ... 11
Bubuk Kayu Siwak ... 11
Larutan Kumur yang Diuji ... 12
Mikroba yang Diuji ... 12
Rancangan Penelitian ... 13
Analisis Statistika ... 14
Hasil dan Pembahasan ... 15
Simpulan dan Saran... 24
Daftar Pustaka ... 25
Nomor Halaman
1. Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap pertumbuhan campuran bakteri ... 17
2. Pengaruh ekstrak kayu Siwak terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. ... 18
3. Pengaruh BET terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus
sp., dan Streptococcus sp. ... 20
4. Pengaruh TC terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus
Nomor Halaman
1. Bakteri Staphylococcus aureus ... 4
2. Bakteri Streptococcus sp.. ... 5
3. Bakteri Bacillus sp.. ... 6
4. Tanaman Siwak. ... 8
5. Batang kayu Siwak ... 9
6. Kurva regresi linier bakteri ... 16
7. Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap Pertumbuhan Campuran Bakteri ... 17
8. Pengaruh ekstrak kayu Siwak terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. ... 18
9. Pengaruh BET terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. ... 20
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemanfaatan bahan yang diperoleh dari daun, akar, dan kayu sebagai obat
sudah diketahui sejak lama oleh masyarakat dunia dan Indonesia. Kelompok
masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan telah terbiasa memanfaatkan
bahan kayu untuk mengobati penyakit-penyakit yang mereka derita (Yusro, 2009).
Masyarakat Muslim di Timur Tengah telah lama memanfaatkan kayu siwak untuk
perawatan gigi. Kelompok yang memanfaatkan kayu siwak mengeluarkan biaya
perawatan gigi yang lebih sedikit dibandingkan kelompok yang tidak
menggunakan kayu siwak (Al-Khateeb et al.,1991; Al-Lafi dan Ababneh, 1995).
Penelitian-penelitian yang mengkaji manfaat bahan kayu yang memiliki
sifat antimikroba telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Al-Bayati dan Al-Mola,
2008; Ghalem dan Mohamed, 2008; Ghosh et al., 2008; Al-Bayati, 2009; Demir
et al., 2009). Penelitian pemanfaatan bahan-bahan kayu pun sudah banyak
dilakukan di Indonesia (Lestari, 2003; Syarif, 2005; Yusro, 2009). Sifat
antimikroba yang dimiliki oleh kayu siwak juga telah banyak diteliti, baik secara
in vitro (Pratama, 2005; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008; Supriyadi 2009) maupun
secara klinis (Almas dan Al-Zeid, 2004). Kayu siwak memiliki sifat antibakteri
terhadap Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis,
Streptococcus pyogenes, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Actinomyces
naeslundii, Phorphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia dan Candida
albicans. Hanya bakteri Lactobacillus acidophilus dan Pseudomonas aeruginosa
saja yang memperlihatkan sifat tahan terhadap efek antibakteri kayu siwak
(AbdElRahman et al., 2002; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008).
Saat ini sudah banyak beredar larutan kumur sebagai salah satu hasil
buatan industri untuk merawat kesehatan gigi. Masyarakat memiliki kebebasan
yang luas untuk memilih larutan kumur yang disukai. Beberapa penelitian sudah
dilakukan untuk melihat efek antimikroba dari larutan kumur ini (McBain et al.,
2003; Pires et al., 2007). Penelitian yang mengamati efek kayu siwak dan bahan
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan
dalam penelitian merupakan pengembangan dari pertanyaan berikut :
5 apakah larutan kumur yang beredar di Indonesia selama ini sudah
memiliki efektifitas antibakteri yang optimal sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?
5 apakah bahan-bahan herbal, seperti kayu siwak, dapat memberikan
efektifitas yang sama dengan larutan kumur komersil yang beredar?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas larutan kumur
komersil yang beredar melalui pemeriksaan secara in vitro dan penilaian
efektifitas antimikroba yang dimiliki oleh larutan kumur; membandingkan
efektifitas antimikroba dari kayu siwak terhadap larutan kumur komersil yang ada
melalui penilaian efek antimikroba secara in vitro; memberikan gambaran ke
masyarakat mengenai mutu mikrobiologik dari larutan kumur komersil dan kayu
siwak yang dijual di Indonesia selama ini.
Hipotesis
Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah
Pertama
H0 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang sama dengan larutan
kumur komersil yang diperiksa
H1 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang berbeda dengan larutan
kumur komersil yang diperiksa
Kedua
H0 : tidak ada perbedaan efek antimikroba dari larutan kumur yang diperiksa
TINJAUAN PUSTAKA
Mikroba Mulut
Mikroba mulut adalah ragam mikroorganisme yang ada dan terdapat di
dalam mulut. Mikroba-mikroba yang terdapat di mulut tersebut bisa bermanfaat
ataupun bisa menimbulkan penyakit/masalah. Penyakit pada mulut berhubungan
erat dengan kebersihan mulut. Saat ini, banyak cara yang dilakukan orang untuk
menjaga kesehatan mulutnya. Salah satunya adalah dengan membersihkan gigi
dan mulut. Produk-produk komersil banyak terdapat di pasaran yang ditujukan
untuk membersihkan gigi dan mulut. Penyakit mulut yang disebabkan oleh
mikroba yang berkembangbiak di dalam mulut, antara lain plak dan karang gigi
(calculus), peradangan gusi (gingivitis), gigi berlubang (cariesdentis), peradangan
amandel dan tenggorokan, radang mulut (stomatitis), dan bau mulut (halitosis).
Mulut merupakan tempat yang ideal untuk tumbuh dan berkembangnya
mikroorganisme karena mulut memiliki kelembaban serta memiliki asupan
makanan yang teratur. Mikroba-mikroba yang terdapat di dalam mulut tersebut
antara lain Candida albicans, Streptococcus viridans, S. aureus, S. mutans,
Lactobacillus, Solobacterium moorei. S. mutans dan Lactobacillus merupakan
kuman yang kariogenik karena mampu dengan segera membentuk asam dari
karbohidrat yang difermentasi. S. mutans merupakan bakteri patogen pada mulut
karena menjadi penyebab utama terbentuknya plak, gingivitis, dan karies gigi
(Lee et al., 1992). Staphylococcus aureus merupakan bakteri penyebab intoksitasi
dan terjadinya berbagai macam infeksi (Supardi dan Sukamto, 1999). S. moorei
merupakan salah satu bakteri penyebab bau mulut.
S. aureus merupakan bakteri positif Gram. Bakteri Staphylococcus mudah
tumbuh pada berbagai media, bermetabolisme aktif dengan memfermentasi
karbohidrat dan menghasilkan pigmen yang beragam mulai dari pigmen berwarna
putih sampai kuning tua. S. aureus untuk koloni yang berwarna kuning serta S.
albus untuk koloni yang berwarna putih (Todar, 2011). Pada media MSA
(Manitol Salt Agar) koloni S. aureus berwarna kuning karena terjadi fermentasi
manitol menjadi asam sehingga warna media yang semula berwarna merah
fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh
berpasangan maupun berkelompok, berdiameter sekitar 0,8-1,0 µm. Bakteri S.
aureus tumbuh dengan optimum pada suhu 37oC dengan waktu pembelahan 0,47
jam. Bakteri ini juga bisa terdapat pada saluran pernafasan atas. Bakteri ini jarang
menyebabkan penyakit pada manusia. Akan tetapi, bakteri ini bisa menjadi faktor
penyebab terjadinya suatu infeksi penyakit pada inang yang sedang dalam kondisi
kekebalan tubuh menurun.
Gambar mikroskopik bakteri S. aureus. terpapar pada Gambar 1 di bawah
ini.
Gambar 1. Bakteri S. aureus
(Sumber : http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/cdc/staph/photomicro2.html)
Streptococcus merupakan bakteri yang memiliki bentuk bulat dan termasuk
ke dalam bakteri positif Gram. Bakteri ini termasuk ke dalam filum Firmicutes
dan juga termasuk kelompok bakteri asam laktat. Bakteri ini tumbuh berantai atau
berpasangan. Oleh karena itu diberi nama streptos (yang berasal dari bahasa
Yunani: επ ο ), yang berarti mudah bengkok atau memutar, seperti sebuah
rantai. Streptococcus tidak memiliki enzim katalase sehingga tidak dapat
mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Streptococcus banyak yang bersifat anaerob
fakultatif. Bakteri katalase negatif tidak memiliki enzim katalase yang
menguraikan H2O2 sehingga H2O2 yang diberikan tidak dapat dipecah oleh bakteri
dan berakibat tidak menghasilkan oksigen.
Bakteri ini dapat menyebabkan radang tenggorokan. Streptococcus spesies
endokarditis, erisipelas, dan necrotizing fasciitis (karena memakan daging yang
tercemar bakteri Streptococcus). Namun demikian, banyak spesies Streptococcus
yang bersifat non-patogenik. Streptococcus juga merupakan bagian dari
mikroflora normal yang bersifat komensal dari mulut, kulit, usus, dan saluran
pernapasan atas manusia.
Gambar mikroskopik bakteri Streptococcus terpapar pada Gambar 2 di
bawah ini.
Gambar 2. Bakteri Streptococcus sp.
(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Streptococci.jpg)
Bacillus adalah bakteri positif Gram yang berbentuk batang. Bakteri ini
merupakan anggota dari divisi Firmicutes. Bacillus merupakan bakteri yang dapat
bersifat obligat aerob atau anaerob fakultatif. Bakteri ini menghasilkan enzim
katalase yang mengubah H2O2 menjadi oksigen dan air. Sel-sel bakteri
menghasilkan endospora oval yang berfungsi untuk bertahan hidup dalam kondisi
lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat tetap aktif untuk waktu yang lama.
Dinding sel Bacillus adalah struktur di luar sel yang membentuk penghalang
antara bakteri dan lingkungan, dan pada saat yang sama bertujuan untuk
mempertahankan bentuknya serta menahan tekanan yang dihasilkan oleh turgor
sel (Wikipedia, 2011). Dinding sel Bacillus terdiri dari peptidoglikan yang
mengandung asam meso-diaminopimelic (DAP) serta mengandung banyak asam
teichoic yang terikat pada residu asam muramic (Todar, 2011).
Gambar mikroskopik bakteri Bacillus terpapar pada Gambar 3 di bawah
Gambar 3. Bakteri Bacillus sp.
(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bacillus _subtilis_Gram.jpg)
Kayu Siwak
Penggunaan alat-alat kebersihan mulut telah dimulai semenjak
berabad-abad yang lalu. Manusia terdahulu menggunakan alat-alat kebersihan yang
beragam seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi. Beranekaragam
peralatan sederhana dipergunakan untuk membersihkan gigi dan mulut mereka
dari sisa-sisa makanan, mulai dari tusuk gigi, batang kayu, ranting pohon, kain,
bulu burung, tulang hewan hingga duri landak. Di antara peralatan tradisional
yang mereka gunakan dalam membersihkan mulut dan gigi adalah kayu siwak
atau chewing stick. Kayu siwak telah lama digunakan sebagai alat untuk
membersihkan mulut. Penggunaan kayu siwak sebagai alat untuk pembersih
mulut menjadi suatu perubahan dari tradisional ke modern dan siwak merupakan
alat pembersih mulut terbaik hingga saat ini. (El-Mostehy et al., 1998).
Penggunaan siwak adalah sebuah budaya pra Islam yang berkaitan dengan
kegiatan bangsa Arab dahulu untuk mendapatkan gigi yang putih dan mengkilat.
Penggunaan siwak juga untuk kegiatan yang bersifat ritual. Budaya ini kemudian
diterapkan oleh masyarakat selama kegiatan keimanan Nabi Muhammad. Orang
Babilonia sejak 7000 tahun yang lalu telah menggunakan siwak sebagai alat
pembersih mulut. Siwak juga digunakan di zaman kerajaan Yunani dan Romawi,
orang-orang Yahudi, Jepang, Mesir, dan masyarakat pada zaman kerajaan Islam.
Banyak nama untuk siwak, seperti misalnya di Timur Tengah disebut dengan
miswak, dan di Pakistan dan India disebut dengan datan atau miswak.
Penggunaan kayu kunyah(chewing stick) berasal dari tanaman yang berbeda-beda
pada setiap negeri. Sumber utama yang sering digunakan di Timur Tengah adalah
pohon Arak (Salvadora persica), dan Afrika Barat yang digunakan adalah pohon
limun (Citrus aurantifolia) dan pohon jeruk (Citrus sinesis). Akar tanaman Senna
(Cassiva vinea) digunakan oleh orang Amerika berkulit hitam, Laburnum Afrika
(Cassia sieberianba) digunakan di Sierre Leone serta Neem (Azadirachta indica)
digunakan secara meluas di benua India (Almas, 2002).
Meskipun siwak sebelumnya telah digunakan dalam berbagai macam
budaya di seluruh dunia, namun pengaruh penyebaran agama Islam dan
penerapannya untuk membersihkan gigi lah yang paling berpengaruh. Istilah
siwak sendiri pada kenyatannya telah umum dipakai selama masa kenabian Nabi
Muhammad SAW yang memulai misinya sekitar 543 M. Nabi Muhammad SAW
bersabda bahwa siwak adalah penerapan pembersihan gigi dan dicintai Allah.
Beliau menambahkan, “Bila kamu membersihkan mulutmu berarti kamu
menghormati Allah, dan saya diperintahkan Allah untuk bersiwak karena Allah
telah mewahyukan kepada saya.” Kepercayaan Nabi memandang kesehatan mulut
yang baik amatlah besar, sehingga beliau senantiasa menganjurkan pada salah
seorang isterinya untuk selalu menyiapkan siwak untuknya hingga akhir hayatnya
(Khoory, 1983).
Siwak terus digunakan hampir di seluruh bagian Timur Tengah, Pakistan,
Nepal, India, Afrika dan Malaysia, khususnya di daerah pedalaman. Sebagian
besar mereka menggunakannya karena faktor religi, budaya dan sosial. Umat
Islam di Timur Tengah dan sekitarnya menggunakan siwak minimal 5 kali sehari
disamping juga mereka menggunakan sikat gigi biasa. Erwin-Lewis menyatakan
bahwa pengguna siwak memiliki relatifitas yang rendah dijangkiti kerusakan dan
penyakit gigi meskipun mereka memakan bahan makanan yang kaya akan
karbohidrat. (Khoory, 1983).
Klasifikasi Tanaman Siwak (Salvadora persica)
Gambar 4. Tanaman Siwak
(Sumber : http://rifafreedom.wordpress.com/2008/09/15/pohon-siwak)
Taksonomi tanaman siwak (Salvadora persica) menurut Tjitrosoepomo
(1998) adalah sebagai berikut :
Divisio : Embryophyta
Sub Divisio : Spermatophyta
Class : Dicotyledons
Sub Class : Eudicotiledons
Ordo : Brassicales
Family : Salvadoraceae
Genus : Salvadora
Spesies : Salvadora persica
Morfologi dan Habitat Tanaman Siwak (Salvadora persica)
Siwak atau Miswak, merupakan bagian dari batang, akar atau ranting
tumbuhan Salvadora persica yang kebanyakan tumbuh di daerah Timur Tengah,
Asia dan Afrika. Siwak berbentuk batang yang diambil dari tanaman arak
(Salvadora persica) yang berdiameter mulai dari 0,1 cm sampai 5 cm. Pohon arak
adalah pohon yang kecil seperti belukar dengan batang yang bercabang-cabang,
berdiameter lebih dari satu kaki. Jika kulitnya dikelupas, kulitnya berwarna agak
keputihan dan memiliki banyak juntaian serat. Akarnya berwarna cokelat dan
bagian dalamnya berwarna putih. Aromanya seperti seledri dan rasanya agak
pedas (Al-Khateeb et al., 1991).
Gambar 5. Batang kayu Siwak
(Sumber : http://ndaruto.files.wordpress.com/2008/03/siwak1.jpg)
Manfaat dan Kandungan Aktif
Dahulu siwak banyak digunakan sebagai alat untuk membersihkan mulut.
Saat ini pun masih ada masyarakat yang menggunakan siwak sebagai alat untuk
membersihkan mulut. Siwak dapat digunakan untuk tujuan terapi. Penerapan
terapi dari siwak dapat berupa pasta gigi, obat kumur, dan larutan irigasi
endodontik.
Zat antimikrobial adalah zat yang mengganggu pertumbuhan dan
metabolisme mikroorganisme (Boyd dan Marr, 1980). Al-Lafi dan Ababneh
(1995) telah melakukan pengujian terhadap aktifitas antibakterial dari kayu siwak
untuk menghambat beberapa bakteri mulut yang bersifat aerob dan anaerob. Hasil
penelitian dari Gazi et al. (1987) menunjukkan bahwa ekstrak kasar kayu siwak
yang dijadikan cairan kumur dan dikaji sifat-sifat antiplaknya beserta efeknya
terhadap bakteri penyusun plak dapat menyebabkan penurunan drastis bakteri
yang berbentuk batang dan bersifat negatif Gram. Selanjutnya Almas (2002)
melakukan penelitian terhadap efektifitas ekstrak siwak 50% dibandingkan
dengan CHX (Chlorhexidine Gluconate) 0,2% pada dentin manusia secara SEM
(Scanning Electrony Microscopy) menunjukkan bahwa ekstrak siwak 50%
memiliki hasil yang sama dengan CHX 0,2% dalam perlindungan dentin. Akan
tetapi, ekstrak siwak 50% lebih dapat menghilangkan smear layer pada dentin
dibandingkan CHX 0,2%.
Penelitian tentang analisis kandungan batang kayu siwak kering
dilanjutkan dengan eter lalu diuji kandungannya melalui prosedur kimia ECP
(Exhaustive Chemical Procedure) menunjukkan bahwa siwak mengandung zat-zat
kimia, seperti trimetilamin, alkaloida yang diduga sebagai salvadorin, klorida,
sejumlah besar fluorida dan silika, sulfur, vitamin C, serta sejumlah kecil tannin,
saponin, flavanoida dan sterol (El-Mostehy et al., 1995). Ekstrak siwak juga
menunjukkan adanya sifat-sifat antimikrobial, terutama antibakterial yang sangat
efektif dalam membunuh dan menghambat beberapa pertumbuhan bakteri dan
antifungal (Al-Lafi dan Ababneh, 1995; Darout, 2000).
Darout (2000) melaporkan bahwa kandungan kimiawi ekstrak kayu siwak
sangat ampuh menghilangkan plak dan mengurangi virulensi bakteri
periodontopatogenik. Kandungan anionik alami dalam siwak dipercaya sebagai
antimikrobial yang efektif untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme.
Sebagai contoh, nitrat yang dapat mempengaruhi pengangkutan aktif porline pada
Eschericia coli serta terbukti ampuh dalam menghambat fosforilasi oksidatif dan
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2009 – April 2010.
Penggilingan kayu dilaksanakan di Laboratorium Kimia Kayu Departemen Hasil
Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Ekstraksi bubuk kayu siwak
dilaksanakan di Laboratorium Biokimia Departemen Biokimia Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Penelitian in
vitro dilaksanakan di Laboratorium Bagian Mikrobiologi Medik Departemen Ilmu
Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran
Hewan Institut Pertanian Bogor.
Bahan Penelitian
Media dan Reagen. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kaldu/agar Brain Heart Infusion (BHI B/A). Beberapa reagen digunakan untuk
pewarnaan Gram, diantaranya larutan kristal violet, larutan ioidin, dan larutan
safranin.
Bubuk Kayu Siwak. Kayu siwak diperoleh dari salah satu daerah di Arab
Saudi dan Libya. Kayu siwak diperoleh dengan cara membeli melalui perantara.
Kayu siwak yang diperoleh berbentuk potongan akar atau batang. Kayu siwak
yang diperoleh dipotong-potong menjadi bagian yang kecil dan dihancurkan untuk
mendapatkan bubuk kayu siwak seperti yang dilakukan oleh AbdElRahman et al.
(2002). Kayu siwak yang ada dibersihkan terlebih dahulu dan dipotong-potong
menjadi bagian yang kecil lalu di jemur atau di oven sehingga menjadi kering
sehingga memperoleh bubuk kayu siwak. Setelah itu, digiling agar menjadi serbuk
kayu siwak yang siap digunakan untuk proses ekstraksi. Ekstraksi kayu siwak
dilakukan dengan menggunakan etanol 96%. Proses ekstraksi dilakukan dengan
cara mencampurkan 50 g bubuk kayu siwak dengan 250 ml larutan pengekstrak
dalam keadaan sucihama di dalam botol kering berpenutup yang juga sucihama.
Botol disimpan selama sembilan hari pada suhu kamar (25-27 oC). Selama
penyimpanan botol digoyang-goyang menggunakan penggoyang (shaker) dengan
disimpan dalam botol terpisah pada suhu 4-6 oC. Volume masing-masing
ekstraksi dikurangi dengan cara penguapan pada suhu 35-38 oC dan pelarut yang
tertinggal dibiarkan menguap oleh pengeringan selama 2-4 hari pada suhu kamar
(25-27 oC). Hasil ekstrak akhir berupa larutan sebanyak 5-10 ml. Larutan terakhir
disimpan di tempat kering pada suhu 4 oC hingga digunakan saat pengujian.
Ketika digunakan untuk pengujian, masing-masing ekstrak kasar ditambah
0,5% Tween 80 untuk dijadikan dua larutan siap pakai dengan kandungan
masing-masing 300 mg/ml dan 200 mg/ml. Larutan yang digunakan untuk pengujian
adalah yang memiliki kandungan sebesar 300 mg/ml. Larutan-larutan ini
disentrifugasi 15800 g selama 20 menit pada suhu 10 oC. Supernatan
disucihamakan menggunakan kertas penyaring 0,2 µm. Masing-masing larutan
diencerkan dengan pola pengenceran serial. Sebanyak 1 ml larutan yang diuji
dimasukkan ke dalam 10 ml BHIB pada pengenceran pertama. Untuk
pengenceran kedua, diambil 1/2 ml untuk dimasukkan ke dalam 10 ml BHIB.
Demikian selanjutnya hingga terjadi sembilan kali pengenceran secara seri.
Larutan Kumur yang Diuji. Beberapa larutan kumur komersil diperoleh
dari tempat penjualan. Setelah dicatat secara rinci informasi yang tertera di atas
label, label dilepaskan dan larutan kumur tersebut diberi identitas baru. Larutan
kumur yang diperiksa diencerkan secara serial dari pengenceran 1:10, 1:20, 1:40
sampai 1:2560 (v/v) menggunakan media tumbuh yang digunakan. Antibiotika
streptomisin digunakan sebagai kontrol positif. Sedangkan media tumbuh yang
tidak diimbuhi larutan kumur dan ekstrak kayu siwak digunakan sebagai kontrol
negatif (placebo).
Mikroba yang Diuji. Bakteri uji diperoleh dari hasil kumur-kumur yang
dilakukan oleh lima orang sukarelawan yang berumur 22-23 tahun dengan
memakai larutan NaCl 0,9%. Pengambilan larutan hasil kumur dilakukan pada
pagi hari sebelum melakukan aktifitas gosok gigi. Hasil kumur dimasukkan ke
dalam plastik yang selanjutnya disimpan dalam kotak pendingin (coolbox).
Sebanyak satu öse dari setiap plastik yang berisi cairan kumur diambil dan
dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang terdapat larutan NaCl sucihama. Tabung
reaksi diputar dengan menggunakan pemutar mixer vortex dengan tujuan agar
reaksi diisolasi ke atas permukaan media Agar Darah (diimbuhi darah domba
5-10%) untuk bakteri. Masing-masing cairan kumur dari tabung reaksi tersebut
diisolasi pada media Agar Darah yang berbeda. Seluruh media diinkubasi pada
suhu 37 oC selama 24-27 jam. Identifikasi bakteri yang tumbuh dilakukan setelah
masa inkubasi dicapai.
Rancangan Penelitian
Rancangan pengujian untuk melihat efek antimikroba dari ekstrak kayu
siwak dan larutan kumur mengikuti Sutter et al. (1979), AbdElRahman et al.
(2002), Koselac et al. (2005), Pires et al. (2007), dan Al-Bayati dan Sulaiman
(2008) yang dimodifikasi. Larutan suspensi dibuat dengan cara memindahkan
sejumlah inokulum bakteri ke dalam media BHIB. Kekeruhan suspensi bakteri
disetarakan dengan kekeruhan larutan McFarland #1 yang baru dibuat.
Larutan ekstrak kayu siwak, larutan kumur komersil yang terdiri dari
betadine (disingkat BET) dan total care (disingkat TC), larutan yang digunakan
sebagai kontrol positif dan negatif diencerkan dengan cara menambahkan satu
milliliter larutan yang diperiksa ke dalam 10 ml kaldu BHI dan agar BHI yang
siap padat untuk media pertumbuhan bakteri. Penambahan ini membuat
pengenceran 1:10 (v/v). Demikian selanjutnya dilakukan sehingga didapatkan
campuran media tumbuh dan larutan yang diperiksa dengan pengenceran 1:20
sampai 1:2560 (v/v).
Sebanyak 10 µl larutan inokulum bakteri, dari masing-masing spesies yang
diperiksa, dipindahkan masing-masing ke dalam tabung reaksi dan cawan berisi
media tumbuh BHI untuk bakteri seperti yang sudah disiapkan di atas. Setelah
agar di cawan memadat, seluruh media yang telah diinokulasi bakteri diinkubasi
pada suhu 37 oC selama 24-72 jam sesuai dengan pertumbuhan mikroba yang
ditanam. Pengujian ini dilakukan secara duplo.
Setelah masa inkubasi dicapai, maka dilakukan penghitungan koloni
secara visual pada media agar padat. Sedangkan untuk melihat pertumbuhan di
media kaldu, dilakukan pengamatan dengan Spektrofotometer UV-VIS pada
panjang gelombang 630-650 nm. Penentuan kadar minimum penghambatan
kadar terendah dari larutan yang diperiksa yang tidak membolehkan tumbuh satu
koloni pun pada media agar padat, dan kekeruhan lebih rendah dari absorbans
0,05 pada panjang gelombang (650 nm) (Cai dan Wu, 1996). Hasil yang diperoleh
kemudian dibandingkan dengan obat baku antibakteri dan bahan baku utama
larutan kumur.
Analisis Statistika
Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis
sidik ragam (analisis of varian, ANOVA). Keragaman total dapat diuraikan
dengan analisis sidik ragam menjadi komponen-komponen yang mengukur
berbagai sumber keragaman. Diasumsikan bahwa contoh acak yang dipilih berasal
dari populasi yang normal dengan ragam yang sama, kecuali bila contoh yang
dipilih cukup besar, asumsi tentang distribusi normal tidak diperlukan lagi
(Wibisono, 2005). Pada pengujian dengan menggunakan analisis ini, akan mudah
diketahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak dari beberapa nilai
rata-rata contoh yang diselidiki, sehingga diperoleh suatu kesimpulan menerima
hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatifnya. Untuk uji lanjutan digunakan
uji Duncan. Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang
ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari
dua nilai tengah yang dibandingkan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan
diantara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bakteridari probandus berhasil diperoleh setelah air kumur-kumur mereka
dibiakkan ke atas media Agar Darah. Koloni-koloni mikroorganisme tersebut
kemudian ditanam pada media umum yaitu BHIA untuk memperbanyak bakteri.
Selanjutnya dilakukan penanaman kembali pada Agar Darah untuk melihat jenis
hemolisis yang terjadi. Koloni bakteri yang ada diwarnai dengan pewarnaan Gram
dan dari hasil pewarnaan ini diperoleh bahwa koloni-koloni yang didapat
merupakan koloni bakteri Positif Gram.
Selanjutnya dilakukan uji katalase menggunakan H2O2 3% untuk
mengetahui apakah bakteri-bakteri yang diperoleh menghasilkan enzim katalase
atau tidak. Enzim katalase yang menguraikan H2O2 sehingga H2O2 yang diberikan
dapat dipecah oleh bakteri dan menghasilkan oksigen. Bakteri yang memiliki
enzim katalase adalah S. aureus, sedangkan yang tidak memiliki diantaranya
Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, dan Clostridium. Bakteri katalase
positif dapat menghasilkan enzim katalase dan dapat mengubah H2O2 menjadi
oksigen.
Koloni bakteri yang tumbuh pada media BHIA dan memiliki sifat katalase
positif ditanam pada media Baird Parker Agar (BPA) yang mengandung lithium
chloride dan tellurite untuk menumbuhkan mikroba yang bersifat koagulase
positif. S. aureus mempunyai koloni spesifik berwarna hitam akibat endapan hasil
tellurite dan media disekitarnya menjadi jernih. Endapan tersebut berwarna hitam
dikarenakan Staphylococcus mereduksi tellurite menjadi telluride dan di sekitar
warna hitam dikelilingi oleh zona yang jernih (Biokar-diagnostics, 2010).
Bila bakteri sudah murni maka dapat dilakukan uji biokimia selanjutnya
untuk menentukan genus dan spesies dari masing-masing bakteri (Cowan, 1974).
Uji biokimia yang dilakukan antara lain uji fermentasi mannitol dan glukosa. Uji
ini ditujukan untuk menentukan bakteri yang mampu memfermentasikan manitol
maupun glukosa. Pada uji gula-gula hanya terjadi perubahan warna pada media
glukosa yang berubah menjadi warna kuning, artinya bakteri ini membentuk asam
uji yang telah dilakukan, koloni bakteri ditanam juga pada media MSA (Manitol
Salt Agar).
Dari seluruh rangkaian uji tersebut di atas, maka didapatkan hasil bahwa
bakteri yang diisolasi dari air kumur probandus adalah S. aureus, Bacillus sp, dan
Streptococcus sp. Bakteri-bakteri tersebut termasuk ke dalam kelompok bakteri
positif Gram. Bakteri positif Gram mempunyai membran plasma tunggal yang
dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Ada beberapa hal yang
menyebabkan bakteri-bakteri tersebut di atas ada pada hasil kumur-kumur.
Hal-hal tersebut antara lain bakteri tersebut merupakan mikroflora normal pada mulut
manusia seperti S. aureus. Bakteri S.aureus juga merupakan patogen yang umum
pada manusia. Hal lain yang menjadi penyebab keberadaan bakteri-bakteri
tersebut adalah masuknya makanan atau air minum yang kurang bersih ke dalam
rongga mulut. Di dalam makanan atau minuman yang kurang bersih tersebut bisa
terdapat bakteri-bakteri tersebut.
Gambar 6 Kurva regresi linier bakteri
Dari kurva regresi linier terlihat bahwa pada ketiga bakteri tersebut yakni
S. aureus, Bacillus, dan Streptococcus mengalami peningkatan jumlah bakteri
Hasil reaksi hambatan dari ekstrak kayu siwak dan larutan kumur komersil
terhadap suspense campuran ketiga bakteri tercantum dalam Tabel 1 dan Gambar
1 di bawah ini.
Tabel 1 Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap pertumbuhan campuran bakteri
Pengenceran (1/x) Larutan Uji (log)
Siwak BET TC
10 2,54425z 2,42199 b -0,72403 q
20 2,16201y 2,25135 c 0,44475 p
40 1,97088x 2,16603 d 1,02915 o
80 1,87532w 2,12337 e 1,32134 n
160 1,82754v 2,10204 f 1,46744 m
320 1,80364 u 2,09138 f 1,54049 l
640 1,79169 u 2,08605 f 1,57702 k
1280 1,78572 u 2,08338 f 1,59528 k
2560 1,78274 u 2,08205 f 1,60441 k
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.
Gambar 7 Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap pertumbuhan campuran bakteri
Efek antimikroba terlihat nyata pada pengenceran 1/160 untuk ekstrak
kayu siwak, pengenceran 1/80 untuk BET, dan pengenceran 1/320 untuk TC. Bila
membandingkan ketiga bahan yang diuji, efek antimikroba ketiga bahan tersebut
ketiga jenis bahan uji tersebut terlihat bahwa TC merupakan bahan uji yang paling
efektif.
Pengamatan selanjutnya dilakukan untuk efek antimikroba ekstrak kayu
siwak, larutan kumur komersil BET dan TC masing-masing terhadap bakteri S.
aureus, Bacillus dan Streptococcus. Hasil percobaan yang melihat pengaruh
ekstrak kayu siwak terhadap pertumbuhan bakteri terpapar pada Tabel 2 dan
Gambar 2 di bawah ini.
Tabel 2 Pengaruh ekstrak kayu Siwak terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.
Kandungan Ekstrak (mg/ml) Jenis bakteri (log kandungan bakteri)
S. aureus Bacillus Streptococcus
0,12 1,51432 yd 1,52914 wh 1,603528 wi
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.
1.4
Dari tabel maupun gambar terlihat bahwa ekstrak siwak tidak efektif untuk
ketiga bakteri. Dalam percobaan ini terlihat bahwa tidak ada efek antibakteri dari
ekstrak kayu siwak terhadap ketiga genus bakteri. Peningkatan nyata jumlah
bakteri terjadi pada kandungan siwak sebesar 3,75 (mg/ml) untuk bakteri S.
aureus dan Bacillus serta sebesar 7,50 (mg/ml) untuk bakteri Streptococcus.
Ketiga genus bakteri telah memperlihatkan reaksi pertumbuhan yang berbeda
nyata pada kadar larutan sebesar 15,00 (mg/ml).
Hasil percobaan ini sangat berlainan dengan hasil penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya. Menurut hasil penelitian Gazi et al. (1987) ekstrak kasar
batang kayu siwak pada pasta gigi yang dijadikan cairan kumur dan dikaji
sifat-sifat antiplaknya, memberikan efek terhadap komposisi bakteri yang menyusun
plak dan menyebabkan penurunan bakteri negatif Gram batang.
Menurut AbdElRahman et al. (2002), perbedaan waktu pengamatan serta
jenis bahan pengekstrak memberikan hasil yang berbeda pada bakteri yang
diamati. Pada penelitian yang dilakukan Gazi et al. (1987), bakteri yang
digunakan adalah bakteri negatif Gram. Sedang pada penelitian yang dilakukan
AbdElRahman et al. (2002), bakteri yang digunakan adalah S. mutans, A.
comitans, L. acidophilus, A. naeslundii, P. gingivalis, dan P. intermedia. Bakteri
yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan dua penelitian tersebut.
Hanya satu bakteri yang genusnya sama yaitu Streptococcus, tetapi spesiesnya
tidak ditegaskan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa ekstrak
siwak tidak memberikan efek antibakteri terhadap bakteri S. aureus, Bacillus, dan
Streptococcus. Pada penelitian yang dilakukan oleh AbdElRahman et al. (2002)
juga dilakukan perbedaan pengamatan waktu yakni 24, 48, dan 72 jam. Pada
waktu-waktu yang berbeda tersebut memberikan hasil pengamatan yang berbeda
juga.
Hasil percobaan yang melihat pengaruh larutan kumur BET terhadap
pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. terpapar pada
Tabel 3 Pengaruh BET terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.
Kandungan BET (x 10-6 ml)
Jenis bakteri (log kandungan bakteri)
S. aureus Bacillus Streptococcus
3,91 1,50093 lg 2,12956 na 1,798374 lh
7,81 1,50078 lg 2,12753 na 1,798602 lh
15,63 1,50047 lg 2,12346 na 1,799059 lh
31,25 1,49986 lg 2,11532 na 1,799973 lh
62,50 1,49864 g 2,09904 p 1,801801 r
125,00 1,49621 g 2,06649 u 1,805457 r
250,00 1,49133 f 2,00137 c 1,812769 b
500,00 1,48157 w 1,87115 z 1,827393 e
1000,00 1,46206 v 1,61070 x 1,856642 y
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.
Gambar 9 Pengaruh BET terhadap pertumbuhan Bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.
Larutan kumur memberikan efek antibiotik pada bakteri S. aureus dan
Bacillus. Jumlah bakteri menurun secara nyata pada kandungan BET sebesar
31,25x10-6 (ml) dengan tingkat kepercayaan 95%. Akan tetapi, hasil yang berbeda
terjadi pada bakteri Streptococcus. Larutan kumur BET tidak memberikan efek
antibiotik pada bakteri ini karena populasi bakteri ini meningkat dengan
Hasil percobaan yang melihat efek antibiotik larutan kumur TC terhadap
bakteri S. aureus, Bacillus sp. dan Streptococcus sp. terpapar pada Tabel 4 dan
Gambar 4 di bawah ini.
Tabel 4 Pengaruh TC terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.
Kandungan TC (x 10-4 mg/ml)
Jenis bakteri (log kandungan bakteri)
S. aureus Bacillus Streptococcus
6,0 1,41077 g 2,01485 c 1,746747 e
12,0 1,40340 g 2,00169 c 1,740689 e
23,0 1,38865 h 1,97537 c 1,728574 e
47,0 1,35916 h 1,92273 d 1,704343 b
94,0 1,30018 i 1,81746 f 1,655882 j
188,0 1,18222 t 1,60691 u 1,558959 v
375,0 0,94630 q 1,18581 r 1,365114 s
750,0 0,47446 n 0,34362 o 0,977424 p
1500,0 -0,46921 m -1,34078 k 0,202043 l
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.
Gambar 10 Pengaruh TC terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.
Larutankumur TC ternyata memiliki efek antibiotik yang baik. Larutan ini
dengan kadar bahan aktif sebesar 23,0x10-4 (mg/ml) untuk bakteri S. aureus dan
47,0x10-4 (mg/ml) untuk bakteri Bacillus dan Streptococcus. Ketiga genus bakteri
telah memperlihatkan reaksi pertumbuhan yang berbeda nyata pada kadar larutan
sebesar 188,0x10-4, 375,0x10-4, dan 750,0x10-4 (mg/ml). Dari Gambar terlihat
bahwa semakin tinggi kadar bahan maka jumlah bakteri semakin menurun.
El-Mostehy et al (1995) melaporkan bahwa tanaman siwak mengandung
zat-zat antibakterial. Efek ini dipercaya berhubungan dengan tingginya kandungan
natrium klorida dan kalium klorida, salvadourea dan salvadorine, saponin, tanin,
vitamin C, silika dan resin, juga cyanogenic glycoside dan benzylsothio-cyanate.
Kandungan kimiawi yang ada berfungsi untuk membersihkan, memutihkan dan
menyehatkan gigi dan gusi. Bahan-bahan ini sering diekstraksi untuk dijadikan
bahan penyusun pasta gigi. Trimetilamin dan vitamin C membantu penyembuhan
dan perbaikan jaringan gusi. Klorida bermanfaat untuk menghilangkan noda pada
gigi, sedangkan silika dapat bereaksi sebagai penggosok. Fluorida mencegah
terbentuknya karies dengan memperkuat lapisan email dan mengurangi suasana
asam yang dihasilkan oleh bakteri. Nitrat (NO3-) dilaporkan mempengaruhi
pengangkutan aktif porline pada E. coli, seperti juga pada aldosa dari E. coli dan
S. faecalis. Nitrat juga mempengaruhi pengangkutan aktif oksidasi fosforilasi dan
pengambilan oksigen oleh Pseudomonas aeruginosa dan S. aureus sehingga
proses penggunaan dalam metabolisme bakteri menjadi terhambat.
Penelitian tentang efek antimikroba ekstrak kayu siwak secara in vitro juga
telah dilakukan oleh Shibl et al. (1985), dengan menggunakan beberapa pelarut
ekstraksi, yaitu petroleum eter, kloroform, dan metanol terhadap bakteri negatif
Gram dan positif Gram serta cendawan. Hasil yang diperoleh menunjukkan semua
jenis ekstraksi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba tersebut. Hasil
yang berbeda dilaporkan oleh Al Bayati dan Sulaiman (2008), dengan
menggunakan pelarut ekstraksi air dan metanol yang menunjukkan adanya
penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri dengan efektifitas yang
bermacam-macam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak siwak tidak memberikan
daya hambat pada bakteri yang diuji. Hal ini berbeda dengan penelitian
dilakukan El Mostehy et al (1995), bahan pengekstraksi yang digunakan adalah
alkohol dan eter. Sedang pada penelitian yang dilakukan oleh Al Bayati dan
Sulaiman (2007), bahan pengekstraksi yang digunakan adalah air dan methanol.
Sedang pada penelitian yang dilakukan oleh AbdElRahman et al (2002), bahan
pengekstraksi etanol digunakan. Akan tetapi, bakteri yang diuji berbeda dengan
bakteri yang duji dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, bahan pengekstraksi
yang digunakan adalah ethanol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak
siwak tidak memberikan daya hambat pada bakteri yang diamati.
Obat kumur memiliki bahan aktif yang berfungsi sebagai zat antibakteri.
Obat kumur BET memiliki bahan aktif povidone iodine dan obat kumur TC
memiliki bahan aktif fluor. Secara umum, kerja dari bahan aktif adalah
berpenetrasi ke dalam sel dan mengganggu fungsi normal seluler secara luas,
termasuk menghambat biosintesis (pembuatan) makromolekul dan persipitasi
protein intraseluler dan asam nukleat (DNA atau RNA).
Fluor bekerja menginaktifkan enzim yang berperan dalam proses
pembentukan energi bagi bakteri. Fluor juga menghambat proses glikolisis dan
menghalangi pengangkutan glukosa ke dalam sel (Satari, 1990). Iodine berfungsi
untuk mempresipitasi protein. Iodine juga telah dikenal luas sebagai antibiotika
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekstrak
kayu siwak tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri yang diamati. Efek
antibakteri larutan kumur komersil BET dan TC masih lebih baik dibandingkan
dengan ekstrak kayu siwak dan TC memberikan efek antibakteri yang lebih baik
dibandingkan BET.
Saran
Untuk memperbaiki penelitian-penelitian sejenis agar dapat melengkapi
hasil yang sudah dicapai, maka disampaikan beberapa saran di antaranya :
1. Penambahan ragam waktu pengamatan terhadap bakteri yang diinkubasi
dengan tujuan untuk memaksimalkan aktifitas antibakteri.
2. Penelitian lanjutan dengan menggunakan metode pengekstraksi dan jenis
bakteri yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan
DAFTAR PUSTAKA
AbdElRahman, HF., Skaug, N., and Francis, GW. 2002. In vitro antimicrobial effects of crude miswak extracts on oral pathogens. Saudi Dental J., 14(1): 26-32.
Al-Bayati, FA. and Al-Mola, HF. 2008. Antibacterial and antifungal activities of different parts of Tribulus terrestris L. growing in Iraq. J. Zhejiang Univ. Sci. B., 9(2):154-159.
Al-Bayati, FA. and Sulaiman, KD. 2008. In vitro Antimicrobial Activity of Salvadora persica L. Extracts Against Some Isolated Oral Pathogens in Iraq. Turk. J. Biol., 32: 57-62.
Al-Bayati, FA. 2009. Isolation and identification of antimicrobial compound from Mentha longifolia L. leaves grown wild in Iraq. Annals Clin. Microbiol. Antimicrobials, 8:20-25.
Al-Khateeb TL, OMullane DM, Whelton H and Sulaiman Ml. 1991.Periodontal treatment needs among Saudi Arabian adults and their relationship to the use of the Miswak. Comm. Dent. Health 8:323-28
Al-Lafi T. and Ababneh H., 1995, The effect of the extract of the miswak (chewing sticks) used in Jordan and the Middle East on oral bacteria. Int. Dent. J., 45(3):218-22
Almas K. 2002. The Effect of Salvadora Persica Extract (Miswak) and Chlorhexidine Gluconate on Human Dentin: A SEM Study. J. Contemp. Dent. Pract., 3(3): 027-035.
Almas, K. and Al-Zeid, Z. 2004. The Immediate Antimicrobial Effect of a Toothbrush and Miswak on Cariogenic Bacteria: A Clinical Study. J Contemp Dent Pract., (5)1:000-000.
Anonim, 2010. Pohon Siwak.
http://rifafreedom.wordpress.com/2008/09/15/pohon-siwak. [30 November
2010]
Anonim, 2010. SIWAK : Keajaiban dalam Sunnah Nabi. http://ndaruto.files.wordpress.com/2008/03/siwak1.jpg. [30 November 2010]
Biokar-Diagnostics. 2010. BAIRD-PARKER AGAR with Egg Yolk Tellurite.
Boyd, RF. and Marr, JJ. 1980. Medical Microbiology. Little, Brown and Co., Boston.
Cai, L., and Wu, CD. 1996. Compounds from Syzygium aromaticum possessing growth inhibitory activity against oral pathogens. J. Nat. Prod., 59(10): 987-990.
Cowan, S.T. 1974. Manual for the Identification of Medical Bacteria. Great Britain : Cambridge University Press
Darout, IA. 2000. Antimicrobial Anionic Components In Miswak Extract, Journal Pharmacology, Department of Odontology, Faculty of Dentistry, University of Bergen, Bergen, Norway
Demir, H., Açık, L., Bali, EB., Koç, LY. and Kaynak, G. 2009. Antioxidant and antimicrobial activities of Solidago virgaurea extracts. African J. Biotech., 8(2): 274-279.
El-Mostehy, DR. M. Ragaii, A.A. Al-Jassem, I.A. Al-Yassin, A.R. El-Gindy, E. Shoukry, 1998, Siwak-As An Oral Health Device (Preliminary Chemical And Clinical Evaluation), Journal Pharmacology, Department of Odontology, Faculty of Dentistry, University of Kuwait, Kuwait
Gazi, M.I., A.Lambourne, A.H. Chagla, 1987, The Antiplaque effect of Toothpaste containing Salvadora persica compared Chlorhexidine Gluconate: A Pilot Study, Medline Journal, Clinical Prentive Dentsitry, Lippincott co., Philadelphia.
Ghalem, BR. and Mohamed, B. 2008. Antibacterial activity of leaf essential oils of Eucalyptus globulus and Eucalyptus camaldulensis, African J. Pharmacy and Pharmacology, 2(10): 211-215.
Ghosh, A., Das, BK., Chatterjee, SK. and Chandra, G. 2008. Antibacterial potentiality and phytochemical analysis of mature leaves of Polyalthia longifolia (Magnoliales: Annonaceae). South Pacific J. Natural Sci., 26: 68-72.
Khoory, T. 1983. The Use of Chewing Sticks in Preventive Oral Hygiene, Journal of Clinical Preventive Dentistry, 5:11-14.
Koselac, I., Pepeljnjak, S., and Kustrak, D. 2005. Antifungal Activity of Fluid Extract and Essensial Oil from Anise Fruit (Pimpinella anisum L., Apiaceae). Acta Pharm., 55: 377-385.
Lestari H. 2003. Sifat Anti Rayap Zat Ekstraktif Kayu Pilang (Acacia leucophloea Wild.). [Skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB. [Tidak diterbitkan]
McBain, AJ., Bartolo, RG., Catrenich, CE., Charbonneau, D., Ledder, RG., and Gilbert, P. 2003. Effects of a Chlorhexidine Gluconate-Containing Mouthwash on the Vitality and Antimicrobial Susceptibility of In vitro Oral Bacterial Ecosystems. App. Environ Microbiol., 69(8): 4770–4776.
Pires, JR., Junior, CR. Pizzolitto, AC. 2007. In vitro antimicrobial efficiency of a mouthwash containing triclosan/gantrez and sodium bicarbonate. Braz. Oral Res. 21(4): 342-347.
Pratama, MR. 2005. Pengaruh Ekstrak Serbuk Kayu Siwak (Salvadora persica) Terhadap Bakteri S. mutans dan S. aureus dengan Metode Difusi Agar [Skripsi]. Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Surabaya. Surabaya.
Satari, HM. 1990. Pengaruh larutan Natrium Florida terhadap Streptococcus mutans dalam upaya pencegahan karies [Tesis]. Bandung: Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjajaran.
Shibl Y, Hammouda A, Molokhia A, Al-Shora H. 1985. Antibacterial and anticendawan activities of various extracts of Salvadora persica [abstrak]. Di dalam : Third Saudi Dental Meeting.
Supardi, I. dan Sukamto. 1999. Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan. Penerbit Alumni: Bandung.
Supriyadi, A. 2009. Sifat Antibakteri Zat Ekstraktif Kayu Siwak (Salvadora persica Wall.) terhadap Bakteri Streptococcus sp. [Skripsi]. Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
Sutter, VL., Barry, AL., Wilkins, TD., and ZABRANSKY, RJ. 1979. Collaborative Evaluation of a Proposed Reference Dilution Method of Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 16(4): 495-502.
Syarif, F. 2005. Sifat Anti-Jamur Zat Ekstraktif Kayu Pilang (Acacia leucophloea Willd.). [Skripsi]. Bogor: Departemen Hasil Hutan, Institut Pertanian Bogor
Tjitrosoepomo, G, 1998, Taksonomi Tumbuhan 2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Todar, K. 2011. Staphylococcus aureus and Staphylococcal Disease.
Todar, K. 2011. The Genus Bacillus.
http://www.textbookofbacteriology.net/Bacillus_2.html. [4 Februari 2011]
Waluyo, L. 2004. Mikrobiologi Umum. Universitas Muhamadiyah Malang: Malang
Wibisono, Y. 2005. Metode Statistika. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Wikipedia. 2011. Bacillus. http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus. [17 Januari 2011]
Yusro, F. 2009. Efektifitas Zat Ekstraktif Kayu Pelanjau (Pentaspadon motleyi,
Hook.f) Dalam Menghambat Pertumbuhan Cendawan Trichophyton
IRAL PREPINIDA. Comparative Inhibition Activity of Extracts Siwak (Salvadora persica) With Mouthwash Commercial Against Oral Bacteria. Supervised by EKO S. PRIBADI and HUDA S. DARUSMAN.
The research aimed to find out antibiotic properties of siwak extraction
solution and compared it to commercial mouthwash solution. The siwak
extraction solution showed poor inhibition activity to isolated mouth bacteria than
BET and TC mouthwash solution, respectively. The TC mouthwash solution
showed more effective to inhibited the bacteria than BET mouthwash solution
and siwak extraction solution.
Keywords : Siwak, commercial mouthwash solution, antibiotic property, mouth
IRAL PREPINIDA. Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora
persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut. Dibimbing oleh EKO S. PRIBADI dan HUDA S. DARUSMAN.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol kayu siwak terhadap bakteri-bakteri mulut dan membandingkannya dengan daya hambat yang dimiliki larutan kumur komersil yang ada saat ini. Hasil akhir ekstraksi kayu siwak didapatkan larutan ekstraksi dengan kadar 200 dan 300 mg/ml. Dari penelitian ini, hasil ekstraksi dengan kandungan 300 mg/ml tidak memiliki daya hambat yang baik terhadap bakteri-bakteri mulut yang diisolasi. Daya hambat yang dimiliki oleh larutan kumur komersil BET dan TC masih lebih baik dibandingkan ekstrak kayu siwak. Larutan kumur TC memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kedua larutan lainnya.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemanfaatan bahan yang diperoleh dari daun, akar, dan kayu sebagai obat
sudah diketahui sejak lama oleh masyarakat dunia dan Indonesia. Kelompok
masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan telah terbiasa memanfaatkan
bahan kayu untuk mengobati penyakit-penyakit yang mereka derita (Yusro, 2009).
Masyarakat Muslim di Timur Tengah telah lama memanfaatkan kayu siwak untuk
perawatan gigi. Kelompok yang memanfaatkan kayu siwak mengeluarkan biaya
perawatan gigi yang lebih sedikit dibandingkan kelompok yang tidak
menggunakan kayu siwak (Al-Khateeb et al.,1991; Al-Lafi dan Ababneh, 1995).
Penelitian-penelitian yang mengkaji manfaat bahan kayu yang memiliki
sifat antimikroba telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Al-Bayati dan Al-Mola,
2008; Ghalem dan Mohamed, 2008; Ghosh et al., 2008; Al-Bayati, 2009; Demir
et al., 2009). Penelitian pemanfaatan bahan-bahan kayu pun sudah banyak
dilakukan di Indonesia (Lestari, 2003; Syarif, 2005; Yusro, 2009). Sifat
antimikroba yang dimiliki oleh kayu siwak juga telah banyak diteliti, baik secara
in vitro (Pratama, 2005; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008; Supriyadi 2009) maupun
secara klinis (Almas dan Al-Zeid, 2004). Kayu siwak memiliki sifat antibakteri
terhadap Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis,
Streptococcus pyogenes, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Actinomyces
naeslundii, Phorphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia dan Candida
albicans. Hanya bakteri Lactobacillus acidophilus dan Pseudomonas aeruginosa
saja yang memperlihatkan sifat tahan terhadap efek antibakteri kayu siwak
(AbdElRahman et al., 2002; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008).
Saat ini sudah banyak beredar larutan kumur sebagai salah satu hasil
buatan industri untuk merawat kesehatan gigi. Masyarakat memiliki kebebasan
yang luas untuk memilih larutan kumur yang disukai. Beberapa penelitian sudah
dilakukan untuk melihat efek antimikroba dari larutan kumur ini (McBain et al.,
2003; Pires et al., 2007). Penelitian yang mengamati efek kayu siwak dan bahan
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan
dalam penelitian merupakan pengembangan dari pertanyaan berikut :
5 apakah larutan kumur yang beredar di Indonesia selama ini sudah
memiliki efektifitas antibakteri yang optimal sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?
5 apakah bahan-bahan herbal, seperti kayu siwak, dapat memberikan
efektifitas yang sama dengan larutan kumur komersil yang beredar?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas larutan kumur
komersil yang beredar melalui pemeriksaan secara in vitro dan penilaian
efektifitas antimikroba yang dimiliki oleh larutan kumur; membandingkan
efektifitas antimikroba dari kayu siwak terhadap larutan kumur komersil yang ada
melalui penilaian efek antimikroba secara in vitro; memberikan gambaran ke
masyarakat mengenai mutu mikrobiologik dari larutan kumur komersil dan kayu
siwak yang dijual di Indonesia selama ini.
Hipotesis
Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah
Pertama
H0 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang sama dengan larutan
kumur komersil yang diperiksa
H1 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang berbeda dengan larutan
kumur komersil yang diperiksa
Kedua
H0 : tidak ada perbedaan efek antimikroba dari larutan kumur yang diperiksa
TINJAUAN PUSTAKA
Mikroba Mulut
Mikroba mulut adalah ragam mikroorganisme yang ada dan terdapat di
dalam mulut. Mikroba-mikroba yang terdapat di mulut tersebut bisa bermanfaat
ataupun bisa menimbulkan penyakit/masalah. Penyakit pada mulut berhubungan
erat dengan kebersihan mulut. Saat ini, banyak cara yang dilakukan orang untuk
menjaga kesehatan mulutnya. Salah satunya adalah dengan membersihkan gigi
dan mulut. Produk-produk komersil banyak terdapat di pasaran yang ditujukan
untuk membersihkan gigi dan mulut. Penyakit mulut yang disebabkan oleh
mikroba yang berkembangbiak di dalam mulut, antara lain plak dan karang gigi
(calculus), peradangan gusi (gingivitis), gigi berlubang (cariesdentis), peradangan
amandel dan tenggorokan, radang mulut (stomatitis), dan bau mulut (halitosis).
Mulut merupakan tempat yang ideal untuk tumbuh dan berkembangnya
mikroorganisme karena mulut memiliki kelembaban serta memiliki asupan
makanan yang teratur. Mikroba-mikroba yang terdapat di dalam mulut tersebut
antara lain Candida albicans, Streptococcus viridans, S. aureus, S. mutans,
Lactobacillus, Solobacterium moorei. S. mutans dan Lactobacillus merupakan
kuman yang kariogenik karena mampu dengan segera membentuk asam dari
karbohidrat yang difermentasi. S. mutans merupakan bakteri patogen pada mulut
karena menjadi penyebab utama terbentuknya plak, gingivitis, dan karies gigi
(Lee et al., 1992). Staphylococcus aureus merupakan bakteri penyebab intoksitasi
dan terjadinya berbagai macam infeksi (Supardi dan Sukamto, 1999). S. moorei
merupakan salah satu bakteri penyebab bau mulut.
S. aureus merupakan bakteri positif Gram. Bakteri Staphylococcus mudah
tumbuh pada berbagai media, bermetabolisme aktif dengan memfermentasi
karbohidrat dan menghasilkan pigmen yang beragam mulai dari pigmen berwarna
putih sampai kuning tua. S. aureus untuk koloni yang berwarna kuning serta S.
albus untuk koloni yang berwarna putih (Todar, 2011). Pada media MSA
(Manitol Salt Agar) koloni S. aureus berwarna kuning karena terjadi fermentasi
manitol menjadi asam sehingga warna media yang semula berwarna merah
fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh
berpasangan maupun berkelompok, berdiameter sekitar 0,8-1,0 µm. Bakteri S.
aureus tumbuh dengan optimum pada suhu 37oC dengan waktu pembelahan 0,47
jam. Bakteri ini juga bisa terdapat pada saluran pernafasan atas. Bakteri ini jarang
menyebabkan penyakit pada manusia. Akan tetapi, bakteri ini bisa menjadi faktor
penyebab terjadinya suatu infeksi penyakit pada inang yang sedang dalam kondisi
kekebalan tubuh menurun.
Gambar mikroskopik bakteri S. aureus. terpapar pada Gambar 1 di bawah
ini.
Gambar 1. Bakteri S. aureus
(Sumber : http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/cdc/staph/photomicro2.html)
Streptococcus merupakan bakteri yang memiliki bentuk bulat dan termasuk
ke dalam bakteri positif Gram. Bakteri ini termasuk ke dalam filum Firmicutes
dan juga termasuk kelompok bakteri asam laktat. Bakteri ini tumbuh berantai atau
berpasangan. Oleh karena itu diberi nama streptos (yang berasal dari bahasa
Yunani: επ ο ), yang berarti mudah bengkok atau memutar, seperti sebuah
rantai. Streptococcus tidak memiliki enzim katalase sehingga tidak dapat
mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Streptococcus banyak yang bersifat anaerob
fakultatif. Bakteri katalase negatif tidak memiliki enzim katalase yang
menguraikan H2O2 sehingga H2O2 yang diberikan tidak dapat dipecah oleh bakteri
dan berakibat tidak menghasilkan oksigen.
Bakteri ini dapat menyebabkan radang tenggorokan. Streptococcus spesies
endokarditis, erisipelas, dan necrotizing fasciitis (karena memakan daging yang
tercemar bakteri Streptococcus). Namun demikian, banyak spesies Streptococcus
yang bersifat non-patogenik. Streptococcus juga merupakan bagian dari
mikroflora normal yang bersifat komensal dari mulut, kulit, usus, dan saluran
pernapasan atas manusia.
Gambar mikroskopik bakteri Streptococcus terpapar pada Gambar 2 di
bawah ini.
Gambar 2. Bakteri Streptococcus sp.
(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Streptococci.jpg)
Bacillus adalah bakteri positif Gram yang berbentuk batang. Bakteri ini
merupakan anggota dari divisi Firmicutes. Bacillus merupakan bakteri yang dapat
bersifat obligat aerob atau anaerob fakultatif. Bakteri ini menghasilkan enzim
katalase yang mengubah H2O2 menjadi oksigen dan air. Sel-sel bakteri
menghasilkan endospora oval yang berfungsi untuk bertahan hidup dalam kondisi
lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat tetap aktif untuk waktu yang lama.
Dinding sel Bacillus adalah struktur di luar sel yang membentuk penghalang
antara bakteri dan lingkungan, dan pada saat yang sama bertujuan untuk
mempertahankan bentuknya serta menahan tekanan yang dihasilkan oleh turgor
sel (Wikipedia, 2011). Dinding sel Bacillus terdiri dari peptidoglikan yang
mengandung asam meso-diaminopimelic (DAP) serta mengandung banyak asam
teichoic yang terikat pada residu asam muramic (Todar, 2011).
Gambar mikroskopik bakteri Bacillus terpapar pada Gambar 3 di bawah
Gambar 3. Bakteri Bacillus sp.
(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bacillus _subtilis_Gram.jpg)
Kayu Siwak
Penggunaan alat-alat kebersihan mulut telah dimulai semenjak
berabad-abad yang lalu. Manusia terdahulu menggunakan alat-alat kebersihan yang
beragam seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi. Beranekaragam
peralatan sederhana dipergunakan untuk membersihkan gigi dan mulut mereka
dari sisa-sisa makanan, mulai dari tusuk gigi, batang kayu, ranting pohon, kain,
bulu burung, tulang hewan hingga duri landak. Di antara peralatan tradisional
yang mereka gunakan dalam membersihkan mulut dan gigi adalah kayu siwak
atau chewing stick. Kayu siwak telah lama digunakan sebagai alat untuk
membersihkan mulut. Penggunaan kayu siwak sebagai alat untuk pembersih
mulut menjadi suatu perubahan dari tradisional ke modern dan siwak merupakan
alat pembersih mulut terbaik hingga saat ini. (El-Mostehy et al., 1998).
Penggunaan siwak adalah sebuah budaya pra Islam yang berkaitan dengan
kegiatan bangsa Arab dahulu untuk mendapatkan gigi yang putih dan mengkilat.
Penggunaan siwak juga untuk kegiatan yang bersifat ritual. Budaya ini kemudian
diterapkan oleh masyarakat selama kegiatan keimanan Nabi Muhammad. Orang
Babilonia sejak 7000 tahun yang lalu telah menggunakan siwak sebagai alat
pembersih mulut. Siwak juga digunakan di zaman kerajaan Yunani dan Romawi,
orang-orang Yahudi, Jepang, Mesir, dan masyarakat pada zaman kerajaan Islam.
Banyak nama untuk siwak, seperti misalnya di Timur Tengah disebut dengan