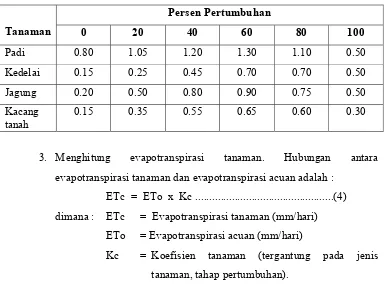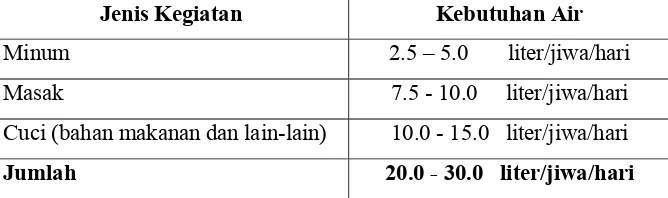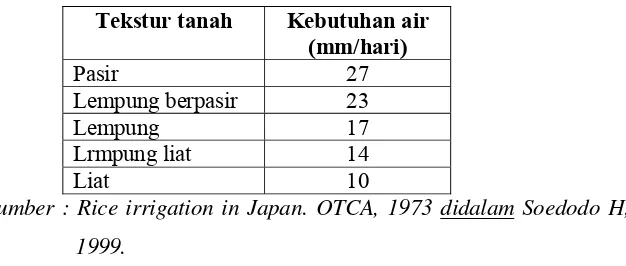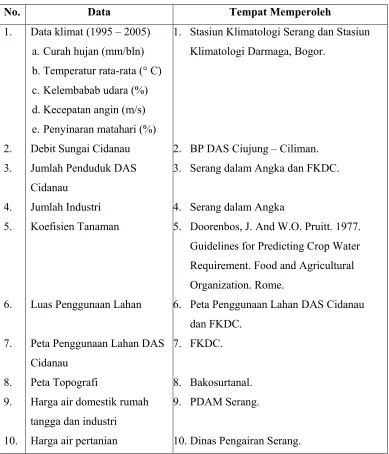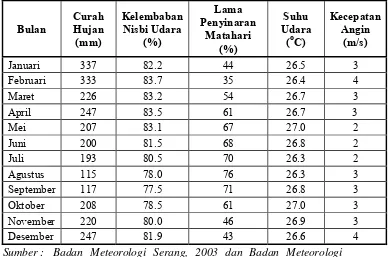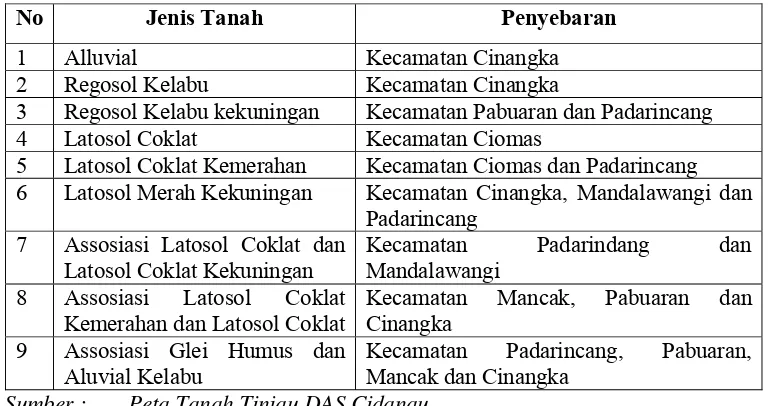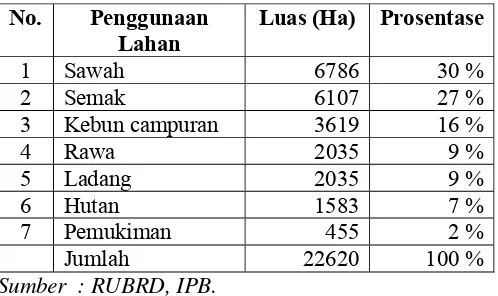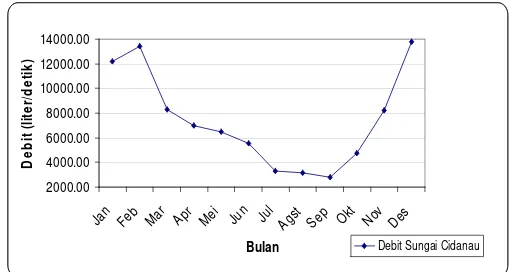OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU
DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.
OLEH : MIADAH F14102075
2006
DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Miadah. F14102075. Optimasi Pemanfaatan Air Baku dengan Menggunakan
Linear Programming (LP) di Daerah Aliran Sungai Cidanau, Banten. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. 2006.
RINGAKASAN
Air merupakan sumberdaya alam terbaharui, tetapi ketersediaannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhannya dalam artian lokasi, jumlah, waktu dan mutu. Jumlah kebutuhan akan air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri dan pertanian selalu meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan juga karena peningkatan taraf hidup akibat pembangunan. Sebaliknya, potensi ketersediaan air relatif tetap dan beragam menurut tempat dan waktu. Keadaan ini sering mengakibatkan timbulnya masalah karena tidak seimbangnya ketersediaan dan kebutuhan pada tempat dan waktu tertentu. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat akan air semakin meningkat adalah pengelolaan DAS dengan metode
linear programming/LP yang dapat mendistribusikan air secara optimum.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model matematik dalam mengoptimalkan sumberdaya air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Tujuan khusus penelitian ini adalah menentukan alokasi optimum sumberdaya air dengan menggunakan Linear Programming (LP) di DAS Cidanau, Banten untuk keperluan domestik, industri dan pertanian.
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : data jumlah penduduk DAS Cidanau, data jumlah industri, data iklim yang meliputi : curah hujan, kelembaban udara, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, dan suhu udara rata-rata. Optimasi yang dilakukan meliputi dua tahap, tahap pertama adalah optimasi alokasi air DAS Cidanau. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah jumlah penduduk, jumlah industri dan debit sungai Cidanau. Hasil optimasi yang diharapkan berupa luas lahan optimum yang dapat diairi oleh sungai Cidanau setelah debit airnya dikurangi kebutuhan untuk domestik dan industri. Industri yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah industri kecil dengan kebutuhan air 0.58 l/det (Purwanto, 1995). Debit yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah debit sungai Cidanau setelah dikurangi dengan kebutuhan air untuk PT. KTI sebesar 1500 l/det. PT. KTI menjadi prioritas utama karena perusahaan ini mengambil air baku dari sungai Cidanau untuk bahan bakunya dan ikut membayar jasa lingkungan. Kebutuhan untuk domestik dalam penelitian ini adalah 0.0003 l/det, dan kebutuhan pertanian rata-rata adalah 0.26 l/det.
Bila ditambah dengan debit untuk PT. KTI maka total debit industri sebesar 1527 l/det, dan debit optimum pertanian dengan luas lahan 4689.29 ha adalah 1219 l/det. Debit untuk domestik dan industri merupakan debit optimum yang dapat dimanfaatkan secara langsung, sedangkan debit untuk pertanian harus disesuaikan dengan pola tanam yang diterapkan walaupun luas lahan merupakan luas optimum hasil optimasi.
Tahap kedua adalah optimasi luas areal sesuai dengan pola tanam. Alternatif pola tanam yang disarankan adalah pola tanam dengan tiga kali tanam dalam setahun dan dua kali tanam dengan bera. Permulaan musim tanam diusahakan pada waktu musim hujan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah kebutuhan air tanaman dan debit optimum yang dihasilkan dari optimasi sebelumnya sebagai faktor pembatas dan luas lahan hasil optimasi sebelumnya.
Hasil optimasi diperoleh tiga alternatif pola tanam yang sesuai di DAS Cidanau dan luas arealnya sebagai berikut : Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan Oktober dengan luas 1562.82 ha, Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan November seluas 683.73 ha, dan Pi – Pi – Be yang ditanam pada bulan Desember seluas 848.34 ha. Total luas yang dihasilkan 3094.89 ha. Luas areal optimum relatif kecil jika dibandingkan luas areal yang ada (hasil optimasi sebelumnya), hal ini disebabkan oleh sedikitnya debit air pada musim kemarau, sehingga menjadikan pembatas yang berpengaruh dalam optimasi ini. Dari luas pola tanam optimum yang terpilih dapat dihitung kebutuhan air secara keseluruhan, sehingga akan terlihat bahwa debit air yang tersedia akan lebih banyak dari debit air yang dibutuhkan. Debit untuk luas lahan 3094.89 ha adalah sebesar 805 liter/detik, sedangkan debit yang tersedia sesuai dengan optimasi pertama untuk luas lahan 4689. 29 ha adalah sebesar 1219 liter/detik. Berdasarkan grafik keseimbangan air irigasi terdapat sebagian kurva ketersediaan air dibawah kurva kebutuhan air. Untuk menanggulangi hal ini, air irigasi tidak dapat dialirkan secara terus menerus, sehingga diperlukan sistem giliran untuk dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Pelaksanaan pola tanam diperlukan ketepatan pembagian air irigasi dan waktu tanamnya, agar air irigasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pada musim kemarau diperlukan tambahan suplai air untuk memenuhi kebutuhan baik domestik, industri dan pertanian. Salah satu alternatif adalah memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur bor, khususnya untuk kebutuhan air pertanian.
Kata kunci : Optimasi, DAS.
DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU
DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN
Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor
Oleh : MIADAH F14102075
2006
DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIANOPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU
DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN
Oleh : MIADAH F14102075
Dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1983 Di Temanggung, Jawa Tengah Tanggal lulus : 7 Agustus 2006
Menyetujui Bogor, Agustus 2006
Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Pembimbing Akademik
Mengetahui
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober
1983 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan orang tua
dengan nama ayah H. Ichsan (Alm) dan ibu bernama Sutarti.
Pada tahun 1996, penulis menyelesaikan pendidikannya di MI
Muhammaddiyah Bejen, Temanggung. Kemudiaan melanjutkan pendidikan di
SLTP Negeri 2 Candiroto, Temanggung dan lulus tahun 1999. Tahun 1999
penulis melanjutkan ke SMU Negeri 1 Parakan, Temanggung dan lulus pada
tahun 2002.
Pada tahun 2002, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian
Bogor melalui program USMI (Ujian Seleksi Masuk IPB) pada Departemen
Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan menyelesaikan studi
sarjananya pada tahun 2006.
Selama menjadi mahasiswa penulis aktif menjadi Pengurus Himateta
periodde 2004-2005. Penulis melakukan kegiatan Praktek Lapangan di Balai
Pengelolaan Sumberdaya Air Serang Lusi Juana, Kudus-Jawa Tengah dengan
topik “ Mempelajari Pengelolaan Sumberdaya Air di Waduk Gembong Pati, Jawa
Tengah” Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Institut Pertanian Bogor
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas dan laporan skripsi ini dengan baik.
Laporan ini ditulis berdasarkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di
Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, Banten. Mulai Februari sampai dengan
Maret 2006.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada
penulis selama ini.
2. Ir. Mohamad Solahudin, M.Si. dan Dr. Ir Sukandi Sukartaatmadja, MS. selaku
dosen penguji atas segala masukannya untuk kelengkapan skripsi.
3. Ibu dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan secara
moril dalam penyusunan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan selama penelitian Ai, Dudung dan Lucky, terima
kasih atas kerjasamanya selama ini.
5. Teman-teman senasib seperjuangan Teknik Sipil ’39 dan Teknik Pertanian
’39, terima kasih atas bantuan dan semangatnya selama penulis melaksanakan
studi, penelitian dan penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah
membantu terlaksananya penelitian hingga tersusunnya laporan ini.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan sebagai bahan perbaikan
laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi
maupun semua pihak yang memerlukannya.
Bogor, Agustus 2006
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... v
DAFTAR LAMPIRAN... vi
I. PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Tujuan ... 2
II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3
A. Siklus Hidrologi ... 3
1. Curah Hujan ... 4
2. Evapotranspirasi ... 7
3. Limpasan ... 8
B. Daerah Aliran Sungai ... 13
1. Pengertian DAS ... 13
2. Komponen Fisik DAS ... 15
C. Kebutuhan Sumberdaya Air ... 18
1. Kebutuhan Air Penduduk... 19
2. Kebutuhan Air Industri... 19
3. Kebutuhan Air Pertanian ... ... 20
D. Ketersediaan Sumberdaya Air ... 24
E. Linear Programming ... 25
1. Bentuk Umum Model Linear Programming (LP) ... 26
2. Asumsi Model Linear Programming (LP) ... 27
3. Penyelesaian Grafik Model LP ... 28
4. Penyelesaian LP dengan Metode Simplek ... 28
III. METODE PENELITIAN ... 29
B. Bahan dan Alat... 29
C. Metode Penelitian ... 29
1. Kebutuhan Air Penduduk... ... 30
2. Kebutuhan Air Industri... 31
3. Kebutuhan Air Pertanian... 31
4. Analisis Sistem dan Teknik Optimasi ... 33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 40
A. Keadaan Umum Daerah ... 40
1. Lokasi Penelitian ... 40
2. Kondisi Hodrologi ... 41
3. Tanah ... 43
4. Topografi dan Bentuk Wilayah ... 45
5. Penggunaan Lahan ... 46
6. Kependudukan ... 47
7. Industri ... 47
8. Pertaniain ... 48
B. Ketersediaan Air DAS Cidanau ... 49
1. Debit DAS Cidanau ... 50
2. Manfaat Debit Cidanau ... 51
C. Satuan Kebutuhan Air ... 52
1. Penduduk ... 52
2. Industri ... 53
3. Pertanian ... 53
D. Alokasi Debit Cidanau ... 58
1. Optimasi Kebutuhan Air ... 58
2. Optimasi Pola Tanam ... 61
V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 65
A. Kesimpulan ... 65
B. Saran ... 66
DAFTAR PUSTAKA ... 67
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Nilai koefisien tanaman sesuai dengan fase pertumbuhan
tanaman menurut Hargreaves ... 8
Tabel 2. Kebutuhan air rumah tangga ... 19
Tabel 3. Kebutuhan air pengolahan tanah pada berbagai tekstur tanah... 23
Tabel 4. Laju perkolasi sesuai dengan tekstur tanah ... 32
Tabel 5. Satuan data penelitian ... 39
Tabel 6. Data iklim Stasiun Klimatologi Serang ... 43
Tabel 7. Jenis tanah dan penyebarannya di DAS Cidanau ... 44
Tabel 8. Kelas kelerengan DAS Cidanau ... 45
Tabel 9. Penggunaan lahan DAS Cidanau ... 46
Tabel 10. Evapotranspirasi potensial bulanan DAS Cidanau ... 55
Tabel 11. Nilai koefisien tanaman (Kc) padi untuk berbagai tahap pertumbuhan... 55
Tabel 12. Curah hujan efektif ... 56
Tabel 13. Debit irigasi yang tersedia ... 57
Tabel 14. Debit rata-rata bulanan DAS Cidanau ... 59
OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU
DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.
OLEH : MIADAH F14102075
2006
DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Miadah. F14102075. Optimasi Pemanfaatan Air Baku dengan Menggunakan
Linear Programming (LP) di Daerah Aliran Sungai Cidanau, Banten. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. 2006.
RINGAKASAN
Air merupakan sumberdaya alam terbaharui, tetapi ketersediaannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhannya dalam artian lokasi, jumlah, waktu dan mutu. Jumlah kebutuhan akan air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri dan pertanian selalu meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan juga karena peningkatan taraf hidup akibat pembangunan. Sebaliknya, potensi ketersediaan air relatif tetap dan beragam menurut tempat dan waktu. Keadaan ini sering mengakibatkan timbulnya masalah karena tidak seimbangnya ketersediaan dan kebutuhan pada tempat dan waktu tertentu. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat akan air semakin meningkat adalah pengelolaan DAS dengan metode
linear programming/LP yang dapat mendistribusikan air secara optimum.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model matematik dalam mengoptimalkan sumberdaya air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Tujuan khusus penelitian ini adalah menentukan alokasi optimum sumberdaya air dengan menggunakan Linear Programming (LP) di DAS Cidanau, Banten untuk keperluan domestik, industri dan pertanian.
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : data jumlah penduduk DAS Cidanau, data jumlah industri, data iklim yang meliputi : curah hujan, kelembaban udara, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, dan suhu udara rata-rata. Optimasi yang dilakukan meliputi dua tahap, tahap pertama adalah optimasi alokasi air DAS Cidanau. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah jumlah penduduk, jumlah industri dan debit sungai Cidanau. Hasil optimasi yang diharapkan berupa luas lahan optimum yang dapat diairi oleh sungai Cidanau setelah debit airnya dikurangi kebutuhan untuk domestik dan industri. Industri yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah industri kecil dengan kebutuhan air 0.58 l/det (Purwanto, 1995). Debit yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah debit sungai Cidanau setelah dikurangi dengan kebutuhan air untuk PT. KTI sebesar 1500 l/det. PT. KTI menjadi prioritas utama karena perusahaan ini mengambil air baku dari sungai Cidanau untuk bahan bakunya dan ikut membayar jasa lingkungan. Kebutuhan untuk domestik dalam penelitian ini adalah 0.0003 l/det, dan kebutuhan pertanian rata-rata adalah 0.26 l/det.
Bila ditambah dengan debit untuk PT. KTI maka total debit industri sebesar 1527 l/det, dan debit optimum pertanian dengan luas lahan 4689.29 ha adalah 1219 l/det. Debit untuk domestik dan industri merupakan debit optimum yang dapat dimanfaatkan secara langsung, sedangkan debit untuk pertanian harus disesuaikan dengan pola tanam yang diterapkan walaupun luas lahan merupakan luas optimum hasil optimasi.
Tahap kedua adalah optimasi luas areal sesuai dengan pola tanam. Alternatif pola tanam yang disarankan adalah pola tanam dengan tiga kali tanam dalam setahun dan dua kali tanam dengan bera. Permulaan musim tanam diusahakan pada waktu musim hujan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah kebutuhan air tanaman dan debit optimum yang dihasilkan dari optimasi sebelumnya sebagai faktor pembatas dan luas lahan hasil optimasi sebelumnya.
Hasil optimasi diperoleh tiga alternatif pola tanam yang sesuai di DAS Cidanau dan luas arealnya sebagai berikut : Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan Oktober dengan luas 1562.82 ha, Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan November seluas 683.73 ha, dan Pi – Pi – Be yang ditanam pada bulan Desember seluas 848.34 ha. Total luas yang dihasilkan 3094.89 ha. Luas areal optimum relatif kecil jika dibandingkan luas areal yang ada (hasil optimasi sebelumnya), hal ini disebabkan oleh sedikitnya debit air pada musim kemarau, sehingga menjadikan pembatas yang berpengaruh dalam optimasi ini. Dari luas pola tanam optimum yang terpilih dapat dihitung kebutuhan air secara keseluruhan, sehingga akan terlihat bahwa debit air yang tersedia akan lebih banyak dari debit air yang dibutuhkan. Debit untuk luas lahan 3094.89 ha adalah sebesar 805 liter/detik, sedangkan debit yang tersedia sesuai dengan optimasi pertama untuk luas lahan 4689. 29 ha adalah sebesar 1219 liter/detik. Berdasarkan grafik keseimbangan air irigasi terdapat sebagian kurva ketersediaan air dibawah kurva kebutuhan air. Untuk menanggulangi hal ini, air irigasi tidak dapat dialirkan secara terus menerus, sehingga diperlukan sistem giliran untuk dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Pelaksanaan pola tanam diperlukan ketepatan pembagian air irigasi dan waktu tanamnya, agar air irigasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pada musim kemarau diperlukan tambahan suplai air untuk memenuhi kebutuhan baik domestik, industri dan pertanian. Salah satu alternatif adalah memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur bor, khususnya untuk kebutuhan air pertanian.
Kata kunci : Optimasi, DAS.
DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU
DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN
Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor
Oleh : MIADAH F14102075
2006
DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIANOPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU
DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN
Oleh : MIADAH F14102075
Dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1983 Di Temanggung, Jawa Tengah Tanggal lulus : 7 Agustus 2006
Menyetujui Bogor, Agustus 2006
Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Pembimbing Akademik
Mengetahui
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober
1983 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan orang tua
dengan nama ayah H. Ichsan (Alm) dan ibu bernama Sutarti.
Pada tahun 1996, penulis menyelesaikan pendidikannya di MI
Muhammaddiyah Bejen, Temanggung. Kemudiaan melanjutkan pendidikan di
SLTP Negeri 2 Candiroto, Temanggung dan lulus tahun 1999. Tahun 1999
penulis melanjutkan ke SMU Negeri 1 Parakan, Temanggung dan lulus pada
tahun 2002.
Pada tahun 2002, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian
Bogor melalui program USMI (Ujian Seleksi Masuk IPB) pada Departemen
Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan menyelesaikan studi
sarjananya pada tahun 2006.
Selama menjadi mahasiswa penulis aktif menjadi Pengurus Himateta
periodde 2004-2005. Penulis melakukan kegiatan Praktek Lapangan di Balai
Pengelolaan Sumberdaya Air Serang Lusi Juana, Kudus-Jawa Tengah dengan
topik “ Mempelajari Pengelolaan Sumberdaya Air di Waduk Gembong Pati, Jawa
Tengah” Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Institut Pertanian Bogor
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas dan laporan skripsi ini dengan baik.
Laporan ini ditulis berdasarkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di
Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, Banten. Mulai Februari sampai dengan
Maret 2006.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada
penulis selama ini.
2. Ir. Mohamad Solahudin, M.Si. dan Dr. Ir Sukandi Sukartaatmadja, MS. selaku
dosen penguji atas segala masukannya untuk kelengkapan skripsi.
3. Ibu dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan secara
moril dalam penyusunan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan selama penelitian Ai, Dudung dan Lucky, terima
kasih atas kerjasamanya selama ini.
5. Teman-teman senasib seperjuangan Teknik Sipil ’39 dan Teknik Pertanian
’39, terima kasih atas bantuan dan semangatnya selama penulis melaksanakan
studi, penelitian dan penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah
membantu terlaksananya penelitian hingga tersusunnya laporan ini.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan sebagai bahan perbaikan
laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi
maupun semua pihak yang memerlukannya.
Bogor, Agustus 2006
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... v
DAFTAR LAMPIRAN... vi
I. PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Tujuan ... 2
II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3
A. Siklus Hidrologi ... 3
1. Curah Hujan ... 4
2. Evapotranspirasi ... 7
3. Limpasan ... 8
B. Daerah Aliran Sungai ... 13
1. Pengertian DAS ... 13
2. Komponen Fisik DAS ... 15
C. Kebutuhan Sumberdaya Air ... 18
1. Kebutuhan Air Penduduk... 19
2. Kebutuhan Air Industri... 19
3. Kebutuhan Air Pertanian ... ... 20
D. Ketersediaan Sumberdaya Air ... 24
E. Linear Programming ... 25
1. Bentuk Umum Model Linear Programming (LP) ... 26
2. Asumsi Model Linear Programming (LP) ... 27
3. Penyelesaian Grafik Model LP ... 28
4. Penyelesaian LP dengan Metode Simplek ... 28
III. METODE PENELITIAN ... 29
B. Bahan dan Alat... 29
C. Metode Penelitian ... 29
1. Kebutuhan Air Penduduk... ... 30
2. Kebutuhan Air Industri... 31
3. Kebutuhan Air Pertanian... 31
4. Analisis Sistem dan Teknik Optimasi ... 33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 40
A. Keadaan Umum Daerah ... 40
1. Lokasi Penelitian ... 40
2. Kondisi Hodrologi ... 41
3. Tanah ... 43
4. Topografi dan Bentuk Wilayah ... 45
5. Penggunaan Lahan ... 46
6. Kependudukan ... 47
7. Industri ... 47
8. Pertaniain ... 48
B. Ketersediaan Air DAS Cidanau ... 49
1. Debit DAS Cidanau ... 50
2. Manfaat Debit Cidanau ... 51
C. Satuan Kebutuhan Air ... 52
1. Penduduk ... 52
2. Industri ... 53
3. Pertanian ... 53
D. Alokasi Debit Cidanau ... 58
1. Optimasi Kebutuhan Air ... 58
2. Optimasi Pola Tanam ... 61
V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 65
A. Kesimpulan ... 65
B. Saran ... 66
DAFTAR PUSTAKA ... 67
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Nilai koefisien tanaman sesuai dengan fase pertumbuhan
tanaman menurut Hargreaves ... 8
Tabel 2. Kebutuhan air rumah tangga ... 19
Tabel 3. Kebutuhan air pengolahan tanah pada berbagai tekstur tanah... 23
Tabel 4. Laju perkolasi sesuai dengan tekstur tanah ... 32
Tabel 5. Satuan data penelitian ... 39
Tabel 6. Data iklim Stasiun Klimatologi Serang ... 43
Tabel 7. Jenis tanah dan penyebarannya di DAS Cidanau ... 44
Tabel 8. Kelas kelerengan DAS Cidanau ... 45
Tabel 9. Penggunaan lahan DAS Cidanau ... 46
Tabel 10. Evapotranspirasi potensial bulanan DAS Cidanau ... 55
Tabel 11. Nilai koefisien tanaman (Kc) padi untuk berbagai tahap pertumbuhan... 55
Tabel 12. Curah hujan efektif ... 56
Tabel 13. Debit irigasi yang tersedia ... 57
Tabel 14. Debit rata-rata bulanan DAS Cidanau ... 59
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Sikllus hidrologi ... 3
Gambar 2. Diagram alir tahap penelitian ... 38
Gambar 3. Grafik ketersediaan air di DAS Cidanau ... 51
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Peta penggunaan lahan DAS CIdanau... 70
Lampiran 2. Peta penggunaan lahan DAS CIdanau dan hasil optimasi .... 71
Lampiran 3. Peta administrasi DAS CIdanau... 72
Lampiran 4. Temperature rata-rata daerah penelitian (° C) ... 73
Lampiran 5. Kelembaban udara rata-rata (%) ... 74
Lampiran 6. Kecepatan angin (m/s) ... 75
Lampiran 7. Lama penyinaran matahari (%) ... 74
Lampiran 8. Curah hujan rata-rata bulanan (mm/bulan) ... 77
Lampiran 9. Perhitungan ETo Penman-Monteith dengan menggunakan
Cropwat ... 78
Lampiran 10. Perhitungan curah hujan efektif dengan menggunakan
Cropwat ... 79
Lampiran 11. Debit rata-rata bulanan DAS Cidanau sepuluh tahun
terakhir ... 80
Lampiran 12. Kebutuhan air tanaman pada tiap pola tanam
(liter/detik/ha) ... 81
Lampiran 13. Kebutuhan air tanaman rata-rata bulanan untuk
masing-masing pola tanam (liter/detik/ha) ... 83
Lampiran 14. Debit Cidanau yang digunakan untuk optimasi (liter/detik)... 84
Lampiran 15. Jumlah penduduk yang memanfaatkan sungai Cidanau
secara langsung ... 85
Lampiran 16. Perhitungan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan
Cropwat ... 86
Lampiran 17. Optimasi penentuan luas lahan ... 103
Lampiran 18. Optimasi pola tanam ... 107
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Air merupakan sumberdaya alam yang sangat penting yang mutlak
diperlukan bagi kehidupan manusia dimuka bumi. Tingkat pemanfaatan
sumberdaya air dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik oleh manusia
maupun oleh makhluk hidup lain, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa
air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup.Tantangan dalam
penyediaan air adalah bagaimana mencapai ketersediaan air baik dari segi
kuantitas maupun kualitas. Keberadaan sumber air yang bersih dan sehat
merupakan salah satu permasalahan terbesar dewasa ini.
Air merupakan sumberdaya alam terbaharui, tetapi ketersediaannya tidak
selalu sejalan dengan kebutuhannya dalam artian lokasi, jumlah, waktu dan
mutu. Jumlah kebutuhan akan air untuk keperluan domestik (rumah tangga),
industri dan pertanian selalu meningkat dengan meningkatnya jumlah
penduduk dan juga karena peningkatan taraf hidup akibat pembangunan.
Sebaliknya, potensi ketersediaan air relatif tetap dan beragam menurut tempat
dan waktu. Keadaan ini sering mengakibatkan timbulnya masalah karena tidak
seimbangnya ketersediaan dan kebutuhan pada tempat dan waktu tertentu.
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu sistem ekologis atau
ekosistem, dimana didalamnya terjadi hubungan timbal balik antara makhluk
hidup, khususnya manusia dengan segala aktivitasnya dan dengan
lingkungannya yang lebih bersifat alami.
Di sekitar wilayah Sungai Cidanau, perkembangan industri dan
penduduk seperti wilayah Cilegon, Anyer, Merak, dan Bojonegara membawa
dampak semakin diperlukannya sarana dan prasarana untuk mendukung
perkembangannya. Kebutuhan air bersih menjadi hal yang mutlak diperlukan
sehingga secara langsung akan memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia
pada kawasan tersebut. Sungai Cidanau sebagai sumber terdekat menjadi
alternatif potensial untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih
Untuk Indonesia kebutuhan dasar air menurut Puslitbang Fisika
Terapan-LIPI, 1990 adalah sebagai berikut untuk minum 2.5 – 5.0
liter/jiwa/hari, masak 7.5 – 10.0 liter/jiwa/hari dan untuk mencuci (bahan
makanan dan lain-lain) 10.0 – 15.0 liter/jiwa/hari, sehingga total kebutuhan
sehari sekitar 20.0 – 30.0 liter/jiwa/hari. Untuk menentukan kebutuhan air
bersih industri, dapat dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan banyaknya
pemakaian masing-masing, untuk industri besar berkisar 151 – 350 m3/hari,
industri sedang berkisar 51 – 150 m3/hari, dan industri kecil berkisar 5 – 50
m3/hari (Purwanto, 1995), dan untuk pertanian ditentukan berdasarkan
faktor-faktor penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkolasi, penggantian lapisan
air, curah hujan efektif serta efisiensi irigasi (Departemen PU, KP-01, 1986).
Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air
yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat akan air semakin meningkat
adalah pengelolaan DAS dengan metode linear programming/LP yang dapat mendistribusikan air secara optimum. Penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh optimasi pendistribusian sumberdaya air pada DAS Cidanau
sehingga kebutuhan akan air dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.
B. TUJUAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model matematik
dalam mengoptimalkan sumberdaya air untuk keperluan domestik, industri
dan pertanian agar diperoleh hasil yang optimum. Tujuan khusus penelitian ini
adalah menentukan alokasi optimum sumberdaya air dengan menggunakan
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. SIKLUS HIDROLOGI
Siklus hidrologi didefinisikan sebagai suksesi tahapan-tahapan yang
dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer (Seyhan, 1990).
Sumber tenaga dari siklus ini adalah matahari. Dalam daur hidrologi, energi
panas matahari dan faktor-faktor iklim lainnya menyebabkan terjadinya proses
evaporasi pada permukaan vegetasi dan tanah, di laut atau badan-badan air
lainnya.
Sumber : Sosrodarsono dan Takeda 2003.
Keterangan :
1. Awan dan uap air di udara
2. Hujan 3. Hujan es 4. Salju
5. Limpasan permukaan 6. Perkolasi
7. Alat ukur salju 8. Alat ukur hujan 9. Sumur pengamatan 10.Air tanah
11.Presipitasi
12.Salju yang mencair 13.Lain-lain
14.Intersepsi
15. Evaporasi hujan yang sedang jatuh
16. Evapotranspirasi 17. Transpirasi 18. Awan dan uap air 19. Evaporasi
20. Evaporasi dari tanah 21. Evaporasi dari
Gambar 1. Sikllus hidrologi.
Uap air sebagai hasil proses evaporasi akan terbawa oleh angin melintasi
daratan yang bergunung maupun datar, dan apabila keadaan atmosfer
memungkinkan, sebagian dari uap air tersebut akan terkondensasi dan turun
sebagai air hujan.
Hujan yang jatuh ke bumi menyebar dengan cara dan arah yang
berbeda-beda. Sebagian besar dari hujan untuk sementara tertahan pada tajuk tanaman
yang pada akhirnya dikembalikan lagi ke atmosfer oleh penguapan yang
merupakan intersepsi selama dan sesudah berlangsungnya hujan. Sebagian
lagi mengalir melalui permukaan dan tanah menuju sungai, sementara lainnya
menembus tanah (infiltrasi dan perkolasi) menjadi air tanah (ground water). Di bawah pengaruh gravitasi, baik aliran permukaan maupun air tanah
bergerak menuju tempat yang lebih rendah dan akhirnya mengalir ke laut.
Namun, selama pengaliran sebagian besar air permukaan dan bawah tanah
dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan (evaporasi) dan transpirasi sebelum
ke laut (Linsley, et al., 1990).
Komponen siklus hidrologi dalam DAS berdasarkan siklus diatas terdiri
dari hujan, evaporasi, intersepsi, transpirasi, infiltrasi, perkolasi, aliran
permukaan dan aliran bawah permukaan serta total aliran yang terjadi di
sungai (outlet).
1. Curah Hujan
Curah hujan adalah faktor utama yang mengendalikan daur hidrologi
disuatu DAS. Terbentuknya ekologi, geografi dan tataguna lahan disuatu
daerah sebagian besar ditentukan atau tergantung pada fungsi daur
hidrologi, dengan demikian curah hujan merupakan kendala sekaligus
kesempatan dalam usaha pengelolaan sumberdaya tanah dan air. Oleh
karenanya, para perencana pengelolaan DAS diharapkan memahami
bagaimana caranya melakukan analisis dan menentukan karakteristik
curah hujan, melakukan pengukuran dan perhitungan-perhitungan
besarnya curah hujan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah
a. Distribusi Curah Hujan
Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan
pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan
rata-rata diseluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada
suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah/daerah
dan dinyatakan dalam mm.
Curah hujan daerah harus diperkirakan dari beberapa titik
pengamatan curah hujan. Adapun cara-cara perhitungan curah hujan
daerah dibeberapa titik adalah sebagai berikut (Sosrodarsono dan
Takeda, 2003) :
1) Metode Rata-rata Aritmatik
Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, dan
cocok diterapkan bila jumlah stasiun banyak dan tersebar merata.
Metode ini memberikan bobot yang sama untuk tiap stasiun, yaitu
dengan menjumlahkan angka pengukuran di tiap stasiun dan
membaginya dengan jumlah stasiun penakar, seperti rumus
berikut :
P =
∑
n Pi
...(1)
Dimana : P = curah hujan daerah (mm)
Pi = curah hujan pada stasiun ke-i
n = jumlah stasiun penakar
2) Metode Poligon Thiessen
Metode ini merupakan metode yang didasarkan pada
pemberian bobot bagi tiap stasiun terhadap luas daerah yang
diwakili. Luas daerah tersebut ditentukan dengan menarik
garis-garis yang menghubungkan stasiun yang satu dengan yang lain,
sehingga terbentuk poligon yang merupakan perpotongan
garis-garis bagi tersebut, dimana di dalam setiap poligon tersebut
Perhitungan curah hujan dengan metode ini menggunakan
rumus sebagai berikut :
P =
( )
∑
∑
Ai Ai Pi
=
∑
Wi Ai...(2)Dimana : P = curah hujan daerah (mm)
Pi = curah hujan pada stasiun ke-i (mm)
Ai = luas poligon ke-i
n = jumlah stasiun
Penerapan metode ini memberikan hasil yang konsisten, tetapi
apabila letak stasiun berubah maka bobot stasiun juga ikut berubah.
3) Metode Isohyet
Metode ini merupakan metode penentu curah hujan daerah
dengan menggunakan peta isohyet, yaitu peta yang mempunyai
garis-garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai
curah hujan yang sama. Peta ini dibuat dengan memperhatikan efek
topografi dan asal datangnya hujan. Penentuan curah hujan daerah
dihitung dengan rumus sebagai berikut :
P =
(
)
∑
∑
− +Ai Ai Pi Pi1 /2
...(3)
Dimana : P = curah hujan daerah (mm)
Pi = curah hujan pada stasiun ke-i (mm)
Ai = luas poligon ke-i
n = jumlah stasiun
Penerapan metode ini biasanya untuk daerah yang luas dengan
jaringan stasiun yang tidak terlalu padat. Hasilnya bersifat
subyektif dan banyak ditentukan oleh ketelitian pembuat peta.
b. Frekuensi Curah Hujan
Cara perkiraan untuk mendapatkan frekuensi kejadian curah hujan
dengan intensitas tertentu yang digunakan dalam perhitungan
pengendalian banjir, rancangan drainase dan lain-lain adalah dengan
seperti cara yang digunakan di Amerika serikat, yakni cara
tahun-stasiun yang menjumlahkan banyaknya titik-titik pengamatan. Cara ini
memperkirakan frekuensi dengan menjumlahkan banyaknya tahun
pengamatan pada titik-titik pengamatan. Cara ini adalah cara yang
paling sederhana, tanpa penyelesaian secara statistik. Penerapan cara
ini dapat diadakan untuk daerah yang mempunyai kondisi meteorologi
yang sama, bukan seperti daerah pegunungan.
2. Evapotranspirasi
Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari
permukaan tanah, air dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer.
Dengan kata lain, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara
evaporasi (penguapan air dari permukaan tanah), intersepsi (penguapan
kembali air hujan dari permukaan tajuk vegetasi) dan transpirasi
(penguapan air tanah ke atmosfer melalui vegetasi). Beda antara intersepsi
dan transpirasi adalah bahwa pada proses intersepsi air yang diuapkan
kembali ke atmosfer tersebut adalah air hujan yang tertampung sementara
pada permukaan tajuk dan bagian lain dari suatu vegetasi sedangkan
transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari dalam tanah melalui
tajuk vegetasi sebagai hasil proses fisiologi vegetasi.
Unsur iklim yang mempengaruhi laju evaporasi adalah radiasi surya,
suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin. Pada permukaan air
yang tenang tidak bergelombang, laju penguapan akan tergantung pada
suhu dan tekanan uap air diatas permukaan air. Suhu air menentukan
tekanan uap air pada permukaan air, dan laju evaporasi sebanding dengan
perbedaan tekanan uap air antara permukaan air dan udara diatasnya.
Gabungan evaporasi dan transpirasi dengan persediaan air yang tidak
terbatas disebut evaporasi potensial (PE).
Menurut Doorenbos dan Pruitt (1977) untuk mengetahui
evapotranspirasi tanaman dapat diduga dari evapotranspirasi acuan yang
berasal dari data klimatologi setempat. Perhitungan evapotranspirasi
1. Menentukan evapotranspirasi acuan (ETo) dengan menggunakan
metode Blaney-Criddle, Radiasi, Penman atau Panci evaporasi.
2. Menentukan koefisien tanaman (Kc), dari hasil penelitian Hargreaves
dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Nilai koefisien tanaman sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman menurut Hargreaves (dalam Hariyanto, 1987)
Persen Pertumbuhan
Tanaman 0 20 40 60 80 100
Padi 0.80 1.05 1.20 1.30 1.10 0.50
Kedelai 0.15 0.25 0.45 0.70 0.70 0.50
Jagung 0.20 0.50 0.80 0.90 0.75 0.50
Kacang tanah
0.15 0.35 0.55 0.65 0.60 0.30
3. Menghitung evapotranspirasi tanaman. Hubungan antara
evapotranspirasi tanaman dan evapotranspirasi acuan adalah :
ETc = ETo x Kc ...(4)
dimana : ETc = Evapotranspirasi tanaman (mm/hari)
ETo = Evapotranspirasi acuan (mm/hari)
Kc = Koefisien tanaman (tergantung pada jenis
tanaman, tahap pertumbuhan).
3. Limpasan
Limpasan dapat diartikan sebagai bagian curah hujan yang membuat
aliran ke saluran-saluran, sungai, danau, atau laut sebagai aliran
permukaan (Schwab. et al, 1968). Menurut Arsyad (1983) Limpasan atau
run-off adalah bagian dari curah hujan yang mengalir keluar dari suatu daerah pengaliran diatas dan dibawah permukaan tanah. Air yang mengalir
dipermukaan tanah disebut limpasan permukaan sedangkan air yang
mengalir dibawah permukaan tanah disebut limpasan dalam.
Sosrodarsono dan Takeda (2003) menyatakan air limpasan
permukaan air tanah, yakni curah hujan yang dikurangi oleh infiltrasi, air
yang tertahan, dan besarnya genangan. Limpasan air permukaan ini
merupakan bagian yang penting dari puncak banjir.
1. Komponen-komponen limpasan
Sumber-sumber air sungai adalah curah hujan atau salju yang
mencair. Menurut Sosorodarsono dan Takeda (2003), air untuk
mencapai sungai melalui tiga jalan sebagai berikut :
a. Curah hujan di saluran (Channel Precipitation), yaitu curah hujan yang jatuh langsung pada permukaan air di sungai utama dan
anak-anak sungainya yang umumnya termasuk dalam limpasan air
permukaan dan tidak dipisahkan sebagai komponen dari hidrograf.
Curah hujan yang langsung jatuh ke sungai merupakan bagian
yang sangat kecil dari curah hujan itu sendiri.
b. Limpasan permukaan, yaitu air yang mencapai sungai tanpa
mencapai permukaan air tanah. Limpasan permukaan merupakan
curah hujan yang dikurangi oleh besarnya infiltrasi, besarnya air
yang tertahan dan besarnya genangan.
c. Aliran air tanah, yaitu air yang terinfiltrasi kedalam tanah, air ini
akan mencapai permukaan air tanah dan bergerak menuju sungai
dalam beberapa hari, beberapa minggu atau lebih. Aliran ini
disebut juga debit aliran dasar yang hanya berubah sedikit selama
musim kering dan basah sepanjang tahun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan
Aliran sungai tergantung dari beberapa faktor secara bersamaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan dibagi ke dalam dua
kelompok, yaitu elemen-elemen meteorologi yang diwakili oleh curah
hujan dan elemen-elemen daerah pengaliran yang menyatakan
sifat-sifat fisik daerah pengaliran.
Faktor-faktor yang termasuk ke dalam kelompok
elemen-elemen meteorologi adalah sebagai berikut :
1) Jenis presipitasi
Pengaruh terhadap limpasan sangat berbeda, tergantung
pada jenis presipitasi (hujan atau salju). Jika hujan maka
pengaruhnya adalah langsung dan hidrografnya hanya
dipengaruhi oleh intensitas curah hujan dan besarnya curah
hujan.
2) Intensitas curah hujan
Pengaruh intensitas curah hujan pada limpasan permukaan
tergantung dari kapasitas infiltrasi. Jika intensitas curah hujan
melampaui kapasitas infiltrasi, maka besarnya limpasan
permukaan akan segera meningkat sesuai dengan peningkatan
intensitas curah hujan. Akan tetapi, besarnya peningkatan
limpasan itu tidak sebanding dengan peningkatan curah hujan
lebih, yang disebabkan oleh efek penggenangan dipermukaan
tanah.
3) Lama curah hujan
Setiap hujan yang terjadi akan mempunyai waktu terjadinya
hujan biasanya disebut lama hujan. Jika lama curah hujan
kurang dari lama curah hujan kritis, maka lama limpasan akan
sama dan tidak tergantung dari intensitas curah hujan. Jika
lama curah hujan lebih panjang, maka lama limpasan air
permukaan juga lebih panjang. Lama curah hujan dapat
menurunkan kapasitas infiltrasi, untuk curah hujan yang jangka
waktunya panjang, limpasan air permukaannya akan lebih
besar meskipun intensitasnya relatif rendah.
4) Distribusi curah hujan dalam daerah pengaliran
Curah hujan yang distribusi hujannya merata akan
menyebabkan debit puncak yang minimum. Banjir didaerah
lebat yang distribusinya merata dan karena curah hujan biasa
yang mencakup daerah yang luas meskipun intensitasnya kecil.
Sebaliknya di daerah pengaliran yang debit puncak maksimum
dapat terjadi oleh curah hujan lebat dengan daerah hujan yang
sempit.
Limpasan yang diakibatkan oleh curah hujan sangat
dipengaruhi oleh distribusi curah hujan, maka sebagai skala
penunjuk faktor ini digunakan koefisien distribusinya.
Distribusi koefisien adalah harga curah hujan maksimum dibagi
harga curah hujan rata-rata di daerah pengaliran, jadi curah
hujan yang yang jumlahnya tetap mempunyai debit puncak
yang lebih besar dan sesuai dengan koefisien distribusinya
yang bertambah besar.
5) Arah pergerakan curah hujan
Umumnya pusat curah hujan bergerak, suatu curah hujan
lebat bergerak sepanjang sistem aliran sungai akan sangat
mempengaruhi debit puncak dan lama limpasan air permukaan.
6) Curah hujan terdahulu dan kelembaban tanah
Jika kadar kelembaban lapisan tanah teratas tinggi, maka
mudah terjadi banjir karena kapasitas infiltrasi kecil. Hal
tersebut berlaku juga jika kelembaban tanah meningkat dan
mencapai kapasitas lapang, maka infiltrasi akan mencapai
permukaan air tanah dan memperbesar aliran air tanah. Selama
periode pengurangan kelembaban tanah oleh evapotranspirasi
dan lain-lain, curah hujan yang lebat tidak akan mengakibatkan
kenaikan permukaan air, karena air hujan yang terinfiltrasi
tertahan sebagai kelembaban tanah. Sebaliknya jika
kelembaban tanah sudah meningkat karena curah hujan
terdahulu, maka kadang-kadang curah hujan dengan intensitas
yang kecil dapat mengakibatkan kenaikan permukaan air yang
7) Kondisi-kondisi meteorologi yang lain
Berdasarkan elemen-elemen meteorologi diatas, curah
hujan mempunyai pengaruh yang besar pada limpasan. Secara
tidak langsung suhu, kecepatan angin, kelembaban relatif,
tekanan udara relatif, curah hujan tahunan dan seterusnya yang
masih berhubungan satu sama lain juga akan mempengaruhi
iklim didaerah tersebut dan akan mempengaruhi limpasan.
b. Elemen-elemen daerah pengaliran
1) Kondisi pengguna lahan (land use)
Hidrograf suatu sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi
penggunaan tanah dalam daerah pengaliran itu. Daerah hutan
yang ditutupi tumbuh-tumbuhan yang lebat sulit terjadi
limpasan permukaan karena kapasitas infiltrasinya yang besar.
Jika daerah hutan ini dijadikan daerah pembangunan dan
dikosongkan, maka kapasitas infiltrasi akan turun karena
pemampatan permukaan tanah. Air hujan akan mudah
berkumpul ke sungai-sungai dengan kecepatan yang tinggi
yang akibatnya akan terjadi banjir besar.
2) Daerah pengaliran
Jika semua faktor-faktor termasuk besarnya curah hujan,
intensitas curah hujan dan lain-lain itu tetap, maka limpasan
akan selalu sama, dan tidak tergantung dari luas daerah
pengaliran. Berdasarkan asumsi ini, mengingat aliran per
satuan tetap, maka hidrograf sebanding dengan luas daerah
pengaliran. Salah satu penyebab berkurangnya debit puncak
adalah hubungan antara intensitas curah hujan maksimum yang
berbanding terbalik dengan luas daerah hujan, dengan asumsi
curah hujan dianggap merata.
3) Kondisi topografi dalam daerah pengaliran
Corak, elevasi, gradien, arah, dan komponen lain dari
hidrologi daerah pengaliran yang bersangkutan. Corak daerah
pengaliran adalah faktor bentuk, yakni perbandingan panjang
sungai utama, terhadap lebar rata-rata daerah pengaliran. Jika
faktor bentuk menjadi lebih kecil dengan kondisi skala daerah
pengaliran yang sama, maka hujan lebat yang merata akan
berkurang dengan perbandingan yang sama sehingga sulit akan
terjadi banjir. Elevasi daerah pengaliran dan elevasi rata-rata
mempunyai hubungan yang penting terhadap suhu dan curah
hujan.
4) Jenis tanah
Struktur dan tekstur tanah merupakan faktor-faktor yang
menentukan kapasitas infiltrasi, maka karakteristik limpasan
sangat dipengaruhi oleh jenis tanah daerah pengaliran.
Bahan-bahan koloidal juga merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi kapasitas infiltrasi karena bahan-bahan ini
mengembang dan menyusut sesuai dengan variasi kadar
kelembaban tanah.
5) Faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi limpasan adalah
karakteristik jaringan sungai-sungai, adanya daerah pengaliran
yang tidak langsung, drainase buatan dan lain-lain. Untuk
mempelajari puncak banjir, debit air rendah, debit rata-rata dan
lain sebagainya diperlukan penyelidikan yang cukup dan
perkiraan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
B. DAERAH ALIRAN SUNGAI 1. Pengertian
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh
titik-titik tinggi dimana air hujan jatuh dan terkumpul kemudian mengalir
dalam suatu sistem sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) juga didefinisikan
sebagai suatu daerah yang dibatasi oleh topografi alami, dimana semua air
melalui suatu outlet pada sungai tersebut atau merupakan suatu hidrologi yang
menggambarkan dan menggunakan satuan fisik biologi dan satuan kegiatan
sosial ekonomi untuk pengelolaan sumberdaya alam.
Chow (1964) menyebutkan DAS merupakan tempat terjadinya
proses-proses yang berangkaian dan menjadi bagian dari siklus hidrologi. Proses
tersebut dapat ditinjau mulai dari terjadinya hujan, yang merupakan produk
langsung dari awan yang berbentuk air maupun salju. Hujan yang jatuh
sebagian tertahan di tajuk tanaman dan atap bangunan, kemudian jatuh ke
tanah (intersepsi), sebagian lainnya jatuh ke tanah. Saat air jatuh ke tanah
maka tejadi proses infiltrasi yaitu perjalanan air melalui permukaan tanah dan
menembus masuk kedalamnya.
Secara topografik, wilayah suatu DAS dibatasi oleh punggung-punggung
gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian
menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Dengan demikian, luas DAS
yang terbentuk secara alami akan sangat bervariasi antara DAS yang satu
dengan DAS yang lainnya, tergantung dari kondisi topografi wilayah tersebut.
Wilayah dengan topografi berbukit dan bergunung-gunung pada umumnya
memiliki DAS dengan luas yang lebih sempit dibandingkan dengan wilayah
yang cenderung datar dan landai.
DAS dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu daerah hulu, tengah dan hilir.
Daerah hulu merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase
yang lebih tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan lereng lebih besar
dari 15%. Daerah ini bukan merupakan daerah banjir dan merupakan daerah
yang pengaturan pemakaian airnya ditentukan oleh pola drainase. Daerah hilir
DAS merupakan daerah pemanfaatan dengan kemiringan lebih kecil dari 8 %,
pada beberapa tempat merupakan daerah banjir atau genangan. Daerah ini
merupakan daerah yang pengaturan pemakaian airnya ditentukan oleh
bangunan irigasi. Sedangkan daerah tengah DAS merupakan daerah transisi
antara daerah hulu dan daerah hilir (Asdak, 2002).
DAS berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) untuk suatu sistem sungai, dan merupakan suatu sistem ekologi (ekosistem) dengan
sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam. Batas alamiah
(ekologis) suatu DAS biasanya tidak sesuai dengan batas administrasi (politis)
yang ada. Ketidaksesuaian batas ini seringkali menjadi kendala dan tantangan
tersendiri bagi tercapainya usaha pengelolaan DAS yang komprehensif.
DAS dapat memberikan respon hidrologis berupa erosi, sedimentasi,
aliran permukaan dan pengangkutan nutrient yang berbeda-beda terhadap hujan yang jatuh diatasnya. Proses-proses hidrologi yang terjadi tergantung
dari kondisi tanah, air dan tanaman yang bergabung membentuk
parameter-parameter pendukung di dalam DAS. Parameter-parameter-parameter tersebut adalah
penutupan tanaman, jenis pengelolaan lahan, kekasaran permukaan tanah,
kemiringan lahan, panjang lereng, tekstur tanah, kadar air tanah, porositas
tanah, kapasitas lapang, erodibilitas tanah, dan kondisi saluran.
2. Komponen Fisik DAS
Dalam hubungannya dengan sistem hidrologi, DAS mempunyai
karakteristik yang spesifik serta berkaitan erat dengan unsur utamanya seperti
jenis tanah, tata guna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng.
Karakteristik biofisik DAS tersebut dalam merespon curah hujan yang jatuh
didalam wilayah DAS tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap
besar-kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, air larian, aliran permukaan,
kandungan air tanah, dan aliran sungai.
DAS terinci atas komponen-komponen fisiknya, yang terdiri dari
vegetasi, tanah, sungai, neraca air dan profil sungai. Komponen-komponen ini
sangat khas disetiap tempat, dicerminkan oleh tata airnya, yang meliputi
kuantitas, kualitas, dan dimensi waktu penyebarannya. Interaksi antara
komponen-komponen inilah yang akan menentukan tata air di DAS tersebut.
a. Vegetasi
Vegetasi suatu DAS meliputi hutan, perkebunan, sawah, dan
vegetasi di daerah pemukiman atau industri. Tiap tipe vegetasi mempunyai
bentuk tajuk, sistem perakaran, dan penutup tanah yang berbeda.
Pengaruh ini dapat dilihat pada perubahan kelembaban tanah pada zona
perakaran, dimana drainase dapat diabaikan.
Dalam kegiatan pengawetan tanah dan air, pemilihan jenis vegetasi
harus diperhatikan, karena vegetasi mempunyai peranan penting dalam
siklus hidrologi. Kecepatan limpasan air permukaan mencapai saluran,
banyak ditentukan oleh permeabilitas tanah yang dalam hal ini erat
hubungannya dengan peranan serasah vegetasi tersebut. Tanah yang
permeabel dengan kapasitas infiltrasi tinggi akan mempunyai cadangan air
tanah tinggi, sehingga akan mengurangi limpasan air permukaan. Pada
siklus hidrologi, vegetasi mempunyai peranan dalam proses intersepsi,
curahan tajuk, aliran batang, transpirasi dan fotosintesa.
b. Tanah
Dalam kehidupan sehari-hari tanah diartikan sebagai wilayah darat
dimana diatasnya dapat digunakan untuk berbagai usaha misalnya
pertanian, pendirian bangunan dan lain-lain.
Menurut Hardjowigeno (2003), dalam bidang pertanian, tanah
diartikan khusus yaitu sebagai media tumbuhnya tanaman darat. Tanah
berasal dari pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa bahan organik
dari organisme (vegetasi atau hewan) yang hidup diatasnya atau
didalamnya. Selain itu di dalam tanah terdapat pula udara dan air.
Air dalam tanah berasal dari air hujan yang tertahan oleh tanah.
Disamping pencampuran bahan mineral dengan bahan organik, maka
dalam proses pembentukan tanah, terbentuk pula lapisan-lapisan tanah
atau horison-horison. Oleh karena itu dalam definisi ilmiahnya tanah
adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam
horison-horison, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air
dan udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman
(Hardjowigeno, 2003).
c. Sungai
Fungsi sungai adalah untuk mengumpulkan curah hujan yang jatuh
dalam suatu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut (Sosrodarsono dan
tetap atau tersendat dan dapat pula menyebabkan erosi, walaupun
pengaruhnya sangat terbatas. Perubahan kondisi permukaan air sungai
dalam jangka waktu yang lama dapat diketahui dengan mengadakan
pengamatan permukaan air sungai itu dalam jangka waktu yang lama pula.
Sedangkan debit sungai dapat diketahui berdasarkan ketinggian
permukaan air sungai tersebut.
Menurut Sosrodarsono dan Takeda (2003), dalam soal pengendalian
sungai, tinggi permukaan air sungai yang telah dikorelasikan dengan curah
hujan dapat membantu penyelidikan data untuk pengelakan banjir,
peramalan banjir, dan pengendalian banjir dengan waduk atau bendungan.
Dalam usaha pemanfaatan air, permukaan air sungai dapat dipergunakan
untuk mengetahui secara umum banyaknya air sungai yang tersedia dan
penentuan kapasitas bendungan.
d. Neraca Air
Sosrodarsono dan Takeda (2003) mendefinisikan neraca air sebagai
hubungan antara aliran kedalam (inflow) dan aliran keluar (outflow) di
suatu daerah untuk suatu periode tertentu.
Air hujan yang jatuh di suatu permukaan bervegetasi, setelah
dievapotranspirasikan, sisanya akan menjenuhkan tanah dan mengalir ke
sungai sebagai limpasan. Bagi suatu DAS, hal ini merupakan indikasi
produksi air, dan kelestariannya merupakan cermin daur hidrologi.
e. Profil Sungai
Debit merupakan suatu paramater utama pada daerah aliran sungai.
Debit adalah volume air yang terjadi disuatu sungai pada periode waktu
tertentu. Periode waktu tersebut biasanya dinyatakan sebagai suatu
kejadian sesaat dimana aliran terjadi. Debit maksimum diartikan sebagai
aliran terbesar yang terjadi pada periode tertentu sedangkan debit
minimum diartikan sebagai aliran terkecil yang terjadi pada suatu aliran
sungai dalam periode tertentu.
Berdasarkan kontinuitas alirannya maka sungai dapat
a. Aliran yang bersifat sementara (ephemeral streams), yaitu aliran yang hanya berlangsung sementara dan bersumber dari limpasan permukaan
yang cepat. Aliran tak tahan lama dan biasanya hanya terjadi selama
hujan atau sesaat setelah turunnya hujan, karena permukaan air bawah
tanahnya berada di bawah dasar sungai.
b. Aliran yang terputus-putus (intermittent streams), adalah jenis aliran yang terjadi hanya pada musim hujan, bersumber dari aliran
permukaan pada musim kemarau tidak terlihat aliran, karena muka air
bawah tanahnya berada di bawah dasar sungai.
c. Aliran abadi (perennial streams), yaitu aliran yang terjadi sepanjang tahun, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Aliran ini
mempunyai ketinggian permukaan air bawah tanahnya berada dia atas
permukaan dasar sungai.
Besarnya aliran atau debit adalah volume air yang mengalir melalui
penampang sungai dalam satuan waktu tertentu, dinyatakan dalam satuan
l/detik atau m3/detik.
C. KEBUTUHAN SUMBERDAYA AIR
Air digunakan manusia untuk kebutuhan rumah tangga, petanian,
industri, pembangkit energi (tenaga listrik), transportasi, dan untuk keperluan
lainnya. Ditinjau dari fungsi air/wilayah perairan, dapat dibagi menjadi 3
golongan :
1. Air sebagai faktor produksi
2. Air sebagai komponen ekosistem, dan
3. Air sebagai sumber kenyamanan (amenity resource) (Nasoetion, 1991
dalam Ananda, R. D.,2003)
Di Indonesia, khususnya sebagai negara agraris, sektor pertanian adalah
sektor yang banyak menggunakan air, penggunaannya meliputi untuk
tanaman, perikanan dan peternakan. Penggunaan untuk rumah
tangga/domestik terdiri atas penggunaan untuk air minum, memasak, mencuci,
mandi dan lain sebagainya. Penggunaan untuk industri diantaranya sebagai
dalam proses industri. Sedangkan infrastruktur menggunakan air untuk
pembangkit tenaga listrik, rekreasi, transportasi, dan lain sebagainya.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan air untuk
rumah tangga akan meningkat. Disisi lain dengan meningkatnya taraf hidup
manusia yang berarti memacu industrialisasi maka berarti juga perlu
sumberdaya air dalam proses produksinya, dengan demikian kebutuhan
sumberdaya air makin hari semakin meningkat sejalan dengan tingkat
pertumbuhan penduduk, tingkat kenaikan taraf hidup serta peningkatan proses
industrialisasi.
1. Kebutuhan Air Penduduk
Besarnya kebutuhan air bagi masing-masing orang tidak sama dan
sangat tergantung pada beberapa faktor diantaranya tingkat sosial, tingkat
pendidikan, kebiasaan penduduk, letak geografis, dan lain-lain. Kebutuhan
dasar air bersih tiap individu digunakan untuk memenuhi keperluan
minum, masak, mencuci dan lain-lain.
Menurut Winrock (1992), Ditjen Cipta Karya menetapkan kebutuhan
air domestik/municipal untuk masyarakat pedesaan adalah 45 lcd (liter/capita/day) dan untuk masyarakat kota sebesar 60 lcd. Untuk Indonesia besar kebutuhan dasar tersebut adalah (Puslitbang Fisika
Terapan-LIPI, 1990) :
Tabel 2. Kebutuhan air rumah tangga
Jenis Kegiatan Kebutuhan Air
Minum 2.5 – 5.0 liter/jiwa/hari
Masak 7.5 - 10.0 liter/jiwa/hari
Cuci (bahan makanan dan lain-lain) 10.0 - 15.0 liter/jiwa/hari
Jumlah 20.0 - 30.0 liter/jiwa/hari
Sumber : Puslitbang Fisika Terapan-LIPI, (1990)
2. Kebutuhan Air Industri
Untuk menentukan kebutuhan air bersih industri dapat dikategorikan
untuk industri besar berkisar 151 – 350 m3/hari, industri sedang berkisar
51 – 150 m3/hari, dan industri kecil berkisar 5 – 50 m3/hari (Purwanto,
1995).
3. Kebutuhan Air Pertanian a. Kebutuhan Air Tanaman
Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air per satuan waktu yang
dibutuhkan untuk mencukupi evapotranspirasi, biasanya dinyatakan
dalam mm/hari. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari evaporasi
dan transpirasi.
Doorenbos dan Pruitt (1977) menjelaskan bahwa kebutuhan air
tanaman merupakan perkalian antara evapotranspirasi potensial
tanaman acuan (ETo) dengan koefisien tanaman (Kc) yang nilainya
tergantung pada jenis dan umur tanaman. Sedangkan yang dimaksud
dengan evapotranspirasi potensial tanaman acuan (ETo) menurut
Suranto (1989) adalah transpirasi dari tanaman rumput yang tumbuh
seragam dan sepenuhnya menutup tanah, tumbuh subur dan tidak
kekurangan air serta dipangkas setinggi 8 – 15 cm.
Besarnya kebutuhan air suatu tanaman dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu varietas tanaman, umur tanaman, keadaan tanah,
iklim serta cara pemberian air. Sedangkan evapotranspirasi
dipengaruhi temperatur, pelaksanaan pemberian air, panjangnya
musim tanam dan presipitasi. Jumlah air yang diuapkan oleh tanaman
tergantung pada temperatur, kelembaban udara, gerakan angin,
intensitas dan lamanya penyinaran, tahap perkembangan tanaman serta
jenis tanaman.
b. Kebutuhan Air Irigasi
Kebutuhan air irigasi atau pertanian adalah jumlah selain air
hujan yang ditambahkan untuk tanaman. Kebutuhan air untuk padi
sawah meliputi kebutuhan air untuk pengolahan tanah, pembibitan,
pertumbuhan sampai saat panen. Jumlah kebutuhan air untuk irigasi
jenis tanaman, keadaan iklim setempat, keadaan topografi dan luas
areal persawahan.
Dalam mengelola sumberdaya air untuk kepentingan irigasi,
curah hujan diperhitungkan sebagai tambahan air irigasi yang dapat
dimanfaatkan. Jumlah curah hujan yang jatuh selama periode
pertumbuhan tanaman dan curah hujan itu dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan air tanaman disebut dengan curah hujan efektif.
Kebutuhan air irigasi ditentukan oleh faktor-faktor penyiapan lahan,
penggunaan konsumtif, perkolasi, penggantian lapisan air, curah hujan
efektif serta efisiensi irigasi (Departemen PU, KP-01, 1986).
1) Penyiapan Lahan
Faktor-faktor penting yang menentukan besarnya kebutuhan
air untuk penyiapan lahan adalah (Departemen PU,KP-01, 1986) :
a. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan penyiapan lahan.
b. Jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan.
c. kebutuhan air selama penyiapan lahan.
Kebutuhan air penyiapan lahan tanaman padi diambil 200
sampai 250 mm untuk jangka waktu penyiapan lahan 30 atau 45
hari yang kemudian ditambah 50 mm setelah pemindahan bibit
sedangkan kebutuhan air penyiapan lahan tanaman palawija
ditentukan sebesar 50 sampai 100 mm.
2) Penggunaan Konsumtif
Besarnya penggunaan konsumtif bagi tanaman sebanding
dengan besarnya nilai evapotranspirasi (Linsley, et al., 1990). Nilai evapotranspirasi untuk suatu daerah dipengaruhi iklim setempat
seperti temperatur, kecepatan angin, radiasi matahari dan
kelembaban udara.
3) Perkolasi
Perkolasi merupakan gerakan air didalam tanah sebagai
mengalamui infiltrasi pada suatu saat akan melampaui batas tanah
untuk menahan air, dimana pori-pori tanah telah terisi oleh air
sehingga air kelebihannya akan terus bergerak kebawah berupa
perkolasi.
Perkolasi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah antara lain
permeabilitas dan tekstur tanah, pengendapan-pengendapan
lumpur, kedalaman muka air tanah (Kartasapoetra dan Sutedjo,
1991 dalam Pribadi, A. 2001). Laju perkolasi pada tanah bertekstur lempung berat dengan pengolahan yang baik mencapai 1 – 3 mm,
sedangkan pada tanah-tanah lebih ringan laju perkolasinya lebih
tinggi (Departemen PU,KP-01, 1986).
4) Penggantian Lapisan Air
Penggantian air dilakukan sesuai jadwal dan kebutuhan. Bila
tidak ada penjadwalan, penggantian air dilakukan sebanyak 2 kali
masing-masing 50 mm (3.3 mm/hari selama setengah bulan)
selama sebulan dan dua bulan setelah pemindahan bibit
(Departemen PU,KP-01, 1986).
5) Curah Hujan Efektif
Curah hujan yang jatuh di suatu areal tidak semuanya dapat
dimanfaatkan oleh tanaman karena sebagian akan hilang
disebabkan intersepsi, infiltrasi, penguapan dan tampungan
cekungan (Sri Harto, 1993). Bagian dari air hujan yang dapat
dimanfaatkan oleh tanaman dinyatakan sebagai hujan efektif.
Curah hujan efektif dapat dicari dengan menggunakan rumus :
1. Persentase pasti
P eff = A x Pmean ...(7)
2. Perkiraan curah hujan andalan
P eff = 0.6 x Pmean - 10, untuk Pmean < 60 mm/bln...(8)
P eff = 0.8 x Pmean - 25, untuk Pmean > 60 mm/bln ...(9)
Rumus ini berlaku untuk daerah arid dan daerah lembah 3. Rumus empirik
Peff = C x Pmean - D, untuk Pmean > x mm/bln ...(11)
Parameter-parameter yang memenuhi berbeda untuk tiap
daerah.
4. USBR
P eff = Pmean x (125– 0.2 Pmean /125), untuk P<250 mm.(12)
P eff = 125 + 0.1 x Pmean, untuk P > 250 mm...(13).
c. Kebutuhan Air Pengolahan Tanah
Pengolahan tanah adalah suatu usaha menciptakan kondisi tanah
yang sedemikian rupa, sehingga tanaman dapat berkecambah dan
tumbuh dengan baik. Kegiatan pengolahan tanah ini bertujuan untuk
membersihkan lahan dari gulma, memberantas hama dan penyakit
dalam tanah.
Kebutuhan air pengolahan tanah dipengaruhi oleh sifat fisik
tanah. Tanah pasir umumnya memerlukan banyak air untuk
pengolahannya, karena tidak lekas jenuh dengan air. Kebutuhan
pengolahan tanah untuk berbagai teksur tanah disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan air pengolahan tanah pada berbagai teksturtanah
Tekstur tanah Kebutuhan air (mm/hari)
Pasir 27
Lempung berpasir 23
Lempung 17
Lrmpung liat 14
Liat 10
Sumber : Rice irrigation in Japan. OTCA, 1973 didalam Soedodo H, 1999.
Penentuan saat pengolahan tanah padi lahan kering tergantung
dari datangnya musim hujan, sehingga perencanaan pola tanam yang
sesuai akan membantu dalam tingkat keberhasilan sistem pola usaha
d. Pola Tanam
Pola tanam merupakan pengaturan jenis tanaman yang ditanam
pada suatu lahan dalam kurun waktu tertentu, tujuannya supaya air
irigasi yang tersedia sangat terbatas masih dapat dimanfaatkan secara
adil dan merata untuk seluruh daerah irigasi.
Pengertian mengenai jenis tanaman dan kesesuaiannya dengan
lahan sangat penting untuk menentukan jenis atau urutan pertanaman
yang dapat dikembangkan, sehingga dengan pengaturan pola tanam
dapat diperoleh manfaat yang maksimal, efisien serta dapat
meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani. Penentuan
jenis tanaman terpilih haruslah mempertimbangkan beberapa faktor,
diantaranya :
Tanaman tersebut dapat tumbuh dan menghasilkan produksi. Tanaman tersebut merupakan tanaman yang disukai petani.
Tanaman tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mudah
untuk dipasarkan.
D. KETERSEDIAAN SUMBERDAYA AIR
Pengertian ketersediaan sumberdaya air adalah air yang dapat
dimanfaatkan oleh makhluk hidup dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.
Ketersediaan sumberdaya air dapat berupa air hujan, air sungai, mata air dan
air tanah, baik air tanah dangkal (unconfined aquifer), maupun air tanah dalam (confined aquifer). Air hujan diasumsikan sebagai masukan tunggal dalam sistem hidrologi DAS, sedangkan air sungai, mata air dan air tanah adalah
bentuk lain dari air hujan. Air merupakan sumberdaya alam yang dapat
diperbaharui (renewable) dan keberadaannya mengikuti suatu kaidah atau sistem yang disebut daur hidrologi (Linsley, et al. 1990).
Dalam mempelajari sistem hidrologi, Manan (1979) mengemukakan
bahwa model Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan model yang baik untuk
menelusuri sumberdaya air, karena dalam suatu DAS akan terjadi proses
masukan-keluaran air yang merupakan bagian dari sistem hodrologi. Dengan
demikian pengelolaan DAS secara umum dapat didefinisikan sebagai