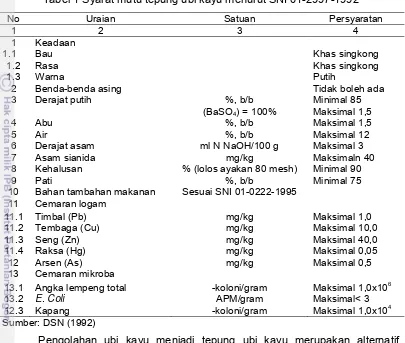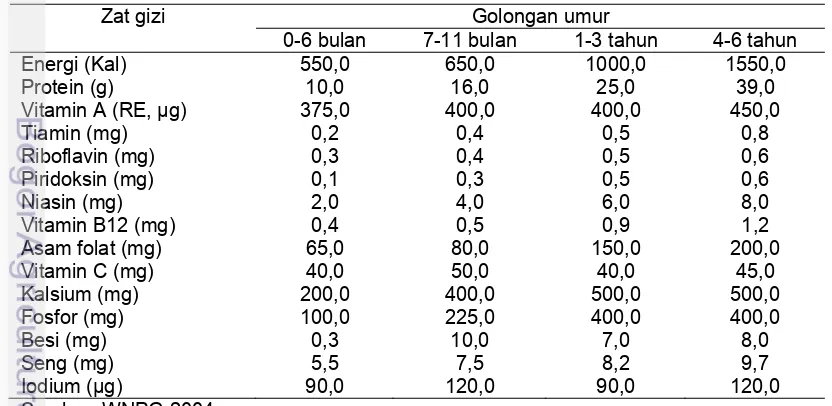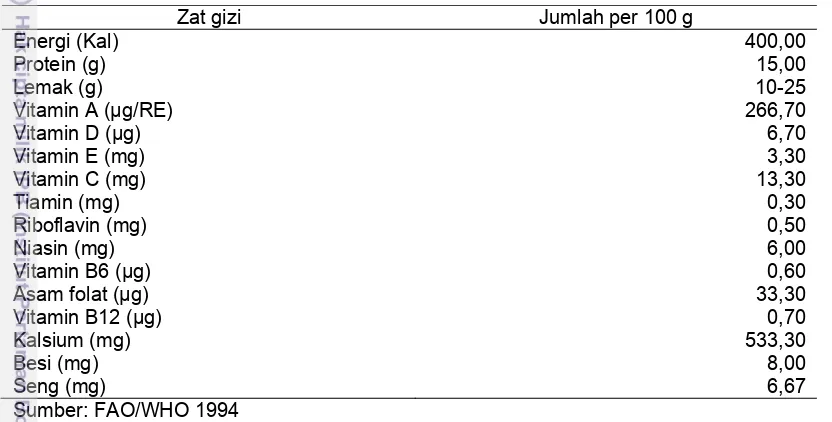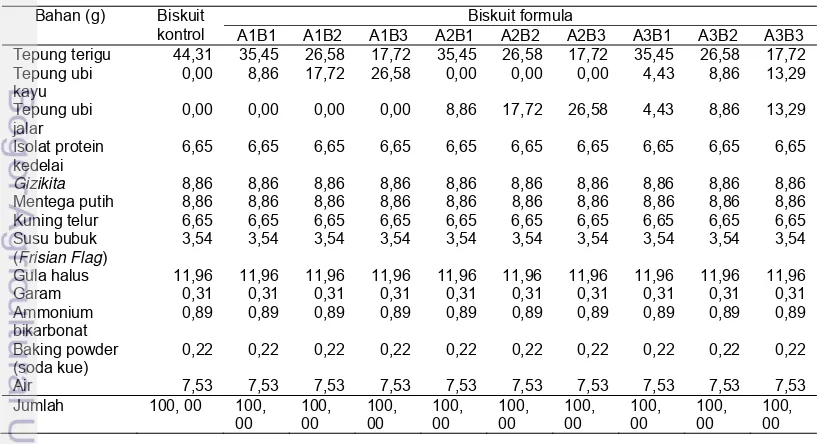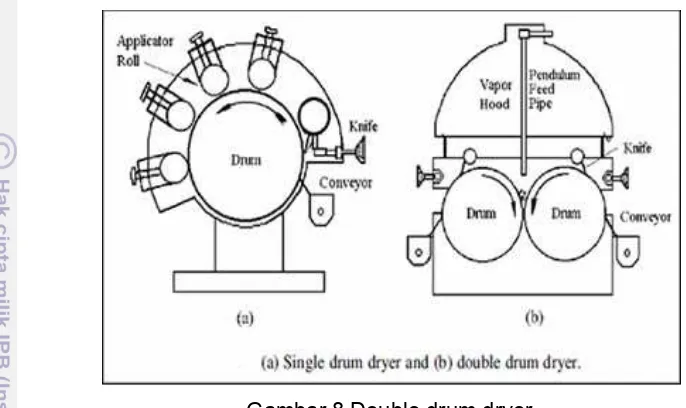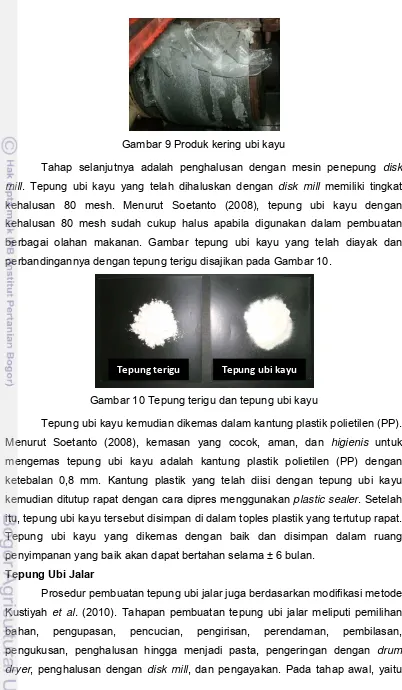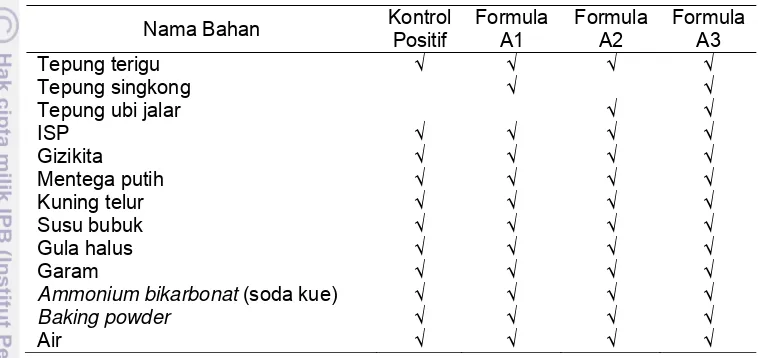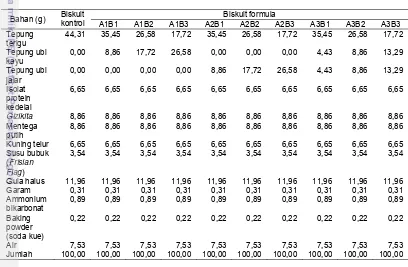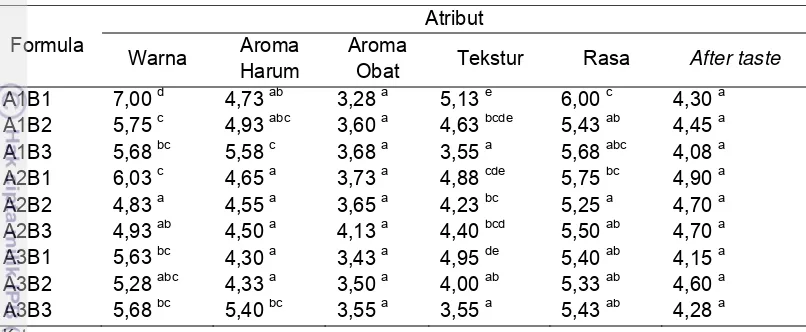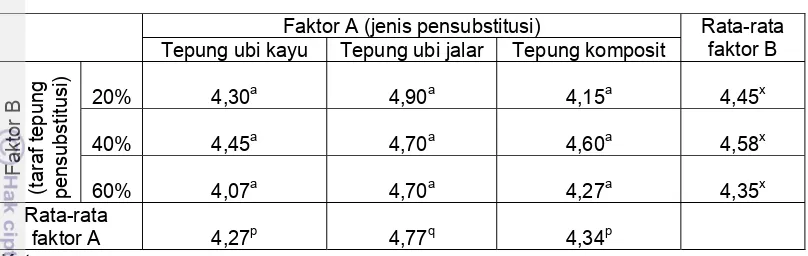FORMULASI BISKUIT SUBSTITUSI TEPUNG UBI KAYU DAN UBI
JALAR DENGAN PENAMBAHAN ISOLAT PROTEIN KEDELAI
SERTA MINERAL Fe DAN Zn UNTUK BALITA GIZI KURANG
HANIFAH DWIYANI
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
ABSTRACT
HANIFAH DWIYANI. Formulation of Moderate Undernutrition Children’s Biscuit Made of Cassava Flour, Sweet Potato Flour, and Soy Protein Isolate with Addition of Fe and Zn. Under guidance of LILIK KUSTIYAH.
Moderate undernutrition is one of major nutritional problems in Indonesia, with a prevalence of 13%. Instead of lack of energy and protein intake, undernutrition children commonly are deficient in iron and zinc. One of the effort to overcome this problem is by giving them foods which contain high energy and protein as well as met with iron and zinc requirement. The objective of this research was to formulate biscuit which were made of cassava flour, sweet potato flour, and soy protein isolate with addition of Fe and Zn as side dish of moderate undernutrition children. Cassava and sweet potato flour is an indigenous food of Indonesia which high in energy content, so can be used to substitute wheat flour in making biscuits as source of energy. To increase protein content of biscuit, it was used soy protein isolate which contains about 90%
protein. Gizikita is a multivitamin mineral supplement containing high iron and
zinc in microcapsules form. Design of this research was experimental which factors that used were kind of flour (cassava, sweet potato, and composite flour) and level of flour substitution (20%, 40%, and 60%). Based on organoleptic test showed that the selected formula was A1B1 (20% cassava substitution). Biscuits
A1B1 has 457 Kcal/100g of gross energy; 2.960,2 gram force of hardness;
8,31% water content (wb); 3,12% ash (db); 13,93% protein (db); 14,23% fat (db); 68,71% carbohydrate (db); 8,38 mg/100g Fe; 10,61 mg/100g Zn; 81,48% protein digestibility; 10,87% bioavailability of Fe ; and 29,45% bioavailability of Zn.
RINGKASAN
HANIFAH DWIYANI. Formulasi Biskuit Substitusi Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan Penambahan Isolat Protein Kedelai serta Mineral Fe dan Zn untuk Balita Gizi Kurang. Dibimbing oleh LILIK KUSTIYAH.
Gizi kurang adalah salah satu masalah gizi utama di Indonesia dengan prevalensi sebesar 13% (Depkes 2010). Konsekuensi dari KEP adalah pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat pada anak-anak (Hull & Johnston 2008). Upaya perbaikan status gizi masih terfokus pada penderita gizi buruk, sedangkan penderita gizi kurang belum mendapat perhatian yang cukup
(Kustiyah et al. 2010). Jika penderita gizi kurang tidak mendapat perhatian yang
cukup maka mereka rentan jatuh dalam kondisi gizi buruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi gizi kurang. Salah satu caranya adalah dengan pemberian makanan tambahan yang tepat, yaitu makanan yang mampu mencukupi kebutuhan energi dan tinggi protein, besi, serta seng. Pada penelitian ini, jenis makanan tambahan yang dibuat adalah biskuit.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat formula biskuit dengan substitusi tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan penambahan isolat protein kedelai serta multivitamin mineral sebagai makanan tambahan untuk balita gizi kurang. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah 1) mempelajari pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar, 2) membuat formula biskuit balita gizi kurang (BGK), 3) menguji daya terima serta menganalisis pengaruh jenis serta taraf tepung pensubstitusi terhadap mutu hedonik biskuit, 4) menganalisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia biskuit formula terpilih dan kontrol, 5) menganalisis keberadaan perbedaan gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia antara biskuit formula terpilih dengan kontrol.
Penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar; formulasi dan pembuatan biskuit BGK; uji organoleptik; serta analisis gross energi, sifat fisik, dan sifat kimia. Pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar berdasarkan modifikasi metode Kustiyah et. al (2010). Tahapannya terdiri dari pemilihan bahan, pengupasan, pencucian, pengirisan, perendaman, pembilasan, pengukusan, penghalusan hingga menjadi pasta, pengeringan dengan drum dryer, penghalusan dengan disk mill, dan pengayakan.
Formulasi biskuit memperhitungkan kebutuhan energi dan zat gizi perhari serta pembatas energi dan zat gizi bagi balita 4-5 tahun. Formulasi biskuit BGK didasarkan pada modifikasi resep Anwar et al. (1993). Biskuit yang dibuat adalah biskuit formula dan biskuit kontrol. Biskuit formula terbagi dalam 9 formula, yaitu: A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, A2B2, A2B3, A3B1, A3B2, dan A3B3. Faktor yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis dan taraf tepung pensubstitusi. Jenis tepung yang mensubstitusi tepung terigu adalah tepung ubi kayu (A1), tepung ubi jalar (A2), dan tepung komposit atau campuran tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan perbandingan 1:1 (A3). Adapun taraf tepung pensubstitusi terdiri dari 20% (B1), 40% (B2), dan 60% (B3). Proses pembuatan biskuit BGK merupakan hasil modifikasi metode Mervina (2009). Tahapan pembuatan biskuit terdiri dari penimbangan bahan, pencampuran dan pengadukan, pendinginan, pemipihan, pencetakan, serta pemanggangan.
tekstur, dan rasa biskuit. Namun jenis formula tidak berpengaruh terhadap aroma obat dan aftertaste pada biskuit.
Jenis dan taraf tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut warna. Namun, interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh. Biskuit tepung ubi kayu memiliki warna lebih terang dibandingkan dengan biskuit tepung ubi jalar dan komposit. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi kayu dapat menyebabkan biskuit berwarna lebih terang. Biskuit bertaraf 20% memiliki warna lebih terang dibandingkan dengan biskuit bertaraf 40% dan 60%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah taraf tepung pensubstitusi maka warna biskuit cenderung semakin terang.
Jenis dan taraf tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut aroma harum. Namun, interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh. Biskuit tepung ubi kayu memiliki aroma harum lebih kuat dibandingkan dengan biskuit tepung ubi jalar dan komposit. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi kayu dapat meningkatkan aroma harum. Biskuit bertaraf 60% memiliki aroma harum lebih kuat dibandingkan dengan biskuit bertaraf 20% dan 40%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi taraf tepung pensubstitusi maka aroma harum biskuit semakin kuat.
Jenis tepung pensubstitusi, taraf tepung pensubstitusi, dan interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap atribut aroma obat. Jenis tepung pensubstitusi tidak berpengaruh terhadap atribut tekstur. Namun, taraf tepung pensubstitusi dan interaksi kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap atribut tekstur. Biskuit bertaraf 20% memiliki tekstur lebih renyah dibandingkan dengan biskuit bertaraf 40% dan 60%. Biskuit bertaraf 40% memiliki tekstur lebih renyah dibandingkan dengan biskuit bertaraf 60%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah taraf tepung pensubstitusi maka tekstur biskuit semakin renyah.
Jenis dan taraf tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut rasa. Namun, interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh. Biskuit tepung ubi kayu memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan biskuit tepung komposit. Namun biskuit tepung ubi jalar tidak berbeda dengan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi kayu dapat meningkatkan rasa manis. Biskuit bertaraf 20% memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan biskuit bertaraf 40%. Namun biskuit bertaraf 60% tidak berbeda dengan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah taraf tepung pensubstitusi maka rasa biskuit semakin manis.
Jenis tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut aftertaste. Namun, taraf tepung pensubstitusi dan interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap atribut aftertaste. Biskuit tepung ubi jalar memiliki aftertaste yang lebih kuat dibandingkan dengan biskuit tepung ubi kayu dan tepung komposit. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi jalar dapat meningkatkan aftertaste.
Formula terpilih ditentukan berdasarkan persen penerimaan, nilai rata-rata, nilai modus, dan berdasarkan atribut keseluruhan. Formula terpilih pada penelitian ini adalah A1B1 (substitusi tepung ubi kayu 20%). Biskuit formula terpilih (FT) memiliki gross energy 457 Kal/100g; nilai kekerasan 2.960,2 gram force; kadar air 8,31%bb; kadar abu 3,12%bk; kadar protein 13,93%bk; kadar lemak 14,23%bk; kadar karbohidrat 68,71%bk; kadar Fe 8,38 mg/100g; kadar Zn 10,61 mg/100g; daya cerna protein 81,48%; bioavailabilitas Fe 10,87%; dan bioavailabilitas Zn 29,45%.
FORMULASI BISKUIT SUBSTITUSI TEPUNG UBI KAYU DAN UBI
JALAR DENGAN PENAMBAHAN ISOLAT PROTEIN KEDELAI
SERTA MINERAL Fe DAN Zn UNTUK BALITA GIZI KURANG
HANIFAH DWIYANI
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi
dari Program Studi Ilmu Gizi pada Departemen Gizi Masyarakat
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
Judul : Formulasi Biskuit Substitusi Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan Penambahan Isolat Protein Kedelai serta Mineral Fe dan Zn untuk Balita Gizi Kurang
Nama : Hanifah Dwiyani
NIM : I14070045
Menyetujui:
Dosen Pembimbing
Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M. Si NIP. 19620507 198703 2 001
Mengetahui :
Ketua Departemen Gizi Masyarakat
Dr. Ir. Budi Setiawan, MS NIP. 19621218 198703 1 001
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Formulasi
Biskuit Substitusi Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan Penambahan Isolat
Protein Kedelai serta Mineral Fe dan Zn untuk Balita Gizi Kurang”. Pada
kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan
sabar senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan
memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis baik dalam
penyusunan skripsi maupun dalam kehidupan penulis.
2. Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, M.Si selaku dosen pemandu seminar dan dosen
penguji yang telah memberikan banyak masukan atau saran yang sangat
berguna bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Mashudi atas kesabaran dan bantuannya baik selama penelitian
maupun penyusunan skripsi serta atas nasihat-nasihat yang sangat berguna
bagi kehidupan penulis.
4. Kedua orangtua tercinta (Achmad Munawar & Muftichah), adik tersayang
(Muhammad Sufi Naritsul Ardhi), serta seluruh keluarga atas kasih sayang,
doa, nasihat, dukungan, semangat, dan pengertian kalian sehingga penulis
dapat terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
5. Seluruh staff Departemen Gizi Masyarakat: Bu Rizky, Bu Titi, Bu Nina, Pak
Ugan, Teh Santi, Pak Karya, dan semua staff lain yang tidak dapat disebutkan
satu persatu atas bantuannya selama ini.
6. Keluargaku di PT Melia Sehat Sejahtera: Ir. Nuraeni, Dr. Ir. Winarso D
Widodo, MS, Andini, Adi, Zulmy, Ghieah, Widya, seluruh downline, upline,
leader, dan crossline yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan, doa, pengertian, dan semangat yang selalu diberikan kepada
penulis untuk berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan.
7. Sahabat-sahabatku tercinta: Latifah, Asia, Khonita, Anita, Anggi, dan Wina
atas motivasi, doa, dan semangatnya.
8. Teman-teman kost Tri Regina: Laras, Pasha, Linda, Fia, Dhanis, Mbak Uwi,
Mbak Apong, Besta, Tita, Kak Resti, Nilam, dan Rossy atas bantuan, doa, dan
9. Teman-teman senasib dan seperjuangan di laboratorium: Kak Eva, Kak Aim,
Atis, Eka, Yulia, Ade, Ai, Anti, Agus, Ibnu, Rohman, Yusti, dan teman-teman
yang lain atas bantuan, doa, dan semangatnya.
10. Teman-teman pembahas seminar: Anti, Wiwi, Agus, dan Bibi.
11. Teman-teman GM 44, GM 45, GM 46, dan GM 47 atas bantuannya selama
penelitian dan kehadirannya dalam seminar.
12. Teman-teman di IAAS
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tak langsung telah membantu
penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang
lebih baik dan lebih besar. Sesungguhnya tiada balasan untuk suatu kebaikan
melainkan dengan kebaikan pula.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat penulis
harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.
Bogor, Februari 2013
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Ungaran pada tanggal 1 Agustus 1989. Penulis
adalah putri dari pasangan Bapak Achmad Munawar dan Ibu Muftichah. Penulis
merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.
Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 02 Ungaran
dari tahun 1995 sampai 2001. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke
sekolah menengah pertama di SLTP Negeri 1 Ungaran dari tahun 2001 sampai
2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di
SMA Negeri 1 Ungaran dari tahun 2004 sampai 2007
Pada tahun 2007 penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa di
Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
melalui jalur USMI. Selama masa kuliah, penulis aktif mengikuti beberapa
organisasi, yaitu IAAS ( International Association of student in Agricultural and
related Sciences), HIMAGIZI (Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi), dan Klub Kulinari. Penulis mendapatkan amanah di IAAS sebagai staff Departemen Exchange
Program (2008-2009), ketua Departemen Exchange Program (2009-2010), sekretaris Departemen Exchange Program (2010-2011), dan Control Council
IAAS Local Committee IPB (2011-2012). Penulis juga mendapatkan amanah di
HIMAGIZI sebagai staff Departemen Keprofesian (2009). Selain itu, penulis
mendapatkan amanah di Klub Kulinari sebagai Bendahara (2010) dan Steering
Committee (2011).
Penulis pernah berkesempatan mengikuti beberapa perlombaan dan
international event. Beberapa perlombaan tersebut diantaranya adalah Jawara Politik (2008) sebagai semifinalis, Environment Projects in Contribution to Save
The World (2009) yang diselenggarakan oleh AIESEC Malaysia sebagai juara pertama, dan Duta FEMA (2010) sebagai delegasi dari Departemen Gizi
Masyarakat. Adapun beberapa international event yang pernah diikuti oleh
penulis adalah IPB International Student Conference (2008) sebagai panitia (staff
Divisi Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi), Youth Leader Conference (2008)
sebagai peserta, International MIRACLE Youth Conference (2009) sebagai
peserta, dan World Congress of IAAS (2010) sebagai panitia (ketua Divisi Acara).
Penulis telah mendapatkan banyak pengalaman berharga selama masa
kuliah. Selain pengalaman organisasi, penulis juga mendapatkan beberapa
pengalaman kerja. Beberapa pengalaman kerja tersebut diantaranya adalah
kegiatan penelitan yang berjudul “Mikroenkapsulasi Mineral Besi dan Seng dalam
Pembuatan Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang” (2010-2011), asisten
praktikum mata kuliah Analisis Zat Gizi Mikro (2010-2011 & 2012-2013), dan
asisten praktikum mata kuliah Percobaan Makanan (2012-2013). Sebelum
melaksanakan tugas akhir, penulis berkesempatan mengikuti internship dietetik
di RSAB Harapan Kita (2011) dengan topik kajian penatalaksanaan diet pada
penyakit bronchopneumonia (BP), gizi kurang, dan down syndrome. Saat ini
penulis aktif sebagai seorang leader di PT Melia Sehat Sejahtera yang bergerak
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI... i
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... vi
DAFTAR LAMPIRAN ... vii
PENDAHULUAN ... 1
Latar Belakang ... 1
Tujuan ... 4
Tujuan Umum ... 4
Tujuan Khusus ... 4
Manfaat ... 4
TINJAUAN PUSTAKA ... 5
Gizi Kurang ... 5
Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz) ... 6
Tepung Ubi Kayu ... 8
Ubi Jalar (Ipomoea batatas) ... 10
Tepung Ubi Jalar ... 12
Isolat Protein Kedelai ... 14
Gizikita ... 15
Mineral ... 15
Zat Besi (Fe) ... 16
Seng (Zn) ... 17
Makanan Balita ... 18
Biskuit ... 19
Klasifikasi Biskuit ... 20
Bahan-bahan Pembuat Biskuit ... 20
Uji Organoleptik ... 22
Uji Hedonik ... 23
Uji Mutu Hedonik ... 23
METODE ... 24
Bahan dan Alat ... 24
Tahapan Penelitian ... 25
Pembuatan Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar ... 25
Formulasi dan Pembuatan Biskuit Balita Gizi Kurang ... 25
Analisis Organoleptik Biskuit Balita Gizi Kurang ... 27
Analisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia ... 28
Rancangan Percobaan ... 28
Pengolahan dan Analisis Data ... 29
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30
Pembuatan Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar ... 30
Tepung Ubi Kayu ... 30
Tepung Ubi Jalar ... 34
Rendemen ... 37
Formulasi dan Pembuatan Biskuit ... 38
Formulasi Biskuit ... 38
Pembuatan Biskuit ... 44
Karakteristik Organoleptik Biskuit BGK ... 47
Hedonik ... 48
Mutu Hedonik ... 51
Pengaruh Jenis dan Taraf Tepung Pensubstitusi terhadap Mutu Hedonik Biskuit ... 54
Karakteristik Daya Terima Formula Terpilih ... 62
Karakteristik Spesifik Formula Terpilih ... 65
Gross Energy, Sifat Fisik, dan Sifat Kimia Biskuit Formula Terpilih dan Biskuit Kontrol ... 67
Gross Energy. ... 67
Sifat Fisik ... 68
Sifat Kimia ... 69
Kontribusi Energi dan Zat Gizi Biskuit Balita Gizi Kurang terhadap AKG Balita 4-5 Tahun ... 75
KESIMPULAN DAN SARAN ... 78
Kesimpulan ... 78
Saran ... 80
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1 Syarat mutu tepung ubi kayu menurut SNI 01-2997-1992 ... 9
Tabel 2 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu ... 9
Tabel 3 Syarat mutu tepung ubi jalar menurut SNI 1996 ... 12
Tabel 4 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu ... 13
Tabel 5 Angka kecukupan gizi balita (per orang per hari) ... 18
Tabel 6 Komposisi zat gizi formula makanan tambahan balita ... 19
T
Tabel 8 Faktor-faktor dalam pembuatan biskuit formula ... 26 abel 7 Syarat mutu biskuit menurut SNI 01-2973-1992 ... 20
Tabel 9 Formula biskuit balita gizi kurang per 100 gram biskuit ... 26
Tabel 10 Rendemen tepung ubi kayu dan ubi jalar ... 37
Tabel 11 Resep biskuit standar (Anwar et al. 1993) ... 38
Tabel 12 Faktor-faktor dalam pembuatan biskuit formula ... 40
Tabel 13 Komposisi bahan dari resep biskuit formula dan biskuit kontrol ... 41
Tabel 14 Formula biskuit balita gizi kurang per 100 gram biskuit ... 45
Tabel 15 Hasil uji hedonik biskuit balita gizi kurang ... 49
Tabel 16 Hasil uji mutu hedonik biskuit balita gizi kurang ... 52
Tabel 17 Hasil ANOVA dari atribut mutu hedonik warna biskuit balita gizi kurang ... 55
Tabel 18 Hasil ANOVA dari atribut mutu hedonik aroma keharuman biskuit balita gizi kurang ... 57
Tabel 19 Hasil ANOVA dari atribut mutu hedonik aroma obat biskuit balita gizi kurang ... 58
Tabel 23 Karakteristik mutu hedonik, hedonik, dan persen penerimaan dari formula terpilih (FT) pada berbagai atribut ... 64
Tabel 24 Hasil analisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia biskuit formula terpilih dan biskuit kontrol ... 67
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Ubi kayu ... 7
Gambar 2 Ubi jalar ... 11
Gambar 3 Diagram alir pembuatan tepung ubi kayu ... 25
Gambar 4 Diagram alir pembuatan tepung ubi jalar ... 26
Gambar 5 Diagram alir pembuatan biskuit BGK ... 27
Gambar 6 Ubi kayu ... 30
Gambar 7 Pasta ubi kayu ... 32
Gambar 8 Double drum dryer ... 33
Gambar 9 Produk kering ubi kayu ... 34
Gambar 10 Tepung terigu dan tepung ubi kayu ... 34
Gambar 11 Ubi jalar ... 35
Gambar 12 Pasta ubi jalar ... 36
Gambar 13 Produk kering ubi jalar ... 36
Gambar 14 Tepung terigu dan tepung ubi jalar ... 37
Gambar 15 Biskuit formula dan biskuit kontrol ... 48
Gambar 16 Biskuit formula terpilih (A1B1) ... 65
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Perhitungan formulasi biskuit balita gizi kurang ... 89
Lampiran 2 Lembar penilaian uji organoleptik tahap I biskuit balita gizi ... 92
Lampiran 3 Lembar penilaian uji organoleptik tahap II biskuit balita gizi ... 97
Lampiran 4 Prosedur analisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia ... 102
Lampiran 5 Perhitungan rendemen tepung ubi kayu dan ubi jalar ... 107
Lampiran 6 Data kandungan gizi bahan-bahan biskuit balita gizi kurang per 100 gram bahan ... 108
Lampiran 7 Hasil ANOVA dan uji lanjut Duncan pada uji hedonik biskuit ... 109
Lampiran 8 Hasil ANOVA dan uji lanjut Duncan pada uji mutu hedonik ... 111
Lampiran 9 Hasil two-way anova (General Linear Model) dan uji lanjut ... 113
Lampiran 10 Persen penerimaan biskuit balita gizi kurang ... 116
Lampiran 11 Nilai rata-rata uji hedonik biskuit balita gizi kurang ... 117
Lampiran 12 Nilai modus uji hedonik biskuit balita gizi kurang ... 117
Lampiran 15 Perhitungan kadar air biskuit balita gizi kurang ... 118
Lampiran 16 Perhitungan kadar abu biskuit balita gizi kurang ... 119
Lampiran 17 Perhitungan kadar protein biskuit balita gizi kurang ... 120
Lampiran 18 Perhitungan kadar lemak biskuit balita gizi kurang ... 121
Lampiran 19 Perhitungan kadar karbohidrat biskuit balita gizi kurang ... 122
Lampiran 20 Perhitungan kadar Fe biskuit balita gizi kurang ... 122
Lampiran 21 Perhitungan kadar Zn biskuit balita gizi kurang ... 123
Lampiran 22 Perhitungan daya cerna protein biskuit balita gizi kurang ... 124
Lampiran 23 Perhitungan bioavailabilitas Fe biskuit balita gizi kurang ... 125
Lampiran 24 Perhitungan bioavailabilitas Zn biskuit balita gizi kurang ... 126
Lampiran 26 Penentuan jumlah biskuit yang harus dikonsumsi dalam ... 130
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masalah kurang energi protein merupakan salah satu masalah gizi utama
di Indonesia. Data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa secara nasional
prevalensi balita dengan status undernutrition (gizi buruk dan kurang) sebesar
17,9%, yaitu gizi kurang sebesar 13% dan gizi buruk sebesar 4,9% (Depkes
2010). Berdasarkan cut off point Depkes (1996), prevalensi balita gizi kurang
tergolong masalah kesehatan masyarakat kategori sedang, sedangkan
prevalensi balita gizi buruk tergolong masalah kesehatan masyarakat.
Konsekuensi dari KEP adalah pertumbuhan dan perkembangan yang lebih
lambat pada anak-anak (Hull & Johnston 2008).
Perbaikan status gizi merupakan salah satu prioritas Pembangunan
Kesehatan 2010-2014 (Minarto 2010). Oleh karena itu, pemerintah melakukan
berbagai macam upaya untuk menanggulangi masalah kurang gizi. Namun,
upaya-upaya tersebut masih terfokus pada penderita gizi buruk, sedangkan
penderita gizi kurang belum mendapat perhatian yang cukup (Kustiyah et al.
2010). Jika penderita gizi kurang tidak mendapat perhatian yang cukup maka
mereka rentan jatuh dalam kondisi gizi buruk. Pada umumnya, satu persen dari
balita berstatus gizi kurang akan jatuh pada kasus gizi buruk (Yumarlis 2011).
Terdapat berbagai macam cara untuk menanggulangi masalah gizi
kurang, salah satunya adalah melalui pemberian makanan tambahan yang tepat,
yaitu makanan yang mengandung energi dan protein yang tinggi serta mampu
memenuhi kecukupan besi dan seng. Pada penelitian ini, jenis makanan
tambahan yang dibuat adalah biskuit.
Biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan
penambahan bahan makanan lain dengan proses pemanasan dan pencetakan
(SNI 01-2973-1992 dalam DSN 1992b). Menurut Manley (2000), biskuit
merupakan makanan yang cukup populer. Hal ini dapat dilihat dari penjualan
biskuit di Indonesia pada tahun 2012 yang meningkat 5-8% menurut asosiasi
industri (Saksono 2012). Hal tersebut menunjukkan permintaan pasar yang
semakin tinggi terhadap biskuit. Permintaan pasar yang semakin meningkat
merupakan indikator diterimanya biskuit sebagai pangan alternatif.
Di rumah sakit, diet-diet yang diberikan untuk anak penderita gizi kurang
berupa pemberian biskuit. Biskuit dapat dipandang sebagai media yang baik
manusia (Manley 2000). Biskuit dapat memenuhi kebutuhan khusus manusia,
salah satunya adalah kebutuhan gizi anak gizi kurang jika dilakukan substitusi
dan fortifikasi terhadap biskuit tersebut. Fortifikasi adalah komplementasi atau
proses penambahan zat gizi (vitamin dan mineral) ke dalam makanan olahan
(Makfoeld 2002). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, biskuit merupakan
makanan tambahan yang cocok bagi penderita gizi kurang.
Biskuit yang umum digunakan sebagai makanan tambahan masih berupa
makanan pabrikan yang berbasis tepung terigu. Namun, sampai saat ini seluruh
kebutuhan biji gandum sebagai bahan baku pembuatan tepung terigu masih
harus diimpor dari luar negeri (Welirang 2011). Oleh karena itu, perlu
dikembangan produk alternatif yang mampu mensubstitusi komoditas tepung
terigu. Pada penelitian ini, bahan pangan yang digunakan untuk mensubstitusi
tepung terigu adalah tepung ubi kayu dan ubi jalar.
Ubi kayu adalah salah satu bahan pangan lokal yang potensial karena
memiliki produksi dan produktivitas yang tinggi di Indonesia. Menurut data BPS
(2012), produksi ubi kayu pada tahun 2011 adalah 24.044.025 ton/tahun dan
produktivitasnya sebesar 202,96 kwintal per hektar. Salah satu produk turunan
ubi kayu adalah tepung kasava. Tepung kasava atau tepung ubi kayu atau
tepung singkong atau cassava flour adalah tepung yang dibuat dari ubi kayu
segar yang memanfaatkan semua kandungan gizi ubi kayu, termasuk pati dan
seratnya (Djuwardi 2011).
Ubi jalar juga merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki
produksi dan produktivitas yang tinggi di Indonesia. Menurut data BPS (2012),
produksi ubi jalar pada tahun 2011 adalah 2.196.033 ton/tahun dan
produktivitasnya sebesar 123,29 kwintal per hektar. Salah satu produk turunan
ubi jalar adalah tepung ubi jalar.
Penderita gizi kurang mengalami kekurangan energi dan protein. Balita
penderita gizi kurang membutuhkan makanan yang mengandung energi dan
protein yang tinggi sehingga diperlukan biskuit dengan kandungan energi dan
protein yang tinggi. Oleh karena itu, digunakan bahan pangan dengan
kandungan energi yang tinggi berupa tepung ubi kayu dan tepung ubi jalar
sebagai pensubstitusi tepung terigu yang merupakan salah satu sumber energi
dalam pembuatan biskuit.
Tepung ubi kayu dan tepung ubi jalar adalah bahan pangan yang memiliki
DKBM dalam Depkes (1981 & 2007), kandungan energi tepung ubi kayu adalah
363 kkal per 100 gram bahan pangan. Adapun kandungan energi tepung ubi jalar
menurut Food Composition Table for use in East Asia dalam FAO (2011) adalah
339 kkal per 100 gram.
Tepung ubi kayu dan ubi jalar meskipun memiliki kandungan energi yang
tinggi, namun memiliki kandungan protein yang rendah. Menurut Daftar
Komposisi Bahan Makanan atau DKBM dalam Depkes (1981 & 2007),
kandungan protein tepung kasava adalah 1,1 gram per 100 gram bahan pangan.
Adapun kandungan protein tepung ubi jalar menurut Food Composition Table for
use in East Asia dalam FAO (2011) adalah 2,85 gram per 100 gram. Oleh karena itu, diperlukan tambahan bahan pangan lain untuk meningkatkan kandungan
protein biskuit. Pada penelitian ini, bahan pangan yang digunakan untuk
meningkatkan kandungan protein biskuit adalah isolat protein kedelai.
Isolat protein kedelai adalah bentuk protein yang paling murni karena
minimal mengandung 90% protein berdasarkan berat kering (Astawan 2009).
Jenis protein yang dipilih dalam pembuatan biskuit adalah isolat protein kedelai
karena sifat fungsionalnya jauh lebih baik dibanding konsentrat protein maupun
tepung atau bubuk kedelai. Hal ini dikarenakan isolat protein kedelai adalah
suatu produk berbentuk tepung halus yang hampir bebas dari karbohidrat, serat,
dan lemak (Koswara 1995).
Anak yang mengalami masalah kurang gizi biasanya mengalami
kekurangan mineral besi dan seng dalam tingkat yang berat, sehingga diperlukan
intervensi untuk mengatasi masalah kekurangan mineral besi dan seng melalui
penambahan dalam bahan makanan yang dikonsumsinya (fortifikasi). Pada
penelitian ini, digunakan mutivitamin mineral dengan merek gizikita untuk
meningkatkan kandungan besi dan seng pada biskuit. Gizikita adalah suplemen
multivitamin dan mineral untuk anak berusia 2-5 tahun (Sarihusada 2012).
Mineral besi dan seng yang terkandung di dalam gizikita tinggi karena dalam
setiap sachet (5 g) gizikita mampu memenuhi 50% AKG.
Penggunaan mineral besi dan seng secara bersamaan dapat
menyebabkan interaksi yang pada akhirnya menyebabkan penurunan
bioavailabilitas salah satu dari mineral tersebut sehingga fortifikasi tidak
mencapai sasaran (Kustiyah et al. 2010). Oleh karena itu, mineral besi dan seng
perlu dimikroenkapsulasi sebelum difortifikasi ke biskuit agar fortifikasi kedua
tersalut oleh bahan pengisi sehingga interaksi kedua mineral tersebut dapat
dikurangi. Selain itu, mikroenkapsulasi juga dapat mengurangi bau tidak sedap
yang timbul karena penggunaan mineral besi (Kustiyah et al. 2010).
Multivitamin dan mineral dalam gizikita berada dalam bentuk mikrokapsul
sehingga dapat dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tanpa mengubah
rasa. Berdasarkan alasan-alasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
formulasi biskuit yang disubstitusi oleh tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan
penambahan isolat protein kedelai serta multivitamin mineral (gizikita) untuk
balita gizi kurang.
Tujuan Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat formula biskuit yang
disubstitusi tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan penambahan isolat protein
kedelai serta multivitamin mineral sebagai makanan tambahan untuk balita gizi
kurang.
Tujuan Khusus
Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:
1. Mempelajari pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar
2. Membuat formula biskuit balita gizi kurang (BGK)
3. Menguji daya terima serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap penilaian organoleptik
4. Menganalisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia biskuit formula
terpilih dan kontrol
5. Menganalisis keberadaan perbedaan gross energy, sifat fisik, dan sifat
kimia antara biskuit formula terpilih dan kontrol
Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam
menanggulangi masalahan gizi kurang pada balita di Indonesia melalui
pengembangan produk biskuit. Produk biskuit tersebut disubstitusi dengan
tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan penambahan isolat protein kedelai serta
multivitamin mineral yang tinggi energi, protein, besi, dan seng.
TINJAUAN PUSTAKA
Gizi Kurang
Gizi kurang adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya
asupan zat gizi makro dan mikro (vitamin dan mineral) dalam jangka waktu lama
(Kustiyah et al. 2010). Berdasarkan penelitian Widya (2012), rata-rata konsumsi
energi dalam sehari pada balita gizi kurang di Kabupaten Sukabumi sebesar
706±188,7 Kal dan tingkat kecukupan energinya sebesar 45,55%. Adapun
rata-rata konsumsi proteinnya dalam sehari sebesar 17,3±4,3 g dan tingkat
kecukupan proteinnya sebesar 44,36%. Menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat
(2006), seorang anak disebut menderita gizi kurang jika hasil penilaian status gizi
secara antropometri (BB/U, TB/U, dan BB/TB) menunjukkan -2 sampai -3 SD.
Adapun jika dinilai secara klinis, anak tersebut tampak kurus. Menurut Kustiyah
et al. (2010), anak gizi kurang biasanya kekurangan energi protein (KEP), menderita anemi gizi besi (AGB), dan kekurangan mineral seng.
Kurang Energi Protein (KEP) adalah salah satu masalah gizi kurang
akibat konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein
serta karena gangguan kesehatan. Balita adalah salah satu golongan yang
rawan kekurangan gizi, termasuk KEP. Penyebab KEP digolongkan menjadi dua,
yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung
berupa faktor makanan yang tidak memenuhi kebutuhan anak akan energi dan
protein serta faktor infeksi. Adapun penyebab tidak langsung berupa ketahanan
pangan yang rawan di keluarga, pola pengasuhan anak yang kurang baik,
pelayanan kesehatan yang kurang dapat dijangkau, dan lingkungan yang tidak
sehat (Soekirman 2000).
Pada gizi kurang, KEP berdampak pada penurunan status gizi anak dari
bergizi baik atau normal menjadi bergizi kurang (Soekirman 2000). Keadaan gizi
kurang menunjukkan kejadian tubuh pendek (stunting) tingkat sedang dan
pelisutan tubuh (wasting) tingkat sedang. Stunting tingkat sedang ditunjukkan
dengan tinggi badan menurut usia (BB/U) -2 sampai -3 SD. Adapun wasting
tingkat sedang ditunjukkan dengan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) -2
sampai -3 SD (Gibney et al. 2009).
Berdasarkan cut off point Depkes (1996), prevalensi balita gizi kurang
digolongkan menjadi bebas masalah kesehatan masyarakat (<5%), masalah
kesehatan masyarakat kategori ringan (5 - 9,9%), masalah kesehatan
kategori berat (≥ 20%). Konsekuensi dari KEP adalah pertumbuhan dan
perkembangan yang lebih lambat pada anak-anak (Hull & Johnston 2008).
Bahkan menurut Soekirman (2000), KEP berdampak terhadap kematian anak.
Anak yang mengalami masalah kurang gizi biasanya mengalami
kekurangan mineral besi dan seng dalam tingkat yang berat. Keadaan kurang
besi terjadi secara perlahan-lahan dan berlanjut melewati beberapa tingkatan
sebelum sampai kepada anemi (Kustiyah et al. 2010). Anemi Gizi Besi (AGB)
adalah suatu keadaan dimana terjadi penurunan cadangan besi yang sangat
parah di dalam hati sehingga jumlah hemoglobin darah menurun di bawah
normal (Soekirman 2000).
Prevalensi AGB ditentukan oleh kadar hemoglobin dalam darah. Titik cut
off point kadar hemoglobin darah digunakan untuk mendefinisikan anemia yang berbeda menurut usia (Gibney MJ et al. 2009). Anak yang berumur 6 bulan
sampai 5 tahun dinyatakan menderita AGB jika kadar hemoglobinnya kurang dari
11 gram/dl (Soekirman 2000). Berdasarkan cut off point Depkes (1996),
prevalensi anemi balita digolongkan menjadi masalah ringan (<15%), masalah
sedang (15 – 40%), dan masalah berat (≥ 40%). Menurut Soekirman (2000),
AGB berdampak terhadap keluhan fisik (cepat lelah), kematian bayi,
keterlambatan pertumbuhan fisik anak, keterbelakangan perkembangan mental
dan motorik, serta gangguan perilaku sosial dan emosional anak.
Menurut Soekirman (2000), masalah kekurangan mineral seng atau
defisiensi zinc (Zn) merupakan masalah zat gizi mikro yang termasuk pendatang
baru dalam perkembangan ilmu gizi. Menurut Gibney MJ et al. (2009), prevalensi
defisiensi Zn tidak diketahui, tetapi keadaan ini lazim ditemukan dalam populasi
yang mengonsumsi sedikit daging dan memakan makanan dengan kandungan
fitat serta serat yang tinggi sehingga mengurangi bioavailabilitas Zn. Pola makan
seperti ini sangat sering dijumpai di banyak negara berkembang. Zn juga hilang
dari tubuh ketika terjadi penyakit diare. Kebutuhan Zn meningkat selama periode
pertumbuhan yang cepat seperti pada bayi. Oleh karena itu, kemungkinan
terdapatnya defisiensi Zn pada banyak negara berkembang sangat besar karena
anak-anak kecil menunjukkan pola makan yang buruk dan penyakit diare yang
sering terjadi (Soekirman 2000).
Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz)
Ubi kayu merupakan tanaman tropis yang termasuk ke dalam divisi
kelas Dicotyledonae (biji berkeping dua), ordo Euphorbiales, dan famili Euphorbiaceae (Deptan 2011). Menurut sejarah botani, ubi kayu berasal dari Brazil kemudian menyebar ke Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok, dan
beberapa negara yang terkenal daerah pertaniannya. Ubi kayu masuk ke
Indonesia pada abad ke 18 dengan mendatangkan plasma nutfah dari Suriname
(Rukmana R 1997). Ubi kayu di Indonesia memiliki beberapa nama daerah, yaitu
ketela pohon, singkong, ubi jenderal, ubi inggris, telo puhung, boled, bodin, telo
jenderal, dan kaspe (Jawa); sampeu, huwidangdeur, dan huwi jenderal (Sunda); kasbek (Ambon); serta ubi perancis (Padang).
Tanaman ubi kayu memiliki tinggi 1,5 – 4 m. Batangnya tumbuh tegak
beruas, berkayu, dan berbuku-buku. Warna batangnya hijau muda, setelah tua
berubah menjadi putih kelabu atau hijau kelabu. Daunnya menjari, tumbuh di
sepanjang batang dengan tangkai yang agak panjang. Umbinya mempunyai
warna kulit coklat, kelabu, atau kombinasi dari kedua warna tersebut. Bentuk
umbi antara besar memendek atau kecil memanjang. Daging umbi berwarna
putih atau kuning (Wargiono 1979 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992). Bentuk
umbi kayu dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Ubi kayu
Tanaman ubi kayu umumya ditanam di daerah-daerah berlahan kering
dengan sistem pengairan tadah hujan (Soetanto 2008). Tanaman ini memiliki
berbagai macam keunggulan, yaitu: masih dapat tumbuh di daerah yang kurang
subur bahkan tandus, pertumbuhannya sangat baik, dan hasilnya cukup
melimpah (Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Soetanto (2008), Indonesia
termasuk salah satu negara utama penghasil ubi kayu setelah Brazil dan Zaire.
Bahkan Indonesia merupakan negara utama penghasil ubi kayu di kawasan
Asean. Menurut Deptan (2012), Provinsi Lampung adalah daerah penghasil ubi
kayu terbesar (24%), diikuti Jawa Timur (20%), Jawa Tengah (19%), Jawa Barat
(11%), Nusa Tenggara Timur (4,5%), dan DI Yogyakarta (4,2%).
Ubi kayu mengandung senyawa kimia yang tergolong cyanogenic
glycoside yang disebut linamarin. Senyawa ini dapat menghasilkan HCN yang dikenal dengan sebutan racun biru karena dapat menyebabkan gejala keracunan
(Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Kadarisman & Sulaeman (1992), ubi
kayu dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan kandungan HCN-nya, yaitu:
a. Jenis yang tidak beracun (ubi kayu manis)
Kandungan HCN ubi kurang dari 50 mg/kg umbi basah kupas. Jenis ini
aman untuk dikonsumsi secara langsung.
b. Jenis setengah beracun (ubi kayu agak pahit)
Kandungan HCN ubi antara 50-100 mg/kg umbi basah kupas. Jenis ini
tidak disarankan untuk dikonsumsi secara langsung.
c. Jenis sangat beracun (ubi kayu pahit)
Kandungan HCN ubi lebih dari 100 mg/kg umbi basah kupas. Jenis ini
dilarang untuk dikonsumsi secara langsung, namun harus diolah dulu
atau dibuat produk olahan lain yang dalam prosesnya dapat
memungkinkan terlarutnya atau hilangnya racun sianida tersebut.
Hampir semua bagian dari ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan
makanan. Namun, hasil utama ubi kayu adalah umbinya (Rukmana & Yuniarsih
2001). Umbi ubi kayu umumnya dapat dipanen saat tanaman berumur 6-12
bulan. Setiap tanaman umumnya dapat menghasilkan 5-25 kg umbi, tergantung
jenis dan tingkat kesuburan tanahnya (Soetanto 2008). Menurut Kadarisman &
Sulaeman (1992), umbi ubi kayu merupakan makanan sumber energi (kalori) dan
karbohidrat. Sayangnya umbi ketela segar hanya dapat disimpan 4-5 hari. Oleh
karena itu, sangat diperlukan upaya pengolahan umbi ubi kayu menjadi berbagai
macam produk olahan agar dapat memperpanjang daya simpannya dan
meningkatkan harga jualnya. Contoh produk olahan umbi ubi kayu adalah tepung
ubi kayu, tepung gaplek, dan tepung tapioka (Soetanto 2008).
Tepung Ubi Kayu
Ubi kayu segar dapat diolah menjadi tiga macam bentuk tepung, yaitu
tepung ubi kayu (cassava flour), tepung gaplek (cassava chip flour), dan tepung
tapioka (tapioca starch) (Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Soetanto
(2008), tepung ubi kayu (tepung kasava) merupakan tepung kering berwarna
putih yang diolah dari ubi kayu segar melalui beberapa tahap pemrosesan.
Tepung ubi kayu dibuat tanpa adanya penambahan bahan pengawet, bahan
pewarna, ataupun bahan perasa sehingga tepung ubi kayu memiliki rasa gurih
dan memiliki aroma khas ketela asli. Daerah penghasil utama tepung ubi kayu di
Indonesia adalah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa
memiliki beberapa syarat mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional
Indonesia (SNI 01-2997-1992), seperti yang tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1 Syarat mutu tepung ubi kayu menurut SNI 01-2997-1992
No Uraian Satuan Persyaratan
1 2 3 4
1 Keadaan
1.1 Bau Khas singkong
1.2 Rasa Khas singkong
1.3 Warna Putih
2 Benda-benda asing Tidak boleh ada
3 Derajat putih %, b/b Minimal 85
10 Bahan tambahan makanan Sesuai SNI 01-0222-1995
11 Cemaran logam
11.1 Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 1,0
11.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 10,0
11.3 Seng (Zn) mg/kg Maksimal 40,0
11.4 Raksa (Hg) mg/kg Maksimal 0,05
12 Arsen (As) mg/kg Maksimal 0,5
13 Cemaran mikroba
13.1 Angka lempeng total -koloni/gram Maksimal 1,0x106
13.2 E. Coli APM/gram Maksimal< 3
12.3 Kapang -koloni/gram Maksimal 1,0x104
Sumber: DSN (1992)
Pengolahan ubi kayu menjadi tepung ubi kayu merupakan alternatif
utama dengan prospek yang cukup baik. Hal ini dikarenakan pengolahannya
cukup sederhana, tidak mudah rusak, dapat disimpan lebih lama, memberikan
nilai tambah yang lebih tinggi, dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan,
serta berfungsi sebagai subtitusi tepung terigu (Madethen 1989 dalam
Kadarisman & Sulaeman 1992). Tabel 2 menunjukkan komposisi zat gizi tepung
ubi kayu per 100 gram bahan.
Tabel 2 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu
No Komponen Jumlah
1 Energi 363 Kal
Tepung ubi kayu bahan pangan yang memiliki kandungan energi yang
tinggi. Menurut Daftar Komposisi Bahan Makanan atau DKBM dalam Depkes
(1981 & 2007). Kandungan energi tepung ubi kayu adalah 363 kkal per 100 gram
bahan pangan. Tepung ubi kayu juga merupakan sumber karbohidrat yang
cukup baik karena per 100 gram bahan pangan terkandung karbohidrat sebesar
82 g. Dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain (beras, jagung, gandum),
tepung ubi kayu mempunyai kandungan serat yang cukup tinggi dan kandungan
gula yang rendah (Soetanto 2008).
Tepung ubi kayu hanya sedikit mengandung protein dan tidak
mengandung protein gluten yang selalu dibutuhkan dalam proses
pengembangan adonan mie, roti, kue, dan biskuit. Tidak adanya gluten tersebut
mengakibatkan produk kue dan biskuit menjadi keras atau kaku. Oleh karena itu,
pemanfaatan tepung ubi kayu untuk produk pangan biasanya dikombinasikan
dengan tepung terigu atau tepung lain yang dikenal sebagai tepung campuran
atau composite flour (Wirakartakusumah et. al 1989 dalam Marlina 2001). Selain
itu, penggunaan ubi kayu sebagai bahan pangan utama sebaiknya
dikombinasikan dengan bahan pangan lain yang banyak mengandung protein
seperti kacang-kacangan (Marlina 2001).
Ubi Jalar (Ipomoea batatas)
Ubi jalar termasuk ke dalam divisi Spermatophyta (tumbuhan berbiji),
subdivisi Angiospermae (berbiji tertutup), kelas Dicotyledonae (biji berkeping
dua), ordo Convolvulales, dan famili Convolvulaceae (suku
kankung-kangkungan) (Juanda & Cahyono 2000). Ubi jalar berasal dari daerah tropik dan
subtropik Amerika kemudian menyebar ke daerah tropik dan subtropik lainnya
(Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut sejarah botani, ubi jalar berasal dari
Amerika bagian tengah kemudian menyebar ke Spanyol melalui Tahiti,
Kepulauan Guam, Fiji, dan Selandia Baru. Ubi jalar dibawa masuk ke Indonesia
oleh orang Spanyol pada abad ke 16 (Rukmana 1997). Menurut Suprapti (2003),
ubi jalar di Indonesia memiliki beberapa nama daerah, yaitu telo rambat (Jawa
Tengah dan Jawa Timur) dan huwi bolet (Jawa Barat)
Tanaman ubi jalar memiliki batang menjalar 1-5 meter, berdiameter 3-10
mm, dan dalamnya bergetah. Pada batang tumbuh daun-daun dengan warna
dan bentuk yang bermacam-macam. Pada ketiak daun tumbuh beberapa akar
penampakan bunga mirip dengan bunga morning glories (Kadarisman &
Sulaeman 1992).
Umbi tanaman ubi jalar sebenarnya adalah akar yang membesar dan
menyimpan cadangan makanan bagi tanaman. Bentuknya antara lonjong sampai
agak bulat. Warna kulit umbi bervariasi, ada yang putih kotor, kuning, merah
muda, jingga, dan ungu tua. Warna daging juga bervariasi, ada yang putih, krem,
merah muda, kekuning-kuningan, jingga, dan keungu-unguan. Hal ini tergantung
pada jenis dan banyaknya pigmen yang terdapat di dalam kulit. Pigmen yang
terdapat dalam umbi ubi jalat adalah karotenoid dan antosianin (Steinbaurer &
Kushman 1971 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992). Bentuk umbi ubi jalar
dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Ubi jalar
Tanaman ubi jalar paling baik ditanam di tanah yang tingkat
kesuburannya sedang. Tanaman ini memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu:
dapat tumbuh di sembarang tanah dan sembarang tempat, dapat dihasilkan
dalam waktu relatif singkat (waktu tanam cepat), dan hasilnya melimpah
(Kadarisman & Sulaeman 1992 serta Suprapti 2003). Indonesia merupakan
negara produsen ubi jalar ketiga di dunia setelah RRC dan Vietnam (Woolfe
dalam Deptan 2012b). Sentra produksi utama ubi jalar di Indonesia adalah
Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, NTT, dan
Papua (BPS 2008 dalam Deptan 2012b).
Bagian dari ubi jalar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan
adalah umbinya (Purwono & Purnamawati 2007). Menurut Kadarisman &
Sulaeman (1992), umbi ubi kayu umumnya dapat dipanen saat tanaman berumur
4-6 bulan bagi ubi jalar berumur pendek dan 8-9 bulan bagi ubi jalar berumur
panjang. Ubi jalar mempunyai potensi yang besar sebagai bahan pangan sumber
karbohidrat (Kadarisman & Sulaeman 1992). Meskipun ubi jalar adalah sumber
karbohidrat, namun ubi jalar memiliki indeks glikemik yang rendah (Marwati
2011).
Sampai saat ini pemanfaatan ubi jalar masih terbatas sebagai bahan
dikembangkan lagi apabila diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku
bagi industri lain (Destialisma 2012). Pengolahan ubi jalar menjadi bahan
setengah jadi, seperti tepung ubi jalar, dapat memperpanjang masa simpan dan
meningkatkan nilai ekonomi (Marwati 2011). Ubi jalar sangat cocok digunakan
sebagai bahan baku agroindustri tepung karena: (1) tanaman ubi jalar berumur
pendek, jangka waktu penanaman sampai panen kurang lebih hanya memakan
waktu 4-5 bulan; (2) jumlah produksi per hektar relatif tinggi (15-30 ton/hektar);
(3) belum terlalu banyak dimanfaatkan untuk industri; (4) harga produksi relatif
rendah yang akan berimplikasi pada harga jual produk rendah tetapi tetap
menguntungkan petani (Destialisma 2012).
Tepung Ubi Jalar
Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan sebagian
airnya (Widjanarko 2008). Tepung ubi jalar tersebut dapat dibuat secara
langsung dari ubi jalar yang dihancurkan dan kemudian dikeringkan, tetapi dapat
pula dibuat dari gaplek ubi jalar yang dihaluskan (digiling) dengan tingkat
kehalusan ± 80 mesh (Suprapti 2003). Tepung ubi jalar memiliki beberapa syarat
mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI (1996) dalam
Widjanarko (2008), seperti yang tercantum pada Tabel 3.
Tabel 3 Syarat mutu tepung ubi jalar menurut SNI 1996
No Uraian Satuan Persyaratan
1 2 3 4
1 Abu %, b/b Maksimal 2
2 Air %, b/b Maksimal 15
3 Derajat asam ml N NaOH/100 g Maksimal 4
4 Pati %, b/b Minimal 55
5 Serat %, b/b Maksimal 3
Sumber: Widjanarko (2008)
Pembuatan tepung ubi jalar adalah salah satu jenis pengolahan yang
penting (Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Wiriano et al. (1985) dalam
Kadarisman & Sulaeman (1992), pengolahan ubi jalar menjadi tepung ubi jalar
dapat mengurangi jumlah umbi yang rusak atau tercecer sehingga dapat
menambah persediaan pangan, khususnya karbohidrat, serta menunjang
penganekaragaman jenis serta mutu gizi masyarakat. Tepung ubi jalar bersifat
stabil, tahan lama disimpan, serta praktis dalam pengangkutan dan penyimpanan
(Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut penelitian Yusuf et al. (1985) dalam
Kadarisman & Sulaeman (1992), tepung ubi jalar yang disimpan selama 9 bulan
masih berwarna putih, tanpa ditumbuhi jamur, dan mempunyai rasa yang normal.
dapat diperdagangkan antarprovinsi bahkan sebagai komoditas ekspor
(Destialisma 2012).
Tabel 4 menunjukkan komposisi zat gizi tepung ubi jalar per 100 gram
bahan.
Tabel 4 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu
No Komponen Jumlah
1 Energi* 339 Kal
2 Protein 2,85 g
3 Lemak 0,45 g
4 Karbohidrat 79,36 g
5 Kalsium (Ca)* 50,00 g
6 Fosfor (P)* 95,00 g
7 Besi (Fe)* 2,00 g
8 Vitamin B1* 0,24 g
9 Air 4,50 g
10 Abu 2,05 g
Sumber: Anwar, Sulaeman, & Setiawan (1993)
*Food composition table for use in East Asia dalam FAO (2012)
Tepung ubi jalar memiliki kandungan energi yang tinggi, yaitu 339 g per
100 gram bahan pangan (Food composition table for use in East Asia dalam FAO
2012). Berdasarkan penelitian Anwar et al. (1993), tepung ubi jalar merupakan
sumber karbohidrat yang cukup baik karena per 100 gram bahan pangan
terkandung karbohidrat sebesar 79,36 g. Akan tetapi kandungan proteinnya
rendah, yaitu 2,85 g per 100 gram bahan pangan (Anwar et al. 1993).
Pengolahan ubi jalar menjadi tepung ubi jalar merupakan salah satu cara
untuk membuka peluang pemanfaatan ubi jalar secara lebih luas dan bervariasi.
Bahan pangan dalam bentuk tepung biasanya lebih mudah dan lebih fleksibel
penggunaannya. Bentuk ini dapat diolah menjadi beranekaragam bahan pangan
atau produk lainnya (Kadarisman & Sulaeman 1992). Tepung ubi jalar dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi pembuatan kue kering, kue basah, mie,
bahan aditif, dan lain-lain (Destialisma 2012).
Berdasarkan penelitian Anwar et al. (1993), tepung ubi jalar dapat
mensubtitusi tepung terigu dalam pembuatan biskuit dan cookies sampai 80%.
Akan tetapi, dalam pengembangan produk kaya protein yang bergizi tinggi harus
diupayakan untuk mencampur tepung ubi jalar dengan sumber lain yang tinggi
protein mengingat kandungan proteinnya yang rendah. Disamping itu, nutrifikasi
mineral-mineral yang kandungannya rendah atau tidak ada sama sekali perlu
Isolat Protein Kedelai
Isolat protein kedelai (IPK) adalah suatu produk berbentuk tepung halus
yang hampir bebas dari hampir bebas dari karbohidrat, serat, dan lemak
(Astawan 2009). Sebagian besar komponen penyusun kedelai dihilangkan
sehingga tinggal protein (Winarsi 2010). IPK merupakan bentuk protein kedelai
yang paling murni, yaitu minimal mengandung 90% protein berdasarkan berat
kering (Astawan 2009).
IPK dibuat dengan cara melarutkan protein tepung kedelai dengan larutan
basa encer pada pH 7-9 kemudian membuang endapan tidak larutnya dengan
cara pemusingan atau penyaringan. Ekstrak yang didapat kemudian diasamkan
sampai pH-nya mencapai 4,5 agar terjadi pengendapan protein. Endapan protein
ini selanjutnya dinetralkan dengan basa dan dikeringan dengan pengering
semprot (spray dryer) sampai diperoleh bentuk tepung (Astawan 2009).
Sifat-sifat fungsional IPK jauh lebih baik dibandingkan dengan konsentrat
protein maupun tepung atau bubuk kedelai (Astawan 2009). IPK kaya protein,
berwarna agak mengkilat, dan memiliki flavour ringan. IPK memiliki flavour yang
lebih netral dibandingkan konsentrat protein kedelai karena dalam
pembuatannya semua komponen karbohidrat dihilangkan sehingga flavour
kedelai juga hilang.
IPK merupakan protein kedelai yang serbaguna. IPK dapat digunakan
secara luas dalam produk pangan pabrikan maupun aplikasinya dalam pangan
fungsional (Winarsi 2010). IPK baik sekali digunakan dalam formulasi makanan
karena dapat berfungsi sebagai pengikat dan pengemulsi. Selain itu, IPK dapat
berfungsi sebagai zat aditif untuk memperbaiki penampakan, tekstur, serta
flavour produk. Penggunaan IPK sangat luas, diantaranya dapat dipakai dalam pembuatan keju, susu, es krim, daging sintetik, roti, dan biskuit (Koswara 1995).
IPK memiliki kemampuan daya serap air yang tinggi karena protein
kedelai bersifat hidrofilik (suka air) dan mempunyai celah-celah polar seperti
gugus karboksil dan amino yang dapat mengion. Adanya kemampuan mengion
ini menyebabkan daya serap IPK dipengaruhi oleh pH makanan. Daya serap IPK
sangat penting peranannya dalam makanan panggang (baked goods) karena
dapat meningkatkan rendemen adonan dan memudahkan penanganannya.
Selain itu, sifat menahan air akan memperlama kesegaran makanan, misalnya
Gizikita
Gizikita merupakan produk suplemen multivitamin mineral untuk anak berusia 2-5 tahun yang diproduksi oleh PT Sari Husada. Gizikita dibuat untuk
membantu melengkapi gizi anak setiap hari. Suplemen ini dibuat dari protein
whey, maltodekstrin, vitamin, dan mineral (Sari Husada 2011). Suplemen ini
mengandung zat besi, kalsium, seng, yodium, selenium, vitamin (A, D, E, K, C,
B1, B2, B3, B6, B12), asam folat, asam pantotenat, natrium, protein, dan
karbohidrat
Gizikita tersedia dalam kemasan sachet 5 gr (Sari Husada 2011). Dalam
setiap sachetnya mampu memenuhi 50% AKG zat besi, seng, yodium, dan
kalsium; 45% AKG vitamin A, D, dan E; 40% AKG vitamin C, K, B1, B3, B6, B12,
asam folat, asam pantotenat, dan selenium; serta 15% AKG vitamin B2. Cara
mengonsumsi gizikita adalah dengan cara ditaburkan atau dicampurkan ke
makanan ataupun minuman. Meskipun gizikita dicampurkan ke dalam makanan
ataupun minuman tapi tidak akan mengubah rasa (Sari Husada 2011).
Mineral
Mineral merupakan bahan inorganik (unsur abu) yang mempunyai fungsi
fisiologis di dalam tubuh. Mineral dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu (Kustiyah
& Marliyati 2008 dalam Nasoetion & Damayanthi 2008):
a. Mineral makro
Mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah ≥ 100 mg per hari. Mineral
makro terdapat ≥ 0,01% di dalam tubuh. Mineral makro meliputi kalsium,
fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan klor.
b. Mineral mikro
Mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah < 100 mg per hari. Mineral
mikro diperlukan tubuh < 0,01% dari berat badan total. Mineral mikro
diantaranya meliputi besi dan seng.
Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96% terdiri dari bahan
organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga
dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran,
bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak, karena itulah disebut abu
(Winarno 1982 dalam Dewi 2011). Kandungan mineral yang terkandung dalam
bahan makanan dan minuman dapat berkurang atau hilang karena proses
dan baking merupakan proses-proses yang dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan mineral dari bahan pangan (Smith 1989 dalam Alfitra 2009).
Zat Besi (Fe)
Zat besi adalah salah satu zat gizi penting yang terdapat pada setiap sel
hidup (Soekirman 2000).Tubuh manusia terdiri dari 3-4 gram zat besi sebagai
bagian dari protein yang bernama hemoglobin yang terdapat di sel darah merah
(lebih dari 65%) dan myoglobin di sel-sel otot (Soekirman 2000 dan Devi 2010).
Tempat penyimpanan atau cadangan utama zat besi adalah hati. Zat besi yang
disimpan di hati dikirim ke sel darah merah melalui sumsum tulang belakang
(Soekirman 2000). Jumlah besi dalam tubuh manusia berhubungan dengan berat
badan serta kondisi fisiologi seperti usia, jenis kelamin, kehamilan, dan masa
pertumbuhan.
Zat besi berfungsi membantu hemoglobin mengangkut oksigen,
membantu myoglobin menyimpan oksigen, membantu berbagai macam enzim
dalam mengikat oksigen untuk pembakaran (membantu metabolisme energi
sebagai kofaktor enzim-enzim), berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, dan
pelarut obat-obatan (Soekirman 2000 dan Almatsier 2006). Angka kecukupan zat
besi bagi anak yang berumur 4-5 tahun adalah 8 mg/hari (WNPG 2004 dalam
Kustiyah et al. 2010). Bila anak kekurangan zat besi atau menderita AGB dapat
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan, menurunkan
kemampuan intelektual dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh
(Kustiyah et al. 2010).
Zat besi diperoleh dari luar tubuh berupa makanan atau suplemen. Zat
besi dalam makanan ada yang berbentuk zat besi heme dan zat besi nonheme.
Zat besi heme terdapat dalam daging, ayam, dan ikan. Adapun dan zat besi
nonheme terdapat dalam susu, telur, beras, sereal, sayuran, dan buah-buahan. Dalam memilih makanan sumber zat besi, perlu diperhatikan jumlahnya yang
terdapat dalam makanan, daya serap, dan nilai biologisnya. Makanan yang
mengandung banyak zat besi yang mudah diserap dan nilai biologinya tinggi
adalah makanan dari hewan (hati, daging, ayam, dan ikan). Zat besi heme lebih
mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi nonheme.
Daya serap dan nilai biologi zat besi makanan dipengaruhi oleh jumlah
kandungan zat besi, bentuk kimia-fisik zat besinya, adanya makanan atau zat
lain yang memacu atau menghambat absorbsi zat besi, dan cara pengolahan
vitamin C, asam sitrat, asam malat, asam tartarat, dan asam amino cistein.
Adapun zat yang aktif menghambat penyerapan zat besi (inhibitor) adalah pitat,
polipenol, kalsium, dan fosfat (Soekirman 2000). Seng (Zn)
Total seng dalam tubuh kita adalah 1,5 – 2,5 g. Seng sebagian besar ada
dalam tulang dan tidak dapat digunakan untuk metabolisme (Linder 2006 dalam
Taufiqurrahman 2009). Almatsier (2004) merincikan lagi bahwa seng sebagian
besar berada di dalam hati, pankreas, ginjal, otot dan tulang. Jaringan yang
banyak mengandung seng adalah bagian mata, kelenjar prostat, spermatazoa,
kulit rambut, dan kuku.
Seng berperan penting dalam pembentukan enzim, pertumbuhan, fungsi
imun, kematangan seksual, pertumbuhan rambut, dan mempercepat
penyembuhan luka, gangguan perilaku, serta depresi (Smith 1988 dalam
Kustiyah et al. 2010). Selain itu, seng diperlukan untuk sintesa DNA, pergantian
sel, dan sintesa protein (Firmansyah 2004 dalam Taufiqurrahman 2009). Linder
(2006 dalam Taufiqurrahman 2009) juga menyebutkan bahwa seng juga
berperan dalam reaksi-reaksi yang berkaitan dengan sintesis dan degradasi
karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat. Studi yang dilakukan pada
anak-anak telah membuktikan peranan penting dari seng dalam hubungannya dengan
fungsi meningkatkan pertumbuhan pada anak yang stunting dan gizi buruk
(Brown 2002 diacu dalam Taufiqurrahman 2009).
Angka kecukupan seng bagi anak yang berumur 4-5 tahun adalah 9,7
mg/hari (WNPG 2004 dalam Kustiyah et al. 2010). Kekurangan seng dapat
menyebabkan terganggunya pembentukan enzim tertentu yang berperan dalam
metabolisme zat gizi, seperti dalam metabolisme protein dan lemak, sehingga
akan menghambat pertumbuhan (Smith 1988 dalam Kustiyah et al. 2010).
Makanan sumber seng adalah daging tanpa lemak (dada ayam & sirloin),
seafood (kerang, kepiting, tiram, ikan tuna, dan kacang-kacangan (Wirakusumah
2004). Penyerapan seng makanan berkisar antara 14-41% (Solomon 1985
dalam Kustiyah et al. 2010). Adapun Prasad (1985 dalam Kustiyah et al. 2010)
menyatakan bahwa penyerapan seng berkisar antara 20-30%. Ada beberapa
faktor yang dapat membantu dan menghambat penyerapan seng. Faktor yang
dapat membantu penyerapan seng diantaranya adalah zat yang berbobot
molekul tinggi seperti metionin, histidin, sistein, dan sitrat (Sanstead & Evan 1984
menjadi faktor penghambat organik dan anorganik. Faktor penghambat organik
penyerapan seng adalah fitat, hemiselulosa, lignin, dan oksalat (Sanstead &
Evan 1984 dan Prasad 1985 dalam Kustiyah et al. 2010). Adapun faktor
penghambat anorganiknya adalah kadmium, tembaga, fosfat, kalsium, dan besi
nonheme (Sanstead & Evan 1984 dalam Kustiyah et al. 2010).
Penelitian tentang interaksi antara mineral besi dan seng sudah banyak
dilakukan dan beberapa peneliti menemukan bahwa terjadi interaksi antara
keduanya selama pencernaan (Kustiyah et al. 2010). Penyerapan seng
berkompetisi dengan penyerapan zat besi (Linder 2006 dalam Taufiqurrahman
2009). Dosis tinggi zat besi yang diberikan akan mempengaruhi penyerapan
seng. Pada rasio besi : seng sebesar 40:1 menunjukkan bahwa penyerapan
seng dapat berkurang sampai 40%. Konsumsi besi dan seng yang tidak
seimbang dapat berakibat pada berkurangnya penyerapan seng dan lebih lanjut
dapat menyebabkan terjadinya kekurangan seng yang nyata (Kustiyah et al.
2010).
Makanan Balita
Anak balita adalah anak-anak yang berumur di bawah lima tahun. Anak
balita merupakan salah satu sasaran utama program gizi (Wiyati 2004 dalam
Mervina 2009). Semakin meningkat usia anak balita, semakin meningkat pula
kebutuhan akan zat gizinya. Anak balita dibagi ke dalam empat golongan umur
berdasarkan angka kecukupan zat gizinya. Angka kecukupan gizi yang
dianjurkan untuk balita dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Angka kecukupan gizi balita (per orang per hari)
Zat gizi Golongan umur
0-6 bulan 7-11 bulan 1-3 tahun 4-6 tahun
Energi (Kal) 550,0 650,0 1000,0 1550,0
Protein (g) 10,0 16,0 25,0 39,0
Vitamin A (RE, µg) 375,0 400,0 400,0 450,0
Tiamin (mg) 0,2 0,4 0,5 0,8
Riboflavin (mg) 0,3 0,4 0,5 0,6
Piridoksin (mg) 0,1 0,3 0,5 0,6
Niasin (mg) 2,0 4,0 6,0 8,0
Vitamin B12 (mg) 0,4 0,5 0,9 1,2
Asam folat (mg) 65,0 80,0 150,0 200,0
Vitamin C (mg) 40,0 50,0 40,0 45,0
Kalsium (mg) 200,0 400,0 500,0 500,0
Fosfor (mg) 100,0 225,0 400,0 400,0
Besi (mg) 0,3 10,0 7,0 8,0
Seng (mg) 5,5 7,5 8,2 9,7
Iodium (µg) 90,0 120,0 90,0 120,0
Sejak usia tertentu, anak balita diberi makanan tambahan disamping ASI.
Makanan tambahan adalah makanan yang diberikan untuk membantu
mencukupi kebutuhan akan zat gizi yang diperlukan (Wiyati 2004 dalam Mervina
2009). FAO/WHO (1994) telah mengeluarkan petunjuk pengembangan formula
makanan bagi anak balita. Komposisi zat gizi dari formula makanan tambahan
untuk balita dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Komposisi zat gizi formula makanan tambahan balita
Zat gizi Jumlah per 100 g
Energi (Kal) 400,00
Protein (g) 15,00
Lemak (g) 10-25
Vitamin A (µg/RE) 266,70
Vitamin D (µg) 6,70
Vitamin E (mg) 3,30
Vitamin C (mg) 13,30
Tiamin (mg) 0,30
Riboflavin (mg) 0,50
Niasin (mg) 6,00
Vitamin B6 (µg) 0,60
Asam folat (µg) 33,30
Vitamin B12 (µg) 0,70
Kalsium (mg) 533,30
Besi (mg) 8,00
Seng (mg) 6,67
Sumber: FAO/WHO 1994
Biskuit
Biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan
penambahan bahan makanan lain dengan proses pemanasan dan pencetakan
(SNI 01-2973-1992 dalam DSN 1992b). Departemen Perindustrian (1990)
mendefinisikan biskuit sebagai produk makanan kering yang dibuat dengan
memanggang adonan yang mengandung bahan dasar terigu, lemak, dan bahan
pengembang dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan lain yang
diijinkan. Whiteley (1971 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992) menambahkan
bahwa pengertian biskuit harus memenuhi persyaratan, yaitu: dibuat dari bahan
serealia (seperti gandum, jagung, dan sebagainya), jika bahan utamanya kurang
dari 60% bukan serealia maka tidak disebut biskuit, mengandung kurang lebih
5% kadar air, jika diisi atau didekantasi dengan bahan lain (seperti krim, krim
gula, jelly, jam) maka kadar airnya melebihi 5%.
Biskuit yang baik harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam
Tabel 7 Syarat mutu biskuit menurut SNI 01-2973-1992
Komponen Syarat Mutu
Air Maksimum 5%
Protein Minimum 9%
Lemak Minimum 9,5%
Karbohidrat Minimum 70%
Abu Maksimum 1,5%
Logam berbahaya Negatif
Serat kasar Maksimum 0,5%
Kalori Minimum 400 Kal/100g
Jenis tepung Terigu
Bau dan rasa Normal, tidak tengik
Warna Normal
Sumber: DSN (1992b)
Menurut Charley (1982), biskuit yang bermutu baik adalah biskuit yang
memiliki lapisan kulit berwarna coklat keemasan dengan tanpa adanya
noda-noda coklat, bentuknya simetris, serta bagian atasnya rata dan halus. Selain itu,
remah-remahnya berwarna putih hingga putih krem, terasa halus, dan lunak.
Selain itu, menurut Matz dan Matz (1978), biskuit umumnya memiliki permukaan
agak licin, bentuk dan ukurannya seragam, kering, renyah, ringan, serta
aromanya menyenangkan.
Klasifikasi Biskuit
Biskuit dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu biskuit keras,
crackers, cookies, dan wafer. Biskuit keras adalah jenis biskuit manis yang dibuat dari adonan keras, berbentuk pipih, bila dipatahkan penampang potongannya
bertekstur padat, dapat berkadar lemak tinggi ataupun rendah. Crackers adalah
jenis biskuit yang dibuat dari adonan keras melalui proses fermentasi atau
pemeraman, berbentuk pipih, rasanya mengarah asin, dan relatif renyah.
Cookies adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah, bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang
padat. Adapun wafer adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair,
berpori-pori kasar, relatif renyah, dan bila dipatahkan penampang potongannya
berongga-rongga (SII 0177-90 dalam Departemen Perindustrian 1990).
Bahan-bahan Pembuat Biskuit
Bahan dalam pembuatan biskuit dibedakan menjadi bahan pengikat dan
bahan perapuh. Bahan pengikat berfungsi membentuk adonan yang kompak.
Bahan pengikat terdiri dari tepung, susu, putih telur, dan air. Adapun bahan
perapuh terdiri dari gula, lemak atau minyak (shortening), bahan pengembang,
Tepung. Tepung merupakan komponen pembentuk struktur dan pengikat telur (Sultan 1983 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Sunaryo
(1985), tepung berfungsi membentuk adonan selama proses pencampuran,
menarik atau mengikat bahan lainnya, serta mendistribusikannya secara merata.
Selain pembentuk struktur, tepung juga berperan penting dalam pembentukan
citarasa (Matz & Matz 1978). Matz & Matz (1978) menambahkan bahwa semua
jenis tepung dapat digunakan dalam pembuatan biskuit. Menurut Vail et al.
(1978), jenis tepung terigu yang cocok digunakan untuk pembuatan biskuit
adalah tepung terigu lunak dengan kadar protein 8%.
Susu. Fungsi susu dalam pembuatan biskuit adalah sebagai pembentuk warna karena terjadi reaksi pencoklatan, pembentuk flavor, pembentuk aroma,
penambah keempukan karena adanya laktosa, bahan pengisi, pengikat air, serta
pembentuk struktur yang kuat dan poros karena adanya protein berupa kasein.
Selain itu, susu dapat meningkatkan nilai gizi terutama kandungan energi biskuit
karena kandungan lemak dan laktosa. Susu bubuk lebih banyak digunakan
dalam pembuatan biskuit karena lebih mudah dalam penanganannya dan
memiliki daya simpan yang cukup lama (Matz & Matz 1978).
Air. Fungsi air dalam pembuatan biskuit adalah untuk mengontrol kepadatan adonan serta melarutkan dan menyebarkan bahan-bahan bukan
tepung secara merata agar terbentuk adonan yang mudah dicetak (Sunaryo
1985).
Telur. Menurut Matz & Matz (1978), telur dalam pembuatan biskuit berfungsi sebagai pengemulsi yang dapat membantu mempertahankan
kestabilan adonan serta meningkatkan dan menguatkan aroma, warna, dan
kelembutan. Penggunaan kuning telur akan menghasilkan biskuit yang empuk
dan mengembang.
Lemak. Lemak merupakan komponen penting dalam pembuatan biskuit karena berfungsi sebagai bahan pengemulsi sehingga menghasilkan tekstur
produk yang renyah (Matz & Matz 1978). Lemak juga berfungsi sebagai
penghalus dan pelunak tekstur sehingga dapat terbentuk struktur biskuit yang
elastis (Sunaryo 1985). Pada saat pengadukan atau pencampuran adonan,
lemak akan mengelilingi terigu sehingga jaringan gluten terputus. Hal ini
menyebabkan biskuit bertekstur lembut dan renyah (Husain 1993 dalam Marlina
2001). Selain itu, lemak dapat memberikan sumbangan terhadap cita rasa biskuit