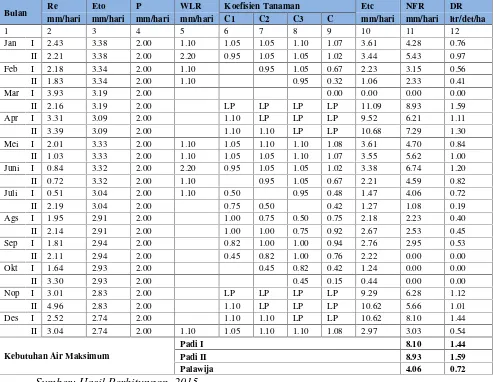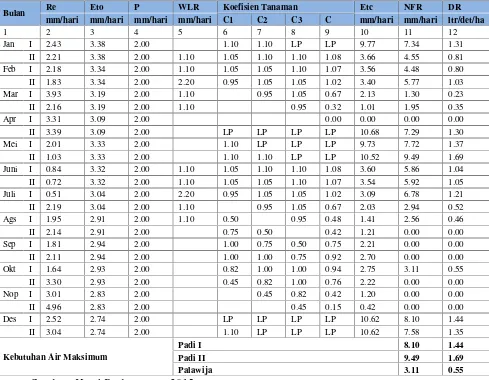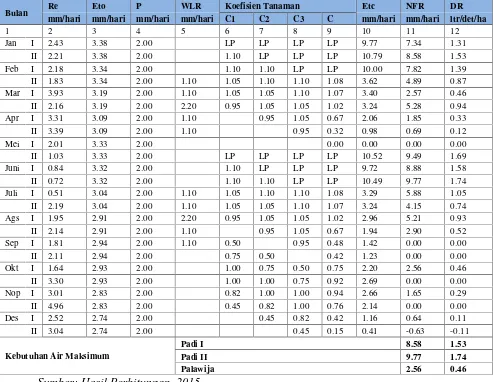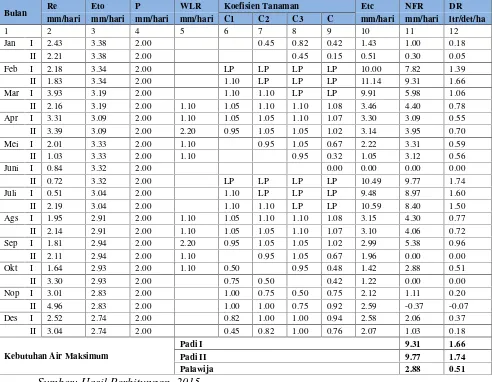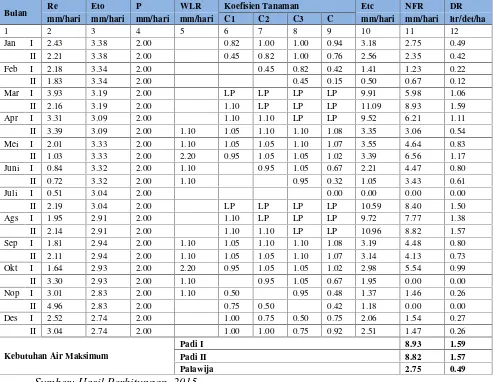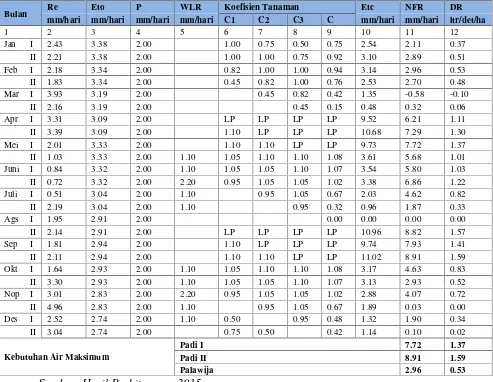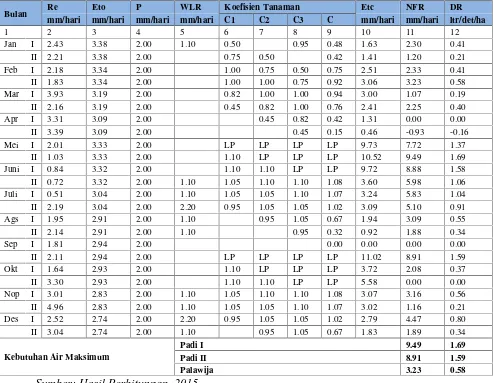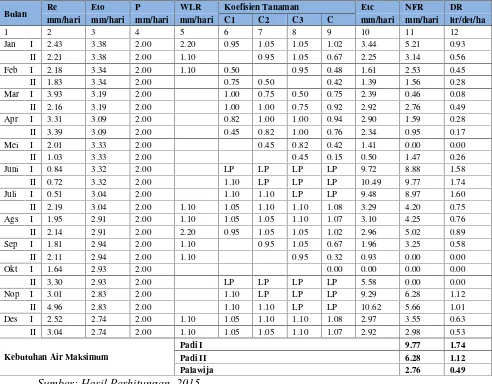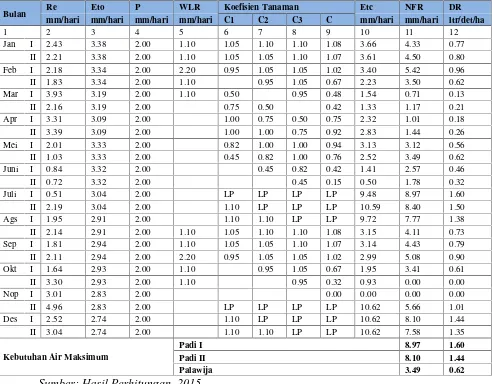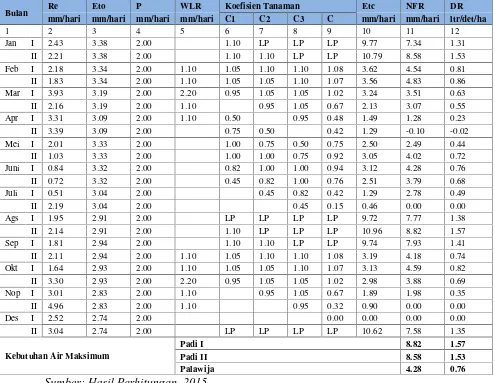Dharma, Agus. Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya
terhadap Pengelolaan Irigasi. (Online).
(http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/ , di akses 8 Mei 2015).
Direktorat Jendral Pengairan. 1986. Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi Bagian Penunjang untuk Standar Perencanaan Irigasi. Bandung : CV. Galang Persada.
Direktorat Jenderal Pengairan. 1986. Standar Perencanaan Irigasi (KP-01).
Departemen Pekerjaan Umum. Bandung: CV. Galang Persada.
Direktorat Jenderal Pengairan. 1986. Standar Perencanaan Irigasi (KP-03).
Departemen Pekerjaan Umum. Bandung: CV. Galang Persada.
Haliem, dkk. 2012.Studi Pola Penatagunaan Potensi Air Sumber Pitu di Wilayah Kali Lajing sebagai Dasar Pengembangan. Jurnal Teknik Pengairan. (Online). Volume 3. Nomor 2. (http://junalpengairan.ub.ac.id, di akses 8 Mei 2015)
Hariyanto, Asep dan K. Herry Iskandar. 2010. Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Air (Studi Kasus : Kabupaten Belitung).
(Online). (http://ejournal.unisba.ac.id , di akses 8 Mei 2015)
Limantara, Lily Montarcih. 1986.Hidrologi Praktis. Bandung: Lubuk Agung. Linsley, Ray K. dkk. 1986. Edisi Ketiga Hidrologi Untuk Insinyur. Jakarta :
Penerbit Erlangga.
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan. 2014. Hidrologi Air Tanah.(Online). (http://siat.bgl.esdm.go.id/?q=content/hidrologi-air-tanah) Subarkah, Iman. 1978. Hidologi Untuk Perencanaan Bangunan Air. Bandung:
Penerbit Idea Dharma.
Wesli. 2008.Drainase Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
Zulkipli, dkk. 2012. Analisa Neraca Air Permukaan DAS Renggung untuk Memenuhi Kebutuhan Air Irigasi dan Domestik. Jurnal Teknik Pengairan. (Online). Volume 3. Nomor 2. (http://junalpengairan.ub.ac.id, di akses 8 Mei 2015)
BAB III
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
3.1 Data Curah Hujan
51 Gambaran umum lokasi penelitian merupakan salah satu bagian yang penting
dalam penulisan.Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada pembaca
wilayah yang dipilih sebagai lokasi penelitian, sebelum membahas lebih lanjut
mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Di bawah ini akan dipaparkan
mengenai lokasi Irigasi di Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten
Simalungun.
3.3 Letak Geografis
Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Simalungun sangat strategis untuk
meningkatkan perekonomian.Posisinya sentral dan memungkin dibuatnya wilayah
Simalungun menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Secara administratif
Kabupaten Simalungun terdiri dari 21 Kecamatan dengan 237 desa/nagori dan 14
kelurahan, dengan jarak rata-rata ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten antara
13 Km s.d 97 Km. Luas wilayah Kabupaten Simalungun adalah 4.386,60 Km²
atau 438660 Ha merupakan 6,12 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Keadaan iklim Kabupaten Simalungun bertemperatur sedang, suhu tertinggi
terdapat pada bulan April dengan rata-rata 25,5ºC. Rata-rata suhu udara tertinggi
per tahun adalah 30,1ºC dan terendah 20,6ºC. (Universitas Sumatera Utara).
Kelembaban udara rata-rata perbulan 83.0 % dengan kelembaban tertinggi erjadi
pada bulan Oktober yaitu 86 %, dengan penguapan rata-rata 3,52 mm/hari. Dalam
satu tahun rata-rata terdapat 15 hari hujan dengan hari hujan tertinggi terdapat
pada bulan Oktober sebanyak 24 hari hujan, curah hujan terbanyak pada bulan
nopember sebesar 407 mm.
Adapun batas-batas wilayah daerah tingkat II Kabupaten Simalungun
terletak di antara 02º36-03º18' LU dan 98º32'-99º35' BT, dengan ketinggian
rata-rata 369 meter di atas permukaan laut yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Asahan, sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Toba Samosir, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo.
Kabupaten Simalungun terdiri dari 21 kecamatan, 237 desa/nagori dan 14
kelurahan, antara lain: Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Purba, Kecamatan
Dolok Pardamean, Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon,
Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Hutabayu Raja, Kecamatan Dolok Panribuan,
Kecamatan Jorlang Hataran, Kecamatan Panei, Kecamatan Raya, Kecamatan
Dolok Silau, Kecamatan Silau Kahean, Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan
Dolok Batu nanggar, Kecamatan Tapian Dolok, Kecamatan Siantar, Kecamatan
Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Bosar Maligas, Kecamatan
Ujung Padang. Wilayah Simalungun yang terdiri dari daerah dataran dan
pegunungan mempunyai curah hujan yang sangat baik untuk perkebunan dan
53
55 Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, skala 1 :
50.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, N.R.Cameron, dkk.., 1982)
terdapat berbagai macam formasi batuan yang dipengaruhi oleh struktur geologi.
Geologi didefinisikan sebagai cabang geologi terapan yang menyangkut
pemanfaatan bumi oleh manusia yang ada hubungannya dengan sumber kekayaan
bumi serta proses-proses yang berlangsung padanya.Geologi memperlihatkan
adanya reaksi terhadap lingkungan yang mencakup sumber alam, proses alam dan
pengembangan lingkungan fisik. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap
manusia dan potensi geologi yang ada serta akan memberikan dampak positif
maupun negarif kepada manusia.
wilayah air tanah dibagi 3, berupa: areal resapan air, limpasan dan areal
munculan air tanah serta aliran permukaan.
• Daerah resapan ± 30 % dari luas daerah. Pada areal ini air hujan meresap ke
bumi melalui permeabilitas batuan (feed-zone). Selanjutnya akan terkumpul sebagai kantong air (catchment-area) dan daerah akumulasi air tanah.
• Daerah limpasan dan munculan air tanah mencakup ± 60 % dari luas daerah
penyelidikan. Air hujan yang meresap ke bumi, yang tidak menjadi kantong air
akan melaju dan muncul di elevasi rendah berupa mata air dingin dan mata air
panas.
• Daerah aliran air permukaan (sungai), mencakup ± 10 % luas daerah
penyelidikan. Berupa air hujan yang mengalir di permukaan tanah.Aliran sungai
secara gravitasi mengalir dari elevasi tinggi ke rendah.
permukaan tanah membagi air hujan menjadi aliran permukaan, kelembaban tanah
dan air tanah (Schwabet al. 1996). Infiltrasi berkaitan erat dengan perkolasi yaitu peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah. Infiltrasi menyediakan air
untuk perkolasi. Laju infiltrasi tanah yang basah tidak dapat melebihi laju
perkolasi (Arsyad 1989).
Sri Harto (1993) mengilustrasikan keterkaitan antara infiltrasi dengan
perkolasi dengan sketsa Gambar Pada Gambar 3.1.Formasi tanah lapisan atas
mempunyai laju infiltrasi kecil tapi lapisan bawah mempunyai laju perkolasi
tinggi, sebaliknya pada gambar 3.2.Lapisan atas dengan laju infiltrasi tinggi
sedangkan laju perkolasi pada lapisan bawah rendah.
Terdapat dua parameter penting berkaitan dengan infiltrasi yaitu laju
infiltrasi dan kapasitas infiltrasi.Laju infiltrasi berkaitan dengan banyaknya air per
satuan waktu yang masuk melalui permukaan tanah.Sedangkan kapasitas infiltrasi
adalah laju maksimum air dapat maksuk ke dalam tanah pada suatu saat (Arsyad 1989).
Gambar 3.2.infiltrasi besar perkolasi kecil Gambar 3.1.Infiltrasi kecil
57 hujan adalah terbesar, kemudian berkurang dengan semakin lamanya hujan,
sehingga mencapai nilai minimum yang konstan (Gambar 3.3).Dari gambar itu,
aliran permukaan baru terjadi setelah beberapa saat hujan berlangsung, yaitu
ketika laju hujan menjadi lebih tinggi dari laju infiltrasi. Selama hujan
berlangsung laju aliran permukaan meningkat dengan semakin berkurangnya laju
infiltrasi. Laju aliran permukaan pada akhirnya akan mencapai nilai maksimum
yang konstan.
Gambar 3.3. Hubungan antara infiltrasi dengan aliran permukaan dan curah hujan
(Sumber: Arsyad 1989)
59 Merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan vulkanis, lava
yang telah membeku (effusif) atau dari abu letusan gunung berapi yang telah
membeku (efflata).Tanah ini sangat subur untuk pertanian karena merupakan
tanah tuff yang berasal dari abu letusan gunung berapi.Jenis tanah ini sangat subur
dan baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.Ciri-ciri tanah vulkanis
adalah berwarna kelabu hingga kuning dan peka terhadap erosi.Pada umumnya
jenis tanah ini mudah meresap air tetapi daya menahan air sangat kurang sehingga
mudah tererosi.Jenis tanah ini banyak terdapat di sekitar gunung berapi atau
daerah lahar gunung berapi seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa
Tenggara.Tanah ini digunakan untuk persawahan, tanaman palawija, tebu,
tembakau, sayur-sayuran, dan perkebunan.
Deskripsi Toba Tuff
Jenis batuan : Batuan sedimen klastik
Struktur : Masif
Tekstur : - Ukuran besar butir : Lempung < 2 mm
- Derajat pemilahan : Pemilahan baik
- Derajat pembundaran : Membundar baik
- Kemas tertutup : Tertutup
Komposisi : - Fragmen :
-- Matrik : Ash
- Semen : Silika
Gambar 3.4.Penampang Tahanan Jenis Batuan(Dinas Pertambangan dan Energi, 2003)
ANTARBUTIR : Terutamapasir,lanau, lempung,dankerikil(aluvium). Bahanrombakanbatuan gunungapiberukuranlanau sampaibongkahdanendapan undak
ANTARBUTIRDAN REKAHAN : TufMuria,terdiriatas bahan-bahanpiroklastik hasilerupsigunungapi berupatuta,tufapasiran, danlahar
REKAHAN : LavaMuri,batuanini terdiriataslavabasal
atauandesit,leusit-tefrit, leusitic,trakit,dansierit
Di Kabupaten Simalungun dijumpai anggota Batugamping Formasi Kuala
61 terdiri dari lapisan lempung serpihan berwarna abu-abu kehitaman serta
kecoklatan, umumnya menyerpih, dijumpai lempung yang diperkirakan bond clay
berwarna coklat, serpihan, karbonan, tebal pada lereng tebing 10 m, agak plastis
bila basah, berdasarkan analisa bakar keramik, mempunyai susut kering 8,0%,
susut bakar 8,91 % (temp. 1200o C) warna bakar merah kecoklatan, dapat
digunakan bahan badan keramik berwarna, mempunya sumberdaya hipotetik
40.000.000 m3. Satuan Tufa Toba (Qvt) terutama terdiri dari tufa berkomposisi riodasit yang sebagian terelaskan, dijumpai bahan galian felspar dan tras.
berdasarkan analisa kimia mengandung SiO2 = 71,89-72,37 %, Al2O3=
14,41-14,47 %, Fe2O3 = 2,03-2,36 %, K2O= 4,34-4,50 dan Na2O= 2,02-2,03 % , analisa
keramik menunjukkan mengandung bahan pelebur (imbuhan), berdasarkan analisa
butir banyak mengandung batuapung 65,71 %.
Batugamping marmeran berwarna abu-abu muda, kompak, keras, banyak
rekahan terisi.Vegetasi berupa pinus, pada tebing yang menjorok ke Danau Toba,
membentuk bukit menggantung, salah satu tujuan wisata. Di daerah Sipolha,
Batugamping marmeran berwarna abu-abu muda, kompak, keras, banyak rekahan
terisi urat halus Dari hasil analisa kimia mengandung CaO = 47,44 %, MgO =
3,95 % dan menurut hasil petrografi termasuk dalam batugamping organik, di
dalam sayatan tipis batuan ini menunjukkan tekstur klastik, dengan fragmen fosil
foraminifera kecil dan mineral opak didalam masa dasar mikrokristalin karbonat.
Sumberdaya hipotetik = 92.000.000 ton.
Anggota Batupasir Formasi Peuteu (Tmppt), terutama terdiri dari lapisan
lempung serpihan berwarna abu-abu kehitaman serta kecoklatan, umumnya
menyerpih, diduga berumur Miosen Tengah. Pada satuan ini dijumpai lempung
yang diperkirakan bond clay berwarna coklat, serpihan, karbonan, tebal pada
lereng tebing 10 m, agak plastis bila basah, berdasarkan analisa bakar keramik,
mempunyai susut kering 8,0%, susut bakar 8,91 % (temp. 1200o C) warna bakar merah kecoklatan, dapat digunakan bahan badan keramik berwarna, mempunya
sumberdaya hipotetik 40.000.000 m3.
Formasi Batuan Gunungapi Haranggaol (Tmvh), terdiri dari lava dan
breksi andesit, dasit serta piroklastik, diduga berumur Miosen Atas. Pada satuan
ini dijumpai andesit merupakan fragmen breksi, tertanam dalam masa dasar tufa,
fragmen berukuran dari kerakal sampai boulder, ditambang menggunakan tali
pada lereng yang terjal (50 m), vegetasi ilalang, termasuk satuan batuan
gunungapi Haranggaol dari hasil analisa petrografi adalah andesit basaltik dengan
tekstur porfiritik, nampak vesikular, disusun oleh fenokris plagioklas, piroksen
dan olivin dalam masa dasar gelas, mikrolit plagioklas dan mineral opak.
Satuan Tufa Toba (Qvt) terutama terdiri dari tufa berkomposisi riodasit
yang sebagian terelaskan, berumur Plistosen. Pada satuan ini dijumpai bahan
galian felspar dan tras. berdasarkan analisa kimia mengandung SiO2 =
71,89-72,37 %, Al2O3= 14,41-14,47 %, Fe2O3 = 2,03-2,36 %, K2O= 4,34-4,50 dan
Na2O= 2,02-2,03 % , analisa keramik menunjukkan mengandung bahan pelebur
63 Kecamatan Ujung Padang terletak 51-200 meter di atas permukaan laut
dan kondisi ini sangat mendukung untuk lahan pertanian terutama tanaman
pangan dan perkebunan. Kecamatan Ujung Padang yang seluas 15.648 km2 terdiri
dari lahan kering sebesar 39,40 persen, lahan sawah sebesar 30,72 persen ,
halaman/ pekarangan sebesar 4,54 persen dan lahan lainnya sebesar 25,33 persen.
Ditinjau dari sudut wilayahnya, tanah Simalungun dapat dibagi menjadi 4 bagian
yaitu dataran seperti dataran rendah, berawa, dan landai, bergelombang, berbukit,
dan bergunung.
Tabel 3.1. Proporsi Wilayah Kecamatan Menurut Penggunaan Lahan Tahun
2010 (%)
Penggunaan
Proporsi (%)
Lahan Sawah 30,72
Lahan Kering 39,40
Halaman/pekarangan 4,53
Lainnya 25,34
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun.
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1 Desain Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif, yakni melalui studi pustaka, tinjauan
lapangan (survey), dan analisis data. Proses tahap penelitian ini dibagi menjadi 4
tahap, yaitu : tahap pengumpulan data sekunder dan literatur, tahapan
pengambilan data lapangan, tahapan analisa data dan tahapan penyusunan laporan.
Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan beberapa tahap adalah sebagai
berikut :
Tahapan pendahuluan, tahapan ini merupakan tahapan studi pustaka, yakni
dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang terkait
dengan penelitian ini. Hasil dari tahapan ini berupa sketsa dan penafsiran
sementara keadaan daerah penelitian yang akan digunakan pada tahap
pengambilan data.
Tahapan pengambilan data di lapangan, tahapan ini meliputi pengambilan
data, meliputi: pengukuran debit aktual yang masuk ke petak sawah dan
pada pintu pengambilan, wawancara dan dokumentasi daerah penelitian.
Tahapan pengambilan data sekunder, tahapan ini meliputi pengambilan
data, meliputi : data curah hujan daerah penelitian, data klimatologi, data
jaringan irigasi dan pola tanam yang diterapkan pada Daerah Irigasi Huta
57 hasil pengambilan yaitu analisa debit andalan untuk memperoleh besar
ketersediaan air, menganalisa curah hujan efektif dan menganalisa pola
tanam yang diterapkan untuk mendapatkan besar pemakaian air pada
Daerah Irigasi Huta Parik.
Tahapan penyusunan laporan, merupakan tahapan akhir dari tahap
penelitian di mana tahap ini hanya menyusun data-data di tahap awal hingga akhir
yang selanjutnya akan dirangkum menjadi sebuah laporan penelitian.
4.2 Metode Pengumpulan Data
4.2.1 Pemakaian Air Irigasi
Data-data dalam menghitung besarnya pemakaian air digunakan
asumsi-asumsi dan ketentuan-ketentuan data perhitungan yang diambil berdasarkan hasil
tinjauan pustaka. Untuk perhitungan besar pemakaian air pada masa penyiapan
lahan.
4.3 Metode Analisis dan Pengolahan Data
Setelah data yang diperlukan didapat, maka selanjutnya
data-data tersebut dianalisis untuk digunakan dalam perencanaan teknis.
4.3.1 Analisis Hidrologi
Sebelum melakukan analisis hidrologi, terlebih dahulu menentukan
stasiun hujan sehingga didapat data hujan di Desa Huta Parik Kecamatan Ujung
Padang. Dalam analisis hidrologi akan membahas langkah-langkah untuk
menentukan kebutuhan air rata-rata tanaman serta volume resapan air
tanah.. Langkah-langkah untuk menentukan kebutuhan air rata-rata
tanaman adalah menghitung curah hujan rata-rata daerah, menghitung curah
hujan efektif, menghitung evapotranspirasi, menghitung kebutuhan air
tanaman, menentukan pola tanam, menghitung kebutuhan air rata-rata tanaman.
Kemudian menghitung volume resapan air tanah dengan cara perhitungan air
permukaan, dan menghitung neraca air (water balance).
4.3.2 Pengolahan Data Curah Hujan
Pengolahan data curah hujan menggunakan metode perhitungan curah
hujan effektif (Reff). Curah hujan effektif (Reff) ditentukan berdasarkan besarnya
R-80 yang merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampaui sebanyak 80%
atau dengan kata lain dilampauinya 8 kali kejadian dari 10 kali kejadian. Dengan
kata lain bahwa besarnya curah hujan yang terjadi lebih kecil dari R80
mempunyai kemungkinan hanya 20%.
4.3.3 Pengolahan Data Klimatologi
Pengolahan data klimatologi menggunakan metode evapotranporasi.
Peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan
permukaan air ke udara disebut evaporasi (penguapan). Transpirasi adalah proses
dimana tanaman menghisap air dari dalam tanah dan menguapkannya ke udara
sebagai uap. Peristiwa yang terjadi secara bersama-sama antara transpirasi dan
59 udara, kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari dan lain-lain
yang saling berhubungan satu sama lain. Besamya evaporasi yang terjadi pada
tanaman dihitung berdasarkan metode Penmann yang telah dimodifikasi. Dalam
hal ini dipakai cara FAO yang dalam perumusannya adalah sebagai berikut:
Eto = c. [W. Rn + (1-W). f (u). (ea-ed)]...(1)
4.4 Analisa Pemakaian Air Dengan Ketersediaan Air
Untuk mengetahui keseimbangan air dalam mengairi daerah irigasi Huta
Parik, maka perlu dilakukan perbandingan antara jumlah debit pemakaian air
berdasarkan kebutuhan air sesuai dengan pola tanam yang diterapkan dengan
besarnya ketersediaan air yang ada. Air yang tersedia adalah air yang tersedia
pada Sungai Lima Puluh, yakni debit andalan sungai Percut berdasarkan hasil
perhitungan.
Dengan mengetahui keseimbangan antara besarnya debit andalan yang
menunjukkan besarnya ketersediaan air dengan besar pemakaian air pada daerah
Irigasi Huta Parik, maka akan diketahui apakah air yang tersedia saat ini pada
Daerah Irigasi Huta Parik mencukupi kebutuhan pemakaian air atau tidak.
Apabila kebutuhan air tidak mencukupi maka direncanakan melakukan
pengambilan air melalui sumur yang memanfaatkan air tanah, dengan mengetahui
jumlah kebutuhan air irigasi maka dapat diketahui jumlah pemakaian air tanah
yang digunakan. Tetapi apabila ketersediaan air tanah tidak mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan air irigasi yang ada saat ini, maka perlu dilakukan tindakan
selanjutnya untuk mengatasi kekurangan air agar tidak berimplikasi negatif pada
produksi.
4.5 Diagram Alir Kegiatan
a
b
Mulai
Identifikasi masalah
Studi Pustaka
Pengumpulan data
Data primer : Survey lokasi
Analisis dan pengolahan data : Analisis hidrologi
Data sekunder :
1. Data curah hujan 2. Data klimatologi
Air tanah/ sumur Curah
hujan
Total ketersediaan air
Kebutuhan Air Irigasai
a > b
Hasil dan Pembahasan
69
ANALISA DAN PEMBAHASAN
5.1 Analisa Hidrologi
5.1.1 Perhitungan Curah Hujan
Tujuan perhitungan curah hujan adalah untuk mengetahui curah hujan
maksimum dan minimum dan untuk menghitung rata rata curah hujan yang terjadi
di Sungai Lima Dua setiap bulannya. Data yang digunakan adalah dari stasiun
penakaran yang berada di daerah Irigasi Huta Parik yaitu St.Sei Muka, Kabupaten
Simalungun. Hasil perhitungan curah hujan dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Curah Hujan Regional
Sumber : Hasil Perhitungan, 2015
Tahun
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2005 34 26 36 31 26 68 68 78 81 112 111 32 138 83 57 93 133 198 116 126 143 89 119 70
2006 116 71 95 55 67 58 140 66 144 136 144 89 65 139 123 95 102 164 200 234 110 173 25 98 2007 129 93 24 25 48 69 74 67 61 123 104 83 57 102 122 269 219 185 107 250 232 159 82 157 2008 62 107 39 56 114 156 180 87 135 167 49 104 180 109 217 191 215 233 230 207 136 141 177 42
2009 85 98 73 34 24 116 51 53 82 151 29 72 52 192 84 137 136 176 155 190 144 223 65 64
2010 122 66 105 138 251 68 84 57 107 418 122 84 124 149 114 162 187 149 123 102 152 139 101 101 2011 175 122 67 67 156 53 127 47 249 119 113 43 137 52 222 52 86 165 266 172 162 134 307 186 2012 76 50 145 199 116 151 128 95 114 110 115 91 61 186 157 111 172 194 309 170 169 198 268 95 2013 184 130 124 54 57 36 94 160 170 112 214 108 186 94 115 251 146 187 192 284 164 171 141 137 2014 68 77 103 23 126 101 164 116 135 115 100 76 82 57 124 175 114 254 149 225 176 161 159 78
Max 184 129 145 199 251 156 180 160 249 118 214 108 186 192 222 269 218,8 254 309 284 232 223 307 186
Rerata 105,3 84,1 81,1 68,1 98,5 87,8 111,0 82,4 127,7 156,2 109,9 78,2 108,2 116,4 133,4 153,5 151,0 190,6 184,6 196,2 158,7 158,8 144,4 102,7
71 terakhir. Setelah di rata-ratakan maka curah hujan tertinggi terjadi pada bulan
Oktober dan terendah pada bulan Juni. Besar curah hujan rata-rata maksimum
terjadi di akhir bulan Oktober sebesar 196,2 mm dan curah hujan rata-rata
terendah terjadi di akhir bulan Februari sebesar 68,1 mm.
5.1.2 Curah Hujan Efektif
Curah hujan efektif adalah bagian dari curah hujan total yang digunakan
oleh tanaman selama masa pertumbuhan. Besarnya jumlah curah hujan efektif
dipengaruhi oleh cara pemberian air irigasi, laju pengurangan air genangan,
kedalaman lapisan air yang dipertahankan, jenis tanaman dan tingkat ketahanan
tanaman terhadap kekurangan air. Untuk irigasi tanaman padi, curah hujan efektif
diambil 80 % kemungkinan curah hujan terlewati. Curah hujan efektif diperoleh
dengan mengurutkan data curah hujan bulanan dari yang terbesar hingga terkecil
rekapitulasi dari perhitungan curah hujan efektif dapat dilihat pada Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Ranking Curah Hujan Efektif
Sumber : Hasil perhitungan,2015
No
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 184 130 145 199 251 156 180 160 249 418 214 108 186 192 222 269 219 254 309 284 232 223 307 186 2 175 122 124 138 156 151 164 116 170 167 113 84 124 186 217 251 215 233 266 250 176 198 268 157 3 129 107 105 67 126 116 140 95 144 151 100 72 61 149 157 191 187 198 230 234 169 173 177 137 4 122 98 103 56 116 101 128 87 135 136 111 83 82 139 124 175 172 194 200 225 164 171 159 101 5 116 93 95 55 114 69 127 78 135 123 144 104 180 109 123 162 146 187 192 207 162 161 141 98
6 85 77 73 54 67 68 94 67 114 119 115 89 137 102 122 137 136 185 155 190 152 159 119 95
7 76 71 67 34 57 68 84 66 107 115 122 91 138 94 115 111 133 176 149 172 144 141 101 78
8 68 66 39 31 48 58 74 57 82 112 49 43 57 83 114 95 114 165 123 170 143 139 82 70
9 62 50 36 25 26 53 68 53 81 112 29 32 52 57 84 93 102 164 116 126 136 134 65 64
10 34 26 24 23 24 36 51 47 61 110 104 76 65 52 57 52 86 149 107 102 110 89 25 42
R-80 68 66 39 31 48 58 74 57 82 112 49 43 57 83 114 95 114 165 123 170 143 139 82 70
73 perhitungan sebagai berikut adalah contoh perhitungan curah hujan yang
digunakan.
1. R80 = 49,3 untuk bulan Juni-1
Reff=0.73 × ×R80
=0.73 × × 49,3
= 2,4 mm/hari
2. Untuk bulan Februari-2 , dengan R80= 30,9 maka
Reff=0.73 × ×R80
=0.73 × × 30,9
= 1,5 mm/hari
Menghitung curah hujan efektif tanaman padi pada bulan yang lain,
digunakan cara yang sama seperti contoh diatas. Hasil perhitungan curah hujan
efektif pada tanaman padi dapat dilihat pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3. Curah Hujan Efektif untuk Tanaman Padi
Sumber : Hasil Perhitungan, 2015
5.1.3 Evapotranspirasi
Evapotranspirasi adalah kebutuhan dasar bagi tanaman yang harus
dipenuhi oleh sistem irigasi yang bersangkutan untuk menjamin suatu tingkat
produksi yang diharapkan. Evapotranspirasi sangat dipengaruhi oleh keadaan
iklim.
Menghitung besarnya evapotranspirasi, dibutuhkan data-data klimatologi
75 2. Kelembaban udara,
3. Lama penyinaran matahari dan
4. Kecepatan angin.
Rekapitulasi perhitungan evapotranspirasi potensial (mm/hari) dapat dilihat
pada Tabel 5.4.
Tabel 5.4. Rekapitulasi Perhitungan Evapotranspirasi Potensial (mm/hari)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
4,57 5,10 5,00 4,40 4,20 4,18 4,28 4,77 4,88 4,63 4,37 4,37 Sumber: Perhitungan, 2015
5.1.4 Air Permukaan
Air permukaan yang merupakan air yang ada di permukaan tanah,
baik berupa sunagi ataupun danau. Di daerah penyelidikan, air permukaan
umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya,
sedangkan ranting sungai yang terutama berada di daerah perbukitan
umumnya berupa sungai musiman atau keing di musim kemarau dan hanya
berair di musim hujan.
Besarnya aliran permukaan di Desa Huta Parik Kabupaten Simalungun di
hitung dengan menggunakan formula yang dikemukakan oleh Lembaga Riset
Pertanian India (Sharma, 1990 dalam Dinas Pertambangan dan Energi, 2003)
sebagai berikut:
Ro= 1,511×P1,44
Tm1,34
×S0,0613
di mana: Ro = Limpasan air permukaan (cm)
P = Curah hujan tahunan (cm)
S = Luas daerah (km2)
Tm = Suhu udara tahunan rata-rata
Di Desa Huta Parik Kabupaten Simalungun, suhu udara rata-rata
tahunan 29,01°C, sedangkan besarnya curah hujan rata-rata tahunan
mencapai 2988,85 mm. Dengan memperhitungkan Luas daerah 0,3425 km2,
didapat Ro sebesar :
=
, ,,
, , , ,
= 64,968
/
ℎ
maka dapat diketahui besarnya aliran permukaan (Ro) sebesar 64,968
cm/tahun atau 649,68 mm/tahun.
5.1.5 Neraca Air (Water Balance)
Neraca air dimaksudkan sebagai imbangan air yang terjadi di alam
atau pada suatu daerah yang membentuk suatu daur atau siklus hidrologi.
Parameter yang diperlukan dalam perhitungan neraca air meliputi jumlah curah
hujan, evepotranspirasi nyata, limpasan air permukaan, dan jumlah air yang
meresap ke dalam tanah.
Perhitungan neraca air di daerah penyelidikan ini dilakukan dengan rumus
umum neraca air Dunne dan Leopolp (1978) dalam Dinas Pertambangan
77 di mana:
R = Curah hujan rata-rata tahunan (mm)
Ro = Air permukaan (run off) yang mengalir (mm) E = Evapotranspirasi nyata (mm)
U = Perkolasi dalam (mm)
∆Sm= Perubahan dalam cadangan kelengasan tanah (mm)
∆Sg= Perubahan dalam cadangan air tanah (mm)
Dalam hal ini, parameter ∆Smdan ∆Sguntuk kondisi tahunan akan terdapat pada
kedudukan konstan, sedangkan curah hujan rata-rata tahunan yang berlangsung di
daerah penyelidikan dapat ditetapkan sebesar 2988,85 mm/tahun. Sehingga
berdasarkan rumus neraca air tersebut, air hujan yang masuk ke dalam tanah
sebesar :
U = R – Ro– E
= 2988,85 – 649,68 – 1668,72
= 670,45 mm/tahun
Jadi air hujan yang masuk kedalam tanah sebesar 670,45 mm/tahun atau 22,43
% dari jumlah curah hujan rata-rata tahunan. Dengan demikian jumlah air
yang masuk ke dalam tanah di Desa Huta Parik Kecamatan Ujung
Padang Kabupaten Simalungun dengan luas 0,3425 km2 diperkirakan sekitar
0,229 juta m3/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan
Tabel 5.6 berikut.
Tabel 5.5.Perhitungan Neraca Air Bulanan
Bulan
Parameter JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES
Suhu Udara (°C) 26,8 26,6 27,2 27,7 27,8 27,4 27,6 27,8 27,6 27,9 27,9 27,5 Penyinaran Matahari (%) 49 54 59 57 57 60 59 58 49 45 43 47
Kelembaban Relatif (%) 85 84 84 84 85 84 83 84 86 87 87 86
Kecepatan Angin (km/hari) 67,2 74,4 72 76,8 76,8 74,4 74,4 76,8 76,8 72 74,4 72
Evapotranspirasi (mm/hari) 4,57 5,10 5,00 4,40 4,20 4,18 4,28 4,77 4,88 4,63 4,37 4,37
Evapotranspirasi (mm/bln) 73,07 76,43 79,96 66,04 67,18 62,65 68,51 76,29 73,20 74,12 65,55 69,87
Tabel 5.6.Perhitungan Neraca Air Tahunan
Curah Hujan
2988,85 29,0 649,68 1705,72 670,45 229629
5.2 Kebutuhan Air Irigasi
Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk
tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang di berikan oleh alam melalui
hujan dan kontribusi air tanah.
Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor–faktor berikut :
1. Penyiapan lahan
2. Penggunaan konsumtif
3. Perkolasi dan rembesan
4. Pergantian lapisan air
5. Curah hujan efektif.
Analisa kebutuhan air irigasi untuk Alternatif 1-12 ditampilkan di Tabel
79
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (November I) Padi-II (Maret I) Palawija (Juli I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
Tabel 5.8. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–2
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Desember I) Padi-II (April I) Palawija (Agustus I)
Sumber: Hasil Perhitungan, 2015
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
81
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Januari I) Padi-II (Mei I)
Palawija (September I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
Tabel 5.10. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–4
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Februari I) Padi-II (Juni I) Palawija (Oktober I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
83
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Maret I) Padi-II (Juli I)
Palawija (November I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
Tabel 5.12. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–6
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (April I) Padi-II (Agustus I) Palawija (Desember I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
85
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Mei I) Padi-II (September I) Palawija (Januari I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
Tabel 5.14. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–8
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Juni I) Padi-II (Oktober I) Palawija (Februari I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
87
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Juli I)
Padi-II (November I) Palawija (Maret I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
Tabel 5.16. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–10
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Agustus I) Padi-II (Desember I) Palawija (April I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
89
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (September I) Padi-II (Januari I) Palawija (Mei I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
Tabel 5.18. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–12
Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija
Periode Tanam : Padi-I (Oktober I) Padi-II (Februari I) Palawija (Juni I)
Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR
mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.00
Dari perhitungan kebutuhan air irigasi dengan 12 alternatif pola tanam di
91
Dengan kebutuhan air untuk irigasi rata-rata tiap bulannya sebesar
0,71 l/dtk/ha. Dengan luas areal sawah sebesar 34,25 ha maka besarnya
kebutuhan air irigasi untuk mengairi daerah tersebut sebesar 24,32 l/dtk. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.20.
Tabel 5.20. Rata-rata kebutuhan air irigasi tiap bulannya berdasarkan 12
Pemahaman sebaran akuifer dibawah permukaan dilakukan dengan
rekonstruksi satuan batuan yang teramati di lapangan. Data informasi umum
yang terkumpul merupakan dasar untuk analisis secara lebih rinci konfigurasi
sistem akuifer didaerah tersebut.
Dengan memahami semua informasi hidrogeologi bawah permukaan yang
telah diperoleh, sistem akuifer di daerah Simalungun dikelompokkan menjadi
akuifer dangkal (akuifer bebas) dan akuifer dalam (akuifer tertekan), namun pada
daerah Huta Parik termasuk jenis sistem akuifer bebas (unconfined akuifer). Pengelompokkan ini berdasarkan atas letaknya terhadap permukaan tanah,
terdapatnya lapisan penyekat yang realatif kedap air sehingga membedakan
sistem akuifer di bagian atas dan bawahnya, serta kemudahan bagi penduduk
93 Akuifer dangkal mempunyai fungsi sebagai lapisan pembawa air tanpa
lapisan penutup yang relatif kedap air diatasnya, sehingga dapat dinyatakan pula
sebagai akuifer tak tertekan (unconfined aquifer). Berdasarkan atas pengamatan batuan di permukaan maupun pada dinding sumur gali, litologi
pembentuk akuifer dangkal didaerah Cekungan Air Tanah Sumatera Utara
tersebut terutama pasir, pasir lempung, pasir kerikilan pada endapan aluvium
dibagian selatan didaerah dataran, akuifer dangkal disusun oleh endapan
aluvium dengan ketebalan berkisar antara 7 - 40 m (Gambar 5.1).
Gambar 5.1.Penampang Litologi Akuifer
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi, 2003
Gambar 5.2.Penampang litologi dan indeks lintasan litologi akuifer
95 Air tanah di Desa Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten
Simalungun dapat digolongkan sebagai air tanah dangkal, dimana air tanah
dangkal bersifat tidak tertekan dengan ketebalan akuifer beragam dari
satu tempat ketempat yang lain dalam kisaran rata-rata 3,0 m.bmt sampai lebih
dari 30 m pada beberapa lokasi tertentu. Dari diagram pagar (Gambar 5.3)
dapat terlihat konfigurasi sistem akuifer dangkal secara tiga dimensi. Akuifer
dangkal atau bebas yang disusun oleh endapan aluvium, umumnya terdiri
atas pasir lempungan atau lempung pasiran dengan kedalaman bagian bawah
akuifer 25 – 45 meter dibawah muka tanah setempat (m.bmt).
DIAGRAM PAGAR (Sumur no. 95, 102, 128 dan 153)
DAERAH SIMALUNGUN dan SEKITARNYA
SKALA TEGAK 1 : 2000 SKALA DATAR 1 : 50.000
Gambar 5.3.Diagram Pagar dan Indeks Lokasi
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi, 2003
5.3.3 Potensi Air Tanah
Pengelompokan potensi air tanah mencangkup pemahaman tentang
jumlah (kuantitas) air tanah pada suatu tempat, yang dikaitkan dengan kemudahan
untuk mendapatkannya dengan teknologi yang umum berlaku, artinya suatu
tempat dikatakan memiliki potensi air tanah yang tinggi bila terdapat
kemungkinan untuk mendapatkan air tanah dengan jumlah yang cukup, serta cara
untuk memperolehnya yang relatif mudah.
Berdasarkan atas kriteria air tanah tersebut, Cekungan Air Tanah dapat
dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yakni:
1. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan tinggi pada akuifer dalam,
2. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan akuifer dalam,
3. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan sedang pada akuifer dalam,
4. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan dalam.
Berdasarkan dari hasil pengamatan melalui penampang litologi dan indeks
lintasan litologi pengelompokan wilayah potensi air tanah tersebut, Desa Huta
Parik Kecamatan Ujung Padang memiliki potensi air tanah sedang pada akuifer
dangkal dan tinggi pada akuifer dalam.
Akuifer dangkal terdapat pada kedalaman antara 3,0 - 45,0 mbmt
dengan ketebalan akuifer yang tidak merata di semua tempat, umumnya kurang
dari 15,0 m. Tercatat MAT berkisar antara 3,0 - 10 mbmt.
5.3.4 Uji Permeabilitas di Lapangan
Prosedur penelitian uji permeabilitas,
97
10. Alat pemukul dari kayu
11. Sealtape (bahan penutup/penyumbat kebocoran)
Cara kerja
1. Tentukan lokasi tanah yang akan diuji
2. Siapkan semua alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan
3. Mengukur kedalaman efektif tanah
4. Ambil tabung permeameter B dan masukkan ke dalam tanah dengan
bantuan pemukul kayu
5. Angkat tabung beserta tanah di dalamnya dengan hati-hati (dengan
bantuan cangkul), agar tanah tidak lepas.
6. Tabung permeameter diberi alas kassa, dan bagian antara tabung dengan
penutup diberi sealtape atau bahan lain agar tidak terjadi kebocoran pada
saat air mengalir.
7. Masukkan air ke corong / wadah air ( C ), hingga ketinggian tertentu dan
dijaga agar tinggi muka airnya tetap selama percobaan berlangsung
8. Tunggu hingga air meresap dan menetes ke dalam gelas ukur (D), tetesan
pertama dicatat sebagai to.
9. Setelah air di gelas ukur (D) mencapai volume tertentu, catat waktu
sebagai tn dan volume airnya diukur
10. Hitung harga koefisien permeabilitasnya dan jelaskan berdasar data yang
ada sifat fisik contoh tanah tersebut
Gambar 5.4.Skema Percobaan Penentuan Permeabilitas
Tabel. 5.21. Data untuk menentukan nilai permeabilitas
ulangan to
Sumber : Data Penelitian Hafiz, 2013
99
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapatkan koefisien permeabilitas
(K) rata-rata pada tabel sebesar 3,642 m/hari dan termasuk jenis batu pasir
menengah. Ini menunjukkan pada batu memiliki porositas yang sangat rendah
sehingga air hanya mengalir melalui rongga atau celah-celah antar partikel
sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menampung air yang keluar lebih cepat
dibandingkan dengan pasir.
5.3.5 Kondisi dan klasifikasi Sumur
Data pemompaan yang dilakukan dilapangan pada satu sumur pompa,
dimana pada setiap tahap uji dilakukan selama 30 detik dan dipompa pada volume
tertentu maka didapat debit yg keluar, dapat dilihat pada tabel 5.22.
Tabel 5.22. Contoh Data Pemompaan dan Penurunan Muka Air Tanah
Tahap Uji T (dtk) Q (l/dt) V (l) Sw (m) Sw/Q (m2/dt)
Q (m3/dt)
1 30 0,67 20 0,003 4,48 0,67x10-3
2 30 1,36 40,8 0,029 21,32 1,36x10-3
3 30 2,14 64,2 0,050 23,36 2,14x10-3
4 30 2,84 85.2 0,075 26,41 2,84x10-3
5 30 3,64 109,2 0,104 28,57 3,64x10-3
6 30 4,45 133,5 0,129 28,98 4,45x10-3
Sumber : Data Primer, 2015
Proses pemompaan uji ada dua tahap yaitu :
1. Tahap pemompaan uji bertingkat yang berlangsung selama 9 jam dengan
debit pemompaan yang ditingkat setiap 3 jam.
2. Tahap terputus dengan debit pemompaan yang konstan. Untuk lebih
mengoptimalkan proses pemompaan uji ini, maka sebelum melaksanakan
pemompaan uji, terus lakukan kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
untuk mengalirkan air sumur bor kedalam kolam penampung sebagai uji
tersebut diketahui bahwa kapasitas sumur cukup besar lebih dari 10
liter/detik.
(Sw) 0,003 meter. Penurunan ini didapat melalui hasil pengukuran dilapangan
101 Gambar 5.5.Hubungan Antara Sw/Q dengan Q
Dari grafik hubungan antara Sw/Q dan Q diperoleh :
Nilai B (perpotongan kurva dengan asumbu Y) ; Nilai C (kemiringan kurva)
B = 2,276 m2/dt C = 317,86 m5/dt2 bahwa kondisi dan klasifikasi sumur adalah baik dan secara umum sumur tersebut
mempunyai produktivitas yang tinggi.
Harga koefisien Well Loss menurut Dalton dan Bierschenk dapat
menunjukkan kondisi dari suatu sumur produksi dapat diikuti pada tabel berikut :
Tabel 5.23 Kondisi sumur produksi berdasarkan harga koefisien
well loss ( C ) menurut Walton
C (m5/mnt2) Kondisi sumur
< 0,5 Baik
0,5–1,0 Mengalami penyumbatan sedikit
1,0–4,0 Penyhumbatan dibeberapa tempat
>4,0 Sulit dikembalikan seperti semula
Faktor bentuk ( development factor)
Faktor bentuk ( Fd) dinyatakan dengan rumus :
Fd= B C
x 100
Klasifikasi sumur produksi berdasarkan factor bentuk dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 5.24. Klasifikasi sumur produksi berdasarkan
Faktor Bentuk ( Fd) menurut Bierschenk Faktor Bentuk (m3/hari) Klas
< 0,1 Sangat baik
0,1–0,5 Baik
0,5–1,0 Sedang
>1,0 Jelek
5.3.6 Debit Optimum Yang Dapat Dieksploitasi Dari Sumur Pompa
Dari data pemompaan dan data karakteristik akuifer (tebal akuifer 10 m,
103
Sumber : Data Primer, 2015
- Menghitung Q maks
- Dari regresi didapat persamaan
Y = 0,000764X2+ 0,006409X (X = Q dan Y = Sw)
Maka Y = 0,000764 (13,6)2+ 0,006409 (13,6) = 0,141 + 0,0872 = 0,228 m
Grafik Debit Optimum
Gambar 5.6.Grafik Untuk Menentukan Debit Optimum Sumur
Dari grafik diatas diketahui bahwa Qoptimum = 5 lt/dt. Debit optimum
tiap sumur adalah 5 lt/dt, sehingga debit yang dapat dihasilkan dari semua sumur
yang ada yaitu 25 lt/dt. Berdasarkan dari hasil analisis diatas, penyadapan air
tanah dengan pemompaan sumur bor daerah Huta Parik tersebut debit optimum
>5 l/detik dan debit maksimun sebesar 13,6 l/dtk. Debit ini dapat dimanfaatkan
untuk mencukupi kebutuhan air irigasi Huta Parik. Sedangkan kekurangan
kebutuhan air pada 3 bulan yaitu februari, maret, dan juni digunakan
tampungan total air yang berlebih dari tiap bulannya.
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
0 2 4 6 8 10 12 14 16
S
w
(m
)
Q lt/dt
105 Gambar 5.7. Aliran Tunak pada Akuifer Bebas
Jika harga N = 0, maka persamaan muka air tanah menjadi :
h2= H2+ .ln( )
Pada kenyataannya perbandingan penurunan muka air
H
Jarak pengaruh (jari-jari pengaruh) akibat pemompaan
R = INV ( ( , ) ,
, + In 0,5 )
R = 9,88 meter
Berdasarkan survey yang telah dilakukan, pada daerah penelitian
kedalaman sumur mencapai rata-rata 15 m, dan debit optimum yang keluar
mencapai 0,005 m3/dtk pada diameter sumur 1,00 m. Berdasarkan analisa
perhitungan jarak pengaruh akibat pemompaan pada satu sumur bor mencapai
9,88 m pada penurunan muka air tanah 10 m.
Tabel 5.26. Tabel Hubungan Antara Ketersediaan Air Dan Kebutuhan
Air Irigasi 34,245 Ha Dengan Pola Tanam
Padi-Padi-Palawija Mulai Awal Bulan Desember.
Parameter JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES
Debit Potensi Air Tanah (l/dtk) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Kebutuhan Air Irigasi (lt/dtk/ha) 0,71 1,05 0,85 0,71 0,45 0,85 0,65 0,45 0,45 0,25 0,15 0,64
Kebutuhan Air Irigasi (l/dtk) 24,32 35,8 29,1 24,3 15,4 29,1 22,3 15,4 15,4 8,6 5,1 21,9
Kelebihan Air (l/dtk) 0,7 0,7 9,6 2,7 9,6 9,6 16,4 19,9 3,1
107 - Grafik Hubungan antara Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Irigasi
34,245 ha dengan Pola Tanam Padi - Padi - Palawija mulai Awal Bulan
Desember.
Gambar 5.8. Grafik Curah Hujan dan Grafik Hubungan antara Ketersediaan Air
dan Kebutuhan Air Irigasi 34,245 ha dengan Pola Tanam Padi–
Padi - Palawija mulai Awal Bulan Desember.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Air Irigasi (lt/dt) 24.32 35.8 29.1 24.3 15.4 29.1 22.3 15.4 15.4 8.6 5.1 21.9
Debit Potensi Air Tanah (lt/dt) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
0 10 20 30
lt
/d
t
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Dari uraian pada bab-bab diatas dalam laporan ini kami menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan analisa kebutuhan air yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan air Irigasi Huta Parik adal ah sebesar 0,71 l/dtk/ha, dimana
kebutuhan tersebut hampir tidak terpenuhi pada saat musim kemarau
sehingga diperlukan penambahan sumur bor selain sumur bor yang sudah
ada.
2. Berdasarkan penelitian ini wilayah potensi air tanah Desa Huta Parik
Kecamatan Ujung Padang memiliki potensi air tanah sedang pada akuifer
dangkal dan tinggi pada akuifer dalam. Sistem akuifer di daerah Simalungun
dikelompokkan menjadi akuifer dangkal (akuifer bebas) dan akuifer dalam
(akuifer tertekan), namun pada daerah Huta Parik termasuk kedalam jenis
sistem akuifer bebas (unconfined akuifer). Akuifer dangkal terdapat pada kedalaman antara 3,0 - 45,0 mbmt dengan ketebalan akuifer yang tidak
merata di semua tempat, umumnya kurang dari 15,0 m. Tercatat MAT
berkisar antara 3,0 - 10 mbmt.
3. Berdasarkan metode Neraca air, curah hujan rata-rata tahunan yang
berlangsung didaerah penyelidikan sebesar 2988,85 mm/tahun kemudian air
hujan yang masuk kedalam tanah sebesar 670,45 mm/tahun atau 22,43% dari
109 5 l/dtk, untuk debit maksimalnya adalah 13,6 l/dtk.
5. Dari hasil survey grafik hubungan antara Sw/Q dan Q, berdasarkan nilai C =
0,088 m5/mnt2 dan Fd = 0,162 m3/hari dapat disimpulkan bahwa kondisi dan klasifikasi adalah baik dan secara umum sumur tersebut mempunyai
produktifitas yang tinggi.
6.2 Saran
1. Kebutuhan air baku terutama air irigasi pada musim kemarau yang terus
meningkat karena beberapa sebab, hal ini menyebabkan pemanfaatan
air tanah juga meningkat, sehingga perlu meningkatkan pemantauan dan
pengawasan terhadap penggunaan air tanah.
2. Perlu diadakan perbaikan pada saluran irigasi Huta Parik sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk mengoptimalkan produktifitas
hasil tanaman.
3. Bangunan-bangunan dalam sistem jaringan irigasi air tanah ini selama
operasional dan pemeliharaannya harus memenuhi standar yang telah
ditetapkan sehingga umur pemakaiannya dapat bertahan lama.
4. Sumur-sumur bor air tanah yang telah dikembangkan hendaknya dikelola
dengan manajemen yang baik, sehingga tidak timbul konflik kepentingan
dengan pengguna air yang lain.
5. Mengikutsertakan berbagai bidang disiplin ilmu dalam perancangan ini,
guna melengkapi dan menyempurnakan detail teknis perancangan sistem
jaringan irigasi air tanah , seperti teknik sipil, geologi, hidrologi, dll.
6. Mengajak partisipasi dari semua pihak untuk menjaga daerah resapan
supaya tetap baik kondisinya sehingga kontinuitas debit air tanah relatif
stabil meskipun di musim kemarau baik untuk masa sekarang maupun masa
6
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Siklus Hidrologi
Di bumi terdapat kira-kira sejumlah 1,3-1,4 milyard km3 air yang terdiri
dari 97,5 % adalah air laut, 1,75% berbentuk es, dan 0,73% berada di daratan
sebagai air sungai, air danau, air tanah dan sebagainya. Hanya 0,001%
berbentuk uap di udara. Air di bumi ini mengulangi terus menerus sirkulasi →
penguapan, presipitasi dan pengaliran keluar (outflow). Air menguap ke udara
dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa
proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke perukaan laut atau daratan.
Sebelum tiba ke permukaan bumi sebagian langsung menguap ke udara dan
sebagian tiba ke permukaan bumi. Tidak semua bagian hujan yang jatuh ke
permukaan bumi mencapai permukaan tanah. Sebagian akan tertahan oleh
tumbuh-tumbuhan dimana sebagian akan menguap dan sebagian lagi akan jatuh
atau mengalir melalui dahan-dahan ke permukaan tanah. (Sosrodarsono, S. dan Kensaku T. 1983)
Siklus hidrologi merupakan rangkaian proses berpindahnya air permukaan
bumi dari suatu tempat ke tempat lainnya hingga kembali ke tempat asalnya.
Air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan melalui evaporasi. Air di
atmosfer dalam bentuk uap air atau awan bergerak dalam massa yang besar di atas
benua dan dipanaskan oleh radiasi tanah. Panas membuat uap air lebih naik lagi
sehingga cukup tinggi dan dingin untuk terjadi kondensasi. Uap air berubah jadi
embun dan seterusnya jadi hujan atau salju. Curahan (precipitation) turun ke
bawah, ke daratan atau langsung ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian
mengalir di atas permukaan sebagai sungai, terus kembali ke laut.
(Limantara,L.M., 1986)
8 Hidrologi air tanah adalah cabang hidrologi yang berhubungan dengan air
tanah dan didefinisikan sebagai ilmu tentang keterdapatan, penyebaran, dan
pergerakan air di bawah permukaan bumi. Geohidrologi mempunyai mempunyai
makna yang sama dan hidrogeologi dibedakan hanya oleh penekanannya yang
lebih besar pada aspek kegeologian (Todd, 1980, h,1). Oleh sebab itu uraian mengenai air tanah tidak akan lepas dari ilmu hidrologi, mulai dari kejadian air
tanah, hingga pergerakan air tanah, sampai akhirnya mencapai lajur jenuh di
dalam akuifer.
2.2.1 Daur Hidrologi
Hampir semua air tanah merupakan komponen dalam daur hidrologi,
termasuk air permukaan danatmospheric waters(uap air). Sebagian kecil air tanah dapat masuk ke dalam daur ini dari masing-masing sumbernya (Todd dan Mays, 2005).
2.2.2 Daur Tertutup
Hujan yang jatuh ke bumi baik langsung menjadi aliran maupun tidak
langsung melalui vegetasi atau media lainnya akan membentuk daur aliran air
mulai dari tempat yang tinggi (gunung, pegunungan) menuju ke tempat yang
rendah baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah yang berakhir di laut.
Air berubah wujud berupa gas/uap akibat panas matahari dan disebut
dengan proses penguapan atau evaporasi. Uap ini bergerak di atmosfer (udara)
kemudian akibat perbedaan suhu di atmosfer dari panas menjadi dingin maka air
akan terbentuk akibat kondensasi dari uap menjadi keadaan cairan. Bila suhu
berada di bawah titik beku kristal-kristal es terbentuk. Tetesan air kecil tumbuh
oleh kondensasi dan berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh
gerakan udara turbulen sampai pada kondisi yang cukup besar menjadi butir-butir
air. Apabila jumlah butir air sudah cukup banyak dan akibat berat sendiri (secara
gravitasi) butir-butir air itu akan turun ke bumi dan proses turunnya butir air ini
disebut dengan hujan. Bila suhu udara turun sampai di bawah 00C, maka butir air akan berubah menjadi salju(Chow dkk., 1988).
Salju jadi persoalan yang penting di tempat atau negara yang mempunyai
perbedaan suhu yang besar. Pada waktu musim panas suhu bisa mencapai + 350C, namun pada waktu musim dingin suhu bisa mencapai–350C (bahkan lebih).
Hujan jatuh ke bumi baik secara langsung maupun melalui media misalnya
melalui tanaman. Di bumi air mengalir dan bergerak dengan berbagai cara. Pada
retensi (tempat penyimpanan) air akan menetap/tinggal untuk beberapa waktu.
Retensi dapat berupa retensi alam seperti daerah-daerah cekungan, danau,
tempat-tempat yang rendah dll., maupun retensi buatan manusia seperti tampungan,
sumur, embung, waduk dll.
Secara gravitasi (alami) air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah
yang rendah, dari gunung-gunung, pegunungan ke lembah, lalu ke daerah lebih
10 sistem jaringan sungai, sistem danau ataupun waduk. Dalam sistem sungai aliran
mengalir mulai dari sistem sungai yang kecil menuju ke sistem sungai yang besar
dan akhirnya akan menuju mulut sungai atau sering disebut muara yaitu tempat
bertemunya sungai dengan laut.
Sebagian air hujan yang jatuh di permukaan tanah meresap ke dalam tanah
dalam bentuk-bentuk infiltrasi, perkolasi, dan kapiler. Aliran air tanah dapat
dibedakan menjadi aliran air tanah dangkal, aliran air tanah dalam, aliran air tanah
antara dan aliran dasar (base flow). Disebut aliran dasar karena aliran ini merupakan aliran yang mengisi sistem jaringan sungai. Hal ini dapat dilihat pada
waktu musim kemarau, ketika hujan tidak turun untuk beberapa waktu, pada suatu
sistem sungai tertentu masih ada aliran secara tetap dan menerus.
Akibat panas matahari air di permukaan bumi juga akan berubah wujud
menjadi gas/uap melalui proses evaporasi dan bila proses tersebut melalui
tanaman disebut transpirasi. Air akan diambil oleh tanaman melalui akar-akarnya
yang dipakai untuk kebutuhan hidup dari tanaman tersebut, lalu air di dalam
tanaman juga akan keluar berupa uap akibat energi panas matahari. Proses
pengambilan air oleh akar tanaman kemudian terjadinya penguapan dari dalam
tanaman disebut sebagai evapo-transpirasi.
Evaporasi yang lain dapat terjadi pada sistem sungai, danau, embung,
waduk maupun air laut yang merupakan sumber air terbesar. Walaupun laut
adalah tempat dengan sumber air terbesar namun tidak bisa langsung
dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan karena mengandung garam dan dikenal
dengan nama air asin . Uap dan gas mengalir dan bergerak di atmosfer.
Kejadian tersebut membentuk suatu pergerakan berulang dan disebut
daur atau siklus hidrologi. Daur ini merupakan konsep dasar tentang
keseimbangan air secara global di bumi. Daur hidrologi juga menunjukkan semua
hal yang berhubungan dengan air. Bila dilihat keseimbangan air secara
menyeluruh maka air tanah dan aliran permukaan: sungai, danau, penguapan dll.
merupakan bagian-bagian dari beberapa aspek yang menjadikan daur hidrologi
menjadi seimbang sehingga disebut dengan daur hidrologi yang tertutup.
2.3 Air Bawah Tanah
2.3.1 Kejadian Air Tanah
Dua zone bawah – tanah utama dibagi oleh suatu permukaan yang tak
beraturan yang disebut bidang batas air – jenuh (water table). Bidang batas air
jenuh merupakan kedudukan titik-titik (dalam bahan bebas) yang mempunyai
tekanan hidrostatik sama dengan tekanan atmosferik. Di atas bidang batas air
jenuh, yakni di zone kapiler. Pori-pori tanah mungkin terisi udara ataupun air;
oleh karenanya kadang-kadang disebut zone aerasi. Dalam zone freatik , yaitu
dibawah bidang batas air jenuh, celah-celah tanah terisi dengan air,
kadang-kadang zone ini disebut zone air-jenuh. Zone freatik dapat memperpanjang
sampai kedalaman yang cukup besar, tetapi jika kedalamannya bertambah, berat
sendiri tanah bertendensi merapatkan ruang-ruang pori dan relative sedikit saja
air yang dijumpai pada kedalaman-kedalaman yang lebih besar dari 3 km (10.000
ft).( Linsley, Ray K., dkk, 1986)
12 Metode ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dengan
pengaturan pemberian air dapat diperoleh luas areal yang diari setiap
harinya konstan. Hal ini berarti bahwa debit yang dialirkan melalui canal
harus secara teratur ditambah dari hari ke hari karena kebutuhan akan air
untuk menjaga tinggi air pada petak basin yang sudah selesai diari dan
mngkounter kehilangan air akibat perkolasi dan evaporasi. (Ginting Makmur, 2014)Secara schematis, besarnya debit rencana yang diperlukan
dengan mempergunakan system ini adalah seperti diperlihatkan pada skets
pada gambar 2.2 dibawah ini :
Gambar 2.2.Prinsip Perencanaan Debit pada Constant Area Method
(Ginting Makmur, 2014)
Permasalahan yang dihadapi dengan metode ini adalah :
Debit rencana yang akan diperoleh mendimensi saluran adalah
besar dan hanya dipakai untuk waktu yang pendek; dan
Debit yang dialirkan berubah-ubah setiap hari sehingga sulit
mengoperasikannya atau mengontrolnya.
b. Constant Discharge Method
Dengan metode ini air diberi konstan dari hari kehari, jadi debit
yang mengalir canal adalah konstan. Pada awalnya air dipergunakan
seluruhnya untuk prewatering. Karena hal ini terus diperlukan terus menerus
dan kebutuhan air untuk menjaga muka air di dalam petak basin bertambah
besar dari hari ke hari maka jumlah areal yang dapat diari akan berkurang
dari hari ke hari.(Ginting Makmur, 2014). Secara skematis proses pengairan petak basin diperlihatkan pada gambar 2.3 di bawah ini.
Gambar 2.3.Prinsip perencanaan Pada constant Discharge Method
(Ginting Makmur, 2014)
Debit rencana dengan metode ini lebih kecil bila dibandingkan
14
menghitung ‘Debit Rencana” untuk pengolahan lahan dengan metode
‘Constant Discharge’ :
Misalkan :
I = Kebutuhan air (m/hari)
A = Total areal Irigasi (m2)
T = Lamanya waktu pengolahan (hari)
S = Kebutuhan air untuk prewatering (m/hari)
M = Kebutuhan air untuk penjagaan/maintenance (m/hari) Misalkan suatu
luasan (y) diolah dalam waktu (t) untuk pertambahan waktu yang
sangat kecil (dt) diperoleh :
Penyediaan air = I x A x dt
Pemakaian air = (S x dy) + (M x y x dt)
I x A x dt = (S x dy) + (M x y x dt)
2.3.2 Recharge dan Discharge antara Air Tanah dan Sungai
Hujan yang turun diatas permukaan tanah suatu daerah tangkapan,
sebagian berinfiltrasi masuk kedalam tanah dan sebagian lagi mengalir diatas
permukaan tanah menuju sungai, serta ada sebagian lagi yang tertahan diatas
permukaan tanah yang akhirnya akan menguap kembali ke atmosefer baik secara
direct(evaporasi), maupun penguapan yang dilakukan oleh tanaman (transpirasi). (Kodoatie & Sjarief., 2008.)
Pergerakan air dalam tanah dan permukaan dipengaruhi oleh gaya
gravitasi. Air permukaan maupun air dalam tanah bergerak menuju tempat yang
lebih rendah yang pada akhirnya akan sampai ke laut. Air tanah dan air
permukaan yang sampai ke laut, nantinya akan diuapkan kembali ke atmosfer
menjadi uap air dan setelah terkondensasi akan turun hujan (siklus hidrologi).
Selengkapnya bisa dilihat pada sketsa di bawah ini
Gambar 2.4. Sketsa daerah tangkapan dan daerah pelepasan pada suatu
daerah aliran
Daerah yang lebih tinggi merupakan daerah tangkapan atau pengisian
(recharge area) dan daerah yang lebih rendah merupakan daerah pelepasan atau pengeluaran (discharge area). Aliran air tanah dan aliran permukaan tidaklah dipandang secara parsial, dalam artian air tanah punya jalur sendiri dan air
permukaan punya jalur sendiri. Bisa saja dalam perjalanannya menuju laut ada air
16 sungai apabila dilihat sisirechargedandischarge.
Salah satu hal yang patut digarisbawahi disini, yakni pada pembahasan
sebelumnya mengenai air permukaan dikatakan suatu daerah tangkapan atau
daerah aliran sungai itu dibatasi oleh lereng atau punggung-punggung bukit.
Kalau air tanah batasannya adalah batas hidrogeologis (struktur batuan,
perlapisan,perlipatan, dll). Pada aliran permukan dikenal istilah daerah aliran air
sungai atau DAS, untuk aliran air tanah dikenal istilah CAT atau cekungan air
tanah. Cekungan air tanah (CAT), adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogelogis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan
(recharge), pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung (discharge).
Tanpa gangguan manusia, cekungan air tanah akan mengisi dan
mengeluarkan air yang berlebih melalui beberapa telusuran sampai keseimbangan
semu (quisiequilibrium). Sungai-sungai yang mempunyai muka air lebih rendah dari muka air tanah akan mendapat sumbangan (recharge) dari air tanah. Sungai-sungai yang memotong muka air tanah dan menerima aliran air tanah termasuk
dalam sungai permanen.
Jika sungai yang elevasi muka airnya lebih tinggi dari muka air tanah
(water table), maka sungai tersebut akan menyumbang ke air tanah (discharge). Sungai semacam ini termasuk dalam kategori sungai ephemeral, yakni sungai
yang hanya mengalir pada saat musim penghujan. Jika hujan tidak terjadi dalam
periode yang cukup panjang, sungai ini akan mengering akibat airnya telah
berperkolasi mengisi air tanah.
Gambar 2.5. Sketsa recharge antara air tanah dan sungai
Dischargedanrecharge air tanah bergantung pada letak air tanah (gorund water) dan muka air tanahnya (water table). Pada daerah tangkapan aliran air tanah menjauhi muka air tanah, atau bisa diartikan pada daerah tangkapan muka
air tanahnya terletak pada kedalaman tertentu sedangkan muka air tanah daerah
pengeluaran umumnya mendekati permukaan tanah, salah satu contohnya adalah
daerah pantai. (Kodoatie & Sjarief., 2008.)
Muka air tanah (water table) merupakan kedudukan titik-titik (di dalam tanah yang tidak tertekan) yang tekanan hidrostatiknya sama dengan tekanan
18 Tidak selalu juga pada daerah tinggi yang merupakan daerah tangkapan,
air tanah menjauhi muka air tanah. Terkadang pada daerah yang tinggi terjadi
perubahan kemiringan lereng, disitu muka air tanah bisa saja memotong muka
tanah. Munculnya air tanah ke permukaan bumi karena muka air tanah memotong
muka tanah, inilah yang disebut dengan mata air. Sumber utama aliran air sungai
berasal dari mata air yang berada di daerah hulu ( daerah yang tinggi).