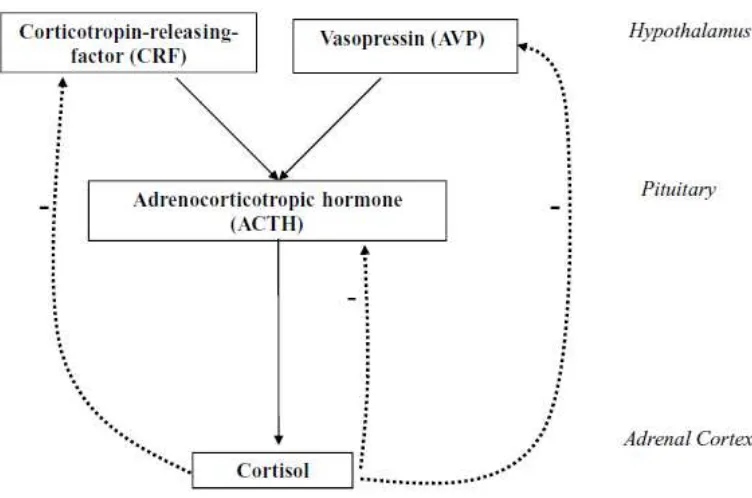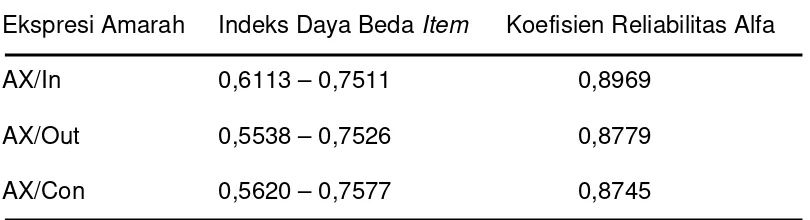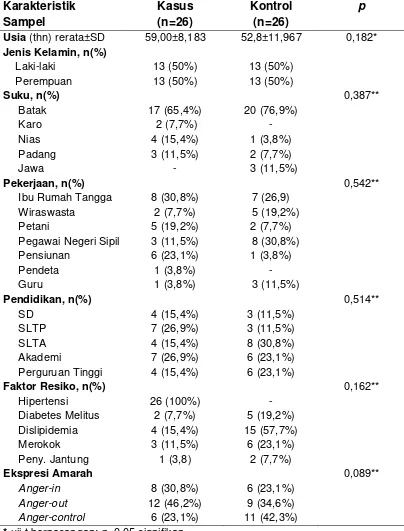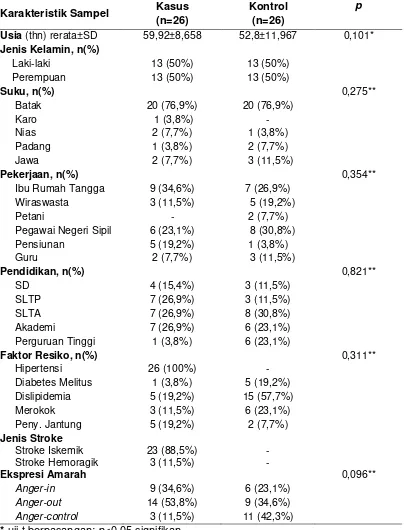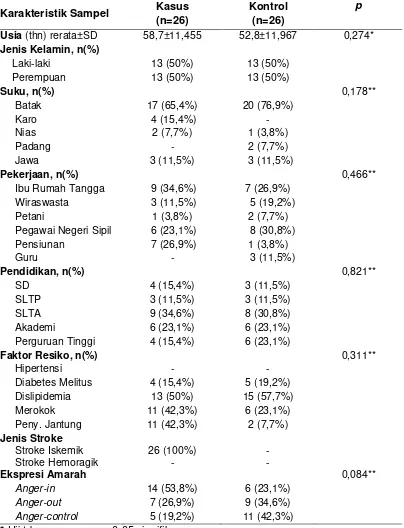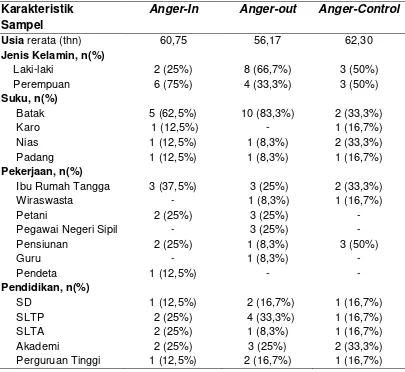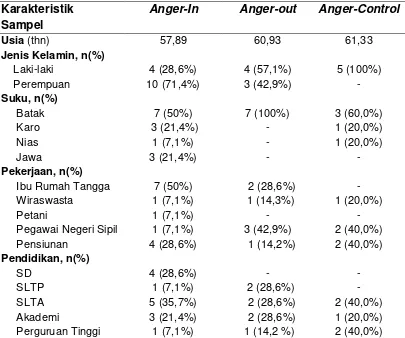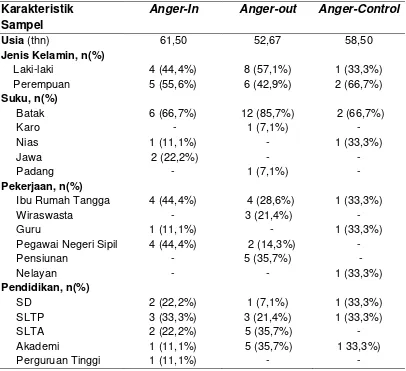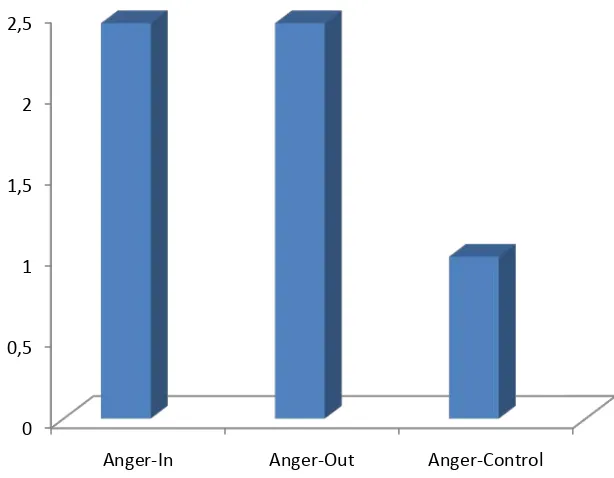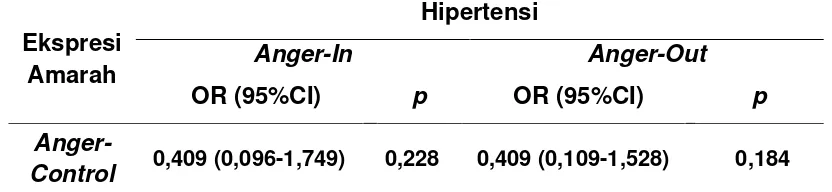RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE
BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH
(
ANGER-IN, ANGER-OUT,
ATAU
ANGER-CONTROL
)
TESIS
Oleh
MARIA THESSARINA SITEPU
Nomor Register CHS : 19817
PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT SARAF
FAKULTAS KEDOKTERAN USU /
RSUP.H. ADAM MALIK
MEDAN
RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE
BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH
(
ANGER-IN, ANGER-OUT,
ATAU
ANGER-CONTROL
)
T E S I S
Untuk Memperoleh Gelar Dokter Spesialis Saraf pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf pada
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
Oleh
MARIA THESSARINA SITEPU Nomor Register CHS : 19817
PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT SARAF
FAKULTAS KEDOKTERAN USU /
RSUP.H. ADAM MALIK
MEDAN
PERNYATAAN
RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE
BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH
(
ANGER-IN, ANGER-OUT,
ATAU
ANGER-CONTROL
)
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Medan, Mei 2014
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tesis : RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH (ANGER-IN, ANGER-OUT, ATAU ANGER- CONTROL) Nama : Maria Thessarina Sitepu
Nomor Register CHS : 19817
Program Studi : Ilmu Penyakit Saraf
Menyetujui Pembimbing I
NIP. 19660524 199203 1 002 dr. Aldy S. Rambe, SpS(K)
Pembimbing II Pembimbing III
dr. Cut Aria Arina, Sp.S dr. Iskandar Nasution, Sp.S, FINS NIP. 19771020 200212 2 001 NIP. 19690110 199903 1 002
Mengetahui / mengesahkan
Ketua Departemen Studi / SMF Ketua Program Studi / SMF Ilmu Penyakit Saraf Ilmu Penyakit Saraf
FK-USU/ RSUP HAM Medan FK-USU/ RSUP HAM Medan
dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K)
Telah diuji pada Tanggal: 6 Mei 2014
PANITIA TESIS
1. Prof. DR. Dr. Hasan Sjahrir, Sp.S(K) 2. Prof. Dr. Darulkutni Nasution, Sp.S(K) 3. Dr. Darlan Djali Chan, Sp.S
4. Dr. Yuneldi Anwar, Sp.S(K)
5. Dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K) (Penguji) 6. Dr. Kiking Ritarwan, MKT, Sp.S(K)
7. Dr. Aldy S. Rambe, Sp.S(K) 8. Dr. Puji Pinta O. Sinurat, Sp.S 9. Dr. Khairul P. Surbakti, Sp.S 10. Dr. Cut Aria Arina, Sp.S 11. Dr. Kiki M. Iqbal, Sp.S 12. Dr. Alfansuri Kadri, Sp.S 13. Dr. Aida Fitri, Sp.S
14. Dr. Irina Kemala Nasution, Sp.S 15. Dr. Haflin Soraya Hutagalung, Sp.S 16. Dr. Fasihah Irfani Fitri, M.Ked(Neu), Sp.S 17. Dr. Iskandar Nasution, Sp.S, FINS
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan kasihNya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan tesis akhir program studi ilmu penyakit saraf ini.
Tulisan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program studi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara / Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan.
Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :
1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan Ketua TKP PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. DR. Dr. Hasan Sjahrir, Sp.S(K), selaku Guru Besar Tetap Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/RSUP H.Adam Malik Medan yang dengan sepenuh hati telah mendorong, membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis mulai dari perencanaan, pembuatan dan penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K), Ketua Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara disaat penulis melakukan penelitian dan sebagai Ketua Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/RSUP H. Adam Malik Medan saat tesis ini selesai disusun yang banyak memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Yuneldi Anwar, Sp.S(K), Ketua Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara disaat penulis melakukan penelitian dan saat tesis ini selesai disusun yang banyak memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
telah mendorong, membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis mulai dari perencanaan, pembuatan dan penyelesaian tesis ini.
6. Guru-guru penulis: Prof Dr. Darulkutni Nasution, Sp.S(K); dr. Darlan Djali Chan, Sp.S; dr. Kiking Ritarwan, MKT, Sp.S(K); dr. Irsan NHN Lubis, Sp.S; dr. Arif Simatupang, Sp.S; dr. Puji Pinta O. Sinurat, Sp.S; dr. Khairul P. Surbakti, Sp.S; dr. S. Irwansyah, Sp.S (alm); dr. Kiki M.Iqbal, Sp.S; dr.Alfansuri Kadri, Sp.S; dr. Aida Fitri, Sp.S; dr.Haflin Soraya Hutagalung, Sp.S, dr. Fasihah Irfani Fitri, M.Ked(Neu), Sp.S; dr. RA Dwi Pujiastuti, M.Ked(Neu), Sp.S dan guru lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan suasana kerja yang baik sehingga penulis dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing Sibolga yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan suasana kerja yang nyaman dan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. DR. Ir. Erna Mutiara, M.Kes, selaku pembimbing statistik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan berdiskusi dengan penulis dalam pembuatan tesis ini.
10. Rekan-rekan sejawat peserta PPDS-I Departemen Neurologi FK-USU/RSUP. H. Adam Malik Medan, teristimewa kepada teman–teman seangkatan (dr. Adikia Andreas Sitepu, dr. Neni Nurchalida, dr. Lisbeth Meilina Sitanggang, dr. Siska Imelda Tambunan, dr. Azwita Effrina Hasibuan), yang banyak memberikan masukan berharga kepada penulis melalui diskusi-diskusi kritis dalam berbagai pertemuan formal maupun informal, serta selalu memberikan dorongan-dorongan yang membangkitkan semangat kepada penulis menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf.
12. Semua pasien yang berobat ke Departemen Neurologi RSUP H. Adam Malik Medan dan RSU FL. Tobing Sibolga yang telah bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini.
13. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, dr. Ngg. Sitepu dan Adelina br Ginting yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan senantiasa memberi dukungan moril dan materi, bimbingan dan nasehat serta doa yang tulus agar penulis tetap sabar dan tegar dalam mengikuti pendidikan ini sampai selesai. 14. Ucapan terima kasih kepada kedua Bapak/Ibu mertua saya, Drs. S.J. Tarigan
dan Purnama br Purba, yang selalu memberikan dorongan, semangat dan nasehat serta doa yang tulus agar tetap sabar dan tegar dalam mengikuti pendidikan sampai selesai.
15. Teristimewa kepada suamiku tercinta Rudy H. Tarigan, BA, MIB yang selalu dengan sabar dan penuh pengertian, mendampingi dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam suka dan duka, saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.
16. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa membantu, memberi dorongan, pengertian, kasih sayang dan doa dalam menyelesaikan pendidikan ini, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
17. Kepada semua rekan dan sahabat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya sekecil apapun, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada kita semua. Akhirnya penulis mengharapkan semoga penelitian dan tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua jasa dan budi baik mereka yang telah membantu penulis tanpa pamrih dalam mewujudkan cita-cita penulis. Akhirnya penulis mengharapkan semoga penelitian dan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Medan, Mei 2014
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap : dr. Maria Thessarina Sitepu Tempat / tanggal lahir : Kabanjahe, 5 Januari 1985 Agama : Katolik
Nama Ayah : dr. Ngguntur Sitepu Nama Ibu : Adelina br Ginting
Nama Suami : Rudy Hartanta Tarigan, BA, MIB
Riwayat Pendidikan
1. Sekolah Dasar di SD. St. Yoseph Kabanjahe tamat tahun 1997.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Santa Maria Kabanjahe tamat tahun 2000. 3. Sekolah Menengah Umum di SMU. Negeri 1 Medan tamat tahun 2003.
4. Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara tamat tahun 2008.
Riwayat Pekerjaan
II.5. EKSPRESI AMARAH DAN STROKE 36
IV.1.2.1. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-In terhadap Kejadian Hipertensi 68
IV.1.2.2. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Out terhadap Kejadian Hipertensi 69
IV.1.2.3. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Control terhadap Kejadian Hipertensi 70
terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 70
IV.1.3.2. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Out terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 72
IV.1.3.3. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Control terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 72
IV.1.4. Besar Resiko Ekspresi Amarah terhadap Kejadian Stroke dengan Hipertensi 73
IV.1.4.1. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-In dengan Kejadian Stroke dengan Hipertensi 73
IV.1.4.2. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Out dengan Kejadian Stroke dengan Hipertensi 75
IV.1.4.3. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Control dengan Kejadian Stroke dengan Hipertensi 75
IV.2.2 PEMBAHASAN 76
IV.2.1. Karakteristik Demografi Subjek Penelitian 77
IV.2.1.1. Karakteristik Demografi Penderita Hipertensi berdasarkan Ekspresi Amarah 77
IV.2.1.2. Karakteristik Demografi Penderita Stroke dengan Hipertensi berdasarkan Ekspresi Amarah 78
IV.2.1.3. Karakteristik Demografi Penderita Stroke tanpa Hipertensi berdasarkan Ekspresi Amarah 79
IV.2.2. Besar Resiko Kejadian Hipertensi Berdasarkan Perbedaan Ekspresi Amarah (Anger-In, Anger-Out, dan Anger-Control) 81
IV.2.3. Besar Resiko Kejadian Stroke dengan Hipertensi Berdasarkan Perbedaan Ekspresi Amarah (Anger-In, Anger-Out, dan Anger-Control) 83
DAFTAR SINGKATAN
CRF : corticotropin-releasing factor
CT : Computed Tomography
dkk : dan kawan kawan
FK USU : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara HPA : Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical
HR : Hazard Ratio
IMT : intimal-medial thickness
JNC : Joint National Committee
LACI : Lacunar Infarct
NCCT : Non-Contrast Computed Tomography
OR : Odds Ratio
PACI : Partial Anterior Circulation Infarct
POCI : Posterior Circulation Infarct
POMC : proopiomelanocortin RH : Relative Hazard
t-PA : tissue-type Plasminogen Activator
DAFTAR ISTILAH / LAMBANG
α : alfa
β : beta
n : Besar sampel p : Tingkat kemaknaan
Zα : Nilai baku normal berdasarkan nilai α (0,05) yang telah ditentukan 1,96
Zβ : Nilai baku berdasarkan nilai β (0,20) yang ditentukan oleh peneliti 0,842
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Kriteria
The Seventh Joint National Committee (JNC VII) 25 Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas STAXI 50 Tabel 3. Karakteristik demografi subjek penelitian kelompok
kasus hipertensi dengan kelompok kontrol 59 Tabel 4. Karakteristik demografi subjek penelitian kelompok
kasus stroke dengan hipertensi dengan kelompok
kontrol 60
Tabel 5. Karakteristik demografi subjek penelitian kelompok
kasus stroke tanpa hipertensi dengan kelompok kontrol 61 Tabel 6. Karakteristik demografi subjek penelitian penderita
hipertensi berdasarkan ekspresi amarah 63 Tabel 7. Karakteristik demografi subjek penelitian penderita
stroke tanpa hipertensi berdasarkan ekspresi amarah 65 Tabel 8. Karakteristik demografi subjek penelitian penderita
stroke dengan hipertensi berdasarkan ekspresi amarah 67 Tabel 9. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap
Kejadian Hipertensi 68 Tabel 10. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah Anger-Control
dengan Kejadian Hipertensi 70 Tabel 11. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap
Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 71 Tabel 12. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah Anger-Control
terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 73 Tabel 13. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah
terhadap Kejadian Stroke dengan Hipertensi 74 Tabel 14. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah Anger-Control
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Diagram hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis 32 Gambar 2. Grafik Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap
Kejadian Hipertensi 69 Gambar 3. Grafik Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap
Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 71 Gambar 4. Grafik Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 LEMBAR PENJELASAN KEPADA SUBJEK PENELITIAN LAMPIRAN 2 PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)
LAMPIRAN 3 LEMBAR PENGUMPULAN DATA LAMPIRAN 4 Spielberger Trait Anger Expression Scale
ABSTRAK
Latar Belakang : Ekspresi amarah merupakan salah satu dimensi dari amarah yang mungkin berkaitan dengan hipertensi dan stroke. Sampai saat ini masih sedikit penelitian yang mengevaluasi hubungan antara ekspresi amarah dengan resiko kejadian hipertensi dan stroke. Penelitian ini secara retrospektif meneliti besar resiko kejadian hipertensi dan stroke berdasarkan perbedaan ekspresi amarah. Metode : Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol pada 104 pasien, yang diambil dari januari 2014 hingga April 2014. Terdapat empat kelompok dalam studi ini, yaitu tiga kelompok kasus dan satu kelompok kontrol. Kelompok kasus merupakan pasien dengan hipertensi, stroke dengan hipertensi dan stroke tanpa hipertensi. Kelompok kontrol merupakan pasien yang tidak menderita stroke maupun hipertensi, yang disesuaikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pada kelompok kasus maupun kontrol diwawancara mengenai jenis ekspresi amarahnya menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Data dianalisa menggunakan menggunakan uji regresi logistik kondisional. Hubungan dinyatakan sebagai OR (odds ratio) dengan confidence interval (CI) 95%.
Hasil : Jumlah total adalah 104 subjek yang memenuhi kriteria, masing-masing kelompok terdiri dari 26 pasien. Laki-laki memiliki jumlah yang sama dengan perempuan, masing-masing berjumlah 13 orang. Besar resiko kejadian hipertensi meningkat baik pada penderita dengan ekspresi anger-in maupun anger-out, namun hal ini bersifat tidak signifikan, dengan nilai berturut-turut adalah OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) dan OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke dengan hipertensi secara signifikan berhubungan dengan ekspresi amarah anger-in maupun anger-out dengan nilai berturut-turut OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke tanpa hipertensi secara signifikan meningkat pada penderita dengan ekspresi anger-in
dibandingkan dengan anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356.
Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa anger-in dan anger-out
meningkatkan resiko kejadian hipertensi, namun tidak signifikan. Ekspresi anger-in
dan anger-out secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke dengan hipertensi. Ekspresi anger-in secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke tanpa hipertensi.
ABSTRACT
Background: Anger expression is a dimension of anger that may be strongly related to hypertension and stroke. To date few studies have evaluated the relationship between anger expression with the risk of hypertension and stroke. This study retrospectively examined the risk of hypertension and stroke based on anger expression style.
Methods : This was a case control study of 104 patients, conducted from January 2014 to April 2014. There were 4 groups in this study, three case groups and one control group. Case groups were patients with hypertension, stroke with hypertension and stroke without hypertension. Control subjects were patients other than hypertension and stroke, matching individually based on age and gender. Both case and control subjects were asked about anger expression style using a structured questionnaire. Data were analyzed with conditional logistic regression. Associations are presented as odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI). Results : A total of 104 subjects were eligible, each group consisted of 26 subjects. Men were the same number as women, 13 (50%) for each gender. Odds ratio for hypertension were increased with both anger-in and anger-out, but not significantly, with OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) and OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke with hypertension were significantly associated with anger-in and anger-out with OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke without hypertension were significantly associated with anger-in if compared with anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356).
Conclusion : This study showed that anger-in and anger-out increased the risk of hypertension, but not significantly. Anger-in and anger-out was significantly increasing the risk of stroke with hypertension. Anger-in was significantly increasing the risk of stroke without hypertension.
ABSTRAK
Latar Belakang : Ekspresi amarah merupakan salah satu dimensi dari amarah yang mungkin berkaitan dengan hipertensi dan stroke. Sampai saat ini masih sedikit penelitian yang mengevaluasi hubungan antara ekspresi amarah dengan resiko kejadian hipertensi dan stroke. Penelitian ini secara retrospektif meneliti besar resiko kejadian hipertensi dan stroke berdasarkan perbedaan ekspresi amarah. Metode : Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol pada 104 pasien, yang diambil dari januari 2014 hingga April 2014. Terdapat empat kelompok dalam studi ini, yaitu tiga kelompok kasus dan satu kelompok kontrol. Kelompok kasus merupakan pasien dengan hipertensi, stroke dengan hipertensi dan stroke tanpa hipertensi. Kelompok kontrol merupakan pasien yang tidak menderita stroke maupun hipertensi, yang disesuaikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pada kelompok kasus maupun kontrol diwawancara mengenai jenis ekspresi amarahnya menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Data dianalisa menggunakan menggunakan uji regresi logistik kondisional. Hubungan dinyatakan sebagai OR (odds ratio) dengan confidence interval (CI) 95%.
Hasil : Jumlah total adalah 104 subjek yang memenuhi kriteria, masing-masing kelompok terdiri dari 26 pasien. Laki-laki memiliki jumlah yang sama dengan perempuan, masing-masing berjumlah 13 orang. Besar resiko kejadian hipertensi meningkat baik pada penderita dengan ekspresi anger-in maupun anger-out, namun hal ini bersifat tidak signifikan, dengan nilai berturut-turut adalah OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) dan OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke dengan hipertensi secara signifikan berhubungan dengan ekspresi amarah anger-in maupun anger-out dengan nilai berturut-turut OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke tanpa hipertensi secara signifikan meningkat pada penderita dengan ekspresi anger-in
dibandingkan dengan anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356.
Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa anger-in dan anger-out
meningkatkan resiko kejadian hipertensi, namun tidak signifikan. Ekspresi anger-in
dan anger-out secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke dengan hipertensi. Ekspresi anger-in secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke tanpa hipertensi.
ABSTRACT
Background: Anger expression is a dimension of anger that may be strongly related to hypertension and stroke. To date few studies have evaluated the relationship between anger expression with the risk of hypertension and stroke. This study retrospectively examined the risk of hypertension and stroke based on anger expression style.
Methods : This was a case control study of 104 patients, conducted from January 2014 to April 2014. There were 4 groups in this study, three case groups and one control group. Case groups were patients with hypertension, stroke with hypertension and stroke without hypertension. Control subjects were patients other than hypertension and stroke, matching individually based on age and gender. Both case and control subjects were asked about anger expression style using a structured questionnaire. Data were analyzed with conditional logistic regression. Associations are presented as odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI). Results : A total of 104 subjects were eligible, each group consisted of 26 subjects. Men were the same number as women, 13 (50%) for each gender. Odds ratio for hypertension were increased with both anger-in and anger-out, but not significantly, with OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) and OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke with hypertension were significantly associated with anger-in and anger-out with OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke without hypertension were significantly associated with anger-in if compared with anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356).
Conclusion : This study showed that anger-in and anger-out increased the risk of hypertension, but not significantly. Anger-in and anger-out was significantly increasing the risk of stroke with hypertension. Anger-in was significantly increasing the risk of stroke without hypertension.
BAB I PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Di negara-negara yang sedang berkembang, penyakit jantung, kanker
dan stroke menggantikan penyakit menular dan malnutrisi sebagai
penyebab kematian dan disabilitas. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2007 yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penyebab
kematian tertinggi adalah penyakit kardiovaskular (31,9%) termasuk
hipertensi (6,8%) dan stroke (15,4%). Di Amerika, diperkirakan 1 dari 4 orang
dewasa menderita hipertensi (Rahajeng, 2009).
Stroke merupakan penyebab kematian ketiga terbanyak di Amerika
Serikat setelah penyakit jantung dan kanker. Stroke diperkirakan menjadi 1
dari 16 penyebab kematian di Amerika Serikat pada tahun 2004. Setiap
tahun sekitar 700.000 orang mengalami serangan stroke baru maupun
berulang. Kira-kira 500.000 merupakan serangan pertama dan 200.000
merupakan serangan berulang. Dan dari seluruh kasus stroke, sekitar 87%
merupakan stroke iskemik dan sisanya merupakan perdarahan. (Hacke dkk,
2003; Rosamond dkk, 2007)
Penelitian yang berskala cukup besar di Indonesia dilakukan oleh
survei ASNA (ASEAN Neurological Association) di 28 rumah sakit di seluruh
Indonesia, pada penderita stroke akut yang dirawat di rumah sakit, dan
dilakukan survei mengenai faktor-faktor resiko, lama perawatan, mortalitas
usia di bawah 45 tahun cukup banyak yaitu 11,8%, usia 45-64 tahun
berjumlah 54,7% dan di atas usia 65 tahun 33,5%. (Misbach, 2007)
Amarah (anger) merupakan emosi yang dapat memberikan
konsekuensi besar dalam hal kesehatan berdasarkan kompleksitas sirkuit
neuron. Beberapa penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 1970-an yang
mencari hubungan antara derajat amarah dengan hipertensi menemukan
bahwa pengaruh amarah khususnya terlihat sebagai tekanan darah yang
labil. Dibandingkan dengan individu yang jarang marah, orang yang dengan
tingkat amarah yang tinggi menunjukkan tekanan darah sistolik dan diastolik
yang lebih tinggi. Bahkan pada anak-anak, analisis multivariat menunjukkan
tingkat amarah berkorelasi positif dengan tekanan darah (Paulus dkk, 2004).
Individu yang mengeluarkan ekspresi amarahnya menunjukkan
tekanan darah diastolik yang tinggi, berbeda dengan individu yang menahan
rasa amarahnya (p<0,04) (Suchday and Larkin, 2001). Penelitian oleh Ohira,
dkk pada tahun 2000 di Jepang menunjukkan adanya hubungan terbalik
yang signifikan antara anger-out dengan tekanan darah sistolik pada pekerja
pria. Sebagai kesimpulan, penelitian tersebut menyatakan pekerja pria di
Jepang yang tidak mengekspresikan amarahnya memiliki kemungkinan yang
lebih tinggi untuk mengalami hipertensi (Ohira dkk, 2000).
Pada satu studi meta-analisis yang meneliti tekanan darah, ekspresi
amarah berhubungan positif dengan tekanan darah sistolik (Schum dkk,
2003), dan pengamatan belakangan ini menunjukkan adanya hubungan
antara ekspresi amarah dengan terjadinya hipertensi esensial (Jorgensen
Everson dkk pada tahun 1998 melakukan penelitian yang mencari
hubungan antara ekspresi amarah dengan kejadian hipertensi, didapatkan
bahwa pria yang sering mengeluarkan ekspresi amarahnya memiliki lebih
dari 2,5 kali resiko lebih tinggi untuk mengalami hipertensi (OR = 2.61, 95%
CI 1.38-4.97; p<0,003) bila dibandingkan dengan pria yang tidak
menunjukkan ekspresi amarahnya setelah dilakukan penyesuaian terhadap
usia dan faktor resiko lainnya.
Everson dkk (1998) meneliti hubungan antara jenis ekspresi amarah
dan insiden hipertensi pada populasi berjumlah 537 pria dengan keadaan
normotensi pada awalnya. Ekspresi amarah diukur menggunakan
Spielberger’s Anger-out and Anger-in scales. Hasil dari empat tahun
pengamatan dan menggunakan analisis regresi dengan penyesuaian
terhadap usia, menunjukkan bahwa peningkatan satu poin pada skor
anger-out akan meningkatkan 12% besar resiko terjadinya hipertensi. Selain itu,
peningkatan satu poin pada skor anger-in juga berkaitan dengan 12%
peningkatan resiko terjadinya hipertensi. Hasil tersebut membuktikan adanya
hubungan antara jenis ekspresi amarah dengan resiko terjadinya hipertensi
sehingga menunjukkan bahwa skor anger-in dan anger-out yang tinggi dapat
menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi (Everson dkk, 1998).
Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang
berbeda. Dimana ekspresi amarah yang rendah berhubungan dengan
peningkatan resiko penyakit kardiovaskular (Suls and Wan, 1993), dan
darah dan terjadinya aterosklerosis (Everson dkk, 1998; Matthews dkk,
1998).
Amarah dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan fisik,
sebagian besar merupakan penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular
atau stroke. Walaupun data epidemiologi dan penelitian klinis menunjukkan
adanya hubungan yang positif antara amarah dengan penyakit
kardiovaskular, sedikit data yang ada menjelaskan kaitannya dengan stroke
(Williams dkk, 2002).
Adler dkk pada suatu penelitian retrospektif, melaporkan bahwa pada
subjek penelitiannya, stroke sebagian besar didahului oleh keadaan yang
cenderung negatif, terutama keputusasaan dan amarah. Sama halnya
dengan Gianturco dkk, melaporkan bahwa bila dibandingkan dengan subjek
kontrol yang diopname, sebagian besar penderita stroke baru saja
mengekspresikan amarahnya keluar sesaat sebelum mendapatkan serangan
stroke. Walaupun laporan penuh dari Framingham Heart Study tidak didapat,
dari abstrak disimpulkan bahwa insiden stroke dalam 10 tahun penelitian
berhubungan signifikan dengan amarah pada wanita dan secara garis besar
berkaitan dengan amarah pada pria, namun hubungan ini secara statistik
tidak signifikan setelah penyesuaian terhadap faktor resiko. (Williams dkk,
2002)
Beberapa penelitian saat ini menunjukkan hubungan yang sangat
signifikan antara amarah dengan kejadian stroke. Contohnya adalah orang
yang mengekspresikan amarahnya bila dibandingkan dengan orang yang
mengalami stroke (RH 2,03; 95% CI, 1,05-3,94) setelah menyesuaikan
terhadap beberapa faktor seperti usia, merokok, kadar profil lipid, riwayat
diabetes dan hipertensi. Analisis tambahan menunjukkan bahwa hubungan
ini terutama terdapat pada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung
iskemik. Pada individu tersebut, amarah yang diekspresikan keluar dapat
memprediksi lebih dari enam kali peningkatan resiko terjadinya stroke (RH
6,87; 95% CI, 1,50-31,4) setelah penyesuaian terhadap beberapa faktor
resiko. Pada penelitian lain, orang dengan usia kurang dari 60 tahun dengan
karakter yang mudah marah berkaitan dengan tiga kali peningkatan resiko
terjadinya stroke hemoragik dan iskemik bila dibandingkan dengan orang
dengan karakter yang tidak mudah marah. Selain itu, amarah juga dapat
menjadi konsekuensi dari stroke. Khususnya, ketidakmampuan untuk
mengontrol amarah atau agresi sangat berkaitan dengan lesi pada daerah
frontal-lentikulokapsular-pontin. (Everson dkk, 1999; Kim JS, 2002; Paulus
dkk, 2004). Selain itu, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Angerer dkk
pada tahun 2000, didapatkan bahwa orang dengan ekspresi amarah
anger-out beresiko tiga kali lebih tinggi mengalami stroke dibandingkan dengan
orang yang jarang menunjukkan amarahnya dengan nilai OR 3,19 (95% CI
2,5-16,6) (Angerer dkk, 2000).
Eng dkk (2003) yang meneliti tentang hubungan skor anger-out
dengan resiko kejadian stroke melaporkan bahwa dari hasil penelitian kohort
selama 2 tahun (1996-1998) pada subjek pria sehat dengan usia 50-85 tahun
tanpa riwayat penyakit kardiovaskular, didapatkan bahwa subjek dengan
setengahnya mengalami stroke (RR 0,56; 95% CI 0,32-0,97) dalam 2 tahun
pengamatan bila dibandingkan dengan subjek yang skor anger-out nya lebih
rendah setelah disesuaikan terhadap faktor resiko yang ada. Disimpulkan
bahwa ekspresi amarah berhubungan terbalik dengan besar resiko terjadinya
stroke.
Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Everson dkk (1999)
didapatkan bahwa anger-in dan anger-control tidak berhubungan dengan
resiko terjadinya stroke.
I.2. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang penelitian-penelitian terdahulu seperti
yang telah dirumuskan di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimanakah besar resiko kejadian hipertensi dan stroke
berdasarkan perbedaan ekspresi amarah (anger-in, anger-out, atau
anger-control) ?
I.3. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan :
I.3.1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui besar kejadian hipertensi dan stroke berdasarkan
perbedaan ekspresi amarah (anger-in, anger-out, atau anger-control).
I.3.2. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui besar resiko kejadian hipertensi pada individu dengan
2. Untuk mengetahui besar resiko kejadian hipertensi pada individu dengan
ekspresi amarah anger-out.
3. Untuk mengetahui besar resiko kejadian hipertensi pada individu dengan
ekspresi amarah anger-control.
4. Untuk mengetahui besar resiko kejadian stroke (dengan atau tanpa
hipertensi) pada individu dengan ekspresi amarah anger-in.
5. Untuk mengetahui besar resiko kejadian stroke (dengan atau tanpa
hipertensi) pada individu dengan ekspresi amarah anger-out .
6. Untuk mengetahui besar resiko kejadian stroke (dengan atau tanpa
hipertensi) pada individu dengan ekspresi amarah anger-control.
7. Untuk mengetahui karakteristik demografi penderita hipertensi dan
stroke.
8. Untuk mengetahui karakteristik demografi penderita hipertensi
berdasarkan ekspresi amarah.
9. Untuk mengetahui karakteristik demografi penderita stroke berdasarkan
ekspresi amarah.
I.4. HIPOTESIS
Ada hubungan antara ekspresi amarah (anger-in, anger-out, dan
I.5. MANFAAT PENELITIAN
I.5.1. Manfaat Penelitian untuk Peneliti
Manfaat penelitian untuk peneliti adalah sebagai tugas dan
persyaratan dalam pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit saraf.
I.5.2. Manfaat Penelitian untuk Ilmu Pengetahuan
Dengan mengetahui adanya hubungan antara ekspresi amarah
(anger-in, anger-out, dan anger-control) dengan kejadian hipertensi dan
stroke, maka diketahui bahwa ekspresi amarah tertentu dapat meningkatkan
resiko kejadian hipertensi dan stroke.
I.5.3. Manfaat Penelitian untuk Masyarakat
Dengan mengetahui adanya hubungan antara ekspresi amarah
(anger-in, anger-out, dan anger-control) dengan kejadian hipertensi dan
stroke, maka diharapkan kepada masyarakat agar dapat mengendalikan diri
dalam hal ekspresi amarah dengan cara yang bijaksana, sehingga dapat
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1. AMARAH
II.1.1. Definisi Amarah (Anger)
Menurut Spielberger (1999), amarah adalah keadaan psikobiologikal
emosional yang pada umumnya disertai dengan ketegangan otot dan
mengaktifkan sistem sistem saraf otonom dan neuroendokrin (Cayubit,
2013). Amarah merupakan reaksi emosional akut, yang dicetuskan oleh
beberapa keadaan seperti adanya ancaman, agresi, terkekang, serangan
verbal, kekecewaan atau kegagalan. Amarah merupakan keadaan emosi
yang paling primitif, dialami pada seluruh tingkat usia, dan timbul secara
teratur dalam kehidupan setiap orang dan merupakan keadaan emosi yang
umum terjadi dalam keadaan inter-personal yang stressful. Menjadi marah
diperkirakan adalah merupakan aksi agresif dan merasa marah diperkirakan
merupakan kesadaran subjektif terhadap adanya impuls agresif. (Palaparthi
& Rani, 2012)
Amarah merupakan emosi yang alami dan normal. Setiap orang
mengalami sesuatu yang mereka tidak inginkan dan kekecewaan dapat
menjadi cukup kuat untuk menyebabkan perasaan marah. Amarah juga
merujuk pada keadaan emosi dengan intensitas yang bervariasi dari marah
Cara alami untuk mengekspresikan amarah adalah dengan
memberikan respon secara agresif. Namun para ahli percaya bahwa
seseorang tidak dapat begitu saja menyerang atau mengekspresikan rasa
amarahnya pada orang atau objek lain yang mengganggunya oleh karena
adanya hukum, norma sosial dan tempat tertentu yang membatasi amarah
seseorang untuk diekspresikan. Menurut Spielberger, ekspresi amarah terdiri
dari tiga jenis, yaitu mengungkapkan keluar, menekan/menahan, dan
mengontrol (meredakan). Ekspresi amarah keluar (anger-out) merefleksikan
kecendrungan sifat agresif di sekitar orang lain. Tipe lain dari ekspresi
amarah adalah menekan (anger-in), yaitu menyimpan rasa amarah atau
mengabaikan atau menyangkalnya. Tetapi melakukan hal ini merupakan hal
yang tidak sehat karena amarah dapat diarahkan ke dalam diri sendiri. Oleh
karena itu, Spielberger merekomendasikan untuk mengubah rasa amarah
tersebut dengan cara menahannya, memikirkannya dan kemudian
memfokuskan pada sesuatu yang positif. Tujuannya adalah untuk
mengubahnya menjadi sifat yang lebih membangun. Dan jenis ekspresi
amarah yang terakhir adalah dimana seseorang dapat meredakan atau
mengontrol rasa amarah baik keluar atau ke dalam dengan merelakskan dan
membiarkan perasaan tersebut untuk surut. (Keskin dkk, 2011; Cayubit,
2013)
II.1.2. Ekspresi Amarah
Ekspresi amarah terbagi atas tiga jenis utama. Jenis pertama adalah
ekspresi amarah yang dikeluarkan ke orang lain atau lingkungan luar
menahan atau menekan perasaan marah (anger-in). Individu yang berusaha
mengontrol ekspresi amarah (anger-control) merupakan komponen ketiga
dari ekspresi amarah (Howell dkk, 2007; Palaparthi & Rani, 2012).
Komponen anger-out dan anger-in bukan berarti berada pada dua kutub
yang berlawanan namun bersifat orthogonal dan keduanya berpotensi untuk
terdapat pada individu yang sama (Stewart dkk, 2008).
Sebagai tambahan terhadap kepribadian, terdapat beberapa
perbedaan pada reaksi amarah berdasarkan jenis kelamin. Dikatakan bahwa
pria mengekspresikan rasa amarahnya relatif secara langsung tidak seperti
wanita yang mengekspresikan amarahnya secara tidak langsung. Dimana
perlakuan yang tidak adil, disalahkan akibat kesalahan orang lain, keegoisan,
kritik lebih menyebabkan amarah pada wanita daripada pria, dan negative
self-perception lebih meningkatkan rasa amarah pada pria (Keskin dkk,
2011).
Di lain pihak, dilaporkan bahwa reaksi amarah menurun dengan
meningkatnya usia. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada
kelompok dewasa muda dan remaja, dimana didapatkan bahwa reaksi dan
sifat amarah meningkat dengan bertambahnya usia. Pada penelitian
mengenai pengaruh pendidikan terhadap reaksi amarah, didapatkan bahwa
individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki level amarah yang
lebih rendah karena kondisi kognitif yang nyaman dan kemampuan untuk
II.1.3. Neurobiologi Anger
Hipotesis somatic marker yang diajukan oleh Damasio dan kolega
merupakan konsep pendekatan yang berguna dalam memahami
neurobiologi emosi pada umumnya, dan amarah pada khususnya. Kunci
gagasan dalam hipotesa ini adalah sinyal petanda atau marker, dimana otak
digambarkan/diwakilkan dalam bentuk body states, yang memiliki pengaruh
penting dalam menentukan bagaimana respon seseorang terhadap stimulus
dari luar. Pengaruhnya berbeda-beda, dimana beberapa terjadi secara
terbuka atau secara sadar dan beberapa terjadi secara tersamar atau secara
tidak sadar. Sinyal petanda ini berasal dari proses bioregulasi, misalnya
mengatasi perbedaan informasi mengenai body state dari sistem saraf
perifer dan otak kemudian menghasilkan dugaan terhadap keadaannya saat
itu. Penanda tersebut disebut dengan somatik karena hubungannya dengan
struktur keadaan tubuh (body-state) dan pengaturan bahkan ketika mereka
tidak timbul pada tubuh secara tepat namun lebih kepada perwakilan
gambaran otak melalui tubuh (Paulus dkk, 2004).
Beberapa peneliti berpendapat bahwa amarah dan agresi timbul
akibat kesalahan dalam meregulasi emosi. Perhatian khusus telah diberikan
pada korteks prefrontal, cingulate anterior, korteks parietal, dan amigdala
sebagai bagian penting dari sirkuit yang mungkin terganggu pada orang
dengan masalah yang berkaitan dengan amarah. Pada pengamatan saat ini
berdasarkan literatur neuroimejing fungsional, korteks prefrontal medial
ditemukan memiliki peranan yang penting dalam proses emosi. Dimana rasa
dengan aktivitas pada cingulate subkalosal. Emosi yang diinduksi oleh
stimulus visual akan mengaktifkan korteks oksipital dan amigdala. Pada
akhirnya, kebutuhan emosi berkaitan dengan keadaan kognitif melibatkan
cingulate anterior dan insula. Dengan demikian, sirkuit yang terdiri dari
amigdala, cingulate anterior dan insula mungkin merupakan struktur kunci
dalam ekspresi amarah (Paulus dkk, 2004).
Amigdala berperan penting dalam mencetuskan pengetahuan
terhadap adanya ancaman dan bahaya yang ditandai melalui ekspresi wajah.
Diantara berbagai emosi dasar, kerusakan amigdala akan
mengganggu proses amarah dan rasa takut, karena amigdala secara khusus
penting dalam merespon emosi-emosi tersebut. Misalnya amigdala bersama
dengan daerah otak lainnya, membantu memberikan respon yang tepat
terhadap sinyal bahaya melalui fungsi auditori. Selain amigdala, daerah
korteks lainnya akan memodulasi naik turunnya ekspresi dari amarah. Dalam
keadaan cemas maupun marah ditemukan adanya peningkatan aliran darah
ke otak pada regio frontal inferior kiri dan temporal kiri. Beberapa peneliti
menyatakan terdapat peran penting bagian posterior dari girus singuli kanan
dan girus temporal medial dari hemisfer kiri yang akan menimbulkan ekspresi
wajah yang marah (Paulus dkk, 2004).
Namun demikian, peneliti lainnya menemukan bahwa amarah
berkaitan dengan aktivasi korteks orbitofrontal kiri, korteks cingulate anterior
kanan, dan daerah temporal anterior bilateral. Penemuan ini konsisten
dengan aktivasi otak berkaitan dengan pelanggaran norma sosial yang
marah, yaitu korteks orbitofrontal lateral dan korteks prefrontal medial.
Sebagai perbandingan, rasa bersalah yaitu emosi yang sering berkaitan
dengan amarah akan meningkatkan aliran darah ke otak pada daerah
paralimbik anterior, temporal anterior bilateral, girus cingulate anterior,
korteks insular anterior kiri atau girus frontal inferior. Sebagai kesimpulan,
ekspresi amarah melibatkan sistem saraf yang terdistribusi, dimana
melibatkan limbik, para-limbik dan daerah kortikal. Namun lebih lanjut, belum
diketahui secara pasti apakah sistem saraf yang tersebar ini terganggu pada
individu yang bermasalah dalam hal amarah (Paulus dkk, 2004).
II.2. STROKE II.2.1. Definisi
Stroke adalah suatu episode disfungsi neurologi akut yang
disebabkan oleh iskemik atau perdarahan yang berlangsung 24 jam atau
meninggal, tetapi tidak memiliki bukti yang cukup untuk diklasifikasikan
(Sacco dkk, 2013).
Stroke iskemik adalah episode disfungsi neurologis yang disebabkan
oleh infark fokal serebral, spinal dan infark retinal. Dimana infark susunan
saraf pusat adalah kematian sel pada otak, medula spinalis, atau sel retina
akibat iskemia, berdasarkan :
- Patologi, pencitraan atau bukti objektif dari injury fokal iskemik
pada serebral, medula spinalis atau retina pada suatu distribusi
- Atau bukti klinis dari injury fokal iskemk pada serebral, medula
spinalis atau retina berdasarkan gejala yang bertahan ≥ 24 jam
atau meninggal dan etiologi lainnya telah disingkirkan. (Sacco dkk,
2013)
Stroke hemoragik adalah disfungsi neurologis yang berkembang cepat
yang disebabkan oleh kumpulan darah setempat pada parenkim otak atau
sistem ventrikuler yang tidak disebabkan oleh adanya trauma (Sacco dkk,
2013).
II.2.2. Epidemiologi
Insiden stroke bervariasi di berbagai negara di Eropa, diperkirakan
terdapat 100-200 kasus stroke baru per 10.000 penduduk per tahun (Hacke
dkk, 2003). Insiden stroke pada pria lebih tinggi daripada wanita, pada usia
muda, namun tidak pada usia tua. Rasio insiden pria dan wanita adalah 1,25
pada kelompok usia 55-64 tahun, 1,50 pada kelompok usia 65-74 tahun,
1,07 pada kelompok usia 75-84 tahun dan 0,76 pada kelompok usia diatas
85 tahun. Di Amerika diperkirakan terdapat lebih dari 700.000 insiden stroke
per tahun, yang menyebabkan lebih dari 160.000 kematian per tahun,
dengan 4,8 juta penderita stroke yang bertahan hidup (Goldstein dkk, 2006).
Meskipun dapat mengenai semua usia, insiden stroke meningkat
dengan bertambahnya usia dan terjadi lebih banyak pada wanita pada usia
yang lebih muda tetapi tidak pada usia yang lebih tua. Perbandingan
insidens pria dan wanita pada umur 55-64 tahun adalah 1,25; pada umur
65-74 tahun adalah 1,50; 75-84 tahun adalah 1,07; dan pada umur ≥ 85 tahun
II.2.3. Faktor Resiko
Faktor - faktor resiko untuk terjadinya stroke dapat diklasifikasikan
sebagai berikut : (Sjahrir, 2003).
1. Non modifiable risk factors :
a. Usia
b. Jenis kelamin
c. Keturunan / genetik
2. Modifiable risk factors
a. Behavioral risk factors
1. Merokok
2. Unhealthy diet : lemak, garam berlebihan, asam urat, kolesterol,
low fruit diet
3. Alkoholik
4. Obat-obatan : narkoba (kokain), antikoaguilansia, antiplatelet, obat
kontrasepsi
b. Physiological risk factors
1. Penyakit hipertensi
2. Penyakit jantung
3. Diabetes mellitus
4. Infeksi/lues, arthritis, traumatic, AIDS, Lupus
5. Gangguan ginjal
6. Kegemukan (obesitas)
7. Polisitemia, viskositas darah meninggi & penyakit perdarahan
9. Dan lain-lain
II.2.4. Klasifikasi
Dasar klasifikasi yang berbeda – beda diperlukan, sebab setiap jenis
stroke mempunyai cara pengobatan, pencegahan dan prognosa yang
berbeda, walaupun patogenesisnya sama (Misbach,1999)
I. Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya :
1. Stroke iskemik
a. Transient Ischemic Attack (TIA)
b. Thrombosis serebri
c. Emboli serebri
2. Stroke Hemoragik
a. Perdarahan intraserebral
b. Perdarahan subarachnoid
II. Berdasarkan stadium / pertimbangan waktu
1. Transient Ischemic Attack (TIA)
2. Stroke in evolution
3. Completed stroke
III. Berdasarkan jenis tipe pembuluh darah
1. Sistem karotis
2. Sistem vertebrobasiler
IV. Klasifikasi Bamford untuk tipe infark yaitu (Soertidewi, 2007) :
1. Partial Anterior Circulation Infarct (PACI)
2. Total Anterior Circulation Infarct (TACI)
4. Posterior Circulation Infarct (POCI)
V. Klasifikasi Stroke Iskemik berdasarkan kriteria kelompok peneliti TOAST
(Sjahrir, 2003)
1. Aterosklerosis Arteri Besar
Gejala klinik dan penemuan imejing otak yang signifikan (>50%) stenosis
atau oklusi arteri besar di otak atau cabang arteri di korteks disebabkan oleh
proses aterosklerosis. Gambaran computed tomography (CT) scan kepala
MRI menunjukkan adanya infark di kortikal, serebellum, batang otak, atau
subkortikal yang berdiameter lebih dari 1,5 mm dan potensinya berasal dari
aterosklerosis arteri besar.
2. Kardioembolisme
Oklusi arteri disebabkan oleh embolus dari jantung. Sumber embolus dari
jantung terdiri dari :
a. Resiko tinggi
• Prostetik katub mekanik
• Mitral stenosis dengan atrial fibrilasi
• Fibrilasi atrial (other than lone atrial fibrillation)
• Atrial kiri / atrial appendage thrombus
• Sick sinus syndrome
• Miokard infark baru (<4 minggu)
• Thrombus ventrikel kiri
• Kardiomiopati dilatasi
• Segmen ventricular kiri akinetik
• Infeksi endokarditis
b. Resiko sedang
• Prolapsus katub mitral
• Kalsifikasi annulus mitral
• Mitral stenosis tanpa fibrilasi atrial
• Turbulensi atrial kiri
• Aneurisma septal atrial
• Paten foramen ovale
• Atrial flutter
• Lone atrial fibrillation
• Katub kardiak bioprostetik
• Trombotik endokarditis nonbacterial
• Gagal jantung kongestif
• Segmen ventrikuler kiri hipokinetik
• Miokard infark (> 4minggu, < 6 bulan)
3. Oklusi Arteri Kecil
Sering disebut juga infark lakunar, dimana pasien harus mempunya satu
gejala klinis sindrom lakunar dan tidak mempunyai gejala gangguan disfungsi
kortikal serebral. Pasien biasanya mempunyai gambaran CT Scan/MRI
kepala normal atau infark lakunar dengan diameter <1,5 mm di daerah
batang otak atau subkortikal.
4. Stroke Akibat dari Penyebab Lain yang Menentukan
a. Non-aterosklerosis Vaskulopati
• Inflamasi non infeksi
• Infeksi
b. Kelainan Hematologi atau Koagulasi
5. Stroke Akibat dari Penyebab Lain yang Tidak Dapat Ditentukan
II.2.5. Patofisiologi
Pada stroke iskemik, berkurangnya aliran darah ke otak menyebabkan
hipoksemia daerah regional otak dan menimbulkan reaksi berantai yang
berakhir dengan kematian sel – sel otak dan unsur–unsur pendukungnya
(Misbach, 2007).
Secara umum daerah regional otak yang iskemik terdiri dari bagian inti
(core) dengan tingkat iskemia terberat dan berlokasi di sentral. Daerah ini
akan menjadi nekrotik dalam waktu singkat jika tidak ada reperfusi. Di luar
daerah core iskemik terdapat daerah penumbra iskemik. Sel – sel otak dan
jaringan pendukungnya belum mati akan tetapi sangat berkurang fungsi–
fungsinya dan menyebabkan juga defisit neurologis. Tingkat iskemiknya
makin ke perifer makin ringan. Daerah penumbra iskemik, di luarnya dapat
dikelilingi oleh suatu daerah hiperemik akibat adanya aliran darah kolateral
(luxury perfusion area). Daerah penumbra iskemik inilah yang menjadi
sasaran terapi stroke iskemik akut supaya dapat direperfusi dan sel-sel otak
berfungsi kembali. Reversibilitas tergantung pada faktor waktu dan jika tidak
terjadi reperfusi, daerah penumbra dapat berangsur-angsur mengalami
Iskemik otak mengakibatkan perubahan dari sel neuron otak secara
bertahap, yaitu (Sjahrir, 2003):
Tahap 1 :
a. Penurunan aliran darah
b. Pengurangan O
c. Kegagalan energi 2
d. Terminal depolarisasi dan kegagalan homeostasis ion
Tahap 2 :
a. Eksitoksisitas dan kegagalan homeostasis ion
b. Spreading depression
Tahap 3 : Inflamasi
Tahap 4 : Apoptosis
Perdarahan otak merupakan penyebab stroke kedua terbanyak
setelah infark otak, yaitu 20-30% dari semua stroke di Jepang dan Cina.
Sedangkan di Asia Tenggara (ASEAN), pada penelitian stroke oleh Misbach
(1997) menunjukkan stroke perdarahan sebesar 26%, terdiri dari lobus 10%,
ganglionik 10%, serebellar 1%, batang otak 2% dan subarakhnoid 4%.
(Misbach & Soertidewi, 2011)
Pecahnya pembuluh darah di otak dibedakan menurut anatominya
yaitu perdarahan intraserebral dan subarakhnoid. Sedangkan berdasarkan
penyebabnya, perdarahan intraserebral dibagi menjadi perdarahan
intraserebral primer dan sekunder. Perdarahan intraserebral primer
vaskulopati serebral dengan akibat pecahnya pembuluh darah otak.
Sedangkan perdarahan sekunder (bukan hipertensif) terjadi antara lain
akibat anomali vaskular kongenital, koagulopati, atau obat anti koagulan.
Diperkirakan hampir 50% penyebab perdarahan intraserebral adalah
hipertensi kronis, 25% karena anomali kongenital dan sisanya adalah
penyebab lain. (Misbach & Soertidewi, 2011)
Pada perdarahan intraserebral, pembuluh darah yang pecah terdapat
di dalam otak atau massa pada otak, sedangkan pada perdarahan
subarakhnoid, pembuluh darah yang pecah terdapat di ruang subarakhnoid,
disekitar sirkulus arteriosus Willisi. Pecahnya pembuluh darah disebabkan
oleh kerusakan dinding arteri (arteriosklerosis) atau karena kelainan
kongenital atau trauma. (Misbach & Soertidewi, 2011)
II.3. HIPERTENSI II.3.1. Definisi
Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana
tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg
(JNC VII, 2003; Shehata, 2010).
II.3.2. Klasifikasi
Menurut The Seventh Report of The Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure
(JNC VII) klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa terbagi menjadi
kelompok normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2
Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Kriteria The Seventh Joint National Committee (JNC VII).
Klasifikasi
Dikutip dari : Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, et al. 2003. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. JAMA.
289;(19):2560-2572.
II.3.3. Epidemiologi
Hipertensi masih merupakan salah satu dari beberapa faktor resiko
yang dapat dicegah terhadap timbulnya penyakit dan kematian (James dkk,
2013). Hipertensi telah menjadi masalah utama dalam kesehatan
masyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di
dunia. Semakin meningkatnya populasi usia lanjut maka jumlah pasien
dengan hipertensi kemungkinan besar juga akan bertambah. Diperkirakan
sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang
tahun 2025 dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, di perkirakan
menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan pada angka
penderita hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini (Armilawati
II.3.4. Etiologi
Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 golongan,
yaitu: hipertensi esensial atau hipertensi primer dan hipertensi sekunder atau
hipertensi renal.
1). Hipertensi esensial
Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui
penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus.
Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan,
hiperaktivitas sistem saraf simpatis, sistem renin angiotensin, defek dalam
ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca intraseluler dan faktor-faktor yang
meningkatkan Resiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia.
Hipertensi primer biasanya timbul pada umur 30 - 50 tahun (Braunwald,
2005).
2). Hipertensi sekunder
Hipertensi sekunder atau hipertensi renal terdapat sekitar 5 % kasus.
Penyebab spesifik diketahui, seperti penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal,
hiperaldosteronisme primer, dan sindrom cushing, feokromositoma,
koarktasio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, dan lain -
lain (Braunwald, 2005).
II.3.5. Patofisiologi
Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah
terletak di pusat vasomotor. Dari pusat vasomotor ini bermula jaras saraf
medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan
pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah
melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion
melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion
ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepinefrin
mengakibatkan konstriksi pembuluh darah (Braunwald, 2005).
Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat
mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor.
Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun
tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi (Braunwald,
2005)
Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang
pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga
terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokontriksi. Medula adrenal
mengsekresi epinefrin yang menyebabkan vasokontriksi. Korteks adrenal
mengsekresi kortisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respon
vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokontriksi yang mengakibatkan
penurunan aliran darah ke ginjal, menyebabkan pelepasan renin. Renin
merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi
angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang
sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi
natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume
intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung mencetus keadaan
II.4. EKSPRESI AMARAH DAN HIPERTENSI
Amarah diperkirakan dapat meningkatkan tekanan darah melalui
efeknya pada sistem saraf simpatis (Meinginger dkk, 2004; Muller dkk,
2001). Episode ulangan dari amarah dapat menyebabkan keadaan kronis
dari peningkatan tekanan darah atau hipertensi (Muller dkk, 2001). Beberapa
peneliti telah menemukan adanya hubungan antara skor amarah dengan
tekanan darah (Hauber dkk, 1998; Eng dkk, 2003).
Terdapat bukti yang kontroversial pada korelasi antara ekspresi
amarah dengan tekanan darah saat ini. Beberapa peneliti mendapatkan
bahwa amarah yang dikeluarkan dapat meningkatkan tekanan darah dan
mengaktivasi sistem kardiovaskular, namun peneliti lainnya menemukan
bahwa menekan rasa amarah justru dapat menginduksi peningkatan tekanan
darah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi dalam konsep atau
pengukuran yang menimbulkan hasil yang inkonsekuen. Amarah telah
dikatakan dapat meningkatkan tekanan darah melalui pengaruh simpatis
langsung dan episode yang berulang dari rasa marah dapat menyebabkan
keadaan kronis dari peningkatan tekanan darah. Lebih lanjut, penelitian pada
remaja didapatkan bahwa sifat amarah merupakan salah satu dari faktor
psikologis yang berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Dimana ketika
seorang yang sehat tidur (biasanya terjadi penurunan tekanan darah sebesar
10% dalam keadaan tidur), didapatkan bahwa amarah mencegah penurunan
tekanan darah fisiologis tersebut (Shehata, 2010).
Secara sederhana, stres psikologikal atau emosional, seperti amarah,
melalui sistem limbik ke nukleus di hipotalamus dimana
corticotropin-releasing factor (CRF) dan arginine vasopressin disintesa. Hormon CRF
berjalan menuju kelenjar pituitari anterior yang kemudian memberi respon
berupa pelepasan adrenocorticotropic hormone (ACTH) yang kemudian
menstimulasi korteks adrenal untuk memproduksi glukokortikosteroid.
Glukokortikosteroid akan membebaskan katekolamin. Arginine vasopressin
juga mengaktivasi sekresi ACTH dab dilepaskan oleh kelenjar pituitari
posterior. Bersama dengan norepinefrin dan epinefrin yang dihasilkan oleh
sistem saraf simpatis, bahan-bahan kimiawi tersebut merupakan hormon
stres utama yang secara sistemik akan mengaktifkan sistem kardiovaskular.
Stimulasi sistem saraf simpatis juga akan mengaktivasi aparatus
juxtaglomerular di ginjal, sehingga merangsang respon dari sistem
renin-angiotensin dimana timbul reaksi enzimatik yang selanjutnya terjadi
vasokonstriksi sistemik dan peningkatan tekanan darah (Black & Garbutt,
2002).
Namun demikian, beberapa penelitian tidak mendukung adanya
hubungan antara amarah dengan peningkatan tekanan darah. Hal ini
mungkin disebabkan perbedaan secara individu seperti dalam hal reaksi
fisiologikal, riwayat keluarga, ras dan jenis kelamin, tipe amarah tertentu,
atau bagaimana seseorang mengatasi rasa amarah. Contohnya, bangsa
Afrika Amerika bila dibandingkan dengan Kaukasia menunjukkan reaktivitas
tekanan darah yang lebih lama terhadap amarah. Lebih lanjut pada subjek
dengan riwayat orang tua dengan hipertensi, tekanan darah sistolik berkaitan
riwayat orang tua tanpa hipertensi didapatkan tekanan darah sistolik
berhubungan dengan sifat mudah marah (iritabilitas) yang tinggi (Paulus dkk,
2004).
Terdapat perkembangan yang signifikan pada penelitian klinis untuk
menilai hubungan kardiovaskular dan neuroendokrin dengan regulasi emosi
yang berkaitan dengan amarah. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana
tipe ekspresi amarah tertentu mempengaruhi sistem saraf otonom dan fungsi
neuroendokrin, khususnya yang berkaitan dengan respon stres pada individu
yang berbeda (al’ Absi & Bongard, 2006).
Paparan berulang dan kronis terhadap amarah yang dicetuskan oleh
keadaan stres dan ekspresi amarah secara terbuka sering berhubungan
dengan stimulasi berulang terhadap HPA
(Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical) axis dan sistem sympatho-adrenomedullary. Sebagai
tambahan, fungsinya dalam meregulasi respon adaptif ketika individu
menghadapi keadaan emosional yang hebat, sistem ini akan berinteraksi
secara bersama-sama (al’ Absi & Bongard, 2006).
II.4.I. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Axis
Sistem ini melibatkan tiga struktur, yaitu hipotalamus, pituitari, dan
korteks adrenal (Gambar 1). Aktivitas dari aksis ini diaktifkan oleh pelepasan
CRF dari badan sel neuron pada nukleus paraventrikular hipotalamus.
Pelepasan CRF menginisiasi kaskade aksis HPA. Hormon CRF berjalan
menuju bagian anterior dari kelenjar pituitari, disana ia bekerja pada sel
corticotrope dan menstimulasi sintesis proopiomelanocortin (POMC), dan
sirkulasi sistemik. Selain CRF, vasopressin juga disintesa dan disekresikan
di nukleus paraventrikular. Vasopressin juga berpartisipasi dalam
menstimulasi pelepasan ACTH. Walaupun efek vasopressin lemah dalam
mestimulasi sekresi ACTH, ketika dikombinasikan dengan CRF, vasopressin
akan sangat meningkatkan pelepasan ACTH. Penelitian menunjukkan bahwa
aktivitas aksis HPA sensitif terhadap pengaruh negative feedback dari
glukokortikoid. Hormon ACTH berjalan melalui sirkulasi perifer untuk
mencapai korteks adrenal sehingga menyebabkan sintesa dan pelepasan
kortikosteroid, yang mana sebagian besar adalah kortisol pada manusia.
Ketika dilepaskan ke sirkulasi, kortisol memberikan efek sentral dan perifer,
seperti metabolik, imunitas dan kardiovaskular. Salah satu fungsi utamanya
pada perifer adalah membuat cadangan energi untuk digunakan tubuh,
dengan meningkatkan katabolisme protein dan glukoneogenesis, dan
dengan menurunkan ambilan glukosa oleh sel sehingga menyebabkan
peningkatan kadar asam amino dan glukosa pada plasma (al’ Absi &
Gambar 1. Diagram hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis.
Dikutip dari : al’ Absi M and Bongard S. Neuroendocrine and Behavioral Mechanisms Mediating the Relationship between Anger Expression and Cardiovascular Risk: Assessment Considerations and Improvements. Journal of Behavioral Medicine. 2006. 29;(6):573-91
Penelitian menunjukkan pengaruh kortisol yang signifikan secara luas
pada fungsi sistem saraf pusat. Kortisol mempengaruhi kerja reseptor beta
adrenergik dan oleh karena itu mengatur efek katekolamin yang akan
berinteraksi dengan reseptor tersebut. Kortisol berperan penting dalam
meregulasi sekresi hormonnya sendiri melalui efeknya pada pituitari,
hipokampus, korteks frontal bagian medial dan amigdala sentral. Melalui ini,
menurunkan sekresi ACTH dan POMC dari kelenjar pituitari (al’ Absi &
Bongard, 2006).
Peningkatan kortisol dalam respon terhadap stres psikologis penting
dalam memulihkan aktivasi imun yang diinduksi oleh stres. Hal ini konsisten
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa aktivitas glukokortikosteroid
akibat stres akan membantu membatasi aktivasi sitokin dan fungsi imunitas
lainnya yang reaktif terhadap stres. Mekanisme ini akan mencegah timbulnya
efek negatif yang dapat dihasilkan oleh respon imun yang tidak terkendali.
Walaupun respon kortisol terhadap stres akut memiliki efek pertahanan yang
baik, peningkatan kortisol yang persisten akan menyebabkan beberapa efek
terhadap metabolik dan sistem kardiovaskular. Oleh karena itu sangat
mungkin bahwa keadaan kortisol tinggi yang disebabkan oleh paparan yang
berulang kali akan menyebabkan peningkatan kadar hormon ini pada
keadaan stres emosional akut menjadi faktor resiko terhadap berbagai
masalah jantung dan pembuluh darah. Namun penelitian lebih lanjut masih
diperlukan untuk menjawab hipotesis ini dan menilai akibat yang ditimbulkan
oleh peningkatan intermiten aktivitas HPA dibandingkan dengan peningkatan
yang persisten dari aktivasi sistem ini (al’ Absi & Bongard, 2006).
II.4.2. The Sympatho-Adrenomedullary System
Sistem ini melibatkan baik sentral (hipotalamus) maupun perifer.
Sistem saraf simpatis memainkan peran penting pada tubuh dan mendasari
respon fight-flight pada saat mengalami stres. Sistem saraf simpatis
mengatur aktivitas otot polos dan otot jantung dengan mensekresikan
otot polos yang diinervasi. Kemudian, sistem saraf simpatis secara umum
meningkatkan aktivasi dan fungsi dari organ yang diinervasinya. Salah satu
bagian penting dari sistem simpato-adrenomedular adalah saraf simpatis dari
kelenjar medula adrenal. Medula adrenal ini menerima preganglion serabut
saraf simpatis secara langsung dari medula spinalis. Serabut saraf ini
mensekresikan asetilkolin sehingga menyebabkan medula adrenal
melepaskan epinefrin dan norepinefrin menuju sirkulasi. Norepinefrin
disekresikan pada saat yang bersamaan dengan epinefrin, namun efeknya
pada jaringan melalui sirkulasi terbatas (al’ Absi & Bongard, 2006).
Locus coeruleus yang berada pada batang otak berperan penting
dalam mengatur pelepasan katekolamin pada saat emosi. Locus coeruleus
90% terdiri dari badan sel yang mensintesa norepinefrin pada sistem saraf
sentral dan diproyeksikan menuju medula spinalis dan beberapa daerah
subkortikal dan kortikal. Ketika sistem ini diaktivasi akan menyebabkan
pelepasan norepinefrin dari neuron-neuron noradrenergik pada beberapa
lokasi di otak. Pelepasan norepinefrin ini memfasilitasi keadaan puncak dari
perhatian dan kewaspadaan dan mungkin berkontribusi dalam meningkatkan
ansietas. Proses ini mungkin ditingkatkan dalam keadaan marah atau
keadaan emosional yang hebat yang diatur oleh amigdala dan korteks
serebri. Terdapat interaksi yang kuat antara CRF dan sistem locus
coeruleus-norepinefrin, dan dua sistem tersebut membentuk basic arousal
unit yang memediasi respon behaviour terhadap keadaan stres, dan
kerjasama kedua sistem tersebut berkontribusi pada koordinasi respon
yang mensekresikan CRF diproyeksikan dari nukleus paraventrikuler menuju
batang otak. Neuron katekolaminergik diproyeksikan dari locus coeruleus
menuju nukleus paraventrikular, dan ambang rangsang neuron locus
coeruleus ditingkatkan oleh adanya CRF (al’ Absi & Bongard, 2006).
Interaksi neuron antara locus coeruleus dan nukleus paraventrikuler
juga ditingkatkan melaui proyeksi terpisah dari nukleus paraventrikuler dan
locus coeruleus ke struktur otak lainnya yang terlibat dalam koordinasi
emosional respon terhadap stres. Sebagai contoh, locus coeruleus
diproyeksikan menuju hipotalamus, dimana akan memberikan kontribusi
secara tidak langsung terhadap peningkatan kerja norepinefrin pada nukleus
paraventrikuler, yang kemudian akan mengaktivasi aksis HPA. Di lain pihak
CRF memfasilitasi proses sensoris dan perhatian selama keadaan stres
melalui peningkatan input katekolamin menuju neuron CRF. Epinefrin dan
norepinefrin memiliki efek stimulus terhadap ACTH; suatu efek yang
diberikan melalui pelepasan katekolamin pada CRF. Penghambatan
pelepasan CRF dapat mencegah efek tersebut. Perubahan katekolamin yang
diinduksi oleh keadaan stres, oleh karena itu, berkontribusi terhadap
pelepasan CRF dan ACTH, dan memberikan substrat yang mungkin
mempengaruhi jenis ekspresi amarah (al’ Absi & Bongard, 2006).
II.5. EKSPRESI AMARAH DAN STROKE
Pada analisis penelitian Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)
sebelumnya, didapatkan bahwa sifat amarah berhubungan positif dengan