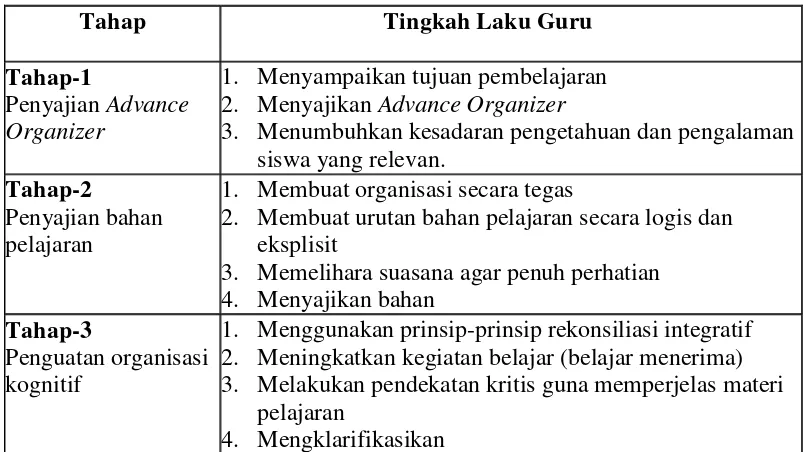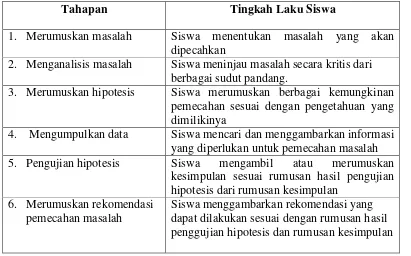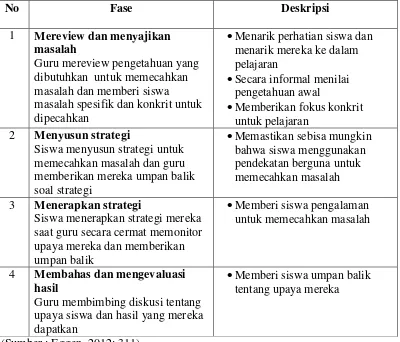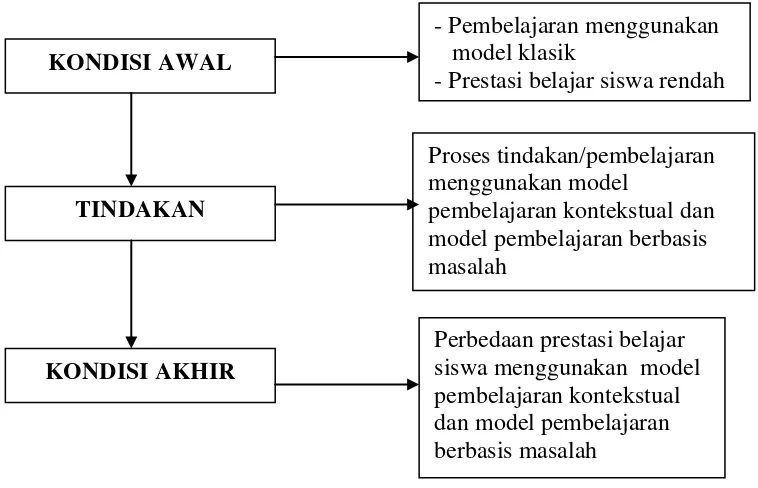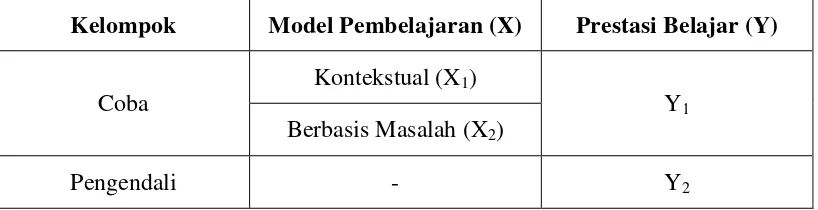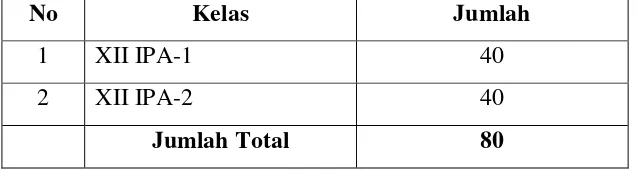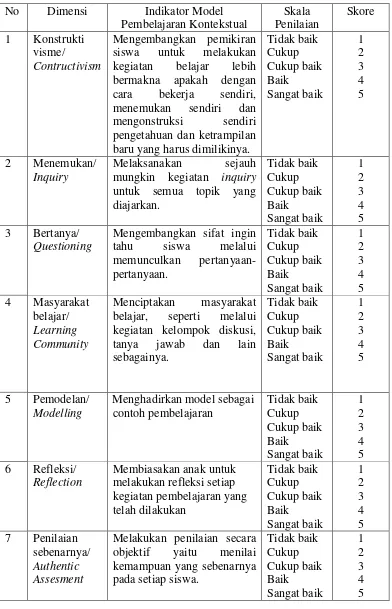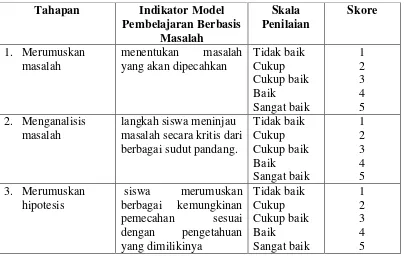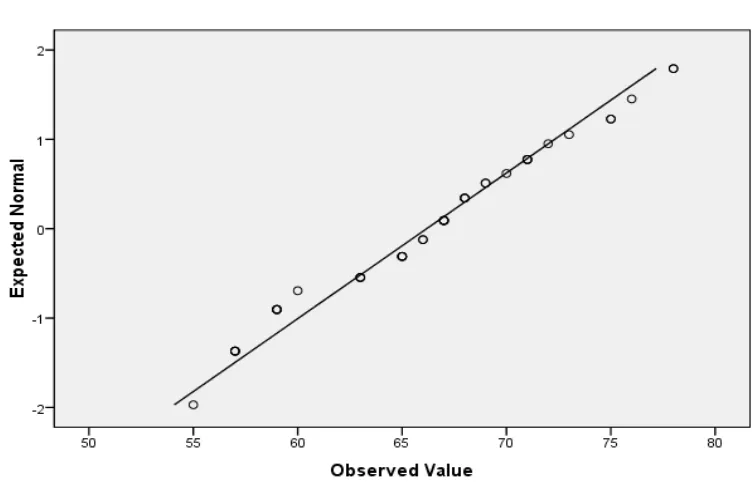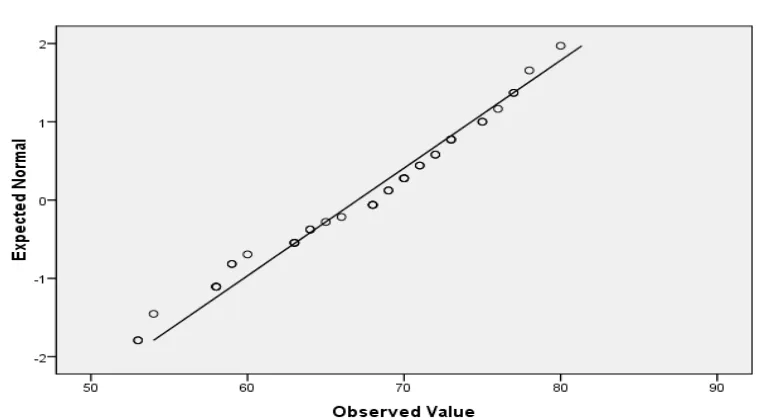ABSTRACT
DIFFERENCES BETWEEN STUDENTS’ ACHIEVEMENT USING THE MODELS OF CONTEXTUAL LEARNING AND PROBLEM-BASED
LEARNING WITH DIFFERENT EARLY COMPETENCE IN THE SUBJECT OF PHYSICS OF GRADE XII OF
SCIENCE PROGRAM OF SMAN 13 BANDAR LAMPUNG
By Triyatmo
The purpose of this study is to describe: (1) The interaction between the students’ achievement using contextual learning model and problem -based learning model with different early competence in the subject of physics; (2) The difference between the students’ average achievement using contextual learning model and problem-based learning model with different early competence in the subject of physics; (3) The difference between the students’ average achievement using contextual learning model and problem-based learning model with high early competence in the subject of physics; (4) The difference between the students’ average achievement using contextual learning model and problem-based learning model with low early competence in physics.
The research method used is ex post facto research. The data was analyzed quantitatively with ANOVA formula and t-test.
Based on the above results, the researchers conclude as follows: (1) There is interaction between students who use contextual learning model and problem-based learning and early competence with the students’ achievement in learning physics with a value of
F
count = 126.645>F
table = 4.11 at 0.05 level; (2) Theaverage of the students’achievement in learning physics using contextual learning is higher than that of using problem-based learning with a value
F
count = 26,05>F
table =4.11 at 0.05 level; (3) The average achievement in learning physics usingcontextual learning is not higher than that of using problem-based learning for the students with a value
t
count = 14.974< t
table = 2.101, with significance level of0.05; (4) The average achievement in learning physics using contextual learning is not higher than that of using problem-based learning for the students with low early competence with a value:
t
count = 36,006>t
table = 2.101 at significance levelof 0.05.
ABSTRAK
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN BERBASIS MASALAH
DENGAN KEMAMPUAN AWAL PADA MATA PELAJARAN FISIKA SISWA KELAS XII IPA DI SMA NEGERI 13
BANDAR LAMPUNG
Oleh
Triyatmo
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan : (1) interaksi antara model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dan kemampuan awal dengan prestasi belajar pada mata pelajaran fisika; (2) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan kemampuan awal pada mata pelajaran fisika; (3) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan kemampuan awal tinggi pada mata pelajaran fisika; (4) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan kemampuan awal rendah pada mata pelajaran fisika.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian ex post facto. Data dianalisis secara kuantitatif dengan rumus anava dan uji t.
Kesimpulan penelitian adalah: (1) Ada interaksi antara pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah serta kemampuan awal dengan prestasi belajar fisika dengan nilai Fhitung = 126,645 > Ftabel = 4,11 pada taraf 0,05; (2) Rata-rata prestasi belajar
fisika siswa yang menggunakan pembelajaran kontekstual lebih tinggi dari siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan Fhitung = 26,005 >
Fhitung = 4,11 pada taraf 0,05; (3) Rata-rata prestasi belajar fisika siswa yang
menggunakan pembelajaran kontekstual tidak lebih tinggi dari siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah pada kemampuan awal tinggi dengan thitung = -14,974 < ttabel = 2,101 dengan taraf signifikan 0,05; (4) Rata-rata
prestasi belajar fisika siswa yang menggunakan pembelajaran kontekstual lebih tinggi dari siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah pada kemampuan awal rendah dengan thitung = 36,006 > ttabel = 2,101 pada taraf
signifikan 0,05.
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN BERBASIS MASALAH
DENGAN KEMAMPUAN AWAL PADA MATA PELAJARAN FISIKA SISWA KELAS XII IPA DI SMA NEGERI 13
BANDAR LAMPUNG
(Tesis)
oleh
TRIYATMO
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Diagram Kerangka Pikir ... 70
3.1 Histogram Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 85
3.2 Diagram Plot Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 85
3.3 Histogram Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-2 ... 86
3.4 Diagram Plot Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-2 ... 86
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi... xii
Daftar Tabel ... xv
Daftar Gambar... xvi
Daftar Lampiran... xvii
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Identifikasi Masalah ... 11
1.3 Pembatasan Masalah ... 12
1.4 Perumusan Masalah ... 12
1.5 Tujuan Penelitian ... 13
1.6 Manfaat Penelitian ... 13
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 2.1 Belajar dan Pembelajaran ... 15
2.2 Teori Belajar dan Pembelajaran ... 21
2.3 Teori Desain Pembelajaran ASSURE ... 31
2.4 Prestasi Belajar ... 38
2.5 Model Pembelajaran Kontekstual ... 40
2.6 Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) ... 49
2.7 Kemampuan Siswa...60
2.8 Karakteristik Fisika SMA ... 62
2.9 Kajian Penelitian Yang Relevan ... 66
2.10 Kerangka Berpikir ... 67
3.1 Jenis penelitian ... 72
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian...73
3.3 Populasi dan Sampel ... 73
3.4 Subjek dan Objek Penelitian...74
3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel...74
3.6 Teknik Pengumpulan Data...77 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Data Penelitian...91
4.1.1 Data kemampuan Awal...91
4.1.2 Data Prestasi Belajar Siswa dengan Pembelajaran Kontekstual...92
4.1.3 Data Prestasi Belajar Siswa dengan Pembelajaran Berbasis Maslah ... 93
4.1.4 Perbandingan Rata-rata Prestasi Belajar Siswa yang Menggunakan Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 93
4.2 Pengujian Hipotesis Penelitian ... 94
4.2.1 Hipotesis Pertama... 94
4.2.2 Hipotesis Kedua ... 96
4.2.3 Hipotesis Ketiga ... 96
4.2.4 Hipotesis Keempat ... 97
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian ... 98
4.3.1 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Pertama ... 98
4.3.2 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Kedua...100
4.3.3 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Ketiga...101
4.3.4 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Keempat...103
5.1 Simpulan...105
5.2 Implikasi...105
5.3 Saran...106
Daftar Pustaka...108
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Silabus Mata Pelajaran Fisika Kelas XII... .... 111
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fisika (Model Pembelajaran Kontekstual) ... 116
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fisika (Model Pembelajaran Berbasis Masalah) ... 128
4. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 139
5. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 140
6. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 141
7. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 142
8. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 143
9. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 144
10. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 145
11. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 146
12. Daftar Skor Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 147
13. Daftar Skor Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 148
14. Data Pembelajaran Kontekstual Untuk Kemampuan Tinggi dan Rendah ... 149
15. Data Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Kemampuan Tinggi dan Rendah ... 150
16. Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa ... 151
17. Uji Normalitas Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 154
18. Uji Homogenitas Untuk Kemampuan Awal ... 159
19. Uji Homogenitas Untuk Pembelajaran Kontekstual ... 160
20. Uji Homogenitas Pembelajaran Berbasis Masalah ... 161
23. Uji Hipotesis 4 ... 165
24. Surat Izin Penelitian ... 166
25. Surat Keterangan Penelitian ... 167
26. Lembar Perbaikan Seminar Proposal ... 168
27. Lembar Perbaikan Seminar Hasil ... 170
28. Lembar Perbaikan Ujian Tesis ... 172
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Advance Organizer ... 28
Tabel 2.2 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 55
Tabel 2.3 Fase Pembelajaran Berbasis Masalah ... 58
Tabel 3.1 Rancangan Penelitian ... 72
Tabel 3.2 Jumlah Siswa Tiap Kelas ... 73
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Prestasi Belajar Siswa ... 79
Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Model Pembelajaran Kontekstual ... 81
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Model Pembelajaran Berbasis Masalah ... 82
Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penilaian Menurut Tingkat Kemampuan Awal dari Kedua Kelas ... 91
Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Pada Pembelajaran Kontekstual ... 92
Tabel 4.3 Rata-rata Nilai Pada Pembelajaran Berbasis Masalah ... 93
Tabel 4.4 Rata-rata Prestasi Belajar Siswa Yang Menggunakan Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 94
KATA PENGANTAR
Assalamu`alaikum Wr.Wb.
Segala puji dan syukur pada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis
sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister Teknologi Pendidikan
pada Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lampung.
Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada
semua pihak yang telah langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi
dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis
menyampaikan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Sugeng P. Hariyanto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas
Lampung.
3. Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lampung.
4. Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister
Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Lampung, dan sekaligus sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan
Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
lampung, sekaligus Pembimbing I yang telah memberi saran dan masukan
serta kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan
arahan, saran dan masukan serta ide-ide dalam penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Dr. Dwi Yulianti, M.Pd., selaku Dosen Pembahas I yang telah
memberikan kritik, saran dan masukan demi perbaikan penulisan tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Teknologi
Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
9. Segenap guru, karyawan dan siswa SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang
telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis mengadakan
penelitian.
10.Istriku tercinta Triaswatiningsih, S.Pd. dan putri-putriku Intan Pratiwi A,
Hutami Lestyo R, dan Hasna Kurnia P. beserta seluruh keluarga besarku yang
telah memberikan doa dan dukungan demi keberhasilanku.
11.Rekan-rekan yang telah memberikan dorongan, dukungan dan motivasi agar
penulis dapat menyelesaikan tesis ini antara lain Sunaryo, S.Pd., M.Pd., Joko
Purwanto, S.Pd., Hj. Rina Devita, S.Pd., M.Pd., Suranto, M.Pd., Tresna Setya
Nuryana, S.Pd., M.Pd., Drs. Nurhamid, Dra. S.R. Bajawati, M.Pd.
12.Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, khususnya
membantu demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
Semoga dukungan dan segala yang telah diberikan selalu mendapatkan imbalan,
pahala dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap tesis ini dapat memberikan
sumbangsih bagi dunia pendidikan.
Bandar Lampung, 30 Agustus 2014
Penulis
MOTO
Hidup Harus Berguna
(Triyatmo)
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini kepada :
1. Istriku tercinta Triaswatingsih, S.Pd. dan ketiga buah hatiku Intan Pratiwi A,
Hutami Lestyo R., dan Hasna Kurnia P. Yang telah memberikan doa dan
dukungan demi keberhasilanku
2. Keluarga besar trah Sastro Wardoyo di Yogyakarta dan keluarga besar trah
Djogo Semito di Sukoharjo yang senantiasa memberikan doa dan restunya
demi keberhasilanku
3. Teman-temanku Sunaryo, S.Pd., M.Pd., Joko Purwanto, S.Pd., Hj. Rina
Devita, S.Pd., M.Pd., Suranto, M.Pd., Tresna Setya Nuryana, S.Pd., M.Pd.,
Drs. Nurhamid, Dra. SR Bajawati, M.Pd., dan seluruh guru serta karyawan
SMA Negeri 13 Bandar Lampung
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 19 Maret 1960
merupakan putra dari pasangan Bapak Djogo Semito dan Ibu Sayem.
Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1972 di SD Negeri 1
Puron Kecamatan Buku Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Sekolah Menengah
Pertama pada tahun 1975 di SMP Pemerintahan Daerah Kecamatan Buku
Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun
1979 di Jurusan Mesin Umum STM Pancasila I Kabupaten Wonogiri Jawa
Tengah, Diploma 3 Kependidikan pada tahun 1985 di Jurusan Ketrampilan
Teknik IKIP Negeri Jakarta, Perguruan Tinggi S-1 diselesaikan pada tahun 1999
pada Program Studi Matematika STKIP PGRI Bandar Lampung, dan pada tahun
2009 penulis melanjutkan pendidikan S-2 pada Program Pascasarjana Teknologi
Pendidikan Universitas Lampung.
Selama 3 tahun yaitu dari tahun 1979 – 1982 menekuni pekerjaan dibidang
pendinginan dan pengaturan kelembaban di sebuah pabrik pemintalan dan
pertenunan di Tangerang Jawa Barat. Pada bulan Februari 1986 penulis diangkat
sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Tanjung Karang dan diberi tugas
mengajar ketrampilan teknik selama 2 semester. Pada tahun 1987 diberi tugas
tanggal 27 Januari 2010 diberi tugas tambahan oleh Bapak Walikota Bandar
Lampung sebagai Kepala SMA Negeri 13 Bandar Lampung sampai sekarang.
Menikah dengan Triaswatiningsih, S.Pd. di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1989
dan telah dikaruniai anak 3 orang putri yaitu Intan Pratiwi A, Hutami Lestyo R,
dan Hasna Kurnia P.
I. PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Masalah
Belajar pada hakekatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada
di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada
tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman dengan melihat,
mengamati dan memahami sesuatu. Hakekat belajar adalah suatu proses yang
ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil
dari proses belajar dapat diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti perubahan
pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, ketrampilan,
kemampuan serta perubahan aspek lain termasuk didalamnya cara berpikir siswa.
Dewasa ini sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat
kompleks dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing diera
global. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sudah menetapkan visi pendidikan
nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat
dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mencapai visi tersebut di
atas, maka diperlukan suatu reformasi pendidikan dimana pendidikan harus
diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
paradigma proses pendidikan yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma
pembelajaran.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu perubahan paradigma
pembelajaran tersebut adalah orientasi pembelajaran yang sebelumnya terpusat
pada guru sekarang beralih pada siswa, metodologi yang semula lebih didominasi
ekspositori berganti partisipatori dan pendekatan yang semula tekstual beralih
menjadi kontekstual.
Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengkaitkan materi
pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari baik
dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar dan dunia kerja, sehingga
siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen
pembelajaran yakni kontruktivisme (constructivism), bertanya (questioning),
penyelidikan (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan
(modeling), refleksi (reflection), dan penilaian autentik (authentic assessment).
Makna kontruktivisme adalah siswa mengkonstruksi/membangun pemahaman
mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal melalui
proses interaksi sosial dan asimilasi-akomodasi. Implikasinya ialah pembelajaran
harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Inti
dari inquiry atau penyelidikan adalah proses perpindahan dari pengamatan
menjadi pemahaman. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini siswa belajar
pembelajaran kontekstual dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Guru bertanya
dimaksudkan untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir
siswa. Sedangkan untuk siswa bertanya merupakan bagian penting dalam
pembelajaran yang berbasis inquiry. Masyarakat belajar merupakan sekelompok
orang (siswa) yang terikat dalam kegiatan belajar, tukar pengalaman, dan berbagi
pengalaman. Sesuai dengan teori kontruktivisme, melalui interaksi sosial dalam
masyarakat belajar ini maka siswa akan mendapat kesempatan untuk
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, oleh karena itu bekerjasama dengan
orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Pemodelan merupakan proses
penampilan suatu contoh agar orang lain (siswa) meniru, berlatih, menerapkan
pada situasi lain, dan mengembangkannya. Penilaian autentik dimaksudkan untuk
mengukur dan membuat keputusan tentang pengetahuan dan keterampilan siswa
yang autentik (senyatanya). Agar dapat menilai kemampuan siswa, penilaian
autentik dilakukan dengan berbagai cara misalnya penilaian produk, penilaian
kinerja (performance), potofolio, tugas yang relevan dan kontekstual, penilaian
diri, penilaian sejawat dan sebagainya. Refleksi pada prinsipnya adalah berpikir
tentang apa yang telah dipikir atau dipelajari, dengan kata lain merupakan
evaluasi dan instropeksi terhadap kegiatan belajar yang telah ia lakukan.
Landasan filosofi pembelajaran kontekstual adalah konstruktivisme yang
menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa seperti
halnya mengisi botol kosong, sebab otak siswa tidak kosong melainkan sudah
berisi pengetahuan hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Siswa tidak hanya
menerima pengetahuan, namun mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui
sosial). Pembelajaran dikatakan mengunakan pendekatan kontekstual jika materi
pembelajaran tidak hanya tekstual melainkan dikaitkan dengan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan keluarga, masyarakat, alam
sekitar, dan dunia kerja, dengan melibatkan ketujuh komponen utama tersebut
sehinggga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Penerapan pembelajaran
kontekstual dalam kurikulum berbasis kompetensi sangat sesuai.
Didalam pelaksanaan model pembelajaran kontekstual, guru dan buku bukan
merupakan sumber dan media sentral, demikian pula guru tidak dipandang
sebagai orang yang serba tahu, sehingga guru tidak harus takut menghadapi
berbagai pertanyaan siswa yang terkait dengan lingkungan baik tradisional
maupun modern.
Selain model pembelajaran kontekstual, didalam proses pembelajaran juga dapat
diterapkan model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah
adalah seperangkat model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai
fokus untuk mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, materi dan
pengaturan diri, (Serafino & Ciccelli, 2005 dalam Eggen, 2012: 310). Pelaksanaan
pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah memiliki tiga
karakteristik yaitu pelajaran berfokus pada memecahkan masalah, tanggung jawab
untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa dan guru mendukung proses
saat siswa mengerjakan masalah. Pelajaran berawal dari satu masalah dan
memecahkan masalah adalah tujuan dari masing-masing pelajaran. Siswa
memiliki tanggungjawab untuk menyusun strategi dan memecahkan masalah yang
proses itu, sehingga membuat siswa bertanggungjawab untuk menyusun strategi
dan memecahkan masalah. Guru menuntun upaya siswa dengan mengajukan
pertanyaan dan memberikan dukungan pengajaran lain saat siswa berusaha
memecahkan masalah. Karakteristik ini penting dan menuntut ketrampilan serta
pertimbangan yang profesional untuk memastikan kesuksesan pembelajaran
berbasis masalah. Jika guru tidak cukup memberikan bimbingan siswa akan gagal,
dan mungkin memiliki konsepsi keliru. Jika diberikan berlebihan siswa tidak akan
mendapatkan banyak pengalaman pemecahan masalah.
Didalam merencanakan pembelajaran berbasis masalah diawali dengan
mengidentifikasi topik, jika topik-topik tidak memiliki karakteristik spesifik maka
perencanaan menjadi kurang konkrit sehingga perlu memahami ide-ide secara
detail. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan, saat merencanakan
pelajaran untuk pembelajaran berbasis masalah hendaknya kita memiliki dua jenis
tujuan belajar, yaitu siswa dapat menguasai materi pelajaran dan siswa dapat
mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah dan pembelajaran mandiri
adalah tujuan jangka panjang dan tujuan ini akan tercapai jika mereka memiliki
pengalaman yang mendorong perkembangan mereka. Tahap ketiga adalah
mengidentifikasi masalah, siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis
masalah memerlukan satu masalah untuk dipecahkan, masalah menjadi efektif
jika jernih, konkrit, dan dekat dengan keseharian pribadi. Saat memilih masalah
harus berusaha menentukan apakah siswa-siswinya memiliki cukup banyak
pengetahuan awal untuk secara efektif merancang satu strategi demi memecahkan
satu masalah tersebut sehingga perlu pengalaman terus menerus untuk mencapai
menghadapi masalah dan langkah ketiga mengakses materi, jika pemecahan
masalah ingin berlangsung mulus, siswa harus memahami apa yang mereka
usahakan untuk dicapai dan mereka harus memiliki akses pada materi yang
dibutuhkan untuk memecahkan masalahnya.
Setelah mengidentifikasi topik, menentukan tujuan, memilih masalah dan
mengakses materi kini kita siap menerapkan pelajaran. Menerapkan pelajaran
untuk pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa harus memecahkan satu
masalah spesifik dan memahami materi yang terkait dengan itu. Kedua, siswa
harus mengembangkan kemampuan pemecahan masalah serta menjadi murid
mandiri.
Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menghendaki bahwa
suatu pembelajaran pada dasarnya tidak hanya mempelajari tentang konsep, teori
dan fakta tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian
materi pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal yang sederhana yang
bersifat hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas materi yang kompleks
yang memerlukan analisis, aplikasi dan sintesis. Oleh karena itu guru harus dapat
menerapkan model pembelajaran yang mampu dan mengembangkan dan
menggali pengetahuan peserta didik secara konkret dan mandiri.
Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran di sekolah adalah masih rendahnya
daya serap peserta didik. Hal ini nampak dari rerata hasil belajar peserta didik
yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Kondisi ini merupakan hasil
kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh
Dalam arti yang lebih substansial, proses pembelajaran hingga dewasa ini masih
memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik untuk
berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. Oleh
karena itu diperlukan perubahan pola pikir dan mindsed guru bahwa orientasi
pembelajaran yang semula berpusat pada guru beralih berpusat pada siswa.
Mata pelajaran fisika merupakan salah satu pilar utama ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memberikan pemahaman mengenai fenomena alam serta
kemungkinan aplikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup umat
manusia. Hampir semua aspek dalam kehidupan ini menggunakan aplikasi konsep
fisika, dari hal yang paling sederhana hingga hal yang begitu rumit. Penguasaan
pemahaman konsep fisika yang kuat diperlukan siswa untuk mengembangkan
konsep-konsep fisika sehingga dapat berguna di masa depan. Pengembangan
konsep-konsep fisika dapat dilakukan jika siswa dapat memahami dan
meningkatkan kemampuan menggunakan konsep fisika dalam mengkomunikasi
ide atau gagasan.
Komunikasi ilmiah sangat diperlukan saat proses pembelajaran fisika supaya
pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa dapat memahami konsep
fisika. Komunikasi ilmiah dalam ilmu fisika sangat penting, seperti halnya yang
diungkapkan oleh Hamid (2011: 3), fisika sebagai bangunan ilmu disangga oleh
enam pilar, yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah, produk ilmiah, penerapan produk
ilmiah ke dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan industri, komunikasi
Proses pembelajaran di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, masih menggunakan
cara yang sangat sederhana, hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan yang
dimiliki oleh guru kepada siswa. Proses pembelajaran tersebut tidak
memperhatikan proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut sehingga
mengakibatkan dalam proses pembelajaran ini siswa kurang berperan aktif dan
sangat bergantung oleh guru sedangkan guru sangat aktif dalam proses
pembelajaran. Guru fisika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dalam kegiatan
proses pembelajarannya masih berpusat pada guru, guru aktif dalam pembelajaran
dan pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pembagian
tugas. Proses pembelajarannya guru memberikan materi pembelajaran, siswa
memperhatikan dan mencatat penjelasan guru. Kemudian mengerjakan soal, salah
satu siswa mengerjakan soal di papan tulis dan siswa lain mengerjakan soal pada
buku catatan. Setelah itu, guru melakukan pengecekan jawaban soal dan
melakukan pembahasan soal terhadap jawaban siswa, tampak pada kegiatan
tersebut siswa tidak memperhatikan atau melakukan aktivitas lain, contohnya
mengobrol dengan temannya. Siswa hanya mencatat hasil jawaban guru yang
tertulis di papan tulis tanpa ada siswa yang berpendapat atau menanyakan
jawabannya yang berbeda dengan jawaban tersebut. Pada kasus lain bahkan
terdapat siswa yang tidak melakukan aktivitas pembelajaran dan hanya
mengganggu teman yang lain. Hal ini membuktikan bahwa guru lebih aktif dalam
kegiatan pembelajaran dan siswa hanya mengikuti proses pembelajaran, tidak
Pada saat mengerjakan tugas atau soal-soal uraian fisika dilembar jawaban soal
uraian, seringkali siswa hanya memberikan atau menuliskan persamaan fisika
tanpa memberikan gambar atau ilustrasi dari soal yang diberikan. Hal itu
mengakibatkan siswa dapat salah konsep oleh adanya kesalahan pemahaman di
saat memahami soal dalam bentuk soal cerita dan belum dalam bentuk matematis
sehingga dapat terjadi kesalahan pada saat mensubsitusikan nilai yang diketahui
pada soal ke dalam persamaan. Hal itu diakibatkan siswa tidak terbiasa atau tidak
dapat mendiskripsikan ilustrasi soal fisika dalam kehidupan nyata disebabkan oleh
tingkat komunikasi ilmiah yang kurang, pemahaman siswa yang kurang, dan
siswa hanya menghafal persamaan bukan memahami konsep fisika dan
kemampuan siswa yang kurang dalam mengubah bentuk soal ke dalam model
fisika.
Kondisi lainnya yang sering terjadi adalah terdapat siswa yang hanya mencatat
atau menuliskan persamaan fisika yang dijelaskan guru yang tertulis di papan
tulis, tanpa siswa mengetahui makna dari persamaan tersebut. Sehingga siswa
hanya mengetahui persamaan fisika dan menghafal persamaan tersebut tanpa
mengetahui makna, konsep dan arti bahasa yang terdapat didalam persamaan itu.
Jadi tidak mengherankan jika siswa memiliki kemampuan komunikasi yang relatif
rendah. Pemahaman konsep fisika lebih penting dari pada mengahafal persamaan
fisika yang telah ada. Siswa yang mampu memahami konsep fisika dapat
menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ilmu fisika dan
penerapannya, tidak hanya mampu menyelesaikan soal-soal fisika yang matematis
namun soal yang telah dikembangakan oleh guru. Sedangkan siswa yang hanya
yang matematis, belum penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari
dan belum tentu dapat mengerjakan soal yang dikembangkan oleh guru. Sehingga
siswa lebih baik memahami konsep fisika dari pada menghafal persamaan fisika.
Siswa dapat memahami konsep fisika maka siswa tersebut mengetahui persamaan
fisika, sedangakan siswa yang menghafal persamaan fisika belum tentu
memahami konsep fisika tersebut.
Peran guru sangatlah penting dalam proses pembelajaran, guru harus dapat
menggunakan model, strategi, metode pembelajaran yang cocok untuk
meminimalisir aspek-aspek siswa tidak dapat memahami konsep fisika. Guru
harus dapat membuat siswa memahami konsep tidak hanya menghafal karena
dengan memahami konsep maka siswa akan lebih mudah memecahkan persoalan
fisika. Untuk itu seorang guru harus dapat menerapkan model pembelajaran yang
dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang fisika salah satunya adalah
penggunaan model pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis masalah.
Inti dari pembelajaran kontekstual adalah keterkaitan setiap materi atau topik
pembelajaran dengan kehidupan nyata. Untuk mengaitkannya dapat dilakukan
berbagai cara, selain karena memang materi yang dipelajari secara langsung
terkait dengan kondisi faktual, juga dapat disiasati dengan pemberian ilustrasi atau
contoh, sumber belajar, media dan lain sebagainya yang memang baik secara
langsung maupun tidak diupayakan terkait atau ada hubungan dengan pengalaman
hidup nyata. Dengan demikian, pembelajaran selain akan lebih menarik, juga akan
dirasakan sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena apa yang dipelajari
masalah adalah pelajaran berfokus pada memecahkan masalah, tanggung jawab
untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa dan guru mendukung proses
saat siswa mengerjakan masalah.
Berdasarkan kajian di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian
tentang : “Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kontekstual dan Berbasis Masalah dengan Kemampuan Awal pada Mata
Pelajaran Fisika Siswa Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung”.
1.2Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah
penelitian ini sebagai berikut:
1. Prestasi belajar fisika siswa masih belum optimal dan rendah, sedangkan
fisika adalah salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional dan
menjadi salah satu kriteria kelulusan siswa.
2. Kurangnya kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran bermakna dalam
menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan
menyenangkan.
3. Penggunaan model pembelajaran yang belum tepat sehingga pembelajaran
masih terpusat pada guru.
4. Model pembelajaran kontekstual belum dilaksanakan oleh guru mata pelajaran
fisika di dalam kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
5. Model pembelajaran berbasis masalah belum dilaksanakan oleh guru mata
pelajaran fisika di dalam kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
1.3Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan kepada
perbedaan prestasi belajar siswa menggunakan model pembelajaran kontekstual
dan berbasis masalah dengan kemampuan awal pada mata pelajaran fisika siswa
Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung.
1.4 Perumusan Masalah
1. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kontekstual dan berbasis
masalah dan kemampuan awal dengan prestasi belajar pada mata pelajaran
fisika siswa Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung?
2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan
kemampuan awal pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di SMA
Negeri 13 Bandar Lampung?
3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan
kemampuan awal tinggi pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di
SMA Negeri 13 Bandar Lampung?
4. Apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan
kemampuan awal rendah pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di
1.5Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki proses pembelajaran fisika dan untuk :
1) Mendeskripsikan interaksi antara model pembelajaran kontekstual dan
berbasis masalah dan kemampuan awal dengan prestasi belajar pada mata
pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung.
2) Mendeskripsikan perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan
kemampuan awal pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di SMA
Negeri 13 Bandar Lampung.
3) Mendeskripsikan perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan
kemampuan awal tinggi pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di
SMA Negeri 13 Bandar Lampung.
4) Mendeskripsikan perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan
kemampuan awal rendah pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di
SMA Negeri 13 Bandar Lampung.
1.6Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Secara Teoritis
Hasil penelitian secara teoritis dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan,
khususnya bagi teknologi pendidikan dalam kawasan disain dan meningkatkan
1.6.2 Manfaat Secara Praktis
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.6.2.1Bagi Siswa
Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika.
1.6.2.2Bagi Guru
Memiliki gambaran mengenai pembelajaran fisika yang efektif, dapat
mengidentifikasi permasalahan belajar yang ada di kelas, dapat mencari solusi
untuk pemecahan masalah tersebut dan dapat digunakan untuk menyusun program
peningkatan prestasi belajar siswa.
1.6.2.3Bagi Peneliti
Peneliti dapat memperoleh pengalaman secara langsung dalam menerapkan model
pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan profesionalisme peneliti
serta dapat dijadikan bahan rujukan penelitian lebih lanjut pada waktu mendatang.
1.6.2.4Bagi Sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi output (lulusan) yang dihasilkan,
15
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS
2.1 Belajar dan Pembelajaran
2.1.1 Pengertian Belajar
Belajar adalah key term,„istilah kunci‟ yang paling vital dalam setiap usaha
pendidikan, sehingga tanpa belajar yang sesungguhnya tak pernah ada pendidikan.
Sebagai suatu proses, belajar selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai
displin ilmu yang berkaitan dengan upaya pendidikan. Menurut Slameto (2010: 2)
belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil
pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Djamarah (2008: 13) menyatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu
kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa dan raga. Gerak
raga yang ditunjukan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan
perubahan. Perubahan yang didapatkan bukan perubahan fisik, tetapi perubahan
jiwa dengan sebab masuknya kesan-kesan yang baru. Perubahan sebagai hasil dari
proses belajar adalah perubahan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.
Anderson (2001: 35) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan
yang relatif menetap terjadi dalam tingkah laku potensial sebagai hasil dari
pengalaman. Gagne dalam Sagala (2011: 17) belajar merupakan kegiatan yang
16
proses yang bersifat internal bagi setiap pribadi yang merupakan hasil
transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan
pribadi yang bersangkutan (kondisi).
Gagne dalam Sagala (2011: 17) menyatakan bahwa di dalam proses belajar
terdapat dua fenomena yang berlaku yaitu: (1) keterampilan intelektual yang
meningkat sejalan dengan meningkatnya umur dan latihan yang didapat individu,
dan (2) belajar akan lebih cepat apabila strategi kognitif dapat dipakai dalam
memecahkan masalah secara lebih efisien. Gagne berpendapat bahwa, belajar
merupakan suatu proses yang bukan terjadi secara alamiah, tetapi hanya akan
terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu. Kondisi ini menyangkut kondisi
internal dan eksternal, kondisi internal berhubungan dengan kesiapan siswa dan
apa yang telah dipelajari sebelumnya, sementara kondisi eksternal merupakan
situasi belajar dan penyajian stimulus yang sengaja diatur oleh guru dengan tujuan
memperlancar proses belajar. Belajar yang terbaik ialah dengan mengalami
sendiri, dan dalam mengalami itu si pelajar menggunakan panca indera. Hal-hal
yang pokok dalam “belajar” adalah bahwa belajar itu membawa perubahan (dalam
arti behavioral changes, actual maupun potensial, bahwa perubahan itu pada
pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru, bahwa perubahan itu terjadi
karena usaha (dengan sengaja).
Pengertian belajar yang merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan
dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun
implisit (Sagala : 2011). Sedangkan Garret dalam Sagala (2011 : 13) menyatakan
17
tertentu lama melalui latihan pengalaman yang membawa kepada perubahan diri
dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang”.
Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan,
sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat
melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Belajar adalah proses berpikir. yang
menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui proses
interaksi secara individu dengan lingkungan. Dalam pembelajaran di sekolah tidak
hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang
diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri
(self regulated).
Purwanto (2004: 85) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) elemen penting yang
mencirikan pengertian belajar yaitu :
1. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan
pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh
pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti
perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. Untuk dapat disebut
belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir
daripada suatu periode waktu yang cukup panjang;
2. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut aspek
kepribadian baik fisik maupun psikis seperti perubahan dalam pengertian,
pemecahan suatu masalah/berfikir, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan ataupun
18
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka dapat dinyatakan
bahwa belajar adalah seperangkat proses kognitif yang menghasilkan kapabilitas
berupa keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai yang diperoleh siswa melalui
pengalaman dan proses latihan. Peristiwa belajar lebih difokuskan pada proses
belajar dalam konteks formal yaitu proses belajar yang sengaja didesain atau
diciptakan untuk membuat seseorang dapat mencapai kompetensi tertentu.
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk mengadakan
perubahan dalam dirinya secara keseluruhan baik berupa pengalaman,
keterampilan, sikap dan tingkah laku sebagai akibat dari latihan serta interaksi
dengan lingkungannya.
2.1.2 Pengertian Pembelajaran
Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa ”pembelajaran
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar”. Dari pernyataan tersebut agar pembelajaran dikatakan
berhasil, harus ada interaksi antara siswa sebagai peserta didik dengan guru
sebagai pendidik maupun dengan sumber belajar.
Dimyati dalam Sagala (2011: 62) memberikan pengertian pembelajaran adalah
”kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat
siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.
Dari pengertian tersebut, agar pembelajaran sejarah berjalan dengan baik guru
19
Definisi pembelajaran disampaikan oleh Smith dan Ragan dalam Pribadi
(2011: 6) yang mengemukakan bahwa pembelajaran adalah pengembangan dan
penyampaian informasi dan kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi
pencapaian tujuan yang spesifik. Miarso (2009: 144) memaknai istilah
pembelajaran sebagai aktivitas atau kegiatan yang berfokus pada kondisi dan
kepentingan pemelajar (learner centered) untuk menggantikan istilah
“pengajaran” yang lebih bersifat sebagai aktivitas yang berpusat pada guru
(teacher centered). Miarso (2009: 545) menjelaskan lebih rinci definisi
pembelajaran sebagai berikut: “pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang
relatif menetap pada diri orang lain. Usaha ini dapat dilakukan oleh seseorang
atau suatu tim yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam merancang
atau mengembangkan sumber belajar yang diperlukan.
Lebih lanjut Miarso (2009: 545) menyatakan bahwa istilah pembelajaran harus
dibedakan dengan istilah pengajaran. Pengajaran merupakan istilah yang
diartikan sebagai penyajian bahan ajar yang dilakukan oleh pengajar, sedangkan
kegiatan pembelajaran tidak harus diberikan oleh pengajar karena kegiatan itu
dapat dilakukan oleh perancang dan pengembang sumber belajar, misalnya
seorang teknolog pendidikan atau tim ahli. Pembelajaran adalah serangkaian
aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya
proses belajar. Proses belajar sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa
belajar. Peristiwa belajar menurut Gagne seperti dikutip oleh Djamarah (2008:
78) disebut sembilan peristiwa pembelajaran (model nine instructional event
20
1) Menarik perhatian agar siap menerima pelajaran;
2) Memberitahukan tujuan pembelajaran agar anak didik tahu apa yang
diharapkan dari belajar itu;
3) Merangsang timbulnya ingatan atas ajaran sebelumnya;
4) Presentasi bahan ajaran;
5) Memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar;
6) Membangkitkan timbulnya unjuk kerja (merespons);
7) Memberikan umpan balik atas unjuk kerja;
8) Menilai unjuk kerja;
9) Memperkuat retensi dan transfer pelajaran.
Pembelajaran merupakan proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan
terjadinya proses belajar dalam diri individu. Pembelajaran merupakan sesuatu
hal yang bersifat eksternal sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya
proses belajar internal dalam diri individu. Dick and Carey (2005: 205)
mendefinisikan pembelajaran sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang
disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau
beberapa jenis media.
Proses pembelajaran mempunyai tujuan yaitu agar siswa dapat mencapai
kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses
pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan sistemik. Pembelajaran
merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan.
Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat dipandang dari
21
pencapaian kualitas pembelajaran merupakan tanggung jawab profesional seorang
guru, misalnya melalui penciptaan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa
dan fasilitas yang didapat siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal.
Pada tingkat makro, melalui sistem pembelajaran yang berkualitas, lembaga
pendidikan bertanggung jawab terhadap pembentukan tenaga pengajar yang
berkualitas, yaitu yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan intelektual,
sikap, dan moral dari setiap individu peserta didik sebagai anggota masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu, guru memegang peran strategis dalam membentuk
watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.
Sehingga peran guru sulit digantikan oleh yang lain.
2.2Teori Belajar dan Pembelajaran
2.2.1 Teori Belajar
Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana
terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam siswa itu.
Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih
meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar.
Gagne seperti yang dikutip oleh Sagala (2011: 25) menyatakan untuk terjadinya
belajar pada diri siswa diperlukan kondisi belajar, baik kondisi internal maupun
kondisi eksternal. Kondisi internal merupakan peningkatan memori siswa sebagai
hasil belajar terdahulu. Memori siswa yang terdahulu merupakan komponen yang
baru dan ditempatkannya bersama-sama. Kondisi eksternal meliputi aspek atau
22
(learning outcomes), Gagne seperti yang dikutip oleh Sagala (2011: 25)
menyatakan dalam lima kelompok, yaitu intelektual skill, cognitive strategy,
verbal information, motor skill, dan attitude.
Gagne lebih lanjut menekankan pentingnya kondisi internal dan kondisi eksternal
dalam suatu pembelajaran, agar siswa memperoleh hasil belajar yang diharapkan.
Dengan demikian, sebaiknya memperhatikan atau menata pembelajaran yang
memungkinkan mengaktifkan memori siswa yang sesuai agar informasi yang baru
dapat dipahaminya. Kondisi eksternal bertujuan antara lain memberikan stimulasi
berpikir siswa, penginformasian tujuan pembelajaran, membimbing belajar materi
yang baru, memberikan kesempatan kepada siswa menghubungkannya dengan
informasi baru guna memacu siswa agar dapat berpikir kritis.
Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori
pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of learning). Teori
konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan
aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.
Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan,
mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk
dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide, mampu berpikir kritis.
Siswa harus membangun sendiri pengetahuan didalam benaknya sedangkan Guru
dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan
siswa untuk menemukan dan menetapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar
23
belajar Teori ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan
informasi, teori berpikir kritis, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori
Bruner (Slavin dalam Nurhadi, 2009: 80).
Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi
pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan
kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.
Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman
yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga
tersebut (Nurhadi, 2009: 8).
Perkembangan kognitif sebagaian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi
aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakin
bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi
terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interakasi sosial
dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu
memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat pemikiran itu menjadi lebih
logis (Nurhadi, 2009).
Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang
perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif
membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui
pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Menurut Piaget perkembangan
kognitif pada anak secara garis besar terbagi empat periode yaitu: a) periode
24
Sedangkan konsep-konsep dasar proses organisasi dan adaptasi intelektual
menurut Piaget yaitu: skemata (dipandang sebagai sekumpulan konsep); asimilasi
(peristiwa mencocokkan informasi baru dengan informasi lama yang telah
dimiliki seseorang; akomodasi (terjadi apabila antara informasi baru dan lama
yang semula tidak cocok kemudian dibandingkan dan disesuaikan dengan
informasi lama); dan equilibrium (bila keseimbangan tercapai maka siswa
mengenal informasi baru).
Menurut Piaget dalam Uno (2010: 3) menegaskan bahwa pengetahuan tersebut
dibangun dalam pikiran seseorang melalui proses asimilasi dan akomodasi.
Asimilasi adalah proses kognitif seseorang dalam mengintegrasikan persepsi,
konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di
dalam pikirannya. Akomodasi adalah proses mental yang meliputi pembentukan
skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi skema yang
sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Sedangkan equilibrium adalah
pengaturan diri seseorang agar terjadi keseimbangan antara proses asimilasi dan
akomodasi. Apabila keadaan tidak seimbang antara asimilasi dan akomodasi maka
disebut dengan disequilibrium.
Tokoh teori belajar konstruktivisme sosial adalah Lev Vygotsky yang berpendapat
bahwa belajar bagi peserta didik dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan
sosial maupun fisik. Lebih lanjut dikatakan bahwa, interaksi sosial memegang
peranan terpenting dalam perkembangan kognitif peserta didik. Ada dua tahapan
belajar, pertama peserta didik belajar melalui interaksi dengan orang lain, baik
25
peserta didik mengintegrasikan apa yang ia pelajari dari orang lain kedalam
struktur mentalnya (Herpratiwi, 2009: 80).
Teori belajar Ausubel merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori yang
menjadi dasar dalam cooperative learning. Ausubel seperti dikutip oleh Dahar
(2008: 115) menyatakan bahwa bahan subjek yang dipelajari siswa haruslah
“bermakna” (meaningfull). Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses
mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam
struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep,
dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Pembelajaran
bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan
dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui
pembelajaran.
Pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa boleh menghubungkan fenomena
baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan subjek itu harus
sesuai dengan keterampilan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang
dimiliki siswa. Oleh karena itu, subjek harus dikaitkan dengan konsep-konsep
yang sudah dimiliki para siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut
benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual-emosional siswa
terlibat dalam kegiatan pembelajaran.
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel
(Dahar, 2008: 116) adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan
pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat
26
informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu, demikian pula sifat proses
interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil, dan diatur dengan baik,
maka arti-arti yang sahih dan jelas atau tidak meragukan akan timbul dan
cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya jika struktur kognitif itu tidak stabil,
meragukan, dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat
belajar.
Menurut Ausubel (Dahar, 2008: 116), seseorang belajar dengan mengasosiasikan
fenomena baru ke dalam sekema yang telah ia punya. Dalam proses itu seseorang
dapat memperkembangkan skema yang ada atau dapat mengubahnya. Dalam
proses belajar ini siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. Teori belajar
bermakna Ausuble ini sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya
menekankan pentingnya siswa mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan
fakta-fakta baru kedalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya
menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru kedalam konsep atau
pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam
proses belajar itu siswa aktif.
Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif
siswa melalui proses belajar yang bermakna., Ausubel beranggapan bahwa
aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar-
akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung.
Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung
akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau
27
Inti dari teori belajar bermakna Ausubel adalah proses belajar akan mendatangkan
hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pelajaran yang baru
dapat menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam
struktur kognisi siswa.
Langkah-langkah yang biasanya dilakukan guru untuk menerapkan belajar
bermakna Ausubel adalah sebagai berikut: advance organizer, progressive
differensial, integrative reconciliation, dan consolidation. Empat tipe belajar
menurut Ausubel (Dahar, 2008: 117) yaitu:
1. Belajar dengan penemuan yang bermakna yaitu mengaitkan pengetahuan yang
telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Atau sebaliknya,
siswa terlebih dahulu menmukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari
kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang
sudah ada.
2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna yaitu pelajaran yang dipelajari
ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah
dimilikinya, kemudian dia hafalkan.
3. Belajar menerima (ekspositori) yang bermakna yaitu materi pelajaran yang
telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir,
kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan
lain yang telah dimiliki.
4. Belajar menerima (ekspositori) yang tidak bermakna yaitu materi pelajaran
yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk
akhir , kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa
28
Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan oleh Ausubel adalah teori
model mengajar Advance Organizer adalah salah satu model dalam rumpun
pemprosesan informasi. David Ausubel dalam Joyce, (2009:208) mengemukakan
teorinya menyangkut empat hal :
1. Bagaimana ilmu itu diorganisasikan artinya bagaimana seharusnya isi
kurikulum itu di tata.
2. Bagaimana proses berpikir itu terjadi bila berhadapan dengan informasi baru.
3. Bagaimana guru seharusnya mengajarkan informasikan baru itu sesuai dengan
teori tentang isi kurikulum dan teori belajar.
4. Sintaks
Model pembelajaran Advance Organizer terdiri dari tiga tahap.
Tabel 2.1: Sintaks Model Pembelajaran Advance Organizer
Tahap Tingkah Laku Guru
3. Menumbuhkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman
siswa yang relevan.
Tahap-2
Penyajian bahan pelajaran
1. Membuat organisasi secara tegas
2. Membuat urutan bahan pelajaran secara logis dan
eksplisit
3. Memelihara suasana agar penuh perhatian
4. Menyajikan bahan
Tahap-3
Penguatan organisasi kognitif
1. Menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi integratif 2. Meningkatkan kegiatan belajar (belajar menerima)
3. Melakukan pendekatan kritis guna memperjelas materi
pelajaran
4. Mengklarifikasikan
29
2.2.2 Teori Pembelajaran
Di dalam teknologi pendidikan dibedakan antara istilah pembelajaran
(instructional) dan pengajaran (teaching). Menurut Miarso (2009: 545)
pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan dan terkendali agar
orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain.
Sedangkan pengajaran adalah usaha membimbing dan mengarahkan pengalaman
belajar kepada peserta didik. Istilah mengajar (teaching) sebagai penyampai
materi pelajaran kepada peserta didik, dianggap tidak sesuai lagi sehingga dalam
literatur teknologi pendidikan hanya digunakan istilah pembelajaran.
Pembelajaran adalah proses yang sistematis, dimana semua komponen antara lain
guru, peserta didik (siswa), material dan lingkungan belajar merupakan komponen
penting untuk keberhasilan belajar. Pembelajaran sebagai sebuah sistem
menggunakan pendekatan sistem dalam desain pembelajaran. Sistem yang
dimaksud adalah bahwa semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran
saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Menurut Reigeluth dan Merill dalam Miarso (2009: 529) pembelajaran sebaiknya
didasarkan pada teori pembelajaran preskriptif, yaitu teori yang memberi resep
untuk mengatasi masalah belajar. Teori pembelajaran preskeptif tersebut
memperhatikan tiga variabel yaitu kondisi, metode dan hasil. Di dalam setiap
metode pembelajaran harus mengandung rumusan pengorganisasian bahan
pelajaran, strategi penyampaian, dan pengelolaan kegiatan dengan memperhatikan
faktor tujuan belajar, hambatan belajar, karakteristik siswa agar dapat diperoleh
30
Menurut Sanjaya (2005: 78) istilah pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan
tekbologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar, peserta didik
ditempatkan sebagai subjek belajar yang memegang peranan paling utama,
sehingga dalam setting proses belajar mengajar peserta didik dituntut beraktivitas
secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. Dengan
demikian kalau didalam istilah pengajaran (teaching) menempatkan guru sebagai
pemeran utama dalam memberikan informasi kepada peserta didik, maka dalam
istilah pembelajaran (instruction) guru lebih banyak sebagai fasilitator yang
mengelola berbagai sumber belajar untuk dipelajari peserta didik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai
proses belajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta
dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai
upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, peserta didik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Selain itu dengan semakin berkembangnya teknologi dalam
pembelajaran, maka pola interaksi antara guru, peserta didik dan sumber belajar
mengalami perubahan dari pola pembalajaran yang berpusat pada guru (teacher
centered) menjadi berpusat pada peserta didik (student centered) dimana peran
31
2.3Teori Desain Pembelajaran ASSURE
Teknologi pendidikan merupakan sebuah bidang yang fokus pada upaya-upaya
yang dapat digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dalam
diri individu. Hal ini sesuai dengan definisi teknologi pendidikan yang
dikemukakan oleh AECT (Association of Educational Communication and
Technology), yaitu sebuah studi dan praktik etis yang berupaya membantu
memudahkan berlangsungnya proses belajar dan perbaikan kinerja melalui
penciptaan, penggunaan, pengelolaan, proses, teknologi dan sumber daya yang
tepat. Seels dan Richey (dalam Pribadi 2011: 63) mengemukakan bahwa
teknologi pendidikan memiliki lima domain atau bidang garapan, yaitu:
(1) desain, (2) pengembangan, (3) pemanfaatan, (4) pengelolaan, dan (5) evaluasi.
Bidang garapan desain meliputi beberapa bidang kerja yaitu desain pembelajaran,
desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Hal ini menunjukkan
bahwa desain merupakan salah satu domain atau bidang garapan yang penting
dalam teknologi pendidikan yang berperan sebagai salah satu sarana untuk
memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dan memperbaiki kinerja.
Pribadi (2011: 54) mengemukakan bahwa upaya untuk mendesain proses
pembelajaran agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif, efisien, dan menarik
disebut dengan istilah desain sistem pembelajaran atau instructional system design
(ISD).
Smith dan Ragan (dalam Pribadi 2011: 55) mengemukakan bahwa desain sistem
pembelajaran adalah proses sistematik yang dilakukan dengan menerjemahkan