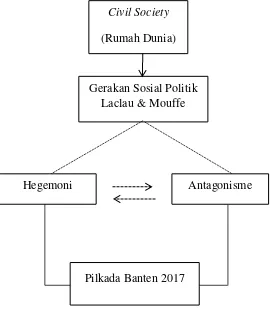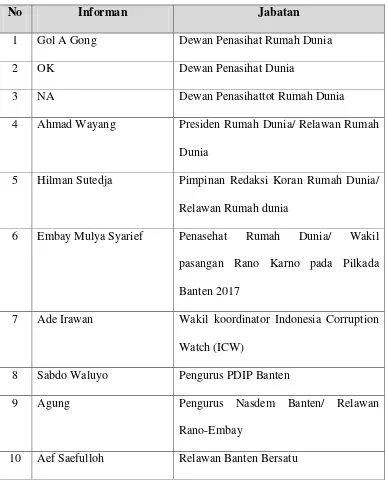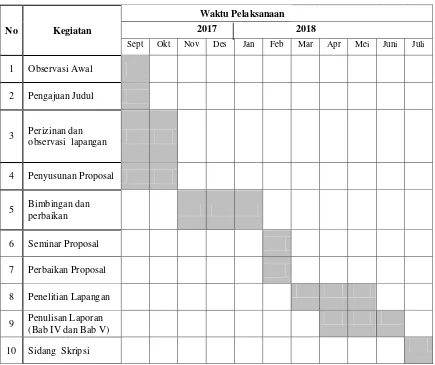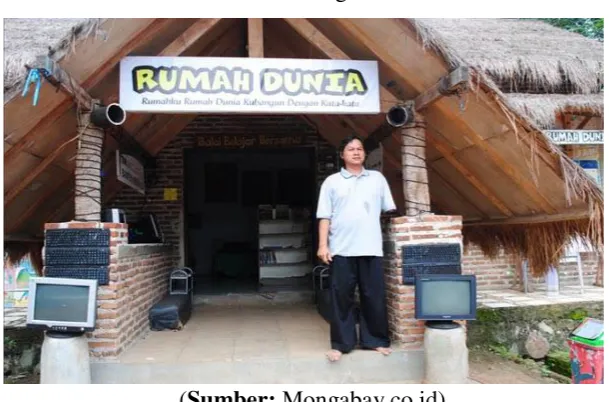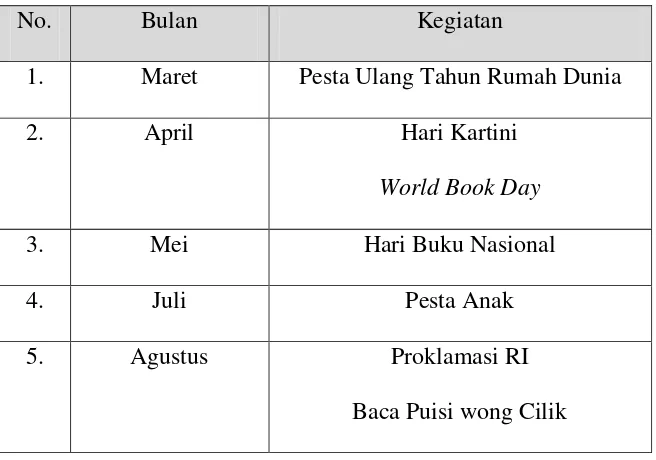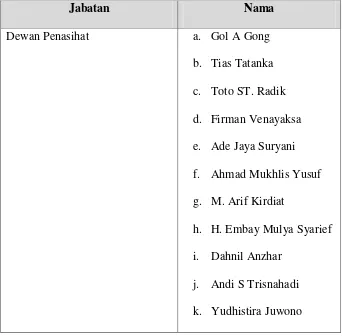SKRIPSI
Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu
Pemerintahan
Disusun Oleh: SIFA NURFADILAH
NIM. 6670142378
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat allah SWT, yang telah
memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya,
dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman
pencerahan. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan
pembuatan skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Civil Society Dalam Pilkada
(Studi Kasus Rumah Dunia Dalam Pilkada Banten 2017).
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud baktiku kepada kedua
orang tua tercinta Bapak Muhayar dan Ibu Munawaroh yang tidak ada hentinya
memberikan kasih sayang, kepercayaan, semangat, nasehat yang diberikan
kepada penulis. Beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menjaga
penulis dari hal-hal negatif, serta memberi materi untuk kecukupan penulis
sehari-hari. Semoga Allah memberi kemudahan dan kesempatan kepada penulis untuk
berbakti kepada orang tua di dunia sebagai bekal di akhirat. Juga penulis
persembahkan pada keluarga besar, kakak-kakak serta adik kesayangan yang
selalu memberikan bantuan doa dan dukungan kepada penulis.
Dengan segala keramahan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan
terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak
Abdul Hamid, Ph.D atau biasa disebut Abah dan M. Dian Hikmawan, S. Hum,
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa
adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu membimbing serta mendukung
penulis secara moril dan materil. Maka dengan segala ketulusan hati, penulis juga
ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak berikut:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Desan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si selaku Wakil dekan I Bidang Akademik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan
dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
7. Ika Arinia Indriyany, S.IP, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
8. Shanty Kartika Dewi, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing akademik
yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama
menempuh pendidikan di kampus ini.
9. M. Rizky Godjali, S.IP, M.IP selaku kepala Laboratorium Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa yang telah memberikan banyak pembelajaran dan
pengalaman kepada penulis sebagai bagian dari anggota Laboratorium
Ilmu Pemerintahan.
10.Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11.Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2014 dan yang penulis
cintai Forum Keluarga Ilmu Pemerintahan (Forklip) Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12.Keluarga Pengurus HIMAIP 2015, DPM FISIP 2016, dan Anggota
13.Yang saya cintai dan sayangi Rumboy’s Family dan The Next Leader’s
14.Segala pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah
membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat
banyak kekurangan, maka kritik dan sara yang membangun sangat penulis
harapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini. Penulis berharap semoga
penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para
pembaca pada umumnya.
Alhamdulillahirrabbil’alamiin.
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.
Tangerang, 7 Juli 2018
Society dalam Pilkada (Studi Kasus Rumah Dunia dalam Pilkada Banten 2017). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Abdul Hamid, Ph.D, Dosen Pembimbing II: M. Dian Hikmawan, S.Hum, M.A.
Pilkada Provisi Banten 2017 merupakan pilkada pertama kali yang hanya diikuti
dua pasangan calon yaitu Wahidin-Andika dan Rano-Embay. Dalam pilkada tentu
tidak bisa dipisahkan dari peran serta civil society. Salah satu yang berperan dalam
pilkada adalah Rumah Dunia yang merupakan civil society yang bergerak di
bidang literasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik
Rumah Dunia dalam pilkada, menganalisis mengapa Rumah Dunia berperan
dalam pilkada dan apa saja yang dilakukan. Tipe penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Adapun jenis data berupa data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik Rumah Dunia dalam
pilkada Banten tahun 2017 adalah bagian dari nilai yang selama ini diperjuangkan
oleh Rumah Dunia yaitu menolak praktik korupsi. Diketahui, salah satu dari
pasangan calon adalah bagian dari keluarga dinasti yang terkena kasus korupsi.
Adapun partisipasi atau gerakan politik Rumah Dunia dalam mendukung
pasangan Rano-Embay antara lain: Membantu proses pembuatan buku biografi
Rano yaitu Si Doel dan melakukan roadshow bedah buku Si Doel di seluruh
Kabupaten dan Kota di Banten, membuat tulisan yang dipublikasikan melalui
media Rumah Dunia berbasis online Koranrumahdunia.com, bergabung dan
menjadi bagian dari koalisi Gempa dan FBB, membuat meme atau gambar yang
mempromosikan figur dari Rano-Embay dan tentang korupsi dan dinasti dan
menghadiri deklarasi pasangan calon Rano-Embay.
Civil Society in Gubernatorial Election (A Case Study of Rumah Dunia in 2017 Banten Gubernatorial Election). Study Program of Government Sciences, Faculty of Social and Political sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Superviser I: Abdul Hamid, Ph.D, Superviser II: M. Dian Hikmawan, S.Hum, M.A.
Banten election 2017 is the first pilkada that only followed two candidate pairs
namely Wahidin-Andika and Rano-Embay. In the pilkada certainly can not be
separated from the participation of civil society. One of those who play a role in
the election is Rumah Dunia which is a civil society engaged in the field of
literacy. This study aims to determine the political participation of Rumah Dunia
in election, analyze why Rumah Dunia role in election and what is done. Type of
descriptive research with qualitative approach. The type of data in the form of
primary data and secondary data. The results of this study indicate that the
political participation of Rumah Dunia in the Banten regional election 2017 is part
of the value that has been fought by Rumah Dunia is to reject the practice of
corruption. Known, one of the candidate pairs is part of a family of political
dynasties affected by corruption case. The participation or political movements of
Rumah Dunia in support of Rano-Embay couples include: Helping the process of
making Rano's biography book Si Doel and conducting Si Doel's surgical
roadshows all of the districts and cities in Banten, making the writings published
through online Rumah Dunia media Koranrumahdunia.com, join and be part of
the Gempa and FBB coalitions, creates memes or images promoting figures from
Rano-Embay and about corruption and political dynasties, and attend the
declaration of the Rano-Embay candidates.
LEMBAR PERSETUJUAN... i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI... ii
KATA PENGANTAR ... iii
DAFTAR ISI ... vi
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR GAMBAR ... x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah ... 1
B. Identifikasi Masalah ... 13
C. Rumusan Masalah ... 13
D. Tujuan Penelitian ... 13
E. Kegunaan Penelitian ... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori ... 16
1. Partisipasi Politik ... 16
2. Konsep Civil Society (Masyarakat Sipil) ... 19
3. Gerakan Sosial Laclau & Maouffe ... 33
4. Demokrasi Lokal di Indonesia ... 43
B. Studi Terdahulu ... 47
C. Kerangka Berpikir ... 53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan dan Desain penelitian ... 55
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian ... 62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 64
Sejarah Rumah Dunia ... 64
1. Politik Lokal di Banten ... 76
2. Rumah Dunia dan Politik Dinasti di Banten ... 89
B. Pembahasan ... 103
1. Rumah Dunia dan Pilkada Banten 2017 ... 103
a. Partisipasi Politik Rumah Dunia Selama Pilkada Banten 2017 ... 116
b. Ancaman dan Teror Terhadap Rumah Dunia Selama Pilkada Banten 2017 ... 127
2. Resistensi Rumah Dunia Terhadap Dinasti Politi Ditinjau Dari Gerakan Sosial Politik Laclau dan Mouffe ... 130
a. Transisi Subjek Politik Rumah Dunia ... 135
b. Dinasti Politik sebagai Rezim Hegemonik ... 139
c. Antagonisme Politik Rumah Dunia Terhadap Dinasti Politik ... 141
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 150
B. Saran ... 152
DAFTAR PUSTAKA ... 154
Tabel 1. Formula Analisis CSO ... 25
Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu ... 51
Tabel 3. Informan penelitian ... 61
Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Penelitian ... 63
Tabel 5. Program Reguler Rumah Dunia ... 69
Tabel 6. Program Unggulan Rumah Dunia ... 70
Tabel 7. Struktur Organisasi Rumah Dunia ... 71
Tabel 8. Persebaran Politik Dinasti Atut di Lembaga Eksekutif dan Legislatif ... 82
Tabel 9. Keganjilan Dana Hibah Tahun 2011 menjelang Pilkada 2012 ... 88
Tabel 10. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2006 ... 104
Tabel 11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2012 ... 104
Tabel 12. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 ... 106
Tabel 13. Roadshow Bedah Buku Si Doel ... 117
Tabel 14. Daftar Tulisan Koran Rumah Dunia Tentang Pilkada dan Dinasti ... 120
Gambar 1.Tulisan Gol A Gong di Koran Rumah Dunia ... 10
Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir ... 54
Gambar 3. Gol A Gong di Rumah Dunia ... 67
Gambar 4. Auditorium Surosowan ... 75
Gambar 5. Beberapa Tokoh Pendiri Banten ... 77
Gambar 6. Atut berserta Keluarga ... 84
Gambar 7. Salah Satu Dokumentasi Kegiatan di Rumah Dunia ... 93
Gambar 8. Toto ST. Radik, Pendiri Rumah Dunia. ... 96
Gambar 9. Tanda Tangan Dana Hibah untuk Rumah Dunia dari Kemenpora RI 99 Gambar 10. Atut Ketika di Rumah Dunia Tahun 2006 ... 101
Gambar 11. Elektabilitas Bakal Calon Gubernur Banten 2017 ... 111
Gambar 12. Pilihan Calon Wakil Gubernur Banten ... 112
Gambar 13. Komunitas Buku si Doel di Bawaslu Banten ... 118
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masa transisi politik dari rezim orde baru ke reformasi membawa
angin segar bagi proses demokratisasi di Indonesia. Reformasi politik pada
tahun 1998 benar-benar telah mereformasi sendi-sendi politik bangsa
Indonesia. Di awal reformasi, setelah runtuhnya rezim Soeharto yang selama
32 tahun memimpin Indonesia secara otoriter, para penggerak reformasi
menuntut Indonesia untuk menerapkan sistem politik yang demokratis. Untuk
memenuhi aspirasi rakyat yang digemakan oleh gerakan reformis,
perubahan-perubahan mendasar harus di tegakkan, termasuk perubahan-perubahan menyeluruh pada
semua pranata sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan pada basis
hubungan antara rakyat dan negara. Perubahan-perubahan itu ditandai dengan
diadakan pemilu langsung, adanya kebebasan pers, mengurangi peran militer
dalam politik dan lain sebagainya yang mengarah pada demokratisasi di
Indonesia.
Praktek demokrasi dengan pemberian otoritas politik yang lebih besar
kepada rakyat diyakini hanya akan efektif terjadi jika pusaran mekanisme
pengelolaan pemerintahan didesentralisasikan kepada otoritas yang makin
dekat dengan rakyat. Karenanya pemberian kewenangan kepada satuan
kekuasaan pemerintahan yang lebih kecil dan lebih dekat dengan rakyat
2002: 31). Atas dasar pemikiran diatas, wacana desentralisasi tumbuh
berkembang mengiringi berbagai perubahan kearah demokratisasi politik
tersebut.
Namun pada kenyataannya semangat awal desentralisasi dan otonomi
daerah untuk perubahan terkadang tidak berjalan dengan baik dikarenakan
muncul masalah-masalah baru di tingkatan lokal. Tidak sedikit daerah yang
dikuasi oleh kekuasaan dominan dan dikendalikan oleh bos-bos lokal seperti
yang terjadi di Provinsi Banten yang berdirinya berbarengan dengan
semangat reformasi dan merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi
Jawa Barat.
Banten selama ini dikenal dengan dominasi politik di bawah dinasti
politik tertentu, yaitu dinasti keluarga Tb. Chasan Sochib. Tidak bisa
dipungkiri Tb. Chasan Sochib adalah aktor yang mampu mengendalikan
kekuasaan Banten melebihi aktor politik formal. Relasi antara penguasa,
pengusaha, kyai dan jawara tersentral di Tb. Chasan Sochib. Hal yang
mencuat ke permukaan adalah dia berhasil mengantarkan anaknya, Ratu Atut
Chasiyah menjadi Wakil Gubernur pertama di Banten melalui cara-cara
politik tidak sehat seperti adanya indikasi money politic dan intimidasi.
Selama masih hidup, Tb. Chasan juga mampu mengendalikan seluruh
proyek-proyek infrastruktur fisik, pengadaan barang dan jasa, dan melakukan
intimidasi proyek kepada pesaing-pesaingnya. Bahkan dia bisa mengarahkan
dan menekan pemerintah provinsi untuk mengakomodasi kepentingannya
tahunan. Maka tidak heran jika dia disebut atau dijuluki sebagai Gubernur
Jenderal di Banten (Hidayat, 2007, Masaaki & Hamid, 2008).
Setelah Chasan Sochib wafat, kekuatan kekuasaan keluarganya tidak
menghilang begitu saja tapi terwarisi pada anaknya yaitu Ratu Atut Chasiyah
dan sanak keluarga lain yang mampu menduduki posisi strategis di tampu
kekuasaan di Banten melalui ajang sarana pilkada. Setelah menjadi Wakil
Gubernur, Atut menjadi Gubernur Banten dua periode yaitu periode
2007-2012 dan 2007-2012-2017, namun pada tahun 2014 Atut dinonaktifkan dari
jabatannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena menjadi
tersangka terkait kasus suap pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada pilkada 2015, Adik ipar Atut, yaitu Airin Rachmi Diany terpilih
menjadi Wali Kota Tangerang Selatan periode 2015- 2020 yang diperiode
sebelumnya juga menjadi sebagai Wali kota Tangerang Selatan. Adik Atut,
Tatu Chasanah memenangkan Pilkada Kabupaten Serang dan terpilih menjadi
Bupati Kabupaten Serang periode 2015-2020. Menantu Atut Chosiyah, Tanto
Warsono Arban terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang periode
2015-2020. Dan pada pilkada serentak 2017 kemarin, Andhika Hazrumy yang
merupakan anak dari Atut terpilih menjadi Wakil Gubernur Banten periode
2017-2022 dengan memperoleh 50,95% suara (Detik. 2014.
https://news.detik.com/berita/d-3432971/wahidin-andika-unggul-atas-rano-embay-ini-peta-perolehan-suaranya sumber diakses 24 desember 2017).
Selain kental dengan budaya politik dinasti, Banten juga menjadi salah
secara langsung atau pun tidak langsung bahwa politik dinasti menjadi lahan
subur untuk melakukan praktik korupsi. Hal ini dikarenakan berkumpulnya
kekuasaan pada segelintir orang. Dan ini terbukti di tahun 2013 silam, Tb.
Chaeri Wardana (Wawan) seorang pengusaha yang juga adik mantan
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
dalam kasus suap pilkada Lebak. Berdasarkan pengembangan penyidikan
KPK juga menetapkan Atut sebagai tersangka dalam kasus suap ini. Tidak
berhenti pada suap pilkada Lebak, KPK terus mengusut dugaan keterlibatan
Wawan dan Atut dalam kasus yang lain. Akhirnya KPK menetapkan Wawan
dan Atut sebagai tersangka pengadaan alat kesehatan Banten. Lebih lanjut
KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang setelah melakukan penelusuran berkoordinasi dengan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketua KPK Abraham Samad pernah menyatakan (Pukat UGM, 2014 :
10) bahwa korupsi di Banten adalah kejahatan keluarga, dan korupsi di
Banten tidak hanya pada pengadaan alat kesehatan saja, tetapi juga pada
proyek-proyek infrastruktur dan bantuan sosial. Kuatnya dinasti Atut di
Banten yang menguasai banyak jabatan publik disinyalir memudahkan
terjadinya korupsi. Pengawasan baik internal pemerintahan maupun
pengawasan eksternal seakan tidak berjalan.
Persoalan lain di Banten adalah sikap pragmatisme masyarakat dalam
praktik berpolitik. Budaya masyarakat di Banten masih sangat kental dengan
disampaikan pada seminar nasional Ilmu Pemerintahan Untirta (November,
2016) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di Banten dalam
menggunakan hak pilihnya sebagian besar tidak berdasarkan kesadaran
politik melainkan didorong oleh adanya politik uang. Artinya, masyarakat
akan datang ke TPS saat hari pencoblosan apabila mereka mendapatkan
sejumlah uang atau barang tertentu dari pasangan calon.
Menurut hasil survei yang disampaikan oleh Hamid dalam seminar
nasional Ilmu Pemerintahan Untirta (2016) sebanyak 71,3 persen publik
menganggap pemberian uang dalam pilkada adalah sebagai hal yang wajar
dan sebanyak 69,4 persen pemberian sejumlah uang dari pasangan calon
kepala daerah akan berpengaruh terhadap pilihan pasangan calon kepala
daerah, sedangkan 45,6 persen, masyarakat menerima pemberian sejumlah
uang atau barang dan akan memilih calon yang memberi sejumlah uang atau
barang tersebut. Hasil dari riset ini menunjukan bahwa efektivitas politik
uang sangat tinggi di Banten. Selain karena pendidikan politik masyarakat
Banten yang masih rendah, keberadaannya malah dimanfaatkan oleh para elit
lokal dengan menggunakan strategi politik demi mencapai suksesi dalam
pilkada.
Melihat kenyataan seperti itu dimana kekuasaan dikendalikan oleh
satu kelompok dominan dan didukung dengan budaya masyarakat yang
pragmatis tidaklah heran jika Banten menjadi salah satu daerah yang rawan
korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Banten termasuk
dan Sumatera Utara (Detik, 2016
https://m.detik.com/news/berita/d-
3356096/banten-termasuk-6-daerah-rawan-korupsi-kini-masuk-radar-kpk-lagi).
Dengan kondisi Banten yang demikian, semangat menuju perubahan
yang lebih baik terus dilakukan. Pilkada berusaha dikendalikan kembali
sebagai ajang pemilihan kepala daerah terbaik yang memiliki integritas dan
kemampuan yang kompeten sebagaimana dengan semangat hadirnya
undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 2004 silam tentang Pemerintahan Daerah, yang
mana pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/ Wali Kota) dilakukan
secara langsung atau dengan kata lain melibatkan partisipasi langsung
masyarakat dalam memilih kepala daerah yang terbaik.
Dan dalam perjalanannya Pilkada melakukan pembaharuan dalam
rangka mencapai tujuan pilkada yang lebih berkualitas yaitu dengan
menerapkan pilkada secara serentak atau biasa di sebut dengan pilkada
serentak yang saat ini menjadi arena baru bagi perpolitikan Indonesia. Bukan
hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan,
prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal, yang oleh
Brian C. Smith dan Robert Dahl, adalah untuk menciptakan local
accountability, political equity dan localresponsiveness (Suara KPU, edisi II
2015: 4).
Pilkada serentak secara nasional baru akan terlaksana pada tahun
2024, karena itu terdapat 3 tahapan transisional pilkada serentak di daerah
transisional tahap I sudah berlangsung pada tahun 2015 lalu di 269 wilayah,
yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Begitu pula pilkada serentak
transisional tahap II sudah berlangsung pada tahun 2017 di 101 wilayah,
yakni 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Sedangkan pilkada serentak
transisional tahap III akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang di 171
wilayah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.
Banten sendiri telah melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2017
kemarin. Pemilihan kepala daerah Banten hanya diikuti oleh dua pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Wahidin Halim yang berpasangan
dengan Andhika Hazrumy diusung oleh partai politik Demokrat, Golongan
Karya, Hati Nurani Rakyat, Partai Kesatuan Bangsa, Partai Amanat Nasional,
Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Rano
Karno berpasangan dengan Embay Mulya Syarief yang diusung oleh partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan
Nasional Demokrat. Andhika Hazrumy sendiri adalah bagian dari keluarga
dinasti yaitu anak dari Ratu Atut.
Sebelumnya, ada empat pasangan calon perseorangan yang
mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPUD
Banten melalui jalur independen. Keempat bakal pasangan calon adalah H.
Yayan Sofyan dan Ratu Enong Mandala, KH. Tb. Sangadilah dan Subadri
Martadinata, R. Achmad Dimyati Natakusumah dan Hj. Yemelia, serta Ampi
Nurkamal Tanudjiwa dan Maryani. Namun dari keempat bakal pasangan
verifikasi administratif yaitu harus mengumpulkan dukungan KTP minimal
berjumlah 601.805 dukungan yang minimal tersebar di lima kabupaten/kota
di Banten (Suara KPU edisi September, 2016). Pada akhirnya, hanya ada dua
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang di usung partai
politik yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah Banten.
Ketika perhelatan Pilkada Banten 2017 kemarin, muncul beberapa
gerakan sosial dari kelompok civil society yang bergerak pada pencerdesan
politik masyarakat Banten. Tentu ini melihat kenyataan situasi politik di
Banten yang menyedihkan dan didukung ruang publik yang saat ini semakin
terbuka ternyata mampu memberi semacam tenaga pendorong baru bagi
menjamurnya gerakan sosial. Diantaranya adalah komunitas Banten Memilih,
Untuk Banten dan Ayo Banten. Komunitas-komunitas tersebut lahir dari
anak-anak muda Banten yang memiliki keprihatinan bersama dengan perilaku
politik masyarakat Banten yang cenderung pragmatis.
Selain itu juga muncul gerakan-gerakan yang menyoroti praktik
korupsi di Banten salah satunya Forum Banten Bersih (FBB) yang memiliki
gerakan berorientasi pada penolakan dinasti politik dan praktik korupsi.
Kemudian, ada pula Gerakan Menolak Politik Dinasti (Gempa) yang juga
memiliki gerakan sama dengan Forum Banten Bersih, keduanya sama-sama
melakukan resistensi kepada korupsi dan resistensi atas kekuasaan dominan
yang dikendalikan oleh dinasti politik Atut atau disebut sebagai rezim
hegemonik yang mana dinasti politik membentuk cara untuk
kekuasaan di wilayah Banten. Ketika ada kekuasaan yang dominan biasanya
ada pertentangan di dalamnya.
Gerakan-gerakan sipil yang terbangun tidak hanya pada saat
momentum Pilkada, banyak juga gerakan yang tidak bersifat momental. Di
Banten sendiri, jumlah Civil Society Organization (CSO) atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) bisa terbilang cukup banyak. Menurut data dari
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten terdapat 1.432 CSO/LSM,
walaupun dari jumlah tersebut hanya 93 yang surat keterangannya masih
terdaftar (Detak Banten, 2015
http://www.detakbanten.com/pandeglang/6688-
wow-1-432-ormas-lsm-banten-hanya-93-ormas-lsm-terdaftar-di-kesbangpol-banten diakses pada 5 Februari 2018). Banyaknya jumlah CSO di tengah
iklim demokratisasi adalah hal wajar, kehadiran civil society tentu merupakan
faktor penting karena kapsitas mereka dalam mendorong peningkatan
kesadaran partisipasi masyarakat yang lebih inklusif.
Salah satu Civil Society Organization di Banten adalah Rumah Dunia
yang bergerak di bidang literasi. Persoalan dinasti politik dan budaya politik
masyarakat Banten yang pragmatis tentu berkaitan dengan budaya literasi.
Karena literasi bukan lagi pada persoalan membaca dan menulis, saat ini
literasi berkenaan dengan praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan
sosial dan politik. Untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat bisa
ditumbuhkan oleh kekuatan literasi. Dengan tradisi literasi yang kuatlah
Pada Pilkada Banten 2017, Rumah Dunia menjadi salah satu bagian
kalangan civil society yang turut terlibat aktif mendukung salah satu pasangan
calon gubernur Banten. Apa yang digelorakannya selama ini tidak lepas dari
penolakan terhadap dinasti Banten Ratu Atut Chasiyah yang dianggap sebagai
akar permasalah korupsi yang menghambat pembangunan di Banten. Hal ini
dibenarkan oleh Presiden Rumah Dunia (2017) mendukung salah satu
pasangan calon yang tidak memiliki ikatan dengan dinasti politik dan
dianggap bersih dari praktik korupsi.
Gambar 1. Salah satu postingan Gol A Gong di Koran Rumah Dunia
(Sumber : Koranrumahdunia.com)
Gol A Gong sebagai pendiri Rumah Dunia tidak jarang mengeluarkan
kritik terhadap dinasti politik. Salah satu postingan di koran rumah dunia
dengan judul “Gol A Gong, Rumah Dunia dan Politik” salah satu kalimat
tahun Banten di era Atut, Ibu Andika, terpuruk oleh prilaku KKN para
pemimpinnya (Koran rumah Dunia. 2016. www.koranrumahdunia.com
diakses pada 17 November 2017). Terdapat juga tulisan-tulisan kritik Gol A
Gong lainnya yang diarahkan pada salah satu pasangan calon Gubernur
Banten.
Rumah Dunia sebagai kelompok civil society. memiliki otonomi baik
terhadap pengaruh dan intervensi negara maupun lembaga-lembaga bisnis
atau masyarakat ekonomi. Secara sederhana otonomi mengandung makna
kemandirian sekaligus kebebasan. Otonomi dalam pengertian politik adalah
tingkat kebebasan tertentu yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau
kelompok tertentu yang dilakukan oleh pihak lain.
Rumah Dunia sendiri merupakan pendidikan masyarakat non formal
yang berkutat di bidang sastra, jurnalistik, teater, musik dan menggambar.
Visinya adalah mencerdaskan dan membentuk generasi baru yang kritis di
Banten. Misi untuk menjalankan visi tersebut adalah dengan mengadakan
diskusi terhadap isu sosial, budaya, politik dan sebagainya, mengadakan
bedah buku, menerbitkan buku, menyelenggarakan pelatihan kepenulisan dan
jurnalistik, melakukan pertunjukan seni dan berbagai kegiatan lainnya (Koran
Rumah Dunia. 2014 koranrumahdunia.com diakses pada 17 November 2017).
Dari awal didirikan sampai sekarang, Rumah Dunia konsen pada
gerakan moral dan kebudayaan. Rumah Dunia bukan saja untuk tempat
membaca buku, belajar menulis, teater tetapi mempunyai suatu gerakan yang
Dunia kerap hadir paling terdepan jika dihadapkan masalah sosial salah
satunya adalah pada persoalan korupsi. Seperti yang diutarakan oleh presiden
Rumah Dunia Ahmad Wayang (wawancara, 2017), bahwasanya Rumah
Dunia menolak keras praktik-praktik korupsi di Banten. Hal ini dapat dilihat
dengan kerja sama yang dilakukan oleh Rumah Dunia dengan lembaga anti
korupsi negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga
Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merupakan organisasi
non-pemerintah yang bergerak di bidang korupsi.
Dan pada musim perhelatan Pilkada Banten berlangsung, bersama
dengan ICW, Rumah Dunia juga menggelar acara bedah buku karya peneliti
rekan-rekan ICW dengan judul buku “Dinasti Banten”. Dalam diskusi itu
beranggapan pemberantasan korupsi akan lebih mudah terwujud ketika
dibarengi dengan upaya meruntuhkan legitimasi politik dan kekuasaan
kelompok dinasti Atut di pemerintahan (Berita Cilegon, 2016. Diakses pada
www.beritacilegon.co.id/dinasti-banten-akan-dikuliti-di-rumah-dunia-sabtu-3-september-2016-2 diakses pada 4 Juni 2017). Diskusi-disksusi semacam ini
yang berlangsung di musim Pilkada tentunya membuat keberpihakan politik
Rumah Dunia menjadi sangat kentara.
Tulisan ini bermaksud menjelaskan bagaimana Partisipasi Politik
Rumah Dunia pada perhelatan pemilihan gubernur Banten 2017. Diketahui,
salah satu dari kedua pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Banten
adalah berasal dari keluarga dinasti politik Banten yaitu Andika Hazrumy
Dunia sebagai gerakan yang menentang keras keberadaan dinasti politik di
Banten, menjadi menarik untuk didalami lebih mendalam mengenai
partisipasi politiknya sebagai civil society yang cukup berpengaruh di Banten
dalam pilgub Banten 2017. Terlebih Rumah Dunia adalah komunitas yang
bergerak di bidang literasi menjadi menarik pula ketika ikut terlibat
mendukung salah satu pasangan calon.
B. Identifikasi Masalah
1. Dunia politik Banten di dominasi oleh dinasti politik
2. Tingkat korupsi yang tinggi di Banten
3. Budaya pragmatis (money politic) yang tinggi di masyarakat Banten
4. Rumah dunia yang selama ini bergerak di bidang literasi kemudian
mendukung salah satu pasangan calon gubernur Banten 2017
C. Rumusan Masalah
Bagaimana Partisipasi Politik Rumah Dunia dalam Pemilihan Gubernur
Banten 2017?
D. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui partisipasi politik Rumah Dunia dalam pemilihan
E. Kegunaan Penelitian 1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian tentang
keterlibatan civil society dalam pilkada Banten 2017.
b. Pengkajian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru
dalam melihat peran Rumah Dunia dalam pelaksanaan sebuah
sistem Pilkada.
c. Merangsang terhadap adanya pengembangan penelitian-penelitian
politik lainnya dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti
1) Untuk mengetahui tentang posisi Rumah Dunia dalam
kontestasi pilkada Banten 2017
2) Untuk memenuhi tugas mata kuliah skripsi pada jenjang
perkuliahan semester 8 Program Studi Ilmu Pemerintahan.
b. Bagi LSM/CSO
1) Pengkajian ini diupayakan dapat digunakan sebagai acuan
LSM/CSO dalam menjalankan perannya dalam sebuah
sistem politik.
2) pengkajian ini dapat dijadikan referensi oleh LSM/CSO
c. Bagi Masyarakat
1) Untuk dapat mengetahui posisi LSM dalam keterlibatannya
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teoritis 1. Partisipasi Politik
Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi.
Karena demokrasi bersifat inklusif dari campur tangan warga negaranya.
Demokrasi memberikan ruang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk
terlibat aktif dalam setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan.
Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling
tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena
keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut
dan mempengaruhi kehidupan warganegara maka warga masyarakat berhak
ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam
keikutsertaan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik.
Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan
capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik
negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa
inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan.
Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan
politik negara (Suharno, 2004:102-103).
Hunington dan Nelson (1984: 3) berpendapat partisipasi politik adalah
kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk
mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi itu dapat
secara perseorangan atau kolektif, terorganisasi atau secara spontan, secara
sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau
illegal, efektif atau tidak efektif.
Sedangkan menurut Miriam Budiarjo (2013: 367) menyatakan bahwa
partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan
politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini
mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,
mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok
kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah
atau anggota perlemen, dan sebagainya.
Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi
adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam menyampaikan saran
atau pendapat untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
agar terjadi suatu perubahan kearah yang lebih baik. Rumah Dunia sebagai
komunitas menjadi kelompok yang berpartisipasi dalam politik karena
partisipasi politik bukan hanya menyasar pada perseorangan namun bisa
Kemudian bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui
berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun
bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan
menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional,
sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik
individu atau kelompok menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk non konvensional.
1. Bentuk konvensional
a. Dengan pemberian suara (voting)
b. Dengan diskusi kelompok
c. Dengan kegiatan kampanye
d. Dengan membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan
e. Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik atau
administratif
f. Dengan pengajuan petisi
2. Bentuk nonkonvensional antara lain:
a. Kegiatan Pemilihan, mencakup memberikan suara, akan tetapi juga
sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu
pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan
yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
b. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan
politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang
c. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi,
baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi
pengambilan keputusan oleh pemerintah.
d. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun
jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi
keputusan mereka, dan
e. Tindakan Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau
kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara
menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini
adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination),
revolusi dan pemberontakan.
2. Masyarakat Sipil (Civil Society) a. Konsep Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang
terbuka, egaliter, bebas dari dominasi, dan tekanan negara. Masyarakat sipil
merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi.
Posisi penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi adalah
adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan
yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.
Masyarakat sipil mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara
(civic engagement) melalui asosiasi-asosiasi sosial yang didirikan secara
terbuka, percaya, dan toleran antar-individu dan kelompok yang berbeda.
Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik Indonesia.
Sebagai sebuah wacana, civil society adalah produk sejarah dari
masyarakat Barat modern. Kemunculannya berbarengan dengan proses
modernisasi, terutama terjadi pada saat proses transformasi dari pola
kehidupan yang masih berbentuk feodal menuju masyarakat industrial
kapitalis. Adam Ferguson adalah yang pertama kali mengemukakan
mengenai civil society dalam konteks Eropa Barat pada abad ke-18 yang
berkaitan dengan tumbuhnya sistem ekonomi pasar (Hikam, 1996: 224).
Kemudian J.J. Rosseau dan John Locke, adalah tokoh-tokoh yang
memberikan landasan filosofis bagi sistem politik yang memberi
penghargaan pada kedaulatan individu, emansipatoris dan persaudaraan
manusia.
Selanjutnya konsep civil society tersebut banyak mengalami pola
pemaknaan, sejalan dengan perubahan sosio-historis tempat gagasan itu
dirumuskan. Dalam sejumlah literatur mengenai konsep civil society,
terdapat lima corak pemikiran yang mewarnai sejarah Barat.
Pertama, civil society di pahami sebagai sistem ketatanegaraan.
Dalam hal ini, civil society identik dengan negara. Pemahaman tersebut di
kembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero
(106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).
Hanya saja, Aristoteles tidak menggunakan istilah civil society, melainkan
terlibat langsung dalam pengambilan keputusan baik itu dalam bidang
ekonomi maupun politik. Cicero pun berbeda dengan Aristoteles, ia
menamakannya dengan societas civilis, yaitu sebuah komunitas yang
mendominasi sejumlah komunitas lain. Sedangkan Thomas Hobbes dan
John locke memaknainya sebagai tahapan lebih lanjut dari natural society,
sehingga civil society sama dengan negara (Rahmat, 2003).
Kedua, dengan mengambil konteks sosial-politik Skotlandia,
Adam Ferguson (1767 ) memberi tekanan terhadap makna civil society
sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menggunakan
pemahaman ini untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan
oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Menurut Ferguson,
munculnya ekonomi pasar bisa melunturkan tanggung jawab publik dari
warga karena dorongan pemuasan kepentingan pribadi. Civil society
disini, lebih dipahami sebagai entitas yang sarat dengan visi etis berupa
rasa solider dan kasih sayang antar sesama, dan ini kebalikan dari
masyarakat primitf atau masyarakat barbar.
Ketiga, dalam pemaknaan Thomas Paine (1792), civil society
merupakan antitesis negara atau cenderung dalam posisi yang berhadapan
dengan negara. Keempat, yang menjadi tokoh pemikirnya antara lain
Hegel, Marx dan Gramsci. Dalam hal ini, Hegel mengembangkan civil
society yang subordinat terhadap negara. Hal ini didasari karena civil
society sangat kuat hubungannya dengan fenomena masyarakat borjuis
dari dominasi negara (Rasyid, 1997: 4). Pandangan civil society yang
pesimis ini juga dikembangkan Karl Marx (1818-1883). Marx
memahaminya sebagai masyarakat borjuis dalam hubungan produksi
kapitalis keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia
dan penindasan. Karena itu, ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan
masyarakat tanpa kelas.
Sedangkan Antonio Gramsci, meski penganut Marx tetapi tidak
memahami civil society dari relasi produksi, tetapi lebih pada sisi
ideologis. Bila marx menempatkan civil society pada basis material,
Gramsci menaruhnya pada suprastruktur, berhadapan dengan negara yang
ia sebut sebagai political society. Civil society adalah adalah sebuah arena
tempat para intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya adalah
upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara.
Akhir dari semua proses itu adalah terserapnya negara dalam civil
society, sehingga terbentuklah apa yang disebut masyarakat teratur
(regulated society) (Syazili & Burhanudin, 2003: 12-13). Dengan
demikian, bila Hegel dan Marx cenderung pesimis dengan kemandirian
civil society maka Gramsci lebih optimis dan dinamis.
Kelima, berdasarkan pengalaman demokrasi di Amerika, Alexis
De‟ Tocqueville mengembangkan teori civil society yang dimaknai
sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Di Amerika pada awal
pembentukannya, demokrasi dijalankan lewat civil society, berupa
professional, yang membuat keputusan pada tingkat lokal dan
menghindari intervensi negara (Rahmat, 2003).
Michael W. Foley dan Bob Edwards (1996) menganalisis civil
society menjadi dua versi yaitu civil society dalam pengertian menekankan
kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai keadaban (civility) bagi
kelompok-kelompok maupun dalam kehidupan warga negara atau
masyarakat secara umum. Pengertian ini selanjutnya disebut civil society I
(CS I). Sedangkan yang kedua dalam pengertian sebagai suatu ruang bagi
tindakan yang independen dari negara dan mampu melakukan perlawanan
terhadap rezim yang tiran. Yang kedua ini selanjutnya disebut sebagai civil
society II (CS II).
Dalam wacana civil society di Indonesia, CS I lebih menekankan
aspek horizontal dan kultural, serta berkait erat dengan civility atau
keberadaban, fratemity dan equality. Sedangkan civil society II atau CS II
memfokuskan aspek vertikal dengan mengutamakan otonomi masyarakat
terhadap negara dan erat dengan aspek politik. Istilah civil dekat dengan
“citizen” dan “liberty”.
Jika civil society dalam pengertian kelompok disebut dengan civil
societyorganization atau CSO dan yang dalam pengertian nilai-nilai dengan
civil society value atau CSV, maka akan didapati formula analisis
sebagaimana yang terlihat dalam matriks tabel 1, sebagai berikut (Rahmat,
1) Civil society organization I (CSO I), yaitu kelompok-kelompok dalam
masyarakat yang berada diwilayah kultural atau memperjuangkan
nilai-nilai kultural (CSV I) dan dilakukan secara horizontal, meliputi:
ormas, orsos, organisasi keagamaan, LSM, KSM, asosisasi
professional.
2) Civil society organization II (CSO II), yaitu kelompok-kelompok
dalam masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai yang berdimensi
politik (CSV II) atau secara vertikal, meliputi: parpol oposisi, LSM
advokasi, kelompok penekan, gerakan buruh, kelompok kepentingan.
Meskipun, tidak semua atau tidak selamanya CSO II
memperjuangkan CSV II, misalnya kelompok kepentingan.
3) Civil society value I (CSV II), yaitu nilai-nilai dalam masyarakat
secara umum ataupun dalam kelompok-kelompok civil society secara
khsus yang berdimensi kultral, meliputi: toleransi, egalitarianisme,
solidaritas, kemandirian, kepatuhan masyarakat pada norma dan
hukum.
4) Civil society value II (CSV II), yaitu nilai-nilai dalam masyarakat
secara umum maupun dalam kelompok-kelompok civil society secara
khusus yang berdimensi politik, meliputi: kemandirian, kebebasan,
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan
Tabel 1. Formula Analisis CSO
CS CSO CSV
I Ormas, Orsos, Org. Keagamaan,
Lsm Community Development
(Cd), Ksm, Asosiasi Profesional
Toleransi, Egalitarianisme,
Solidarotas, Mandiri, Patuh Pada
Norma Dan Hukum
II Parpol Oposisi, Lsm Advokasi,
Kelompok Penekan, Gerakan
Buruh, Kelompok Kepentingan
Mandiri, Kebebasan, Partisipasi,
Supremasi Hukum
(Sumber: Rahmat, 2003)
b. Tinjauan Tentang Civil Society Organization
Menurut Gramsci (Anaida, 2016: 17-19) civil society adalah
masyarakat yang memiliki privasi, otonom serta terlepas dari proses
produksi, yaitu semua organisasi yang membentuk masyarakat sipil dalam
sebuah jaringan kerja dari praktek praktek dan hubungan sosial yang
kompleks, termasuk buruh dan pemodal. Dalam masyarakat sipil semua
kepentingan dari semua kelompok muncul harus dibedakan antara
masyarakat sipil dengan aparat pembentuk negara karena mereka
mempunyai monopoli dan bersifat koersif yang disebut masyarakat politik.
Masyarakat sipil dalam komunitasnya, terjadi proses hegemoni antar
kelompok didalamnya karena terdapat kompleksitas hubungan sosial.
dilakukan oleh masyarakat politik. Masyarakat politik oleh Gramsci bukan
dalam pengertian negara, koersif dan aparat negara.
Menurut Gramsci, “supremasi sebuah kelompok sosial terwujud
dalam dua cara sebagai „dominasi‟ dan sebagai „kepentingan intelektual dan
moral‟ atau „hegemoni‟. Sebuah kelompok sosial itu dominan atas
kelompok-kelompok yang dipimpinnya jika ia memiliki pengaruh yang
mendorong munculnya persetujuan dari kelompok-kelompok tersebut
hingga mereka memberikan dukungan sukarela. Civil society merupakan
lokus hegemoni. Ia juga merupakan arena untuk membangun dan merebut
hegemoni.
Proses pembangunan hegemoni atau hegemonisasi adalah gerakan
dari kepentingan korporat-ekonomis partikular atau kepentingan kelas
tertentu kedalam kepentingan universal umum; atau dari kehendak khusus
ke kehendak umum. Dalam proses ini terjadilah pembentukan aliansi yang
dilandaskan pada kepemimpinan moral dan intelektual. Kelompok yang
memimpin harus membangun kepentingan dan nilai yang cukup umum dan
luas untuk menarik dukungan kelompok-kelompok lain. Jadi, pembangkitan
dan pembentukan consent mengandaikan kesebangunan kepentingan
ekonomis dan formulasi serta cara hidup dan pandangan dunia ke
masyarakat. Dengan begitu, civil society memiliki posisi sentral dalam
pemikiran Gramsci. Dalam civil society-lah terletak momen sosial-kultural
Menurut Larry Diamond (2003), civil society diarahkan kepada
kehidupan sosial yang terorganisasi dengan mengusung sifat-sifat
keterbukaan, sukarela dan lahir secara mandiri, otonom dari negara dan
terkait dalam tatanan nilai bersama. Civil society dapat dimengerti sebagai
keterlibatan warga negara yang bertindak secara kolektif dalam ruang publik
guna mencapai tujuan berpartsama. Civil society merupakan fenomena
penengah yang berada di wilayah privat dan negara, civil society bukan
ranah kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok internal, bukan pula sebuah
medan kegiatan ataupun usaha untuk memperoleh keuntungan dari suatu
kegiatan perusahaan milik perseorangan.
Civil society menurut Diamond (2003) “tidak sama dengan
masyarakat parokial, (sebuah bentuk kehidupan individu, keluarga dan
kegiatan kelompok internal) misalkan saja lembaga keagamaan dan
organisasi pertemanan”. Namun organisasi seperti ini bisa saja menjadi
bagian dari civil society, jika melibatkan diri dalam upaya mengentaskan
kemiskinan, mencegah kejahatan dan berusaha meningkatkan sumber daya
manusia. Selain itu, civil society juga berbeda dengan organisasi politik. Hal
ini terjadi karena dalam prakteknya organisasi politik hanya untuk
memperoleh kekuasaan.
Berdasarkan pemikiran Diamond tersebut, yang mengemukakan
tentang definisi civil society, nampaknya cocok untuk melihat Rumah Dunia
sebagai komunitas atau CSO di Banten. Organisasi tersebut berkiprah
ditunjukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu kehidupan sosial
di Provinsi Banten. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diambil sebuah
kesimpulan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bagian
dari masyarakat sipil. Komunitas sipil adalah sebuah kelompok sosial dari
beberapa individu memiliki ketertarikan yang sama terhadap salah satu
bidang yang mana anggotanya berasal dari warga masyarakat.
Berdasarkan pendapat tersebut, semakin menguatkan bahwa
organisasi kemsyarakatan merupakan bagian dari komunitas sipil. Lebih
lanjut Diamond (2003) juga melakukan analisis terhadap fungsi efektif
masyarakat sipil, yaitu dapat membawa rakyat secara bersama-sama dalam
kebersamaan yang tidak ada habisnya untuk tujuan-tujuan yang sangat
bervariasi. Pada konteks ini masyarakat sipil tidak saja mengarahkan
anggotanya untuk memperbanyak tuntutan kepada negara. Tetapi juga, akan
mengingatkan kemampuan kelompok untuk memperbaiki kesejahteraannya
sendiri, tanpa harus bergantung kepada negara khususnya pada tingkat lokal.
Fungsi lain dari civil society adalah sebagai arena merekrut dan
melatih pimpinan baru. Sebagai pelatihan kepemimpinan politik baru itu
terselenggara melalui “on the job training” belajar sambil bekerja. Seorang
warga masyarakat yang memahami bagaimana metode secara efektif dalam
mengorganisir tetanganya, rekan-rekan kerjanya, mengelola keuangan
organisasi secara bertanggung jawab, atau bagaimana cara menyelesaikan
konflik dan membawa teman-temannya yang tidak sepaham ke dalam suatu
keterampilan yang sangat diperlukan agar mampu secara efektif juga dalam
menangani urusan urusan Negara (Anida, 2016: 16-21).
Adapun tiga konsep CSO sebagai gerakan masyarakat sipil adalah
(Culla, 2006: 31) :
Pertama, peran CSO sebagai kekuatan pengimbang
(countervailing power) dalam mengontrol, mencegah, dan membendung
dominasi serta manipulasi negara maupun dunia usaha (masyarakat
ekonomi) terhadap masyarakat. Peran kritis, politis, konfliktual, dan
transformatif ini biasanya dimainkan melalui advokasi kebijakan, lobi,
pernyataan politik, petisi, protes, dan aksi unjuk rasa di tingkat nasional,
bahkan internasional.
Kedua, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Peran ini
dijalankan melalui aksi pengembangan kapasitas kelembagaan,
produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat,
termasuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun
keswadayaan, menjaga kemandirian, menggalang partisipasi, dan
memperkuat hak-hak warga negara. Peran ini diakualisasikan lewat jalur
pendidikan, pelatihan, pengorganisasian, pengerahan, dan penjelajahan
metodologi alternative yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Ketiga, peran sebagai lembaga perantara (intermediary institusion)
yang memautkan hubungan antara masyarakat dan pemeritah atau negara
maupun dengan aktor-aktor negara seperti dunia usaha dan lembaga
masyarakat dengan CSO, antar CSO sendiri, serta jejaring kerja sama
antar kelompok masyarakat.
Tiga peran tersebut secara teoritis tampil serentak dalam aksi CSO.
Namun demikian, penerapannya tergantung CSO bersangkutan karena
kasus yang ditangani dan dihadapi mungkin saja akan lebih
memprioritaskan satu peran ketimbang peran lainnya. Artinya, memilih
dan menekankan salah satu peran tidak serta merta menafikan peran
lainnya. Bagaimanapun juga, tidak perlu terlalu dipersoalkan peran apa
yang dipilih dan dimainkan CSO bersangkutan mengingat variasi dalam
aksi-aksi CSO di lapangan.
c. Tipologi Paradigma Civil Society Organization
Mansour Fakih (dalam Culla, 2006: 77-79) mencoba
mengkontruksikan tipologi paradigma CSO berdasarkan paradigma
perubahan sosial yang dikembangkan oleh Anne Hope dan Saily Himmel.
Fakih menderivasikannya dari pandangan aktivis CSO tentang bagaimana
mereka mendefinisikan masalah-masalah rakyat dan implikasi definisi ini
bagi program-program aksi CSO. Posisi politis CSO Indonesia, menurut
Mansour Fakih dapat di golongkan menjadi tipologi tiga lipatan:
1) Tipe Konformis
Tipe ini bisa dilihat pada aktivitas CSO yang bekerja berdasarkan
mereka yang membutuhkan. Mereka berorientasi proyek dan bekerja
sebagai organisasi yang menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur
yang ada. Visi mereka di lapangan mengikuti perspektif reformis, yakni
pengembangan masyarakat yang bersifat partisifatif.
2) Tipe Reformis.
Pemikiran CSO yang masuk dalam kategori ini didasarkan pada
“ideologi” modernisasi dan developmentalisme. Perlunya meningkatkan
“partisipasi” rakyat dalam pembangunan adalah tema utama paradigma itu.
Tesis pokok paradigma tersebut adalah bahwa keterbelakangan mayoritas
rakyat disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dengan mentalitas,
perilaku dan kultur rakyat. Mentalitas dan nilai-nilai terbelakag dianggap
sebagai penyebab utama kelemahan “partisipasi” rakyat dalam
pembangunan. Oleh karena rakyat dianggap sebagai bagian dari masalah,
maka tugas CSO adalah menjadi fasilitator, yakni memfasilitasi rakyat
dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar menjadi
lebih modern sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ditingkat
aksi untuk mencapai tujuan itu, hal terpenting adalah berjuang
mempengaruhi pemeritah agar pendekatan dan metodologi yang
ditawarkan akan dipakai dan diimplementasikan pemerintah. Walaupun
dalam banyak hal berbeda kepentingan dengan pemerintah, CSO tipe
dikembangkan oleh kedua tipe itu lebih kepada jalur perubahan bersifat
struktural-fungsional.
3) Tipe Transformatif
Salah satu ciri tipe tranformatif adalah mempertanyakan paradigma
mainstream serta ideologi yang tersembunyi di dalamnya. Tipe ini
berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur
dan suprastruktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi
rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiannya. Paradigma alternatif
yang ditemukan harus mendorong kearah terciptanya suprastuktur dan
sturuktur yang memungkinkan rakyat mengontrol cara produksi, produk
informasi, dan ideologi mereka sendiri. Menurut perspektif ini, salah satu
penyebab masalah rakyat adalah karena berkembangnya diskursus
pembangunan dan struktur yang timpang dalam sistem yang ada. Metode
dan program aksi CSO tipe itu melihat bahwa program-program
pembangunan adalah titik masuk untuk berbagi kegiatan jangka panjang
seperti mengorganisasi dan mengadvokasi masyarakat, melalui kampanye,
publikasi, serta penelitian guna mendukung kaum tani, buruh dan
kelompok-kelompok marjinal lainnya untuk perubahan. Mereka yang
menggunakan pendekatan tranformatif ini juga mendasarkan kegiatan pada
metodologi transformatif, yaitu proses pendidikan untuk memunculkan
Rakyat harus memiliki kontrol atas sejarah dan pengetahuan mereka
sendiri. Corak perubahan sosial paradigm tersebut kritikal dan struktural.
3. Gerakan Sosial
Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang lahir
dari dan atas upaya masyarakat pemerintah dalam usahanya menuntut
perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur. Di sini terlihat tuntutan
perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan
konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu.
Gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak
diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak
adil. Gerakan sosial dapat dipahami sebagai tantangan terhadapat pembuatan
keputusan-keputusan dalam upaya melakukan perubahan sosial tertentu.
Meskipun gerakan sosial sering digerakkan oleh satu atau berbagai organisasi,
banyak penekanan bahwa gerakan sosial sebaiknya tidak diidentifikasi hanya
pada organisasi-organisasi tersebut. Tindakan individu, kelompok dan kegiatan
para pemimpin yang membentuk opini dan unsur-unsur lain kebudayaan, juga
dapat disebut sebagai elemen gerakan sosial.
Dalam argumentasi Charles Tilly (1978), ia menghubungkan antara
munculnya gerakan-gerakan sosial menuju “proses politik” yang lebih luas,
mengeksklusi kepentingan-kepentingan dengan mencoba untuk mendapatkan
akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan (established polity).
mobilisasi pada hal-hal tertentu dalam arena politik. Ini misalnya bisa dilihat
dalam gerakan sosial yang mengangkat isu keagamaan, atau etnisistas.
Aktivitasnya secara luas dibangun dalam “wilayah gerakan”, yakni “jaringan
kerja kelompok-kelompok dan individu-individu yang memiliki kesamaan
dalam konfliktual secara kultural dan identitas kolektif”.
a. Tinjauan Gerakan Sosial Laclau dan Mouffe
Menurut Laclau dan Mouffe suatu gerakan sosial haruslah mampu
membangun sebuah revolusi demokratik yang bersifat populis, yang dapat
mengakomodasi tuntutan berbagai macam kelompok-kelompok, seperti:
kaum urban, kaum ekologis, otoriterian, institusional,
anti-kapitalisme, feminis, anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan regional, gerakan
kaum minoritas dan juga gerakan kaum minoritas secara seksual (kaum
lesbian dan homoseksual).
Laclau dan Mouffe melihat gerakan sosial dalam konteks hubungan
antagonistik dalam masyarakat. Dalam argumentasi Chantal Mouffe,
setidaknya ada empat posisi teoritik dalam melihat hubungan agen dan
gerakan sosial.
Pertama, dalam setiap masyarakat, setiap agen sosial adalah lokus
bagi multiplisitas dari relasi-relasi sosial – bukan hanya relasi sosial
produksi, tetapi juga relasi-relasi sosial seperti sex, ras, nasionalitas dan
lingkungan (mis. neighborhood). Semua hubungan-hubungan sosial ini yang
karena itu setiap agen sosial merupakan lokus dari sejumlah posisi subyek,
dan tidak dapat direduksi hanya kepada satu posisi. Contohnya, seorang
buruh yang ada dalam hubungan produksi, adalah juga laki-laki atau
perempuan, berwarna kulit putih atau kulit hitam, beragama Islam, Katolik
atau Protestan, bersuku sunda atau jawa, dan seterusnya. Subyektivitas
seseorang bukanlah konstruksi yang hanya berdasarkan pada hubungan
produksi. Terlebih daripada itu, setiap posisi sosial, setiap posisi subyek,
masing-masing di dalamnya merupakan lokus dari kemungkinan berbagai
konstruksi, sesuai dengan perbedaan discourse yang dapat mengkonstruksi
posisi tersebut.
Kedua, menolak pandangan ekonomi mengenai evolusi sosial yang
diatur oleh satu logika ekonomi, pandangan yang memahami bahwa
kesatuan dari formasi sosial sebagai suatu hasil dari “necessary effects”
yang diproduksi dalam supertsruktur politik dan ideologi oleh infrastruktur
ekonomi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa ekonomi dapat berjalan atas
logikanya sendiri, dan mengikuti logika tersebut. Logika yang secara
absolut independen dari hubungan-hubungan yang akan dilihat determinan.
Lain dari itu, Mouffe mengajukan konsepsi bahwa masyarakat sebagai suatu
perangkat yang kompleks terdiri dari hubungan-hubungan sosial yang
heterogen dan memiliki dinamikanya sendiri. Kesatuan suatu formasi sosial
merupakan produk dari artikulasi-artikulasi politik, yang mana, pada
gilirannya kemudian, merupakan hasil dari praktek-praktek sosial yang
Ketiga, “formasi hegemonik” adalah seperangkat format-format
sosial yang stabil. Formasi hegemonik merupakan materialisasi dari suatu
artikulasi sosial, di mana hubungan-hubungan sosial yang berbeda bereaksi
secara timbal-balik. Baik masing-masing saling menyediakan
kondisi-kondisi eksistensi secara mutual, atau juga setidaknya menetralisir potensi
dari efek-efek destruktif dari suatu hubungan-hubungan sosial dalam
reproduksi dari hubungan-hubungan lain yang sejenis. Suatu formasi
hegemonik selalu berpusat di antara hubungan-hubungan sosial tertentu.
Dalam kapitalisme, misalnya, adanya hubungan produksi – yang tidak mesti
dijelaskan sebagai akibat dari struktur – di mana sentralitas dari
hubungan-hubungan produksi sudah di berikan kepada kebijakan hegemonik.
Meskipun demikian, hegemoni tidak akan pernah mapan. Terlebih,
perkembangan kapitalisme merupakan subyek dari perjuangan politik yang
terus-menerus, yang secara periodik memodifikasi format-format sosial
tersebut, melalui hubungan-hubungan sosial produksi yang memberikan
garansi bagi sentralitas perjuangan tersebut.
Keempat, semua hubungan-hubungan sosial dapat menjadi lokus
antagonisme, sejauh hubungan-hubungan tersebut dikonstruksi sebagai
hubungan-hubungan subordinasi. Banyak format-format subordinasi yang
berbeda dapat menjadi asal-mula konflik dan juga perjuangan. Hal ini dapat
ditemukan dalam masyarakat sebagai potensi multiplisitas antagonisme, dan
anatagonisme kelas hanyalah satu dari sekian banyak. Tidaklah mungkin
satu ekspresi logika tunggal yang ditempatkan pada ekonomi. Reduksifikasi
ini tidak dapat juga di diabaikan dengan memposisikan sebuah mediasi
kompleks antara antagonisme-antagonisme sosial dengan ekonomi. Ada
banyak bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat yang tidak dapat
direduksi atau dideduksi dari satu asal-muasal atau satu sumber saja.
Dalam pandangan ini, agen-agen baru dalam konsepsi gerakan
sosial bukanlah sebagai pengganti dari buruh sebagai agen dalam konsepsi
gerakan sosial lama, melainkan buruh sebagai agen gerakan sosial bukanlah
satu-satunya, melainkan salah satu dari yang lainnya. Empat posisi teoritis
ini yang dijadikan dasar untuk melihat pemikiran Laclau dan Mouffe
mengenai gerakan sosial (Hutagalung, 2006).
b. Hegemoni dan Antagonisme dalam Gerakan Sosial Laclau & Mouffe Laclau dan Mouffe mendasarkan analisis politik mereka pada teori
hegemoni Gramsci. Namun, mereka menambahkan dimensi-dimensi lain
dari pemikiran Gramsci tersebut. Berbeda dengan Gramsci, Laclau dan
Mouffe tidak lagi memfokuskan kelas buruh sebagai agen dari praktek
hegemoni. Mereka mengajukan tesis mengenai agen sosial baru, yang bisa
mengisi ruang kosong dalam gerakan sosial, ketika gerakan buruh melemah,
dan menjadi kekuatan yang tidak strategis dalam gerakan sosial di
penghujung abad ke duapuluh.
Gramsci melihat bahwa hegemoni merupakan hasil dari kontestasi
Kuasa hegemoni, dilanjutkan Gramsci, bekerja sempurna ketika satu
kelompok sosial mampu menghadirkan dan menjaga consent dari
keseluruhan komponen masyarakat (Gramsci 1986 dikutip dalam
Hutagalung 2008; Xxv). Kemampuan sebuah kelas/kelompok untuk
melakukan pengorganisiran persetujuan (dari penentang dan pendukung)
inilah yang menjadi roh dari konsepsi Gramsci tentang hegemoni. Proses
penciptaan hegemoni ini berlangsung dalam ranah pertarungan gagasan
dengan melakukan konstruksi tentang ide yang sejatinya bias satu
kepentingan menjadi ide yang diterima oleh semua kepentingan
(Hutagalung 2008 : xxv).
Dalam pandangan Gramsci, hegemoni bukan menjadi
keistimewaan satu pihak (yang berkuasa) semata, namun hegemoni
dimungkinkan muncul dari pihak yang dikuasai. Dengan kata lain,
mekanisme bekerjanya hegemoni berjalan dalam dua aras besar. Hegemoni
bekerja dalam alur top-down (dari atas ke bawah) ketika kelas/kelompok
yang berkuasa melakukan pelanggengan sistem yang sedang dijalankannya.
Serta hegemoni yang bekerja dalam alur bottom-up (dari bawah ke atas)
ketika kelas/kelompok yang tertindas melakukan resistensi terhadap system
yang sedang menekannya (Gramsci dikutip dalam Hutagalung 2008 : xxvii).
Hegemoni dalam alur bottom-up merupakan sebuah counter hegemony
terhadap sistem yang tengah mapan. Konsepsi Gramsci tentang Hegemoni
dilanjutkan oleh Laclau dan Mouffe dengan melakukan modifikasi yang