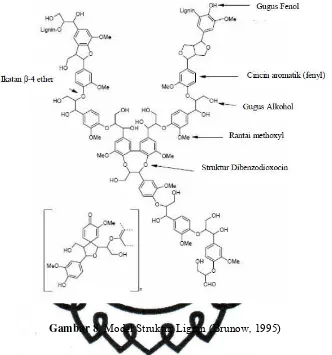commit to user
PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM DAN LIMBAH KAYU AREN
(
Arenga pinnata
) UNTUK MENURUNKAN LOGAM Cr(VI)
PADA LIMBAH CAIR BATIK
TESIS
Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Lingkungan
Disusun oleh:
Dian Kresnadipayana
A130809004
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM DAN LIMBAH KAYU AREN
(Arenga pinnata) UNTUK MENURUNKAN LOGAM Cr(VI)
PADA LIMBAH CAIR BATIK
TESIS
Oleh:
Dian Kresnadipayana A130809004
Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal
Ketua merangkap anggota
Dr. Prabang Setyono, M.Si. NIP. 19720524 199903 1 002
……… …………
Sekretaris merangkap anggota
Inayati, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 19710829 199903 2 001
……… …………
Anggota Penguji Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. NIP. 19600809 198612 1 001
……… …………
Anggota Penguji Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. NIP. 19681124 199403 1 001
……… …………
Telah dipertahankan di depan penguji Dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 20 Februari 2012
Direktur Program Pascasarjana UNS
Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP. 19610717 198601 1 001
Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan
commit to user
iii
PERNYATAAN
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
1. Tesis yang berjudul: “PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM DAN LIMBAH
KAYU AREN (Arenga pinnata) UNTUK MENURUNKAN LOGAM
Cr(VI) PADA LIMBAH CAIR BATIK” ini adalah karya penelitian saya
sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagian acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17 tahun 2010)
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs UNS sebagai institusi. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Ilmu Lingkungan PPs-UNS berhak mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Lingkungan PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.
Surakarta, Februari 2012
Yang membuat pernyataan
commit to user
iv
ABSTRAK
Dian Kresnadipayana. 2012. Pemanfaatan Zeolit Alam dan Limbah Kayu Aren
(Arenga pinnata) untuk Menurunkan Logam Cr(VI) pada Limbah Cair Batik.
TESIS. Pembimbing I: Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D., II: Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pemanfaatan zeolit alam dan limbah kayu aren (Arenga pinnata) telah dilakukan untuk menurunkan logam Cr(VI) pada limbah cair batik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas limbah cair batik dari kandungan logam Cr(VI) dan mengetahui perbandingan antara adsorpsi zeolit alam (ZA), limbah kayu aren (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA) yang telah teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI) pada limbah cair batik.
Zeolit alam diaktivasi secara fisika dengan pemanasan pada suhu 150 oC dan secara kimia dengan HCl 6 M dan NH4NO3 2 M. Limbah kayu aren diaktivasi secara
fisika dengan pemanasan pada suhu 105 oC dan aktivasi secara kimia dengan HNO3
0.6 M dan NaOH 0.1 M. Variasi isian matrik adsorben pada kolom digunakan untuk mengetahui perbandingan besarnya adsorpsi dengan panjang unggun 20 cm. Aplikasi ZA, LKA dan ZA-LKA terhadap larutan K2Cr2O7 80 ppm dilanjutkan aplikasi
terhadap limbah cair batik. Analisis kadar logam Cr(VI) menggunakan metode spektrofotometer serapan atom (SSA).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar logam Cr(VI) pada sampel limbah cair sebesar 14,68 ppm. Satu kali elusi larutan K2Cr2O7 80 ppm pada kolom
adsorpsi ZA, LKA dan ZA-LKA berturut-turut kemampuan adsorpsinya sebesar 99,96 %; 81,40 %; dan 99,83 %. Satu kali elusi sampel limbah cair batik pada kolom adsorpsi ZA, LKA dan ZA-LKA berturut-turut kemampuan adsorpsinya sebesar 99,97 %; 98,39 %; dan 99,39 %. Limbah cair batik setelah perlakuan telah memenuhi kriteria baku mutu air limbah ditinjau dari kandungan logam Cr(VI).
commit to user
v
ABSTRACT
Dian Kresnadipayana. 2012. The Use of Natural Zeolites and Solid Waste of Palm (Arenga pinnata) to Reduce Metal Cr(VI) in Liquid Waste of Batik. THESIS. Concultant I: Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D., II: Dr. Masykuri Mohammad, M.Sc. Postgraduate Program of Environmental Science Study Program of Surakarta Sebelas Maret University.
Natural zeolite and solid waste of palm (Arenga pinnata) have been used to reduce the metal Cr(VI) content in liquid waste of batik manufacturing. The aims of the research were to determine the quality of liquid waste of batik manufacturing in term of from the metal Cr(VI) content and to compare the adsorption using three activated adsorbents, i.e, natural zeolite (ZA), solid waste of palm (LKA) and natural zeolite-solid waste of palm (ZA-LKA) that has been activated in the column system.
The natural zeolite was activated physically by heating it at temperature of 150° C and chemically using 6 M HCl and NH4NO3 2 M. The solid waste of palm
was activated physically by heating it at temperature of 105 °C and was activated of chemical using HNO3 0.6 M and NaOH 0.1 M. Three columns were filled by ZA,
LKA and LKA, respectively each bed was 20 cm height. Solution of 150 mL 80 ppm of K2Cr2O7 was flown to each column. The same experiment was done for liquid
waste of batik manufacturing. Both experiment apllied one time elution. The Cr(VI) content were analyze using atomic absorption spectrophotometer (AAS).
The Cr(VI) content in waste water was 14,68 ppm. The result showed that 99.96%, 81.40% and 99.83% of Cr(VI) in K2Cr2O7 have been removed when using
ZA, LKA, and ZA-LKA. Meanwhile, for waste water sample, percentage of Cr(VI) removed when using ZA, LKA, and ZA-LKA respectively of 99.97%, 98.39% and 99.39 %. This system have been proven to be able to improve the quality of the waste and have been fullfilled the requrement in term of Cr(VI) content.
commit to user
vi
MOTTO
“... dan apabila dikatakan : “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang
commit to user
vii
PERSEMBAHAN :
Karya ini dipersembahkan, Kepada :
•
Alloh dan Rasul-Nya
, semoga karya ini dapat menjadi pemberat
amal kebaikan pada
yaumul mizan
nantinya.
•
Ibu dan Ayah
, yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk
meneruskan perjuangan ini.
•
Bidadariku
, Betty Herawati yang telah memberikan senyuman
manis, canda tawa, doa, dukungan, semangat dan motivasi.
•
Sulungku
, Arkan Dian Husnayan yang telah memberikan
senyuman semangat dan wajah penyejuk cahaya mata.
•
Kakakku
, Yoga Aristo dan Yona Arthea yang telah membantu
penyelesaian tesis ini.
•
Ikhwah fillah
, semoga hati kita senantiasa dipersatukan dalam
ikatan cinta kepada-Nya.
commit to user
viii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,
hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan
lancar.
Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak,
maka dalam kesempatan ini diucapkan banyak terimakasih kepada :
1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret.
2. Dr. Prabang Setyono, selaku Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
3. Dr. Sunarto, M.S. selaku Sekretaris Program Magister Program Studi Ilmu
Lingkungan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
4. Prof. Dr Sri Budiastuti, M.Si selaku Sekretaris Program Doktor Program
Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
5. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah banyak
memberikan arahan dan masukan.
6. Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabar
membimbing dan memberikan motivasi serta mengarahkan pemikiran
penulis.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Lingkungan yang telah memberikan ilmu
commit to user
ix
8. Teman-teman satu perjuangan di Program Studi Ilmu Lingkungan: Habib,
Andhika Bayu, Mas Narno, Pak Yoni, Pak Wahyono, Pak Wondo, Bu
Handayani, Bu Indriati, Pak Gunawan, Pak Edy, Pak Rusdiansjah, Hendrik
Boby, Sylvia Pulot, Sacksy Vilayhak, Pak Haruddin, Mas Budi, dan Pak Arif,
tetap jaga semangat dan kekompakan angkatan 2009. Mas Joni, Dek Mila dan
Dek Dhina yang telah membantu secara administrasi selama ini.
9. Ikhwah fillah: Ustadz Abdul Hakim, S.HI., Ustadz Muhammad Rodhi, S.T.,
Ustadz Sugeng Riyanto, S.Sos., dan teman-teman jebres yang telah
memberikan semangat, doa dan dukungan.
10.Semua pihak yang telah membantu penulis selama penulis menempuh
pendidikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih semua.
Menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dengan
segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan dan penyempurnaan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi
kita semua. Amin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
Surakarta, Februari 2012
Penulis
commit to user
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN... ii
HALAMAN PERNYATAAN ……… iii
ABSTRAK ……….. iv
HALAMAN MOTTO ………. vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ………. vii
KATA PENGANTAR ……… viii
DAFTAR ISI ……….. x
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR... xiv
BAB I. PENDAHULUAN ...
A. Latar Belakang ...
B. Perumusan Masalah ...
C. Tujuan Penelitian ...
D. Manfaat Penelitian ... 1
1
6
7
7
BAB II. LANDASAN TEORI … ...
A. Tinjauan Pustaka...
1. Limbah Cair Batik ...
2. Logam Krom (Cr) ...
3. Pengolahan Air Limbah ... 8
8
8
9
commit to user
xi
4. Zeolit ...
5. Aren (Arenga pinnata)...
6. Komponen Kimia Kayu ...
7. Adsorpsi...
8. Spektrofotometer Serapan Atom ...
B. Penelitian Terkait ...
C. Kerangka Pemikiran ... 14 20 23 29 32 33 35
BAB III. METODE PENELITIAN ...
A. Tempat dan Waktu Penelitian ...
1. Lokasi Penelitian ...
2. Waktu Penelitian ...
B. Peralatan Penelitian ...
1. Alat...
2. Bahan...
C. Prosedur Penelitian ...
1. Survei Pendahuluan ...
2. Persiapan Awal ...
3. Aktivasi Adsorben Zeolit Alam ...
4. Aktivasi Adsorben Limbah Kayu Aren……….
5. Persiapan Seperangkat Alat Adsorpsi Kolom...
6. Aplikasi Adsorben pada Larutan Standard ………..
7. Aplikasi Adsorben pada Limbah Cair Batik ………
commit to user
xii
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ………
A. Limbah Cair Batik ………..
B. Aktivasi Adsorben...
1. Aktivasi Zeolit Alam (ZA) ...
2. Aktivasi Limbah Kayu Aren (LKA) ...
C. Karakterisasi Adsorben ...
1. Karakterisasi Zeolit Alam...
2. Karakterisasi Limbah Kayu Aren ...
D. Aplikasi Adsorben ………...
1. Larutan Standard K2Cr2O7 ...
2. Limbah Cair Batik ………...
E. Dampak Penggunaan Adsorben terhadap Lingkungan ……… 46
46
48
48
53
55
55
58
61
61
66
72
BAB V. PENUTUP ………. 75
DAFTAR PUSTAKA ... 76
commit to user
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Sifat Zeolit Jenis Mordenit ……….. 18
Tabel 2. Karakteristik Limbah Kayu Aren dan Baku Mutu ... 23
Tabel 3. Jadwal Penelitian ………. 36
Tabel 4. Spektra Inframerah dari Zeolit Alam ... 55
Tabel 5. Karakteristik Air Sumur dan Baku Mutu KEP-51/MENLH/10/1995, untuk Golongan B ... 58
Tabel 6. Hasil Aplikasi Adsorben Sistem Kolom pada 150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm………... 54
Tabel 7. Hasil Elusi ke-n pada Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada 150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm ... 63
commit to user
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Diagram Masuknya Krom dalam Tubuh ……….. 11
Gambar 2. Kerangka Utama Zeolit ………. 14
Gambar 3. Skematika Pembetuktan Struktur Zeolit Tiga Dimens ... 15
Gambar 4. (a) Struktur Zeolit Jenis Mordenit Na8 [Al8Si40O96]. 24H2O (b) Struktur Zeolit Jenis Klinoptilolit Na6 [Al6Si30O72]. 24H2O. 19 Gambar 5. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Aren ………. 21
Gambar 6. Selulosa ... 23
Gambar 7. Model Struktur Lignin ………. 27
Gambar 8. Mekanisme Gugus OH pada Selulosa dengan Ion Logam …… 24
Gambar 9. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Penelitian ……….. 35
Gambar 10. Seperangkat Alat Adsorpsi Kolom ……….. 37
Gambar 11. Komposisi Matrik Isian. (a) ZA, (b) LKA dan (c) ZA-LKA… 42 Gambar 12. Kurva Standard dengan Persamaan abs = mC + A ……… 43
Gambar 13. Lokasi Pembuangan Sampel Limbah Cair Batik ……….. 45
Gambar 14. Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Cair Batik ……….. 46
Gambar 15. Zeolit Wonosari Ayakan (-80+100) mesh ……… 47
Gambar 16. Perendaman Zeolit 500 gr dengan 1 L HCl 1 M (1:2) selama 24 jam ……… 48
commit to user
xv
Gambar 18. Pencucian Zeolit dengan Akuades dan Penyaringan ………… 49
Gambar 19. Mekanisme Reaksi Aktivasi Zeolit ... 50
Gambar 20. Limbah Kayu Aren ……… 52
Gambar 21. Impregnasi Basa NaOH Limbah Kayu Aren setelah perlakuan
Asam Nitrat (HNO3) dan Pencucian dengan Akuades Panas
setelah Impregnasi Basa ……… 52
Gambar 22. Mekanisme Reaksi Aktivasi Limbah Kayu Aren
menggunakan HNO3 dan NaOH ... 53
Gambar 23. Spektra FTIR (a) Zeolit Alam dan (b) Zeolit Terdealuminasi... 54
Gambar 24. Difraktogram Sinar X pada Zeolit Alam ... 56
Gambar 25. Difraktogram Sinar X pada Zeolit Alam Dealumunasi ... 56
Gambar 26. Aplikasi Absorben pada 150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm
pada sistem kolom. (a) Kombinasi zeolit alam dan limbah
kayu aren (ZA-LKA), (b) limbah kayu aren (LKA) dan (c)
zeolit alam (ZA) ... 61
Gambar 27. Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada 150 mL Larutan
K2Cr2O7 80 ppm ……… 62
Gambar 28. Hasil Elusi ke-n pada Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada
150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm ... 63
Gambar 29. Perbedaan Warna Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom
Larutan K2Cr2O7 80 ppm... 64
Gambar 30. Aplikasi Absorben pada 150 mL sampel Limbah Cair Batik
commit to user
xvi
Gambar 31. Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada 150 mL sampel
limbah cair batik dengan kadar Cr (VI) 14,68 ppm ... 66
Gambar 32. Mekanisme Adsorpsi Cr(VI) dengan adsorben zeolit alam
(ZA) ... 67
Gambar 33. Mekanisme Adsorpsi Cr(VI) dengan adsorben limbah kayu
aren (LKA) ……… 67
Gambar 34. Perbedaan Warna Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom
commit to user
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Aktivitas kehidupan manusia yang sangat tinggi ternyata telah menimbulkan
bermacam-macam efek yang buruk bagi kehidupan manusia dan tatanan lingkungan
hidupnya. Akibatnya akan terjadi pergeseran keseimbangan dalam tatanan
lingkungan ke bentuk baru yang cenderung lebih buruk. Seiring dengan
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan penggunaan logam-logam berat
terutama dalam industri semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah
pencemaran yang berasal dari limbah industri. Keberadaan logam berat dalam
lingkungan bisa membahayakan berbagai macam spesies hidup dan perlu
dihilangkan (Palar, 2008).
Zat pencemar berupa logam-logam berat merupakan masalah yang lebih serius
dibandingkan dengan polutan organik karena ion-ion logam berat merupakan racun bagi
organisme serta sangat sulit diuraikan secara biologi maupun kimia. Menurut harian
Joglo Semar (24 Nopember 2007), limbah batik mencemari sungai dan air sumur
warga sekitarnya, hal ini terlihat warna merah pada air sumur milik warga, yang
disebabkan karena buangan pabrik batik yang tidak dilengkapi dengan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini sesuai dengan asas lingkungan ke-2 bahwa
tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien.
Limbah cair industri batik cetak tersebut di atas adalah karakteristik berwarna
commit to user
2
warna di dalamnya terdapat kandungan logam berat. Senyawa logam berat yang
bersifat toksis yang terdapat pada buangan industri batik cetak, diduga krom(Cr),
Timbal (Pb), Nikel (Ni), tembaga (Cu), dan mangan (Mn). Sumber logam berat
Krom (Cr) dan Timbal (Pb) yang bersifat toksis, dapat berasal dari zat pewarna
(CrCl3, K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu merupakan pengikat zat warna
meliputi Cr(NO3)2 dan PbCrO4 (Muljadi, 2009).
Kromium adalah salah satu logam yang sering merusak lingkungan.
Pemanfaatan logam krom dan senyawaannya dapat dijumpai dalam industri
elektroplating, penyamakan kulit, dan lain-lain. Cr(VI) merupakan bahan
pengoksidasi kuat, mempunyai potensi karsinogenik, bersifat lebih toksik terhadap
makhluk hidup termasuk manusia dibandingkan dengan Cr(III) (Anderson, 1997).
Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh logam kromium khususnya
Cr(VI) bagi makhluk hidup dan lingkungan, maka keberadaan logam tersebut
sebagai pencemar di lingkungan perlu diminimalkan bahkan dihilangkan. Berkaitan
dengan hal tersebut, berbagai metode telah dikembangkan untuk menurunkan
kandungan logam kromium di lingkungan. Salah satunya adalah metode adsorpsi.
Pada proses adsorpsi terjadi penjerapan molekul-molekul gas atau cairan pada
permukaan sorben.
Peningkatan daya guna atau optimalisasi zeolit sebagai adsorben dapat dilakukan
melalui aktivasi secara fisis maupun kimia. Proses aktivasi secara fisis dilakukan dengan
pemanasan (kalsinasi). Pemanasan ini bertujuan untuk menguapkan air yang
terparangkap dalam pori-pori kristal zeolit sehingga jumlah pori dan luas permukaan
commit to user
dilakukan dengan menggunakan larutan asam klorida atau asam sulfat yang bertujuan
untuk membersihkan permukaan pori, membuang senyawa pengganggu dan menata
kembali letak atom yang dapat dipertukarkan (Suyartono dan Husaini, 1991).
Kemampuan zeolit alam dapat menurunkan kadar logam ion Zn, Cd (Bujnova
dan Lesny, 2006), Mn, Cr, Pb dan As (Campos, 2009). Kemampuan zeolit Jordania
yang telah diaktivasi dengan pemanasan dapat 105 oC menghilangkan logam Hg
dalam air (Salem, 2010). Kemampuan zeolit alam dan vermuculite yang telah
diaktivasi dengan HNO3 sebagai adsorben dalam menghilangkan logam Cu
(Stylianou, 2007). Kemampuan zeolit alam yang telah diaktivasi dengan pemanasan
150 oC selama 60 menit dapat mereduksi kadar logam Cr dalam limbah cair
(Susetyaningsih et al., 2009), menghilangkan Zn2+, Cd2+, Pb2+ dalam air (Minceva et
al., 2007), meremediasi logam beracun Cu, Cr dan Cd (Minato et al., 1999) dan
dapat menurunkan kadar Zn, Cd, Pb, Fe pada air tambang buatan (Wingenfelder et
al., 2005) ,dan Mn pada penyaringan air tanah (Rahman dan Hartono, 2004).
Pemanfaatan zeolit alam digunakan untuk adsorpsi fenol yang diaktivasi dengan HCl
1 N (Swantomo et al., 2009) dan teraktivasi dengan HCl dan NH4NO3
(Mutngimaturrohmah et al., 2009). Pemnfaatan zeolit alam dapat menjerap
logam-logam air kesadahan (Ca dan Mg) yang telah diaktifkan dengan larutan HCl
(Srihapsari, 2006).
Selain zeolit yang merupakan senyawa kimia anorganik sebagai adsorpsi ion
logam, senyawa organik juga dapat sebagai biosorpsi. Limbah cair kayu aren dari
pohon aren (Arenga pinnata) mengandung bahan organik berupa pati atau serat
commit to user
4
organik bergantung pada efisiensi proses pemisahan pati dari air. Pembuatan tepung
aren dilakukan melalui terlebih dahulu menebang batang pohon aren kemudian
dipotong-potong sepanjang 1,25 - 2 meter. Pada industri tradisional, serat tadi
dimasukkan ke bak yang dialiri air serta diaduk-aduk dengan cara menginjak-injak
untuk memisahkan antara ampas aren dan tepungnya. (Firdayati dan Handajani,
2005).
Penggunaan sorben dari bahan organik (biosorben) akhir-akhir ini sangat
banyak dikembangkan. Biosorben lain yang dapat digunakan untuk mengatasi
pencemaran logam kromium di lingkungan antara lain bahan-bahan organik mati,
serbuk gergaji, hasil samping pertanian, dan mikro alga. Biosorben mempunyai
keunggulan untuk mengatasi logam berbahaya dan beracun di lingkungan karena
harganya yang relatif murah, mudah didapat, dapat diperbaharui serta sifatnya yang
ramah lingkungan (Shukla et al., 2002).
Selulosa, hemiselulosa dan lignin mempunyai potensi yang cukup besar untuk
dijadikan sebagai penjerap karena gugus OH yang terikat dapat berinteraksi dengan
komponen adsorbat. Adanya gugus OH, pada selulosa dan hemiselulosa menyebabkan
terjadinya sifat polar pada adsorben tersebut. Dengan demikian selulosa dan
hemiselulosa lebih kuat menjerap zat yang bersifat polar dari pada zat yang kurang polar
(Yantri, 1998).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biosorben dari limbah hasil
pertanian yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin dapat dijadikan
sebagai biosorpsi logam berat Cr(VI). Pemanfaatan daun Azadirachta indica yang
commit to user
97 %. (Rao, et.al,. 2007). Pemanfaatan tongkol jagung dengan ukuran 100 mesh
tanpa diaktivasi dan diaktivasi dengan HNO3 disertai NaOH sebagai adsorben zat
warna biru metilena menunjukkan bahwa dengan aktivasi lebih efektif daripada
tanpa aktivasi (Fahrizal, 2008). Tongkol jagung (Zea maize), ampas tebu (Saccharum
officinarum) dan sekam padi (Oryza sativa) sebagai limbah pertanian dapat
menurunkan logam Cr(VI) berturut-turut sebesar 98,7 ; 98,64 ; dan 100 % yang
berbentuk serbuk dengan ukuran 200 mesh diaktivasi dengan pemanasan 105 oC
selama 3 menit (Abbas et al., 2010). Serabut kelapa telah diaktivasi dengan larutan
KNO3 (Nogueira et al., 2008) dapat menurunkan logam Cr(VI) pada limbah. Limbah
organik pertanian seperti kulit pisang, kulit kacang dan sekam padi yang telah
teraktivasi dapat menurunkan logam berat Cr(VI). Aktivasi dengan pemanasan di
antaranya adalah daun-daunan Platanus orientalis (Mahvi et al., 2007), serbuk
gergaji (Vinodhini and Das, 2009) dan serbuk gergaji pohon cemara (Biparva et al.,
2011) dapat menurunkan logam Cr(VI). Serat sabut kelapa hijau (Cocos nucifera)
dapat sebagai adsorpsi ion logam Cr(VI) dengan jenis interaksi yang terjadi antara
ion Cr(VI) dengan biosorben serat sabut kelapa hijau (Cocos nucifera) adalah ikatan
hidrogen, ikatan Van der Waals, pertukaran kation, dan ikatan kompleks (Sudiharta
dan Yulihastuti, 2010). Serbuk gergaji kayu Albizia (Albizzia falcata) berukuran 40
mesh diaktivasi dengan campuran pelarut etanol-toluena dapat sebagai adsorpsi ion
logam Cr(III) (Sukarta, 2008). Serbuk gergaji yang telah diaktivasi dengan NaOH
dapat digunakan untuk adsorpsi logam Cu (II) (Subakti, 2009).
Pada penelitian ini akan digunakan zeolit alam dan limbah kayu aren (Arenga
commit to user
6
batik. Zeolit alam akan diaktivasi menggunakan HCl serta dilanjutkan pemanasan
pada suhu suhu tertentu. Limbah kayu aren akan diaktivasi menggunakan HNO3 dan
dilanjutkan proses impregnasi NaOH disertai dengan pemanasan pada suhu tertentu.
Perlunya aktivasi pada adsorben untuk optimalisasi adosrben secara kimia dan fisis.
Penentuan baku mutu limbah cair batik menggunakan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah no. 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah.
Perbandingan antara penggunaan adsorben zeolit alam sebagai adsorpsi, adsorben
limbah kayu aren (Arenga pinnata) dan kombinasi keduanya digunakan untuk
mengetahui penggunaan pengolahan yang efektif.
B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diharapkan dapat dikaji
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana kualitas limbah cair batik ditinjau dari kandungan logam Cr(VI)
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no. 10 tahun 2004 ?
2. Bagaimana perbandingan kemampuan adsorpsi antara zeolit alam (ZA), limbah
kayu aren (Arenga pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA)
yang telah teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI)
pada larutan standard K2Cr2O7?
3. Bagaimana perbandingan antara kemampuan adsorpsi antara zeolit alam (ZA),
limbah kayu aren (Arenga pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren
(ZA-LKA) yang telah teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar
commit to user
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui besarnya kandungan logam Cr(VI) pada sampel limbah cair batik
dan kualitas limbah cair batik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah no. 10 tahun 2004.
2. Mengetahui kemampuan adsorpsi zeolit alam (ZA), limbah kayu aren (Arenga
pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA) yang telah
teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI) pada
larutan standard K2Cr2O7.
3. Mengetahui kemampuan adsorpsi zeolit alam (ZA), limbah kayu aren (Arenga
pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA) yang telah
teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI) pada
limbah cair batik.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat bagi peneliti: Penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangan
pemikiran secara ilmiah bagi ilmu kimia lingkungan dalam hal menurunkan
kadar Cr(VI) pada limbah cair batik.
2. Manfaat bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengolahan limbah cair batik pada industri rumah tangga batik khususnya
masyarakat di karesidenan Surakarta.
3. Manfaat bagi pemerintah: Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan
untuk membuat kebijakan pemerintah daerah setempat untuk pengendalian
commit to user
8 BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Limbah Cair Batik
Pada proses industri batik cetak dari persiapan kain putih, pengkanjian dan
penghilangan kanji, pewarnaan (deying), pencetakan (printing), pencelupan,
pengeringan, pencucian sampai penyempurnaan menghasilkan pencemar limbah cair
dengan parameter BOD, COD dan bahan lain dari zat pewarna yang dipakai
mengandung seperti zat organik, dan logam berat.
Karakteristik limbah batik cetak adalah meliputi karakteristik fisika yaitu
warna, bau, zat padat tersuspensi , temperatur, sedangkan karakteristik kimia yaitu
bahan organik,anorganik, fenol, sulfur, pH, logam berat senyawa racun (nitrit),
maupun gas. Limbah cair industri batik cetak juga mempunyai karakteristik berwarna
keruh, berbusa, pH tinggi, konsentrasi BOD tinggi, kandungan lemak alkali dan zat
warna dimana didalamnya terdapat kandungan logam berat.
Senyawa logam berat yang bersifat toksis yang terdapat pada buangan
industry batik cetak, diduga krom(Cr), Timbal (Pb), Nikel (Ni), tembaga (Cu), dan
mangan (Mn). Sumber logam berat Krom (Cr) dan Timbal (Pb) yang bersifat toksis,
dapat berasal dari zat pewarna (CrCl3, K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu
merupakan pengikat zat warna meliputi Cr(NO3)2 dan PbCrO4 (Muljadi, 2009).
Mordan disebut juga sebagai zat khusus yang dapat meningkatkan lekatnya berbagai
commit to user
2. Logam Krom (Cr)
Logam krom merupakan logam golongan transisi, diketemukan di alam
sebagai bijih terutama kromit (Fe(CrO2)2). Krom merupakan elemen berbahaya di
permukaan bumi dan dijumpai dalam kondisi oksida antara Cr(II) sampai Cr(VI).
Krom bervalensi tiga umumnya merupakan bentuk yang umum dijumpai di alam,
dan dalam material biologis krom selalu berbentuk valensi tiga, karena krom valensi
enam merupakan salah satu material organik pengoksidasi yang tinggi
(Suhendrayatna, 2001).
Ada beberapa jenis kromium yang berbeda dalam efek pada organisme.
Kromium memasuki udara, air dan tanah di Cr(III) dan Cr(VI) bentuk melalui
proses-proses alam dan aktivitas manusia. kegiatan utama manusia yang
meningkatkan konsentrasi Cr(III) yang meracuni kulit dan manufaktur tekstil.
Kegiatan utama manusia yang meningkatkan Cr(VI) konsentrasi kimia, kulit dan
manufaktur tekstil, elektro lukisan dan Cr(VI) aplikasi dalam industri. Aplikasi ini
terutama akan meningkatkan konsentrasi kromium dalam air. Melalui kromium
pembakaran batubara juga akan berakhir di udara dan melalui pembuangan limbah
kromium akan berakhir di tanah.
Sebagian besar kromium di udara pada akhirnya akan menetap dan berakhir
di perairan atau tanah. Kromium dalam tanah sangat melekat pada partikel tanah dan
sebagai hasilnya tidak akan bergerak menuju tanah. Kromium dalam air akan
menyerap pada endapan dan menjadi tak bergerak. Hanya sebagian kecil dari
kromium yang berakhir di air pada akhirnya akan larut. Cr(III) merupakan unsur
commit to user
10
menyebabkan kondisi hati, ketika dosis harian terlalu rendah. Cr(VI) adalah terutama
racun bagi organisme. Dapat mengubah bahan genetik dan menyebabkan kanker.
Tanaman mengandung sistem yang mengatur kromium-uptake harus cukup
rendah tidak menimbulkan bahaya. Tetapi ketika jumlah kromium dalam tanah
meningkat, hal ini masih dapat mengarah pada konsentrasi yang lebih tinggi dalam
tanaman. Peningkatan keasaman tanah juga dapat mempengaruhi pengambilan
kromium oleh tanaman. Tanaman biasanya hanya menyerap kromium (III). Ini
mungkin merupakan jenis penting kromium, tetapi ketika konsentrasi melebihi nilai
tertentu, efek negatif masih dapat terjadi.
Kromium tidak diketahui terakumulasi dalam tubuh ikan, tetapi konsentrasi
tinggi kromium, karena pembuangan produk-produk logam di permukaan air, dapat
merusak insang ikan yang berenang di dekat titik pembuangan. Pada hewan,
kromium dapat menyebabkan masalah pernapasan, kemampuan yang lebih rendah
untuk melawan penyakit, cacat lahir, infertilitas dan pembentukan tumor.
Dalam perairan, krom berada pada bilangan oksidasi +2, +3, dan +6, dan
hanya +6 merupakan tingkat oksidasi yang paling dominan. Ion kromos (Cr2+)
merupakan krom tingkat oksidasi +2, bersifat tidak stabil, dan jumlahnya relatif
sedikit. Cr2+dengan cepat teroksidasi ke tingkat oksidasi +3 yang lebih stabil dalam
lingkungan aerobik. Di samping itu, sebagai Cr(OH)2, Cr2+akan mengendap dalam
air pada pH mendekati 6. Dengan demikian krom tingkat oksidasi +3 dan +6 lebih
banyak berperan dalam lingkungan perairan (Bert,1982). Senyawa Cr(III) dan Cr(VI)
sering dipakai untuk bahan pelapis logam lain agar lebih tahan korosi dan kelihatan
commit to user
pembuatan cat, pewarna tekstil dan lain-lain. Dalam zat warna tekstil jenis Grey
Lanaset G mengandung krom (III) sebesar 2,5 % sebagai senyawa kompleks
organologam (Blanques et al., 2004). Cr(VI) lebih mudah diserap oleh tubuh
dibandingkan dengan Cr(III). Namun, Cr(VI) setelah di dalam tubuh segera
mengalami reduksi menjadi Cr(III) (ATSDR, 2000). Keterdapatan Cr(III) dalam
tubuh dapat menyebabkan kanker paru-paru. Proses penjerapan krom oleh tubuh dan
dampaknya bagi kesehatan disajikan pada Gambar 1 (Kaim and Schwederski, 1994).
Gambar 1. Diagram Masuknya Krom dalam Tubuh
3. Pengolahan Air Limbah
Secara umum, metode pengolahan yang dikembangkan tersebut dapat
digolongkan atas 3 jenis metode pengolahan, yaitu secara fisika, kimia maupun
commit to user
12
Cara fisika, merupakan metode pemisahan sebagian dari beban pencemaran
khususnya padatan tersuspensi atau koloid dari air dengan memanfaatkan gaya-gaya
fisika (Eckenfelder, 1989; MetCalf dan Eddy, 2003). Dalam pengolahan air industri
secara fisika, proses yang dapat digunakan antara lain adalah filtrasi dan
pengendapan (sedimentasi). Filtrasi (penyaringan) menggunakan media penyaring
terutama untuk menjernihkan dan memisahkan partikel-partikel kasar dan padatan
tersuspensi dari air. Dalam sedimentasi, flok-flok padatan dipisahkan dari aliran
dengan memanfaatkan gaya gravitasi.
Cara kimia, merupakan metode penghilangan atau konversi
senyawa-senyawa polutan dalam air dengan penambahan bahan-bahan kimia atau reaksi kimia
lainnya (MetCalf dan Eddy, 2003).
Proses netralisasi biasanya diterapkan dengan cara penambahan asam atau
basa guna menetralisir ion-ion terlarut dalam air sehingga memudahkan proses
pengolahan selanjutnya. Dalam proses koagulasi-flokulasi menurut Mysels (1959),
partikel-partikel koloid hidrofobik cenderung menyerap ion-ion bermuatan negatif
dalam air melalui sifat adsorpsi koloid tersebut, sehingga partikel tersebut menjadi
bermuatan negatif. Koloid bermuatan negatif ini melalui gaya-gaya Van der Waals
menarik ion-ion bermuatan berlawanan dan membentuk lapisan kokoh (lapisan stern)
mengelilingi partikel inti. Selanjutnya lapisan kokoh stern yang bermuatan positif
menarik ion-ion negatif lainnya dari dalam larutan membentuk lapisan kedua
(lapisan difus). Kedua lapisan tersebut bersama-sama menyelimuti partikel-partikel
koloid dan membuatnya menjadi stabil. Partikel-partikel koloid dalam keadaan stabil
commit to user
lainnya membentuk flok-flok berukuran lebih besar, sehingga tidak dapat
dihilangkan dengan proses sedimentasi ataupun filtrasi.
Koagulasi pada dasarnya merupakan proses destabilisasi partikel koloid
bermuatan dengan cara penambahan ion-ion bermuatan berlawanan (koagulan) ke
dalam koloid, dengan demikian partikel koloid menjadi netral dan dapat
beraglomerasi satu sama lain membentuk mikroflok. Selanjutnya
mikroflok-mikroflok yang telah terbentuk dengan dibantu pengadukan lambat megalami
penggabungan menghasilkan makroflok (flokulasi), sehingga dapat dipisahkan dari
dalam larutan dengan cara pengendapan atau filtrasi (Eckenfelder, 1989; Farooq dan
Velioglu, 1989).
Koagulan yang biasa digunakan antara lain polielektrolit, aluminium, kapur,
dan garam-garam besi. Masalah dalam pengolahan limbah secara kimiawi adalah
banyaknya endapan lumpur yang dihasilkan (Eckenfelder, 1989; MetCalf dan Eddy,
2003), sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Cara biologi dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan
memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan air. Pada dasarnya cara biologi
adalah pemutusan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Proses ini sangat
peka terhadap factor suhu, pH, oksigen terlarut (DO) dan zat-zat inhibitor terutama
zat-zat beracun. Mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan limbah adalah
bakteri, algae, atau protozoa (Ritmann dan McCarty, 2001). Sedangkan tumbuhan air
yang mungkin dapat digunakan termasuk gulma air (aquatic weeds) (Lisnasari,
commit to user
14
4. Zeolit
Kata “zeolit” berasal dari kata Yunani zein yang berarti membuih dan lithos
yang berarti batu. Zeolit merupakan mineral hasil tambang yang bersifat lunak dan
mudah kering. Warna dari zeolit adalah putih keabu-abuan, putih kehijau-hijauan,
atau putih kekuning-kuningan. Ukuran kristal zeolit kebanyakan tidak lebih dari 10–
15 mikron. Zeolit terbentuk dari abu vulkanik yang telah mengendap jutaan tahun
silam. Sifat-sifat mineral zeolit sangat bervariasi tergantung dari jenis dan kadar
mineral zeolit. Zeolit mempunyai struktur berongga biasanya rongga ini diisi oleh air
serta kation yang bisa dipertukarkan dan memiliki ukuran pori tertentu. Oleh karena
itu zeolit dapat dimanfaatkan sebagai penyaring molekuler, senyawa penukar ion,
sebagai filter dan katalis. (Sutarti, 1994)
a. Struktur Zeolit
Zeolit mengandung unsur utama silikon, aluminium, dan oksigen serta
mengikat sejumlah tertentu molekul air di dalam porinya. Unsur lain yang juga
[image:30.612.131.522.223.461.2]terdapat pada zeolit adalah unsur logam alkali dan alkali tanah.
Gambar 2. Kerangka Utama Zeolit
commit to user
Dalam struktur tersebut Si4+dapat diganti Al4+(Gambar 2), sehingga rumus
umum komposisi zeolit dapat dinyatakan sebagai berikut :
Mx/n [(AlO2)x(SiO2)y] m H2O (Lesley et al., 2001)
dengan :
n = Valensi kation M (alkali / alkali tanah) x dan y = Jumlah tetrahedron per unit sel m = Jumlah molekul air per unit sel M = Kation alkali / alkali tanah
Struktur zeolit yang merupakan senyawa aluminosilikat dapat dijabarkan
seperti pada gambar di bawah. Tetrahedral SiO4 dan AlO4 saling berhubungan pada
sudut-sudut tetrahedralnya untuk membentuk Al, Si framework tiga dimensi yang
berpori. Kation-kation alkali monovalen atau divalen menempati posisinya di dalam
pori-pori. Kehadiran kation-kation ini akan menetralkan muatan zeolit. Sebagian pori
[image:31.612.133.520.192.643.2]ditempati atau diisi oleh molekul-molekul air.
commit to user
16
b. Sifat Zeolit
Zeolit mempunyai sifat-sifat kimia, di antaranya :
1. Dehidrasi
Sifat dehidrasi zeolit berpengaruh terhadap sifat jerapannya. Keunikan zeolit
terletak pada struktur porinya yang spesifik. Pada zeolit alam di dalam pori-porinya
terdapat kation-kation atau molekul air. Bila kation-kation atau molekul air tersebut
dikeluarkan dari dalam pori dengan suatu perlakuan tertentu maka zeolit akan
meninggalkan pori yang kosong (Bambang et al., 1995).
2. Penjerapan
Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh molekul
air yang berada disekitar kation. Bila zeolit dipanaskan maka air tersebut akan keluar.
Zeolit yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai penjerap gas atau cairan
(Bambang et al., 1995).
3. Penukar Ion
Ion-ion pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-ion ini
dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang terjadi tergantung dari ukuran
dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat sebagai penukar ion dari zeolit antara lain
tergantung dari sifat kation, suhu, dan jenis anion (Bambang et al., 1995).
4. Katalis
Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa mempengaruhi
kesetimbangan reaksi karena mampu menaikkan perbedaan lintasan molekular dari
reaksi. Katalis berpori dengan pori-pori sangat kecil akan memuat molekul-molekul
commit to user
disebut molecular sieve yang terdapat dalam substansi zeolit alam (Bambang et al.,
1995).
5. Penyaring / pemisah
Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah didasarkan atas perbedaan
bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Molekul yang berukuran lebih
kecil dari ruang hampa dapat melintas sedangkan yang berukuran lebih besar dari
ruang hampa akan ditahan (Bambang et al., 1995).
Kekuatan zeolit sebagai penjerap, katalis, dan penukar ion sangat tergantung
dari perbandingan Al dan Si, sehingga dikelompokkan menjadi 3 (Sutarti, 1994)
sebagai berikut:
1. Zeolit dengan kadar Si rendah yaitu zeolit jenis ini banyak mengandung Al (kaya
Al), berpori, mempunyai nilai ekonomi tinggi karena efektif untuk pemisahan atau
pemurnian dengan kapasitas besar. Volume porinya dapat mencapai 0,5 cm3/cm3
volume zeolit. Kadar maksimum Al dicapai jika perbandingan Si/Al mendekati 1 dan
keadaan ini mengakibatkan daya penukaran ion maksimum.
2. Zeolit dengan kadar Si sedang yaitu kerangka tetrahedral Al dari zeolit tidak stabil
terhadap pengaruh asam dan panas. Jenis zeolit mordenit mempunyai perbandingan
Si/Al = 5 sangat stabil.
3. Zeolit dengan kadar Si tinggi yaitu zeolit ini mempunyai perbandingan Si/Al
=10-100 sehingga sifat permukaannya tidak dapat diperkirakan lebih awal. Sangat
higroskopis dan menyerap molekul non-polar sehingga baik digunakan sebagai
commit to user
18
c. Zeolit Alam
Komposisi dan struktur zeolit alam kebanyakan terdiri dari mineral
mordernit dan klinoptillit (Gambar 4). Dari uji pendahuluan terhadap zeolit alam
Wonosari dengan menggunakan difraksi sinar x diketahui bahwa sebagian besar
penyusunnya adalah mordernit. Analisis lebih lanjut terhadap zeolit alam Wonosari
menunjukkan bahwa zeolit mempunyai rasio Si/Al 4,75; keasaman sebesar 2,39
mmol/g; luas permukaan 24,13 m2/g; volume pori 74,25 x 10-3 mL/g; rerata jejari
pori 60,54 dan memilki kandungan logam Na, K, Ca dan Fe masing-masing sebesar
4,29 %; 1,34 %; 2,39 5 dan 1,04 %. (Budi, 2006)
Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zeolit alam
mampu dimanfatkan sebagai adsorben limbah pencemar dari beberapa industri.
Zeolit mampu menjerap berbagai macam logam, antara lain Ni, Np, Pb, U, Zn, Ba,
[image:34.612.140.519.214.665.2]Ca, Mg, Sr, Cd, Cu dan Hg (Kosmulski, 2001).
Tabel 1. Sifat Zeolit Jenis Mordenit
Zeolit Mordenit Sifat
Struktur kristal
Swelling
Kestabilan panas
Kestabilan radiasi
Adsorpsi
Penukar kation
Penyaring molekul
Katalis
Framework 3 dimensi
Sangat kecil
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
commit to user
[image:35.612.136.503.150.462.2](a) (b)
Gambar 4. (a) Struktur Zeolit Jenis Mordenit Na8 [Al8Si40O96]. 24H2O
(b) Struktur Zeolit Jenis Klinoptilolit Na6 [Al6Si30O72]. 24H2O.
(Guisnet, M. dan Gilson, JP., 2002)
d. Aktivasi Zeolit Alam
Proses aktivasi zeolit alam dapat dilakukan dengan 2 cara, yang pertama yaitu
secara fisika melalui pemanasan dengan tujuan untuk menguapkan air yang
terperangkap di dalam pori-pori kristal zeolit, sehingga luas permukaannya
bertambah (Khairinal, 2000). Proses pemanasan zeolit dikontrol, karena pemanasan
yang berlebihan kemungkinan akan menyebabkan zeolit tersebut rusak.
Aktivasi zeolit secara kimia dengan tujuan untuk membersihkan permukaan
pori, membuang senyawa pengotor dan mengatur kembali letak atom yang dapat
dipertukarkan. Proses aktivasi zeolit dengan perlakuan asam HCl pada konsentrasi
0,1N hingga 11 N menyebabkan zeolit mengalami dealuminasi dan dekationisasi
commit to user
20
menyebabkan terjadinya dekationisasi yang menyebabkan bertambahnya luas
permukaan zeolit karena berkurangnya pengotor yang menutupi pori-pori zeolit.
Luas permukaan yang bertambah diharapkan meningkatkan kemampuan zeolit dalam
proses penjerapan (Weitkamp, 1999). Menurut Hamdan yang dikutip oleh Dina
tingginya kandungan Al dalam kerangka zeolit menyebabkan kerangka zeolit sangat
hidrofilik. Sifat hidrofilik dan polar dari zeolit ini merupakan hambatan dalam
kemampuan penjerapannya. Proses aktivasi dengan asam dapat meningkatkan
kristalinitas, keasaman dan luas permukaan (Hari, 2001). Heraldy (2003) juga
mengkaji aktivasi asam terhadap zeolit alam asal Ponorogo dan Wonosari. Asam
yang dipergunakan adalah HCl, HNO3, H2SO4dan H3PO4.Hasilnya menunjukkan
bahwa perlakuan asam terhadap zeolit alam asal Ponorogo dan Wonosari
meningkatkan daya jerap zeolit terhadap limbah cair. Penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa perlakuan asam telah berhasil melepaskan alumunium dari
kerangka zeolit dan mampu meningkatkan keasaman zeolit. Peningkatan keasaman
zeolit disebutkan mampu memperbesar kemampuan penjerapan zeolit. Hal itu terjadi
karena banyaknya pori-pori zeolit yang terbuka dan permukaan padatannya menjadi
bersih dan luas.
5. Aren (Arenga pinnata)
Aren (Arenga pinnata) merupakan tumbuhan berbiji tertutup dimana biji
buahnya terbungkus daging buah. Tepung aren dapat digunakan untuk pembuatan
aneka produk makanan, terutama produk yang sudah dikenal masyarakat luas, yaitu
commit to user
belum dapat disubstitusi. Pembuatan tepung aren dilakukan melalui terlebih dahulu
menebang batang pohon aren kemudian dipotong-potong sepanjang 1,25 - 2 meter.
Pada industri tradisional, serat tadi dimasukkan ke bak yang dialiri air serta
diaduk-aduk dengan cara menginjak-injak untuk memisahkan antara ampas aren dan
[image:37.612.142.502.209.644.2]tepungnya. Diagram alir proses pembuatan tepung pati aren dapat dilihat pada
Gambar 5.
Gambar 5. Diagram alir proses pembuatan tepung aren
commit to user
22
Industri tepung aren berada di Dukuh Bendo, Desa Daleman Kecamatan
Tulung, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, sekitar 15-18 km ke arah utara kota Klaten.
Luas Dukuh Bendo mencapai 61.190 m2, dengan jumlah penduduk 1.164 jiwa. Mata
pencaharian penduduk terutama adalah dari industri aren yang mencapai jumlah 35
buah. Industri yang kebanyakan rumahan tersebut mendapatkan pasokan bahan baku
batang pohon aren dari 3 pabrik yang juga berlokasi di dukuh tersebut. Saat ini,
industri tepung aren menghasilkan limbah limbah cair dan limbah padat (Firdayati
dan Handajani, 2005).
Limbah cair berasal dari proses pemarutan/pelepasan pati dari serat dan
pengendapan tepung aren. Limbah padat yang berupa serbuk serat aren semula
dimanfaatkan oleh industri budidaya jamur di kota Yogyakarta. Namun pada dua
tahun terakhir, industri tersebut tidak beroperasi lagi, akibatnya timbunan limbah
padat memenuhi bantaran sungai dan daerah sekitar sawah. Lindi dari limbah padat
ini mulai terasa mencemari badan air dan sistem irigasi yang ada di daerah tersebut.
Dampak yang dirasakan penduduk berupa timbulnya gangguan kulit setelah
menggunakan sumber air yang sudah tercemar oleh lindi ampas aren dan juga
matinya ikan-ikan pada kolam ikan milik penduduk, selain bau yang menyengat,
khususnya setelah ampas terbasahi oleh hujan (Firdayati dan Handajani, 2005).
Limbah padat yang tidak ditangani dengan baik, berpotensi menimbulkan
masalah bagi komunitas sekitarnya. Limbah padat yang komponen dasarnya ada
materi organik akan terdekomposisi secara alamiah di lingkungan. Namun dalam
prosesnya sering sekali timbul gangguan bau dan estetika dari timbunan limbah padat
commit to user
Kandungan fosfor dan kalium limbah kayu aren dalam bentuk ampas masih
tinggi (Tabel 4). Tingginya kandungan besi (Fe) dan Mangan (Mn) pada limbah
diperkirakan berasal dari air sumur yang digunakan selama proses (Tabel 2)
[image:39.612.137.455.217.463.2](Firdayati dan Handajani, 2005).
Tabel 2. Karakteristik Limbah Kayu Aren dan Baku Mutu (Firdayati dan Handajani, 2005)
No. Parameter Satuan Hasil Analisa
1. C-Organik % BK 69,94
2. N-Organik % BK 0,70
3. Total Phospat mg/kg BK 1464,46
4. Amoniak mg/kg BK 0,04
5. Kalium (K) mg/kg BK 2206,96
6. Magnesium (Mg) mg/kg BK 635,85
7. Besi (Fe) mg/kg BK 652,23
8. Seng (Zn) mg/kg BK 106,06
9. Tembaga (Cu) mg/kg BK 5,82
10. Fosfor (P) mg/kg BK 487,67
11. Mangan (Mn) mg/kg BK 41,86
6. Komponen Kimia Kayu
Kayu sebagian besar tersusun atas tiga unsur yaitu unsur C, H dan O.
Unsur-unsur tersebut berasal dari udara berupa CO2dan dari tanah berupa H2O. Namun,
dalam kayu juga terdapat unsur-unsur lain seperti N, P, K, Ca, Mg, Si, Al dan Na.
Unsur-unsur tersebut tergabung dalam sejumlah senyawa organik, secara umum
dapat dibedakan menjadi dua bagian (Fengel dan Wegener, 1995) yaitu:
1. Komponen lapisan luar yang terdiri atas fraksi-fraksi yang dihasilkan oleh
kayu selama pertumbuhannya. Komponen ini sering disebut dengan zat
commit to user
24
2. Komponen lapisan dalam terbagi menjadi dua fraksi yaitu fraksi karbohidrat
yang terdiri atas selulosa dan hemiselulosa, fraksi non karbohidrat yang
terdiri dari lignin.
a. Selulosa dan Hemiselulosa
Selulosa merupakan senyawa organik yang terdapat pada dinding sel
bersama lignin berperan dalam mengokohkan struktur tumbuhan. Selulosa pada kayu
umumnya berkisar 40-50%, sedangkan pada kapas hampir mencapai 98%. Selulosa
terdiri atas rantai panjang unit-unit glukosa yang terikat dengan ikatan 1-4β
[image:40.612.133.519.216.472.2]-glukosida.
Gambar 6. Model Struktur Selulosa
Hemiselulosa adalah polimer polisakarida heterogen tersusun dari unit
D-glukosa, D-manosa, L-arabiosa dan D-xilosa. Hemiselulosa pada kayu berkisar
antara 20-30%. Dilihat dari strukturnya, selulosa dan hemiselulosa mempunyai
potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai penjerap karena gugus OH- yang
terikat dapat berinteraksi dengan komponen adsorbat. Adanya gugus OH-, pada
selulosa dan hemiselulosa menyebabkan terjadinya sifat polar pada adsorben tersebut.
Dengan demikian selulosa dan hemiselulosa lebih kuat menjerap zat yang bersifat
commit to user
OH- yang terikat pada permukaan dengan ion logam yang bermuatan positif (kation)
[image:41.612.136.521.189.464.2]merupakan mekanisme pertukaran ion sebagai berikut (Yantri, 1998).
Gambar 7. Mekanisme Gugus OH- pada Selulosa dengan Ion Logam
M
+
dan M
2+
adalah ion logam, OH- adalah gugus hidroksil dan Y adalah
matriks tempat gugus OH- terikat. Interaksi antara gugus OH- dengan ion logam juga
memungkinkan melalui mekanisme pembentukan kompleks koordinasi karena atom
oksigen (O) pada gugus OH- mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan ion
logam mempunyai orbital d kosong. Pasangan elektron bebas tersebut akan
menempati orbital kosong yang dimiliki oleh ion logam, sehingga terbentuk suatu
senyawa atau ion kompleks.
Menurut Terada et al. (1983) ikatan kimia yang terjadi antara gugus aktif
pada zat organik dengan molekul dapat dijelaskan sebagai perilaku interaksi
asam-basa Lewis yang menghasilkan kompleks pada permukaan padatan. Pada sistem
commit to user
26
b. Lignin
Lignin adalah polimer tiga dimensi yang terdiri dari unit fenil propana yang
diikat dengan ikatan eter (C-O-C) dan ikatan karbon (C-C). Lignin bersifat tahan
terhadap hidrolisis karena adanya ikatan arilalkil dan ikatan eter. Lignin adalah suatu
polimer yang komplek dengan bobot molekul tingi yang tersusun atas unit-unit
fenilpropana. Lignin termasuk ke dalam kelompok bahan yang polimerisasinya
merupakan polimerisasi cara ekor (endwisepolymerization), yaitu pertumbuhan
polimer terjadi karena satu monomer bergabung dengan polimer yang sedang
tumbuh. Polimer lignin merupakan polimer bercabang dan membentuk struktur tiga
dimensi (Gambar 8) (Judoamidjojo et al., 1989).
Di alam keberadaan lignin pada kayu berkisar antara 25-30%, tergantung
pada jenis kayu atau faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kayu. Pada kayu,
lignin umumnya terdapat di daerah lamela tengah dan berfungsi pengikat antar sel
serta menguatkan dinding sel kayu. Kulit kayu, biji, bagian serabut kasar, batang dan
daun mengandung lignin yang berupa substansi kompleks oleh adanya lignin dan
polisakarida yang lain. Kadar lignin akan bertambah dengan bertambahnya umur
tanaman. Lignin bersifat tidak larut dalam kebanyakan pelarut organik. Lignin yang
melindungi selulosa bersifat tahan terhadap hidrolisa yang disebabkan oleh adanya
ikatan alkil dan ikatan eter. Pada suhu tinggi, lignin dapat mengalami perubahan
struktur dengan membentuk asam format, metanol, asam asetat, aseton, vanilin dan
lain-lain. Sedangkan bagian lainnya mengalami kondensasi (Judoamidjojo et al.,
commit to user
Gambar 8. Model Struktur Lignin (Brunow, 1995)
Proses delignifikasi merupakan perlakuan pendahuluan terhadap bahan baku
sehingga mempermudah pelepasan hemiselulosa. Proses ini berfungsi untuk
membersihkan lignin. Berbagai perlakuan pendahuluan atau delignifikasi dapat
dilakukan seperti perlakuan secara fisik (penggilingan, pemanasan dengan uap,
radiasi atau pemanasan dengan udara kering) dan secara kimia (pelarut, larutan
pengembang, gas SO2) (Frida, 1998). Menurut Foody et al., (1999) menyatakan
bahwa perlakuan pendahuluan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara
perlakuan fisik dan kimia. Perlakuan fisik seperti penggilingan, tekanan, pengepresan
commit to user
28
c. Modifikasi Biosorben
Modifikasi biosorben bertujuan meningkatkan kapasitas adsorpsi dari
biosorben. Modifikasi dapat dilakukan dengan memberi perlakuan kimia seperti
direaksikan dengan asam dan basa atau perlakuan fisika seperti pemanasan dan
pencucian (Marshall dan Mitchell, 1996). Pada penelitian ini, biosorben dimodifikasi
dengan menggunakan asam, kemudian dilanjutkan dengan impregnasi basa.
Modifikasi asam merupakan cara paling umum yang digunakan untuk
mengaktivasi biosorben sehingga kapasitas penjerapannya jauh lebih besar dibanding
arang aktif (David, 2000). Menurut Gufta (1998), modifikasi biosorben dengan asam
paling umum dilakukan dan terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas
adsorpsi dari biosorben. Asam yang digunakan pada percobaan ini adalah asam
nitrat, sedangkan basa yang digunakan pada proses impregnasi adalah natrium
hidroksida (NaOH).
Impregnasi adalah suatu proses penjenuhan sampai ke bagian dalam adsorben
dengan gas atau cairan yang akan membentuk pori-pori atau rongga. Impregnan
NaOH pada permukaan biosorben membuat unsur karbon (C) bereaksi dengan
oksigen menjadi gas CO2 pada saat proses impregnasi. Hilangnya unsur karbon
tersebut meninggalkan ruang kosong sehingga mampu membentuk rongga yang
makin lama makin mendalam. Dengan fenomena ini, maka pori-pori terbentuk di
permukaan biosorben (Setiadi dan Edi, 1999). Rongga atau pori ini akan menjerap
zat warna biru metilena. Impregnasi dengan NaOH mampu mempercepat kinetika
commit to user
7. Adsorpsi
Salah satu metode yang digunakan untuk menghilangkan zat pencemar dari air
limbah adalah adsorpsi (Rios et al., 1999). Adsorpsi merupakan terjerapnya suatu zat
(molekul atau ion) pada permukaan adsorben. Mekanisme penjerapan tersebut dapat
dibedakan menjadi dua yaitu, jerapan secara fisika (fisisorpsi) dan jerapan secara kimia
(kemisorpsi). Pada proses fisisorpsi gaya yang mengikat adsorbat oleh adsorben adalah
gaya-gaya van der Waals. Molekul terikat sangat lemah dan energi yang dilepaskan pada
adsorpsi fisika relatif rendah sekitar 20 kJ/mol (Castellan, 1982). Sedangkan pada proses
adsorpsi kimia, interaksi adsorbat dengan adsorben melalui pembentukan ikatan kimia.
Kemisorpsi terjadi diawali dengan adsorpsi fisik, yaitu partikel-partikel adsorbat
mendekat ke permukaan adsorben melalui gaya van der Waals atau melalui ikatan
hidrogen. Kemudian diikuti oleh adsorpsi kimia yang terjadi setelah adsorpsi fisika.
Dalam adsorpsi kimia partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan
kimia (biasanya ikatan kovalen), dan cenderung mencari tempat yang
memaksimumkan bilangan koordinasi dengan substrat (Atkins, 1999).
Kekuatan interaksi adsorbat dengan adsorben dipengaruhi oleh sifat dari
adsorbat maupun adsorbennya. Gejala yang umum dipakai untuk meramalkan
komponen mana yang diadsorpsi lebih kuat adalah kepolaran adsorben dengan
adsorbatnya. Apabila adsorbennya bersifat polar, maka komponen yang bersifat polar
akan terikat lebih kuat dibandingkan dengan komponen yang kurang polar.
Kekuatan interaksi juga dipengaruhi oleh sifat keras-lemahnya dari adsorbat
maupun adsorben. Sifat keras untuk kation dihubungkan dengan istilah polarizing
commit to user
30
ikatan. Kation yang mempunyai polarizing power cation besar cenderung bersifat
keras. Sifat polarizing power cation yang besar dimiliki oleh ion-ion logam dengan
ukuran (jari-jari) kecil dan muatan yang besar. sebaliknya sifat polarizing power
cation yang rendah dimiliki oleh ion-ion logam dengan ukuran besar namun
muatannya kecil, sehingga diklasifikasikan ion lemah.
Pengertian keras untuk anion dihubungkan dengan istilah polarisabilitas
anion yaitu, kemampuan suatu anion untuk mengalami polarisasi akibat medan listrik
dari kation. Anion bersifat keras adalah anion berukuran kecil, muatan besar dan
elektronegativitas tinggi, sebaliknya anion lemah dimiliki oleh anion dengan ukuran
besar, muatan kecil dan elektronegatifitas yang rendah. Ion logam keras berikatan
kuat dengan anion keras dan ion logam lemah berikatan kuat dengan anion lemah
(Atkins, 1999).
Pearson (1963) mengklasifikasikan asam-basa Lewis menurut sifat keras dan
lemahnya. Menurut Pearson, situs aktif pada permukaan padatan dapat dianggap
sebagai ligan yang dapat mengikat logam secara selektif. Logam dan ligan
dikelompokkan menurut sifat keras dan lemahnya berdasarkan pada polarisabilitas
unsur. Pearson (1963) mengemukakan suatu prinsip yang disebut Hard and Soft Acid
Base (HSAB). Ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan berukuran
kecil merupakan basa keras, sedangkan ligan-ligan dengan atom yang elektron
terluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar merupakan basa lemah.
Sedangkan ion-ion logam yang berukuran kecil namun bermuatan positip besar,
elektron terluarnya tidak mudah dipengaruhi oleh ion dari luar, ini dikelompokkan ke
commit to user
kecil atau nol, elektron terluarnya mudah dipengaruhi oleh ion lain, dikelompokkan
ke dalam asam lemah.
Menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras
untuk membentuk kompleks, begitu juga asam lemah dengan basa lemah. Interaksi
asam keras dengan basa keras merupakan interaksi ionik, sedangkan interaksi asam
lemah dengan basa lemah, interaksinya lebih bersifat kovalen.
Porositas adsorben juga mempengaruhi daya adsorpsi dari suatu adsorben.
Adsorben dengan porositas yang besar mempunyai kemampuan menjerap yang lebih
tinggi dibandingkan dengan adsorben yang memilki porositas kecil. Untuk
meningkatkan porositas dapat dilakukan dengan mengaktivasi secara fisika seperti
mengalirkan uap air panas ke dalam pori-pori adsorben, atau mengaktivasi secara
kimia. Salah satu cara mengaktivasi adsorben secara kimia adalah aktivasi selulosa
melalui penggantian gugus aktif OH- pada selulosa dengan gugus HSO
3 -
melalui
proses sulfonasi. Selulosa yang teraktivasi dengan cara sulfonasi memberikan daya
adsorpsi yang meningkat dua kali lipat dibandingkan daya adsorpsi selulosa yang
tidak diaktivasi (Setiawan et al., 2004)
Jumlah zat yang diadsorpsi pada permukaan adsorben merupakan proses
berkesetimbangan, sebab laju peristiwa adsorpsi disertai dengan terjadinya desorpsi.
Pada awal reaksi, peristiwa adsorpsi lebih dominan dibandingkan dengan peristiwa
desorpsi, sehingga adsorpsi berlangsung cepat. Pada waktu tertentu peristiwa
adsorpsi cendung berlangsung lambat, dan sebaliknya laju desorpsi cendrung
commit to user
32
disebut sebagai keadaan berkesetimbangan. Pada keadaan berkesetimbangan tidak
teramati perubahan secara makroskopis. Waktu tercapainya keadaan setimbang pada
proses adsorpsi adalah berbeda-beda, Hal ini dipengaruhi oleh jenis interaksi yang
terjadi antara adsorben dengan adsorbat. Secara umum waktu tercapainya
kesetimbangan adsorpsi melalui mekanisme fisika (fisisorpsi) lebih cepat
dibandingkan dengan melalui mekanisme kimia atau kemisorpsi (Castellans, 1982).
8. Spektrofotometer Serapan Atom
Prinsip dasar pengukuran dengan SSA adalah penyerapan energi (sumber
cahaya) oleh atom-atom dalam keadaan dasar menjadi atom-atom dalam keadaan
tereksitasi. Pembentukan atom-atom dalam keadaan dasar atau proses atomisasi pada
umumnya dilakukan dalam nyala. Cuplikan sampel yang mengandung logam M
sebagai ion M+dalam bentuk larutan garam M+ dan A-akan melalui serangkaian
proses dalam nyala, sebelum akhirnya menjadi atom logam dalam keadaan dasar M0.
Atom-atom dalam keadaan dasar (M0) akan menyerap energi sumber energi berupa
lampu katode berongga, yang mana jumlah energi yang diserap adalah sebanding
dengan populasi atau konsentrasi atom-atom dalam sampel (Welz, 1985). Penentuan
konsentrasi unsur logam dalam sampel dapat dilakukan dengan bantuan kurva
kalibrasi yang merupakan aluran antara absorbansi terhadap konsentrasi larutan
standar. Hal ini sesuai dengan Hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa jumlah
energi yang diserap (absorbansi) adalah sebanding dengan konsentrasi (C) (Khopkar,
commit to user
B. Penelitian Terkait
Penelitian mengenai zeolit alam dan limbah kayu aren sebagai alternatif
sebagai adsorben untuk menurunkan logam Cr(VI) terkait dengan beberapa
penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut turut mendasari dan menjadi referensi
bagi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini memiliki nilai-nilai yang terbarukan
apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Maknanya bahwa terdapat
hal-hal baru dan belum diangkat pada penelitian sebelumnya.
Beberapa penelitian yang terkait penggunaan zeolit alam untuk menurunkan
logam Cr dan beberapa logam antara lain :
1. Susetyaningsih et al. (2009) melakukan penelitian bahwa kemampuan zeolit
alam untuk ukuran (-80+100) mesh memiliki kondisi yang paling baik dan telah
diaktivasi dengan pemanasan 150 oC selama 60 menit dapat mereduksi kadar
logam Cr dalam limbah B3 cair industri penyamakan kulit yaitu sebesar 92,60 %.
2. (Mutngimaturrohmah et al., 2009) melakukan penelitian bahwa pemanfaatan
zeolit teraktivasi dengan dengan HCl 6 M dan NH4NO3 2 M dapat digunakan
untuk adsorpsi fenol 100 ppm teradsorpsi sebesar 65,89 ppm.
3. Rahman dan Hartono (2004) melakukan penelitian tentang penyaringan air tanah
dengan zeolit alami untuk menurunkan kadar besi dan mangan. Kolom adsorpsi
terbuat dari kolom gelas ber-stopcock berdiameter 4 cm panjang 50 cm.
4. Campos (2009) melakukan penelitian dari zeolit alam dari Sao Paulo, Brasil
yang telah diaktivasi dengan cara pemanasan dapat menurunkan kadar logam
commit to user
34
Beberapa penelitian yang terkait penggunaan selulosa untuk menurunkan
logam Cr antara lain:
1. Rao et al. (2007) melakukan penelitian tentang pemanfaatan daun Azadirachta
indica yang diaktivasi dengan H2SO4 dan NaOH dapat menurunkan logam
Cr(VI) sebesar 94 – 97 %.
2. Fahrizal (2008) melakukan penelitian tentang pemanfaatan tongkol jagung
dengan ukuran 100 mesh tanpa diaktivasi dan diaktivasi dengan HNO3 disertai
NaOH sebagai adsorben zat warna biru metilena menunjukkan bahwa dengan
aktivasi lebih efektif daripada tanpa aktivasi
3. Abbas et al. (2010) melakukan penelitian tentang pemanfaatan tongkol jagung
(Zea maize), ampas tebu (Saccharum officinarum) dan sekam padi (Oryza
sativa) sebagai limbah pertanian dapat menurunkan logam Cr(VI) berturut-turut
sebesar 98,7 ; 98,64 ; dan 100 % yang berbentuk serbuk dengan ukuran 200
mesh diaktivasi dengan pemanasan 105 oC selama 3 menit.
4. Sudiharta dan Yulihastuti (2010) melakukan penelitian tentang pemanfaatan
serat sabut kelapa hijau (Cocos nucifera) dapat sebagai adsorpsi ion logam
Cr(VI) dengan jenis interaksi yang terjadi adalah ikatan hidrogen, ikatan Van der
Waals, pertukaran kation, dan ikatan kompleks. Kapasitas biosorpsi serat sabut
commit to user
C. Kerangka Pemikiran
Zat pencemar berupa logam-logam berat merupakan masalah yang lebih serius
dibandingkan dengan polutan organik karena ion-ion logam berat merupakan racun bagi
organisme serta sangat sulit diuraikan secara biologi maupun kimia.Senyawa logam
berat yang bersifat toksis yang terdapat pada buangan industri batik, salah satunya
adalah krom (Cr). Sumber logam berat krom total (Cr) dapat berasal dari zat
pewarna (CrCl3, K2Cr2O7). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no.
10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah, logam Cr(VI) pada golongan I sebesar
0,1 ppm dan golongan II sebesar 0,5 ppm.
Pemanfaatan zeolit alam dan limbah kayu aren yang teraktivasi merupakan
salah satu upaya pengolahan air limbah secara kimia. Salah satu metode yang
digunakan untuk menghilangkan zat pencemar dari air limbah adalah adsorpsi. Adsorpsi
merupakan terjerapnya suatu zat (molekul atau ion) pada permukaan adsorben.
Komposisi dan struktur zeolit alam kebanyakan terdiri dari mineral mordernit
dan klinoptillit. Zeolit alam Wonosari dengan menggunakan difraksi sinar x
diketahui bahwa sebagian besar penyusunnya adalah zeolit dengan jenis mordernit
Na8[Al8Si40O96].24H2O. Zeolit alam sebagai material awal dipanaskan dan diaktivasi
secara kimia dengan perlakuan asam klorida (HCl). Dealuminasi zeolit alam
menggunakan konsentrasi HCl 1 M yang merupakan konsentrasi untuk dealuminasi
zeolit alam (Swantomo et al., 2009). Pada dealuminasi, ion H+ yang dihasilkan dari
reaksi penguraian HCl dalam medium air akan mengurai ikatan atom Al yang berada
commit to user
36
Si dan Al. Ion H+ akan cenderung menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan Al-O
dan akan terbentuk gugus silanol. Dengan demikian gugus hidroksi OH- yang
nantinya akan berikatan dengan ion logam Cr secara kovalen.
Limbah kayu aren mengandung bahan organik berupa pati atau serat selulosa
baik terlarut maupun partikel tersuspensi. Selulosa merupakan senyawa organik yang
terdapat pada dinding sel bersama lignin berperan dalam mengokohkan struktur
tumbuhan. Selulosa pada kayu umumnya berkisar 40-50%, sedangkan pada kapas
hampir mencapai 98%. Selulosa terdiri atas rantai panjang unit-unit glukosa yang terikat
dengan ikatan 1-4β-glukosida.
Limbah kayu aren sebagai material awal dipanaskan dan diaktivasi
menggunakan asam dan basa. Asam yang digunakan adalah asam nitrat yang
berfungsi mengaktifkan gugus hidroksi pada selulosa. Asam nitrat telah digunakan
untuk memodifikasi karbon aktif dan menunjukkan hasil adsorpsi yang lebih baik
dibanding karbon aktif tak termodifikasi (Wu dan Paul, 1998). Kemudian diikuti
dengan impregnasi basa untuk mengaktifkan biosorben sampai ke dalam pori dan
bukan hanya terbatas pada permukaan. Menurut Alamsyah (2007) asam nitrat dapat
mengaktifkan gugus hidroksi pada selulosa sehingga dapat mengikat logam berat.
Dengan demikian gugus hidroksi (OH-) yang nantinya akan berikatan dengan ion
logam Cr secara kovalen.
Pengolahan limbah cair batik untuk menurunkan kadar logam Cr(VI)
dilakukan dengan adsorpsi sistem kolom di mana terlebih dahulu digunakan larutan
standard larutan K2Cr2O7 dengan konsentrasi tertentu sehingga dapat diketahui
commit to user
setelah aplikasi larutan standard K2Cr2O7 dengan konsentrasi



![Gambar 4. (a) Struktur Zeolit Jenis Mordenit Na8 [Al8Si40O96]. 24H2O (b) Struktur Zeolit Jenis Na [AlSiO]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/947678.393346/35.612.136.503.150.462/gambar-struktur-zeolit-jenis-mordenit-struktur-zeolit-jenis.webp)