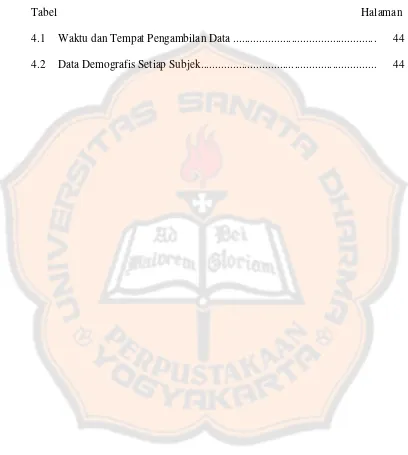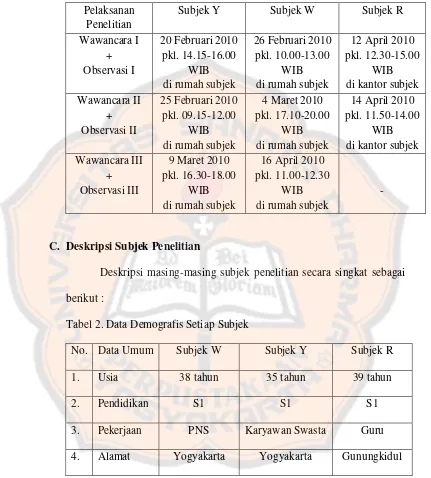KESE
EJAHTER
Diaju
M
P
UN
RAAN PS
USIA D
S
ukan untuk M
Memperoleh
Program
Di Retna Dw NIM
PROGRAM FAKULT NIVERSITA
YO
IKOLOG
EWASA A
S k r i p s i
Memenuhi Sa
Gelar Sarjan
m Studi Psik
isusun Oleh wi Palupi Wu M : 0491140
M STUDI PS TAS PSIKO AS SANATA GYAKART
2011
GIS WANI
AWAL
alah Satu Sy
na Psikologi
kologi
h:
ulandari 079
SIKOLOGI OLOGI
A DHARMA TA
ITA LAJA
yarat
i
A
iv
HALAMAN MOTTO
“Ia membuat segal a sesuatu indah pada wak tuny a.” (Pengk hotbah 3 : 11)
“Kedamai an tidak datang begitu saja. Kedamai an hadir k arena al asan y ang jelas. All ah memilik i semua al asan y ang tidak dimilik i oleh dunia. Karena
itu hany a All ah, dan buk an dunia, y ang dapat memberi k edamai an.”
(Billy Graham)
“Jangan pernah tak ut terjatuh, sebab i tu adal ah proses y ang membuat seseorang berani bangk i t dan berani mendak i l agi dan l agi hi ngga suk ses.”
(NN)
“Empat l angk ah k esuk sesan : buat rencana sesuai tujuan, persi apk an dengan doa, mulai dengan cara y ang positif , k erjak an terus-menerus.”
(Willi am Arthur Ward)
“Kecemasan tidak ak an menghil angk an k esusahan masa y ang ak an datang tetapi justru hany a ak an menghabi sk an k ek uatan k ita hari ini.”
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Tuhan Y esus K ristus...
K arena segala karya adalah wujud syukur atas anugerah-N ya....
B apak dan I bu Sukamto...
vii
KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS WANITA LAJANG USIA DEWASA AWAL
Retna Dwi Palupi Wulandari
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis wanita lajang pada usia dewasa awal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang difokuskan pada fenomena tertentu dengan subjek penelitian 3 orang wanita lajang yang berusia di atas 30 tahun, lulusan S1, bekerja dan berdomisili di Yogyakarta. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan sistem terbuka dan bersifat semiterstruktur. Sedangkan observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan. Kredibilitas hasil penelitian dicapai dengan tiga cara, yaitu konfirmasi data dengan subjek, triangulasi metode (dipakainya dua metode yang berbeda untuk meneliti hal yang sama), serta konsep kecukupan referensial dengan menggunakan tape recorder untuk merekam hasil wawancara sebagai data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kesejahteraan psikologis para wanita lajang tersebut ke arah positif. Hal ini ditandai dengan kemampuan para subjek dalam menerima diri berupa rasa syukur atas kemampuan yang dimiliki serta kelebihan dan kekurangan mereka; menjalin hubungan positif dengan keluarga, teman dan sahabat; kemampuan penguasaan lingkungan; memiliki tujuan hidup ke masa depan; dan pengembangan diri dalam kemampuan dan kepribadian. Pada kemampuan otonomi diri, ketiga subjek telah mampu memenuhi kebutuhan finansial dari penghasilan mereka. Selain itu, subjek 1 dan subjek 2 memiliki kemampuan otonomi berupa kemampuan mempertahankan prinsip hidup dan keteguhan dalam pendirian. Berbeda dari kedua subjek, subjek 3 masih mudah terpengaruh dan tergantung pada orang lain. Dalam menghadapi tekanan sebagai wanita lajang, ketiga subjek menunjukkan reaksi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal yang berbeda.
viii
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SINGLE WOMEN ADULT EARLY AGE
Retna Palupi Dwi Wulandari
ABSTRACT
This study aims to determine how the psychological well-being of single women in early adulthood looks like. This type of research is a qualitative descriptive study that focused on a particular phenomenon with a subject of study of 3 single women over the age of 30 years, S1 graduates, working and living in Yogyakarta. Researchers determined the subjects based on criteria that have been determined. Data is collected by interview and observation. Interviews in this study using an open system that is semistructured. While the observation is carried out by participant observation. The credibility of research results achieved in three ways, namely confirmation of data by subject, the triangulation method (two different methods for researching the same thing), and the concept of referential adequacy using a tape recorder to record the result of interviews as a data. The results of this study indicate that in general the condition of psychological well-being of single women is in the positive direction. It is characterized by the ability of the subjects in the self-acceptance in the form of gratitude for the capabilities as well as their advantages and disadvantages; establish positive relationships with family, friends and companions; the ability of environmental mastery; have a purpose in life into the future, and self-development in the ability and personality. On the ability of self-autonomy, the three subjects have been able to meet the financial needs of their income. In addition, subject 1 and subject 2 have the ability to maintain the principle of autonomy of the ability and determination to live in the establishment. Different from the two subjects, subject 3 was easily influenced and dependent on others. In the face of pressure as a single woman, three subjects showed a different reaction. This is influenced by a different neighborhood.
x
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi
ini dengan baik. Hari-hari yang sedikit berbeda karena “skripsi” menjadi bagian
dari kehidupan. Ternyata, perjuangan dan pengalaman dalam proses penulisan
skripsi ini memberikan banyak makna bagi penulis, selain sekedar pemenuhan
syarat pencapaian gelar kesarjanaan.
Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis
banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, dorongan, serta pengarahan dari
berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, dengan segala
kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan perlindungan,
pengharapan, kekuatan, dan keajaiban-keajaiban dalam menjalani hidup.
2. Dr. Christina Siwi Handayani, M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Titik Kristiyani, M.PSi., selaku Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
4. P. Henrietta P.D.A.D.S., S.Psi., M.A., selaku dosen pembimbing akademik,
terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan selama ini.
5. ML. Anantasari, S.Psi., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
xi
saran serta dukungan yang membuat penulis mampu menyelesaikan karya ini
dan mengalahkan rasa takut dalam proses pengerjaan skripsi. Sungguh Ibu
Peri, kebaikan, kesabaran dan kelembutanmu mengalihkan duniaku…
6. Agung Santoso, S.Psi., M.A. dan C. Wijoyo Adinugroho, S.Psi. selaku dosen
penguji skripsi, terimakasih atas masukan-masukannya.
7. T. Priyo Widiyanto, M.Si., yang telah memberi kesempatan pada peneliti
untuk bergabung dalam P2TKP angkatan 2008. Terima kasih juga kepada
Pak Toni, Mbak Tia, Dra. Pratidarmanastiti, M.S., Kristiana Dewayani,
S.Psi., M.Si., dan Mbak Diana atas bimbingan, pelajaran berharga, semangat
dan rasa kekeluargaan selama berproses di P2TKP.
8. Segenap dosen di Fakultas Psikologi USD, terima kasih atas ilmu dan
dinamika yang penulis peroleh selama belajar di Fakultas Psikologi.
9. Mas Gandung, Mbak Nanik, Mas Doni, Mas Muji dan Pak Gie’ yang dengan
sabar membantu dan memberikan kemudahan bagi penulis selama proses
studi penulis di Fakultas Psikologi… maaf jika selama ini sering merepotkan.
10. Mbak Wiwing, Mbak Yustin dan Mbak Rini, terimakasih atas pembelajaran
melalui interaksi selama ini. Sungguh, banyak hal berharga yang saya dapat
saya petik...
11. Bapak dan ibu tercinta atas segala doa, kasih sayang, kehangatan dan
dukungan yang tiada henti. Terima kasih juga atas rasa percaya yang
diberikan sehingga penulis mampu belajar menjadi lebih dewasa dan mandiri
xii
disediakan meskipun bapak dan ibu sedang dalam kesulitan. Maaf jika
sempat ada rasa kecewa karena keterlambatan ini……. I love u……
12. Mbak Nung dan Mas Aris, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang
kalian berikan sampai hari ini. Juga untuk Pangeran Kecil “Nevan” dan
“Radit” (hey…Tante udah jadi sarjana nich…….)
13. Keluarga besar 367B : Widhut, d’Nimas, Irma, Ajeng, Kak Dewi, Mbak
Nanik, Cik Ivana, Cik Lusi, Dewik, Vina, Merly, Hesti dan seluruh
alumni-alumninya, semua pahit yang ada tidak akan berubah jadi manis tanpa
kalian…. kalian semua tidak hanya teman tapi keluarga buat aku… Tak lupa
juga untuk pengunjung setia 367B : Aa’ Utiez, Aa’ Hima, Aa’ Hevi,
Monyonk, Desti... canda tawa kalian semakin mewarnai istana kami...
14. Yudi, yang pernah dan telah hadir kembali dalam perjalanan hidupku...
Terimakasih untuk doa, dukungan dan kasih yang tiada henti... Ingatlah,
bagaimanapun juga, semuanya akan indah pada waktunya...
15. Jojow Mojow, atas waktu dan tenaganya demi verbatimku... Tengkyu yah...
16. Sahabat-sahabat terbaik dalam hidup penulis : Lucia Peppy Novianti,
Rahadyan Widaruningtyas, dan Purnaning Wahyuni Astuti, terima kasih
kalian selalu ada disaat suka maupun duka. Banyak pelajaran hidup yang
telah aku bagi bersama kalian. Tuhan sungguh baik karna telah mengirim
kalian untuk melengkapi hidupku….
17. Sahabat-sahabatku selama di Psikologi : Devi, Inne, Adip, Yoyok, Wawan,
Betty, Patje dan Yuni, terima kasih atas jalinan indah yang kita rangkai
xiii
lupa untuk Lusi, Tinul, Kaka, Nico, Lala, Kike, Helen, Simin, Thithit, Johan,
Wilis, Panji, akhirnya…..☺ Tetap semangat Temans….!!! perjuangan kita
tidak hanya sebatas skripsi saja….
18. Teman-teman di UNISON, bukan waktu yang sebentar aku berdinamika
bersama kalian semua, banyak hal yang aku pelajari dari kalian... makasih
banyak ya mas bro untuk pengalaman, kerja sama dan dukungan selama ini...
19. Teman-teman Psikologi, terlebih teman-teman seperjuanganku angkatan
2004, terima kasih atas dinamikanya selama ini.
20. Teman-teman asisten P2TKP angkatan 2008 dan 2009, terima kasih atas
proses pembelajaran serta kerjasama yang indah dan menyenangkan selama
kita bekerja bersama.
21. Serta semua pihak di sekitar penulis yang belum penulis sebutkan satu per
satu dalam karya ini.
Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang
dapat menjadi masukan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan penulis
menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan
menjadi inspirasi bagi banyak orang dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Penulis
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
HALAMAN MOTTO ... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ... v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi
ABSTRAK ... vii
ABSTRACT ... viii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... ix
KATA PENGANTAR ... x
DAFTAR ISI ... xiv
DAFTAR TABEL ... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ... xvii
BAB I. PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang penelitian ... 1
B. Rumusan Masalah ... 7
C. Tujuan Penelitian ... 7
D. Manfaat Penelitian ... 8
xv
2. Manfaat Praktis ... 8
BAB II. LANDASAN TEORI ... 9
A. Kesejahteraan Psikologis ... 9
1. Pengertian Kesejahteraan Psikologis ... 9
2. Dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis ... 10
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis... 14
B. Wanita Lajang ... 17
1. Pengertian Wanita Lajang ... 17
2. Struktur Kehidupan Masa Dewasa ... 19
3. Tipologi Lajang ... 23
C. Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang Usia Dewasa Awal ... 25
D. Pertanyaan Penelitian ... 29
BAB III. METODE PENELITIAN ... 30
A. Jenis Penelitian ... 30
B. Variabel Penelitian ... 31
C. Batasan Variabel Penelitian ... 31
D. Subjek Penelitian ... 33
E. Metode Pengumpulan Data ... 34
F. Metode Analisis Data ... 36
G. Kredibilitas Penelitian ... 39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 41
A. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian ... 41
xvi
C. Deskripsi Subjek Penelitian ... 44
D. Pembahasan Penelitian ... 45
1. Pembahasan Tiap Subjek ... 45
2. Gambaran Kesejahteraan Psikologis ketiga Subjek ... 75
3. Gambaran Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang Usia Dewasa Awal ... 88
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 96
A. Kesimpulan ... 96
B. Keterbatasan Penelitian ... 98
C. Saran ... 98
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
4.1 Waktu dan Tempat Pengambilan Data ... 44
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
A Lampiran Instrumen : Pedoman Wawancara ... 102
B Lampiran Data ... 107
1. Subjek 1 Wawancara I Subjek 1 ... 107
Wawancara II Subjek 1 ... 148
Wawancara III Subjek 1 ... 186
2. Subjek 2 Wawancara I Subjek 2 ... 200
Wawancara II Subjek 2 ... 219
Wawancara III Subjek 2 ... 250
3. Subjek 3 Wawancara I Subjek 3 ... 266
Wawancara II Subjek 3 ... 288
C Lampiran Koding Data Wawancara 1. Subjek 1 ... 301
2. Subjek 2 ... 324
3. Subjek 3 ... 343
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Sepanjang rentang kehidupan manusia terdapat tuntutan-tuntutan
atau harapan-harapan masyarakat yang harus dikuasai oleh setiap individu
sebagai anggota masyarakat. Havighurst (dalam Ahmadi & Sholeh, 2005)
mengemukakan bahwa perjalanan hidup individu ditandai oleh adanya
tugas-tugas yang harus dipenuhi dan dalam batas-batas tertentu tugas-tugas
tersebut bersifat khas atau spesifik untuk masa-masa kehidupan individu.
Individu yang berhasil menuntaskan tugas-tugas tersebut akan merasa
bahagia dan sukses dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara itu, jika
individu tersebut gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri
individu yang bersangkutan sehingga dapat menimbulkan penolakan
masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas
berikutnya (Havighurst, dalam Rochmah, 2005).
Havighurst juga menyatakan bahwa dalam tiap tahap perkembangan
individu terdapat harapan sosial. Dalam hal ini setiap kelompok budaya
mengharapkan anggotanya menguasai ketrampilan tertentu yang penting dan
memperoleh pola perilaku yang disetujui pada berbagai usia sepanjang
rentang kehidupan. Keterampilan-keterampilan dan pola-pola perilaku
adalah hal yang mutlak bagi penyesuaian-penyesuaian pribadi dan sosial
pada usia-usia tertentu. Oleh karena itu, tiap kelompok kebudayaan
mengharapkan agar tiap-tiap anggotanya memiliki dan melaksanakan
keterampilan-keterampilan dan pola-pola tingkah perilaku tersebut. Salah
satu harapan masyarakat yang harus dikuasai oleh setiap individu pada masa
dewasa awal adalah mencari pasangan hidup.
Masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara
akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak berlangsung ketika
individu berada pada usia dewasa awal (Santrock, 1995). Dengan kata lain,
masa dewasa awal merupakan masa ketika individu mulai mengemban tugas
untuk menikah dan membina keluarga. Masa dewasa awal dimulai dari usia
20 hingga 40 tahun (Berk, 2007) atau akhir usia belasan tahun hingga usia
tigapuluhan tahun (Santrock,1995).
Erikson (dalam Santrock, 1995) juga menjelaskan suatu teori yang
menyatakan bahwa individu pada masa dewasa awal akan mengalami suatu
tahap perkembangan yaitu keintiman dan keterkucilan. Menurut Erikson,
masing-masing tahap perkembangan terdiri dari tugas perkembangan yang
khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi.
Krisis bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan
kerentanan dan peningkatan potensi. Semakin berhasil individu mengatasi
krisis, akan semakin sehat perkembangan mereka.
Pada tahap perkembangan keintiman dan keterkucilan ini, Erikson
menggambarkan keintiman sebagai penemuan diri sendiri pada orang lain
namun kehilangan diri sendiri (Santrock, 1995). Keintiman akan dicapai
lain. Hal ini didukung oleh pendapat Berk (2007) yang menyatakan bahwa
seseorang harus menemukan pasangan dan membangun sebuah ikatan
perasaan yang mereka pertahankan sejak lama untuk mewujudkan suatu
hubungan yang intim. Namun jika individu tidak dapat membentuk suatu
komitmen yang mendalam dengan individu lain, maka mereka akan
mengalami keterkucilan dan penarikan diri (Erikson, dalam Papalia, Olds &
Feldman, 2004).
Mencari pasangan hidup merupakan suatu hal yang tidak mudah
untuk dilakukan setiap orang, sebab pilihan ini menentukan masa depan
(Gunarsa, 1991). Bagi orang dewasa, menikah dan menjadi seorang ibu atau
bapak merupakan peran yang sangat berarti pada masa dewasa. Menurut
Kartono (2006), seorang wanita yang belum menikah dan belum menjadi
seorang ibu pada usia dewasa ini, seringkali dianggap sebagai pribadi yang
gagal karena motif dasar untuk mengembangkan keturunan tidak terlaksana.
Bahkan bagi kebanyakan orang Jawa, seorang wanita dianggap sempurna
jika ia telah menikah dan melahirkan anak.
Sumarah (2000) berpendapat bahwa dalam masyarakat patriarkal,
hidup perkawinan dianggap sebagai satu-satunya jalan yang wajar dan orang
yang menjalani hidup sendirian atau lajang sering menjadi bahan olok-olok
dan pergunjingan. Menikah dipandang sebagai suatu kelaziman, tidak saja
diterima tetapi juga dikehendaki secara sosial. Akibatnya, melajang dapat
dipandang sebagai suatu keterpaksaan yang menyedihkan (Risnawaty,
Indonesia tetap menempatkan menikah dan memiliki anak sebagai prioritas
hidup wanita, sedangkan hidup melajang akan dicap sebagai tidak lengkap.
Sangat sedikit orang yang bisa memahami bahwa jalan hidup lajang
merupakan suatu pilihan bebas yang dapat memberikan kebahagiaan
sepenuhnya bagi orang yang memilihnya. Masyarakat masih menganggap status lajang sebagai sesuatu hal yang janggal, bahkan menganggap sebagai
pertanda adanya cacat psikologis.
Sejak dulu hingga sekarang, nampaknya sebagian besar masyarakat
lebih dapat menerima wanita yang telah memasuki usia dewasa awal yang
telah menikah daripada wanita yang belum menikah atau wanita yang
memilih untuk tidak menikah. Sebaliknya, pria yang membujang tidak
terlalu mendapat tekanan dari masyarakat. Pandangan umum yang diberikan
terhadap pria yang tidak menikah berbeda dengan pandangan terhadap
wanita yang tidak menikah. Menurut Jacoby dan Bernard (dalam Suryani,
2007), dibandingkan dengan pria, umumnya pada usia sekitar 30 tahun,
wanita mendapat tekanan yang lebih besar untuk menikah dari orang tua,
sahabat, bahkan teman kerjanya. Beban menjadi lajang selalu lebih berat
bagi wanita karena tingginya penilaian atas diri wanita, yaitu menjadi istri,
ibu dan sebagai pengatur rumah tangga (Meiyuntariningih, 2001).
Pandangan-pandangan negatif masyarakat mengenai wanita lajang
diperkuat dengan adanya mitos-mitos maupun stereotipe-stereotipe
mengenai wanita lajang di dalam masyarakat. Wanita lajang sering dilihat
merawat, kurang menarik secara seksual, dan lebih egois (Suryani, 2007).
Selain itu penilaian sebagai wanita yang dingin, judes, galak, kesepian,
sombong dan terlalu pemilih menjadi stereotipe lain bagi wanita lajang
(Esterlianawati, 2007). Bahkan sebutan perawan tua dan wanita yang tidak
laku juga menjadi label bagi wanita yang belum menikah pada usia di atas
30 tahun. Semua mitos dan stereotipe ini pada intinya menyatakan bahwa
wanita yang tidak menikah dianggap tidak sehat secara psikologis sehingga
tidak mampu mencapai kesejahteraan psikologis.
Kesejahteraan psikologis merupakan kondisi diri yang dicirikan oleh
dimilikinya kesehatan mental diri yang positif, sedangkan stres, kecemasan
ataupun frustasi merupakan gejala kondisi kesehatan mental yang mengarah
negatif. Kesejahteraan psikologis merupakan suatu bentuk evaluasi secara
lebih global dan mendalam mengenai kemampuan afektif individu dan
kualitas kehidupannya. Kesejahteraan psikologis merupakan istilah yang
digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu
berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif yang dikemukakan
oleh beberapa ahli psikologi (Ryff, 1989). Fungsi psikologi positif yang
dimaksud oleh Ryff (1989) adalah enam kriteria dari teori-teori psikologi
kepribadian maupun psikologi perkembangan, yaitu : penerimaan diri,
hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi diri, penguasaan
lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi.
Pada umumnya masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan
kenyataannya semakin banyak wanita yang cenderung menunda pernikahan
atau bahkan tidak menikah sama sekali demi kesuksesan karirnya. Menurut
Permanasari (2003), ketika wanita memasuki dunia kerja, timbul suatu
fenomena yang menunjukkan bahwa wanita pekerja yang sukses dalam
karirnya kebanyakan tidak menikah atau melajang. Hasil penelitian yang
dilakukan Permanasari (2003) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi
motivasi wanita untuk berkarir maka semakin tinggi pula kecenderungan
untuk menunda perkawinan. Hal tersebut terjadi seiring dengan pergeseran
nilai tentang peranan wanita akibat adanya gerakan emansipasi, terbukanya
kesempatan bagi wanita untuk mengenyam pendidikan tinggi dan peluang
untuk memasuki dunia kerja.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Sugianto (2000) menunjukkan
hasil bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan yang tinggi memberi
kesempatan bagi individu untuk mengaktualisasikan diri dan menjalani
hidup yang berkualitas baik, yang dianggap turut mendukung kesejahteran
psikologis kaum lajang. Faktor pendidikan tinggi dan pekerjaan yang mapan
pada umumnya cenderung diidentikkan dengan peningkatan kualitas hidup
yang dapat menunjang kesejahteraan psikologis kaum lajang.
Sementara itu, pilihan untuk melajang membawa konsekuensi bagi
individu. Status lajang dapat membuat individu merasa tertekan, tetapi di
sisi lain juga dapat menjadi keuntungan bagi individu karena wanita lajang
lebih leluasa dalam mengelola waktu maupun uang untuk merawat diri
untuk membuat keputusan bagi diri sendiri, bebas mengembangkan pribadi,
berpeluang untuk meraih jenjang pendidikan dan karir yang lebih tinggi,
serta lebih leluasa dalam bepergian.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tergugah untuk meneliti
lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya kesejahteraan psikologis
wanita lajang dan hal ini nantinya diharapkan dapat mengungkap tentang
fenomena tersebut.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran
kesejahteraan psikologis wanita lajang usia dewasa awal?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah
menggali dan memahami lebih dalam bagaimana pengalaman hidup wanita
lajang pada usia dewasa awal serta bagaimana mereka merefleksikan
pengalaman hidupnya tersebut. Tujuan lain yang hendak dicapai adalah
menggambarkan bagaimana dan dinamika kesejahteraan psikologis wanita
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
tentang gambaran kesejahteraan psikologis pada diri wanita lajang usia
dewasa awal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya
dalam bidang perkembangan, klinis maupun kesehatan mental.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi para wanita lajang
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai keadaan wanita lajang secara psikologis sehingga dapat
menjadi bahan evaluasi dan instropeksi diri bagi para wanita lajang.
b. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada
masyarakat mengenai kondisi psikologis wanita lajang yang belum
menikah pada usia dewasa awal, sehingga masyarakat dapat lebih
memahami dan menerima keberadaan mereka dalam lingkungan
BAB II
DASAR TEORI
A. Kesejahteraan Psikologis
1. Pengertian Kesejahteran Psikologis
Kesejahteraan psikologis merupakan penggambaran kesehatan
psikologis seorang individu. Tingkat kesehatan secara psikologis ini
berdasarkan pada pemenuhan kriteria fungsi kesehatan mental positif
yang dikemukakan oleh para ahli psikologi (Ryff, 1995). Kesejahteraan
psikologis meliputi pula penerimaan tantangan eksistensi kehidupan.
Ryff (1995) menjelaskan bahwa secara teoritis, kesejahteraan psikologis
meliputi aspek multidimensional yang terdiri dari enam aspek, yaitu:
penerimaan diri secara positif, hubungan positif dengan orang lain,
otonomi diri, kemampuan dalam pengelolaan lingkungan sosial, hidup
yang memiliki tujuan dan kemampuan pengembangan diri.
Pada awalnya, indikator kesejahteraan dilihat dari kebahagiaan
individu yang tercermin dari perbandingan perasaan dengan emosi
positif dan negatif dari individu (Bradburn dalam Ryff, 1989). Beberapa
waktu kemudian, beberapa peneliti perkembangan mengukur
kesejahteraan psikologis dari tingkat kepuasan hidup individu
(Andrews; Diener; Havighurst; Neugarten dan Tobin, dalam Ryff dan
Keyes, 1995). Ryff (1989) melihat kesejahteraan psikologis sebagai
bentuk penurunan dari konsepsi Allport mengenai kematangan,
konsepsi Jung mengenai formulasi atas individuasi, konsepsi Maslow
mengenai aktualisasi diri, dan konsepsi Rogers mengenai orang yang
berfungsi sepenuhnya.
Berdasarkan penelitian kesejahteraan psikologis yang dilakukan
oleh Ryff (1989), peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan
psikologis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan
kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi
psikologis positif yang dikemukakan oleh para ahli psikologi.
2. Dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis
Ryff (1989) menghasilkan suatu model kesejahteraan dalam
bentuk multidimensi yang terdisi atas enam fungsi psikologis positif,
yaitu:
a. Penerimaan diri
Penerimaan diri merupakan merupakan bagian utama dari
kesehatan mental, seperti karakteristik dari aktualisasi diri,
keberfungsian yang optimal, dan kedewasaan. Teori rentang
kehidupan juga menekankan pada individu untuk dapat menerima
diri sendiri dan kehidupan masa lalu pribadi. Jadi, memegang sikap
yang positif terhadap diri sendiri merupakan suatu karakteristik
b. Hubungan positif dengan orang lain
Dimensi ini menekankan pada pentingnya hubungan
interpersonal yang hangat dan terdapat rasa percaya. Kemampuan
untuk mencintai dipandang sebagai suatu komponen yang penting
dari kesehatan mental. Individu yang mampu mengaktualisasi diri
dengan baik, mempunyai rasa empati dan afeksi yang kuat untuk
sesama manusia, mampu memiliki cinta dan persahabatan yang
mendalam, serta mampu mengidentifikasikan dirinya secara
lengkap dengan orang lain. Hubungan yang hangat dengan orang
lain merupakan suatu kriteria kedewasaan. Teori perkembangan
kedewasaan juga menekankan perlunya kemampuan untuk
membina hubungan yang intim dengan orang lain dan pentingnya
kemampuan untuk mengarahkan atau membimbing orang lain.
Relasi positif dengan orang lain sangat penting dalam konsep
kesejahteraan psikologis.
c. Otonomi Diri
Dimensi ini menekankan pada kualitas-kualitas seperti
determinasi diri, independensi dan pengaturan perilaku dari dalam
diri. Individu yang mampu mengaktualisasikan diri digambarkan
sebagai orang yang mampu menunjukkan fungsi yang mandiri dan
mampu bertahan dalam inkulturasi. Orang yang berfungsi
sepenuhnya juga digambarkan memiliki locus internal dalam
dari orang lain, akan tetapi mengevaluasi diri mereka sendiri
berdasarkan standar-standar pribadi. Orang yang terindividuasi
juga bebas dari ketentuan yang mengikat seperti
ketakutan-ketakutan, keyakinan-keyakinan, dan hukum-hukum kolektif.
Konsep rentang hidup juga menekankan arti penting kemerdekaan
pribadi dari norma-norma yang mengikat individu dalam
kehidupan sehari-hari.
d. Penguasaan lingkungan
Dimensi ini menekankan pada kemampuan individu untuk
memilih atau menciptakan lingkungan sesuai dengan kondisi
fisiknya. Hal ini merupakan suatu karakteristik dari kesehatan
mental. Perkembangan rentang kehidupan juga menekankan bahwa
individu membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan
mengendalikan lingkungan yang kompeks. Teori ini menekankan
kemampuan seseorang untuk menguasai dunia, mengubahnya
secara kreatif melalui aktivitas mental ataupun fisik. Masa lanjut
usia akan optimal ketika individu beruntung mendapatkan
peluang-peluang dari lingkungannya. Beberapa perspektif menunjukkan
bahwa partisipasi aktif dalam penguasaan lingkungan merupakan
unsur penting dari fungsi psikologis yang positif.
e. Tujuan hidup
Keyakinan perasaan tentang tujuan dan makna dalam
dari kematangan juga menekankan suatu pemahaman yang jelas
mengenai tujuan hidup, perasaan yang mempunyai arah dan niat.
Teori perkembangan rentang kehidupan mengambarkan
bermacam-macam tujuan atau sasaran dalam hidup, seperti menjadi produktif
dan kreatif atau mencapai integrasi emosi dalam kehidupan
selanjutnya. Jadi, seseorang yang berfungsi secara positif memiliki
tujuan, niat dan perasaan akan arah. Semua unsur tersebut
berkontribusi terhadap perasaan bahwa hidup adalah bermakna.
f. Pengembangan pribadi
Taraf fungsi psikologis yang optimal tidak hanya bertujuan
untuk mencapai pembentukan karakteristik-karakteristik, tetapi
juga mengharuskan seseorang terus mengembangkan potensi
dirinya untuk tumbuh dan mengupayakan peningkatan pribadi.
Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan menyadari potensi
pribadi dalam perspektif klinis merupakan hal utama dalam
pertumbuhan pribadi. Keterbukaan tehadap pengalaman merupakan
karakteristik kunci dari orang yang berfungsi sepenuhnya. Individu
semacam ini secara terus-menerus selalu berkembang dan menjadi
sesuatu daripada mencapai suatu kondisi tetap ketika segala sesuatu
tidak dapat terpecahkan. Teori rentang kehidupan memberikan
penekanan secara eksplisit terhadap individu untuk tumbuh secara
berkelanjutan dan menghadapi tantangan-tantangan atau
pribadi yang berkelanjutan dan realisasi diri adalah suatu hal yang
menonjol dalam teori tersebut.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis Ryff (1995) memaparkan bahwa apapun aspek yang dipakai
dalam mengukur kesejahteraan psikologis, hal penting yang harus
diperhatikan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kesejahteraan psikologis individu. Faktor yang mempengaruhi
kesejahteraan psikologis antara lain: latar belakang budaya, norma
masyarakat yang berlaku, suku, kelas sosial, dan kapasitas intelektual
seorang individu. Faktor-faktor tersebut satu sama lain saling
mempengaruhi.
Cooper, dkk. (1995) memandang bahwa keyakinan dalam
kemampuan pribadi individu yang mencakup kemandirian dan
menentukan tujuan pribadi akan berkaitan langsung dengan keyakinan
internal individu. Keyakinan tersebut akan memegang kontrol atas
kehidupan individu dan akan membuat individu mampu untuk memilih
atau menciptakan lingkungan yang positif bagi dirinya sehingga dapat
menunjang pencapaian kesejahteraan psikologis.
McGregor dan Little (dalam Compton, 2001) menyatakan ada
dua hal yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang yaitu pencapaian
kepercayaan diri (berasosiasi dengan kebahagiaan) dan integritas tujuan
mendukung asumsi bahwa kesejahteraan psikologis dapat diperoleh
dengan mencapai dua hal, yaitu kebahagiaan atau kepuasan hidup dan
perkembangan pribadi atau kebermaknaan hidup dalam kondisi yang
optimal.
Faktor lain yang juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis
adalah adanya sikap penuh kesadaran. Kualitas dari sikap penuh
perhatian secara individual penting dalam mengelola dan meningkatkan
kesejahteraan. Penelitian yang berkembang dewasa ini menunjukkan
bahwa peningkatan sikap penuh perhatian melalui pelatihan
memfasilitasi kualitas kesejahteraan dalam diri. Secara spesifik, makna
dari sikap penuh perhatian digambarkan dengan ciri kondisi yang
terbuka dan menerima terhadap kesadaran dan perhatian (Brown, dkk.,
2003). Sikap penuh perhatian dipahami sebagai suatu kondisi individu
ketika memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu dan sadar akan
apa yang sedang terjadi pada saat situasi sedang berlangsung.
Sikap penuh perhatian melibatkan penerimaan perhatian
terhadap makna psikologis. Dalam kondisi yang tidak penuh perhatian,
emosi yang muncul dapat terjadi di luar kesadaran. Selain itu, perilaku
dapat muncul sebelum seseorang secara jelas memahaminya. Sikap
penuh perhatian juga memiliki keterkaitan dengan aspek kepribadian
yaitu dimensi keterbukaan terhadap pengalaman (dalam Brown, dkk.,
2003), yang di dalamnya dimaknai sebagai penerimaan dan ketertarikan
pengalaman positif terhadap tiga hal, yaitu: tingginya kemandirian,
sering memiliki perasaan positif, dan jarang memunculkan
perasaan-perasaan negatif.
Cross, dkk., (2003) menyatakan bahwa faktor pendukung lain
dari kesejahteraan psikologis pada individu adalah sikap konsistensi
dalam diri individu tersebut. Individu yang mampu menunjukkan
bahwa diri mereka cukup konsisten dalam situasi dan kondisi peraturan
yang berbeda memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi
daripada individu yang kurang konsisten atau memiliki konsep diri
yang belum jelas. Konsistensi merupakan suatu pendekatan kognitif
dalam pengambilan keputusan dalam konteks komitmen. Lecky dan
Alport (dalam Cross, dkk., 2003) berpendapat bahwa konsistensi
merupakan hal yang penting dalam mengatur keutuhan diri. Konsistensi
juga merupakan indikator penting dari kesuksesan dalam beradaptasi
dan kesehatan mental yang baik. Konsistensi pada diri individu ditandai
dengan adanya kematangan, integritas kepribadian dan kesatuan, yang
berarti pula berasosiasi dengan dimensi positif dari kesejahteraan diri.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain latar belakang
budaya, norma masyarakat yang berlaku, suku, kelas sosial, kapasitas
intelektual individu, rasa percaya diri, integritas tujuan hidup, dan
B. Wanita Lajang
1. Pengertian Wanita Lajang
Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
perempuan dewasa, sedangkan lajang berarti sendirian atau belum
kawin. Oleh karena itu, wanita lajang adalah perempuan dewasa yang
belum kawin atau masih sendirian. Batasan wanita lajang di Indonesia
lebih sempit daripada istilah single woman yang terdapat dalam
literatur-literatur berbahasa Inggris, yang pada umumnya mengacu pada
wanita yang hidup tanpa pasangan (belum pernah menikah atau
berstatus janda akibat pasangan meninggal maupun perceraian), atau
wanita yang hidup bersama pasangan di luar lembaga perkawinan yang
sah.
Santrock (1995) mengemukakan berbagai pendapat mengenai
orang dewasa yang hidup sendiri. Menurut pandangannya, orang
dewasa yang hidup sendiri seringkali memiliki masalah-masalah dalam
hubungan yang intim dengan orang dewasa lain, menghadapi kesepian,
dan menemukan tempat dalam masyarakat yang berorientasi pada
pernikahan. Hidup sendiri seringkali dihubungkan dengan mitos dan
stereotip seperti hidup mengikuti arus, hidup sendiri penuh kesepian
dan cenderung bunuh diri. Mereka sering ditantang untuk menikah
sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai orang yang tidak
bertanggung jawab, mementingkan diri sendiri, impoten, frigid, dan
kebebasan penuh untuk mengatur kehidupan pribadinya dan mencapai
tujuan-tujuan dalam hidupnya.
Pada awalnya, sebagian orang dewasa yang tidak pernah
menikah dianggap memiliki kehidupan yang menyenangkan dan
berkecukupan. Akan tetapi, ketika mencapai usia 30 tahun tekanan pada
orang dewasa untuk menetap dan menikah akan semakin meningkat.
Salah satu alasannya, wanita dewasa mungkin akan merasakan situasi
darurat ketika mencapai usia 30 tahun apabila mereka ingin
memperoleh keturunan. Pada saat itu banyak orang dewasa yang hidup
sendirian membuat suatu keputusan sadar untuk menikah atau tetap
melajang (Santrock, 1995).
Hal senada diungkapkan juga oleh Neugarten dalam teorinya
tentang social clock (dalam Berk, 2007). Menurut Neugarten, istilah
social clock berarti tingkatan usia yang berkaitan dengan norma-norma
dan harapan masyarakat yang mengarahkan sekaligus membatasi
perilaku maupun pilihan individu selama rentang hidupnya, seperti
kapan saatnya untuk bekerja, menikah, melahirkan anak pertama,
membeli rumah dan pension, bahkan saat untuk menghadapi krisis
tengah baya.
Neugarten juga menambahkan bahwa lingkungan sosial dari
kelompok usia tertentu dapat mengubah social clock.
Peristiwa-peristiwa dan kecenderungan-kecenderungan yang khas pada kelompok
kelompok usia tersebut. Bagi seorang wanita, misalnya, social clock
untuk menikah tampaknya dibatasi oleh usia reproduksinya, sehingga
masyarakat pada umumnya usia tiga puluh tahun sebagai usia yang
cukup rawan bagi seorang wanita yang belum menikah dan memiliki
keturunan. Oleh sebab itu, wanita yang berusia tiga puluh tahun akan
mendapat tekanan dari masyarakat untuk segera menikah.
Sumber utama dalam perubahan kepribadian pada masa dewasa
adalah kesesuaian atau permulaan dari social clock. Dalam sebuah studi
disebutkan bahwa social clock feminin adalah menikah dan menjadi
orang tua pada usia awal atau pertengahan duapuluhan, sedangkan para
maskulin masuk pada status karir yang baik dan kenaikan pangkat pada
usia duapuluhan akhir. Menurut Berk (2007), wanita yang tidak berada
pada social clock yaitu mereka yang belum menikah dan memulai karir
pada usia 30 tahun menjadi ragu-ragu, merasa tidak mampu, dan
kesepian.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menetapkan definisi wanita
lajang sebagai wanita berusia tiga puluh tahun ke atas yang belum
pernah menikah.
2. Struktur Kehidupan Masa Dewasa
Selama hidup, individu membuat pilihan dan keputusan yang
disebabkan maupun menyebabkan perubahan dalam dirinya. Meskipun
tetapi pada tingkat tertentu mereka tetap mengalami suatu perubahan.
Peneliti mengambil struktur kehidupan masa dewasa dari Levinson
(dalam Berk, 2007) untuk melihat tahap-tahap perkembangan individu
pada masa dewasa.
Levinson (dalam Berk, 2007) mengungkapkan bahwa struktur
kehidupan merupakan model yang mendasar pada kehidupan seseorang
yang terdiri dari hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti
individu-individu, kelompok-kelmpok, dan lembaga-lembaga. Struktur
kehidupan ini menjadi batasan antara diri dengan dunia luar yang
berfungsi sebagai kerangka untuk bekerja maupun membina keluarga.
Levinson menjelaskan tahap-tahap perkembangan masa dewasa
dengan menggunakan istilah season. Menurut Levinson, tiap tahap
menunjukkan adanya tantangan perkembangan tertentu yang akan
dihadapi oleh individu. Ada tiga season utama dari struktur kehidupan
Levinson (dalam Berk, 2007), yaitu:
a. Masa Dewasa Awal (17-40 tahun)
Masa dewasa awal ini dapat dijabarkan menjadi empat tahap,
antara lain:
1). Transisi ke masa dewasa awal (17-22 tahun), ditandai oleh
adanya upaya individu untuk mandiri dari pengaruh orang tua
serta perencanaan tujuan hidup yang disebut Levinson sebagai
impian (dream), yaitu suatu gambaran dari individu sendiri
keputusan mereka. Impian ini dapat memberikan motivasi dan
gairah hidup pada individu untuk menghadapi masa depan.
Menurut Levinson, impian para pria biasanya menekankan pada
kemandirian dalam pekerjaan, walaupun sebagian besar wanita
yang berorientasi pada karir menunjukkan impian mengenai
pernikahan dan karir yang mencolok. Sementara itu, impian para
wanita cenderung mendefinisikan diri dalam hubungan dengan
suami, anak-anak, dan rekan kerja.
2). Memasuki struktur kehidupan dewasa awal (22-28 tahun),
ditandai oleh adanya usaha individu untuk membangun
hubungan pribadi yang khusus, misalnya pernikahan.
3) Usia 30 sebagai usia transisi (28-33 tahun), dititikberatkan pada
usia 30 tahun saat individu mengevaluasi kembali struktur
kehidupan mereka. Menurut Levinson (dalam Berk, 2007), usia
30 tahun merupakan periode transisi untuk menghapus struktur
kehidupan yang ada dan memberikan kesempatan bagi individu
untuk menciptakan struktur kehidupan yang baru. Mereka yang
masih menikmati karir dan belum menikah biasanya fokus
dalam menemukan pasangan hidup. Akan tetapi, jarang sekali
para laki-laki yang berkebalikan dengan prioritas karir dan
keluarga, sedangkan wanita yang berorientasi pada karir
kadang-kadang melakukannya. Levinson juga menjelaskan
mereka tidak mencapai kepuasan dalam ikatan keintiman atau
pencapaian jabatan pada usia transisi 30. Bagi individu yang
mempertanyakan apakah mereka dapat membuat struktur hidup
yang penuh arti, pada saat itulah terjadi banyak konflik dan
ketidakstabilan.
4). Puncak struktur kehidupan dewasa awal (33-40 tahun), ditandai
oleh keberhasilan individu untuk menemukan tempat di
masyarakat serta komitmennya untuk meningkatkan karir dan
jalan hidupnya.
b. Masa Dewasa Tengah (40-60 tahun)
Pada masa dewasa tengah ini, individu akan mengevaluasi diri
untuk yang kedua kalinya mengenai apa yang telah dicapai dalam
hidup, merubah atau semakin memantapkan tujuan yang hendak
dicapai. Masa dewasa tengah dapat dijabarkan menjadi empat, yaitu:
1). Transisi ke masa dewasa tengah (40-45 tahun).
2). Memasuki struktur kehidupan dewasa tengah (45-50 tahun).
3). Usia 50 sebagai usia transisi (50-55 tahun).
4). Puncak struktur kehidupan dewasa tengah (55-60 tahun).
c. Masa Dewasa Lanjut (60 tahun keatas)
Pada masa dewasa lanjut, individu telah mampu menerima
dirinya dengan segala keterbatasan dan kefanaan dirinya sebagai
salah satu persiapan menghadapi kematian. Masa dewasa lanjut
1). Transisi ke masa dewasa lanjut (60-65 tahun).
2). Dewasa Lanjut (65 tahun-kematian).
3. Tipologi Lajang
Stein (dalam Laswell & Laswell, 1987) mengemukakan empat
tipe individu yang melajang berdasarkan kesediaannya untuk melajang,
yaitu dengan kehendak sendiri (voluntary) atau dengan keterpaksaan
(involuntary); dan berdasarkan sifat status lajangnya, yaitu bersifat
sementara (temporary) atau tetap (permanent). Menurut Stein, tipe
individu masih dapat berubah tergantung pengalaman-pengalaman dan
prioritas-prioritas yang dimiliki oleh individu tersebut.
Berikut ini penjelasan mengenai Tipologi Lajang yang
dikemukakan oleh Stein, yaitu :
a. Temporary Voluntary Singlehood
1) Orang muda yang belum pernah menikah dan menunda
pernikahan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
2) Orang yang baru saja bercerai atau janda yang membutuhkan
waktu untuk sendiri tetapi pada akhirnya ingin menikah
kembali.
3) Orang yang sudah tua yang tidak menikah dan memutuskan
untuk menikah ketika ada orang yang tepat, tetapi dia tidak
4) Orang yang tinggal bersama dan akhirnya menikah satu sama
lain atau dengan orang lain.
b. Temporary Involuntary Singlehood
1) Orang muda yang belum menikah dan berkeinginan untuk
menikah dan aktif mencari pasangan, tetapi belum
menemukan.
2) Menunda sementara pernikahan dan mencari pernikahan
dengan prospek yang lebih cerah.
3) Orang yang bercerai atau janda atau orang tua tunggal yang
ingin segera menikah kembali.
c. Permanent Voluntary Singlehood
1) Orang yang tinggal bersama tetapi memilih untuk tidak
menikah.
2) Orang yang memenuhi janji-janji religiusitas untuk tidak
menikah.
3) Orang yang tidak pernah menikah dan tidak bermaksud untuk
menikah.
4) Tipe-tipe orang yang menikah hanya satu kali saja.
d. Permanent Involuntary Singlehood
1) Orang yang tidak menikah atau bercerai dan ingin menikah
atau menikah kembali, tetapi tidak memiliki kesempatan dan
2) Orang yang tidak pernah menikah karena sesuatu yang tidak
memungkinkan mereka menemukan pasangan, misal : cacat
mental atau cacat fisik.
Berdasarkan tipologi lajang yang dikemukakan oleh Stein, peneliti
menggunakan tipe individu lajang yang bersifat sementara dengan
keterpaksaan (Temporary Involuntary Singlehood) sebagai dasar
pemilihan subyek, yaitu wanita muda lajang yang belum pernah menikah
dan berkeinginan untuk menikah yang secara aktif mencari pasangan,
tetapi belum menemukan.
C. Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang Usia Dewasa Awal
Dalam perjalanan hidup, individu selalu dihadapkan pada
pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang dapat menyebabkan perubahan
dalam diri individu tersebut. Pilihan dan keputusan yang dibuat oleh
individu tidak terlepas dari pengaruh masyarakat maupun lingkungan
tempat individu tinggal. Pandangan masyarakat yang secara umum
didasarkan pada kebudayaan setempat akan menjadi suatu norma standar
bagi perilaku yang diharapkan dari anggotanya. Bagi mereka yang
berperlaku tidak sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan akan
mendapat sanksi sosial yang menekan (Neugarten, dalam Berk, 2007).
Menurut Sumarah (2000), dalam masyarakat patriarkal, perkawinan
merupakan suatu norma standar bagi individu yang sudah menginjak
sering menjadi bahan pergunjingan masyarakat dan “ketidakmampuan”
untuk menikah akan dianggap sebagai kegagalan individu sebagai pribadi
dan menunjukkan adanya keadaan patologis dalam diri individu.
Bagi wanita, status lajang akan memberikan beban sosial yang
lebih berat dibandingkan dengan pria. Shostak (1987, dalam Olson &
DeFrain, 2003) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hal yang
penting bagi wanita dewasa daripada pria dewasa. Meskipun wanita
dewasa terus menerus mencari pekerjaan dan karir, mereka masih lebih
memelihara nilai dari suatu perkawinan bila dibandingkan dengan para
pria. Terlebih lagi dalam kebanyakan masyarakat Jawa, wanita yang belum
menikah dalam usia dewasa dianggap belum lengkap. Dengan demikian,
sejak dulu masyarakat mengasumsikan bahwa kesejahteraan individu yang
menikah akan lebih tinggi dari individu yang tidak menikah.
Permasalahan yang dianggap sebagai penyebab rendahnya
kesejahteraan psikologis pada individu yang melajang adalah masalah
penyesuaian diri yang disebabkan adanya perasaan kesepian, terutama bila
individu tidak tinggal bersama keluarga dekat, akan menjadi beban
emosional bagi individu tersebut. Secara sosial, individu yang melajang
cenderung terkucil dari pergaulan orang dewasa yang kebanyakan dari
mereka sudah menikah. Kondisi seperti ini akan menyulitkan individu
untuk menjalin pertalian sosial yang akrab dan bermakna dengan orang
Pada kenyataannya, banyak wanita dewasa yang masih bertahan
dengan status lajangnya. Olson & DeFrain (2003) berpendapat bahwa
banyak faktor yang mempengaruhi bertambahnya individu yang hidup
sendiri. Salah satunya adalah pendidikan dan karir, yang menjadikan orang
dewasa menunda usianya untuk menikah. Selain itu, belum ketemu jodoh
atau masih ingin menikmati kebebasan hidup lajang merupakan alasan lain
individu menunda perkawinannya.
Sementara itu, beberapa masyarakat belum bisa menerima
keberadaan wanita dewasa lajang sehingga muncul pandangan negatif
mengenai wanita lajang. Wanita dewasa yang belum juga menikah pada
usia dewasanya, seringkali dianggap sebagai pribadi yang kurang feminin,
kurang mampu mencintai dan merawat, kurang menarik secara seksual,
egois, galak, judes, kesepian dan terlalu pemilih. Oleh karena itu, wanita
usia lajang yang berusia 30 tahun sering mendapat desakan dari
orang-orang di sekitar mereka untuk segera menikah (Laswell & Laswell, 1987).
Perilaku lingkungan sosial yang sering mendesak individu lajang untuk
menjalin hubungan dengan lawan jenis seringkali membuat individu
semakin enggan untuk terlibat dalam pergaulan di lingkungannya. Pada
saat-saat tertentu, kesulitan untuk menjalin hubungan akrab, untuk
menerima cinta dan menjaga kestabilan emosi akan sangat terasa, yang
akan menambah beban individu, dan pada gilirannya akan memberikan
Di sisi lain, status lajang juga memiliki segi positif bagi individu,
terutama bagi wanita. Individu yang masih lajang memiliki peluang yang
lebih banyak untuk mandiri dan mengembangkan pribadinya, misalnya
untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mengembangkan karir
dan terlibat aktif dalam pelayanan masyarakat dibandingkan dengan
individu yang berkeluarga. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wanita
lajang akan lebih mampu untuk bertahan daripada wanita yang telah
menikah. Hal ini disebabkan karena wanita yang telah menikah cenderung
kehilangan identitas dirinya. Identitas wanita hampir selalu melebur dalam
identitas suaminya, misalnya setelah menikah akan kehilangan nama
gadisnya dan akan dikenal dengan nama suaminya. Selain itu, wanita yang
telah menikah akan dihadapkan pada peran ganda antara pekerjaan dan
rumah tangga ketika wanitatersebut memilih untuk bekerja. Namun, ketika
tidak bekerja, ia akan sangat tergantung kepada pasangannya.
Kelebihan-kelebihan tersebut di atas tentunya memberikan dampak
positif bagi kesejahteraan psikologis wanita lajang. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa sebenarnya ada faktor-faktor yang dapat
meningkatkan ataupun menurunkan kesejahteraan psikologis individu
terlepas dari status perkawinannya. Faktor-faktor tersebut antara lain latar
belakang keluarga, latar belakang budaya, norma-norma masyarakat yang
D. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah: “Bagaimanakah kesejahteraan psikologis wanita lajang pada usia
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari isu-isu tertentu
secara mendalam dan mendetail karena pengumpulan data tidak dibatasi
pada kategori-kategori tertentu (Poerwandari, 2005). Selain itu, tujuan dari
penelitian ini adalah memahami suatu kasus yang dialami oleh manusia
dalam segala kompleksitasnya (Poerwandari, 2005). Dengan pendekatan
kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam tanpa
mengurangi makna dari informasi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang
difokuskan pada fenomena tertentu (penelitian fenomenologis), yaitu
memahami tentang respon atau keberadaan manusia, bukan sekedar
memahami bagian-bagian yang spesifik atau khusus. Tujuan penelitian
fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami
oleh seseorang dalam kehidupannya, termasuk interaksinya dengan orang
lain. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti
peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam
situasi-situasi tertentu (Moleong, 2008).
Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang
akan menggambarkan tentang kesejahteraan psikologis wanita lajang yang
akan nampak dari penggalian pengalaman-pengalaman dan interaksinya
dengan orang lain yang dialami oleh subjek dalam kehidupan sehari-hari,
maka penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi.
B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan
psikologis wanita lajang usia dewasa awal.
C. Batasan Variabel Penelitian
Definisi kesejahteraan psikologis wanita lajang usia dewasa awal
adalah gambaran psikologis wanita berusia tiga puluh tahun ke atas yang
belum pernah menikah, berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologis
positif yang dikemukakan oleh para ahli psikologi, yang diungkap melalui
aspek-aspek kesejahteraan psikologis. Aspek-aspek tersebut antara lain:
penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi diri,
penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pengembangan pribadi (Ryff,
1989).
Penerimaan diri merupakan kemampuan untuk menerima semua
pengalaman hidup serta segala segi pribadi, baik itu kelebihan maupun
kekurangan. Relasi positif dengan orang lain merupakan kemampuan
menjalin hubungan yang hangat dan terdapat rasa percaya dengan orang
sikap diri dan pilihan-pilihan tanpa tekanan dari pihak luar. Penguasaan
lingkungan adalah kemampuan mengendalikan berbagai aktivitas dalam
kehidupan sehari-hari yang kompleks. Tujuan hidup merupakan dimensi
yang memberi tujuan, makna dan arah pada individu dalam kehidupan.
Pengembangan pribadi merupakan kemampuan individu untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan fase kehidupannya.
Tipe wanita lajang dalam penelitian ini bersifat sementara dengan
keterpaksaan (Temporary Involuntary Singlehood), yaitu wanita lajang yang
belum pernah menikah dan berkeinginan untuk menikah akan tetapi belum
menemukan pasangan hidup yang tepat. Pemilihan tipe ini berdasarkan pada
tipologi lajang yang dikemukakan oleh Stein (dalam Laswell & Laswell,
1987). Peneliti memilih tipe lajang ini dengan alasan bahwa wanita lajang
yang peneliti cari tidak menjatuhkan pilihan hidupnya untuk melajang
sehingga masih ada keinginan dalam dirinya untuk menikah. Dalam
masyarakat Indonesia, menikah dan memiliki anak masih menjadi prioritas
hidup wanita, sedangkan hidup melajang akan dicap sebagai wanita yang
tidak lengkap (Jones, dalam Suryani 2007). Selain itu, peneliti juga ingin
melihat apakah karir menjadi alasan para wanita lajang menunda
perkawinannya, seperti hasil penelitian Permanasari (2003) yang
mengatakan bahwa semakin tinggi motivasi wanita untuk berkarir maka
D. Subjek Penelitian
Subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini harus memenuhi
kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu:
1. Wanita berusia 30 tahun ke atas.
2. Masih lajang atau belum pernah menikah.
3. Bekerja.
4. Pendidikan terakhir S1
5. Berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peneliti menentukan usia 30 tahun sebagai usia minimal subjek karena
mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Levinson (dalam Berk,
2007) bahwa usia 30 merupakan usia transisi dimana individu akan
mengalami krisis ketika mereka tidak mencapai kepuasan dalam ikatan
keintiman. Sedangkan kriteria wanita bekerja ini dengan pertimbangan
bahwa dunia kerja saat ini menuntut prestasi tinggi dan menyita banyak
waktu dari individu yang akan menyebabkan individu menganggap
perkerjaannya lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
dan semakin larut dalam pekerjaannya. Selain itu, dengan bekerja individu
akan berinteraksi dengan banyak orang yang memungkinkan munculnya
desakan-desakan atau gunjingan-gunjingan rekan kerja terhadap wanita
lajang untuk segera menikah.
Ketentuan bahwa subjek harus berdomisili di Daerah Istimewa
Selain itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta, wanita lajang di atas usia 30
tahun belum sepenuhnya bisa diterima.
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Poerwandari (2005)
mengemukakan bahwa wawancara kualitatif dilakukan untuk memperoleh
pengetahuan tentang makna subyektif yang dipahami oleh individu
berkenaan dengan topik yang diteliti. Selain itu, wawancara kualitatif juga
bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak
dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Apabila dilihat berdasarkan
sasaran penjawabnya, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara
perorangan, yaitu proses tanya-jawab tatap muka berlangsung secara
langsung antara pewancara dengan seorang yang diwawancarai. Alasan
peneliti meggunakan wawancara ini adalah agar mendapatkan data yang
lebih intensif.
Wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan sistem terbuka.
Hal ini berarti bahwa individu yang diwawancarai mengetahui dan
menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Di samping itu, individu
yang diwawancarai juga mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara.
Cara ini sesuai dengan penelitian kualitatif yang berpandangan terbuka
bersifat semiterstruktur yaitu peneliti menggunakan panduan wawancara
atau daftar pertanyaan yang akan diajukan dan dapat digunakan untuk
menemukan info tetapi tidak terikat pada pertanyaan dalam panduan
tersebut. Pertanyaan tidak harus sesuai dengan urutan, dapat berubah dan
bertambah sesuai dengan kondisi, situasi maupun respon subjek penelitian
ketika proses wawancara berlangsung. Pertanyaan tambahan adalah
pertanyaan yang dianggap relevan sebagai probing atas jawaban subjek
penelitian. Poerwandari (2005) mengatakan bahwa dalam proses wawancara
ini, peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum.
Pedoman wawancara dengan metode pedoman umum nantinya akan
digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai hal-hal yang harus
dibahas, sekaligus sebagai daftar pengecek apakah hal-hal relevan tersebut
telah dibahas atau ditanyakan. Peneliti merekam wawancara dengan alat
perekam kemudian dituliskan dalam bentuk teks kata per kata atau verbatim.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi sebagai data
tambahan yang berupa catatan lapangan dari hasil-hasil pengamatan selama
proses penelitian. Catatan lapangan, menurut Bogdan dan Biklen (dalam
Moleong, 2008), adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat,
dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi
terhadap data dalam penelitian kualitatif.
Protokol penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai
berikut :
2. Peneliti meminta izin kepada subjek untuk berpartisipasi dalam
penelitian yang akan dilakukan.
3. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian.
4. Penelitian mengumpulkan data melalui wawancara dengan subjek.
5. Observasi sebagai data tambahan dilakukan oleh peneliti ketika peneliti
bersama dengan subjek (pada saat pengambilan data).
F. Metode Analisis Data
Pengolahan dan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data
dengan rapi, sistematis, dan selengkap mungkin. Hal ini memungkinkan
peneliti untuk memperoleh kualitas data yang baik, mendokumentasikan
analisis yang dilakukan, serta menyimpan data dan analisis yang berkaitan
dalam penyelesaian penelitian. Langkah penting yang pertama adalah
membubuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh. Koding dimaksudkan
untuk dapat mengorganisasi dan mensistematisasi data secara lengkap dan
mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang
dipelajari. Langkah-langkah koding yang dilakukan adalah menyusun
transkripsi verbatim, secara urut dan kontinyu melakukan penomoran pada
baris-baris transkripsi, kemudian dilanjutkan dengan memberikan nama
untuk masing-masing berkas dengan kode tertentu. Wawancara yang
dilakukan dalam penelitian ini diberi kode sebagai berikut :
1. WS1.I. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek pertama untuk
2. WS1.II. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek pertama untuk
kedua kali.
3. WS1.III. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek pertama
untuk ketiga kali.
4. WS2.I. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek kedua untuk
pertama kali.
5. WS2.II. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek kedua untuk
kedua kali.
6. WS2.III. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek kedua untuk
ketiga kali.
7. WS3.I. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek ketiga untuk
pertama kali.
8. WS3.II. adalah kode verbatim wawancara dengan subjek ketiga untuk
kedua kali.
Sedangkan aspek-aspek kesejahteraan psikologis yang digunakan dalam
penelitian ini diberi kode sebagai berikut :
1. PD adalah kode untuk aspek penerimaan diri.
a. PD1 adalah kode untuk penerimaan masa lalu subjek.
b. PD2 adalah kode untuk penerimaan kehidupan subjek saat ini.
c. PD3 adalah kode untuk penerimaan subjek terhadap kekurangan dan
kelebihan dirinya.
2. HP adalah kode untuk aspek hubungan positif dengan orang lain.
a. HP1 adalah kode untuk hubungan dengan keluarga.
b. HP2 adalah kode untuk hubungan dengan teman.
c. HP3 adalah kode untuk hubungan dengan sahabat.
d. HP4 adalah kode untuk hubungan dengan lawan jenis.
e. HP5 adalah kode untuk hubungan dengan rekan kerja.
f. HP6 adalah kode untuk hubungan dengan lingkungan sosial.
g. HP7 adalah kode untuk kemampuan subjek untuk berempati dan
memiliki afeksi yang kuat.
3. OD adalah kode untuk aspek otonomi diri.
a. OD1 adalah kode untuk sikap mandiri yang dimiliki subjek.
b. OD2 adalah kode untuk kemampuan subjek dalam mengatasi
tekanan dari lingkungan.
4. PL adalah kode untuk aspek penguasaan lingkungan.
a. PL1 adalah kode untuk kemampuan subjek mengontrol serangkaian
aktivitas.
b. PL2 adalah kode untuk kemampuan subjek memanfaatkan
lingkungan secara efektif.
c. PL3 adalah kode untuk kemampuan subjek melaksanakan tanggung
jawab dengan baik.
5. TH adalah kode untuk aspek tujuan hidup.