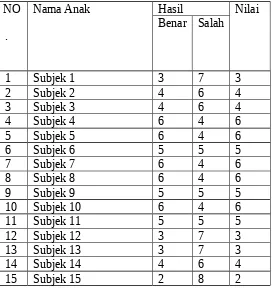PENELITIAN KUANTITATIF
PENINGKATAN KECERDASAN EMOSI MELALUI METODE SIMULASI BERUPA SOSIODRAMA “BAWANG MERAH BAWANG PUTIH” PADA ANAK USIA DINI
KELOMPOK B
TK BAITUL MU’MIN – SURABAYA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2015
PENELITIAN KUANTITATIF
PENINGKATAN KECERDASAN EMOSI MELALUI METODE SIMULASI BERUPA SOSIODRAMA “BAWANG MERAH BAWANG PUTIH” PADA ANAK USIA DINI
KELOMPOK B
TK BAITUL MU’MIN - SURABAYA
Oleh:
1. Novia Solichah (B77212110)
2. Siti Maisyaroh (B07212030)
3. Siti Auliyatus Sholawati (B07212029)
4. Fitri Yanuar Aini (B07212050)
JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UIN SUNAN-AMPEL SURABAYA
2015 BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Emosi merupakan perasaan yang selalu menyertai perbuatan yang ditandai oleh
perubahan-perubahan fisik manusia. Seperti gembira, cinta, marah, takut, cemas, malu,
kecewa, dan benci. Setiap manusia dalam segala rentang usia, pada umumnya selalu
menyertakan emosi dalam setiap tindakannya.
Sering kali ketika manusia berbuat sesuatu kurang dapat mengendalikan
emosinya, sehingga emosi negatiflah yang digunakan dalam menyelesaikan suatu
masalah. Emosi negatif itu seperti : marah, benci, dendam, tempramen. Emosi negatif itu
menyebabkan akibat yang buruk, seperti: perkelahian antar pelajar, bullying, kekerasan
dalam rumah tangga, dan lain-lain.
Akhir-akhir ini banyak pemberitaan tentang kenakalan pelajar karena
ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan emosi negatifnya. Seperti dilansir pada
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) oleh Davit Setyawan mengatakan bahwa tawuran pelajar memprihatinkan di dunia pendidikan.1
Perkelahian, atau yang sering disebut tawuran, sering terjadi di antara pelajar.
Bahkan bukan hanya antar pelajar SMU, tapi juga sudah melanda sampai ke
kampus-kampus. Ada yang mengatakan bahwa berkelahi adalah hal yang wajar pada remaja.
Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran ini sering
terjadi. Data di Jakarta misalnya (Bimmas Polri Metro Jaya), tahun 1992 tercatat 157
kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan
10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2
anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2
anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat
dari tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering
tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus.
Selain emosi negatif yang banyak terjadi pada pelajar, para orang tua sering kali
tidak bisa mengontrol emosi negatif yang ada pada dirinya. Hal ini sesuai dengan berita
yang dilansir pada Komisi Nasional Perlindungan Anak2 oleh Samsul Ridwan
mengatakan bahwa Merujuk data layanan pengaduan masyarakat melalui Hotline
Service dalam bentuk pengaduan langsung, telephone, surat menyurat maupun elektronik,
sepanjang tahun 2011 KomNas Anak menerima 2.386 kasus. Sama artinya bahwa setiap
bulannya KomNas Anak menerima pengaduaan masyarakat kurang lebih 200 (dua ratus)
pengaduan pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 98% jika dibanding
dengan pengaduan masyarakat yang di terima Komisi Nasional Perlindungan Anak pada
tahun 2010 yakni berjumlah 1.234 pengaduan. Dalam laporan pengaduan tersebut,
pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata-mata pada tingkat kuantitas jumlah saja
yang meningkat, namun terlihat semakin komplek dan beragamnya modus pelanggaran
hak anak itu sendiri. Pengaduan hak asuh (khususnya perebutan anak pasca perceraian)
misalnya, mendominasi pengaduan sepanjang tahun 2011 ini.
Sepanjang tahun 2011 ini, kasus tawuran cukup banyak mendapat sorotan dan
menjadi topik hangat ditengah-tengah masyrakat. Maraknya peristiwa kekerasan antar
sesama anak sekolah merupakan fenomena sosial yang berkembang ditengah-tengah
masyarakat remaja. Sementara itu, sepanjang tahun 2011, Komisi Nasional Perlindungan
anak mencatat ditemukan 339 kasus tawuran. Kasus tawuran antar pelajar di Jabodetabek
meningkat jika dibanding 128 kasus yang terjadi pada ahun 2010. KomNas Anak
mencatat, dari 339 kasus kekerasan antar sesama pelajar SMP dan SMA ditemukan 82
diantaranya meninggal dunia, selebihnya luka berat dan ringan.
Dari beberapa kasus yang dikemukakan di atas, kasus-kasus tersebut terjadi
karena ketidak mampuan setiap orang dalam mengontrol emosi negatifnya, untuk itu
perlu adanya kecerdasan emosi yang di ajarkan sejak anak usia dini.
Berdasarkan teori perkembangan Piaget (dalam Trianto 2011), maka anak yang
berada di TK/RA dan usia kelas awal SD/MI adalah anak yang berada pada rentangan
usia dini. Masa usia dini merupakan masa yang pendek tetapi merupakan masa yang
sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi
yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Hal ini
sesuai dengan berita republika.co.id, Surabaya. Faktor Ini Pengaruhi Tingkat
Keberhasilan Anak.3
Kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) mempengaruhi keberhasilan anak
pada masa mendatang karena aspek tersebut dapat mengarahkan pikiran dan tindakan
mereka dalam kehidupan sehari-hari.
"Dulu kecerdasan identik dengan Intelectual Quotient (IQ) dan ternyata IQ hanya
mempengaruhi 20 persen keberhasilan individu di masyarakat. Sementara, 80 persen
ditentukan kecerdasan emosi," kata Psikolog, Rose Mini di Surabaya, Sabtu (21/2).
Romi mengungkapkan ketika kecerdasan emosi anak terasah dengan baik ada
beberapa manfaat yang diperoleh seperti bergaul dan menghargai orang lain. Selain itu,
anak akan memperlihatkan kasih sayang kepada orang tuanya, lancar berkomunikasi, dan
mudah menerima stimulasi lingkungan untuk membentuk multitalentanya.
"Stimulasi kecerdasan emosi pada masa 1.000 hari kehidupan awal anak tentu
akan mempersiapkan landasan emosi anak yang lebih stabil pada masa mendatang.
Dengan begitu, anak sudah terbiasa mempergunakan kecerdasan emosi itu," ujar Romi.
Hal ini dikuatkan dengan pemberitaan di Indosiar.com yang menyatakan
Kecerdasan Emosi Bekal Terpenting Anak.4 indosiar.com - Kecerdasan emosi kini
menjadi perhatian dan prioritas. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam
mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat
berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil
secara akademis. Selain itu, kecerdasan emosi juga sangat penting dalam hubungan pola
asuh anak dengan orang tua. Hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of
Missouri-St. Louis, yang diterbitkan dalam sebuah sebuah buletin, Character Educator,
oleh Character Education Partnership, dijelaskan tentang keberhasilan kecerdasan emosi
terhadap keberhasilan akademik.
Kecerdasan emosi hendaknya diterapkan sejak dini, karena menurut pendapat
Rosmalia Dewi (2005: 3) menyebutkan bahwa Masa usia dini sering disebut sebagai
golden age (masa emas). Pada masa emas ini anak sedang dalam masa sangat mudah
untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri mereka.Masa setiap aspek
pengembangan seperti sosial emosional, kognitif, bahasa, motorik halus, motorik kasar,
dankreativitas yang ada dalam diri anak dapat berkembang dengan pesat.
Perkembangan emosi anak hingga usia 6 tahun ialah anak dapat mengekspresikan
reaksi terhadap orang lain, dapat mengontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan orang
tua, dan telah mulai belajar tentang benar dan salah. Untuk perkembangan kecerdasannya
anak usia TK/RA ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi,
mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatnya
perbendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat, dan berkembangnya
pemahaman terhadap ruang dan waktu. 5
Namun dalam kenyataan yang diperoleh peneliti, di TK Baitul Mu’min,
perkembangan emosi siswa kelompok B masih belum sesuai dengan teori. Sebagian
siswa masih belum mampu berpisah dengan orang tua, kira-kira ada 12 siswa. Sebagian
lain masih belum mampu mengontrol emosinya, sering bertengkar dan mengejek antar
teman. Bahkan ada yang sampai saling memukul sehingga keduanya terluka parah hingga
di bawa rumah sakit. Para siswa masih belum mampu membedakan perbuatan yang benar
dan yang salah.
Kecerdasan emosi anak perlu ditingkatkan dan dikembangkan sejak dini. Banyak
metode yang dapat di aplikasikan dalam pembelajaran di kurikulum TK, salah satu
metode yang digunakan adalah metode simulasi. Metode simulasi merupakan salah satu
metode mengajar yang cara penyajiannya menggunakan situasi tiruan yakni
memperagakan proses terjadinya suatu cerita. Metode simulasi memiliki beberapa jenis,
antara lain: sosiodrama, psikodrama, role playing, per teaching, dan simulasi game.
Namun dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik
sosiodramadalam meningkatkan kecerdasan emosi anak, karena berdasarkan penelitian
terdahulu teknik sosiodrama sangat efektif untuk meningkatkan keccerdasan emosi.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah metode
pembelajaran simulasi yang berupa sosiodrama dapat meningkatkan kecerdasan emosi
5Trianto. Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA dan Anak Kelas Awal SD/MI.
anak, dan penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Peningkatan Kecerdasan Emosi
Melalui Metode Simulasi Berupa Sosiodrama Bawang Merah Bawang Putih pada Anak
Usia Dini Kelompok B TK Baitul Mu’min - Surabaya”.
B. Rumusan Masalah
Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar penelitian ini tidak terjadi
kerancuan, maka penulis dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan
diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Peningkatan Kecerdasan Emosi
Melalui Metode Simulasi Berupa Sosiodrama Bawang Merah Bawang Putih pada Anak
Usia Dini Kelompok
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Kecerdasan
Emosi Melalui Metode Simulasi Berupa Sosiodrama Bawang Merah Bawang Putih pada
Anak Usia Dini Kelompok B.
D. Manfaat Penelitian
Dari tujuan diadakanannya penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka adapun
manfaat penelitian, yaitu :
a. Manfaat secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembelajaran, dalam rangka
mengembangkan ilmu, khususnya PG-PAUD, Psikologi Perkembangan dan
Psikologi Pendidikan.
b. Manfaat secara praktis
1. Penelitian ini juga menjadi masukan agar para guru dapat meningkatkan
2. Bagi para orang tua, diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan emosi anak
dengan mengajak si anak menggunakan metode simulasi berupa sosiodrama
kepada anaknya sejak dini.
3. Bagi para mahasiswa yang menempuh pendidikan guru PAUD, psikologi
perkembangan, dan Psikologi pendidikan agar menjadi pengetahuan baru
tentang metode simulasi berupa sosiodrama yang dapat meningkatkan
kecerdasan emosi anak.
E. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini membahas tentang peningkatan kecerdasan emosi melalui metode
simulasi berupa sosiodrama bawang merah dan bawang putih pada anak usia dini
kelompok B. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan memahami perasaan dan emosi,
baik pada diri sendiri maupun orang lain. Metode simulasi dapat diartikan cara penyajian
pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep,
prinsip, atau keterampilan tertentu. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain
peran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan
yang menyangkut hubungan antarmanusia.
Kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui metode simulasi berupa
sosiodrama, ini dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Alfasnur (2013) berjudul “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Emosional Melalui Metode
Sosiodrama Pada Siswa Kelas VIII Smp Negeri 1 Sleman” mengatakan bahwa
kecerdasan emosional dapat ditingkatkan melalui metode Sosiodrama.6
Selain itu, dalam penelitian Darmansyah (2007), terungkap bahwa siswa yang
diberikan perlakuan pembelajaran dengan sisipan huor, ternyata kecerdasan
emosionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar yang dilaksanakan secara
normal.7 Nurnaningsih (2011), hasil penelitian enunjukkan bahwa bimbingan kelompok
efektif untuk meningkatkan kcerdasan emosional siswa. Program bimbingan kelompok
ini direkomendasikan untuk dipertimbangkan sebagai salah satu kerangka kerja dalam
pngembangan program bimbingan dan konseling unuk meningkatkan kecerdasan
emosional siwa. 8
Baskara dkk (2011), telah melakukan penelitian tentang pengaruh dari
keikutsertaan individu dalam program meditasi terhadap kecerdasan emosi. 9Ada juga
yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan Emosi dengan
kemampuan coping adaptif, yang dibuktikan dalam penelitiannya Saptoto (2010), based
on these minor hipotesis, it is concluded hat generally there is correlation between
emotional intelligence and adaptive coping ability.10
Dari beberapa penelitian terhadulu tentang upaya meningkatkan kecerdasan emosi
di atas, peneliti lebih tertarik dengan upaya meningkatkan kecerdasan emosional melalui
metode sosiodrama. Karena menurut teori Albert Bandura telah dijelaskan bahwa anak
usia dini adalah masa meniru, sehingga pengoptimalan kognitif-emosional anak usia dini
dapat dioptimalkan dengan metode sosiodrama.
7 Darmansyah. Trategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012. Hlm.134 8 Nurnaningsih. Bimbingan Kelompok untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Edisi khusu no.1, Agustus
2011.
9 Baskara dkk. Kecerdasan Emosi ditinjau dari keikutsertaan dalam program meditasi. Jurnal psikologi vol. 35, No. 2,juni 2011. 101-115
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari segi
subjek, penelitian kami menggunakan subjek yang berusia prasekolah 6-7, dan dari segi
metodenya, meskipun penelitian ini menggunakan metode sosiodrama, namun drama
yang akan ditirukan oleh subjek berbeda yakni drama “bawang merah bawang putih”, hal
ini dipilih karena dari cerita ini, siswa akan mendapatkan nilai-nilai moral yang baik
BAB II KAJIAN TEORI
A. Definisi PAUD
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.11
Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. mulai terbentuk pada usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut the golden age (usia emas). Atas dasar ini, disimpulkan bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini, yaitu melalui PAUD.
Merujuk pada undang-undang nomer 20 tahun2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistematik. Artinya, pendidikan harus dimulai dari usia dini yaitu
pendidikan anak usia dini (PAUD). Dengan demikian, PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dalam penjelasan selanjutnya, PAUD dapatdiselenggarakn melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), RaudhatulAthfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak(TPA) atau benuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau
Perkembangan ini demikian pentingnya sehingga mendapat perhatian yang cukup luas dari para pakar psikologi/pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, agar mampu mengasuh dan membimbing anak dengan efektif, seorang guru PAUD seyogiyanya menguasai konsep perkembangan anak usia dini.13
I. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pengertian
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan pelatihan. Kemudian dalam arti luas, pendidikan adalah segala macam bentuk pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan
12Suyadi. PSIKOLOGI BELAJAR PAUD. (2010, Hal 9) jogjakarta : PT PUSTAKA INSAN MADANI
masyarakat untuk mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin sejak lahir sampai akhir hayat.14
Pendidikan anak usia dini merupakan serangkaian upaya sistematis dan terporgram dalam melakukan pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaniah agar anak memiliki kesiapan untuk masuk ke pendidikan yang lebih lanjut.
2. UU NO.23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak memperolleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”
3. UU NO.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, pasal 1, butir 14, yang menyatakan:
“Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.” b. Landasan Filosofis
Pendidikan adalah suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang lebih baik. Standar manusia yang “baik” berbeda antar masyarakat, bangsa atau negara, karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak dan kecerdasan. Menurut Wittrock, sebagaimana diikuti Tim Pengembang Kurikiulum PAUD, ada perkembanga wilayah otak yang mengalami peningkatan pesat, yaitu pertumbuhan serabut dendrit, kompleksitas hubungan sinepsis, dan pembagian sel saraf. Ketiga wilayah otak tersebut sangat penting untuk dikembangkan sejak usia dini.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jean Piaget (1972). Ia menyatakan “Anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru bisa menentukan anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi yang terpenting agar ana dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri, dan ia harus menemukannya sendiri.“17
3. Tujuan
Secara garis besar, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapt menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 4. Prinsip-prinsip dalam Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
Dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini, terdapat prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.
a. Mengutamakan kebutuhan anak
b. Belajar melalui bermain atau bermain seraya belajar c. Lingkungan yang kondsif dan menantang
d. Menggunakan pembelajaran terpadu dalam bermain
e. Mengembangkan berbagai kecakapan atau ketrampilan hidup (life skills)
f. Menggunakan berbagai media atau permainan edukatif dan
sumber belajar
g. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang18 5. Standar kompetensi Anak Usia Dini
Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas,
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemberian layanan pendidikan bagi anak sejak usia dini (0-6 tahun) masih sangat rendah. Hal itu disebabkan antara lain karena kurangnya
sosialisasi kepada masyrakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.
Meskipun selama ini pemerintah dan masyarakat telah menyelenggarakan berbagai program layanan pendidikan bagi anak usia dini, namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak anak usia dini yang belum memperoleh layanan pendidikan.
Banyak anggapan sebelumnya yang mengatakan bahwa pendidikan yang tepat diberikan kepada anak adalah pada saat anak mulai masuk usia kematangan yang siap untuk bersekolah yaitu antara 5-7 tahun. Sedangkan, yang sebenarnya adalah bahwa pendidikan bisa dimulai dari usia 0-6 tahun.
Dengan demikian, urgensi pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial, dan emosional.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
hubungan yang sangat kuat antara perkembangan yang dialami
anak pada usia dini dan keberhasilan mereka dalam kehidupan
selanjutnya.20
II. Pembentukan Karakter Anak Usia Dini
a. Karakter sebagai esensi pendidikan anak usia dini
Ada empat pilar yang menopang pembangunan bangsa, antara lain pilar
ekonomi, pilar politik, pilar kesehatan, dan pilar kesehatan. Dari keempat pilar
tersebut, pendidikan merupakan pilar yang paling utama di antara tiga pilar
lainnya. Kuatnya pilar pendidikan akan menguatkan pilar ekonomi, pilar politik,
dan pilar kesehatan.
Dalam konteks kenegaraan, penyelenggaraan pendidikan secara yuridis
formal di atur dalm Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2004. Dalam
Undang-undang tersebut, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan demikian, pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia
merupakan upaya untuk membangun bangsa yang cerdas secara fisik, intelektual,
emosional, dan spiritual. Hal ini selaras dengan pendapat Muhammad Roqib yang
menyatakan bahwa pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana terkait dengan
gerak dinamis, positif,dan kontinu setiap individu menuju idealitas kehidupan
manusia agar mendapatkan milai terpuji. Aktivitas individu tersebut meliputi
pengembangan kecerdasan pikir (rasio, kognitif), dzikir (afektif, rasa, hati,
spiritual), dan keterampilan fisik (psikomotorik).
Sementara itu, dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang berimna, dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
Dari deskripsi tentang fungsi dan tujuan pendidikan di atas, maka dapat
kita simpulkan bahwa dalam pendidikan terdapat proses transformasi pengetahuan
dan transformasi nilai. Transformasi pengetahuan akan menghasilkan peserta
didik yang cerdas secara intelektual, sedangkan transformasi nilai menghasilkan
peserta didik yang berkarakter. Dalam perjalannnya, terjadi perdebatan antarpakar
pendidikan tentang mana yang lebih utama, menghasilkan anak yang pintar atau
menghasilkan anak yang berkarakter?.
Disadari ataupun tidak, bangsa Indonesia sedang menuai akibat dari
dilakukannya praktik pendidikan yang mengabaikan aspek afektif (karakter).
Maka, kini dekadensi moral menimpa bangsa kita. Data hasil survei mengenai
seks bebas di kalangan remaja Indonesia menunjukkan 63% remaja Indonesia
telah melakukan seks bebas. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Gangguan
Sosial DKI Jakarta, pelajar SD, SMP, SMA, yang terlibat tawuran mencapai 0,08
persen atau sekitar 1.318 persen peserta didik dari total 1.647.835 peserta didik di
DKI Jakarta, bahkan akibat dari tawuran tersebut, 26 peserta didik meninggal
dunia.
Untuk mengatasi problematika di atas, pendidikan di Indonesia harus
diarahkan pada pembentukan karakter. Bung Karno, Bapak pendiri bangsa
menegaskan bahwa “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan
pembentukan karakter karena pembentukan karakter inilah yang akan membuat
pembentukan karakter tidak dilakukan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa
kuli.21
Yahya Khan mengartikan karakter dengan sikap pribadi yang stabil dari
hasil konsolidasi secara progresif dan dinamis yang mengintregasikan antara
pernyataan dan tindakan. Sementara menurut penulis, karakter adalah cara brpikir
dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja
sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan karakter sendiri merupakan usaha untuk mendidik anak agar
mereka dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam
kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif
kepada lingkungannya. Dalam pendidikan karakter, ada tiga gagasan penting,
yaitu proses tranformasi nilai-nilai, ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, dan
menjadi satu dalam perilaku.
Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan
dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter anak
didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan
anak didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan
pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasikan serta mempersonalisasi
nilai-nilai karakter yang terwujud dalam perilaku sehari-hari.
Dari deskripsi di atas, pendidikan karakter dapat dilaksanakan dalam
lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan
karakter dapat dilaksanakan sedini mungkin, bukan hanya dimulai ketika anak
belajar di SD, SMP, dan SMA saja, melainkan pula sudah dilaksanakan sejak anak
belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini atau yang sering kita kenal
dengan akronim PAUD. Ada dua tujuan diselenggarakannya PAUD, sebagai
berikut :
1. Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan
berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki
kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi
kehidupan di masa dewasa.
2. Membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik di
sekolah).
PAUD menyelenggarakan pendidikan yang menitikberatkan pada
peletakan dasar ke beberapa arah berikut ini.
1. Pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar). 2. Kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan
spiritual).
3. Sosioemosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi yang
disesuaikan dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan anak usia dini.
B. The Golden Ages
eksplorasi, masa identifikasi/imitasi, masa peka,masa bermain,dan masa trozt alter 1 (masa membangkang tahap 1).22
Periode emas adalah masa dimana otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Periode ini hanya berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu 0-6 tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir, sampai usia 4 (empat) tahun adalah masa-masa yang paing menentukan. Periode ini pula yang disebut-sebut sebagai epriode emas atau yang lebih dikenal sebagai The Golden Ages.
Mengapa periode itu disebut sebagai masa keemasan?Sebab, pada masa itu otak anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.Dan, otak merupakan kunci utama bagi pembentukan kecerdasan anak. Setelah lahir hingga usia 2 tahun, sel-sel saraf pada bayi yang belum matang dan jaringan urat saraf yang masih lemah terus tumbuh dengan cepat dan dramatis mencapai kematangan seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Pada saat lahir, berat otak bayi seperdelapan dari berat totalnya atau sekitar 25% dari berat otak dewasanya.Pada ulang tahun ke dua, otak bayi sudah mencapai kira-kira 75% dari otak dewasanya. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika anak berusia 8 sampai 18 tahun. Pertumbuhan fungsional sel-sel otak tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung, baik dalam situasi pendidikan keluarga, masyarakat, maupun sekolah.
Para ahli sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung 1 kali sepanjang rentang kehidupan manusia.23
Oleh karena itu, kunci pembentukan kecerdasan otak anak adalah pada usia dini atau periode emas ini. Berkaitan dengan periode emas sebagai kunci pembentukan kecerdasan anak tersebut, Deborah
Stipek menyatakan bahwa anak usia dini menaruh harapan yang tinggi untuk berhasil dalam mempelajari segala hal, meskipun dalam praktiknya selalu buruk. Artinya, pada usia ini, anak dapat dididik untuk melalukan apa saja (segala hal) dan mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk berhasil, meskipun dalam praktiknya sangat buruk bahkan terkesan mustahil.24
C. Perkembangan Kognitif I. Definisi Kognitif
Manusia adalah makhluk Tuhan yang telah diciptakan secara sempurna dan istimewa, serta dikaruniai akal dan pikiran. Melalui akal dan pikiranlah manusia dapat hidup dan bersosialisasi dengan sesama serta makhluk lainnya. Kemampuan kognitif ini berisikan akal dan pikiran manusia yang harus dikembangkan bersamaan dengan kemampuan lainnya (bahasa,sosial–emosional,moral dan agama).Pamela Minet mendefinisikan bahwa perkembangan intelektual adalah sama dengan perkembangan mental, sedangkan perkembangan kognitif adalah perkembangan pikiran. Pikiran adalah bagian dari proses berpikir otak.
Memahami psikologi perkembangan kognitif pada anak usia dini tidak bisa dilepaskan dari tokoh psikologi terkemuka yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya guna mengkaji hal ini. Tokoh ini adalah Jean Piaget (1896-1980).Salah satu teori Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui kegiatan atau aktivitas pembelajaran.Piaget menolak paham lama yang menyatakan bahwa kecerdasan adalah bawaan secara genetis.Ini terjadi pada setiap manusia, termasuk anak-anak.
Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal didalam pusat penyusunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir (Gagne,1967). Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap
sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada dipusat susunan syaraf. Beberapa ahli psikologis yang berkecimpung dalam pendidikan mendefinisikan intelektual atau kognitif dengan berbagai peristilahan:
1. Terman mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak.
2. Colvin mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
3. Henman mendefinisikan bahwa kognitif adalah intelektual ditambah dengan pengetahuan.
4. Hunt mendefinisikan bahwa kognitif adalah teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indra.
Sementara itu yang dimaksud dengan intelek adalah berpikir, sedangkan yang dimaksud dengan intelegensi adalah kemampuan
kecerdasan.Gardner dalam Munandar (2000), mengemukakan
bahwa pengertian intelegensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk mencipta karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih.25
Dalam rangka mengoptimalkan potensi kognitif pada seseorang, kita dapat melihat dari Teori Kognitif Jan Piaget
Perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat komulatif, artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Dengan demikian apabila terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu maka perkembangan selanjutnya akan mengalami hambatan.
Piaget membagi kognitif kedalam empat fase, yang diantaranya (Piaget, 1972:49-91):
1. Fase sensori motor (usia 0-2 tahun)
Dua tahun pertama kehidupan seorang anak berinteraksi dengan dunia sekitarnya, terutama melalui aktifitas
sensori( melihat, meraba, merasa, mencium dan mendengar) dan persepsinya terhadap gerakan fisik dan aktivitas yang berkaitan dengan sensori tersebut. Koordinasi aktivitas ini disebut dengan istilah sensori motor.
Fase sensori motor dimulai dengan gerakan-gerakan refleks yang dimiliki anak sejak lahir. Fase ini berakhir pada usia 2 tahun. Pada masa ini anak mulai membangun pemahamannya tentang lingkungannya melalui kegiatan sensorik motorik. Seperti: menggenggam, menghisap, melihat, melempar dan secara perlahan ia mulai menyadari bahwa suatu benda tidak menyatu dengan lingkungannya atau dapat dipisahkan dari lingkungan dimana benda itu berada. Anak pada masa ini juga mulai membangun pemahaman terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan kausalitas, bentuk dan ukuran, sebagai hasil pemahamannya terhadap aktivitas sensorimotor yang dilakukannya.
Pada akhir anak usia 2tahun anak sudah menguasai pola-pola sensorimotor yang bersifat kompleks seperti bagaimana cara menapatkan benda yang diinginkannya ( menarik, mengggemnggam atau meminta), menggunakan suatu benda dengan tujuan yang berbeda. Dengan benda yang ada ditangannya, ia mampu melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan ini merupakan awal kemampuan berpikir simbolik, kemmapuan memikirkan suatu objek tanpa kehadiran objek tersebut secara empirik.
2. Fase Praoperasional (2-7 tahun)
Pada fase ini anak mulai menyadari bahwa pemahamannya terhadap benda-benda yang ada disekitarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui aktifitas sensorimotorakan tetapi dapat juga dilakukan melalui aktifitas yang bersifat
telepon mainan atau berpura-pura menjadi bapak atu ibu dan kegiatan simbolik lainnya.Fase ini memberikan andil besar dalam kognitif anak. Fase ini aka sudah tidak berpiir secara operasinal yaitu suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menginternalisasikan suatu aktivitas anak yang memungkinkan anak mengaitkan dengan kegiatan yang telah dilakukannya sebelumnya.
Fase ini merupakan permulaan bagi anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikirannya.Oleh karena itu cra berfikir ada pada saat fase ini belum stabil dan tidak terorganisasi secara baik. Fase praoperasional dapat dibagi kedalam tiga sub fase, antara lain;
a. Sub fase fungsi simbolik
Fase ini terjadi pada saat anak usia 2-4 tahun. Masa ini anak telah mempunyai kemampuan untuk menggambarkan suatu objen secara fisik tidak hadir.Kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumah, menyusun puzzle, anak juga dapat menggambar manusia secara sederhana.
b. Sub fase berpikir egosentris
ia tidak mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan balok-balok itu dapat disusun menjadi rumah. Dengan kata lain anak belum memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis tentang apa yang ada dibalik suatu kejadian.26
II. Teori Dasar Perkembangan Kognitif
Pada rentang usia 3-4 sampai 5-6 tahun, anak mulai memasuki masa pra sekolah yang merupakan masa kesiapan untuk memasuki pendidikan formal yang sebenarnya di sekolah dasar. Menurut Montessori masa ini ditandai dengan masa peka terhadap segala stimulasi yang diterimanya melalui panca indera.Masa peka memiliki arti penting bagi perkembangan setiap anak. Itu artinya bahwa apabila orang tua mengetahui anaknya telah memasuki masa peka dan mereka segera member stimulasi yang tepat, maka akan mempercepat penguasaan terhadap tugas-tugas perkembangan pada usianya.27
Pieget berpendapat bahwa, anak pada rentang usia ini, masuk dalam perkembangan berpikir pra-operasional konkret. (Bryden&Vos, 2000). Hurlock (1999) menyatakan bahwa anak usia 3-5 tahun adalah masa permainan. Bermain dnegan benda atau alat permainan dimulai sejak usia satu tahun pertamadan akan mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Menurut Pieget, usia 5-6 tahun ini merupakan pra-operasional konkret. Pada tahap ini anak dapat memanipulasi objek symbol, termauk kata-kata yang merupakan karakteristik penting dalam tahapan ini.Hal ini dinyatakan dalam peniruan yang tertunda dan dalam imajinasi pura-pura dalam bermain.
Menurut Montessori dalam Patmonodewo (2000), masa peka anak yang berada pada usia 3,5 tahun ditandai dengan suatu keadaan dimana potensi yang menunjukkan kepekaan (sensitif)
26PLPG. Hal 4
untuk berkembang. Maka masa peka ini merupakan masa yang efektif bagi orang tua atau pendidik dalam memberikan pemahaman atau pembelajaran kepada anak melalui pemberian contoh-contoh konkrit atau berupa peragaan yang mendidik akan lebih efektif diterima oleh anak. Dalam kaitan itu, menurut Dewey dalam Soejono (1960), pendidik atau orang tua harus memberikan kesempatan pada setiap anak untuk dapat melakukan sesuatu, baik secara individual maupun kelompok sehingga anak akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Sekolah harus dijadikan laboratorium bekerja bagi anak-anak.28
Memahami psikologi perkembangan kognitif pada anak usia dini tidak bisa dilepaskan dari tokoh psikologi terkemuka yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya guna mengkaji hal ini. Tokoh ini adalah Jean Piaget (1896-1980).Salah satu teori Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui kegiatan atau aktivitas pembelajaran.Piaget menolak paham lama yang menyatakan bahwa kecerdasan adalah bawaan secara genetis.Ini terjadi pada setiap manusia, termasuk anak-anak.
Khususnya ada anak usia dini, Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui eksplorasi, manipulasi, dan konstruksi secara elaboratif. Lebih dari itu, Piaget juga menjelaskan bahwa karekterisasi aktivitas anak-anak juga berdasarkan pada tendensi-tendensi biologis yang terdapat pada semua organisme.Tendensi-tendensi tersebut mencakup tiga hal, yaitu asimilasi, akomodasi dan ekuilibrium.29
III. Teori Kognitif Sosial Bandur
Teori kognitif sosial (social cognitive theory) menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif , dan juga faktor perilaku, memainkan peran penting dalam
28Ahmad Susanto,PerkembanganAnakUsiaDini: PengantarDalamBerbagai Aspeknya,Jakarta:Kencana.2011. hal50)
pembelajaran. Faktor mungkin kognitif mungkin berupa ekspektasi murid untuk
meraih keberhasilan, faktor sosial mungkin mencakup pengamatan murid terhadap
perilaku orang tuanya. 30
Albert bandura (1986,1997,2000,2001)adalah salah satu arsitek utama teori
kognitif sosial. Dia mengatakan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat
mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Ingat
bahwa dalam pengkondisian operan,hubungan terjadi hanya antara pengalaman
lingkungan dengan perilaku.
Bandura mengembangkan model determinisme resiprokal yang terdiri dari
tiga faktor utama: perilaku, person/kognitif, dan lingkungan. Seperti ditunjukkan
dalam gambar 7.7, faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk memengaruhi
pembelajaran: faktor lingkungan memengaruhi perilaku, dan sebagainya. Bandura
menggunakan istilah person, tetapi kita memodifikasinya menjadi person (cognitive)
karena banyak faktor orang yang dideskripsikannya adalah faktor kognitif. Faktor
person bandura yang tak punya kecenderungan kognitif terutama adalah pembawaan
personalitas dan temperamen. Ingat dalam Bab 4, ”variasi individual”, dikatakan
bahwa faktor-faktor tersebut mungkin mencakup sikap introvert atau ekstravert, aktif
atau inaktif(pasif), tenang atau cemas, dan ramah atau bermusuhan. Faktor kognitif
mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi, pemikiran, dan kecerdasan.
Perhatikan bagaimana model bandura dalam kasus perilaku akademik murid
sekolah menengah yang kita sebut saja sebagai Nila.
1. Kognisi memengaruhi perilaku. Nilamenyusun strategi kognitif untuk berpikir
secara lebih mendalam dan logis tentang cara menyelesaikan suatu masalah.
Strategi kognitif meningkatkan perilaku akademiknya.
2. Perilaku memengaruhi kognisi. Proses (perilaku) belajar Nila membuatnya
mendapat nilai baik, yang pada gilirannya menghasilkan ekspektasi positif tentang
kemampuannya dan membuat dirinya percaya diri (kognisi).
3. Lingkungan memengaruhi perilaku. Sekolah tempat Nila belajar baru-baru ini
mengembangkan proram percontohan keterampilan-belajar untuk membantu murid
belajar cara membuat catatan, mengelola waktu, dan mengerjakan ujian secara
lebih efektif. Program keterampilan-belajar ini meningkatkan perilaku akademik
Nila.
4. Perilaku memengaruhi lingkungan. Program keteranpilan-belajar ini berhasil
meningkatkan perilaku akademik banyak murid dikelas Nila. Perilaku akademik
yang meningkat ini memicu sekolah untuk mengembangkan program itu sehingga
semua murid di sekolah itu bisa turut serta.
5. Kognisi memengaruhi lingkungan. Ekspektasi dan perencanaan dari kepala
sekolah dan para guru memungkinkan program keterampilan-belajar itu terwujud. 6. Lingkungan memengaruhi kognisi. Sekolah tersebut mendirikan pusat sumber
daya di mana murid dan orang tua dapat mencari buku dan materi tentang
peningkatan keterampilan belajar. Pusat sumber daya ini juga memberikan layanan
tutoring keterampilan-belajar untuk murid. Nila dan orang tuanya memetik
keuntungan dari tutoring dan pusat sumber daya ini. Layanan ini meningkatkan
Dalam model pembelajaran bandura, faktor person (kognitif) memainkan
peran penting. Faktor person (kognitif) yang ditekankan bandura (1997, 2001) pada
masa belakangan ini adalah self-efficacy, yakni keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan menghasilkan hasil positif. Bandura mengatakan bahwa
efficacy berpengaruh besar terhadap perilaku. Misalnya, seseorang murid yang
self-efficacy-nya rendah mungkin tidak mau berusaha belajar untuk mengerjakan ujian
karna dia tidak percaya bahwa belajar akan bisa membantunya mengerjakan soal. Kita
akan membahas lebih banyak tentang self-efficacy ini dia Bab 13, “motivasi,
pengajaran, dan pembelajaran”. 31 IV. Perkembangan Intelegensi
Intelegensi bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual.Dalam mengartikan intelegensi (kecerdasan) ini para ahli mempunyai pengertian yang beragam.32
Deskripsi perkambangan fungsi-fungsi kognitif secara kuantitatif dapat dikembangkan berdasarkan hasil laporan berbagai hasil studi pengukuran dengan menggunakan tes intelegensi sebagai alat ukurnya yang dilakukan secara longitudinal terhadap sekelompok subjek dari dan sampai ke tingkat usia tertentu secara
test-retest, yang alat ukurnyadisusun secara skuensial (Standfort Revision Benet Test).
Dengan menggunakan hasil pengukuran tes intelegensi yang mencakup general (Information and Verbal Analogies, Jones and Conrad) (Loree,1970: 78), telah mengembangkan sebuah kurva perkembangan intelegensi, yang dapat ditafsirkan antara lain:
31 Ibid Hal 286
a. Laju perkembangan intelegensi pada masa anak-anak masa-masa sebelumnya yang ditempuh oleh subjek yang sama, kita akan dapat melihat perkembangan presentase taraf kematangan dan kemampuannya sebagai berikut:
a. Usia 1 tahun berkembang sampai sekitar 20%-nya b. Usia 4 tahun sekitar 50%-nya
c. Usia 8 tahun sekitar 80%-nya d. Usia 13 tahun sekitar 92%-nya
Hasil studi Bloom ini tampaknya juga menjelaskan bahwa laju perkembangan IQ itu bersifat proporsional.Tetapi pada umunya orang berpendapat, bahwa intelegensi merupakan salah satu factor penting yang ikut menentukan berhasil atau gagalnya belajar seseorang; terlebih-lebih pada waktu anak masih sangat muda,
intelegensi sangat besar pengaruhnya.
(Susanto,Ahmad,Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya,Jakarta:Kencana.2011. h 35)
Menurut konsepsi ini intelegensi adalah persatuan (kumpulan yang dipersatukan) dari daya-daya jiwa yang khusus. Karena itu, pengukuran mengenai intelegensi juga dapat ditempuh dengan cara mengukur daya-daya iwakhusu itu sendiri, misalnya daya mengamati, dan mereproduksi, dan daya berpikir. (Suriasumantri, 2004: 125)
intelegensi diberi definisi sebagai taraf umum yang mewakili daya-daya khusus.33
Berkaitan dengan itu, Piaget menemukan tahap berpikir pra operasional, suatu tahap yang berlangsung dari usia dua atau tiga tahun sampai tujuh atau delapan tahun. (Hurlock, Elizabeth B. 1978.,Perkembangan Anak (terj.). MeitasariTjandrasa dan Soejarwo. Jakarta: Erlangga. Jilid II Edisi-VI. Halaman: 109-123)
V. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif
1. Faktor hereditas / keturunan
Teori hereditas atau nativisme pertama kali dipelopori oleh seorang ahli filsafat. Dia berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi lingkungan. Berdasarkan teorinya, taraf intelegensi anak sudah ditentukan sejak anak dilahirkan, sejak faktor lingkungan tak berarti pengaruhnya.
Para ahli psikologi Loehlin, Lindzey dan Spuhler berpendapat bahwa taraf intelegensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan.Pembawaan ditentukan oleh ciri-ciri sejak lahir (batasan kesanggupan).
2. Faktor Lingkungan
Teori lingkungan atau emirisme dipelopori oleh John Locke.Dia berpendapat bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci atau tabularasa.Menurut pendapatnya, perkembangan manusia sangatlah ditentukann oleh lingkungannya.Berdasarkan pendapat John Locke tersebut perkembangan taraf intelegensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya.
3. Kematangan
Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis (usia kalender).
4. Pembentukan
Pembentukan adalah segala keadaan diluar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelegensi. Pembentukan dapat dibendakan pembentukan sengaja (sekolah/formal) dan pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar/informal), sehingga manusia berbuat intelegen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian hidup.
5. Minat dan Bakat
Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu.Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu, maka akan semakin mudah dan cepat mempelajari hal tersebut. 6. Kebebasan
1. Asimilasi dan Akomodasi
dengan cara-cara yang harus dilakukannya agar buah tersebut dapat dimakan. 34
VII. Urgensi Perkembangan Kognitif
Pada dasarnya perkembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melaluli panca inderanya, sehingga dnegan pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memberdayakan apa yang ada di dunia untuk kepentingan dirinya dan orang lain.35
Adapun proses kognisi meliputi berbagai aspek, seperti persepsi, ingatan, pikiran, symbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Sehubungan dengan hal ini Pieget berpendapat, bahwa pentingnya guru mengembangkan kognitif pada anak, adalah:
1. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif; 2. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa
dan kejadian yang pernah dialaminya;
3. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya;
4. Agar anak mampu memahami symbol-simbol yang tersebar di dunia sekitarnya.
5. Agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran, baik yang terjadi secara alamiah (spontan), maupun melalui proses ilmiah (percobaan);
34PLPG. Hal 8
6. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya, sehingga pada akhirnya anak akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya sendiri.
Menurut Sunaryo Kaartadinata, dalam jurnal ilmu pendidikan Pedagogia Vol. 1 April 2003, menyebutkan bahwa, perkembangan otak, struktur otak anak tumbuh terus setelah lahir. Sejumlah riset menunjukkan bahwa pengalaman usia dini, imajinasi yang terjadi, bahasa yang didengar, buku yang ditunjukkan, akan turt membentuk jaringan otak.
Dengan demikian, melalui pengembangan kognitif, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi untuk memecahkan suatu masalah.36
VIII. Klasifikasi Pengembangan Kognitif
Dengan pengetahuan pengembangan kognitif akan lebih mudah untuk orang dewasa lainnya dalam menstimulasi kemampuan kognitif anak, sehingga akan tercapai optimalisasi potensial pada masing-masing anak. Adapun tujuan pengembangan kognitif diarahkan pada pengembangan kemampuan auditory,visual, taktik, kinestetik, aritmetika, geometri, dan sains permulaan. (Susanto,Ahmad. Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya,Jakarta:Kencana.2011.h 61) Salah satu uraian dari bidang pengembangan kemampuan yaitu Pengembangan Sains Pemulaan sebagai berikut: (Susanto,Ahmad,Perkembangan
Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai mengeksplorasi berbagai benda yang ada disekitar; b) mengadakan
berbagai percobaan sederhana; c) mengomunikasikanapa yang telah diamati dan diteliti. Contoh kegiatan yang dapat dikembangkan melalui permainan, sebagai berikut: proses merebus atau membakar jagung, membuat jus, warna dicampur, mengenal asal mula sesuatu, balon ditiup laluldilepas,benda kecil dilihat dengan kaca pembesar, besi berani didekatkan dengan macam-macam benda, biji ditanam, benda-benda dimasukkan ke dalam air, mengenal sebab akibat mengapa sakit gigi, dan mengapa lapar.37
D. Kecerdasan Emosi
Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi
diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan, dorongan hari, dan tidak
melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak
melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdo’a.
Menurut shapiro, istilah kecerdasan emosio pertama kali dilontarkan pada tahun 1990
oleh dua orang ahli, yaitu Peter Salovey dan John Mayer untuk menerangkan jenis-jenis
kualitas emosi yang dimaksudkan antara lain : (1) empati, (2) mengungkapkan dan
memahami perasaan, (3) mengendalikan amarah, (4) kemampuan kemandirian, (5)
kemampuan menyesuaikan diri, (6) diskusi, (7) kemampuan memecahkan masalah
antarpribadi, (8) ketekunan, (9) kesetiakawanan, (10) karamahan, dan (11) sikap hormat.
Teori lain dikemukakan oleh Ruven Bar-On, sebagaimana dikutip oleh Steven J. Stein
dan Howard E. Book, ia menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah serangkaian
kemampuan, kompetensi, dan kecakapan nonkognitif, yang memengaruhi kemampuan
seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Selanjutnya, Steven J.
Stein dan Howard E. Book menjelaskan pendapat Peter Salovey dan John Mayer, pencipta
istilah kecerdasan emosional, bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk
mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran,
memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga
membantu perkembangan emosi ddan intelektual.
Dengan kata lain, menurut Stein dan Book, EQ adalah serangkaian kecakapan yang
memungkinkan kita melapangkan jalan di dunia yang rumit, mencakup aspek pribadi, sosial,
dan pertahanan diri seluruh kecerdasan, akal sehat yang penuh misteri, dan kepekaan yang
penting untuk berfungsi secara efektif setiap hari. dalam bahasa sehari-hari, kecerdasan
emosional biasanya kita sebut sebagai “ Street Smarts (pintar)”, atau kemampuan khusus
yang kita sebut “akal sehat”, terkait dengan kemampuan membaca lingkungan politik dan
sosial, dan menatanya kembali, kemampuan memahami dengan spontan apa yang diinginkan
dan dibutuhkan orang lain, kelebihan dan kekurangan mereka, kemampuan untuk tidak
terpengaruh tekanan, dan kemapuan untuk menjadi orang yang menyenangkan, yang
kehadirannya didambakan orang lain.
Ketrampilan kecerdasan emosi bekerja secara sinergi dengan keterampilan kognitif,
orang-orang yang berprestasi tinggi memiliki keduanya. Makin kompleks pekerjaan, makin
penting kecerdasan emosi . emosi yang lepas kendali dapat membuat orang pandai menjadi
bodoh. Tanpa kecerdasan emosi, orang tidak akan mampu menggunakan kemampuan
kognitif mereka sesuai dengan potensi yang maksimum. Kemudian, Doug Lennick
menegaskan, “ yang diperlukan untuk sukses dimulai dengan keterampilan intelektual, tetapi
orang memerlukan kecakapan emosi untuk memanfaatkan potensi bakat mereka secara
Cooper dan sawaf menegaskan bahwa kecerdasan emosional dan
kecerdasan-kecerdasan lain sebetulnya saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Emosi menyulut
kreativitas, kolaborasi, inisiatif dan transformasi, sedangkan penalaran logis berfungsi
mengatasi dorongan yang keliru dan menyelaraskan tujuan dengan proses, teknologi dengan
sentuhan manusiawi.
Dengan demikian, seseorang yang memiliki IQ saja belum cukup, yang ideal adalah
IQ yang dibarengi dengan EQ yang seimbang. Pemahaman ini didukung oleh pendapat
Goleman yang dikutip oleh Patton, bahwa para ahli psikologi sepakat kalau IQ hanya
mendukung sekitar 20 persen faktor yang menentukna keberhasilan. Sedangkan 80 persen
sisanya berasal dari faktor lain. Termasuk kecerdasan emosional.
Selanjutnya, Patton menyebutkan bahwa EQ mencakup semua sifat seperti : (1)
kesadaran diri, (2) manajemen suasana hati, (3) motivasi diri, (4) mengendalikan impulsi
(desakan hati), (5) keterampilan mengendalikan orang lain. Dengan demikian, jelaslah bahwa
IQ bukan satu-satunya faktor yang dapat membuat seseorang berhasil, tetapi paduan EQ dan
IQ dapat meraih keberhasilan di tempat kerja.
Terdapat beberapa manfaat dari keselarasan IQ dan EQ, yaitu seseorang akan
mampu : (1) bekerja lebih baik dari pekerja lainnya, (2) menjadi anggota kelompok yang
lebih baik, (3) merasa percaya diri dan diberdayakan untuk mencapai tujuan, (4) mennagani
masalah dengan lebih efektif, (5) memberikan pelayanan lebih baik, (6) berkomunikasi
dengan lebih efektif, (7) memimpin dan mengelola pekerjaan dengan falsafah hati dan
kepala, dan (8) menciptakan perusahaan (organisasi) yang memiliki integritas, nilai, dan
Patton berpendapat bahwa hubungan IQ dan EQ sebagai berikut. IQ adalah faktor
genetik yang tidak dapat berubah yang dibawa sejak lahir. Sedangkan EQ tidak demikian,
karena dapat disempurnakan dengan kesungguhan, pelatihan, pengetahuan, dan kemauan.
Dasar untuk memperkuat EQ seseorang adalah dengan memahami diri sendiri.
Kesadaran diri adalah bahan baku penting untuk menunjukkan kejelasan dan
pemahaman tentang perilaku seseorang. Kesadaran diri juga menjadi titik tolak bagi
perkembangan pribadi, dan pada titik inilah pengembangan EQ dapat dimulai. Saluran
menuju pada kesadaran diri adalah rasa tanggung jawab dan keberanian. Faktor-faktor inilah
yang sangat penting artinya pada saat mengahdapi berbagai aspek diri sendiri yang tidak
menyenangkan. Pada saat ini pula diperlukan suatu jembatan, yakni EQ yang berfungsi untuk
menjelaskan apa yang sewajarnya dilakukan. Semakin tinggi derajat EQ seseorang, semakin
terampil ia melakukan mengetahui mana yang benar.
Semakin tinggi kecerdasan emosional kita, semakin besar kemungkinan untuk sukses
sebagai pekerja, orang tua, manajer, anak dewasa bagi orang tua kita, mitra bagi pasangan
hidup kita, atau calon untuk suatu posisi jabatan.
Penting untuk diketahui, bahwa kecerdasan emosi adalah dasar bagi lahirnya
kecakapan emosi yang diperoleh dari hasil belajar, dan dapat menghasilkan kinerja menonjol
dalam pekerjaan. Inti dari kecakapan emosi ini adalah dua kemampuan (1) empati, yang
melibatkan kemampuan membaca perasaan orang lain, (2) keterampilan sosial, yang berarti
mampu mengelola perasaan orang lain dengan baik.
Mlengkapi pendapat tersebut, Patton mengingatkan bahwa keberhasilan antarpribadi
hidup. Emosi menambah kedalaman dan kekayaan dalam kehidupan seseorang. Tanpa
perasaan, tindakan seseorang akan lebih menyerupai komputer, berpikir namun tanpa gairah.
Begitu pula dukungan bagi suatu proyek penting, dan bisa menyatu dengan emosi orang lain
akan menjadi keterampilan yang penting ditempat kerja.
Kecerdasan emosional bukanlah muncul dari pemikiran intelek yang jernih, tetapi
dari pekerjaan hati manusia. Emotionnal Inteligensi (EI) bukanlah trik-trik tentang penjualan
atau menata sebuah ruangan, dan bukan tentang memakai topeng kemunafikan atau ke
psikologi untuk mengendalikan, mengeksploitasi, atau memanipulasi seseorang.
Kecerdasan emosionalah yang memotivasi seseorang untuk mencari manfaat dan
mengaktifkan aspirasi dan nilai-nilai yang paling dalam, mengubah apa yang dipikirkan
menjadi apa yang dijalani. Kecerdasan emosional menuntut seseorang untuk belajar
mengakui dan mengahargai perasan pada dirinya dan orang lain untuk menganggapi dengan
tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan energi, emosi dalam kehidupan dan
pekerjaan sehari-hari. Jadi , kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan,
memahami, dan secara efekktif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagia sumber
informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.
Berkaitan denganpekerjaan, seseorang yang bekerja tentu saja penting memiliki
pengetahuan teknis atau pengetahuan praktis dalam melukan tugas-tugasnya, namun
demikian, faktor lingkungan dengan kenyataan di tempat kerja juga harus menjadi
pertimbangan, terutama yang berkaitan dengan orang-orang yang ada di tempat kerja tersebut
atau dengan siapa kita bekerja. Dalam hubungan ini, Patton mengemukakan adanya beberapa
masalah umum yang mungkin dihadapi seseorang atau organisasi, yaitu (1) seseorang merasa
secara pribadi atas apa yang ia kerjakan, (3) sesorang menjadi sakit karena merasa tidak
mampu menyeseuaikan diri ditempat kerja, (4) seseorang merasa tertekan dan kurang
berminat dalam pekerjaannya, (5) seseorang kehilangan gairah, semangat dan motivasi diri,
(6) seseorang membuat suasana tidak menyenangkan bagi teman-teman karena perilakunya,
(7) seseorang memberi umpan balik yang tidak efektif kepada orang lain, (8) seseorang
merasa sukar membentuk kelompok yang sinergis, (9) orang-orang tidak merasa puas dengan
pelayanan dan mencari yang lain, (10) keluarga menderita akibat tekanan pekerjaan,(11)
munculnya masalah ketahanan dan moral karyawan, (12) kreativitas dan inovasi.
Dengan demikian, kecerdasan emosi atau emotional Intelegensi merunjuk pada
kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan
memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengna baik pada diri sendiri dan
dalam hubungan dengan orang lain.
Selanjutnya, dijelaskan bahwa kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan
yang berbeda tetapi saling melengkapi dengan kecerdasan akademik (akademik Intelegensi),
yaitu kemampuan-kemampuan kognitif murni yan di ukur dengan IQ dan EQ. Banyak orang
yang cerdas dalam arti terpelajar, tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosi. Sehingga, saat
bekerja menjadi bawahan dari orang yang ber iQ lebih rendah, tetapi unggul dalam
keterampilan kecerdasan emosi.
kecerdasan akademis praktis tidak meawarkan persiapan untuk menghadapi
gejolak-atau kesempatan-yang ditimbulkan oleh kesulitan hidup. Sebaliknya, keterampilan emosional
merupakan meta-ability, yang menentukan beberapa baik kita mampu menggunakan
keterampilan-keterampilan lain manapun yang kita miliki, termasuk intelektual yang belum
mendalam memengaruhi semua kemampuan lainnya, baik memperlancar maupun
menghambat kemampuan itu.
Lebih lanjut, Goleman menjelaskan bahwa orang yang secara emosional cakap-yang
mengetahui dan menangani perasaan mereka dengan baik, yang mampu membaca dan
menghadapi perasaan orang lain dengan efektif-memiliki keuntungan dalam setiap bidang
kehidupan,entah itu dalam hubungan asmara dan persahabatan atau dalam mnangkap
aturan-aturan tidak tertulis yang menentukan keberhasilan dalam politik organisasi. Orang dengan
keterampilan emosional yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan bahagia
dan berhasil dalam kehidupan, menguasai kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitas
mereka. Sementara, orang yang tidak dapat menghimpunkendali tertentu atas kehidupan
emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan mereka untuk
memusatkan perhatian pada pekerjaan pada pekerjaan dan memiliki pikiran yang jernih.
Kecakapan emosi yang paling sering mengantar orang ke tingkat keberhasilan ini
antara lain:
1. Inisiatif, semangat juang, dan kemampuan menyesuaikan diri: 2. Pengaruh, kemampuan memimpin tim, dan kesadaran politis: 3. Empati, percaya diri, dan kemampuan mengembangkan orang lain.
Sebaliknya, dua pembawaan yang paling lazim dijumpai pada mereka yang gagal adalah 4. Bersikap kaku: mereka tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam
budaya perusahaan, atau mereka tidak mampu menerima atau menanggapi dengan baik
umpan balik tentang sikap mereka yang perlu diubah atau diperbaiki. Mereka tidak
mampu mendengarkan atau belajar dari kesalahan.
5. Hubungan yang buruk: faktor yang paling sering disebut, seperti terlalu mudah
melancarkan kritik pedas, tidak peka, atau terlalu menuntut sehingga mereka cenderung
Kemudian, Goleman menjelaskan pendapat Salovey yang menempatkan kecerdasan
pribadi Gardner sebagai dasar dalam mendefinisikan kecerdasan emosional yang
dicetuskannnya. Dalam hal ini, Salovey memperluas kemampuan kecerdasan emosional
menjadi lima wilayah utama, sebagai berikut.
1. Mengenali emosi diri. Intinya adalah kesadaran diri, yaitu mengenali perasaan sewaktu
perasaan itu terjadi. Ini merupakan dasar kecerdasan emosional. Kesadaran diri adalah
perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam kesadaran refleksi diri
ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi. Sementara, menurut
John Mayer, kesadaran diri berarti diri berarti waspada, baik terhadap suasana hati
maupun pikiran kita tentang suasana hati. Kemampuan untuk memantau perasaan dari
waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri.
Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita
berada dalam kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang
perasaannya adalah pilot yang andal bagi kehidupan mereka, karena memiliki perasaan
lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan
keputusan-keputusan masalah pribadi.
2. Mengelola emosi. Yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas.
Kecakapan ini bergantung pula pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan
dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan,
atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan
emosional dasar. Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam ketrampilan ini akan
terus-menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar
dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam
3. Memotivasi diri sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan menata emosi
sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk
memotivasi diri sendiri, dan untuk berkreasi. Begitu juga dengan kendali diri emosional
menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati merupakan landasan
keberhasilan dalam berbagai bidang. Kmudian, mampu menyesuaikan diri dalam “flow”
memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang
memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apa pun
yang mereka kerjakan.
4. Mengenali emosi orang lain. Yaitu empati, kemampuan yang juga bergantung pada
kesadaran diri emosional, yang merupakan “keterampilan bergaul “ dasar. Kemampuan
berempati yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain ikut
berperan dalam pergulatan dalam arena kehidupan. Menurut teori Titchener, emapati
berasal dari semacam peniruan secara fisik atas beban orang lain, yang kemudian
menimbulkan perasaan yang serupa dalam diri seseorang. Orang yang empatik lebih
mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa
yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.
5. Membina hubungan. Seni membina hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan
mengelola orang lain. Dalam hal ini ketrampilan dan ketidakterampilan sosial, serta
keterampilan-keterampilan tertentu yang berkaitan adalah termasuk di dalamnya. Ini
merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan
antarpribadi. Keterampilan sosial adalah unsur untuk menajamkan kemampuan
antarpribadi, unsur pembentuk daya tarik, keberhasilan sosial, bahkan karisma.
Orang-orang yang terampil dalam kecerdasan sosial dapat menjalin hubungan dengan Orang-orang