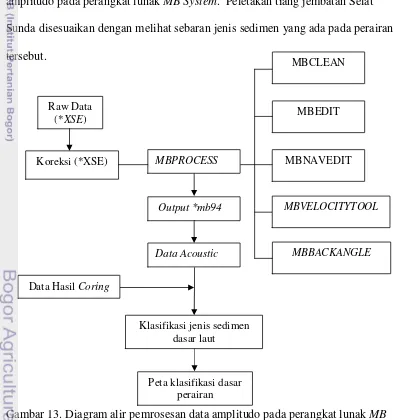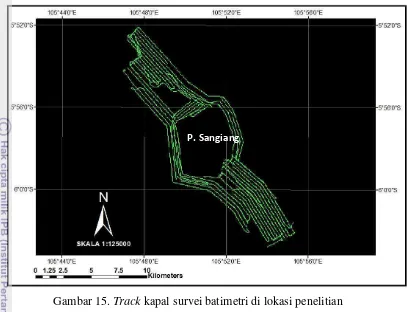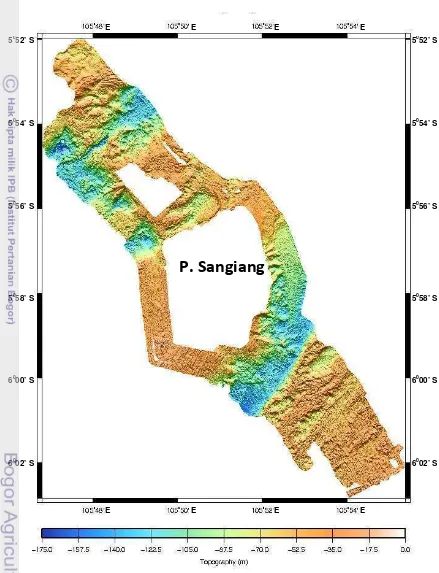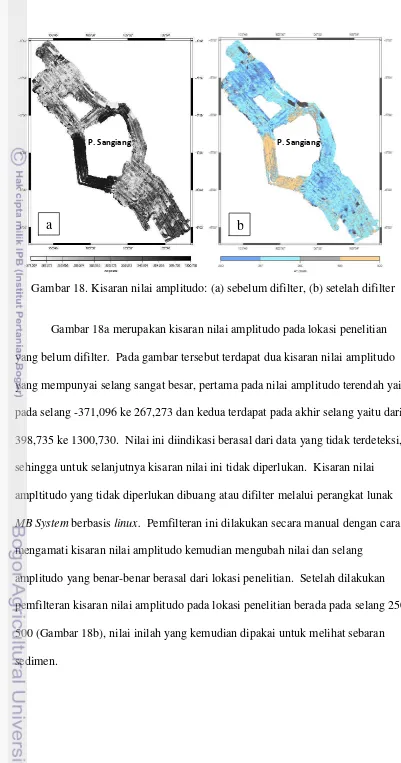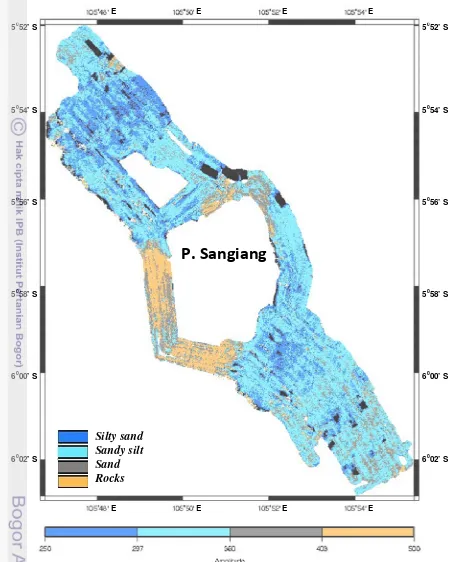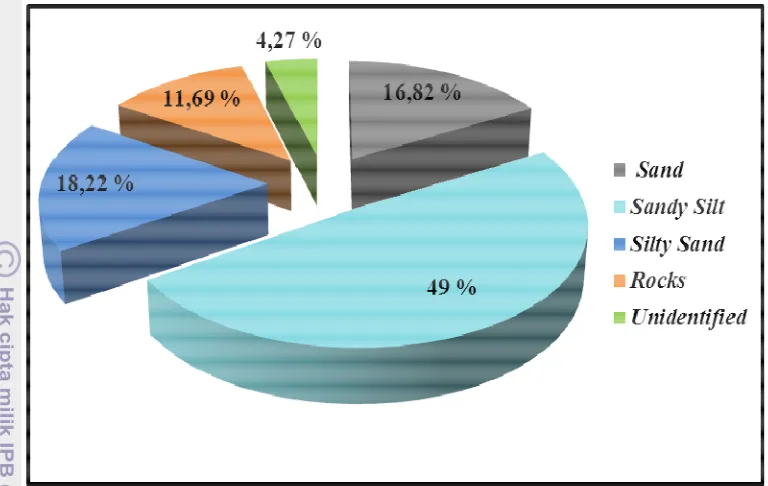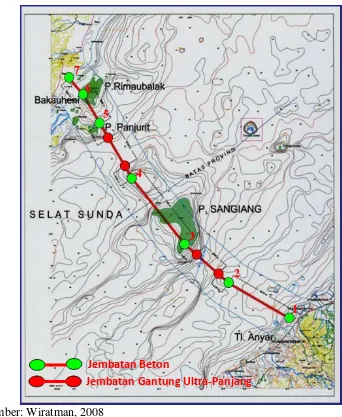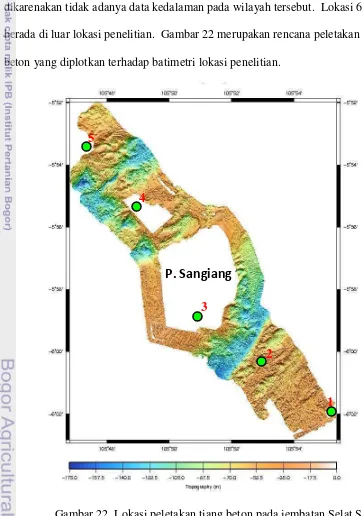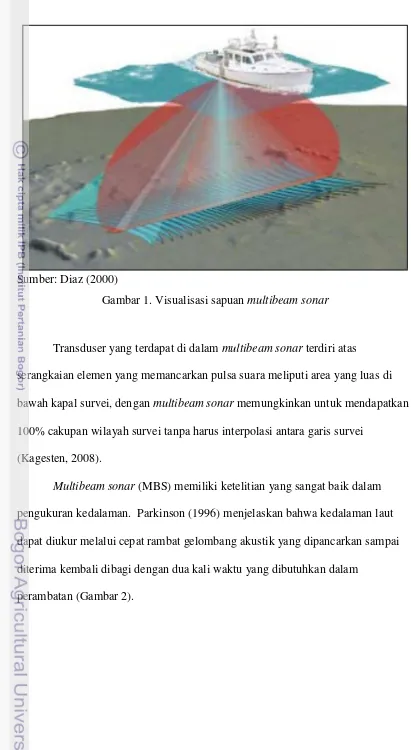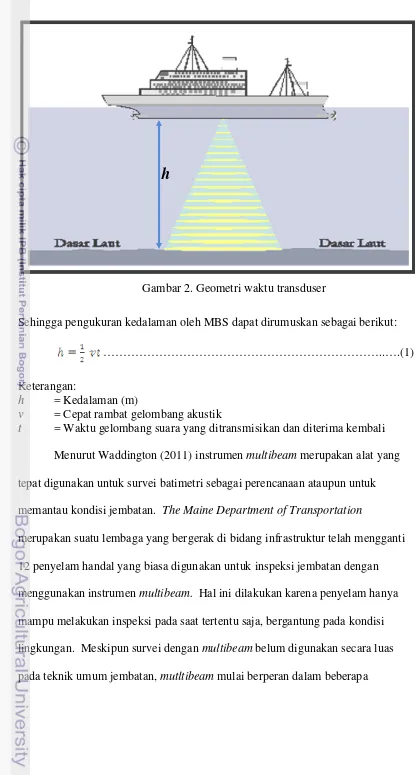Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Dibimbing oleh HENRY M. MANIK dan DJOKO HARTOYO
Jembatan merupakan suatu kontruksi yang dibangun untuk sarana transportasi. Pemerintah Indonesia mencanangkan akan melaksanakan
pembangunan jembatan Selat Sunda pada awal tahun 2014 sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pembangunan jembatan tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan informasi yang relevan agar berjalan dengan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan instrumen hidroakustik multibeam sonar dalam interpretasi kedalaman dan sebaran jenis sedimen sebagai informasi utama dalam kegiatan pembangunan jembatan Selat Sunda.
Pemeruman dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 1 Januari 2011 di perairan Selat Sunda yaitu pada kordinat 5052’-6002’ LS dan 105045’-106054’ BT. Pemeruman ini dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menggunakan Kapal Baruna Jaya IV. Alat yang digunakan untuk penentuan posisi yaitu DGPS Sea star 8200 VB yang bekerja dengan metode Real Time Differensial GPS (RTDGPS). Coda Octopus F180 berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap pengaruh perubahan vertikal pada beam (heading, pitching dan rolling). Perangkat lunak Caris HIPS&SIPS 6.1. digunakan untuk mengolah data kedalaman, sedangkan untuk untuk
mendapatkan nilai amplitudo yang digunakan untuk klasifikasi sedimen dasar laut menggunakan perangkat lunak MB-System berbasis linux.
Pasang surut di lokasi penelitian termasuk ke dalam tipe campuran,
Construction at Sunda Strait. Supervised by HENRY M. MANIK and construction of the bridge is running efficiently. The purpose of this research is to apply the instrument hydroacoustic of multibeam sonar to measure sea water depths and to map the distribution of sediment types. Survey conducted in Sunda Strait on the coordinates of 5052’-6002’S and 105045’-106054’E. Data acquisition done by using hydrostar software. Bathymetry data was processed with Caris HIPS&SIPS. Data amplitude was processed with MB Systems to make sediment classification. Tides in research area is mixture type, where tidal type is suitable for the construction of the bridge was held because tidal type has a relatively small effect on the scatter and distribution of sea floor sediments. Depth research area have range from 17,5-175 m, there are several ridge sea that can be used as a laying pole bridge. There are two locations considered suitable on location 1 and 2, where both the location is ridge sea with depth range17-35 m. The type of sediment obtained by processing data amplitude and core of sample sediment. The types of sedimen in research area are silty sand, sandy silt, sand and rocks. Sediment is dominated by sandy silt with percent coverage of 49%. Location 1 and 2 have a sandy silt sediment. The pole type that fits is the pillar of the prisoner's coherency between the pole to the ground (Friction piles), when the pole to stick on the ground with powerful high friction values such as sand, then load that is accepted by the mast will be withheld based on friction between the pole and the land around the pole.
1 1.1. Latar Belakang
Jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewatkan
angkutan di atas suatu penghalang. Semakin lebar halangan yang harus dilewati,
makin besar panjang jembatan yang dibutuhkan. Jembatan sangat berperan
sebagai salah satu prasarana perhubungan yang pada hakikatnya merupakan unsur
penting dalam mendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat. Jembatan
yang dibangun harus direncanakan dengan matang agar mampu melewatkan
lalulintas yang dilayaninya dengan aman dan nyaman serta mampu bertahan
dalam waktu yang sangat lama.
Pemerintah Indonesia mencanangkan akan melaksanakan pembangunan
jembatan Selat Sunda pada awal tahun 2014 sebagai penghubung antara Pulau
Jawa dengan Pulau Sumatera. Salah satu proses pembangunan jembatan adalah
tahap studi kelayakan, dimana semua aspek ditinjau untuk memastikan bahwa
proses pembangunan jembatan dapat dilanjutkan atau tidak serta untuk
mengetahui kapan jembatan tersebut dibutuhkan. Salah satu aspek yang harus
ditinjau dalam perencanaan jembatan adalah informasi dasar perairan yang akan
dijadikan sebagai penopang tiang jembatan. Informasi mengenai dasar perairan
dapat diperoleh melalui survei batimetri. Multibeam merupakan instrumen
hidroakustik yang telah banyak digunakan dalam kegiatan survei batimetri.
Anderson et al. (2008) menyatakan bahwa intrumen multibeam sonar mampu
memindai dasar perairan dengan cakupan area yang luas dengan resolusi yang
batimetri yang akurat pada setiap titik pengukuran di dasar perairan, sehingga dari
survei ini mampu menghasilkan peta batimetri yang baik.
Pengamatan karakteristik dasar perairan akan diamati dengan
menggunakan instrumen multibeam sonar, yaitu gelombang berupa pulsa akan
dipancarkan ke dasar perairan dengan menggunakan panjang gelombang tertentu
yang kemudian bila gelombang tersebut telah menyentuh dasar perairan
gelombang akan dikembalikan dan diterima kembali oleh receiver dalam bentuk
echo. Penentuan sebaran jenis sedimen dapat dilakukan dengan menganalisis nilai back scattering strength yang dihasilkan (Munandar, 2008). Nilai back
scattering strength secara kuantitatif berdasarkan besarnya frekuensi yang digunakan untuk berbagai tipe dasar perairan. Sebaran sedimen pada suatu
perairan akan berubah secara berkala bergantung pada masukan yang ada di
sekitar perairan tersebut.
Pemasangan tiang jembatan harus memperhatikan sebaran sedimen. Studi
awal dilakukan untuk mengetahui keadaan mengenai dasar laut, yaitu kedalaman
dan jenis sedimen pada dasar periran yang nantinya akan berguna untuk
mengestimasi panjang dan jenis tiang yang akan ditanam ke dalam dasar perairan.
Setelah tiang terpasang perlu dilakukan pengecekan secara berkala untuk
mengetahui perubahan yang terjadi setelah adanya pemasangan kontruksi. Studi
yang dilakukan adalah untuk mengetahui sebaran jenis sedimen akibat adanya
kegiatan bawah laut yang dilakukan serta mendeteksi kedalaman perairan
1.2. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan instrumen hidroakustik
multibeam sonar dalam interpretasi kedalaman dan sebaran jenis sedimen sebagai informasi utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan jembatan Selat
4 2.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Perairan Selat Sunda terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa
serta berhubungan dengan Laut Jawa dan Samudera Hindia. Pada perairan ini
terdapat pulau–pulau kecil dan gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung
Krakatau. Di perairan selat bagian utara yang berhubungan dengan Laut Jawa,
kedalaman lautnya dangkal (kurang dari 50 m), tetapi di perairan selat bagian
selatan yang berhubungan dengan Samudera Hindia mempunyai kedalaman laut
lebih dari 1000 m. Wyrtki (1961) menyatakan bahwa massa air di Selat Sunda
bergerak ke arah Samudera Hindia sepanjang tahun dan sangat kuat hubungannya
dengan gradien permukaan muka laut (sea level).
Sebagai perairan yang menghubungkan Laut Jawa dan Samudera Hindia,
Selat Sunda merupakan salah satu selat yang menarik karena hampir setiap saat
kondisinya dipengaruhi oleh karakteristik oseanik Samudra Hindia dan sifat
perairan dangkal Laut Jawa. Menurut Kurnio dan Hadjawidjaksana (1995),
keberadaan Gunung Krakatau yang terdiri atas beberapa gugusan pulau yaitu
Sertung, Rakata dan Anak Krakatau yang aktif selalu memuntahkan material
piroklastik antara selang waktu satu hingga empat menit dan cenderung
menghasilkan tsunami dengan gelombang sedang dan kecil. Topografi perairan
Selat Sunda sangat beragam, ada yang berbentuk paparan, slope deep sea basin
dan gunung bawah laut.
Kedalaman perairan Selat Sunda dapat dibagi menjadi tiga kategori umum
yaitu (1) perairan oseanik, (2) wilayah tengah selat dan (3) perairan dengan
berbagai jenis usaha perikanan yang dapat dilakukan. Arus pantai yang terjadi di
kedalaman laut kurang dari 200 m adalah lebih merupakan akibat angin dan arus
pasang surut yang rata-rata memiliki pola relatif lemah (Bishop, 1984).
Dijelaskan lebih lanjut bahwa arus pantai dapat diketahui dengan Model Ekman
yang dikembangkan dimana di dalamnya meliputi topografi dasar laut dan gradasi
tekanan.
2.2. Pinsip Kerja Multibeam Sonar
Multibeam sonar merupakan instrumen hidroakustik yang memiliki resolusi lebih tinggi dibandingkan dengan echo sounder pada umumnya dan
mampu memetakan berbagai lokasi dasar perairan. Pada dasarnya prinsip kerja
dari mutibeam sonar sama dengan prinsip kerja single beam, namun pada
multibeam sonar terdapat banyak beam yang memancarkan pulsa suara secara
bersamaan dan memiliki penerimanya masing-masing. Multibeam sonar
menghasilkan pancaran yang melebar dan melintang terhadap badan kapal.
Hanya dengan satu ping instrumen ini mampu mencakup area yang luas dengan
berbagai kedalaman yang berbeda (L-3 Communications Sea Beam Instruments,
2000). Oleh karena itu instrumen ini dapat menghasilkan peta batimetri yang
akurat. Berikut ini merupakan gambar yang memperlihatkan daerah hasil sapuan
Sumber: Diaz (2000)
Gambar 1. Visualisasi sapuan multibeam sonar
Transduser yang terdapat di dalam multibeam sonar terdiri atas
serangkaian elemen yang memancarkan pulsa suara meliputi area yang luas di
bawah kapal survei, dengan multibeam sonar memungkinkan untuk mendapatkan
100% cakupan wilayah survei tanpa harus interpolasi antara garis survei
(Kagesten, 2008).
Multibeam sonar (MBS) memiliki ketelitian yang sangat baik dalam pengukuran kedalaman. Parkinson (1996) menjelaskan bahwa kedalaman laut
dapat diukur melalui cepat rambat gelombang akustik yang dipancarkan sampai
diterima kembali dibagi dengan dua kali waktu yang dibutuhkan dalam
Gambar 2. Geometri waktu transduser
Sehingga pengukuran kedalaman oleh MBS dapat dirumuskan sebagai berikut:
………..….(1)
Keterangan:
h = Kedalaman (m)
v = Cepat rambat gelombang akustik
t = Waktu gelombang suara yang ditransmisikan dan diterima kembali
Menurut Waddington (2011) instrumen multibeam merupakan alat yang
tepat digunakan untuk survei batimetri sebagai perencanaan ataupun untuk
memantau kondisi jembatan. The Maine Department of Transportation
merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang infrastruktur telah mengganti
12 penyelam handal yang biasa digunakan untuk inspeksi jembatan dengan
menggunakan instrumen multibeam. Hal ini dilakukan karena penyelam hanya
mampu melakukan inspeksi pada saat tertentu saja, bergantung pada kondisi
lingkungan. Meskipun survei dengan multibeam belum digunakan secara luas
jembatan dan aplikasi yang terkait. Beberapa tahun terakhir survei multibeam
telah digunakan sebagai alat penilaian untuk inspeksi secara berkala baik sebelum
maupun setelah pembangunan jembatan.
Kedalaman hasil pengukuran yang didapatkan tetap harus dikoreksi dari
berbagai kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan tersebut dapat berasal dari
kecepatan gelombang suara, pasang surut, kecepatan kapal, sistem pengukuran,
offset dan posisi kapal (PPDKK BAKOSURTANAL, 2004). Berdasarkan S-44 International Hydrographyc Organisation (IHO) batas toleransi kesalahan ketelitian kedalaman (σ) dihitung dengan menggunakan persamaan 2.
………...………..………….………..(2)
Keterangan:
σ = ketelitian kedalaman
a = konstanta kesalahan kedalaman, yaitu jumlah dari semua konstanta kesalahan
b = faktor pengganti kesalahan kedalaman lain d = kedalaman (m)
bxd = kesalahan kedalaman lain, jumlah semua kesalahan
2.3. SEA BEAM 1050 D Multibeam Sonar
SEA BEAM 1050 D Multibeam Sonar merupakan jenis multibeam yang dapat digunakan pada kedalaman laut tidak lebih dari 3000 m. Multibeam jenis
ini memiliki kemampuan untuk memetakan wilayah laut secara luas dengan lebar
sapuan mencapai 1530 dan memiliki 126 beam dengan jumlah bukaan 1,50 untuk
masing-masing beam (Lampiran 1). SEABEAM 1050 D memiliki dua frekuensi
yang dapat digunakan, yaitu 50 kHz dan 180 kHz. Kemampuan deteksi
menggunakan frekuensi 50 kHz dapat mencapai kedalaman 3000 m (Gambar 3),
kedalaman 0-100 m. Frekuensi 180 kHz dioperasikan di perairan dangkal
menghasilkan data kedalaman yang lebih detail dibandingkan dengan frekuensi 50
kHz, frekuensi 180 kHz pada laut dalam akan menghasilkan atenuasi yang tinggi.
Atenuasi adalah gejala pelemahan sinyal yang terjadi pada proses transmisi
gelombang suara pada medium air. Faktor-faktor yang mempengaruhi atenuasi
adalah absorpsi, refleksi dan refraksi gelombang suara.
Keunggulan lain dari SEABEAM 1050 D multibeam sonar adalah
menghasilkan data dengan standar IHO dan memiliki kemampuan yang sama
bagus untuk digunakan di laut dangkal ataupun laut kedalaman medium (L3
Communications ELAC Nautik GmbH, 2003).
Sumber: L3 Communications ELAC Nautik GmbH (2003)
Gambar 3.Jangkauan sapuan ELAC SEABEAM 1050 D (Frekuensi 50 kHz) terhadap kedalaman
2.4. Sedimen Dasar Laut
Sedimen laut meliputi fragmen-fragmen batuan dengan berbagai ukuran
dipengaruhi oleh masukan sedimen pada perairan tersebut. Informasi mengenai
sedimen sangat diperlukan untuk mengetahui biota-biota yang mendiami perairan
tersebut, selain itu juga sangat diperlukan untuk mengetahui kekuatan atu
kekokohan sedimen dalam menopang beban yang ada di atasnya seperti halnya
dalam pembangunan jembatan. Pujiyati (2008) menyatakan bahwa substrat dasar
perairan memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan biota yang ada
di dasar perairan seperti ikan demersal, baik ikan demersal besar maupaun ikan
demersal kecil.
Menurut asal usulnya sedimen dasar laut dapat digolongkan sebagai
berikut (Wibisono 2005):
1. Lithogenus: merupakan jenis sedimen yang berasal dari pelapukan batuan
dari daratan, lempeng kontinen termasuk yang berasal dari kegiatan
vulkanik. Sedimen ini memasuki kawasan laut melalui drainase air sungai.
2. Biogenous: merupakan jenis sedimen yang berasal dari organisme laut yang
telah mati terdiri atas remah-remah tulang, gigi-geligi dan
cangkang-cangkang tanaman maupun hewan mikro.
3. Hydrogenous: merupakan jenis sedimen yang berasal dari komponen kimia yang larut dalam air laut dengan konsentrasi lewat jenuh sehingga menjadi
pengendapan di dasar laut.
4. Cosmogenous merupakan jenis sedimen yang berasal dari luar angkasa, partikel dari benda-benda angkasa ditemukan di dasar laut dan banyak
mengandung unsur besi sehingga mempunyai respon magnetik dan memiliki
Wentworth (1922) mengklasifikasikan jenis sedimen berdasarkan
ukurannya menjadi 6 jenis.
Tabel 1. Jenis sedimen dan ukurannya
Nama Partikel Ukuran (mm) Sedimen Nama Batu Bongkah/Boulder >256 Gravel Konglomerat dan
Bereaksi berdasarkan kebundaran partikel Kerakal/Cobble 64-256 Gravel
Kerikil/Pebble 2-64 Gravel
Pasir/Sand 0.0625-2 Sand Sandstone
Lanau/Silt 0.0039-0.0625 Silt Batu Lanau
Lempung/Clay <0.0039 Clay Batu Lempung
2.5. Klasifikasi Dasar Perairan
Informasi mengenai tipe dasar perairan termasuk vegetasi perairan secara
umum dapat digambarkan pada sinyal dan sebaran spasial echo, dimana sinyal ini
dapat disimpan dan divalidasi dengan posisi objek yang diperoleh menggunakan
Global Positioning System (GPS). Verifikasi hasil sampel dasar perairan harus
diobservasi melalui penyelaman atau dengan menggunakan kamera bawah air
(underwater camera) yang harus direkam bersamaan dengan akuisisi data akustik
sehingga pada saat verifikasi data yang ada dapat digunakan untuk
membandingkan tipe dasar perairan yang belum diketahui (Burczynski, 2002).
Nilai dari sinyal echo selain bergantung pada tipe dasar perairan
khususnya kekasaran dan kekerasan juga bergantung pada parameter alat seperti
frekuensi dan transducer beam width (Burczynski, 2002). Kloser et al., (2001)
dan Schlagintweit (1993) mengamati klasifikasi dasar laut dengan frekuensi
akustik yang berbeda. Dasar perairan yang memiliki ciri-ciri yang sama,
perbedaan indeks kekasaran diamati berdasarkan perbedaan dua frekuensi yang
perbedaan yang timbul dari frekuensi 40 dan 208 kHz disebabkan oleh perbedaan
penetrasi dasar laut berdasarkan frekuensi pada berbagai tipe dasar perairan.
Kagesten (2008) menjelaskan bahwa klasifikasi sedimen dapat dilakukan
dengan menganalisis nilai amplitudo, yaitu kuatnya intensitas sinyal suara yang
diterima oleh receiver dalam bentuk energi listrik (backscatter). Multibeam sonar
memiliki kemampuan untuk membedakan dasar laut melalui analisis nilai
amplitudo, sedimen yang keras akan memantulkan nilai amplitudo yang tinggi yang dipengaruhi oleh tingkat kekerasan dan kekasaran dasar tersebut. Analisis
terhadap amplitudo dari gelombang suara yang kembali dapat menghasilkan
informasi mengenai struktur dan kekerasan dari dasar laut. Amplitudo dari
Multibeam sonar mempunyai sapuan dan detail yang lebih baik dibanding dengan
single beam, namun proses pengolahan data lebih kompleks. Berdasarkan penjelasan tersebut besaran amplitudo dapat dihitung dengan persamaan 3.
, I = Intensity [W/m2], I0 = 1012 W/m2………..(3)
2.6. Ketentuan Pembangunan Jembatan
Gagasan untuk menghubungkan pulau-pulau di nusantara ini dicetuskan
oleh almarhum Prof. Sedyatmo yaitu menghubungkan pulau Sumatera dengan
pulau Jawa. Pada bulan April 1986, Bapak Presiden RI ke-2 meminta untuk
dilakukan studi kemungkinan-kemungkinan untuk merealisasikan gagasan
tersebut. Oleh karena itu, pada bulan Januari 1989 telah disepakati bersama
antara BPPT, Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum untuk melaksanakan
studi hubungan Jawa-Sumatera-Bali. Studi ini dikenal dengan nama “Tri Nusa
Ada 3 alternatif sarana penyeberangan selat Sunda yaitu terowongan di
bawah dasar laut, terowongan terapung dan jembatan panjang. Namun demikian,
selama pembuatan jembatan memungkinkan alternatif ini pada umumnya paling
murah dan memberikan berbagai keuntungan yang lebih baik dari pada alternatif
terowongan. Sehingga dalam usaha mewujudkan penyeberangan Selat Sunda
selanjutnya dilakukan studi kelayakan jembatan penyeberangan untuk
menentukan panjang bentang dan kedalaman pondasi yang paling optimal,
kemudian langsung dilanjutkan dengan desain. Diperkirakan jembatan ini
memiliki panjang total kurang lebih 27,4 km dan waktu pembangunan kurang
lebih 13 tahun.
Lingkup kerja pra-studi pembangunan jembatan Selat Sunda terdiri atas
empat paket, yaitu paket I pemetaan, paket II geologi, paket III pra desain dan
paket IV kajian lingkungan (Wiratman, 2008). Paket I meliputi topografi,
hidrografi (batimetri), sub bottom prifiling (profil dasar laut), oseanografi (arus,
gelombang, pasang surut), studi tsunami, side scan sonar test (citra dasar laut),
magnetometri (pendeteksian obyek logam) dan klimatologi & meteorology. Paket
II meliputi pengeboran dasar laut, studi geologi, geologi teknik, vulkanologi
seismologi dan rekayasa gempa studi geoteknik. Paket III meliputi studi
transportasi, desain geometri (alinyemen horisontal dan vertikal), studi banding,
studi material dan metode konstruksi pra desain jembatan (struktur atas/bawah),
uji terowongan angin, uji hidrodinamika (sedimentasi dan abrasi). Tahap IV
meliputi kajian fisika-kimia, biologi darat dan laut, sosial budaya dan kesehatan
2.6.1. Definisi Jembatan
Jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewatkan
angkutan di atas suatu penghalang. Jembatan dibangun untuk memberikan ruang
bagi pejalan kaki, pemandu kenderaan atau kereta api di atas halangan tersebut.
Jembatan terdiri dari enam bagian pokok yaitu:
1. Bagian atas jembatan yaitu bagian struktur jembatan yang berada pada
bagian atas jembatan, berfungsi menampung beban-beban yang
ditimbulkan oleh lalu lintas orang dan kendaraan dan juga yang lain
kemudian menyalurkannya kebangunan bawah.
2. Landasan yaitu bagian ujung bawah dari suatu bagian atas jembatan yang
berfungsi menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas ke bangunan
bawah.
3. Bagian bawah jembatan yaitu bagian struktur jembatan yang berada di
bawah struktur atas jembatan yang berfunsi untuk menerima/memikul
beban-beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian
menyalurkannya ke pondasi.
4. Pondasi yaitu bagian struktur jembatan yang berfungsi untuk menerima
beban beban dari bangunan bawah dan menyalurkannya ke tanah.
5. Oprit yaitu timbunan tanah di belakang bangunan bawah jembatan yang
terletak pada kedua ujung pilar–pilar jembatan (abutment), timbunan
tanah ini harus dibuat sepadat mungkin untuk menghindari terjadinya
6. Bangunan pengaman jembatan yaitu bagian struktur jembatan yang
berfunsi untuk pengamanan terhadap pengaruh sungai yang bersangkutan
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sumber: Ohio Department of Transportation (2012)
Gambar 4. Bagian pokok jembatan
2.6.2. Tiang Pondasi
Fungsi dari tiang pondasi adalah untuk mendukung seluruh bangunan di
atasnya dan mentransfer beban dari bangunan ke tanah atau batuan. Berbagai
tipe tiang yang digunakan dalam konstruksi pondasi sangat tergantung pada
beban yang bekerja pada pondasi tersebut selain tersedianya bahan yang ada,
juga cara-cara pelaksanaan pemancangannya. Klasifikasi tiang pondasi
berdasarkan tiang meneruskan beban dapat dibedakan menjadi dua (Usman et al.,
2004) yaitu :
1. Tiang tahanan ujung ( End Bearing Pile). Bila ujung tiang mencapai
tanah keras dengan kuat dukung tinggi, maka beban yang diterima akan
2. Tiang tahanan lekatan antara tiang dengan tanah (Friction piles). Bila
tiang dipancangkan pada tanah dengan nilai kuat gesek tinggi (jenis
tanah pasir), maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan
berdasarkan gesekan antara tiang dan tanah sekeliling tiang (Gambar 5b).
(a) (b)
Sumber: Usman et al., (2004)
17 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Pengukuran kedalaman laut atau pemeruman pada penelitian ini dilakukan
di perairan Selat Sunda yang dimaksudkan untuk mendapatkan data kedalaman
laut, morfologi dasar laut dan sebaran sedimaen yang terdapat pada perairan
tersebut. Survei ini perlu dilakukan terutama untuk memperoleh gambaran
kedalaman dasar laut dan hubungannya dengan konstruksi jembatan yang akan
dibangun sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra.
Pemeruman dilakukan dengan menggunakan intrumen multibeam tipe SEA
BEAM 1050 D yang terdapat pada kapal riset Baruna Jaya IV (Lampiran 2) milik
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tanggal 27 Desember
2010 sampai dengan 1 Januari 2011 di perairan Selat Sunda yaitu pada kordinat
5052’-6002’ LS dan 105045’-106054’ BT. Pemeruman ini dilakukan untuk
mendapatkan morfologi dasar perairan Selat Sunda sebagai perencanaan dalam
pembangunan Jembatan Selat Sunda yang rencananya akan mulai dijalankan pada
awal tahun 2014. Pengolahan data akustik dilakukan di Laboratorium Akustik
dan Instrumentasi Kelautan, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dan Laboratorium Balai
Teknologi Survei Kelautan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gambar 6. Peta lokasi penelitian di perairan Selat Sunda
3.2. Perolehan Data Penelitian 3.2.1 Data Pasang Surut
Data pasang surut diperoleh dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional (BAKOSURTANAL) yang diambil pada bulan Desembar 2010. Stasiun
pengamatan pasang surut terletak di perairan Ciwandan, Banten yaitu pada
kordinat 6001’09” LS dan 105057’03” BT. Stasiun tersebut merupakan tempat
yang sangat dekat dengan daerah peneliatian. Menurut Hasanudin (2009) data
pasang surut yang digunakan sebaiknya data pasang surut lokasi penelitian atau
dari lokasi yang terdekat dengan daerah penelitian. Instrumen yang digunakan
adalah Tide Gauge Valeport 740 (Gambar 7), pengukuran dilakukan selama 30
hari dengan interval waktu pengambilan setiap 1 jam.
Pengukuran pasang surut dilakukan sesuai dengan ketetapan Special
Gambar 7. Tide gauge valeport 740
3.2.2 Data Sampel Coring
Data sampel coring diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan
Geologi Kelautan (PPPGL). Pengambilan sampel tersebut dilakukan pada
pertengahan bulan Maret sampai dengan awal bulan April tahun 2010. Peralatan
yang digunakan dalam pengambilan contoh sedimen permukaan dasar laut adalah
Gravity core dan grab sampler (Gambar 8). Spesifikasi dari gravity core yang
digunakan dapat terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Spesifikasi gravity core
No Spesifikasi Satuan Alat
1 Diameter tabung 2,5 inchi
2 Panjang 100 cm
3 Pemberat 60 kg
4 Panjang kabel 150 m
5 Penggerak winch (penggerak mesin)
Penggunaan gravity core dan grab sampler bergantung pada kondisi
sedimen di lokasi pengambilan sampel. Penggunaan kedua peralatan dalam
yang maksimal, sehingga data yang dihasilkan dapat mewakili dan
menginterpretasikan sebaran sedimen di perairan Selat Sunda.
Gambar 8. Peralatan sampling sedimen pada kapal survei PPPGL; (a)gravity core, (b) grab sampler
3.2.3 Data Pemeruman
Pengambilan data akustik atau pemeruman dilakukan dengan
menggunakan instrumen SEA BEAM 1050 D multibeam sonar yang dioperasikan
dengan frekuensi 50 kHz. Sebelum dilakukan pemeruman, kapal yang digunakan
harus dilakukan koreksi offset, yaitu penentuan titik referensi kapal. Nilai offset
dari setiap sensor yang digunakan harus dihitung terhadap center line. Nilai offset
tersebut penting untuk melakukan koreksi dari beberapa sensor yang digunakan
terhadap sumbu salib kapal. Berikut merupakan offset dari multibeam ELAC SEA
BEAM 1050 D, DGPS Sea star 8200 VB yang digunakan untuk penentuan posisi
kapal dengan metode Real Time Differensial GPS (RTDGPS) dan Coda Octopus
F180 yang berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap pengaruh perubahan
vertikal pada beam (heading, pitching dan rolling) (Gambar 9).
Gambar 9. Posisi offset sensor pada Kapal Baruna Jaya IV
Coda Octopus F180 diasumsikan berada tepat pada posisi center line. Mekanisme koreksi offset dilakukan dengan pendekatan jarak dari masing-masing
instrumen tersebut dibuat nol sehingga ketiga instrumen tersebut diasumsikan
berhimpit (Djunarsjah, 2005). Pada sumbu x nilai -0,530 m artinya posisi offset
Seastar 8200 VB digeser ke arah kiri sejauh 0,530 m sedangkan pada sumbu z, draft transduser dinaikan sejauh 3,40 m sehingga diasumsikan berhimpit pada center line. Sistem navigasi yang digunakan dalam Kapal Baruna Jaya IV diatur
dalam perangkat lunak Hypack yang secara langsung terhubung dengan sistem
akuisisi data multibeam ELAC SEA BEAM 1050D.
Pengambilan sampel sedimen atau coring dilakukan oleh Pusat Penelitian
dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) pada pertengahan bulan Maret
sanpai dengan awal bulan Mei 2010. Pengambilan sampel sedimen tersebut
alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan pengolahannya pada penelitian
ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
Perangkat Keras Perangkat lunak
Multibeam Sonar (SEA BEAM 1050 D) MB System (Basis Linux) Personal Computer (PC) Generic Mapping Tool (GMT)
Gravity core Caris HIPS & SIPS 6.1
Grab sampler ArcGis 7.2
Microsoft Excel 2007
Akuisisi data multibeam dilakukan menggunakan perangkat lunak
Hydrostar. Data yang telah diakuisisi selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak CARIS HIPS and SIPS 6.1 dan MB Systems. Perangkat lunak CARIS HIPS
and SIPS 6.1 digunakan untuk mengolah nilai kedalaman sehingga didapatkan produk akhir berupa peta batimetri yang divisualisasikan menggunakan perangkat
lunak Generic Mapping Tool (GMT ) baik secara dua dimensi maupun tiga
dimensi. Perangkat lunak MB Systems digunakan untuk melakukan klasifikasi
dasar perairan dengan mencocokan nilai amplitudo yang sudah diinterpolasi
dengan data hasil coring. Informasi yang telah didapatkan kemudian digunakan
sebagai informasi utama dalam perencanaan peletakan tiang jembatan. Gambar
10 merupakan diagram alir sistem akuisisi dan pengolahan data multibeam ELAC
Gambar 10. Diagram alir perolehan data multibeam sonar
3.3. Pemrosesan Data
3.3.1 Pemrosesan Data Pasang Surut
Data pasang surut diolah dengan menggunakan Metode admiralty. Metode
admiralty merupakan metode pengolahan data pasut yang disederhanakan untuk
menentukan amplitudo (A) dan fase (G) dari komponen-komponen utama pasang
surut. Pengolahan data pada metode admiralty sangat sederhana yaitu hanya
dengan memasukkan nilai tinggi pasang surut pada program admiralty. Proses
ini akan menghasilkan konstanta pasang surut yang akan digunakan dalam
penentuan tipe pasut dengan bilangan formzahl. Penentuan tipe pasut dengan
menggunakan rumus Formzahl adalah sebagai berikut : XSE* Data Processing
MB system
GMT 2D dan 3D GMT
XSE* Data Processing Caris HIPS and SIPS
……….…(4)
Keterangan:
F = nilai Formzahl
K1 dan O1 = amplitudo komponen pasut diurnal
M2 dan S2 = amplitudo komponen pasut semidiurnal
Dengan kisaran nilai Formzahl:
0.00 < F ≤ 0,25 = tipe pasut semidiurnal
0,25 < F ≤ 1,50 = tipe pasut campuran cenderung semidiurnal 1,50 < F ≤ 3,00 = tipe pasut campuran cenderung diurnal F ≥ 3,00 = tipe pasut diurnal
Setelah bilangan formzahl diperoleh, maka dapat ditentukan tipe pasang
surut pada lokasi penelitian. Secara garis besar langkah yang digunakan pada
metode admiralty tampak seperti pada diagram alir di bawah ini.
Gambar 11. Diagram alir pengolahan data pasang surut dengan metode admiralty Tipe Pasang Surut
Lihat Kisaran
Bilangan Formzahl
Diperoleh Konstanta Pasang Surut Input Data Pasang Surut
Hitung Konstanta dengan
Rumus Formzahl
3.3.2 Pemrosesan Data Kedalaman
Pengolahan data kedalaman dilakukan menggunakan perangkat lunak
CARIS HIPS&SIPS 6.1 milik BPPT dengan nomor seri CW9605878. Tahap awal pengolahan data adalah pembuatan file kapal (Vessel file). Vessel file berisi nilai
jarak setiap sensor yang direferensikan terhadap titik pusat kapal (centre line).
Proses berikutnya, yaitu pembuatan proyek baru (create new project) denga
menggunakan vessel file yang telah dibuat. Setelah proyek dibuat, data
kedalaman dalam bentuk *XSE diubah menjadi hsfmenggunakan menu
Conversion Wizard sehingga data tersebut dapat diproses dalam perangkat lunak
CARIS HIPS&SIPS 6.1.
Data kedalaman tersebut selanjutnya dikoreksi (Clean Auxiliary Sensor
Data) menggunakan menu Swath Editor untuk menghilangkan ping yang
dianggap buruk, menu Altiutde Editor dan Navigation Editor kemudian digunakan
untuk menghilangkan pengaruh pergerakan dan kecepatan kapal yang memiliki
nilai diluar kisaran. Setelah koreksi data dilakukan kemudian masukan parameter
yang mempengaruhi nilai kedalaman, yaitu pasang surut dan kecepatan
gelombang suara masing-masing melalui menu Load Tide dan Sound Velocity
Correction. Data tersebut kemudian digabungkan (Merging) untuk mendapatkan hasil akhir berupa peta batimetri. Peta batimetri tersebut kemudian diexport
kedalam bentuk ASCII sehingga dapat divisualisasikan menggunakan GMT
secara tiga dimensi. Gambar 12 merupakan diagram alir pemrosesan data data
Gambar 12. Diagram alir pemrosesan data kedalaman pada perangkat lunak CARIS HIPS&SIPS 6.1
Swath Editor
Altitude Editor
Navigation Editor Clean Auxiliary Sensor
Data
Convert Raw Data Create New Project Create a Vessel File
GMT 3D Merge
Product Surface Base Surface New Field Sheet
Export to ASCII
Sound Velocity Correction
3.3.3 Pemrosesan Data Amplitudo
Data amplitudo yang diperoleh harus dilakukan beberapa kalibrasi
menggunakan softwawe MB System. Beberapa kalibrasi yang dilakukan adalah
kedalaman perairan, kecepatan suara dan navigasi kapal. Masing-masing beam
akan memancarkan gelombang suara hingga mengenai dasar perairan yang
kemudian dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver. Sinyal yang diterima
receiver akan disimpan dengan format *.XSE, data ini merupakan data mentah. MBCLEAN merupakan proses penyaringan secara otomatis yang
dilakukan oleh alat untuk beam yang menghasilkan nilai buruk. MBEDIT
merupakan tindak lanjut MBCLEAN dengan memberikan visualisasi terhadap nilai
kedalaman yang akan dikoreksi. MBNAVEDIT merupakan kalibrasi yang
dilakukan terhadap gerakan kapal seperti heave, picth dan roll.
MBVELOCITYTOOL merupakan proses kalibrasi terhadap besarnya kecepatan suara selama pengambilan data berlangsung. MBBACKANGEL
merupakan kalibrasi yang dilakukan dengan cara memunculkan tabel amplitudo
dengan grazing angel yang digunakan sebagai acuan untuk nilai amplitudo
dengan kedalaman. MBPROSES meruapakan proses yang dilakukan untuk
mengabungkan semua kalibrasi dan menghasilkan keluaran data dengan format
*.mb94.
Klasifikasi dasar perairan merupakan pemetaan sebaran jenis sedimen
yang terdapat pada suatu perairan. Sedimen pada suatu perairan cenderung
didominasi oleh satu atau beberapa jenis partikel, akan tetapi mereka tetap terdiri
dari ukuran yang berbeda-beda (Hutabarat dan Evants, 1985). Setiap sampel
diketahui dengan cara mencocokkan posisi atau kordinat pada sampel coring
dengan data hasil ekstrak. Penentuan nilai amplitudo dilakukan pada titik
kordinat pada beam yang memiliki kordinat sama dengan posisi sampel coring,
kemudian diambil beberapa penarikan contoh nilai amplitudo di sekitar titik
sampel coring serta pada ping sebelum dan sesudah pada beam yang sama di
pengambilan coring.
Proses berikutnya adalah menampilkan peta sebaran sedimen berdasarkan
nilai amplitudonya. Gambar 13 merupakan diagram alir pemrosesan nilai
amplitudo pada perangkat lunak MB System. Peletakan tiang jembatan Selat
Sunda disesuaikan dengan melihat sebaran jenis sedimen yang ada pada perairan
tersebut.
Gambar 13. Diagram alir pemrosesan data amplitudo pada perangkat lunak MB System
Koreksi (*XSE) MBPROCESS MBNAVEDIT
29 4.1. Pasang Surut
Pasang surut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya
permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi
dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari dan
bulan. Data hasil pengamatan diuraikan menjadi komponen harmonik. Hasil
akhir perhitungan dengan menggunakan metode admiralty dapat dilihat pada
Tablel 4 berikut.
Tabel 4. Konstanta harmonik di lokasi penelitian
S0 M2 S2 N2 K1 O1 M4 MS4 K2 P1
S0 = Muka laut rata-rata (mean sea level)
M2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh posisi bulan
S2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh posisi matahari
N2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh perubahan jarak bulan
K1 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh deklinasi bulan dan matahari
O1 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh deklinasi bulan
M4 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh pengaruh ganda M2
MS4 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh interaksi antara M2 dan S2
K2 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh perubahan jarak matahari
P1 = Konstanta harmonik yang dipengaruhi oleh deklinasi matahari
Konstanta harmonik tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan,
yaitu koreksi batimetri. Menurut Sasmita (2008) untuk mengurangi kesalahan,
nilai kedalaman yang didapatkan dari pemeruman dikoreksi dengan menggunakan
nilai Mean Sea Level (MSL) sehingga menghasilkan data kedalaman yang akurat.
atau chart datum yang dapat digunakan sebagai referensi ketinggian dengan
diikatkan ke bench mark.
Berdasarkan konstanta harmonik di atas diperoleh nilai bilangan formzahl
sebesar 0,52. Hal ini menujukkan bahwa pada lokasi penelitian mempunyai tipe
pasang surut campuran. Hasil ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Witasari dan Rubiman (2003),
menjelaskan pasang surut di perairan Selat Sunda memiliki tipe pasang surut
campuran dominan ganda. Gambar 14 menunjukan pasang surut di lokasi
penelitian dengan sumbu x sebagai waktu pengambilan data dan sumbu y sebagai
tinggi pasang surut. Nilai kisaran pasang surut di lokasi penelitian sebesar
0,85-1,68 m.
Gambar 14. Pasang surut di lokasi penelitian pada bulan Desember 2010
Pasang surut tipe campuran merupakan tipe pasang surut yang
memungkinkan dalam sehari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut
dengan tinggi dan periode yang berbeda. Data pasang surut pada suatu wilayah
dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur,
khususnya dalam pemodelan desain konstruksi. Nilai MSL yang diperoleh 136,5
pemeruman. Nilai MSL diartikan sebagai tinggi muka air rata-rata antara muka
air tinggi rata-rata dan muka air rendah rata-rata, elevasi ini sering digunakan
sebagai referensi elevasi di daratan. Siswanto (2010) menyatakan bahwa tipe
pasang surut campuran mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap sebaran
dan distribusi sedimen permukaan dasar, sehingga hal demikian sesuai bila pada
perairan ini akan dibangun sebuah jembatan.
4.2. Profil Batimetri
Profil batimetri dapat memberikan informasi mengenai struktur dan asal
pembentukan dasar laut karena dasar perairan sendiri dapat berupa pasir, lumpur,
atau batuan. Profil batimetri merupakan informasi awal dalam pertimbangan
kegiatan bawah laut seperti pemasangan kabel dan peletakan pipa bawah laut.
Kemiringan dan unsur yang menyusun dasar perairan merupakan hal yang sangat
dipertimbangkan dalam kegiatan tersebut. Jalur pipa dan kabel bawah laut
ditentukan secara optimal dengan mengacu pada peta geologi dasar laut.
Perairan Selat Sunda merupakan perairan yang sangat unik karena perairan
tersebut mendapatkan pengaruh dari dua perairan yang berbeda yaitu dari perairan
Laut Jawa sebagai perairan dangkal dan dari perairan Samudra Hindia. Gambar
15 merupakan jalur atau track kapal survei batimetri yang dilakukan di lokasi
Gambar 15. Track kapal survei batimetri di lokasi penelitian
Profil batimetri perairan Selat Sunda mempunyai gradasi yang nyata, hal
tersebut ditunjukkan dari hasil pemeruman kedalaman bervariasi antara 17,5 m
sampai dengan 175 m. Perubahan kedalaman terjadi secara bergradasi mulai dari
perairan Banten dan berangsur-angsur bertambah dalam menuju ke perairan
Lampung.
Nilai keakuratan data yang diperoleh selama akuisisi dijaga agar selalu
tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan peta batimetri yang akurat.
Berdasarkan ketentuan IHO Tahun 2008, lokasi penelitian termasuk dalam orde
dua dengan ketelitian horizontal sebesar 150 meter. Spasi lajur perum maksimum
orde ini yaitu empat kali kedalaman rata-rata. Special Publication No. 44
(S.44)-IHO Tahun 1998 menjelaskan bahwa skala pemeruman menentukan resolusi dari
peta batimetri yang dihasilkan (Lampiran 3). Gambar 16 merupakan profil tiga
dimensi batimetri lokasi penelitian.
Gambar 16. Profil 3 dimensi batimetri lokasi penelitian
E E E E
50 52’ S
50 54’ S
5056’ S
50 58’ S
6000’ S
6002’ S
E E E E
50 52’ S
50 54’ S
5056’ S
50 58’ S
6000’ S
6002’ S
Gambar 16 menunjukkan profil batimetri Selat Sunda yang diperoleh dari
hasil pemeruman, dimana pada gambar tersebut terlihat pola batimetri yang tidak
rata. Hasil pemeruman menujukkan bahwa perairan ini termasuk dalam kategori
perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata antara 35-52,5 m. Kedalaman
perairan yang terdeteksi menunjukkan adanya variasi kedalaman yang berbeda
untuk setiap posisi lintang dan bujur, ada yang berupa paparan dan ada juga yang
berupa slope.
Kedalaman tertinggi berada kordinat 5054’32,14” LS dan 105047’19,21” BT
dengan nilai kedalaman antara 157,5-175,5 m. Posisi tersebut merupakan sebuah
palung, yaitu dasarlaut yang dalam yang biasanya diakibatkan oleh menyusupnya
lempeng samudera ke bawah lempeng benua. Jadi lokasi palung berada di
daerah-daerah tumbukan lempeng benua dan samudera. Kedalaman palung
sangat berbeda dengan kedalaman di daerah sekitarnya. Selain itu juga palung
terdapat pada kordinat 6000’58,12” LS dan 105051’46,38” BT. Palung pada
kordinat ini terbentuk lebih lebar namun memiliki kedalaman yang berbeda, yakni
lebih dangkal berkisar antara 140-157,5 m.
4.3. Klasifikasi Dasar Perairan
Sedimen laut merupakan akumulasi dari mineral-mineral dan
pecahan-pecahan batuan yang bercampur dengan hancuran cangkang dan tulang dari
organisme laut serta beberapa partikel lain yang terbentuk melalui proses kimia
yang terjadi di laut (Gross, 1999). Selat sunda mempunyai jenis sedimen yang
beragam, menurut Helfinalis (2003) jenis sedimen di dasar perairan Selat Sunda
Jenis sedimen clayey silt tersebar dari perairan barat Banten hingga ke sisi
perairan timur Bakauhuni. Penyebaran tersebut sangat dipengaruhi oleh aktifitas
arus yang melintasi perairan Selat Sunda.
Klasifikasi jenis sedimen dasar laut dapat dilakukan dengan menggunakan
nilai sebaran amplitudo, yaitu kuatnya intensitas sinyal suara yang diterima oleh
receiver dalam bentuk energi listrik. Data amplitudo difilter dan diinterpolasi
dengan menggunakan metode Gaussian Weighted Mean. Pemilihan metode
tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai amplitudo seluruh lokasi
pemeruman. Gaussian Weighted Mean melakukan pemfilteran terhadap data
amplitudo dari setiap beam. Amplitudo pada metode ini merupakan fungsi
eksponensial dari arah antar beam dan normal factor. Nilai amplitudo yang
digunakan sebagai patokan dalam klasifikasi jenis sedimen dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti source level, frekuensi yang digunakan, sudut datang,
jarak kolom air, kekerasan, kekasaran, ukuran butiran, densitas dan luas
permukaan (Urick, 1983).
Berdasarkan data survei PPPGL terdapat 22 stasiun pengambilan data
sampel coring dengan jenis sedimen yang teridentifikitasi yaitu silty sand, sandy
silt, sand dan rocks (Lampiran 4). Setiap sampel coring memiliki data posisi atau kordinat, kordinat tersebut dioverlay terhadap nilai amplitudo yang dihasilkan dari
hasil pemeruman. Setiap jenis sedimen akan mempunyai kisaran amplitudo, nilai
inilah yang digunakan untuk klasifikasi dasar perairan. Kisaran nilai amplitudo
Gambar 17. Grafik sebaran nilai amplitudo berdasarkan data coring
Pengambilan data sampel coring dilakukan di sekitar jalur penelitian.
Gambar 17 menunjukkan sebaran nilai ampltitudo dasar perairan yang diperoleh
dari data pemeruman yang telah diekstrak dengan mencocokkan kordinat sampel
coring. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut diperoleh sebaran nilai amplitudo
dengan nilai minimum sebesar 250 dan nilai maksimum sebesar 500. Kisaran
nilai amplitudo tersebut didasarkan pada jenis sedimen yang ditemui dari hasil
pengambilan sampel coring, dimana terdiri atas empat jenis sedimen yaitu, silty
sand, sandy silt, sand dan rocks. Keempat jenis sedimen tersebut kemudian
diplotkan kedalam peta klasifikasi dasar perairan.
Penelitian mengenai klasifikasi jenis sedimen dasar laut menggunakan
nilai amplitudo dicocokkan dengan hasil pengambilan sampel coring telah
dilakukan oleh Aritonang pada tahun 2010 di perairan Labuhan Maringgai
(Lampung)-Bojonegara (Banten) menggunakan data multibeam Elac Seabeam
pertimbangan dalam kegiatan peletakan pipa bawah laut di perairan Balongan,
Indramayu. Hasil penelitian tersebut menujukkan sebaran sedimen di lokasi
penelitain dengan kisaran ampltitudo tertentu yang bergantung pada jenis
sedimennya. Tabel 5 memperlihatkan kisaran ampltitudo dan jenis sedimen dari
penelitian yang pernah dilakukan.
Tabel 5. Kisaran ampltitudo dan jenis sedimen di lokasi penelitian
Peneliti Kisaran
Amplitudo
Jenis Sedimen Ukuran Butiran
(mm)
Aritonang (2010)
311-352 Silty clay 0,004-0,062
352-399 Clayey silt <0,004
399-428 Sandy silt 0,062-2
Gumbira (2011)
300-350 Silt 0,01-0,08
350-400 Silty clay 0,008-0,01
400-450 Clayey silt 0,001-0,01
Penelitian ini (2012)
250-297 Silty Sand 0,004-0,04
297-360 Sandy Silt 0,04-0,062
360-403 Sand 0,062-2
403-500 Rocks > 256
Dasar perairan laut memiliki karakteristik memantulkan dan
menghamburkan kembali gelombang suara seperti halnya permukaan perairan
laut. Perbedaan nilai amplitudo yang didapatkan disebabkan kedalaman kolom
perairan dan ukuran butiran sedimen yang berbeda (Urick, 1983). Nilai amplitudo
yang berada di luar kisaran dianggap sebagai data yang tidak terdeteksi. Nilai
amplitudo difilter sehingga hanya dihasilkan nilai amplitudo dari lokasi penelitian.
Nilai inilah yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat sebaran sedimen
di lokasi penelitian. Gambar 18 merupakan perbedaan antara nilai ampltitudo
Gambar 18. Kisaran nilai amplitudo: (a) sebelum difilter, (b) setelah difilter
Gambar 18a merupakan kisaran nilai amplitudo pada lokasi penelitian
yang belum difilter. Pada gambar tersebut terdapat dua kisaran nilai amplitudo
yang mempunyai selang sangat besar, pertama pada nilai amplitudo terendah yaitu
pada selang -371,096 ke 267,273 dan kedua terdapat pada akhir selang yaitu dari
398,735 ke 1300,730. Nilai ini diindikasi berasal dari data yang tidak terdeteksi,
sehingga untuk selanjutnya kisaran nilai ini tidak diperlukan. Kisaran nilai
ampltitudo yang tidak diperlukan dibuang atau difilter melalui perangkat lunak
MB System berbasis linux. Pemfilteran ini dilakukan secara manual dengan cara
mengamati kisaran nilai amplitudo kemudian mengubah nilai dan selang
amplitudo yang benar-benar berasal dari lokasi penelitian. Setelah dilakukan
pemfilteran kisaran nilai amplitudo pada lokasi penelitian berada pada selang
250-500 (Gambar 18b), nilai inilah yang kemudian dipakai untuk melihat sebaran
sedimen.
a
b
Peta klasifikasi dasar perairan memperlihatkan sebaran jenis sedimen yang
teramati secara spasial melalui pemeruman. Data hasil pemeruman yang diolah
menjadi peta klasifikasi dasar perairan merupakan hasil olahan nilai amplitudo
yang terdeteksi. Klasifikasi dasar perairan pada penelitian ini dimulai dari
perairan di sekitar Banten sampai ke perairan Lampung. Kisaran nilai amplitudo
dari 250-500 terdiri atas empat jenis sedimen, dimana setiap jenis sedimen
mempunyai kisaran nilai amplitudo yang berbeda-beda.
Perairan Selat Sunda merupakan perairan yang sangat unik, hal demikian
terlihat pada sebaran sedimen yang berbeda dengan perairan yang lain. Perairan
Selat Sunda mendapatkan pengaruh dari dua perairan yang mempunyai karakter
berbeda yaitu Laut Jawa dan Samudera Hindia. Laut Jawa relatif mempunyai
aktifitas oseanografi yang lemah, berbeda dengan perairan Samudera Hindia yang
mempunyai aktifitas oseanografi yang relatif lebih tinggi. Hal tersebut
berpengaruh terhadap sebaran sedimen di sekitar Pulau Sangiang, dimana pada
sebelah barat pulau sangiang jenis sedimen didominasi oleh rocks dan di sebelah
timur didominasi oleh sandy silt. Hal ini terjadi karena energi atau arus yang
berasal dari perairan Samudera Hindia lebih besar dari arus Laut Jawa yang
bergerak ke arah perairan Selat Sunda, sehingga partikel yang berukuran kecil
akan terbawa oleh energi atau arus yang berasal dari perairan Samudera Hindia ke
sebelah timur dan timur laut Pulau Sangiang. Gambar 19 merupakan peta
Gambar 19. Peta klasifikasi jenis sedimen dasar perairan di lokasi penelitian
Klasifikasi jenis sedimen dasar perairan yang terlihat pada gambar di atas
sebagian besar ditutupi oleh jenis sedimen sandy silt dengan persen penutupan Silty sand
Sandy silt Sand Rocks
P. Sangiang
5052’ S
5054’ S
5056’ S
5058’ S
6000’ S
60 02’ S
5052’ S
5054’ S
5056’ S
5058’ S
6000’ S
60 02’ S
E E E E
sebesar 49%. Kisaran nilai amplitudo jenis sedimen ini berada pada 297-360.
Sandy silt di lokasi penelitian menyebar secara merata yaitu dari perairan di sekitar Banten sampai ke perairan Lampung. Helfinalis (2003) menyatakan
bahwa endapan sedimen di perairan Ciwandan dan perairan Anyer didominasi
oleh kerikil dan pasir. Jenis sedimen berikutnya yaitu silty sand dengan persen
penutupan sebesar 18,22%. Jenis sedimen ini terfokus pada perairan Selatan
Lampung yaitu pada kordinat 5052’-5056’ LS dan 105047’-105050’ BT. Selain itu
silty sand juga berada di sebelah selatan Pulau Sangiang. Rocks atau batuan hanya berada di sebelah barat Pulau Sangiang dengan persen penutupan sebesar
11,69%. Jenis batuan dari hasil coring merupakan batuan yang berupa
pecahan-pecahan karang. Jenis sedimen yang terakhir yaitu sand dengan persen penutupan
sebesar 16,82% yang berada di sekitar pulau Sangiang dan sebagian kecil
menyebar di sepanjang jalur penelitian.
Pada peta klasifikasi dasar perairan terdapat spot-spot yang berwarna
hitam, bagian ini merupakan bagian yang tidak teridentikasi atau bagian yang
tidak termasuk ke dalam selang nilai amplitudo yang ada. Nilai amplitudo yang
lebih besar dari 500 diartikan bahwa jenis sedimen yang tidak teridentifikasi lebih
keras dari jenis sedimen rocks sedangkan nilai amplitudo yang lebih kecil dari 250
diartikan bahwa jenis sedimen lebih lunak dari silty sand. Dengan demikian nilai
amplitudo yang lebih besar dari 500 dan lebih kecil dari 250 dikatakan sebagai
kelas yang tidak teridentifikasi. Jenis sedimen yang tidak teridentifikasi memiliki
persen penutupan sebesar 4,27%. Gambar 20 merupakan presentasi sebaran
Gambar 20. Persentase sebaran sedimen di lokasi penelitian
Sedimen di laut tersusun oleh 4 komponen pokok yang diklasifikasikan
berdasarkan asal-usulnya, yaitu sebagai sedimen terigenik (dari daratan dan
lingkungan vulkanik), biogenik (dari aktifitas organisme), halmirogenik (dari
reaksi inorgenik) dan kosmogenik (dari luar angkasa). Menurut Rubiman (2003),
sedimen di perairan Selat Sunda tersusun dari endapan biogenik, terigenik dan
halmirogenik. Jenis sedimen pada penelitian ini umumnya didominasi oleh jenis
sedimen golongan biogenik yaitu jenis sedimen yang berasal dari organisme laut
yang telah mati terdiri atas remah-remah tulang, gigi-geligi dan
cangkang-cangkang tanaman maupun hewan mikro. Hasil coring menunjukkan jenis
sedimen pada lokasi penelitian berasal dari cangkang-cangkang organisme dan
4.4. Ketentuan Pembangunan Jembatan
Penelitian ini mengkaji pra-studi pembangunan jembatan Selat Sunda
hanya pada dua parameter dari paket I yaitu profil batimetri dan pasang surut.
Profil batimetri di perairan Selat Sunda sangat bervariasi, seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya kedalamannya bergradasi mulai dari perairan Banten yang
berangsur-angsur bertambah dalam menuju ke perairan Lampung. Berdasarkan
hasil pemeruman yang telah dilakukan kedalaman berkisar antara 17,5-175 m.
Perairan Selat Sunda yang merupakan penghubung Pulau Sumatera dan
Pulau Jawa memiliki kondisi batimetri yang sangat bervariasi. Pada umumnya
perairan sebelah timur bagian utara Selat Sunda cukup dangkal dengan kedalaman
rata-rata berkisar antara 20 hingga 80 m, sedangkan untuk perairan sebelah barat
bagian selatan Selat Sunda pada umumnya masih terpengaruh oleh kedalaman
dari Samudera Hindia yaitu kedalamannya lebih dari 100 m. Informasi
kedalaman ini merupakan informasi awal yang sangat penting untuk melihat
dimana lokasi peletakan tiang beton yang cocok agar dapat menopang beban
dalam jangka waktu yang sangat lama. Gambar 21 merupakan rencana peletakan
Sumber: Wiratman, 2008
Gambar 21. Rencana peletakan tiang beton dan jembatan gantung ultra panjang pada jembatan Selat Sunda
Berdasarkan hasil penelitian ini rencana peletakan tiang tersebut bisa
dikatakan sesuai, dengan melihat kedalaman pada lokasi satu (Gambar 21).
Lokasi tersebut mempunyai kedalaman berkisar 17-35 m, dimana pada lokasi
tersebut terdapat punggungan laut. Menurut Usman et al., 2004 menyatakan
bahwa punggungan laut dapat berfungsi sebagai tempat peletakan tiang pondasi di
laut. Namun untuk mengetahui kekuatan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
seperti dikorelasikan dengan data seismik. Hal yang sama terlihat pada lokasi 2, J
JeemmbbaattaannBBeettoonn
J
JeemmbbaattaannGGaannttuunnggUUllttrraa--PPaannjjaanngg
1 2
3 4
adanya punggungan laut yang lebih besar daripada wilayah 1. Pemasangan tiang
berikutnya akan dilakukan di daratan Pulau Sangiang, dimana pada daerah ini
tidak dilakukan pengamatan. Peletakan tiang pada Pulau Sangiang perlu
dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai struktur tanah pada pulau tersebut.
Lokasi 4 dan 5 tidak dapat ditentukan kesesuaian peletakan tiang, hal ini
dikarenakan tidak adanya data kedalaman pada wilayah tersebut. Lokasi 6 dan 7
berada di luar lokasi penelitian. Gambar 22 merupakan rencana peletakan tiang
beton yang diplotkan terhadap batimetri lokasi penelitian.
Gambar 22. Lokasi peletakan tiang beton pada jembatan Selat Sunda
1 5
4
3
Ketinggian tiang peyangga juga harus diperhatikan karena antara Pulau
Prajurit dan Pulau Sangiang merupakan jalur Alur Layar Kepulauan Indonesia
(ALKI), sehingga adanya jembatan Selat Sunda diharapkan tidak akan
mengganggu aktifitas pelayaran pada perairan tersebut.
Selain kedalaman perairain peletakan tiang juga memperhatikan jenis
sedimen pada wilayah yang akan dijadikan tempat penempatan tiang. Lokasi 1
dan 2 memiliki jenis sedimen sandy silt, jenis sedimen ini merupakan jenis
sedimen yang mempunyai gaya gesek yang tinggi. Menurut Usman et al, (2004)
jenis tiang yang digunakan adalah tiang tahanan lekatan antara tiang dengan
tanah (Friction piles) yaitu bila tiang dipancangkan pada tanah dengan nilai kuat
gesek tinggi (jenis tanah pasir), maka beban yang diterima oleh tiang akan ditahan
berdasarkan gesekan antara tiang dan tanah di sekeliling tiang.
Pasang surut dilokasi penelitian merupakan tipe pasang surut campuran
yaitu memungkinkan dalam sehari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air
surut dengan tinggi dan periode yang berbeda. Tipe pasang surut pada lokasi
penelitian menunjukkan range yang tidak begitu besar antara kondisi pasang dan
pada saat surut. Siswanto (2010) menyatakan bahwa tipe pasang surut ini
mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap sebaran dan distribusi sedimen
permukaan dasar laut. Hal tersebut dirasa cocok apabila pada perairan ini akan
dibangun jembatan karena aktifitas gerusan sedimen yang relatif kecil. Namun
untuk lebih memastikan perlu dilakukan pengamatan lebih serius terhadap arus,
47
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Pasang surut di lokasi penelitian termasuk kedalam jenis campuran. Nilai
MSL yang diperoleh 136,5 cm, nilai inilah yang digunakan dalam pengoreksian
data kedalaman dari hasil pemeruman. Profil batimetri perairan Selat Sunda
mempunyai gradasi yang nyata, hal tersebut ditunjukkan dari hasil pemeruman
kedalaman bervariasi antara 17,5 m sampai dengan 175 m. Berdasarkan hasil
pemeruman terdapat dua palung dengan kedalaman dan ukuran yang berbeda.
Klasifikasi jenis sedimen dasar laut dapat dilakukan dengan menggunakan nilai
sebaran amplitudo yaitu kuatnya intensitas sinyal suara yang diterima oleh
receiver dalam bentuk energi listrik. Hasil pemeruman menunjukkan kisaran nilai amplitudo pada lokasi penelitian berkisar antara 250-500, dimana pada selang
nilai amplitudo tersebut terdapat empat jenis sedimen yaitu silty sand, sandy silt,
sand dan rocks.
Berdasarkan hasil penelitian ini rencana peletakan tiang bisa dikatakan
sesuai yaitu pada lokasi 1 dan 2. Kedua lokasi tersebut merupakan punggung laut
dengan kedalaman berkisar antara 17-35 m, namun untuk mengetahui kekuatan
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti dikorelasikan dengan data seismik.
Selain itu, perairan Selat Sunda memiliki tipe pasang surut campuran dimana tipe
pasang surut ini mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap sebaran dan
5.2. Saran
Disarankan untuk penelitian berikutnya dalam bidang yang sama
menggunakan data yang lengkap, sehingga dalam interpretasi tidak mengalami
kesulitan. Selain itu juga perlu dilakukan pengkajian khusus mengenai jenis
sedimen dan lapisannya serta kecepatan arus, baik arus permukaan maupun arus
JEMBATAN SELAT SUNDA
AHMAD SIROJI
SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:
KOMPUTASI DATA
MULTIBEAM SONAR
UNTUK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT
SUNDA
adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Skripsi ini.
Bogor, Desember 2012
Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Dibimbing oleh HENRY M. MANIK dan DJOKO HARTOYO
Jembatan merupakan suatu kontruksi yang dibangun untuk sarana transportasi. Pemerintah Indonesia mencanangkan akan melaksanakan
pembangunan jembatan Selat Sunda pada awal tahun 2014 sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pembangunan jembatan tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan informasi yang relevan agar berjalan dengan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan instrumen hidroakustik multibeam sonar dalam interpretasi kedalaman dan sebaran jenis sedimen sebagai informasi utama dalam kegiatan pembangunan jembatan Selat Sunda.
Pemeruman dilakukan pada tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 1 Januari 2011 di perairan Selat Sunda yaitu pada kordinat 5052’-6002’ LS dan 105045’-106054’ BT. Pemeruman ini dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menggunakan Kapal Baruna Jaya IV. Alat yang digunakan untuk penentuan posisi yaitu DGPS Sea star 8200 VB yang bekerja dengan metode Real Time Differensial GPS (RTDGPS). Coda Octopus F180 berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap pengaruh perubahan vertikal pada beam (heading, pitching dan rolling). Perangkat lunak Caris HIPS&SIPS 6.1. digunakan untuk mengolah data kedalaman, sedangkan untuk untuk
mendapatkan nilai amplitudo yang digunakan untuk klasifikasi sedimen dasar laut menggunakan perangkat lunak MB-System berbasis linux.
Pasang surut di lokasi penelitian termasuk ke dalam tipe campuran,
Construction at Sunda Strait. Supervised by HENRY M. MANIK and construction of the bridge is running efficiently. The purpose of this research is to apply the instrument hydroacoustic of multibeam sonar to measure sea water depths and to map the distribution of sediment types. Survey conducted in Sunda Strait on the coordinates of 5052’-6002’S and 105045’-106054’E. Data acquisition done by using hydrostar software. Bathymetry data was processed with Caris HIPS&SIPS. Data amplitude was processed with MB Systems to make sediment classification. Tides in research area is mixture type, where tidal type is suitable for the construction of the bridge was held because tidal type has a relatively small effect on the scatter and distribution of sea floor sediments. Depth research area have range from 17,5-175 m, there are several ridge sea that can be used as a laying pole bridge. There are two locations considered suitable on location 1 and 2, where both the location is ridge sea with depth range17-35 m. The type of sediment obtained by processing data amplitude and core of sample sediment. The types of sedimen in research area are silty sand, sandy silt, sand and rocks. Sediment is dominated by sandy silt with percent coverage of 49%. Location 1 and 2 have a sandy silt sediment. The pole type that fits is the pillar of the prisoner's coherency between the pole to the ground (Friction piles), when the pole to stick on the ground with powerful high friction values such as sand, then load that is accepted by the mast will be withheld based on friction between the pole and the land around the pole.
© Hak Cipta milik Ahmad Siroji, tahun 2012
Hak cipta dilindungi
Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya
JEMBATAN SELAT SUNDA
AHMAD SIROJI
SKRIPSI
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan pada
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan
DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Judul Skripsi : KOMPUTASI DATA MULTIBEAM SONAR UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA
Nama Mahasiswa : Ahmad Siroji
Nomor Pokok : C54080047
Departemen : Ilmu dan Teknologi Kelautan
Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Utama Anggota
Dr. Ir. Henry M. Manik, M.T Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc NIP. 19701229 199703 1 008 NIP. 19681020 1994031 1 005
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan
Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc NIP. 19580909 1988303 1 003
viii
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas semua rahmat
dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa Rasul
tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan tauladan umat
islam. Skripsi yang berjudul KOMPUTASI DATA MULTIBEAM SONAR UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu
Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Selama menyelesaikan penelitian ini Penulis telah memperoleh banyak
dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis
mengucapkan terima kasih banyak kepada:
1. Kedua orang tua Penulis, Rosyidi dan Kartini beserta semua keluarga besar
Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.
2. Dr. Ir. Henry M. Manik, M.T dan Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc selaku komisi
pembimbing yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi,
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Ir. Totok Hestirianoto, M.Sc selaku penguji tamu, terima kasih atas saran
dan masukannya.
4. Nurhidayah Siregar yang selalu menemani Penulis dalam pembuatan skripsi,
beserta keluarga terima kasih atas perhatian dan motivasi yang telah diberikan.
5. Gugum Gumbira atas bantuan dan bimbingannya yang diberikan kepada
Penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf penunjang Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan
7. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah memberikan
kesempatan kepada Penulis untuk menggunakan data multibeam sonar.
8. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang
telah membantu Penulis dalam perolehan data pasang surut di lokasi penelitian.
9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) yang telah
memberikan informasi mengenai data sampel coring di perairan Selat Sunda.
10.Teman-teman ITK, khususnya ITK 45 terima kasih atas motivasi, doa dan
kerjasamanya.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
sehingga Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan
skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Bogor, Desember 2012
63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Indramayu, pada tanggal 16
Maret 1989. Penulis adalah anak ke enam dari pasangan Ayah
Rosyidi dan Ibu Kartini. Penulis mengenyam pendidikan
Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cisarua, Bandung
pada tahun 2005-2008, kemudian pada tahun 2008
melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan
Seleksi Masuk IPB (USMI).
Selama kuliah di Institut Pertanian Bogor, penulis pernah menjadi asisten
praktukum mata kuliah Iktiologi pada tahun ajaran 2010-2011, dan asisten
praktukum mata kuliah Ekologi perairan pada tahun ajaran 2011-2012 Program
Diploma IPB. Penulis juga aktif mengikuti organisasi BEM FPIK IPB pada
divisi Pengembangan Budaya Olahraga dan Seni (PBOS) pada tahun 2009-2010
dan sebagai pengurus pada divisi Hubungan Luar dan Komunikasi
(HUBLUKOM) di Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelauatan pada
tahun 2010-2011. Penulis juga mengikuti beberapa kepanitian selama masa kuliah
yakni menjadi Kordinator Divisi Keamanan dalam kegiatan PORIKAN 2010 dan
mengikuti Pelatihan Aplikasi GIS untuk Pemetaan Sumberdaya Pertanian Lokal
Potensial, SEAMEO BIOTROP 2012.
Tugas akhir yang dikerjakan penulis untuk menyelesaikan pendidikan di
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan,
melakukan penelitian dengan judul “Komputasi Data Multibeam Sonar untuk