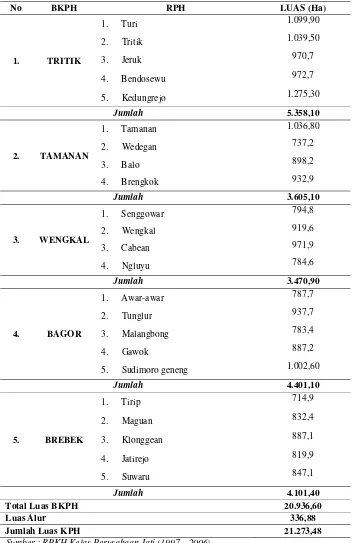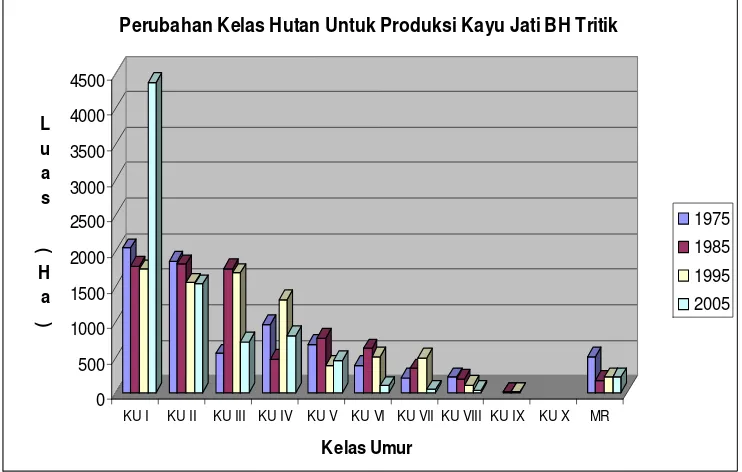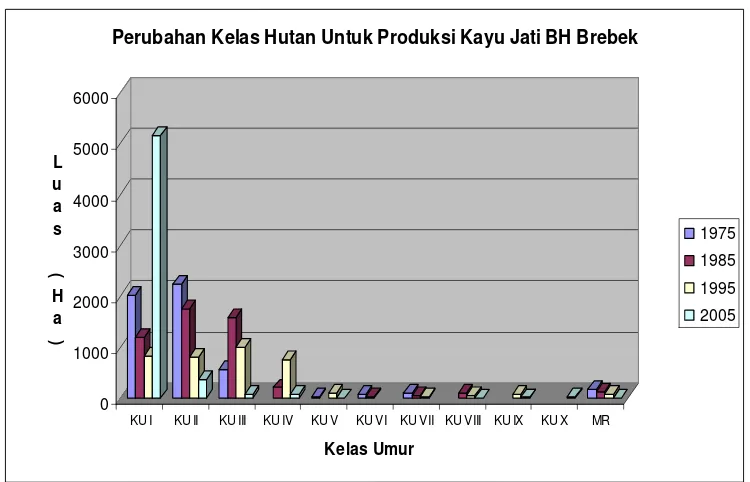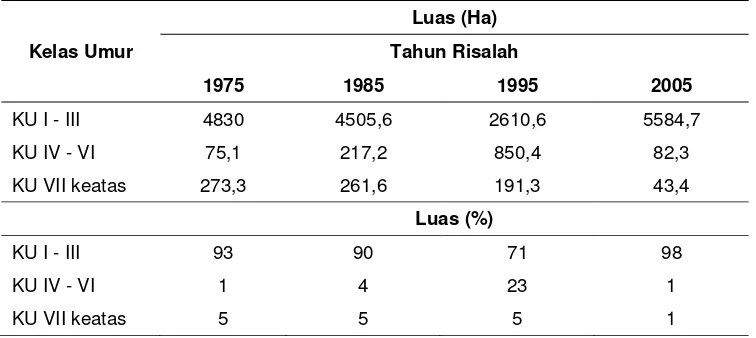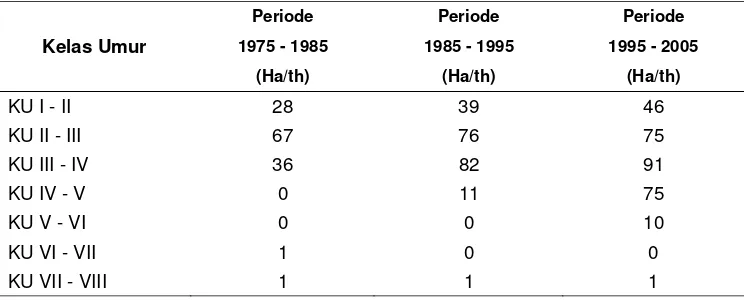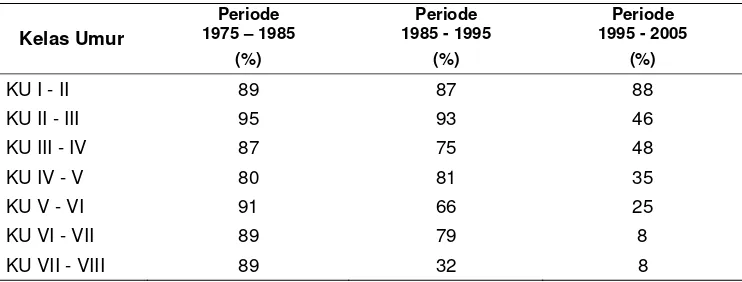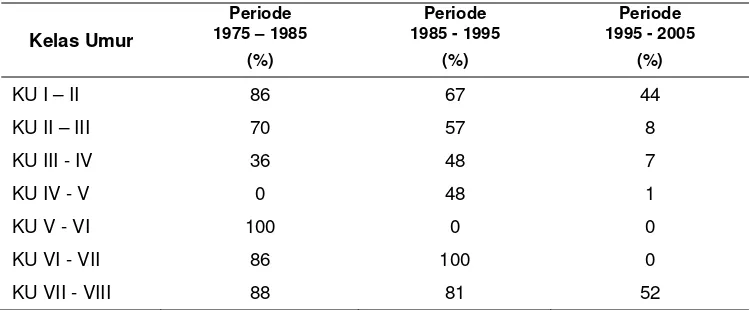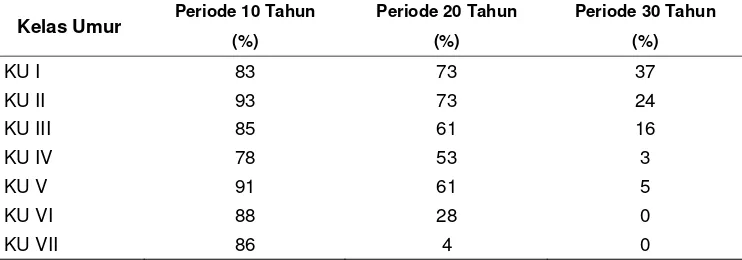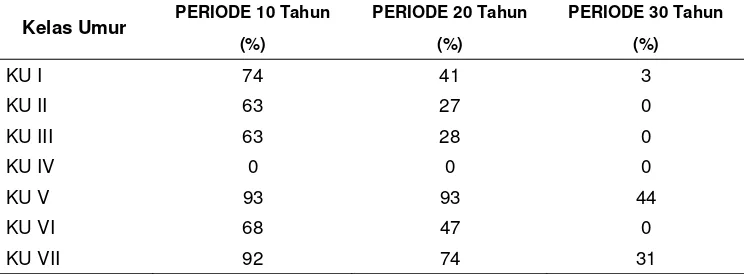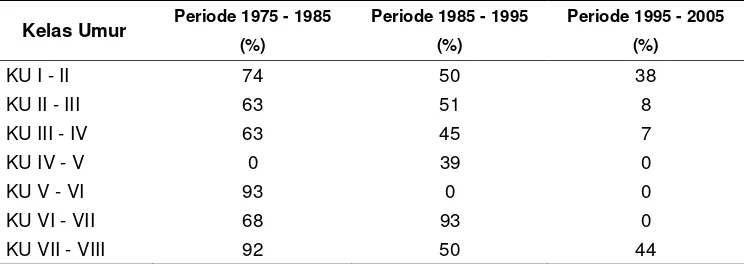(
Tectona grandis
L.f.)
(Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk Perum Perhutani
Unit II Jawa Timur)
Pudy Syawaluddin
E14101052
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
Tegakan Jati (Tectona grandis L.f.) (Kasus di KPH Nganjuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur). Dibimbing oleh Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS.
Laju pembangunan yang pesat mengakibatkan banyak terjadinya
perubahan hutan dalam waktu yang relatif singkat dan terjadi secara terus
menerus. Perubahan hutan ini bisa terjadi karena 2 hal, yaitu perubahan hutan
yang direncanakan (penebangan dan penjarangan), dan perubahan hutan yang
tidak direncanakan (gangguan hutan). Metode pengaturan hasil dalam rangka
penentuan jumlah volume tebangan per tahun yang digunakan oleh Perum
Perhutani adalah metode Burn, dengan ciri menggunakan daur tunggal (satu daur).
Daur ekonomis tanaman Jati adalah 80 tahun (daur panjang). Pada metode ini
kondisi tegakan dianggap tidak mengalami perubahan selama jangka waktu
tersebut, kenyataan di lapangan hampir setiap tahun tegakan hutan mengalami
perubahan.
Menurut catatan Perum Perhutani, 1.700 hektar dari 21.077 hektar luas
hutan di seluruh KPH Nganjuk rusak parah, yang sebagian besar diakibatkan oleh
pencurian kayu (Anonymous 2001). Sehingga penebangan untuk rehabilitasi
(tebangan B dan D) semakin meningkat bahkan lebih banyak jumlahnya daripada
penebangan hutan lestari (tebangan A). Melihat masalah tersebut, diperlukan
evaluasi perubahan kelas hutan produktif tegakan jati agar dapat mengetahui
kondisi tanaman jati di lapangan saat ini dan tindakan pengelolaan hutan yang
sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga diketahui pola perubahan komposisi
tegakan jati yang sedang terjadi sampai saat ini, dan dapat diketahui pula apakah
dengan pola perubahan yang ada tegakan jati masih pantas menggunakan daur
panjang atau sebaliknya. Dengan adanya Jati Plus Perhutani (JPP) dan trubusan
yang mampu tumbuh berkali-kali serta dapat tumbuh dengan baik, kemungkinan
untuk menggunakan daur ganda (2 daur) dalam menentukan pengaturan hasil
prospek pengelolaan tanaman jati dengan menggunakan daur panjang.
Berdasarkan dari hasil identifikasi perubahan hutan dan tegakan selama 3
periode menunjukkan bahwa di BH Tritik dan Brebek perubahan tegakan terbesar
terjadi saat KU III - KU IV di periode 1995 – 2005, masing-masing sebesar
878,30 Ha dan 911,60 Ha. Persentase penyebaran komposisi tegakan jati tertinggi
di kedua BH yaitu pada umur di bawah 30 tahun (KU I – III) di tahun risalah
2005, sebesar 80 % di Tritik dan 98 % di Brebek. Persentase yang dimiliki kelas
umur di atas 30 tahun sebesar 20 % (BH Tritik) dan 2 % (BH Brebek). Laju
perubahan areal produktif tertinggi di kedua BH selama 3 periode terjadi di
periode 1995 - 2005 pada saat KU III - KU IV sebesar 88 Ha/Th (BH Tritik) dan
91 Ha/Th (BH Brebek). Persentase luas tegakan produktif terkecil yang mencapai
kelas umur berikutnya dalam 3 periode terakhir di BH Tritik pada saat KU VI -
KU VII di periode 1995 – 2005 sebesar 8 %, dan di BH Brebek pada saat KU V -
KU VI dan KU VI - KU VII di periode 1995 – 2005 yaitu sebesar 0 %. Persentase
luas tegakan produktif terkecil yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30
tahun di BH Tritik adalah KU IV di periode 30 tahun sebesar 3 %, sedangkan di
BH Brebek pada KU II dan KU III di periode 30 tahun sebesar 0 %. Persentase
luas tegakan produktif terkecil yang mencapai KU berikutnya setiap periode 10
tahun di BH Tritik adalah pada KU VI - KU VII di periode 1995 - 2005 sebesar 8
%, dan di BH Brebek pada KU IV – KU V dan KU V – KU VI di periode 1995 –
2005 masing-masing sebesar 0 %. Pada tahun risalah 2005 KBD rata-rata tertinggi
di BH Tritik adalah pada KU II sebesar 1,17 dan yang paling rendah pada KU I
yaitu sebesar 0,65. Sementara di BH Brebek pada tahun risalah 2005 KBD
rata-rata tertinggi pada KU II sebesar 1,10, dan yang paling rendah pada KU I sebesar
0,63. Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa perubahan
kelas hutan produktif tegakan jati di kedua BH yang mengalami penurunan atau
degradasi hutan terbesar lebih sering terjadi di periode 1995 – 2005, kondisi hutan
di BH Tritik lebih baik keadaannya dibandingkan dengan kondisi di BH Brebek,
dan tegakan jati di KPH Nganjuk hanya mampu bertahan selama kurang lebih 20
(
Tectona grandis
L.f.)
(Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk Perum Perhutani
Unit II Jawa Timur)
PUDY SYAWALUDDIN
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
Nama Mahasiswa : Pudy Syawaluddin
NIM : E14101052
Menyetujui:
Dosen Pembimbing
Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS
NIP. 131760840
Mengetahui:
Dekan Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor
Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.
NIP. 131578788
Penulis dilahirkan di Bogor, pada tanggal 15 Juli 1983. Penulis adalah
putra keempat dari empat bersaudara dari keluarga Bapak Maman Sulaeman dan
Ibu Rd. Elly Rossaly.
Pendidikan SD ditempuh dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 di
SD POLISI 4 BOGOR, pada tahun 1990 sampai 1995 penulis melanjutkan
pendidikan SD di SD BINA INSANI BOGOR. Selanjutnya pada tahun 1995
penulis melanjutkan sekolah di SLTP BINA INSANI BOGOR hingga tahun 1998.
Setelah itu pada tahun 1998 penulis melanjutkan sekolah di SMU BINA INSANI
BOGOR sampai dengan lulus pada tahun 2001. Sejak tahun 1995 hingga 2000
penulis aktif mengikuti kegiatan ekstrakulikuler diantaranya OSIS, Pramuka,
PMR, dan olah raga bola basket. Pada tahun 1999 penulis sempat menjabat
sebagai ketua OSIS SMU BINA INSANI BOGOR sampai dengan tahun 2000.
Penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada
tahun 2001 melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).
Penulis memilih Program Studi Manajemen Hutan, Departemen Manajemen
Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Selama melaksanakan studi
di IPB, penulis pernah melakukan Praktek Umum Pengenalan Hutan di Cagar
Alam Leuweung Sancang dan Cagar Alam Kamojang serta Praktek Pengelolaan
Hutan di KPH Indramayu Unit III Jawa Barat. Kemudian penulis juga pernah
melakukan Praktek Kerja Lapangan di IUPHHTI PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk,
Site Bhirawa, Samarinda, Kalimantan Timur.
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala
rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi
ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad
SAW dan para Sahabatnya yang jihad di jalan-Nya.
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS selaku dosen pembimbing atas segala
bimbingan berupa petunjuk, saran, kritik, serta bantuan dan dukungan yang
telah diberikan kepada penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Papah (atas pola pikir dan prinsip hidup yang diberikan), Mamah (atas kasih
sayang dan segala dukungannya), Teteh Mela dan Mas Cheppi (atas
bantuannya dalam pengambilan data), A Cica dan Teh Ratih, Rizal (Sang
Pengekor) dan Teh Anti, Putri dan Sheilla. Keluarga besar H. Aip Syarif (alm)
dan keluarga besar H. R. Saban Suryakartaatmaja (alm). Terima kasih atas doa
dan dukungannya.
3. Pihak Perum Perhutani Unit II Jawa Timur terutama untuk Bapak Adm/KKPH
Nganjuk dan Bapak Ajun/KTKU, serta seluruh staf KPH Nganjuk yang turut
membantu atas terlaksananya penelitian ini.
4. Teman-temanku yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini
(Hendra, Priyo, Harris, Irwan, Dika, Ery, Berry, Ranggi, dan Sekab).
5. Baby Y. S. R. atas perhatian, kesabaran, dukungan dan doanya.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini.
Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT sedangkan penulis hanyalah
hamba-Nya yang penuh kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkannya.
Bogor, Mei 2007
DAFTAR ISI ... i
3.4.1 Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan ... 14
3.4.2 Identifikasi Perubahan Komposisi Tegakan Jati ... 15
3.4.3 Identifikasi Perubahan Kerapatan Bidang Dasar Rata-rata ... 17
5.2 Identifikasi Perubahan Kelas Hutan Produktif ... 29
5.2.1 Persentase Luas Tegakan Produktif yang Mencapai Kelas Umur Berikutnya dalam 3 Periode Terakhir ... 29
5.2.2 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Selama 30 Tahun .. 31
5.2.3 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Setiap Periode 10 Tahun ... 34
5.3 Pengaruh Perubahan KBD Terhadap Kelas Umur dan Bonita .. 36
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 42
6.1 Kesimpulan ... 42
6.2 Saran ... 43
DAFTAR PUSTAKA ... 44
1 Luas BKPH dan RPH Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk ... 19
2 Rekapitulasi hutan produktif BH Tritik ... 26
3 Rekapitulasi hutan produktif BH Brebek ... 26
4 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Tritik ... 27
5 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Brebek ... 27
6 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Tritik) ... 29
7 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Brebek) ... 30
8 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Tritik) ... 32
9 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Brebek) ... 33
10 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya setiap periode 10 tahun (BH Tritik) ... 34
1. Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Tritik ... 23
2 Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Brebek ... 24
3 Grafik Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Kelas Umur (Tritik) ... 37
4 Grafik Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Kelas Umur (Brebek) ... 38
5 Grafik Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Bonita (BH Tritik) ... 39
1. Hasil Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan BH Tritik
dan Brebek ... 46
2. Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Tritik
dan BH Brebek ... 65
3. Pengaruh Perubahan KBD Rata-rata Terhadap KU
(BH Tritik dan Brebek) ... 67
4. Pengaruh Perubahan KBD Rata-rata Terhadap Bonita
1.1 Latar Belakang
Laju pembangunan yang begitu pesat, mengakibatkan banyak terjadinya
perubahan hutan dalam waktu yang relatif singkat dan terjadi secara terus
menerus. Agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga maka dengan adanya
pengelolaan hutan lestari, perubahan hutan yang terjadi secara terus menerus ini
tetap dapat berlangsung tanpa mengurangi nilai kelestariannya. Perubahan hutan
ini bisa terjadi karena dua hal, yaitu perubahan hutan yang direncanakan seperti
penebangan dan penjarangan, serta perubahan hutan yang tidak direncanakan
seperti gangguan hutan. Perubahan hutan yang tidak direncanakan ini tentunya
akan sangat merugikan bagi pihak pengelola hutan.
Pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) merupakan suatu proses hutan untuk mencapai kontinuitas produksi dan manfaat lain yang
diinginkan tanpa mengakibatkan kemunduran nilai produktivitas hutan di masa
mendatang dan tanpa menimbulkan efek yang merugikan pada lingkungan fisik
serta sosial (ITTO 1992). Agar pengelolaan hutan lestari dapat tercapai, maka
dalam pengelolaannya dibutuhkan pengaturan hasil. Sebagaimana diungkapkan
Meyer et al., (1961) bahwa kelestarian hasil memerlukan rencana jangka panjang sehingga memungkinkan pengaturan persediaan dan penggantian persediaan
tegakan.
Metode pengaturan hasil dalam rangka penentuan jumlah volume tebangan
per tahun yang digunakan oleh pihak Perum Perhutani sebagai pihak pengelola
hutan tanaman di Pulau Jawa sampai saat ini adalah metode Burn, dengan ciri
menggunakan daur tunggal (satu daur). Daur ekonomis (umur tanaman yang
paling menguntungkan untuk ditebang) tanaman Jati adalah 80 tahun. Pada
metode Burn, kondisi tegakan dianggap tidak mengalami perubahan selama
jangka waktu tersebut, kenyataan di lapangan hampir setiap tahun tegakan hutan
mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi cenderung ke arah penurunan
potensi tegakan hutan sebagai akibat dari terjadinya gangguan berupa pencurian
Menurut catatan Perum Perhutani, 1.700 hektar dari 21.077 hektar luas
hutan di seluruh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk rusak parah, yang
sebagian besar diakibatkan oleh pencurian kayu (Anonim 2001). Gangguan hutan
yang tinggi di KPH Nganjuk mengakibatkan rusaknya tegakan produktif dan
sangat mengganggu pengaturan hasil yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.
Pencurian kayu yang terjadi lebih sering pada kelas umur yang tua, sehingga
potensi tegakan pada kelas umur yang masak tebang tidak dapat memenuhi
jumlah volume tebangan per tahun yang telah ditetapkan. Karena banyaknya
tegakan produktif yang rusak, penebangan untuk rehabilitasi (tebangan B dan D)
semakin meningkat bahkan lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan
penebangan hutan lestari (tebangan A).
Pihak Perhutani KPH Nganjuk mengatasi hal tersebut selain dengan
meningkatkan pengamanan (bantuan personel keamanan dari pihak TNI/POLRI)
juga melakukan beberapa progam terhadap masyarakat sekitar, salah satunya
adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan harapan tingkat
gangguan hutan dapat ditekan. Dalam program PHBM ini masyarakat turut
mendukung dalam kegiatan pemeliharaan dan pengamanan sampai tanaman Jati
itu dipanen. Pembagian hasil yang ditawarkan dalam PHBM ini adalah 30 persen
untuk masyarakat dan 70 persen untuk pihak Perhutani. Namun dari program
PHBM ini dampak yang diharapkan belum terlihat, hal ini terjadi karena daur jati
yang digunakan di KPH Nganjuk terlalu panjang (80 tahun), sehingga masyarakat
kurang berminat karena hasil yang diperoleh terlalu lama untuk dinikmati.
Bila melihat masalah tersebut di atas, maka diperlukan evaluasi perubahan
kelas hutan produktif tegakan jati agar dapat mengetahui kondisi tanaman jati di
lapangan saat ini dan tindakan pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi yang
ada. Dari hasil evaluasi ini maka akan diketahui pola perubahan komposisi
tegakan jati yang sedang terjadi sampai saat ini. Selain itu, juga dapat diketahui
apakah dengan pola perubahan yang ada tegakan jati masih pantas menggunakan
daur panjang atau sebaliknya. Dengan adanya Jati Plus Perhutani (JPP) dan
trubusan yang mampu tumbuh berkali-kali serta dapat tumbuh dengan baik,
kemungkinan untuk menggunakan daur yang lebih pendek dalam menentukan
Penggunaan daur yang lebih pendek ini memiliki beberapa kelebihan yaitu hasil
yang diperoleh lebih cepat, menekan biaya-biaya pengelolaan serta menarik bagi
masyarakat yang ikut program PHBM.
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk mengetahui pola seluruh perubahan komposisi tegakan Jati.
2. Merumuskan prospek pengelolaan tanaman Jati dengan menggunakan daur
panjang.
1.3 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
bagi pihak perencana dan pengelola hutan dalam pengambilan kebijakan
manajemen pengaturan hasil yang dapat diterapkan pada kelas perusahaan Jati
2.1 Jati (Tectona grandis L. f.)
Jati dengan nama botani Tectona grandis L. F. Termasuk famili verbenaceae, dengan ciri tinggi pohon antara 25 sampai dengan 30 m. Apabila
ditanam pada daerah yang subur dan memiliki keadaan lingkungan yang baik,
tingginya dapat mencapai 50 m dengan diameter lebih kurang 150 cm. Batang
umumnya bulat dan lurus, batang yang besar berakar dengan warna kulit agak
kelabu muda, agak tipis beralur memanjang agak ke dalam (Dirjen Kehutanan
1976).
Jati lebih dikenal dengan nama deleg, dodokan, jate, jatos, kiati dan
kulidawa. Di berbagai daerah lain Jati lebih dikenal dengan nama gianti
(Venezuela), Teak (USA, Jerman), Kyun (Birma), Sagwan (India), Mai Sak
(Thailand), Teck (Perancis) dan Teca (Brazilia). Penyebaran Jati di Indonesia
terdapat di daerah Jawa, Muna, Maluku (Wetar) dan Nusa Tenggara, sedangkan di
luar Indonesia terdapat di India, Thailand dan Vietnam.
Pertumbuhan Jati sangat baik pada tanah sarang yang mengandung kapur,
jenis ini tumbuh di daerah dengan musim kering nyata, tipe curah hujan c-f
Schmidt and Ferguson dengan curah hujan rata-rata 1200-2000 mm per tahun,
pada ketinggian 0-200 mdpl (Martawijaya et al., 1981).
Karena sifat-sifatnya yang baik, kayu Jati merupakan jenis kayu yang
paling banyak disukai dan dipakai untuk berbagai keperluan, terutama di Pulau
Jawa. Kayu Jati praktis sangat cocok dimanfaatkan untuk segala jenis konstruksi
bangunan. Kayu Jati termasuk kayu yang memiliki kelas keawetan I dan kelas
keawetan II, agak keras, baik sekali untuk keperluan bahan bangunan, alat-alat
rumah tangga dan sebagainya (Dirjen Kehutanan 1976).
Pengurusan kawasan hutan di Jawa diserahkan kepada Perum Perhutani
dan dalam upaya memenuhi kebutuhan kayu di Jawa, perusahaan tersebut mampu
meningkatkan produksi kayu Jati tanpa membahayakan kelestariannya
(Djajapertjunda 2002).
Dalam pengelolaan hutan tanaman Jati, Perhutani melaksanakan
terjadi dan dapat membentuk tegakan murni setelah mengalami kebakaran serta
mudah tumbuh tunas tunggak, tetapi permudaan alami ini jarang dilakukan karena
akan menghasilkan kayu berkualitas rendah. Menurut Martawijaya et al., (1981), tanaman Jati mempunyai sistem tebang habis permudaan buatan musim hujan
yang berjarak tanam 3m x 1m atau 3m x 3m tergantung pada bonita tanah.
2.2 Pengelolaan Hutan Lestari
Pengelolaan hutan yang lestari adalah pengurusan dan penggunaan lahan
hutan dan hutan pada tingkatan rata-rata yang memungkinkan tetap terpeliharanya
keanekaragaman hayati, produktivitas, kapasitas regenerasi, vitalitas, dan
kemampuannya untuk memenuhi fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial pada
tingkat lokal, nasional, dan global serta tidak menyebabkan kerusakan kepada
ekosistem lainnya pada saat ini maupun pada masa yang akan datang (Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe (1993) dalam Helms 1998).
Sejak konferensi bumi yang kedua di Rio De Janeiro tahun 1992,
pengelolaan hutan yang lestari tidak hanya menjadi perhatian rimbawan saja,
melainkan menjadi tanggung jawab semua perencana pembangunan di semua
sektor dan bersifat global. Pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi kepada
masalah kelestarian hasil hutan saja tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan
masyarakat lokal, kelestarian lingkungan hidup secara luas, dan keanekaragaman
hayati (Simon 1994).
Menurut ITTO (1992) untuk dapat terlaksananya manajemen hutan lestari,
maka terdapat lima pokok kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Forest Resource Base, yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara lestari.
2. The Continuity of Flow of Forest Products, yaitu kontinuitas hasil hutan yang dapat dipungut berdasarkan azas-azas kelestarian.
3. The Level of Environmental Control, yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampak-dampaknya yang
perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari yang berwawasan
lingkungan.
sekitar hutan. Dalam tingakt nasional, juga memperhitungkan peningkatan
pendapatan penduduk dan negara dalam arti luas.
5. Institutional Frameworks, yaitu penyempurnaan wadah kelembagaan yang dinamis dan mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
Institutional frameworks juga mencakup pengembangan sumber daya
manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang kesemuanya
turut mendukung terciptanya manajemen hutan lestari.
Kelima kriteria yang diperkenalkan ITTO tersebut kemudian dijabarkan
lebih lanjut dalam bentuk ciri atau indikator. Maka indikator berikut merupakan
tanda-tanda yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen hutan yang lestari.
1. Tersedianya tata guna hutan yang komprehensif yang secara penuh
mempertimbangkan tujuan-tujuan pengelolaan hutan dan kehutanan.
2. Tercukupinya luas hutan permanen, yaitu hutan tetap yang dipertahankan
fungsinya sebagai hutan. Luas hutan yang permanen akan mendukung
target dan sasaran pembangunan hutan dan kehutanan.
3. Ditetapkannya target dan sasaran pembangunan hutan tanaman, distribusi
kelas umur, dan rencana tanaman tahunan.
Kesemua indikator tersebut di atas mengarah kepada terlaksananya kriteria
pertama yaitu Forest Resource Base.
Menurut Meyer (1961), kelestarian hasil hutan adalah penyediaan yang
teratur dan kontinyu hasil hutan yang diperuntukan sesuai kemampuan maksimum
hutan tersebut. Tipe-tipe kelestarian hasil yang dikenal antara lain :
1. Hasil integral (integral yield), terdiri dari satu tegakan seumur sehingga
penanaman dilakukan pada saat yang sama dan pemanenan pada saat yang
sama pula.
2. Hasil periodik (intermittent yield), terdiri dari beberapa kelas umur
sehingga penanaman dan penebangan dilakukan pada selang waktu
tertentu.
3. Hasil tahunan (annual yield), terdiri dari beberapa kelas umur dan selalu
Agar pengelolaan hutan yang lestari dapat tercapai, sudah semestinya ada
pola ideal yang mendekati keadaan hutan normal. Dimana ada beberapa syarat
umum yang harus dimiliki, yaitu (Osmaston 1968) :
1. Komposisi dan struktur hutannya harus seimbang dengan lingkungan
sekitar. Dengan kata lain pertumbuhan tanaman dan metode silvikultur
yang dipakai harus cocok dengan semua keganjilan yang ada.
2. Stok pertumbuhan tanaman harus dapat terus memberikan kemungkinan
yang terbaik dari kuantitas yang diinginkan.
3. Pengorganisasian hutan secara menyeluruh harus disediakan untuk dapat
memenuhi kebutuhan pasar.
4. Pengorganisasian hutan sampai pada unit-unit pekerjaan dan seluruh
administrasinya harus jadi kemungkinan yang terbaik.
Keempat syarat tersebut di atas dikombinasikan untuk efesiensi kerja, dan bukan
hanya secara silvikultur saja, tetapi secara pengelolaan dan pelaksanaannya juga.
Menurut Knuchel (1953) diacu dalam Osmaston (1968) definisi hutan
normal itu sendiri adalah hutan yang telah mencapai dan dapat mempertahankan
tingkat yang hampir mendekati kesempurnaan untuk mencapai seluruh tujuan
yang telah direncanakan. Konsep hutan normal pada intinya agar dalam
pengelolaan hutan sebaiknya dapat diperoleh hasil yang tetap dan secara
terus-menerus, dimana di dalam hutan tersebut seharusnya terdapat tegakan dengan
umur yang berbeda-beda, sehingga dalam menentukan jumlah volume
tebangannya tidak mengalami kekurangan atau kelebihan jatah tebang (Osmaston
1968).
Berdasarkan sistem silvikultur, hutan normal diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu sistem tegakan seumur dan sistem tegakan tidak seumur. Prinsip hasil yang
secara terus-menerus dan konsep hutan normal dibuat untuk tegakan seumur. Pada
model tegakan seumur didasarkan pada sistem tebang habis silvikultur dan hasil
tahunan secara terus-menerus, beberapa tegakan yang berumur seragam
masing-masing memiliki area produktifitas yang sama. Dengan kata lain ada beberapa
rangkaian normal dari beberapa gradasi umur yang masing-masing dibedakan satu
tahun, yang mana setiap kelas umur memiliki kapasitas hasil yang sama. Setiap
tahunan yang tetap dan secara terus-menerus dapat tercapai. Kemudian dalam
tegakan seumur terdapat beberapa kelas umur, yang mana kelas umur ini
merupakan hasil dari pengelompokkan dari beberapa gradasi umur (lima, sepuluh
tahun atau lebih). Untuk tegakan jati, dalam satu kelas umur biasanya
menggunakan sepuluh gradasi umur atau umur satu tahun hingga sepuluh tahun
untuk kelas umur pertama. Jadi ada 3 (tiga) norma yang harus dimiliki oleh hutan
normal, yaitu rangkaian normal dari beberapa gradasi umur, stok pertumbuhan
yang normal dan pertumbuhan yang normal (Osmaston 1968).
Kelestarian hasil hutan menuntut tingkat produksi yang konstan untuk
intensitas pengelolaan hutan tertentu, dimana antara pertumbuhan dan pemanenan
harus seimbang. Menurut Simon (1994), hutan yang tertata penuh akan
menghasilkan kayu yang sama, tahunan atau selama periode tertentu, baik dalam
arti volume, ukuran maupun kualitas. Terwujudnya kelestarian hutan adalah
adanya jaminan kepastian kawasan hutan yang tetap yang diakui oleh semua
pihak, sistem perhitungan etat yang tidak over-cutting, dan telah dirumuskan sistem permudaan yang menjamin permudaan kembali kawasan bekas tebangan.
2.3 Pembagian Kelas Hutan
Kelas hutan adalah penggolongan kawasan hutan ke dalam kelas-kelas
berdasarkan aspek dan tujuan tertentu. Ada beberapa aspek yang digunakan dalam
penggolongan kawasan hutan, yaitu (Perum Perhutani 1992) :
a. Kondisi fisik kawasan (misal: TPK, halaman, rumah dinas, jalan, kuburan)
b. Kesesuaian lahan
1. Tanaman jenis kayu lain
2. Areal perlindungan
c. Lingkungan
1. Lingkungan biofisik
2. Lingkungan sosial ekonomi
d. Vegetasi
1. Bervegetasi pohon
1) Bervegetasi pohon (produktif dan tidak produktif)
2) Tidak bervegetasi pohon
Tujuan dari penggolongan kawasan hutan ke dalam kelas-kelas hutan
adalah untuk menentukan tindakan silvikultur yang perlu dilakukan pada tiap
(induk) kelas hutan. Pola tindakan pada tiap kelas hutan dan kelas hutan yang ada,
diuraikan sebagai berikut (Perum Perhutani 1992) :
1. Untuk penghasilan
1) Areal yang disediakan untuk penghasilan, sesuai untuk tanaman
pokok.
a. Baik untuk tebang habis
a) Kelas umur (KU)
b) Hutan alam (HA) / Miskin riap (MR)
c) Tanaman kayu lain (Tkl)
d) Bertumbuhan kurang (BK)
e) Tanah kosong (TK)
b. Tidak baik untuk tebang habis (Tbth)
2) Areal yang disediakan untuk penghasilan, tidak sesuai untuk tanaman
pokok.
3) Tanaman jenis kayu lain (Tjkl)
4) Areal perlindungan (AP)
2. Bukan untuk penghasilan
1) Hutan lindung
2) Sungai, rawa, batu dan seterusnya.
3) Lapangan dengan tujuan istimewa (Ldti)
2.4 Pengaturan Hasil
Menurut Simon (1994), dalam pelaksanaan pengaturan hasil hutan
memerlukan tiga tahap kegiatan, yaitu :
1. Perhitungan etat, yaitu jumlah hasil yang dapat diperoleh setiap tahun atau
selama jangka waktu tertentu. Bila hasil tersebut dinyatakan dalam luas
dinamakan etat luas, dan bila dinyatakan dalam m3 dinamakan etat volume.
2. Pemisahan jumlah hasil tersebut ke dalam hasil penjarangan dan hasil tebangan
akhir.
3. Penyusunan rencana tebangan, baik tebangan penjarangan maupun tebangan
Menurut Osmaston (1968), ada beberapa alasan penebangan dan
pengaturan hasil dalam hubungannya dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu.
Alasan tersebut adalah :
1. Penyediaan bagi konsumen, penebangan harus dilaksanakan agar tersedia
jenis, ukuran, mutu dan jumlah kayu sesuai dengan permintaan pasar.
2 Pemeliharaan tegakan persediaan untuk mempertahankan dan
mengembangkan produksi di dalam bentuk serta kualitas yang baik secepat
mungkin.
3. Penyesuaian jumlah dan bentuk tegakan persediaan agar lebih sesuai dengan
tujuan pengelolaan.
4. Penebangan perlindungan, terutama dipergunakan dalam sistem silvikultur
untuk melindungi tegakan dari angin, kebakaran hutan dan sebagainya.
Metode pengaturan hasil menurut Davis dan Johnson (1954), Meyer et al., (1961), dan Osmaston (1968) dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu :
1. Metode berdasarkan luas
a. Pengendalian berdasarkan prinsip silvikultur
b. Pengendalian dengan daur dan sebaran kelas umur
c. Pengendalian berdasarkan kelas pengembangan dan pembinaan
2. Metode berdasarkan volume dan riap
a. Metode Austrian
b. Metode Hundeshagen
c. Metode Von Mantel
d. Metode Gerhardt
e. Metode Chapman
3. Metode berdasarkan luas dan volume yaitu metode Burn
Menurut Suhendang (1996), pengaturan hasil secara garis besar
dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pengaturan hasil hutan seumur
a. Berdasarkan luas
b. Berdasarkan volume
c. Berdasarkan luas dan volume
Metode pengaturan hasil yang digunakan oleh pihak Perum Perhutani
dalam mengelola hutan tanaman di pulau Jawa adalah metode yang berdasarkan
luas dan volume. Pada dasarnya metode yang digunakan di dalam pengaturan
hasil ini merupakan kombinasi dari etat luas dan etat volume. Ada 3 (tiga) tahap
yang harus dilakukan dalam menetapkan besarnya etat, yaitu (Perum Perhutani
1992) :
1. Tahap pertama
Dalam tahap pertama ini diperoleh perhitungan etat secara garis besar, baik
etat luas maupun volume. Untuk menghitung etat volume, besarnya volume
jenis kayu pokok merupakan penjumlahan dari volume hutan tanaman pada
umur tengah rata-rata tanaman dan volume hutan alam. Agar jangka waktu
penebangan yang dihitung berdasarkan etat luas tidak jauh berbeda dengan
jangka waktu penebangan yang dihitung berdasarkan etat volume, maka etat
yang dihitung perlu dilakukan pengujian pada setiap kelas umur.
2. Tahap kedua
Etat yang telah diuji kemudian diproyeksikan ke dalam tiap jangka (dari
jangka pertama hingga jangka daur), proyeksi ini dilakukan pada bagan tebang
yang menggambarkan hubungan antara jumlah etat di setiap jangka dengan
kelas umur yang akan ditebang di jangka yang bersangkutan. Jumlah tebangan
di setiap jangka diusahakan sama dengan etat satu jangka, atau jika mungkin
diusahakan meningkat secara berkesinambungan.
3. Tahap ketiga
Bagian yang terpenting dari bagan tebang adalah besarnya etat dalam jangka
pertama. Kemudian etat jangka pertama ini dijabarkan ke dalam rencana
tebangan setiap tahun sekaligus ditetapkan lokasi tebangannya, sehingga
perhitungan etat tahap ketiga ini berupa rencana tebangan (baik luas atau
volume) yang disusun setiap tahun dengan lokasi petak tebangnya.
2.5 Daur
Daur (production period) adalah interval waktu dari mulai penanaman hingga tegakan dianggap masak tebang dan mendapat giliran untuk ditebang
dalam suatu kelas perusahaan (Osmaston 1968). Daur adalah faktor pengatur
hutan seumur, lahirnya istilah daur berkaitan erat dengan adanya konsep hutan
normal (Departemen Kehutanan 1997).
Lama daur tidak selalu sama dengan satu tahun besarnya tegakan harus
ditebang. Karena keadaan silvikultur atau pertimbangan lainnya, dapat
menyebabkan tegakan harus ditebang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu
yang ditentukan. Lamanya daur tergantung dari interaksi dari beberapa faktor
yaitu (Osmaston 1968) :
1. Tingkat kecepatan pertumbuhan tegakan, tergantung pada jenis pohon, tanah
dan faktor tempat tumbuh yang lain seperti iklim, topografi, suplai air, dan
interaksi penebangan.
2. Karakteristik harus memperhatikan umur maksimal secara alami, umur
menghasilkan benih, umur kecepatan tumbuh terbaik, dan umur kualitas
terbaik.
3. Pertimbangan ekonomi, memperhitungkan ukuran yang dapat dipasarkan
dan harga terbaik yang dapat diperoleh.
4. Respon tanah seperti kemunduran atau perubahan karakter sesudah
pembongkaran yang berulang-ulang.
Menurut Departemen Kehutanan (1997), ada enam macam daur yang
sering disebutkan dalam buku-buku kehutanan klasik, yaitu :
1. Daur fisik, yaitu jangka waktu yang berimpitan dengan periode hidup suatu
jenis untuk kondisi tempat tumbuh tertentu, sampai jenis tersebut mati secara
alami.
2. Daur silvikultur, yaitu jangka waktu selama hutan masih menunjukkan
pertumbuhan yang baik, dan dapat menjamin permudaan sesuatu, dengan
kondisi yang sesuai dengan tempat tumbuhnya.
3. Daur tehnik, yaitu jangka waktu perkembangan sampai suatu jenis dapat
menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya, untuk keperluan tertentu.
4. Daur volume maksimum, yaitu jangka waktu perkembangan suatu tegakan
yang memberikan hasil kayu tahunan terbesar, baik dari hasil penjarangan
5. Daur pendapatan maksimum, daur ini juga dikenal sebagai daur ”bunga
hutan” maksimum (The highest forest rental), yaitu daur yang menghasilkan rata-rata pendapatan bersih maksimum.
6. Daur finansial, yaitu daur yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan
maksimum dalam nilai uang.
Daur yang digunakan Perhutani pada dasarnya adalah daur ekonomis atau
daur finansial, karena lebih sesuai dengan tujuan perusahaan. Berdasarkan jangka
waktunya, daur juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu (Perum Perhutani
1992) :
1. Daur pendek : Kurang dari 15 tahun.
2. Daur menengah : 15 – 35 tahun.
3. Daur panjang : > 40 tahun.
Lamanya daur untuk kelas perusahaan Jati, Perum Perhutani telah menetapkan
daur panjang 40 tahun sampai 80 tahun, tergantung dari karakter dan tingkat
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Februari s/d Agustus 2006 dan
bertempat di KPH Nganjuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
3.2 Objek Penelitian
Objek penelitian adalah tegakan Jati sebagai kesatuan pengelolaan pada
tingkat KPH Nganjuk.
3.3 Pengumpulan Data
Data utama yang diperlukan mencakup :
1. Hasil risalah hutan yang dimuat dalam buku Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan (RPKH) tiga periode terakhir (1975 – 1985 ; 1985 –
1995 ; 1995 – 2005).
2. Hasil risalah sela dan risalah kilat (2000 – 2006).
3. Data perubahan kelas hutan (1975 – 2005).
4. Peta kawasan hutan skala 1 : 10.000 (memperlihatkan petak dan anak
petak).
5. Laporan rencana, realisasi produksi (dalam berbagai RTT).
Selain data utama diperlukan data penunjang, mencakup data keadaan
umum fisik dan sosial wilayah KPH Nganjuk. Data tersebut di atas akan
dikumpulkan dari kantor KPH Nganjuk dan Seksi Perencanaan Hutan (SPH)
Jombang. Data diperoleh dengan cara mengutip dan memproses kembali data
yang sudah ada.
3.4 Analisis Data
3.4.1 Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan
Identifikasi dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi akibat
adanya pengelolaan hutan dan tegakan (penebangan A2, penanaman) dan
perubahan yang terjadi akibat gangguan hutan. Perubahan dianalisis untuk
setiap bagian hutan (BH) yang ada di KPH Nganjuk. Identifikasi perubahan
hutan dan tegakan mencakup :
1) Perubahan pada setiap kelompok umur tegakan.
10 Thn
Dalam identifikasi perubahan hutan ini dibutuhkan data yang dimuat
dalam buku RPKH yaitu : Model RPKH 1 (hasil risalah (data setiap petak
ukur), Model RPKH 2 (Register Risalah Hutan), dan Model RPKH 3 (Daftar
Kelas Hutan). Dari data tersebut dapat diperoleh beberapa informasi tentang
perubahan luas dan potensi tegakan jati, sehingga dapat terlihat pada umur
berapa dan di petak mana saja gangguan hutan yang sering terjadi (daerah
yang tingkat kerawanannya tinggi).
Analisis identifikasi perubahan hutan dan tegakan dilakukan dengan cara
memproses data dari hasil risalah hutan selama 3 (tiga) periode terakhir. Data
tersebut dimuat ke dalam tabel hasil identifikasi perubahan hutan dan tegakan
(Lampiran 1). Dari tabel hasil identifikasi terlihat perubahan komposisi
tegakan masing-masing petak dan anak petak pada setiap periode. Kondisi
tegakan dianggap mengalami gangguan hutan apabila terjadi perubahan kelas
hutan, penurunan luasan kelas umur dan penurunan kelas umur pada tiap
periode. Jika suatu tegakan mengalami peningkatan kelas umur pada setiap
periode dan, maka tegakan tersebut dianggap tidak mengalami gangguan
hutan. Kemudian dari tabel hasil identifikasi perubahan hutan dan tegakan di
KPH Nganjuk diolah lagi untuk mengetahui besarnya komposisi tegakan jati
di setiap kategori kelas umur muda (KU I – III), kelas umur tua (KU IV – VI),
dan kelas umur masak tebang (KU VII ke atas). Disamping itu juga dapat
diperoleh data laju perubahan areal produktifnya, dengan rumus sebagai
berikut :
Laju Perubahan Areal Produktif (Ha/Th) =
Dimana L0 = Luas awal tegakan (Ha)
L1 = Luas akhir tegakan (Ha)
3.4.2 Identifikasi Perubahan Komposisi Tegakan Jati
Kegiatan identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui pola perubahan
komposisi tegakan jati setiap kelas umur produktif di masing-masing bagian
hutan (BH) selama 3 periode. Dimana ada tiga tipe identifikasi yang
dilakukan, diantaranya adalah :
1) Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati dalam 3 periode terakhir.
2) Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati selama 30 tahun.
3) Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati setiap periode 10 tahun.
Kegiatan identifikasi perubahan komposisi tegakan jati dalam 3 periode
terakhir dilakukan dengan cara memproses data dari tabel perubahan kelas
hutan untuk produksi kayu jati, sehingga diperoleh hasil persentase komposisi
tegakan jati dalam 3 periode terakhir. Dari data persentase komposisi tegakan
jati tersebut dapat terlihat perubahan komposisi tegakan dari kelas umur muda
sampai masak tebang untuk setiap periode. Kegiatan ini dilakukan agar dapat
diketahui seberapa besar persentase kemampuan suatu kelas umur tegakan
untuk tumbuh dengan baik selama 3 periode terakhir, tanpa memperhatikan
keadaan di setiap petaknya. Dimana untuk mengolah data tersebut dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Persentase (%) = 1 - x 100 %
Dimana KUii = Luas tegakan kelas umur ke-i pada periode ke-i
KUjj = Luas tegakan kelas umur ke-j pada periode ke-j
Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati selama 30 tahun bertujuan
untuk melihat kemampuan suatu kelompok umur tegakan yang dapat tumbuh
dengan baik dalam jangka waktu yang berlainan. Kegiatan ini dilakukan
dengan memperhatikan perubahan luasan di setiap petak dan anak petaknya.
Adapun beberapa jangka waktu yang diidentifikasi adalah 10 tahun, 20 tahun,
dan 30 tahun, dimana kondisi awalnya sama yaitu pada tahun 1975. Sehingga
dapat diketahui seberapa besar persentase komposisi tegakan jati yang dapat
tumbuh sesuai dengan yang diharapkan dalam jangka waktu tersebut, selain
itu juga dapat terlihat seberapa lama suatu kelompok umur tegakan tersebut
bisa dipertahankan.
Identifikasi perubahan komposisi tegakan jati setiap periode 10 tahun
dilakukan dengan cara melihat perubahan luas suatu kelas umur tegakan setiap
periode 10 tahun, dengan memperhatikan perubahan di setiap petak dan anak
petaknya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pola (KUii – KUjj)
KUj
KUi
perubahan suatu kelas umur tegakan setiap 10 tahun dengan kondisi awal
tegakan yang berlainan selama 3 periode, yaitu pada tahun risalah 1975, 1985,
dan 1995. Adapun rumus yang digunakan dalam kegiatan identifikasi ini sama
dengan identifikasi perubahan komposisi tegakan jati selama 30 tahun, yaitu
sebagai berikut :
Persentase (%) = x 100 %
Dimana KUi = Luas tegakan kelas umur ke-i di periode awal
KUj = Luas tegakan kelas umur ke-j di periode berikutnya
Seluruh kegiatan identifikasi perubahaan komposisi tegakan jati yang
dilakukan baik itu yang selama 30 tahun atau pun yang per periode 10 tahun
pada prinsipnya sama, perbedaannya hanya pada penggunaan kondisi awal
tegakan dan jangka waktunya. Kegiatan ini dilakukan hanya memperhatikan
kelas umur produktifnya saja, yang kemudian dicari persentase luas suatu
kelas umur yang mengalami perubahan di suatu petak atau anak petak. Dari
persentase tersebut maka diperoleh data luas yang mampu tumbuh dengan
baik dan yang rusak di suatu petak atau anak petak.
3.4.3 Identifikasi Perubahan Kerapatan Bidang Dasar Rata-rata
Kegiatan identifikasi perubahan kerapatan bidang dasar (KBD) rata-rata
dilakukan untuk melihat pengaruh perubahannya terhadap kelas umur tegakan
dan bonita selama 30 tahun (4 tahun risalah). Untuk mengetahui pengaruh
perubahan KBD rata-rata terhadap kelas umur tegakan jati dibutuhkan data
KBD setiap petak yang diperoleh dari tabel hasil identifikasi, kemudian
dilakukan pengelompokan setiap kelas umur, sehingga diperoleh hasil KBD
rata-rata untuk masing-masing kelas umur selama 30 tahun. Perlakuan yang
sama dilakukan juga untuk mengetahui perubahan KBD rata-rata terhadap
bonita. Dari hasil kegiatan identifikasi dapat terlihat apakah perubahan KBD
rata-rata yang dimiliki oleh setiap kelas umur dan bonita selama 30 tahun
terakhir sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Disamping itu data tersebut
juga mendukung dalam melihat pengaruh perubahan komposisi tegakan jati
yang terjadi terhadap perubahan KBD rata-rata yang ada di KPH Nganjuk
4.1 Letak dan Luas
Letak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk dari segi geografis
terletak antara 111º 5’ – 112º 13’ Bujur Timur dan 7º 20’ – 7º 59 ‘ Lintang
Selatan. Wilayah KPH Nganjuk terletak diantara 3 (tiga) Keresidenan dan 1 (satu)
Kabupaten, yaitu :
1. Keresidenan Kediri di sebelah Selatan.
2. Keresidenan Madiun di sebelah Barat.
3. Keresidenan Bojonegoro di sebelah Utara
4. Keresidenan Jombang di sebelah Timur.
Luas seluruh kawasan Kelas Perusahaan Jati KPH Nganjuk adalah
21.273,48 Ha. Areal hutan yang termasuk Kelas Perusahaan Jati ini secara
administratif terletak di dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten
Madiun. KPH Nganjuk terbagi menjadi 2 (dua) Bagian Hutan yaitu Bagian Hutan
(BH) Tritik dan Bagian Hutan (BH) Brebek. Bagian Hutan Tritik yang masuk
dalam Kabupaten Nganjuk seluas 11.345,6 Ha, sedangkan yang masuk dalam
wilayah Kabupaten Madiun seluas 1.251,8 Ha. Jadi luas seluruh BH Tritik adalah
12.627,4 Ha BH Brebek memiliki luas 8.646,08 Ha yang keseluruhannya masuk
dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dan Keresidenan Kediri.
Berdasarkan pembagian resort, KPH Nganjuk dibagi menjadi 5 (lima)
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 23 (dua puluh tiga) Resort
Pemangkuan Hutan (RPH). Luas masing-masing BKPH dan RPH dapat dilihat
Tabel 1. Luas BKPH dan RPH Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk.
Total Luas BKPH 20.936,60
Luas Alur 336,88
Jumlah Luas KPH 21.273,48
Sumber : RPKH Kelas Perusahaan Jati (1997 – 2006)
Wilayah KPH Nganjuk terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
Brantas, anak sungai Brantas yang utama adalah DAS Widas. Ditinjau dari tingkat
BH Brebek lebih tinggi tingkat kehidupannya daripada BH Tritik. Hal ini
disebabkan karena BH Brebek banyak terdapat sumber air dan tanahnya lebih
subur.
4.2 Keadaan Lapangan
KPH Nganjuk terletak di lembah antara pegunungan Kendeng yang berada
di sebelah Barat Utara dan pegunungan Wilis yang berada di sebelah Selatan.
Selain itu KPH Nganjuk berada dalam DAS berikut ini :
1. DAS Widas
2. DAS Kedung Pedet
3. DAS Kuncir
4. DAS Kedung Gupit
5. DAS Kedung Maron
6. DAS Rejoso
7. DAS Kedung Padang
8. DAS Senggowar
9. DAS Tretes
10.DAS Hedung Soko
Tinggi dari permukaan air laut terendah adalah ± 60 meter dari permukaan laut
(mdpl) sejajar dengan jalan Kereta Api Madiun – Surabaya.
4.3 Tanah, Iklim dan Geologi
Menurut peta tanah Jawa Timur jenis-jenis tanah yang terdapat di BH
Tritik dari Utara ke Selatan adalah :
a. Kelompok tanah termasuk latosol dan tanah mediteran merah dengan
mengandung tanah-tanah regur dari bahan vulkanis, berisi batu kapur, tanah
liat campur kapur (marl) pada tanah-tanah pegunungan.
b. Kelompok tanah termasuk sebagian besar lithosol, dari batu-batuan sedimen
yang serupa, pada tanah-tanah berbukit hingga pegunungan.
c. Regosol dan tanah mediteran berkapur dari tanah liat campur kapur di atas
bukit-bukit.
d. Tanah-tanah serupa dari timbunan-timbunan calluvial dan alluviar pada
dataran dengan permukaan bergelombang atau pada tanah-tanah bawah
Jenis-jenis tanah yang terdapat di BH Brebek adalah :
a. Tanah-tanah di tepi sebelah Timur terdiri dari tanah-tanah serupa dari
timbunan calluvial dan alluviar pada dataran dengan permukaan
bergelombang atau pada tanah-tanah bagian bawah (bottom land).
b. Sebagian besar bagian Utara dan tengah terdiri dari latosol coklat dari bahan
vulkanis intermedian dan dasar pada tanah lembah dari kerucut-kerucut
vulkanis.
c. Sedangkan bagian Selatan terdiri dari latosol coklat tua kemerah-merahan dan
latosol merah tua dari bahan vulkanis intermedian dan dasar pada tanah
lembah dari kerucut-kerucut vulkanis.
Suhu pada umumnya tetap sepanjang tahun berkisar 26º C - 27º C. Curah
hujan termasuk tipe 4 C dari Dr. Boerema, yaitu curah hujan sedikit di musim
kemarau, karena terdapatnya angin-angin kering dari arah Selatan dan Tenggara.
Hujan turun lebat pada bulan Desember sampai dengan Februari, yang disebabkan
oleh adanya angin dari Barat Daya yang dapat mencapai daerah ini. Iklim di KPH
Nganjuk cocok dengan syarat-syarat pertumbuhan jati, karena menurut Dr. J. H.
Becking syarat pertumbuhan jati adalah sebagai berikut :
a. Jati dapat tumbuh di seluruh Jawa pada ketinggian 0 – 500 mdpl.
b. Di daerah-daerah dengan musim kemarau sedang sampai kering.
c. Pada tanah yang baik peresapannya.
d. Mencapai perkembangan optimal di daerah-daerah 10 – 20 hari hujan, dalam 4
bulan terkering struktur tanah baik tinggi 0 – 250 mdpl.
Berdasarkan pembagian dari R. W. Van Bemmeloem (1949) dalam
bukunya The Geologic of Indonesia BH Tritik termasuk Isac Physic Graphis Tectonis, sedangkan pada BH Brebek termasuk Zone Solo.
4.4 Kondisi Sosial Ekonomi
Wilayah Kabupaten Nganjuk dibagi dalam 20 kecamatan, 20 kelurahan
dan 264 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2004
sebesar 1.029.468 jiwa dengan perincian 509.156 jiwa penduduk laki-laki dan
520.312 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar mata pencaharian
jiwa per km². Penduduk di Kabupaten Nganjuk menganut beberapa agama dan
kepercayaan namun penduduknya mayoritas beragama Islam.
Fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2002
sudah cukup memadai, dimana jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 726 unit,
jumlah SLTP ada 69 unit, sedangkan SMU berjumlah 51 unit, untuk Perguruan
0
Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Tritik
1975 1985 1995 2005 5.1 Identifikasi Perubahan Hutan dan Tegakan
Identifikasi perubahan kelas hutan dilakukan untuk setiap kelas umur
tegakan pada kelas perusahaan Jati di KPH Nganjuk selama 3 periode terakhir
(1975 – 2005), dimana dalam pengolahannya dibedakan menjadi 2 bagian yaitu
Bagian Hutan (BH) Tritik dan Bagian Hutan (BH) Brebek. Data hasil identifikasi
perubahan hutan yang bersumber dari buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil
(RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Nganjuk disajikan pada Lampiran 1 (BH
Tritik dan BH Brebek). Grafik perubahan luasan kelas hutan untuk produksi kayu
jati pada BH Tritik dapat dilihat pada Gambar 1, dan pada BH Brebek dapat
dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1 Perubahan kelas hutan untuk produksi kayu jati BH Tritik.
Perubahan tegakan yang tejadi di BH Tritik untuk setiap kelas umur selalu
mengalami penurunan pada saat menjadi kelas umur berikutnya dan perubahan
yang paling besar terjadi pada saat KU III menjadi KU IV di periode III (1995 -
2005). Dapat dilihat pada Gambar 1, perubahan tegakan setiap kelas umur terus
mengalami penurunan luas dari periode awal hingga periode akhir, akan tetapi
luas total produktif dari periode ke periode-periode berikutnya terus bertambah,
0
Perubahan Kelas Hutan Untuk Produksi Kayu Jati BH Brebek
1975 1985 1995 2005
lahan bekas tebangan, seperti pada risalah tahun 1975 luas KU VIII (masak
tebang) sebesar 218,6 Ha, sedangkan penanaman yang dilakukan pada risalah
tahun 1985 sebesar 1779,7 Ha. Dapat terlihat pula dari Gambar 1 di atas bahwa
pada KU I di tahun risalah 2005 memiliki luas areal yang sangat jauh lebih besar
daripada di tahun-tahun risalah sebelumnya, hal ini menunjukkan luas areal
penanaman di tahun-tahun risalah sebelumnya dengan kondisi di lapangan saat ini
sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak
memungkinkan lagi dengan luasan tersebut bisa dipanen di umur masak tebang.
Oleh karenanya dilakukan peningkatan luas areal penanamannya, hal ini didukung
dengan kondisi tanaman pada kelas umur tua (KU III ke atas), terutama pada kelas
umur masak tebang yang luas arealnya jauh lebih lebih kecil.
Luas tanah kosong (TK) dan tanaman Jati bertumbuhan kurang (TJBK)
pada setiap tahun risalah semakin bertambah (Lampiran 2) sejak tahun 1985
sampai tahun 2005, dengan demikian dapat dikatakan bahwa luasan tegakan jati
yang mengalami kerusakan terus mengalami peningkatan dari periode II (1985 –
1995) hingga periode III (1995 – 2005).
Gambar 2 Perubahan kelas hutan untuk produksi kayu jati BH Brebek.
Perubahan tegakan yang terjadi di BH Brebek (Gambar 2) juga mengalami
hal yang sama dengan yang terjadi di BH Tritik, yaitu luasan setiap kelas umur
Perubahan yang paling besar terjadi pada saat KU III menjadi KU IV di periode
III (1995 – 2005), dimana luas KU III pada tahun risalah 1995 adalah sebesar
982,9 Ha kemudian di tahun risalah 2005 KU III yang dapat tumbuh menjadi KU
IV hanya sebesar 71,3 Ha. Pada Gambar 2 terlihat luas setiap kelas umur dan luas
total produktif dari tahun risalah 1975 hingga tahun risalah 2005 selalu
mengalami penurunan, terkecuali untuk luas total produktif pada tahun risalah
2005 yang mengalami kenaikan akibat kegiatan penanaman sebesar 5163,6 Ha.
Sehingga dapat dikatakan untuk BH Brebek perubahan kelas umur tegakan selama
3 periode (30 tahun) sudah tidak dapat tumbuh sesuai dengan yang diharapkan
dan sudah mengalami gangguan hutan sejak periode awal.
Hal yang sama juga terjadi di BH Brebek apabila melihat perubahan kelas
hutan yang tidak produktif pada (Lampiran 2), yaitu luas TK dan TJBK pada
setiap tahun risalah selalu mengalami kenaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pada BH Brebek luasan tegakan jati yang mengalami kerusakan terus mengalami
peningkatan sejak periode awal hingga periode akhir. Sehingga tegakan yang
masak tebang tidak dapat memenuhi jumlah tebangan yang sudah ditentukan oleh
pihak Perhutani.
Jika melihat pada syarat-syarat umum yang ditentukan Osmaston (1968),
secara umum kondisi yang terjadi di KPH Nganjuk baik di BH Tritik maupun di
BH Brebek saat ini tidak dapat memenuhinya. Karena tegakan yang ada di
lapangan saat ini tidak bisa mencapai kuantitas atau hasil yang diinginkan,
sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Begitu juga sama halnya dengan
konsep hutan normal pada tegakan seumur, dimana menurut Osmaston (1968) ada
beberapa norma utama yang harus dimiliki. Kondisi tegakan di lapangan saat ini
tidak dapat memenuhi beberapa norma tersebut, yaitu stok pertumbuhan yang ada
di lapangan dan pertumbuhannya tidak normal.
Untuk mengetahui besarnya total luas hutan produktif dan penyebaran
komposisi tegakan jati dalam setiap kisaran kelas umur dan di setiap tahun risalah,
diperlukan data hasil rekapitulasi hutan produktif yang disajikan pada Tabel 2
Tabel 2 Rekapitulasi hutan produktif BH Tritik.
Kelas Umur
Luas (Ha)
Tahun Risalah
1975 1985 1995 2005
KU I - III 4424,9 5330,9 4963,8 6598,9
Dari Tabel 2 di atas terlihat sejak tahun risalah 1975 hingga tahun risalah
2005 tegakan Jati kelas umur di bawah 30 tahun (KU I – III) selalu memliki luas
yang domninan di atas 50 % dibandingkan dengan tegakan Jati kelas umur di atas
30 tahun. Terutama pada kondisi akhir (tahun 2005) sangat terlihat jelas tegakan
jati muda (KU I – III) sangat mendominasi, bahkan sampai melebihi 75 %
(sebesar 80 %). Sehingga pada KU IV – VI komposisinya sangat kecil yaitu
sebesar 16 %, apalagi pada KU VII ke atas (masak tebang) hanya memiliki
komposisi yang lebih kecil lagi yaitu sebesar 4 %.
Tabel 3 Rekapitulasi hutan produktif BH Brebek.
Kelas Umur
Tegakan jati KU I – III di BH Brebek (lihat Tabel 3) selalu memiliki luas
yang dominan pada setiap tahun risalah yaitu sebesar 93 %, terutama pada tahun
sebesar 98 %. Sedangkan untuk KU IV ke atas hanya memiliki komposisi yang
sangat kecil, yaitu masing-masing sebesar 1 %.
Setelah melihat perubahan kelas hutan dan rekapitulasi hutan produktif di
kedua BH KPH Nganjuk, dapat dikatakan perubahan kelas hutan yang terjadi
selalu mengalami kerusakan atau gangguan hutan pada setiap periodenya, hal ini
didukung dengan semakin meningkatnya luasan TK dan TJBK, serta komposisi
tegakan jati di kelas umur tua (KU III ke atas) pada risalah tahun 2005 yang
sangat kecil baik di BH Tritik maupun di BH Brebek. Kemudian dari data laju
perubahan areal produktif di kedua BH dari periode awal hingga periode akhir
menunjukkan angka yang relatif besar untuk setiap tahunnya, yang berarti
semakin besar pula penurunan luas areal produktifnya. Untuk melihat laju
perubahan areal produktif kedua bagian hutan dapat dilihat pada Tabel 4 dan
Tabel 5.
Tabel 4 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Tritik.
Kelas Umur
Periode Periode Periode
1975 - 1985 1985 - 1995 1995 - 2005
Tabel 5 Laju perubahan areal produktif setiap KU pada BH Brebek.
Laju perubahan areal produktif di atas merupakan laju pengurangan luas
areal produktif (berhutan) setiap tahun, dari kelas umur awal menjadi kelas umur
berikutnya. Dapat dilihat bahwa pada Tabel 4, secara keseluruhan laju perubahan
areal produktif yang paling tinggi selama 3 periode terakhir terjadi di periode
1995 - 2005 pada saat KU III menjadi KU IV yaitu sebesar 88 ha/th. Sedangkan
laju perubahan areal produktif yang paling kecil pada saat KU VII menjadi KU
VIII di periode 1975 – 1985 yaitu sebesar 2 ha/th. Apabila dilihat menurut
masing-masing periode, maka pada periode awal (1975 – 1985) laju perubahan
tertinggi yaitu pada saat KU I menjadi KU II adalah sebesar 23 ha/th dan yang
terkecil pada saat KU VII menjadi KU VIII yaitu sebesar 2 ha/th. Kemudian di
perode berikutnya (1985 – 1995) laju perubahan yang paling besar terjadi pada
saat KU III menjadi KU IV yaitu sebesar 44 ha/th, sedangkan laju perubahan yang
paling kecil terjadi pada saat KU IV menjadi KU V yaitu sebesar 9 ha/th. Di
periode terakhir (1995 – 2005) laju perubahan tertinggi terjadi pada saat KU III
menjadi KU IV yaitu sebesar 88 ha/th, dan untuk laju perubahan terkecil terjadi
pada saat KU I menjadi KU II yaitu sebesar 21 ha/th. Selain itu, rata-rata laju
perubahan areal produktif terbesar dari periode awal hingga periode akhir yang
terjadi di BH Tritik adalah pada saat KU III menjadi KU IV. Sehingga dapat
dikatakan tegakan jati di BH Tritik pada saat sekarang ini tidak mampu
dipertahankan.
Sedangkan pada BH Brebek (lihat Tabel 5), secara keseluruhan laju
perubahan areal produktif yang paling tinggi selama 3 periode terjadi di periode
terakhir pada saat KU III menjadi KU IV yaitu sebesar 91 ha/th. Sedangkan laju
perubahan yang terkecil terjadi di periode 1975 – 1985 dan periode 1985 – 1995
pada saat KU V menjadi KU VI yaitu sebesar 0 ha/th atau tidak mengalami laju
perubahan areal produktif, hal ini dikarenakan pada kelas umur tersebut hanya
terdapat satu petak di BH Brebek. Sama halnya dengan KU IV dari periode awal
hingga periode akhir selalu tidak mengalami laju perubahan areal produktif, hal
ini dikarenakan sudah tidak ada lagi kelas umur tegakan yang tergolong KU IV
sejak tahun 1975. Bila dilihat menurut masing-masing periode, pada periode awal
laju perubahan yang paling besar terjadi pada saat KU II menjadi KU III yaitu
menjadi KU VI yaitu sebesar 0 ha/th. Kemudian di periode berikutnya laju
perubahan terbesar yaitu pada saat KU III menjadi KU IV sebesar 82 ha/th dan
laju perubahan terkecil pada saat KU VI menjadi KU VII sebesar 0 ha/th. Di
periode terakhir laju perubahan yang paling besar terjadi pada saat KU III menjadi
KU IV yaitu sebesar 91 ha/th, sedangkan laju perubahan yang paling kecil terjadi
pada saat KU VII menjadi KU VIII yaitu sebesar 1 ha/th. Disamping itu rata-rata
laju perubahan areal produktif terbesar dari periode awal sampai periode terakhir
adalah pada saat KU II menjadi KU III dan pada saat KU III menjadi KU IV.
5.2 Identifikasi Perubahan Kelas Hutan Produktif
5.2.1 Persentase Luas Tegakan Produktif yang Mencapai Kelas Umur Berikutnya dalam 3 Periode Terakhir
Dalam mengidentifikasi perubahan kelas hutan produktif tegakan jati
dalam 3 periode terakhir diperlukan data persentase luas tegakan produktif yang
mencapai kelas umur berikutnya di kedua bagian hutan, dimana data tersebut
diperoleh dari data perubahan kelas hutan produktif di KPH Nganjuk selama 3
periode tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya, seperti yang disajikan
pada Tabel 6 (BH Tritik) dan Tabel 7 (BH Brebek). Dari data tersebut dapat
terlihat seberapa besar persentase komposisi tegakan jati untuk setiap kelas umur,
yang mampu tumbuh dengan baik dari periode awal hingga periode akhir.
Tabel 6 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode terakhir tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Tritik).
Dari Tabel 6 (BH Tritik) dapat terlihat pada periode awal (1975 – 1985)
persentase luas tegakan jati yang mencapai kelas umur berikutnya di setiap KU
atas 75 %) terkecuali untuk KU VII ke atas, karena pada KU tersebut sudah
memasuki umur masak tebang. Kemudian jika melihat pada periode-periode
berikutnya persentase luas tegakan jati yang mencapai kelas umur berikutnya di
BH Tritik telah mengalami penurunan, terutama pada periode III (1995 – 2005).
Persentase luas tegakan jati yang tertinggi pada periode I adalah KU II – III yaitu
sebsar 95 %, sedangkan persentase yang paling rendah pada KU IV - V yaitu
sebesar 80 %. Di periode II (1985 – 1995) yang memiliki persentase tertinggi
adalah KU II – III yaitu sebesar 93 %, dan persentase yang paling rendah adalah
KU V – VI yaitu sebesar 66 %. Sedangkan persentase luas tegakan jati di periode
III telah mengalami penurunan yang lebih drastis hampir di semua kelas umur
kecuali pada KU I – II yang mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena pada KU I
telah dilakukan penanaman. Dimana pada periode III yang memiliki persentase
tertinggi adalah KU I – II yaitu sebesar 88 %, dan persentase yang paling rendah
pada KU VI – VII yaitu hanya sebesar 8%. Setelah melihat perubahan persentase
luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya yang terjadi di BH
Tritik selama 3 periode, dapat terbukti bahwa kerusakan yang paling tinggi terjadi
di periode III (1995 – 2005).
Tabel 7 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya dalam 3 periode terakhir tanpa memperhatikan perubahan di setiap petaknya (BH Brebek).
Untuk BH Brebek menunjukkan kondisi yang berbeda (lihat Tabel 7),
akan tetapi tetap mengalami penurunan dari periode awal hingga periode akhir,
hampir di setiap kelas umur. Di periode I hanya pada KU V – VI yang mampu
tumbuh dengan baik hingga 100 %, dan persentase yang paling rendah pada KU
besar antara nilai tertinggi dengan nilai terkecil, hal ini diduga karena pada tahun
risalah 1975 tidak ada tegakan yang tergolong KU IV. Kemudian di periode
berikutnya hampir seluruh KU mengalami penurunan atau kerusakan, dimana
persentase tertinggi adalah KU VI – VII yang di periode sebelumnya merupakan
KU V – VI yaitu sebesar 100 %, sedangkan persentase terkecil adalah KU V – VI
yang di periode sebelumnya KU IV – V yaitu sebesar 0 %. Di periode III
menunjukkan kadaannya lebih buruk dibanding periode sebelumnya, seluruh KU
mengalami penerunan yang sangat drastis. Selain KU VII ke atas yang memiliki
persentase tertinggi adalah KU I – II yaitu sebesar 44 %, sedangkan persentase
yang paling rendah adalah KU V – VI dan KU VI – VII, yaitu masing-masing
sebesar 0 % atau tidak ada tegakan pada KU tersebut yang mencapai kelas umur
berikutnya. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa keadaan di BH Brebek pada
periode terakhir lebih buruk daripada periode-periode sebelumnya, hal ini juga
menunjukkan gangguan hutan yang terjadi semakin lama semakin tinggi.
Dari Tabel 6 dan Tabel 7 di atas dapat terlihat bahwa keadaan di BH
Brebek lebih buruk, hal ini ditunjukkan dengan lebih rendahnya nilai-nilai
persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya di BH
Brebek. Walaupun di kedua BH keadaanya berbeda, akan tetapi sama-sama
mengalami penurunan atau kerusakan di setiap periodenya, terutama di periode
akhir (1995 – 2005).
5.2.2 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Selama 30 Tahun
Untuk melihat besarnya persentase komposisi tegakan jati yang dapat
tumbuh dengan baik selama 30 tahun, diperlukan data persentase luas tegakan
produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 3 periode, seperti yang
disajikan pada Tabel 8 (BH Tritik) dan Tabel 9 (BH Brebek). Data tersebut
diperoleh dari hasil identifikasi perubahan kelas umur setiap petak dalam jangka
waktu yang berbeda-beda. Pada data ini kondisi awal setiap periodenya sama
yaitu pada tahun 1975, sehingga lamanya jangka waktu yang dimiliki dari periode
awal hingga periode akhir adalah 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Dari data ini
maka akan diketahui seberapa besar persentase kemampuan suatu tegakan kelas
umur yang mencapai kelas umur berikutnya dengan jangka waktu yang
Tabel 8 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Tritik).
Kelas Umur Periode 10 Tahun Periode 20 Tahun Periode 30 Tahun
(%) (%) (%)
Dari Tabel 8 (BH Tritik) dapat terlihat dalam jangka waktu 10 tahun (1975
- 1985) luas tegakan jati yang dapat tumbuh dengan baik di setiap KU memiliki
persentase yang tinggi. Dimana persentase tertinggi pada KU II yaitu sebesar 93
%, dan persentase terkecil pada KU IV yaitu sebesar 78 %. Dalam jangka waktu
20 tahun (1975 - 1995) dapat terlihat telah terjadi penurunan persentase pada
setiap KU, dimana persentase tertinggi pada KU I dan KU II yaitu sebesar 73 %
sedangkan persentase paling rendah pada KU IV yaitu sebesar 53 %. Kemudian
dalam jangka waktu 30 tahun (1975 - 2005) persentase luas tegakan jati yang
mencapai kelas umur berikutnya mengalami penurunan yang sangat drastis pada
setiap KU. Persentase tertinggi yang dimiliki hanya sebesar 37 % yaitu pada KU I,
dan persentase yang paling rendah terjadi pada KU IV yaitu sebesar 3 %. Untuk
KU VII yang hampir selalu memiliki persentase paling rendah dalam setiap
periode disebabkan oleh adanya kegiatan penebangan atau pemanenan, karena
daur yang digunakan di KPH Nganjuk adalah 80 tahun. Begitu pula dengan KU V
di periode 30 tahun dan KU VI di periode 20 tahun yang sudah mencapai umur
masak tebang. Apabila dilihat secara keseluruhan perubahan persentase luas
tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun di BH
Tritik dengan kondisi awal pada tahun 1975, dapat terlihat bahwa kerusakan
tegakan selalu mengalami penurunan di setiap periode berjalan, dan kerusakan
yang paling tinggi terjadi pada periode 30 tahun atau di atas tahun 1995, sehingga
tegakan yang diharapkan tumbuh dengan baik hanya mampu bertahan selama satu
Tabel 9 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya selama 30 tahun (BH Brebek).
Kelas Umur PERIODE 10 Tahun PERIODE 20 Tahun PERIODE 30 Tahun
(%) (%) (%)
Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya
selama 3 periode yang terdapat di BH Brebek (Tabel 8) dalam jangka waktu 10
tahun (Periode 10 tahun) bisa dikatakan tidak sebaik yang dimiliki di BH Tritik,
kemudian persentase tertinggi justru dimiliki oleh kelas umur tua yaitu pada KU
V sebesar 93 %, sedangkan persentase yang paling rendah pada KU II dan KU III
yaitu sebesar 63 %. Dalam jangka waktu 20 tahun (Periode 20 tahun) persentase
luas tegakan jati hampir di setiap KU mengalami penurunan, kecuali pada KU V
yang masih memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 93 %, dan persentase
paling rendah pada KU II sebesar 27 %. Sedangkan dalam jangka waktu 30 tahun
(periode 30 tahun) telah terjadi penurunan yang sangat drastis, untuk KU V
walaupun mengalami penurunan yang drastis tapi masih memiliki persentase yang
paling tinggi yaitu sebesar 44 %, penurunan ini diduga karena pada periode 30
tahun KU V sudah mencapai kelas umur masak tebang sama halnya dengan KU
VI dan KU VII yang sudah mencapai umur masak tebang sejak periode 20 tahun
dan periode 10 tahun. Selain KU V ke atas, kelas umur yang memiliki persentase
paling tinggi adalah KU I yaitu hanya sebesar 3 %, sedangkan persentase paling
rendah yaitu pada KU II dan KU III sebesar 0 % atau dengan kata lain tidak ada
tegakan yang bisa tumbuh dengan normal sampai jangka waktu 30 tahun. Pada
KU IV yang di setiap periodenya selalu memiliki persentase paling rendah (0 %)
dikarenakan sudah tidak terdapat tegakan yang tergolong KU tersebut sejak awal
tahun risalah 1975. Bila dilihat dari data yang disajikan pada Tabel 8, di BH
Brebek tegakan jati sudah mengalami kerusakan sejak periode pertama, dan selalu
terjadi penurunan setiap periodenya. Terutama pada periode 30 tahun bisa
hanya 3 % yang kini sudah mencapai KU IV, disamping kelas umur yang masak
tebang.
5.2.3 Perubahan Komposisi Tegakan Jati Setiap Periode 10 Tahun
Besarnya perubahan persentase komposisi tegakan jati setiap periode, yang
mana kondisi awal pada masing-masing periode berbeda-beda tetapi memliki
jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun untuk setiap periode, dapat dilihat pada
Tabel 10 (BH Tritik) dan Tabel 11 (BH Brebek). Data ini diperoleh dari hasil
identifikasi perubahan kelas umur tegakan jati setiap petak, dengan cara
mengidentifikasi perubahan kelas umur setiap petak dalam jangka waktu 10 tahun
(1 periode). Dari kedua tabel tersebut dapat terlihat persentase luas tegakan jati
yang dapat tumbuh dengan baik selama 10 tahun dalam 3 periode terakhir (30
tahun).
Tabel 10 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya setiap periode 10 tahun (BH Tritik).
Kelas Umur Periode 1975 - 1985 Periode 1985 - 1995 Periode 1995 - 2005
(%) (%) (%)
Tabel 11 Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya setiap periode 10 tahun (BH Brebek).
Kelas Umur Periode 1975 - 1985 Periode 1985 - 1995 Periode 1995 - 2005
(%) (%) (%)
Persentase luas tegakan produktif yang mencapai kelas umur berikutnya