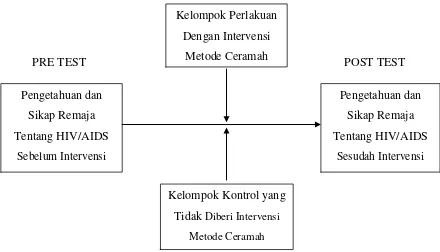BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Komunikasi
Menurut Effendy (2003), komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia
baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak
komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Sejak dilahirkan
manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Selain itu komunikasi diartikan
pula sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah
hubungan atau dapat pula diartikan bahwa komunikasi adalah saling tukar menukar
pikiran atau pendapat.
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Menurut Wilbur Schramm dalam
Effendy (1992), komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh
komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of references), yakni panduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences), yang pernah diperoleh komunikan (Effendy, 1992).
Menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh
komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dari
(siapa), Says What (berkata apa), in Which Channel (melalui saluran apa), to Whom
(kepada siapa) dan With What Effect (dengan efek apa) (Effendy, 2003).
a) Who (siapa) : Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi bisa dalam bentuk perorangan ataupun lembaga atau
instansi.
b) Says What (apa yang dikatakan) : pernyataan umum adalah dapat berupa suatu ide, informasi, opini, pesan dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan
pesan yang disampaikan.
c) In Which Channel (melalui saluran apa) : media komunikasi atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi.
d) To Whom (kepada siapa) : komunikan atau audience yang menjadi sasaran komunikasi adalah kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan, berkaitan
dengan si penerima pesan.
e) With What Effect (dengan efek apa) : hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju.
Sedangkan defenisi lain menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu
transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang yang mengatur
lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui
pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4)
2.1.1. Tujuan Komunikasi
Menurut Effendy (2003), pada umumnya komunikasi mempunyai tujuan,
antara lain :
1. Untuk mengubah sikap (to charge the attitude), yaitu kegiatan memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan
berubah sikapnya.
2. Untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (to the change the opinion), mencakup pemberian berbagai informasi pada masyarakat. Tujuan akhirnya
supaya masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan
informasi yang disampaikan.
3. Untuk mengubah perilaku (to change the behavior), yaitu kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan supaya
masyarakat akan berubah perilakunya.
4. Untuk mengubah masyarakat (to change the society), mencakup pemberian berbagai informasi kepada masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan agar
masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang
disampaikan.
2.1.2. Fungsi Komunikasi
Menurut Effendy (2003), proses komunikasi tidak terlepas dari bentuk dan
fungsi komunikasi, dimana komunikasi yang baik tidak jauh dari fungsi yang
Adapun fungsi komunikasi itu sendiri adalah sebagai berikut :
1) Menginformasikan (to inform)
Fungsi memberikan informasi adalah suatu fungsi yang menyebarluaskan suatu
berita atau info yang kita ketahui kepada masyarakat. Perilaku menerima informasi
merupakan perilaku alamiah dari masyarakat. Dengan menerima informasi yang
benar masyarakat akan merasa aman tentram.
2) Mendidik (to educated)
Kegiatan komunikasi pada masyarakat dengan memberikan berbagai informasi
tidak lain agar masyarakat menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang
kebudayaannya. Kegiatan memberi pengetahuan atau mendidik dalam arti luas adalah
memberikan berbagai informasi yang dapat menambah kemajuan dan dalam arti
sempit adalah memberikan berbagai informasi dan juga berbagai ilmu pengetahuan
melalui berbagai tatanan komunikasi pada pertemuan-pertemuan, kelas-kelas, dan
sebagainya.
3) Menghibur (to entertain)
Perilaku masyarakat menerima informasi selain untuk memenuhi rasa aman juga
menjadi sarana hiburan. Apalagi pada masa sekarang ini banyak penyajian informasi
melalui sarana hiburan. Fungsi menghibur ini dapat memberi kesenangan dan
mencegah kebosanan masyarakat sebagai penerima informasi. Fungsi menghibur ini
dapat menumbuhkan kesadaran (social awareness) dalam menerima pesan. Maksudnya adalah penerima pesan itu dapat merasakan apa yang dialami oleh
4) Memengaruhi (to influence)
Fungsi memengaruhi adalah suatu kegiatan memberikan berbagai informasi pada
masyarakat juga dapat dijadikan sarana untuk memengaruhi masyarakat tersebut
kearah perubahan sikap, pendapat dan perilaku yang diharapkan.
2.2. Efektivitas
2.2.1. Pengertian Efektivitas
Menurut Danfar (2009) efektivitas berasal dari kata efektif, dimana pengertian
efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan
yang telah ditetapkan atau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Menurut Suprapto (2011), efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah
keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari
produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu
pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas
berarti ada pengaruhnya, efeknya, manjur atau mujarab dan dapat membawa hasil
atau berdaya guna. efektivitas dipandang tidak hanya dari aspek hasil atau output
yang berdimensi sempit, tetapi sebagai sebuah konsep, efektivitas juga dapat
dipandang dari aspek yang berdimensi lebih luas.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu
aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah
yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan
dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka
aktifitas itu dikatakan tidak efektif (Suprapto, 2011).
Menurut Campbell (1989), terdapat cara pengukuran terhadap efektivitas yang
secara umum dan yang paling menonjol adalah : keberhasilan program, keberhasilan
sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan
menyeluruh.
2.2.2. Pendekatan Efektivitas
Menurut Price (1972), pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur
sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap
efektivitas yaitu :
a) Pendekatan Sasaran (Goal Approach)
Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil
merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran
efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan
keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.
b) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)
Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga
dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga
harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan
sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan
yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh
sumber-sumber yang merupakan input dan output yang dihasilkan juga dikembalikan pada
lingkungannya.
c) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)
Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi
kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal
berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara
terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan
memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber
yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan
lembaga.
2.2.3. Masalah dalam Pengukuran Efektivitas
Steers (1985), mengemukakan bahwa efektivitas selalu diukur berdasarkan
prestasi, produktivitas dan laba. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran
yang sebenarnya dan memberikan hasil pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran
dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut :
a) Adanya macam-macam output
Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran
efektivitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran
juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya.
Efektivitas tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan suatu indikator atau
yang rendah pada sasaran lainnya. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran
efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektivitas
pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang sering
dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektivitas
dimana kriteria dalam pengukuran efektivitas adalah : adaptabilitas dan fleksibilitas,
produktivitas, keberhasilan memperoleh sumber, keterbukaan dalam komunikasi,
keberhasilan pencapaian program, pengembangan program (Steers, 1985).
b) Subjektivitas dalam adanya penilaian
Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali
mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan
juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran. Untuk
itu ada baiknya bila meninjau bahwa perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk
mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya dari
dalam suatu lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau
masyarakat, seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas. Untuk sasaran yang dinyatakan
dalam bentuk kualitatif, unsur subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran
yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat
tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya (Steers,
2.3. Peran Komunikasi Kesehatan
Menurut Liliweri (2009), komunikasi kesehatan adalah studi yang
mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk
menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat memengaruhi individu dan
komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan
pengelolaan kesehatan.
Komunikasi kesehatan merupakan kegunaan teknik komunikasi dan teknologi
komunikasi secara positif untuk memengaruhi individu, organisasi, komunitas dan
penduduk bagi tujuan mempromosikan kondisi yang kondusif atau yang
memungkinkan tumbuhnya kesehatan manusia dan lingkungan. Kegunaan itu
termasuk beragam aktivitas seperti interaksi antara profesional kesehatan dengan para
pasien di Klinik, kampanye, media massa, dan penciptaan peristiwa.
Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit,
promosi kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, yang sejauh mungkin
mengubah dan membaharui kualitas individu dalam suatu komunitas atau masyarakat
dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika (Liliweri, 2009).
2.4. Komunikasi Tatap Muka Forum (Kelompok)
2.4.1. Pengertian Komunikasi Tatap Muka Forum
Menurut Vardiansyah (2004) yang mengutip pendapat Goldberg dan Larson
(1985), komunikasi tatap muka forum adalah suatu bidang studi, penelitian dan
dalam kelompok, tetapi pada tingkah laku individu dalam komunikasi kelompok
tatap muka yang kecil.
Komunikasi tatap muka forum bersifat langsung, terjadi dalam suasana yang
lebih berstruktur dimana para pesertanya lebih cenderung melihat dirinya sebagai
kelompok serta mempunyai kesadaran tinggi tentang sasaran bersama, komunikasi ini
kurang dipengaruhi emosi dan melibatkan pengaruh antar pribadi, umpan balik pesan
berlangsung cepat, adaptasi pesan bersifat khusus, serta lebih cenderung dilakukan
secara sengaja dan umumnya para pesertanya lebih sadar akan peranan dan tanggung
jawab mereka masing-masing (Vardiansyah, 2004).
Komunikasi tatap muka forum merupakan komunikasi yang berlangsung
antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua
orang (kalau kelompok kecil berjumlah 4-20 orang, kelompok besar 20-50 orang)
(Liliweri, 2009). Komunikasi tatap muka forum pada dasarnya adalah aktivitas
komunikasi. Aktivitas komunikasi tatap muka ini bentuknya bermacam-macam,
mulai dari perbincangan, wawancara, ceramah, seminar, rapat, konseling, lokakarya,
hingga pameran (Vardiansyah, 2004).
2.4.2. Efek Komunikasi Tatap Muka Forum
Efek komunikasi kita artikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan
komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat tiga tataran pengaruh dalam diri
komunikan, yaitu kognitif (seseorang menjadi tahu tentang sesuatu), afektif (sikap
seseorang terbentuk, misalnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu) dan konatif
komunikasi dapat diukur dengan membandingkan antara pengetahuan, sikap dan
tingkah laku sebelum dan sesudah komunikan menerima pesan (Stuart, 1987) dalam
(Vardiansyah, 2004). Karenanya efek adalah salah satu elemen komunikasi yang
penting untuk mengetahui berhasil atau tidaknya komunikasi yang anda inginkan.
Menurut (Vardiansyah, 2004) komunikasi efektif adalah sejauh mana motif
komunikasi komunikator terwujud dalam diri komunikannya, apabila motif
komunikasi kita maknai sebagai tujuan komunikasi, maka dapat dinyatakan bahwa
apabila hasil yang didapatkan sama dengan tujuan komunikasi, maka dapat
dinyatakan bahwa komunikasi berlangsung efektif, apabila hasil yang didapatkan
lebih besar dari tujuan yang diharapkan, dikatakan bahwa komunikasi berlangsung
sangat efektif, sebaliknya apabila hasil yang didapatkan lebih kecil daripada tujuan
yang diharapkan, dikatakan bahwa komunikasi tidak atau kurang efektif.
Menurut Huraerah dan Purwanto (2006) yang mengutip pendapat De vito (1983),
ada enam faktor efektivitas komunikasi tatap muka forum, yaitu :
1) Leadership (Kepemimpinan)
Kemampuan pembicara untuk memengaruhi pihak lain. Untuk dapat memengaruhi
orang lain, maka pada diri seseorang pembicara diperlukan adanya suatu kekuatan,
kekuasaan (power) dan kredibilitas (credibility) agar dapat mengarahkan atau memengaruhi orang lain pada pencapaian tujuan. Pada dasarnya dalam suatu
komunikasi, komunikator telah disiapkan kekuatan serta kredibilitas sebagai seorang
Menurut Liliweri (2009) yang mengutip pendapat (De Vito, 1983) aspek
kredibilitas komunikator meliputi :
a. Competence (Kompetensi) yaitu kemampuan komunikator yang diperlihatkan melalui kewenangan (pangkat, jabatan, kepakaran) atas suatu subjek yang
sedang diperbincangkan.
b. Character (Karakter), kebiasaan yang diperlihatkan oleh moral komunikator. c. Intention (Intensi), motif atau maksud yang mendorong komunikator
mengatakan sesuatu.
d. Personality (Personaliti), yakni perasaan kedekatan (proximity) antara komunikan dengan komunikator (kesamaan psikologis, sosiologis,
antropologis sering memengaruhi rasa kedekatan antara komunikan dengan
komunikator).
e. Dynamics (Dinamis), yakni dinamika yang diperlihatkan oleh seorang
komunikator.
2) Goals (Tujuan)
Tujuan masyarakat yang menyebabkan komunikasi berlangsung. Tiap komunikasi
tatap muka forum pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yang
merupakan tujuan bersama, yang menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan ini
merupakan integrasi dari tujuan individu masing-masing.
3) Norms (Norma)
Aturan main yang ada sehingga komunikasi dapat berlangsung. Dalam komunikasi
simbol oleh seorang komunikator kepada komunikan. Norma disini adalah
pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu kelompok.
Pedoman ini sesuai dengan rumusan tingkah laku yang patut dilakukan dalam
komunikasi tatap muka forum.
4) Roles (Peran)
Peran yang dijalankan oleh individu-individu yang ada dalam melakukan
komunikasi. Peranan tersebut meliputi, pemecahan masalah atau melahirkan
gagasan-gagasan baru, memelihara emosional diantara komunikan dan
komunikator, serta mengkoordinasi kegiatan yang menunjang demi tercapainya
tujuan dalam komunikasi tatap muka forum.
5) Cohesiveness (Keeratan)
Keeratan hubungan diantara anggota forum atau komunikan sangat perlu
dilakukan. Cara yang paling efektif adalah membentuk hubungan yang
kooperatif diantara komunikator dan komunikan pada saat berkomunikasi.
Beberapa cara lainnya adalah memperdalam kepercayaan diantara anggota
forum, mengekspresikan afeksi lebih jauh lagi diantara anggota forum,
meningkatkan ekspresi saling inklusi dan menerima diantara anggota forum dan
mengembangkan norma-norma yang menunjang ekspresi individu diantara
anggota forum. Sehingga terbina komunikasi efektif diantara komunikator
6) Outcomes (Hasil)
Hasil penyelenggaraan komunikasi forum merupakan indikator yang baik untuk
mengukur seberapa besar efektivitas yang terjalin selama komunikasi berlangsung
karena untuk menimbulkan hasil yang dicapai, kita harus berhasil terlebih dahulu
menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan
hubungan yang baik dalam seluruh proses komunikasi. Efektivitas komunikasi
ditentukan oleh kualitas pelakunya, yakni persepsi yang dihasilkan oleh suatu pihak
terhadap pihak lainnya. Kualitas pelaku tersebut meliputi kredibilitas (credibility) dan kekuasaan (power). Kredibillitas merupakan suatu image atau gambaran audiens
mengenai kepribadian komunikator. Seorang pendengar akan mendengarkan
komunikator yang dia nilai mempunyai tingkat kredibilitas tinggi.
Menurut Liliweri (2009) yang mengutip pendapat De vito (1978), tiga tipe
kredibilitas, yaitu :
a. Initial credibility, yakni inisial yang menunjukkan status atau posisi seseorang, misalnya jabatan, pangkat, gelar-gelar akademik atau
kebangsawanan, dan lain-lain.
b. Derived credibility, yakni sesuatu yang mengesankan bagi komunikan pada saat komunikasi sedang berlangsung, misalnya tentang kemampuan
intelektual, moral komunikator, tentang kompetensi hingga kemampuan
untuk mengekspresikan kata-kata melalui bahasa isyarat (non verbal)
Menurut Huraera dan Purwanto (2006) yang mengutip pendapat Iskandar
(1990), power (kekuasaan ) meliputi :
a. Legitimasi power, merupakan kekuatan yang sah dimiliki oleh seorang komunikator sebagai pemimpin, kepada komunikan untuk dapat memerintah
dirinya atau mengatur dirinya dalam bertingkah laku untuk mencapai tujuan
berkomunikasi yang ingin dicapai.
b. Coercive power, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh komunikator untuk mengontrol atau mengawasi komunikan, sejalan dengan proses pencapaian
tujuan.
c. Reward power, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh komunikator, yang mana komunikator dapat memberikan penghargaan, pujian serta hadiah
kepada komunikan. Hal ini dilakukan oleh komunikator karena komunikannya
telah berhasil menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pencapaian tujuan.
d. Expert power, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang komunikator yang karena keahliannya, dan atau pengetahuannya, komunikator diakui oleh
orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat dipengaruhi olehnya.
e. Referent power, suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dimana selalu digunakan sebagai tempat acuan seperti, pesona kharismatik, panutan, idola,
sehingga komunikator dianggap mempunyai kekuatan kepada komunikannya.
2.4.3. Teori Rogers Difusi Inovasi
Menurut Liliweri (2009) yang mengutip pendapat Rogers, difusi inovasi
para penerima yang ada dalam suatu sistem sosial. Difusi inovasi merupakan model
penyebarluasan gagasan atau material (teknologi) dengan mengetengahkan cara
penyebarluasan inovasi (misalnya gagasan baru, pendekatan baru, dan strategi baru)
melalui saluran tertentu (umumnya sistem sosial tradisional-moderen) dalam suatu
waktu tertentu kepada sejumlah anggota masyarakat atau komunitas dalam suatu
sistem sosial.
Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1978)
merupakan suatu landasan yang menekankan pentingnya saluran komunikasi dan
penyebarserapan ide-ide melalui peran agen-agen perubahan dalam lingkungan sosial.
Secara relatif, tetangga, petugas kesehatan atau agen perubahan yang lain ikut
membantu menghasilkan perubahan perilaku dengan cara-cara tertentu, misalnya
dengan cara meningkatkan kebutuhan akan perubahan, membangun hubungan
interpersonal yang diperlukan, rnengidentifikasi masalah-masalah dan penyebabnya,
mendapatkan sasaran dan jalan keluar yang potensial serta memotivasi seseorang
supaya menerima dan memelihara aksi (Liliweri, 2009).
Asumsi dari suatu inovasi adalah adanya jenis-jenis gagasan tertentu yang
perlu diadopsikan kepada anggota-anggota dari suatu sistem sosial karena mereka
sangat membutuhkan informasi tersebut dari para pemuka pendapat dalam sistem
sosial. Sedangkan karakteristik sukses inovasi terjadi kalau para anggota sistem sosial
itu menerima inovasi tersebut (Liliweri, 2009).
Menurut Effendy (2003) yang mengutip pendapat Rogers (1995), mengatakan
pengetahuan dan percobaan sikap terhadap ide baru dalam upaya memengaruhi
keputusan untuk melakukan adopsi atau menolak ide baru, sumber hubungan dari
saluran komunikasi dapat menambahkan informasi atau mengklarifikasi poin-poin
dan mungkin mengatasi kendala psikologis dan sosial (paparan yang selektif,
perhatian, persepsi, daya ingat , norma-norma kelompok serta nilai-nilai).
2.5. Promosi Kesehatan
Promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk
memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya melalui
pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar dapat menolong
dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat,
sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan
kesehatan (Depkes, 2005).
Promosi kesehatan dapat diartikan sebagai upaya menyebarluaskan,
mengenalkan atau menjual pesan-pesan kesehatan sehingga masyarakat menerima
atau membeli pesan-pesan kesehatan tersebut dan akhirnya masyarakat mau
berperilaku hidup sehat (Notoatmodjo, 2005).
Menurut Notoatmodjo (2005) yang mengutip pendapat Lawrence Green
(1984) merumuskan definisi promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi
pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan
organisasi, yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan
Promosi kesehatan mencakup aspek perilaku, yaitu upaya untuk memotivasi,
mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat
agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dengan kata lain,
adanya promosi tersebut diharapkan dapat membawa akibat terhadap perubahan
perilaku sasaran (Notoatmodjo, 2007).
2.6. Metode Promosi Kesehatan
Di dalam suatu proses promosi kesehatan yang menuju tercapainya tujuan
promosi kesehatan yakni perubahan perilaku, dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu
faktor metode, faktor materi atau pesannya, pendidik atau petugas yang
melakukannya untuk menyampaikan pesan. Metode dan teknik promosi kesehatan,
adalah dengan cara apa yang digunakan oleh pelaku promosi kesehatan untuk
menyampaikan pesan-pesan kesehatan atau mentransformasikan perilaku kesehatan
kepada sasaran atau masyarakat (Notoatmodjo, 2007).
2.6.1. Metode Ceramah
Metode ceramah merupakan metode pertemuan yang paling sederhana dan
paling sering diselenggarakan untuk menggugah kesadaran, minat sasaran, serta
pembicara lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan
materi dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk menyampaikan
tanggapannya (Mardikanto, 1993).
Nurlaili (2009) mengatakan bahwa metode ceramah adalah suatu cara
ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan. Peranan ceramah adalah
mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan
oleh orang yang memberikan ceramah tersebut.
Ceramah merupakan metode penyuluhan yang efektif pada kelompok sasaran
yang besar yaitu lebih dari 15 orang. Metode ini baik untuk sasaran yang
berpendidikan tinggi maupun rendah (Notoatmodjo, 2003).
Pengaruh besarnya jumlah sasaran dalam metode ini seringkali dengan
menggunakan alat bantu yang berupa materi tertulis dan gambar terproyeksi untuk
menarik perhatian dan memperjelas materi yang disampaikan. Waktu
penyelenggaraan ceramah juga harus dibatasi, maksimum 1-2 jam (Mardikanto,
1993).
Menurut Lunandi (1993), beberapa keuntungan menggunakan metode
ceramah adalah murah dari segi biaya, mudah mengulang kembali jika ada materi
yang kurang jelas ditangkap peserta daripada proses membaca sendiri, lebih dapat
dipastikan tersampaikannya informasi yang telah disusun dan disiapkan. Apalagi
kalau waktu yang tersedia sangat minim, maka metode inilah yang dapat
menyampaikan banyak pesan dalam waktu singkat. Selain keuntungan ada juga
kelemahan menggunakan metode ceramah, salah satunya adalah pesan yang terinci
mudah dilupakan setelah beberapa lama.
Metode ceramah juga mempunyai keunggulan-keunggulan antara lain : cepat
untuk menyampaikan informasi, informasi yang disampaikan bisa masuk pada
dari kalangan kelompok sasaran. Disamping keunggulan-keunggulan tersebut,
metode ceramah juga memiliki kelemahan, dimana merupakan komunikasi satu arah
sehingga sasaran menjadi pasif untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, pada
metode ceramah tidak dapat diidentifikasi kebutuhan per individu, sasaran tidak
diberi kesempatan untuk berfikir dan berperilaku kreatif, sasaran mudah menjadi
bosan jika waktu terlalu lama (LP3I Unair, 2009).
Menurut Notoatmodjo (2007), ceramah akan berhasil apabila penceramah itu
sendiri mempunyai persiapan dengan menguasai materi yang akan diceramahkan.
Untuk itu penceramah harus mempersiapkan diri dengan mempelajari materi dengan
sistematika yang baik, lebih baik lagi kalau disusun dalam diagram atau skema,
mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran (makalah singkat, slide, transparan, sound
sistem dan sebagainya).
Keberhasilan pelaksanaan ceramah adalah apabila penceramah tersebut dapat
menguasai sasaran ceramah. Untuk itu penceramah harus mempunyai sikap dan
penampilan yang meyakinkan, tidak boleh bersikap ragu-ragu dan gelisah, suara
hendaknya cukup keras dan jelas, pandangan harus tertuju ke seluruh peserta
ceramah, berdiri di depan (dipertengahan) dan tidak boleh duduk (Notoatmodjo
2007).
2.7. Proses Adopsi Perilaku
Menurut Notoatmodjo (2007) yang mengutip pendapat Rogers (1974),
di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni : kesadaran, interes,
evaluasi, percobaan dan adopsi.
Namun demikian dalam penelitian lanjutan Rogers (1983), telah menemukan
model baru dalam memperbaiki penelitiannya proses perubahan perilaku terdahulu
dengan teori yang dikenal “Diffusion of Innovation” meliputi :
a. Knowledge (Pengetahuan) terjadi bila individu (ataupun suatu unit perbuatan keputusan lainnya) diekspos terhadap eksistensi inovasi dan memperoleh
pemahamannya.
b. Persuasion (Persuasi) terjadi bila suatu individu (ataupun suatu unit keputusan lainnya) suatu sikap mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi
c. Decision (Keputusan) terjadi bila individu (atau unit pembuat keputusan lainnya) terlibat dalam berbagai aktivitas yang mengarah kepada pilihan untuk menerapkan
dan menolak inovasi
d. Implementation (Implementasi) terjadi bila individu (atau unit keputusan lainnya) menggunakan inovasi
e. Confirmation (Konfirmasi) terjadi bila individu (atau unit pembuatan keputusan lainnya) mencari dukungan atas keputusan inovasi yang sudah dibuat, akan tetapi
ia sendiri mungkin mencanangkan keputusan sebelumnya jika diarahkan terhadap
pesan-pesan yang menimbulkan konflik tentang inovasi tersebut.
Apabila penerimaan perilaku baru dan adopsi perilaku melalui proses seperti
ini, dimana didasari pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku
didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama
(Notoatmodjo, 2003).
2.7.1. Pengetahuan (Knowledge)
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan
manusia di peroleh melalui mata dan telinga.
Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk
terbentuknya tindakan seseorang (overt behavioral).
Pengetahuan yang tercakup di dalam domain kognitif mempunyai enam
tingkatan, yakni :
a. Tahu (Know) sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
b. Memahami (Comprehension) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar objek yang diketahui dan dapat mengintepretasikan
materi tersebut secara benar.
c. Aplikasi (Application) yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.
d. Analisis (Analysis) adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur
organisasi tersebut dan masih saling berkaitan antara yang satu dengan yang
e. Sintesis (Synthesis) adalah suatu kemampuan meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru
dalam arti telah mampu untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang
telah ada.
f. Evaluasi (Evaluation) bahwa seseorang tersebut telah mampu untuk melakukan justification atau penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoatmodjo, 2003).
2.7.2 Sikap (Attitude)
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang
terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya
kesesuaian reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.
Menurut Notoatmodjo (2005) yang mengutip pendapat Allport (1954),
menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai tiga komponen pokok, yaitu :
a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek .
b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.
c. Kecenderungan untuk bertindak.
Ketiga komponen diatas secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh.
Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan dan emosi
memegang peranan penting. Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari
berbagai tingkatan sikap, yakni :
b. Merespon (Responding) yaitu memberikan jawaban apabila di tanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi
dari sikap.
c. Menghargai (Valuing) mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga
(kecenderungan untuk bertindak).
d. Bertanggung jawab (Responsible) yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko adalah merupakan sikap yang
paling tinggi (Notoatmodjo, 2003).
Menurut Liliweri (2009), sikap manusia tersusun oleh 4 komponen utama, yaitu :
1. Kognitif
Aspek kognitif berisi apa yang diketahui mengenai suatu obyek, bagaimana
pengalaman anda tentang obyek tersebut, bagaimana pendapat atau pandangan
anda tentang obyek tersebut. Aspek kognitif berkaitan dengan kepercayaan kita,
teori, harapan, sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif
terhadap obyek tertentu.
2. Afektif
Afektif berisi apa yang anda rasakan mengenai suatu obyek, jadi komponen
afektif berisi emosi. Afeksi sebagai komponen afektif menunjukkan perasaan
respek atau perhatian kita terhadap obyek tertentu, seperti ketakutan, kesukaan
3. Konatif
Konatif berisi predisposisi anda untuk bertindak terhadap obyek. Jadi berisi
kecenderungan untuk bertindak (memutuskan) atau bertindak terhadap obyek,
atau mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap obyek.
4. Evaluatif
Evaluasi seringkali dipertimbangkan sebagai inti dari tiga komponen sikap
tersebut. Evaluasi dapat dibayangkan sebagai suatu rentangan menggambarkan
derajat sikap kita terhadap obyek mulai dari yang paling baik sampai yang paling
buruk. Ketika kita bicara tentang sikap yang positif dan negatif ke arah obyek,
kita melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan fungsi kognitif, afektif, dan
perilaku terhadap obyek. Pada umumnya, evaluasi dikeluarkan dari memori yang
sudah tersimpan dalam otak kita (kognitif).
2.8. Remaja
2.8.1. Definisi Remaja
Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari kata Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescence memiliki arti yang luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 2007).
Menurut Soetjiningsih (2004), masa remaja merupakan masa peralihan antara
masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11
Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya
terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Dengan batasan usia berada pada
usia 11-24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2000).
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), remaja merupakan suatu
individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur
mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa kanak-kanak
menjadi dewasa dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan
menjadi relatif mandiri (Notoatmodjo, 2007).
Monks (1999) dalam Nasution (2007), menyatakan bahwa remaja adalah
individu yang berusia antara 12-20 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari
masa anak-anak ke masa dewasa, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal,
15-18 tahun masa remaja pertengahan dan 18-20 tahun masa remaja akhir.
Berdasarkan pembagian tersebut, proses remaja menuju kedewasaan disertai
dengan karakteristiknya, yaitu :
1) Remaja awal (12-15 tahun)
Pada tahap ini, remaja masih merasa heran terhadap perubahan-perubahan
yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai
perubahan-perubahan tersebut. Mereka mulai mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat
tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis. Kepekaan yang
berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya pengendalian terhadap ego dan
2) Remaja madya (15-18 tahun)
Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ada
kecenderungan narsistik yaitu mencintai diri sendiri, dengan cara lebih menyukai
teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Pada tahap
ini, remaja berada dalam kondisi kebingungan karena masih ragu harus memilih
yang mana, peka atau peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis dan
sebagainya.
3) Remaja akhir (18-20 tahun)
Tahap ini adalah masa mendekati kedewasaan yang ditandai dengan
pencapaian :
a) Minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan
mendapatkan pengalaman-pengalaman baru.
c) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan
keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
e) Tumbuh dinding pemisah antara diri sendiri dengan masyarakat umum.
2.8.2. Ciri-ciri Masa Remaja
Hurlock (2003) mengemukakan berbagai ciri remaja adalah sebagai berikut :
a) Masa remaja adalah masa peralihan
Yaitu peralihan dari satu tahap perkembangan ke perkembangan berikutnya
juga bukan seorang dewasa. Masa ini merupakan masa yang sangat strategis,
karena memberi waktu kepada remaja untuk membentuk gaya hidup dan
menentukan pola perilaku, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang sesuai dengan yang
diinginkannya.
b) Masa remaja adalah masa terjadi perubahan
Sejak awal remaja, perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku
dan sikap juga berkembang. Ada empat perubahan besar yang terjadi pada
remaja, yaitu perubahan emosi, peran, minat, pola perilaku (perubahan sikap
menjadi bercabang dua yang saling bertentangan (seperti mencintai dan
membenci sekaligus terhadap orang yang sama).
c) Masa remaja adalah masa yang penuh masalah.
Masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Hal ini
terjadi karena remaja belum terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa
meminta bantuan orang lain. Akibatnya, terkadang terjadi penyelesaian yang
tidak sesuai dengan yang diharapkan.
d) Masa remaja adalah masa mencari identitas.
Identitas diri yang dicari remaja adalah berupa kejelasan siapa dirinya dan apa
peran dirinya di masyarakat. Remaja tidak puas dirinya sama dengan
kebanyakan orang, ia ingin memperlihatkan dirinya sebagai individu,
sementara pada saat yang sama ia ingin mempertahankan dirinya terhadap
e) Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan.
Ada stigma dari masyarakat bahwa remaja adalah anak yang tidak rapi, tidak
dapat dipercaya, cenderung berperilaku merusak, sehingga menyebabkan
orang dewasa harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja. Stigma
ini akan membuat masa peralihan remaja ke dewasa menjadi sulit, karena
orang tua yang memiliki pandangan seperti ini akan selalu mencurigai remaja,
sehingga menimbulkan pertentangan dan membuat jarak antara orang tua
dengan remaja.
f) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis.
Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca matanya sendiri, baik
dalam melihat dirinya maupun melihat orang lain, mereka belum melihat apa
adanya, tetapi menginginkan sebagaimana yang ia harapkan.
g) Masa remaja adalah ambang masa dewasa.
Dengan berlalunya usia belasan, remaja yang semakin matang berkembang
dan berusaha memberi kesan sebagai seseorang yang hampir dewasa. Ia akan
memusatkan dirinya pada perilaku yang dihubungkan dengan status orang
dewasa, misalnya dalam berpakaian dan bertindak.
2.8.3. Perkembangan Masa Remaja
Menurut Ahmadi (1998), berbagai perkembangan pada masa remaja dapat
a) Perkembangan fisik
Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja merupakan gejala utama dari
perkembangan remaja karena ada hubungannya dengan aspek lain dari
perkembangan remaja.
b) Perkembangan kognitif
Perkembangan kognitif remaja dalam tahap formal operasional yaitu saat
pemikirannya menjadi semakin rasional. Pada tahap ini remaja mulai
mengembangkan pemikiran yang bersifat abstrak, hipotesis serta mampu
melihat berbagai kemungkinan dalam pemecahan masalah yang dihadapi serta
mulai memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya.
c) Perkembangan kepribadian
Pada tahap ini terjadi suatu konflik diri. Dimasa ini remaja sedang dalam
proses pembentukan identitas diri yang merupakan masa dimana individu
berharap dapat mengatakan siapa dirinya saat ini dan apa yang
dikehendakinya di masa mendatang. Ciri-ciri yang mencolok dari tahap ini
adalah adanya sublimasi (usaha pengalihan hasrat yang bersifat primitif ke
tingkah laku yang dapat diterima oleh norma masyarakat) melalui ekspresi
libido, yaitu dengan cara jatuh cinta dengan lawan jenis.
d) Perkembangan emosi
Suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan
fisik dan kelenjar. Pada masa perkembangan emosi terjadi ketidakstabilan
sifatnya, seperti sinis terhadap orang lain maupun terhadap kejadian tertentu,
benci, perasaan cinta, apatis, peduli dan sebagainya.
e) Perkembangan sosial
Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang
berhubungan dengan penyesuaian sosial. Upaya yang terpenting dan tersulit
adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya,
perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai
baru dalam seleksi persahabatan ataupun dukungan dan penolakan sosial serta
seleksi pemimpin. Karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama
teman-teman sebaya sebagai suatu kelompok, maka pengaruh teman sebaya
lebih besar daripada pengaruh keluarga (Ahmadi, 1998).
2.9. HIV/AIDS
2.9.1. Pengertian HIV/AIDS
Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyebab AIDS (Acquired Immuno Deficiency Sindrome). Virus ini dapat merusak sel-sel system imun yang menyebabkan kekebalan tubuh hilang, sehingga sangat mudah terserang
berbagai jenis penyakit (Djoerban, 2001).
AIDS (Acquired Immuno Deficiency Sindrome) merupakan kumpulan gejala penyakit dan sebagai fase terminal (akhir) yang disebabkan oleh virus HIV yang
mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh
terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain (Notoatmodjo,
2007).
AIDS disebabkan oleh adanya virus HIV. Virus HIV ini hidup didalam 4
(empat) cairan tubuh manusia, yaitu : cairan darah, cairan sperma, cairan vagina dan
Air Susu Ibu (ASI). Virus ini tidak dapat hidup dalam cairan tubuh lainnya, seperti
ludah (air liur), air mata maupun keringat, sehingga penularannya hanya lewat empat
cairan tubuh tersebut (FK UI, 2005).
Penularan virus ini adalah melalui hubungan seksual, suntikan jarum yang
terkontaminasi HIV, transfusi darah atau komponen darah terkontaminasi HIV, ibu
yang hamil ke bayi yang dikandungnya dan sperma terinfeksi HIV yang disimpan di
bank sperma, yang dimaksud hubungan seksual adalah hubungan seksual dengan
jenis (lelaki-perempuan), hubungan homoseksual (lelaki-lelaki) atau biseksual, yaitu
lelaki kadang-kadang berhubungan seksual dengan lelaki dan kadang-kadang juga
dengan wanita (Djoerban, 2001).
AIDS adalah penyakit yang fatal, sementara vaksin atau obat untuk
pengobatannya sampai saat ini belum ditemukan walaupun melalui berbagai
penelitian dan penemuan para ahli sudah banyak yang mencoba membuat obat atau
vaksin AIDS namun belum ada seperti yang diharapkan, sehingga tidak
mengherankan bila sampai saat ini sudah banyak penderita AIDS yang meninggal.
Obat yang ada sekarang ini hanya bermanfaat mengurangi penderitaan, memperbaiki
kualitas hidup dan memperpanjang lama hidup penderita AIDS. Pembagian tingkat
Tingkat klinik 2 (Dini), (3) tingkat klinik 3 (Menengah) dan (4) Tingkat klinik 4
(Lanjut). Ada pula yang membagi gambaran klinik AIDS dalam 3 kelompok yaitu :
(1) Akibat langsung HIV, (2) Gejala infeksi Oportunistik dan (3) kanker (Djoerban,
2001).
2.9.2. Etiologi AIDS
Penyebab AIDS adalah sejenis virus yang tergolong Retrovirus yang disebut
Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus ini pertama kali diisolasi oleh Montagnier dan kawan-kawan di Prancis pada tahun 1983 dengan nama
Lymphadenopathy Associated Virus (LAV), sedangkan Gallo di Amerika Serikat pada tahun 1984 mengisolasi (HIV) III. Kemudian atas kesepakatan internasional
pada tahun 1986 nama virus dirubah menjadi HIV (FK UI, 2005).
Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis Retrovirus RNA. Dalam bentuknya yang asli merupakan partikel yang inert, tidak dapat berkembang atau
melukai sampai ia masuk ke sel target. Sel target virus ini terutama sel Lymfosit T
(sel-sel darah putih yang merupakan sistem kekebalan tubuh yang bertugas
menangkal infeksi), karena ia mempunyai reseptor untuk virus HIV yang disebut
CD-4. Didalam sel Lymfosit T, virus dapat berkembang dan seperti retrovirus yang lain,
dapat tetap hidup lama dalam sel dengan keadaan inaktif. Walaupun demikian virus
dalam tubuh pengidap HIV selalu dianggap infectious yang setiap saat dapat aktif dan dapat ditularkan selama hidup penderita tersebut. Kini diketahui virus ini juga dapat
langsung merusak sel-sel tubuh lainnya, seperti yang terdapat di otak, saluran
2.9.3. Gejala dan Tanda AIDS
Gejala seseorang telah terkena HIV dapat diketahui dengan dilakukannya tes
darah Elisa-1dan Elisa-2 dan bila positif harus dikonfirmasi dengan tes Western Blot.
Gejala dan tanda seseorang terinfeksi AIDS antara lain : (1) Rasa lelah yang
berkepanjangan, (2) Sesak nafas dan batuk yang berkepanjangan, (3) Pembesaran
kelenjar (sekitar leher dan lipatan paha), (4) tanpa sebab sering demam lebih dari
380C disertai keringat tanpa sebab yang jelas di malam hari, (5) Berat badan menurun
secara mencolok, (6) Diare yang berkepanjangan dan (7) Bercak-bercak merah
kebiruan yang timbul pada kulit (Djoerban, 2001).
Untuk keperluan surveilans epidemiologi seseorang yang telah dewasa (>12
tahun) dianggap penderita AIDS apabila menunjukkan tes HIV positif dengan strategi
yang sesuai dan sekurang-kurangnya didapatkan 2 gejala mayor dan 1 gejala minor,
dan gejala-gejala ini bukan disebabkan oleh keadaan-keadaan lain tidak berkaitan
dengan infeksi HIV (Depkes, 2005).
Beberapa gejala mayor penyakit AIDS adalah penurunan kesadaran dan
gangguan neurologis serta dementia atau HIV ensefalopati, demam berkepanjangan
lebih dari 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, dan berat badan
menurun lebih dari 10 % dalam 1 bulan
Untuk gejala minor penyakit AIDS ditandai dengan infeksi jamur berulang
pada alat kelamin wanita, limadenopati generalisata, herpes simpleks kronis
herpes zoster multisegmental dan atau berulang serta kandidiasis orofaringeal
(Djoerban, 2001).
Seorang anak (<12 tahun) dianggap penderita AIDS bila umur anak tersebut
dari 18 bulan, ditemukan 2 gejala mayor dan 2 gejala minor, dan gejala-gejala ini
bukan disebabkan oleh keadaan-keadaan lain yang tidak berkaitan dengan infeksi
HIV dan untuk anak umur kurang dari 18 bulan apabila ditemukan 2 gejala mayor
dan 2 gejala minor dengan ibu yang HIV (+) (Depkes, 2005).
2.9.4. Penyebaran HIV dan Cara Penularan AIDS
Menurut (Djoerban, 2001), penularan AIDS dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu :
1. Transmisi seksual
Penularan melalui hubungan seksual baik Homoseksual maupun
Heteroseksual merupakan penularan infeksi HIV yang paling sering terjadi.
Penularan ini berhubungan dengan semen dan cairan vagina atau servik. Infeksi
dapat ditularkan dari setiap pengidap infeksi HIV kepada pasangan seksnya.
Risiko penularan HIV tergantung pada pemilihan pasangan seksual, jumlah
pasangan seksual, frekuensi melakukan hubungan seksual dan jenis hubungan
seksualnya
a. Homoseksual
Cara hubungan seksual ini merupakan perilaku seksual dengan risiko tinggi
bagi penularan HIV, khususnya bagi mitra seksual yang pasif menerima ejakulasi
yang sangat tipis dan mudah sekali mengalami pertukaran pada saat berhubungan
dan sering menyebabkan luka-luka kecil pada selaput lendir rektum.
b. Heteroseksual
Penularan heteroseksual dapat terjadi dari laki-laki ke wanita dan sebaliknya.
Menurut beberapa pakar, penularan dari laki-laki ke wanita lebih besar
kemungkinannya dari pada sebaliknya. Kontak seksual oral mengandung risiko
yang rendah.
2. Transmisi Non Seksual
a. Transmisi Parenteral
Yaitu akibat penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya (alat tindik, tato)
yang telah terkontaminasi, misalnya pada penyalahgunaan obat dengan suntikan
yang menggunakan jarum suntik yang tercemar secara bersama-sama. Disamping
dapat juga terjadi melaui jarum suntik yang dipakai oleh petugas kesehatan tanpa
disterilkan terlebih dahulu.
b. Darah/Produk Darah
Transfusi darah dari donor dengan HIV positif mengandung risiko yang
sangat tinggi
c. Transmisi Transplasental
Penularan dari ibu yang mengandung HIV positif ke anak mempunyai risiko
sebesar 50%. Penularan dapat terjadi sewaktu hamil, melahirkan dan sewaktu
menyusui. Penularan melalui air susu ibu termasuk penularan dengan risiko
AIDS tidak menular, karena bersentuhan dengan penderita HIV, berjabat
tangan dengan penderita HIV, hidup serumah dengan penderita HIV (tidak
mengadakan hubungan seksual), penderita HIV bersin atau batuk di dekat kita,
melalui alat makan atau minum, gigitan nyamuk atau serangga lainnya,
bersama-sama berenang di kolam dengan penderita HIV, bersentuhan dengan pakaian atau
barang lain dari bekas penderita HIV, berciuman di pipi dengan penderita HIV
(Depkes, 2005).
2.9.5. Pencegahan Penularan Infeksi AIDS
Menurut Depkes (2005), upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah :
1. Pencegahan penularan melalui jalur non seksual
a. Transfusi darah, pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan uji
skrining kepada pendonor darah sebelum ditransfusikan kepada orang lain.
b. Pencegahan penularan melalui jarum suntik oleh dokter atau paramedis dapat
dicegah dengan menggunakan jarum suntik sekali pakai tidak secara
bergantian, baik menggunakan pisau cukur dan sikat gigi, menghentikan
penyalahgunaan narkotik.
c. Produk darah dapat dicegah dengan inaktivasi virus pada konsentrat faktor
pembekuan darah.
2. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan menganjurkan kepada ibu yang
menderita AIDS untuk tidak memilih melahirkan anak (hamil). Selain itu perlu
edukasi) kepada masyarakat terutama masyarakat yang berisiko tinggi seperti remaja.
Misalnya mengurangi pasangan seksual, monogami, menghindari hubungan seksual
dengan WTS, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita AIDS dan
meningkatkan penggunaan kondom. Masyarakat yang berisiko rendah juga perlu
dilibatkan untuk mencegah penyebaran infeksi HIV dengan menanamkan rasa
keimanan serta kesetiaan pada pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan dalam
berhubungan seksual (Depkes, 2005).
2.9.6. Upaya Penanggulangan HIV/AIDS
Prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDS :
1. Setiap upaya penanggulangan HIV/AIDS harus mencerminkan nilai-nilai
sosio-budaya masyarakat setempat.
2. Setiap kegiatan diharapkan untuk mempertahankan dan memperkukuh ketahanan
dan kesejahteraan keluarga serta sistem dukungan sosial yang mengakar dalam
masyarakat.
3. Pencegahan penularan HIV/AIDS diarahkan kepada upaya pendidikan dan
penyuluhan untuk memantapkan perilaku.
4. Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang benar guna melindungi diri
sendiri dan orang lain terhadap infeksi HIV/AIDS.
5. Setiap kebijakan, pelayanan dan kegiatan harus tetap menghormati harkat dan
martabat individu.
6. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan
sesudah pemeriksaan harus diberikan konseling yang memadai dan hasil
pemeriksaan wajib dirahasiakan.
7. Setiap pemberi layanan berkewajiban memberikan pelayanan tanpa diskriminasi
pada pengidap HIV/AIDS (Depkes, 2005).
a. Cakupan Program
Dalam lingkup program upaya penanggulangan HIV/AIDS lebih difokuskan
kepada :
1. Peningkatan kemampuan institusi baik kabupaten/kota maupun
lembaga-lembaga non pemerintah dalam hal penanggulangan HIV/AIDS
2. Penyampaian informasi mengenai HIV/AIDS serta upaya-upaya
penanggulangannya kepada masyarakat (KIE)
3. Advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya
penanggulangan HIV/AIDS
4. Peningkatan kerjasama antar lembaga baik lembaga-lembaga pemerintah
maupun non pemerintah (Depkes, 2005).
b. Sasaran Program
Secara umum sasaran program penanggulangan HIV/AIDS adalah :
1. Masyarakat
Masyarakat yang menjadi sasaran program kegiatan penanggulangan
HIV/AIDS dibedakan berdasarkan risiko yaitu :
a. Kelompok risiko tinggi mencakup pekerja seks komersil, pengguna narkotika
hiburan (pub, diskotik, dll), mitra pekerja seks komersil, supir jarak jauh,
nelayan dan narapidana.
b. Kelompok risiko rendah yang mencakup remaja/generasi muda, pasangan usia
subur, calon pasangan suami istri, TKW, karyawan (pegawai Negeri dan
Swasta) dan Aparat Keamanan (TNI, Polri).
c. Sektor Pemerintahan
Dalam hal ini kegiatan lebih ditekankan pada koordinasi program sehingga
dapat terjadi sinergisme dari program-program yang dijalankan, diharapkan
program-program pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS
dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak dalam hal yang sama
d. Penentu Kebijakan
Dalam hal ini kegiatan lebih ditekankan pada advokasi. Diharapkan melalui
kegiatan-kegiatan ini, upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS mendapat
dukungan politis (Depkes, 2005).
2.10. Landasan Teori
Penyakit AIDS belum banyak dikenal baik, sehingga hal ini semakin memicu
penambahan jumlah penderitanya. HIV/AIDS merupakan virus dan penyakit yang
dapat menyerang siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, status dan tingkat sosial.
Namun ada kecenderungan besar penyakit ini menimpa kelompok masyarakat yang
energik dan produktif dalam beraktifitas dimana termasuk di dalamnya adalah remaja.
relatif bebas sehingga memungkinkannya melakukan hubungan seks pranikah dimana
cara penularan HIV/AIDS paling sering adalah melalui hubungan seksual yang tidak
aman (K4health, 2012).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah termasuk melakukan upaya
promosi kesehatan. Promosi kesehatan yang telah dilakukan ternyata belum mampu
menurunkan angka temuan kasus. Promosi kesehatan pada hakekatnya adalah usaha
menyampaikan pesan kesehatan pada masyarakat, kelompok atau individu, dengan
harapan masyarakat, kelompok dan individu dapat memperoleh pengetahuan,
akhirnya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku (Notoatmodjo,
2005).
Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1983)
merupakan suatu landasan yang menekankan pentingnya saluran komunikasi dan
penyebarserapan ide-ide melalui peran agen-agen perubahan dalam lingkungan sosial.
Secara relatif, tetangga, petugas kesehatan atau agen perubahan yang lain ikut
membantu menghasilkan perubahan perilaku dengan cara-cara tertentu, misalnya
dengan cara meningkatkan kebutuhan akan perubahan, membangun hubungan
interpersonal yang diperlukan, mengidentifikasi masalah-masalah dan penyebabnya,
mendapatkan sasaran dan jalan keluar yang potensial serta memotivasi seseorang
supaya menerima dan memelihara aksi.
Teori difusi inovasi juga mencakup jenis-jenis gagasan tertentu yang perlu
diadopsikan kepada anggota-anggota dari suatu sistem sosial karena mereka sangat
Sedangkan karakteritik sukses inovasi terjadi kalau para anggota sistem sosial itu
menerima inovasi tersebut (Liliweri, 2009). Penelitian ini dilakukan untuk melihat
efektivitas saluran komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah
tentang HIV/AIDS terhadap pengetahuan dan sikap remaja.
2.11. Kerangka Konsep
Berdasarkan tujuan penelitian, maka kerangka konsep dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
PRE TEST POST TEST
Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian
Konsep utama penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas promosi
kesehatan menggunakan metode ceramah tentang HIV/AIDS terhadap pengetahuan