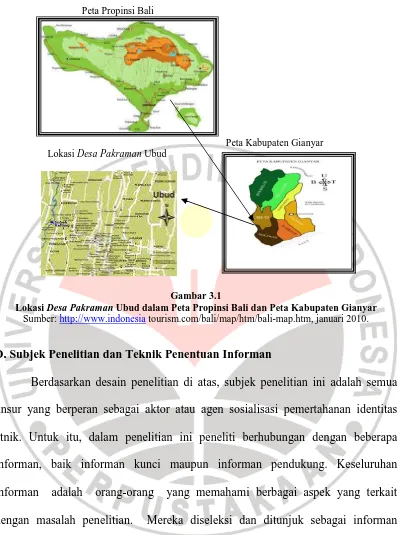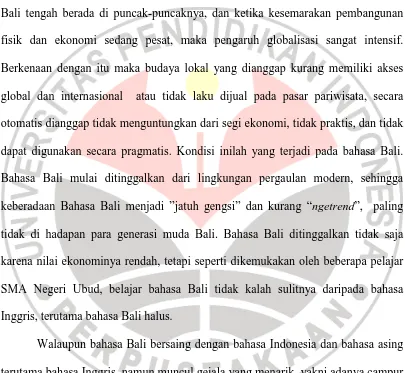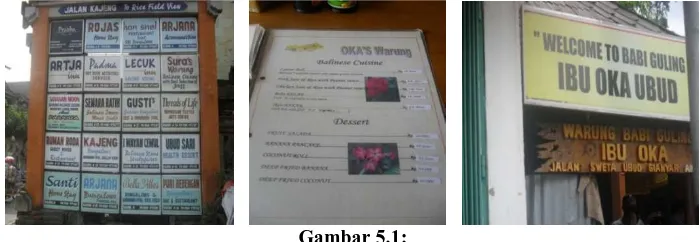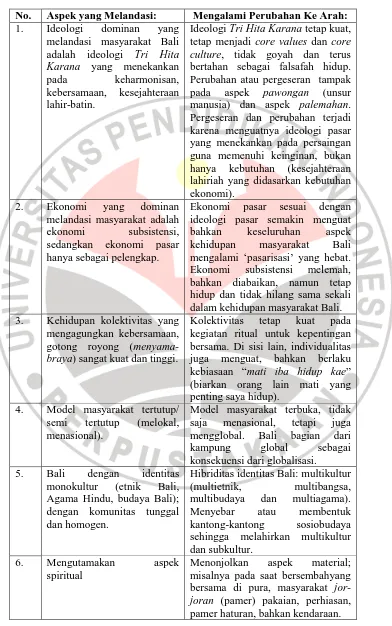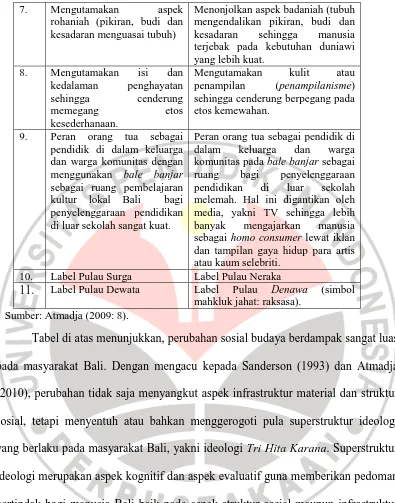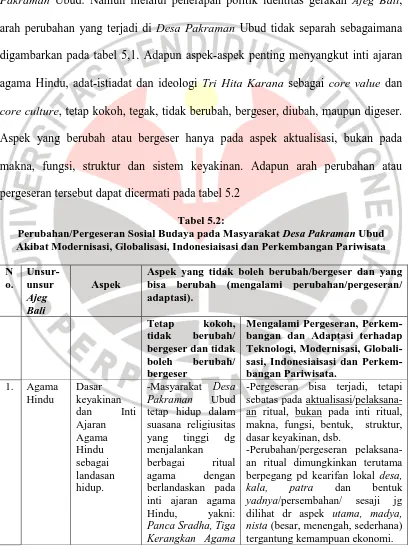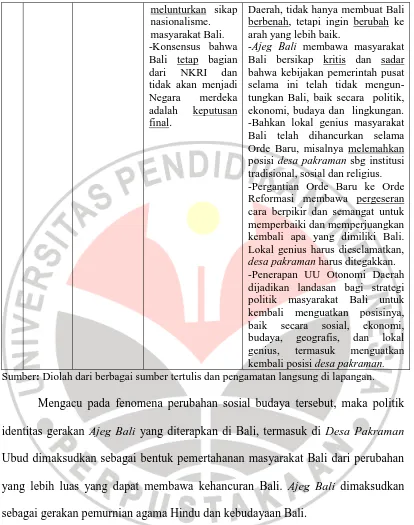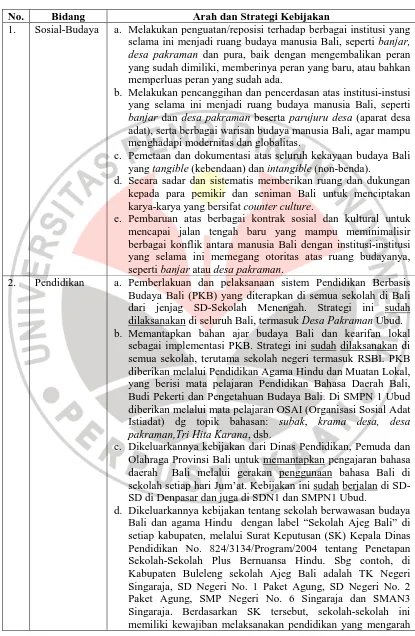xiv
b. Keragaman dalam Perspektif Multikulturalisme ... 104
4. Gerakan Ajeg Bali sebagai Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ... 107
a. Dasar-dasar Konseptual IPS ... 107
b. Ajeg Bali sebagai Proses Pendidikan IPS ... 110
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan... 115
C. Posisi Teoritik Penelitian ... 121
D. Kerangka Berpikir ... 123
BAB III METODE PENELITIAN ... 127
A. Desain Penelitian... 127
B. Pendekatan Penelitian ... 127
C. Penentuan Lokasi Penelitian ... 128
D. Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Informan ... 130
E. Teknik Pengumpulan Data……… ... 131
F. Instrument Penelitian ... 134
G. Teknik Verifikasi Data ... 135
H. Teknik Analisis Data ... 137
I. Prosedur dan Tahap-tahap Penelitian ... 138
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA PAKRAMAN UBUD ... 140
A. Ubud sebagai Desa Dinas dan Desa Pakraman ... 140
1. Latar Belakang Sejarah Desa Ubud ... 140
2. Sistem Pemerintahan Desa Ubud ... 146
B. Penjabaran Ideologi Tri Hita Karana sebagai Landasan Desa Pakraman Ubud 157 1. Penjabaran Berdasarkan Aspek Palemahan ... 160
a. Lokasi, Batas, dan Tataguna Palemahan Ubud ... 161
b. Kedaan Geografis dan Potensi Palemahan ... 173
2. Penjabaran Berdasarkan Aspek Pawongan ... 178
a. Keadaan Demografis/Kependudukan ... 179
b. Ikatan Kekerabatan dan Organisasi Tradisional ... 189
c. Hubungan Antar Krama Desa Pakraman ... 195
3. Penjabaran Berdasarkan Aspek Parhyangan ... 197
BAB V LATAR BELAKANG PEMERTAHANAN IDENTITAS ETNIK MELALUI POLITIK IDENTITAS GERAKAN AJEG BALI DI DESA PAKRAMAN UBUD ... 203
xv
1. Karakteristik Politik Kebudayaan Orde Baru ... 209
2. Politik Kebudayaan Memarjinalkan Desa Pakraman... 217
3. Politik Kebudayaan Memarjinalkan Bahasa dan Aksara Bali ... 221
B. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan Kebudayaan Bali dari Modernisasi ... 224
C. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan Kebudayaan Bali dari Globalisasi ... 232
D. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan dan Kelanggengan Ekonomi ... 240
E. Ajeg Bali sebagai Pemertahanan Kebudayaan Bali dari Kehadiran Pendatang 251 F. Arah Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Desa Pakraman Ubud ... 259
BAB VI POLA PENYELENGGARAAN PEMERTAHANAN IDENTITAS ETNIK MELALUI POLITIK IDENTITAS GERAKAN AJEG BALI DI DESA PAKRAMAN UBUD ... 272
A. Pemertahanan Identitas Etnik melalui PKB pada Lembaga Pendidikan Informal... 273
B. Pemertahanan Identitas Etnik Melalui PKB pada Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah) ... 339
1. PKB melalui Pendidikan Agama Hindu ... 340
2. PKB melalui Pengajaran Muatan Lokal ... 344
a. PKB melalui Muatan Lokal Bahasa Daerah Bali ... 346
b. PKB melalui Muatan Lokal Budaya Bali ... 350
C. Pemertahanan Identitas Etnik Melalui Media (Pendidikan Nonformal) ... 356
1. Implemtasi Ajeg Bali melalui Media Cetak Bali Post ... 357
2. Implementasi Ajeg Bali melalui Media Televisi Bali TV ... 361
VII IMPLIKASI PEMERTAHANAN IDENTITAS ETNIK MELALUI POLITIK IDENTITAS GERAKAN AJEG BALI PADA KEHIDUPAN MULTIKULTURAL DI DESA PAKRAMAN UBUD ... 365
A. Penguatan Desa Pakraman sebagai Basis Budaya Bali... 365
1. Reposisi Desa Pakraman: Bercorak Dominatif dan Hegemonik ... 367
2. Penguatan Eksistansi Pecalang sebagai Benteng Desa Pakraman ... 371
B. Hubungan Antaretnik di Desa Pakraman Ubud ... 376
1. Respon terhadap Kedatangan Pendatang (Etnik NonBali) ... 377
2. Gejala Sosial pada Hubungan Antaretnik di Desa Pakraman Ubud ... 382
a. Hubungan Mayoritas-Minoritas ... 383
xvi
3. Proses Sosial dalam Hubungan Antaretnik di Desa Pakraman Ubud ... 389
a. Proses Sosial Disosiatif ... 389
b. Proses Sosial Asosiatif ... 392
VIII KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PERUMUSAN TEORI ... 397
A. Kesimpulan ... 397
B. Rekomendasi ... 400
C. Perumusan Teori ... 402
DAFTAR PUSTAKA ... 405
xvii
DAFTAR TABEL
No. Tabel Nama Tabel Halaman
2.1. Arah Perubahan Masyarakat Bali sebagai Akibat dari
Modernisasi, Indonesiaisasi dan Globalisasi ... 38 2.2. Makna yang Terkandung pada Konsep Mayoritas dan Minoritas 86 4.1. Luas Wilayah/Palemahan di Desa Pakraman Ubud ... 166 4.2. Tata Guna Wilayah Utama Palemahan Desa Pakraman Ubud
pada Zona 1 ... 168 4.3. Tata Guna PalemahanDesa Pakraman Ubud Pada Zona 2 ... 169 4.4. Tata Guna Palemahan Desa Pakraman Ubud Pada Zona 3 ... 169 4.5. Jumlah Subak, Tempekan Subak dan Pekaseh di Wilayah
Kelurahan Ubud ... 174 4.6. Jenis Tanaman yang Terdapat di Kelurahan Ubud ... 177 4.7. Keadaan Penduduk Desa Pakraman Ubud berdasarkan
Jumlah KK dan Jenis Kelamin ... 180 4.8. Komposisi Penduduk Desa Pakraman Ubud menurut
Kelompok Umur ... 181 4.9. Keadaan Penduduk Desa Pakraman Ubud menurut Tingkat
Pendidikan ... 182 4.10. Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Ubud ... 183 4.11. Keadaan Penduduk Desa Pakraman Ubud berdasarkan Mata
Pencaharian ... 185 4.12. Program Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Ubud dan
Desa Pakraman Ubud Tahun 2007-2008 ... 188 4.13. Nama-nama Sekaa Kesenian di Desa Pakraman Ubud ... 199 5.1. Arah Perubahan Masyarakat Bali sebagai Akibat dari
Modernisasi, Indonesianisasi dan Globalisasi ... 260 5.2. Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Desa Pakraman Ubud
Akibat Modernisasi, Globalisasi, Indonesianisasi dan Pariwisata 262 5.3. Arah dan Strategi Kebijakan Ajeg Bali ... 270 6.1. Keberadaan Geriya dan Sulinggih (Pedanda) di Kelurahan Ubud 333 6.2. Mata Pelajaran Muatan Lokal pada SD Negeri 1 Ubud,
SMP Negeri 1 Ubud dan SMA Negeri 1 Ubud ... 345 6.3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pengajaran
Muatan Lokal Mata Pelajaran Organisasi Sosial Adat Istiadat
xviii
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Nama Gambar Halaman
3.1. Peta Lokasi Desa Pakraman Ubud ... 130
4.1. Pusat Desa Pakraman dan Pemerintahan Lokal ... 162
4.2. Balai Banjar di Desa Pakraman Ubud ... 163
4.3. Tata Palemahan pada Pemukiman Penduduk ... 171
4.4. Setra (Kuburan) di Desa Pakraman Ubud ... 172
4.5. Sawah di Subak Juwuk Manis Desa Pakraman Ubud ... 175
4.6. Aktivitas Pendudk Berkaitan dengan Pariwisata ... 186
4.7. Pentas Sekaa di Desa Pakraman Ubud ... 194
4.8. Pura Kahyangan Tiga di Desa Pakraman Ubud ... 198
4.9. Pura-pura Umum di Desa Pakraman Ubud ... 199
410. Pura Fungsional di Desa Pakraman Ubud ... 200
4.11. Pura Keluarga di Desa Pakraman Ubud ... 201
5.1. Penggunaan Bahasa Campura di Desa Pakraman Ubud ... 232
5.2. Identitas Budaya/Etnik Desa Pakraman Ubud ... 239
6.1. Sanggah Kemulan Rong Tiga ... 274
6.2. Lambang Kelurahan Ubud ... 297
6.3. Kegiatan Sekaa Pesantian di Desa Pakraman Ubud ... 288
6.4. Palemahan Subak Juwuk Manis... 305
6.5. Pura Subak Juwuk Manis ... 317
6.6. Puri Ubud sebagai Arena Belajar Kesenian ... 322
6.7. Sulinggih Geriya Peling Baleran dan Peralatan Ritual ... 331
6.8. Suasana Sosial-Religius di SDN 1, SMPN1, SMAN 1 Ubud... 335
6.9. Penggunan Bahasa dan Aksara Bali di SMPN1 Ubud ... 343
6.10. Lomba Tari Jauk di SMAN 1 Ubud ... 350
6.11. Ekstrakulikuler Menyalin Aksara Bali di SMPN 1 Ubud ... 353
6.12. Ekstrakulikuler Mejejahitan di SDN 1 Ubud ... 354
6.13. Karya Lukis Bertema Filosofis Hindu di SMPN 1 Ubud ... 355
7.1. Pecalang di Desa Pakraman Ubud ... 375
7.2. Papan “Pemulung Dilarang Masuk” di Desa Pakraman Ubud ... 388
xix
No. Bagan Nama Bagan Halaman
2.1. Pemertahanan Budaya Bali Berbasis Agama Hindu Melalui
Berbagai Agen Pendidikan ... 57
2.2. Kerangka Berpikir: Latar Belakang Pemertahanan Identitas Etnik, Sosialisasi dan Ilmplikasinya bagi Hubungan Antaretnik pada Masyarakat Multikultur ... 123
3.1. Prosedur Kerja Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif ... 137
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Dinas (Kelurahan) Ubud ... 153
4.2. Struktur Kepengurusan Desa Pakraman Ubud ... 155
5.1. Politik Kebudayaan Orde Baru dalam Rangka Nasionalisasi ... 212
xx
Lampiran-Lampiran
01: Ijin Penelitian UPI
02: Ijin Penelitian Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali
03: Ijin Penelitian Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Gianyar
04: Kisi-kisi Panduan Penggalian Data di Lapngan
05: Pedoman Wawancara
06: Pedoman Observasi
1 BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang sangat populer,
tidak saja di Indonesia tetapi juga mancanegara. Citra dan identitas Bali sebagai
daerah tujuan wisata yang indah, agung, eksotis, lestari, dengan perilaku
masyarakatnya yang ramah dan bersahaja, ditopang oleh adat istiadat dan
budayanya yang mendasarkan pada prinsip keharmonisan dan keseimbangan
dengan bertumpu pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah hidup Tri Hita
Karana. Kedua ajaran ini saling berkaitan, di mana agama Hindu menjiwai
falsafah Tri Hita Karana, dan sebaliknya falsafah Tri Hita Karana mendasarkan
pada ajaran agama Hindu.
Pendukung kebudayaan Bali adalah masyarakat Bali, yang dikenal sebagai
etnik Bali atau orang Bali. Sebagai sebuah etnik, orang Bali memiliki ciri identitas
etnik yang melekat pada diri dan kelompoknya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
(2008: 3) mendefinisikan etnik Bali sebagai sekelompok manusia yang terikat oleh
kesadaran akan kesatuan kebudayaan, baik kebudayaan lokal Bali maupun
kebudayaan nasional. Rasa kesadaran akan kesatuan kebudayaan Bali ini diperkuat
oleh adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Bali, agama Hindu, dan kesatuan
perjalanan sejarah dan kebudayaanya. Keyakinan terhadap agama Hindu
melahirkan berbagai macam tradisi, adat, budaya, kesenian, dan lain sebagainya
yang memiliki karakteristik yang khas, yang merupakan perpaduan antara tradisi
dalam berbagai konsepsi, aktivitas sosial, maupun karya fisik orang Bali (Supatra
2006; Geriya, 2008).
Identitas etnik orang Bali juga tampak pada busana tradisional Bali dan
identitas ruang serta lingkungan tempat tinggal (Supatra, 2006: 88-89). Dalam
pengertian ruang dan tempat tinggal, persamaan-persamaan yang menjadi ciri
identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa)
dari suatu desa pakramanan (desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya,
yang termuat dalam Awig-awig Desa Pakraman (peraturan tertulis desa adat)
(Windia dan Sudantra, 2006; Sirtha, 2005). Disamping hidup sebagai krama desa
sebuah desa pakraman, seluruh masyarakat Bali juga terikat dalam
kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut dadia, yang jumlah anggotanya bervariasi dan
bertempat tinggal menyebar, tidak selalu pada satu teritorial tertentu. Geertz and
Geertz (1975) menyebutkan, bahwa dadia merupakan basis atau unit terkecil dari
kelompok masyarakat adat di Bali yang terdiri dari beberapa kuren (keluarga), dan
merupakan bagian dari desa pakraman. Mereka terikat oleh kesamaan wit (asal)
berdasarkan kesamaan leluhur, dan terikat pula oleh suatu tempat
persembahyangan bersama, yakni Pura Dadia (Windia dan Sudantra, 2006: 71).
Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga
mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah
hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan
keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang
Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi
dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi
3
pengetahuan, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya.
Pada akhirnya falsafah Tri Hita Karana ini menjadi ideologi dan core values (inti
ajaran) dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Ideologi dan core
values inilah yang kemudian menjadi landasan bagi standar peraturan yang
digunakan institusi-institusi utama, seperti kuren dan dadia, sekaa (organisasi
tradisional), subak (organisasi pengairan) dan desa pakramanan di Bali, dalam
mengevaluasi perilaku anggotanya.
Implikasi yang lebih luas dari adanya pandangan yang mengandung core
values tersebut adalah, unsur-unsur dalam struktur sosial yang membangun
masyarakat Bali senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tri Hita Karana sesuai
dengan lingkungan kehidupannya. Pada tataran individu, manusia Bali sebagai
bagian dari lingkungan dunia mikrokosmos, meyakni bahwa kehidupan manusia
merupakan wujud yang dinamis dari gerak hubungan unsur-unsur atman (jiwa),
prana (tenaga, kekuatan), dan sarira (unsur badan kasar) (Kaler, 1983: 13).
Sehubungan dengan itu, maka pranata-pranata sosial masyarakat Bali mulai dari
yang lebih luas sebagai pencerminan dari lingkungan makrokosmos, maupun unit
terkecil sebagai pencerminan lingkungan mikrokosmos, menerapkan pola yang
sama dalam menciptakan hubungan harmonis dari ketiga unsur di atas. Hal tersebut
melandasi pola aktivitas budaya sehari-hari, melalui peneguhan pelaksanaan pada
tiga aspek lingkungan hidup yakni, lingkungan spiritual (parhyangan), lingkungan
manusia (pawongan), dan lingkungan fisik (palemahan) (Gorda, 1996; Geriya,
2008; Parimartha, 2009).
Fenomena perubahan sosial budaya sebagai akibat dari modernisasi dan
keprihatinan berbagai elemen masyarakat di Bali. Berbagai elemen tersebut
menilai, Bali tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, bahkan “ancaman”.
Hal yang paling meresahkan adalah, adanya ketakutan akan terancamnya
eksistensi ideologi Tri Hita Karana, berikut agama Hindu dan kebudayaan Bali.
Globalisasi yang berintikan pada kapitalisme dan perdagangan bebas, diikuti oleh
masuknya modal asing, telah membawa Bali terseret pada mekanisme jejaring
ideologi pasar. Bali yang menurut istilah Nordholt (2005: xxix) adalah ”benteng
terbuka”, tidak kuasa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, bahkan jerat
ideologi pasar ini membawa Bali pada sebutan “MacDonaldisasi of Bali” atau
“Coca-Colanisasi of Bali” (Inside Indonesia, Desember 1994; Atmadja, 2010).
Sebutan ini merujuk pada maraknya perusahaan multinasional kelas dunia yang
berkembang di Bali seperti: Coca Cola, Mc Donald, KFC, Pizza Hut, dan
produk-produk lain yang sebagian besar berpusat di Amerika. Oleh karena itu, dalam
istilah lain, Bali juga dapat dikatakan telah mengalami gejala “Amerikanisasi” atau
“Westernisasi”.
Fenomena di atas memberi petunjuk, bahwa globalisasi dan modernisasi
adalah sebuah persoalan besar yang berpotensi membuat segala sesuatunya
berubah. Potensi terjadinya perubahan sosial budaya semakin menguat, sebagai
akibat dari perkembangan pariwisata yang telah mengarah pada komodifikasi.
Kemajuan dan perkembangan pariwisata juga memunculkan persoalan lain, yakni
berkenaan dengan etnik pendatang. Burhanuddin (2009) dan Sukarma (2009)
menunjukkan, kehadiran pendatang melahirkan konsep pemisahan dan pemilahan
5
(binary opposition). Kondisi ini turut membentuk karakter orang Bali yang penuh
dengan perasaan curiga, terlebih sikap itu dijustifikasi melalui simbol kultural.
Pada akhirnya, sikap tersebut memunculkan paham etnosentrisme.
Pendatang, sebagaimana disebutkan Degung Santikarma (Bali Post, 2004) sering
ditempatkan sebagai sumber masalah (trouble makers), yang tidak saja mengancam
sumber nafkah mereka, tetapi juga ditempatkan sebagai ancaman terhadap identitas
budaya mereka. Pendatang dianologikan sebagai perusak identitas, karena ia datang
dengan latar belakang adat, budaya, dan keyakinan yang berbeda; sedangkan
penduduk asli (etnik Bali) adalah penjaga tradisi dan kemurnian identitas.
Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa ancaman terhadap identitas enik Bali
juga berasal dari etnik-etnik lain yang bermigrasi ke Bali.
Berbagai persoalan di atas dikhawatirkan dapat berdampak pada perubahan
pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, dan budaya masyarakat Bali. Karakter
budaya lokal luntur, dikalahkan budaya barat maupun budaya luar yang masuk ke
Bali, dibawa oleh pendatang maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke
Bali. Apabila tidak segera diambil langkah-langkah penyelamatan, kondisi tersebut
dapat menggangu eksistensi ideologi Tri Hita Karana dan kekokohan agama
Hindu.
Sebagai tanggapan atas kekhawatiran tersebut, berbagai kalangan
masyarakat Bali memunculkan suatu wacana yang kemudian berkembang sebagai
sebuah gerakan politik identitas yang bertujuan mengembalikan Bali pada
identitasnya semula. Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan Ajeg Bali.
Kemunculan gerakan Ajeg Bali adalah jawaban terhadap dampak dari pencitraan
juga pada tataran global, yakni: pertama, citra Bali yang turistik; kedua, citra Bali
dengan identitas budaya yang tunggal dan homogen; dan ketiga adalah citra
tentang Bali dengan keajegan budayanya. Dalam citra yang ketiga ini, Bali
dibayangkan memiliki kultur dan tradisi yang senantiasa tegar (ajeg); citra budaya
Bali yang tegar inilah yang tereproduksi sampai saat ini melalui ikon Ajeg Bali
(Vikers, 1989; Picard, 1997; Dwipayana, 2005).
Menguatnya fenomena Ajeg Bali yang diiringi dengan penguatan identitas
kebalian orang Bali, yang diikuti oleh munculnya sikap etnosentris, melahirkan
faham Baliisme, dengan jargonnya “Bali adalah Hindu dan Hindu adalah Bali”
(Burhanuddin, 2009: 127). Faham ini antara lain mengukuhkan prasangka etnik
dan melahirkan sikap resistensi terhadap nilai-nilai luar yang masuk ke Bali. Dalam
konteks ini, pendatang dari luar Bali yang non-Bali dan non-Hindu “tercurigai”
sebagai ancaman. Kondisi ini semakin nyata terutama setelah peristiwa Bom Bali I
dan II, yang meluluh-lantakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali yang
berbasis pada pariwisata. Kehancuran basis ekonomi ini berimplikasi luas dan
kompleks pada komponen struktur sosial dan superstuktur ideologi masyarakat
Bali. Pelaku bom Bali adalah orang luar Bali yang kebetulan beragama Islam.
Fakta ini kemudian menimbulkan pemaknaan yang “hipergeneralisasi”, tercermin
pada penyamaan bahwa Islam identik dengan kekerasan, dan bahkan identik
dengan terorisme. Lebih jauh fakta ini juga menggangu hubungan antara umat
Hindu dan Islam di Bali yang secara historis sangat baik dan harmonis, tercermin
dari penggunaan idiom “Nyama Bali”- “Nyama Selam”.
Pada akhirnya, Ajeg Bali menyerap seluruh wacana pengetahuan dan
7
adat, media massa, sampai akademisi memberi pengakuan dan persetujuan moral
intelektual pada kata-kata ini. Mengacu pada gagasan para pakar yang mengkaji
tentang Ajeg Bali, misalnya, Suryawan (2009), Sirtha (2005), Subagiasta (2005),
Wiana (2005), Wibawa (2005), Titib (2005), Nordholt (2006), Atmadja (2010), dan
lain-lain, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Ajeg Bali pada dasarnya
merupakan politik identitas yang bertumpu pada cita-cita mempertahankan
kebudayaan Bali yang berbasisikan Agama Hindu. Gerakan ini merupakan
resistensi terhadap kondisi kebudayaan Bali yang tidak lagi ajeg atau miring
sebagai akibat dari adanya globalisasi. Kondisi ini harus dikembalikan agar kondisi
yang tidak ajeg menjadi ajeg.
Ajeg Bali sebagai gerakan politik identitas telah memenuhi berbagai aspek
kehidupan masyarakat Bali baik sosial-religius, budaya, politik, ekonomi, bahkan
pendidikan. Untuk itu diperlukan ruang gerak, wadah atau institusi sebagai media
sosialisasi dan sarana implementasinya. Salah satu institusi yang paling penting
dan menjadi basisnya adalah desa pakraman sebagai institusi sosial-kultural
berlandaskan agama Hindu dan ideologi Tri Hita Karana. Sebagai kesatuan hukum
masyarakat adat di Bali, desa pakraman mempunyai kesatuan tradisi dan tata
krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, yang
diwujudkan dalam ikatan Tri Kahyangan Desa (tiga tempat suci/parhyangan),
mempunyai wilayah, dan harta kekayaan sendiri, serta berhak untuk megurus
rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Th. 2001).
Desa Pakraman Ubud merupakan salah satu desa pakraman di Ubud,
Gianyar, Bali yang menerapkan politik identitas gerakan Ajeg Bali sebagai upaya
dalam konteks menjaga kemurnian budaya Bali, agama Hindu, ideologi Tri Hita
Karana, maupun dalam konteks menjaga identitas pariwisatanya yang bertumpu
pada pariwisata budaya. Hal ini penting, mengingat kehidupan sosial ekonomi
masyarakat Desa Pakraman Ubud sebagian besar bertumpu pada sektor pariwisata.
Desa Pakraman Ubud sebagai salah satu desa di Kawasan Pariwisata Ubud
menampilkan gejala yang amat menarik. Jika banyak pengamat melihat bahwa
pariwisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi adalah faktor
penting yang menyebabkan perubahan secara drastik pada sistem sosiobudaya
masyarakat Bali, ternyata apa yang terjadi di Desa Pakraman Ubud menunjukkan
gejala yang sebaliknya. Desa Pakraman Ubud tetap bisa mempertahankan
kebudayaan Bali. Padahal dilihat dari Sejarah Keperiwisataan Bali, seperti
dikemukakn Picard (2005) dan Atmadja (2009), pengenalan Desa Pakraman Ubud
dan sekitarnya dengan pariwisata bukan hal yang baru. Kawasan ini mulai
dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata (DTW) pada tahun 1920-an. Kondisi
ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial yang amat intensif dan berlangsung
secara terus-menerus antara wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal dengan
masyarakat setempat. Bersamaan dengan itu Ubud tidak saja menjadi DTW yang
sangat terkenal, tetapi juga sebagai daerah hunian wisata. Dengan adanya
kenyataan ini tidak mengherankan jika Atmadja, Atmadja dan Widiastuti (2009)
menyebut Desa Pakraman Ubud sebagai Kampung Global di Bali. Label ini
berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa wisatawan yang berkunjung dan
atau menetap di Desa Pakraman Ubud berasal dari berbagai negara. Selain
wisatawan, banyak pula etnik pendatang dari luar Bali yang bekerja dan menetap di
9
mereka, sehingga Desa Pakraman Ubud sebagai Kampung Global, sekaligus juga
berbudaya global.
Walaupun Desa Pakraman Ubud berkembang menjadi Kampung Global
dan bercorak multikultur bahkan bisa pula disebut multietnik, namun warga Desa
Pakraman Ubud masih tetap bisa mempertahakan identitas kebudayaannya, yakni
kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali yang mereka kembangkan, memang tidak lagi
bersifat tradisionalis, melainkan bercorak post-tradisionalis. Artinya, warga Desa
Pakraman Ubud memang telah melewati masa kebudayaan tradisional, namun
bukan meninggalkannya, melainkan membentuk suatu pola campuran yang
harmonis antara kebudayaan tradisional Bali dan kebudayaan modern. Kondisi ini
menarik dikaji, terutama berkaitan dengan latar belakang dan motif atau alasan
maknawi yang menyebabkan mereka mempertahankan identitas kebudayaannya.
Dalam rangka menerapkan atau mengimplentasikan politik identitas
gerakan Ajeg Bali, Desa Pakraman Ubud memerlukan media sebagai agen
sosialisasi. Hal ini mengingat bahwa kebudayaan menyatu dengan masyarakat dan
kebudayaan adalah milik masyarakat (Atmadja, 2010, 2011; Koentjaraningrat,
1982; Keesing (1992). Namun kesatuan antara masyarakat dan kebudayaan tidak
terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan proses pendidikan, yang di
dalamnya melibatkan proses enkultulrasi, sosialisasi, maupun ideologisasi.
Pendidikan membutuhkan agen pendidikan atau agen sosialisasi. Untuk itu,
masyarakat Bali termasuk juga masyarakat Desa Pakraman Ubud mengenal
berbagai agen sosialisasi atau lembaga pendidikan tradisional yang lazim pula
Agen sosialisasi tradisional tersebut di dalamnya mencakup kuren
(keluarga batih), dadia (klen kecil patrilineal), desa pakraman (komunitas berbasis
adat dan agama Hindu), desa dinas (desa administrasi), subak (organisasi
pertanian) dan sekaa (pekumpulan sukarela atas dasar kepentingan) (Geertz dan
Geertz, 1975; Atmadja, 1998, 2010b). Agen-agen sosialisasi ini memainkan peran
penting dalam menjaga kelanggengan identitas etnik Bali melalui sistem
pendidikan yang lazim disebut pendidikan informal.
Dengan masuknya modernisasi, maka selain mengenal agen sosialisasi
tradisional, Desa Pakraman Ubud juga mengenal agen sosialisasi modern, yakni
sekolah. Pengamatan kancah menunjukkan, bahwa di dalam wilayah Desa
Pakraman Ubud, tidak saja ada Sekolah Dasar (SD), tetapi juga SMPN dan SMAN
RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Intenasional). Berbagai jenjang lembaga
pendidikan formal ini memainkan peran penting dalam mewujudkan pencapaian
gerakan Ajeg Bali. Pada sekolah-sekolah ini dilembagakan kebudayaan Bali
melalui apa yang disebut Pendidikan Kebudayaan Bali (PKB). PKB dituangkan
dalam berbagai bentuk matapelajaran, yakni Agama Hindu, Bahasa Daerah, dan
Muatan Lokal. Selain itu berbagai konsep maupun prinsip tentang kebudayaan Bali
bisa pula diintegrasikan pada bidang-bidang studi yang relevan, misalnya
Pendidikan IPS.
Agen pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya adalah media massa,
terutama Televisi (TV) dan Surat Kabar. Peran media massa sangat penting bagi
pelembagaan suatu kebudayaan. Dengan adanya kenyataan ini tidak mengherankan
jika media massa, terutama TV sangat penting bagi pelembagaan kebudayaan Bali.
11
kancah menunjukkan bahwa hampir semua keluarga yang berada pada kawasan
Desa Pakraman Ubud pasti memiliki TV. Data ini menandakan bahwa peran
media terutama TV sebagai agen pendidikan dalam konteks pemertahanan
kebudayaan Bali tidak bisa diabaikan.
Agen-agen sosialisasi tersebut, baik secara terpisah maupun secara
berkomplementer, dengan memakai metode pendidikan informal maupun metode
pendidikan formal, sangat penting bagi pemertahanan kebudayaan Bali yang
berkembang pada Desa Pakraman Ubud. Agen-agen pendidikan tersebut
memiliki fungsi bagi komunitas, yakni apa yang disebut fungsi latent, yakni
pemeliharaan pola yang tersembunyi yang terkait dengan masalah pemeliharaan
nilai dan sistem. Nilai dan sistem yang dipelihara adalah nilai-nilai kebudayaan
Bali yang memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat Bali.
Pencapaian sasaran ini bukan aktivitas yang sekali jadi, melainkan terbentuk
melalui suatu proses yang berkelanjutan.
Gerakan Ajeg Bali sebagai politik identitas yang berkembang pada
masyarakat Bali, termasuk di Desa Pakraman Ubud, di satu sisi berdampak
positif, yakni memperkuat identitas kebalian orang Bali. Namun di sisi yang lain
bisa memunculkan etnosentrisme yang berlanjut pada kegiatan me-liyan-kan etnik
lain sehingga kemunculan kekerasan, yakni kekerasan fisik, psikologis, ekonomi,
dan kultural acap kali tidak terhindarkan (Atmadja, 2010). Begitu pula Barker
(2004) dan Munawar-Rachman (2010) menunjukkan bahwa politik identitas, apa
pun labelnya, apakah berlabel budaya maupun agama, sangat rentan akan konflik
yang berlanjut dengan kekerasan. Pendek kata, politik identitas di satu sisi bisa
identitas kebalian orang Bali, namun di sisi yang lain peluang bagi timbulnya
konflik baik konflik over maupun latent yang disertai dengan kekerasan selalu
terbuka adanya.
Bertolak dari pemikiran di atas, maka implementasi politik identitas melalui
gerakan Ajeg Bali dalam rangka kebertahanan kebudayaan Bali di Desa Pakraman
Ubud menarik dipertanyakan, sekaligus menjadi alasan penting yang melandasi
penelitian ini. Hal ini tidak saja dilihat dari segi latar belakang atau alasan
maknawinya (mengapa mereka melakukan pemertahanan identitas etnik melalui
gerakan Ajeg Bali), tetapi juga tentang proses sosialisasi yang dilakukan oleh
agen-agen pendidikan yang ada di kawasan Desa Pakraman Ubud (bagaimana proses
sosialisasi, enkultulrasi dan ideologisasi yang berlangsung pada agen-agen
sosialisasi tradisional maupun modern atau informal maupun formal). Kedua
pertanyaan ini penting mengingat bahwa kebertahanan suatu sistem budaya tidak
terjadi secara otomatis, melainkan melalui suatu proses atau tunduk pada asas
prosesual berwujud sosialisasi, enkulturasi atau ideologisasi.
Berkenaan dengan kedua permasalahan di atas, maka pemertahanan
identitas etnik Bali yang berlaku di Desa Pakraman Ubud juga penting dilihat dari
segi implikasinya. Apakah gerakan politik identitas yang berkembang di Desa
Pakraman Ubud hanya berimplikasi integratif dengan berlandaskan pada
penguatan identitas kebalian atau sebaliknya, menimbulkan implikasi yang
berdampak pada hubungan antaretnik di Desa Pakraman Ubud, mengingat Desa
Pakraman Ubud tidak lagi bercorak monokultur, tetapi multikultur.
Mengacu pada paparan di atas, politik identitas gerakan Ajeg Bali sebagai
13
akan dilihat dari perspektif pendidikan. Dalam konteks ini, Ajeg Bali adalah proses
pendidikan dan pembudayaan (enkulturasi), yang juga sangat relevan sebagai
kajian pendidikan IPS, khususnya pendidikan IPS yang diaplikasikan dalam
kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengingat pendidikan IPS dapat dilihat dari
dua kepentingan, yakni kepentingan yang didasarkan pada tujuan pendidikan
formal sebagaimana dikembangkan dalam kurikulum pendidikan IPS di
sekolah-sekolah, dan pendidikan IPS sebagai bentuk aplikasi dan memraksis dalam
kehidupan sosial budaya masyarakat (Al Muchtar, 2001; 2002). Ajeg Bali sebagai
kajian pendidikan IPS yang memraksis dalam kehidupan masyarakat juga sangat
relevan dan penting untuk diakomodasi dalam kurikulum pendidikan IPS di
persekolahan. Dalam konteks ini Ajeg Bali dapat digunakan sebagai sumber belajar
IPS yang memberikan pengetahuan praktis kepada siswa tentang kehidupan sosial
budaya yang berkembang di lingkungannya.
Ajeg Bali sebagai proses pendidikan IPS akan dikaji melalui pendekatan
yang komprehensif, yakni pendekatan multidisipliner sebagaimana yang
dikembangkan dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Cakupan multi
disiplin ilmu dikembangkan oleh pendidikan IPS, yang berangkat dari konsep
Social Studies. Social Studies dipancangkan pertama kali oleh Edgar Bruce Wesley
pada tahun 1937, didefinisikan sebagai “…the social studies are the social
sciences simplified pedagogical purpose…social studies adalah ilmu-ilmu sosial
yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan” (Barr, dalam Winataputra, 2001:
20). Pengertian ini kemudian dibakukan dalam Pengembangan Kurikulum
Pendidikan di Amerika, sebagai: “The Social Studies Comprised of those aspects
geography, and philosophy wich in practice are selected for purposes in schools
and colleges...” (Barr, dalam Winataputra, 2001: 20). Maksudnya, bahwa social
studies berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi,
antropologi, psikologi, ilmu geografi dan filsafat, yang dipilih untuk tujuan
pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi (Winataputra, 2001). Mengacu pada
pemahaman tersebut, maka kajian tentang gerakan Ajeg Bali sebagai politik
identitas pemertahanan identitas etnik, dapat dilihat dari perspektif pendidikan,
sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, politik, bahkan agama.
Sebagai kajian ilmu, IPS menjadi salah satu mata pelajaran yang terdapat
dalam kurikulum Pendidikan Nasional dan diajarkan mulai jenjang Sekolah Dasar
(SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Al Muchtar, 2001; Somantri, 2001).
Berkenaan dengan itu, kajian tentang Ajeg Bali juga sangat relevan sebagai materi
pilihan dalam pembelajaran IPS. Studi pendahuluan menunjukkan, gerakan Ajeg
Bali dalam konteks sosial, budaya, kemasyarakatan, dan dalam konteks perubahan
sosial, merupakan isu penting yang sangat relevan sebagai materi pembelajaran
pendidikan IPS. Konteks ini berkaitan dengan masalah-masalah etnisitas, integrasi
nasional, maupun nasionalisme.
Mengacu pada berbagai paparan di atas, maka penelitian tentang politik
identitas gerakan Ajeg Bali ini sangat penting dilakukan, dan diharapkan menjadi
masukan atau rekomendasi bagi pelaksana pendidikan IPS di berbagai jenjang
sekolah, agar mulai memasukkan materi terkait isu-isu Ajeg Bali dalam kurikulum
pendidikan sekolah mereka. Pendidikan IPS yang diberikan di sekolah-sekolah di
Bali, dapat menguatkan mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu, Bahasa Daerah
15
lain, hal ini juga sangat memungkinkan, mengingat pendidikan IPS juga dapat
dilihat sebagai suatu proses enkulturasi atau pembudayaan, baik itu pembudayaan
nilai-nilai kemanusiaan, pembudayaaan dalam konteks pewarisan budaya
(transmission of culture), pembudayaan dalam konteks ideologi bangsa,
pembentukan nation character building, maupun pembudayaan nilai-nilai
pengetahuan yang terdapat dari disiplin ilmu bersangkutan (Cohen, 1971; Widja,
2002; Azra, 2002; Tillar, 2007; Suyanto, 2006). Pemahaman ini tidak terlepas dari
pandangan filsafat ilmu seperti empirisme, positivisme, rasionalisme, dan
idealisme, maupun filsafat ilmu pendidikan yang mendasari pendidikan IPS, seperti
filsafat esensialisme, perenialisme, progresivisme, maupun rekontruksionalisme
(Ornstein dan Levine, 1985; Somantri, 2001).
Dalam implementasinya, pendidikan IPS sebagai sarana pendidikan
kebudayaan Bali, dapat diwujudkan melalui kurikulum pendidikan IPS maupun
kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal memungkinkan pendidikan IPS
mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan isu-isu penting di daerah,
sebagaimana dikemukakan Dakir (2004):
Dalam kurikulum muatan lokal, proses pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Begitu pula bahan yang ada pada muatan lokal dapat tercantum pada intrakurikuler, misalnya; berbagai mata pelajaran yang termasuk dalam bidang studi kesenian dan keterampilan, bahasa (bahasa daerah dan Inggris) dan beberapa topik atau subtopik pokok bahasan yang bernaung dalam bidang studi IPA dan IPS, dan pelajaran lainnya (Dakir, 2004: 108-109).
Berdasarkan definisi tersebut, melalui materi-materi pilihan yang relevan
dengan konteks pemertahanan identitas etnik, maka Pendidikan IPS yang diberikan
di sekolah-sekolah di Bali dapat mendukung strategi pendidikan kebudayaan Bali.
dilaksanakan, yakni dengan merujuk pada konten atau ruang lingkup materi ajar
pendidikan IPS di sekolah menengah, yang menyangkut aspek-aspek: (1) Manusia,
Tempat dan Lingkungan; (2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan; (3) Sistem
Sosial dan Budaya; (4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan (Kurikulum
Pendidikan IPS, 2006).
Paparan di atas menunjukkan, bahwa kajian tentang gerakan Ajeg Bali
sangat penting, tidak saja karena masalah tersebut sangat aktual dan mendominasi
berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali saat ini, tetapi juga dalam konteks
pengembangan sumber belajar IPS, yakni dengan menggali masalah
sosial-masyarakat sebagai sumber belajar IPS. Masalah penelitian ini juga menarik, tidak
semata-mata dilihat dari akibat adanya penguatan identitas kesukubangsaan, tetapi
terkait pula usaha mewujudkan cita-cita ideal bagi penyelenggaraan pendidikan,
termasuk pendidikan IPS, antara lain mewujudkan manusia yang menjunjung
tinggi asas multikulturalisme atau Bhineka Tunggal Ika.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan penelitian, yakni:
1. Mengapa masyarakat Desa Pakraman Ubud melakukan pemertahanan
identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali ?
2. Bagaimana pola penyelenggaraan pemertahanan identitas etnik melalui
politik identitas gerakan Ajeg Bali di Desa Pakraman Ubud, baik yang
berlangsung pada masyarakat sebagai agen sosialisasi tradisional,
17
3. Bagaimana implikasi adanya pemertahanan identitas etnik melalui
politik identitas gerakan Ajeg Bali terhadap hubungan antaretnik di Desa
Pakraman Ubud ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini
dapat dipilah menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.
1. Tujuan Umum
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang
pemertahanan identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali dan
bagaimana hal itu berlangsung pada Desa Pakraman Ubud dengan melibatkan
berbagai agen pendidikan, baik pendidikan informal melalui berbagai institusi
tradisionalnya, maupun pendidikan formal yakni sekolah. Pemahaman ini penting,
tidak saja guna memperkuat dan menambah pengetahuan ilmu sosial, tetapi bisa
pula memberikan pengayaan, pengembangan atau bahkan sebagai sumber materi
bagi pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Bahkan yang tidak
kalah pentingnya, pemahaman teoretis yang didapat bisa pula berguna bagi
pengembangan Desa Pakraman Ubud sebagai desa wisata yang mengglobal, tanpa
kehilangan identitas kebalian-nya dan sekaligus terbebas dari konflik.
2. Tujuan Khusus
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab
permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan-permasalahan di atas, yakni:
(1) Mengungkapkan latar belakang munculnya upaya pemertahanan
identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali di Desa
(2) Mengungkapkan pola penyelenggaraan pemertahanan identitas etnik
melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali di Desa Pakraman Ubud.
(3) Menemukan implikasi atau dampak dari penerapan pemertahanan
identitas etnik melalui politik identitas gerakan Ajeg Bali terhadap
hubungan antaretnik di Desa Pakraman Ubud.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat bermanfaat, baik
secara teoritik maupun praktis yakni sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretik
Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Desa Pakraman
Ubud mempertahankan citra dan identitasnya, baik identitas etnik yang melekat
sebagai ciri khas institusi desa pakraman, maupun identitasnya sebagai kawasan
pariwisata budaya. Hal ini penting, karena dengan demikian Desa Pakraman Ubud
sekaligus mengemban dua misi sekaligus, yakni: pertama, sebagai sebuah desa
adat/desa pakraman yang berada pada lingkup budaya dan Pemerintah Provinsi
Bali, mempertahankan identitas etnik orang Bali adalah merupakan tugas dan
kewajibannya, seperti juga desa-desa pakaraman lainnya. Kedua,
mempertahankan identitas etnik berarti juga mempertahankan komoditas
pariwisatanya yang bertumpu pada potensi adat, budaya, dan agama. Jika identitas
ini pudar, maka pariwisata budaya yang menjadi andalan Ubud juga akan pudar.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu
19
dikembangkan Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pasca Sarjana Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, selama ini masih didominasi oleh
penelitian-penelitian yang berdimensi pendidikan dan pembelajaran IPS di sekolah-sekolah.
Sementara itu kajian ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada masalah-masalah sosial
kemasyarakatan di lapangan, seperti fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi,
jender, dan sebagainya masih jarang dilakukan.
Masalah ini juga sangat relevan dan dapat memperkaya studi Pendidikan
IPS, baik dalam konteks kajian secara multi disipliner, maupun dalam rangka
melahirkan rekomendasi penelitian, yakni dikembangkannya isu-isu etnisitas
termasuk tetang Ajeg Bali dan isu-isu kearifan lokal lainnya dalam struktur materi
IPS di sekolah-sekolah.
Secara khusus, manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini
adalah:
(1) Mengembangkan konsep tentang gerakan Ajeg Bali sebagai sebuah gerakan
politik identitas.
(2) Memberikan manfaat dalam rangka pengembangan konsep, proposisi,
maupun teori baru dalam hubungan dengan konteks sosil-budaya
masyarakat Bali.
(3) Memberikan masukan kepada para pemikir, pengambil kebijakan dan
peneliti lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian berikutnya.
(4) Memberi manfaat kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui Bali
E. Klarifikasi Konsep
Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah atau konsep yang
memerlukan penjelasan atau pembatasan, yakni sebagai berikut:
1. Ajeg Bali
Istilah Ajeg Bali berasal dari dua kata, “Ajeg” dan “Bali”, yang secara
harfiah kedua kata tersebut memiliki artinya masing-masing. Dalam Kamus
Bali-Indonesia (1993: 9) kata: “ajeg”= tegak, kukuh (peraturan); “ajegan”=tegakkan.
Contoh penggunaan kata ini seperti: “ajegang awig-awig desane” (=tegakkan
peraturan desa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 13), terdapat kata
“ajek” yang memiliki arti yang sama, yakni: tetap; teratur; tidak berubah. Kata
“ajek” merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Jawa, yang mempunyai
makna yang sama dengan kata “ajeg”. Sedangkan kata “Bali” merujuk pada Pulau
Bali atau Propinsi Bali yang secara hukum, geografis, dan politis merupakan
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian Ajeg
Bali dapat diartikan sebagai “meng-ajeg-kan Bali” atau “Bali yang ajeg”. Merujuk
pada arti kata “ajeg” tersebut maka Bali yang ajeg, berarti adalah, “Bali yang
kokoh, teratur, tegak, stagnan, mantap, tidak berubah”.
Dalam konteks penelitian ini, Ajeg Bali dimaknai sebagai sebuah politik
identitas atau gerakan pemertahanan identitas etnik Bali. Gerakan ini bertujuan
mengembalikan masyarakat Bali dalam konteks pengamalan ajaran agama Hindu
dan kebudayaan Bali, atau disebut pula sebagai re-Baliisasi dan re-Hinduisasi.
2. Politik Identitas
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 417) menunjukkan bahwa identitas
21
ciri khusus seseorang. Menurut Tilaar (2007: 16) identitas merupakan konsep yang
sangat erat kaitannya dengan etnisitas. Identitas sering pula dikaitkan dengan
stereotip-stereotip, baik yang positf maupun negatif dari suatu etnik.
Politik secara umum dapat diartikan sebagai “segala urusan dan tindakan
(kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara; politik juga
mengandung arti; cara bertindak dalam mengatasi atau menangani suatu masalah”
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 780).
Dari dua deskripsi tersebut, maka politik identitas sebagaimana
dikemukakan Cressida Heyes (dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007)
dapat diartikan sebagai “tindakan politis untuk mengedepankan
kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan
identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau
keagamaan”. Politik identitas juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik
yang dibangun berdasarkan perbedaan etnik di mana simbol-simbol kebudayaan
masih digunakan sebagai ciri suatu kelompok. Jadi, politik identitas seperti
dikatakan Barker (2003) dan Sarup (2008), terletak pada pandangan bahwa
manusia dapat bertindak secara sengaja dan secara kreatif guna membentuk dan
mempertahankan identitas etniknya.
3. Desa Pakraman
Dalam sistem pemerintahan desa di Bali dikenal dua sistem pemerintahan,
yakni desa dinas dan desa adat atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan
desa pakraman. Kedua jenis desa tersebut memiliki tugas dan wewenang yang
mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah
desa di bawah kecamatan (Sirtha, 2008: 2).
Secara formal, istilah desa pakraman dimuat dalam Peraturan Daerah
Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang ditetapkan pada
tanggal 21 Maret 2001. Dalam Perda tersebut dijelaskan pengertian desa
pakraman, yakni: “…kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat
Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Tri Kahyangan Desa (Tiga Pura Pusat
yang melandasi desa pakraman di Bali), yang mempunyai wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri serta berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri”.
4. Pariwisata
Konteks penelitian ini tidak terlepas dari masalah pariwisata, sebagai setting
latar Desa Pakraman Ubud, yang dikenal sebagai kawasan pariwisata budaya.
Dalam Undang-Undang Kepariwisataan (Undang-Undang RI No. 10/2009),
dijelaskan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Sedangkan pengertian
pariwisata budaya sebagaimana dikemukakan Yoeti (2006: 26) adalah jenis
kegiatan pariwisata yang objeknya adalah kebudayaan. Objek daya tarik wisata
budaya itu dapat berkisar pada beberapa hal, seperti: kesenian, baik seni rupa
maupun segala bentuk seni pertunjukan, tata busana, tata boga, upacara adat,
demonstrasi kekebalan dan komunikasi dengan alam gaib, lingkungan binaan, serta
lain-23
lain. Objek tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk turis, dengan
maksud agar lebih menarik.
5. Globalisasi
Globalisasi antara lain dapat dijabarkan dari asal katanya yakni “global” ,
yang maknanya adalah universal. Pengertian dan pendefinisian globalisasi sangat
luas, sehingga pemaknaannya tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada
yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses
alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat
satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan
ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya
setempat (Brunsvick dan Danzin, 2007).
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan disertasi disesuaikan dengan keluasan cakupan
penelitian, di mana hasil dan pembahasan masing-masing permasalahan penelitian
dipaparkan pada bab-bab tersendiri. Model sistematika seperti ini dimaksudkan
untuk memudahkan pemaparan dan pencermatan. Secara keseluruhan disertasi
terdiri dari delapan bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan
BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran
BAB III: Metode Penelitian
BAB IV: Memaparkan gambaran umum lokasi penelitian
BAB V: Memaparkan pembahasan dari permasalahan penelitian pertama.
BAB VI: Memaparkan pembahasan dari permasalahan penelitian kedua.
BAB VII: Memaparkan pembahasan dari permasalahan ketiga
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research (Creswell,
1998) dengan menggunakan rancangan atau desain penelitian kualitatif. Dengan
demikian, penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada pemaknaan dan
konteks pendeskripsian (Mulyana, 2001; Irawan, 2006). Pendeskripsian yang
terkait dengan pemaknaan akan bersifat rich and thick description (Creswell,
1989), yakni suatu pendeskripsian yang kaya dan tebal, bersifat holistik, emik dan
etik,tentang bentuk, fungsi, dan makna yang tampak maupun makna yang tersirat
di balik suatu teks tertulis atau lisan, dan teks sosial dalam bentuk fenomena sosial
budaya yang ada di balik perilaku individu atau masyarakat. Dalam konteks
penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Desa Pakraman Ubud
dengan berbagai pranata sosial-budaya-religius yang mengaturnya.
B. Pendekatan Penelitian
Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa
Pakraman Ubud mengiplementasikan politik identitas gerakan Ajeg Bali, sebagai
upaya mempertahankan identitasnya, baik identitas etnik yang melekat sebagai ciri
khas institusi desa pakraman berikut krama desa yang menjadi anggotanya,
maupun identitasnya sebagai kawasan pariwisata budaya. Agar tujuan penelitian
tercapai secara maksimal, dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan etnografi,
yang lazim digunakan dalam kajian yang bersifat sosial-budaya. Etnografi adalah
metode riset yang menggunakan observasi langusng terhadap kegiatan manusia
128
adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli.
Dalam konteks penelitian ini, metode etnografi digunakan dengan sasaran untuk
memahami segala aktivitas sosial masyarakat termasuk di dalamya memahami pula
berbagai teks tertulis maupun lisan dan teks sosial dalam perspektif pelakunya
(emik), yakni masyarakat Desa Pakraman Ubud, Bali berserta segala institusi
sosial-religiusnya (Bungin, 2003).
Dalam rangka menganalisis temuan, pendekatan etnografi dibantu dengan
metode dekonstruksi dan metode semiotika. Dekonstruksi mengandalkan pola pikir
kritis dalam konteks membongkar suatu teks guna menemukan ideologi dominan
yang ada di baliknya. Metode ini digunakan untuk mencermati dan memahami
berbagai bentuk permainan kekuasaan yang dilakukan pihak pengelola desa
pakraman untuk menghegemoni krama desa (warga) Desa Pakraman Ubud dalam
rangka mengimplementasikan gerakan pemertahanan identitas etnik melalui politik
identitas gerakan Ajeg Bali. Sedangkan semiotika adalah ilmu tentang tanda atau
penanda, atau dapat pula dikatakan sebagai metode analisis untuk mengkaji tanda
atau penanda. Dalam konteks penelitian ini, semua gejala atau fenomena sosial
terkait dengan upaya pemertahanan identitas etnik diposisikan sebagai tanda. Ini
meliputi seluruh institusi sosial-religius maupun institusi formal, yakni sekolah
yang berfungsi sebagai agen sosialisasi, maupun tanda bahasa yang terdapat pada
teks seperti lontar, awig-awig, perarem desa (perangkat tata aturan), perangkat
pembelajaran, seperti kurikulum, silabus, RPP, dsb (Piliang, 2006: 30-34).
C. Penentuan Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pakraman Ubud yakni salah satu
Kabupaten Gianyar, Bali. Desa Pakraman Ubud memiliki empat banjar adat
(bagian dari desa pakraman) yakni: (1) Banjar Ubud Kaja, (2) Banjar Ubud
Tengah, (3) Banjar Ubud Kelod, dan (4) Banjar Sambahan.
Dipilihnya Desa Pakraman Ubud sebagai lokasi penelitian didasarkan
beberapa alasan lainnya, yakni:
1. Desa Pakraman Ubud berada di pusat wilayah Kelurahan Ubud yang
sekaligus merupakan zona inti Kawasan Pariwisata Ubud. Kelurahan Ubud
berstatus sebagai desa dinas dan menjadi basis kegiatan pemerintahan lokal
dan pelayanan administratif dalam sistem desentralisasi.
2. Desa Pakraman Ubud sebagai zona inti Kawasan Pariwisata Ubud
memiliki kompleksitas masalah yang tinggi sebagai akibat perkembangan
pariwisata. Kondisi ini menyebabkan Desa Pakraman Ubud sangat terbuka
dengan dunia luar, baik dalam konteks globalisasi dan modernisasi, maupun
dengan kedatangan etnik dari luar Bali.
3. Kekuatan Desa Pakraman Ubud didukung oleh Puri Ubud yang
merupakan penyokong utama dan salah satu agen sosialisasi gerakan
pemertahanan identitas etnik. Puri Ubud memainkan peran penting dalam
menguatkan kebijakan desa pakraman.
Adapun lokasi penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:
130 Peta Propinsi Bali
Peta Kabupaten Gianyar Lokasi Desa Pakraman Ubud
Gambar 3.1
Lokasi Desa Pakraman Ubud dalam Peta Propinsi Bali dan Peta Kabupaten Gianyar Sumber: http://www.indonesia tourism.com/bali/map/htm/bali-map.htm, januari 2010.
D. Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Informan
Berdasarkan desain penelitian di atas, subjek penelitian ini adalah semua
unsur yang berperan sebagai aktor atau agen sosialisasi pemertahanan identitas
etnik. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti berhubungan dengan beberapa
informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Keseluruhan
informan adalah orang-orang yang memahami berbagai aspek yang terkait
dengan masalah penelitian. Mereka diseleksi dan ditunjuk sebagai informan
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penunjukan informan diawali
dengan penentuan informan kunci atau key informant. Selanjutnya penunjukan
informan akan dikembangkan pada saat penelusuran lapangan dengan
melainkan tergantung pada tingkat kejenuhan data yang akan dikumpulkan sesuai
prinsip kerja penelitian kualitatif (Spradley, 1979).
Informan kunci terdiri dari para tokoh adat dan agama. Mereka adalah
Bendesa Adat (kepala adat) Ubud, Kelihan Banjar (kepala banjar), Pelingsir
(tokoh) Puri, pemuka agama dari Geriya, para ketua sekaa (organisasi sosial
tradisional), pengurus subak, pecalang (pengaman desa), dan krama desa (warga
desa) Ubud, baik yang mewakili kuren (keluarga) maupun dadia (klen). Selain itu
ditunjuk pula tokoh dari desa dinas, yakni Lurah, Ketua LPM, Yayasan Bina
Wisata Ubud, dsb. Informan kunci lainnya adalah dari unsur pendidikan, yakni
sekolah dan guru yang juga berperan sebagai agen sosialisasi pemertahanan
identitas etnik. Sekolah yang ditunjuk adalah sekolah-sekolah yang berada di
wilayah Desa Pakraman Ubud, yang mewakili jenjang SD-SMA, yakni SDN 1
Ubud, SMPN 1 Ubud dan SMAN 1 Ubud.
Sedangkan informan pendukung diambil dari unsur pemerintah dan
dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan.
Instansi-instansi ini sangat penting keberadannya dalam konteks koordinasi
kebijakan maupun sebagai mitra pendukung kebijakan. Informan yang juga penting
adalah para pendatang yang berdomisili di Desa Pakraman Ubud. Penunjukan
mereka sebagai informan adalah karena mereka merupakan bagian dari kehidupan
multi etnik di kawasan Ubud, dan bagian dari kehidupan pariwisata itu sendiri.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan
penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan
132
1. Teknik Wawancara
Informan yang telah ditetapkan sebagai sumber informasi akan
diwawancarai secara mendalam (in-dept interviw) dan terbuka (open-ended), untuk
menggali, memahami dan mengetahui pola pikir mereka terhadap kasus atau
permasalahan penelitian yang diajukan. Agar wawancara mendalam dan terbuka
dapat berlangsung secara terarah, maka peneliti merujuk pada pedoman wawancara
yang telah disusun sebagai perangkat atau instrumen penelitian yang memuat
pokok-pokok pikiran yang terkait dengan masalah yang dikaji (lihat lampiran 05).
Dengan cara ini wawancara diharapkan berlangsung secara fleksibel. Begitu pula
informasi yang digali, tidak saja bertumpu pada apa yang mereka ucapkan, tetapi
didasarkan pula pada penggalian yang mendalam tentang pemaknaan mereka
terhadap ucapan maupun perilaku mereka. Dengan demikian, melalui wawancara
mendalam dan terbuka ini akan tergali aspek explicit knowledge yang melekat pada
informan. Untuk menghindarkan adanya distorsi data, maka pencatatan hasil
wawancara dilakukan secara manual dan atau disertai perekaman dengan
menggunakan alat perekam. Pemakaian alat perekam adalah atas persetujuan
informan sehingga suasana wawancara tetap berjalan secara alamiah dan semua
informan diharapkan tidak keberatan akan perekaman hasil wawancara tersebut.
Untuk itu peneliti telah meyakinkan informan, bahwa data yang diberikan sangat
berharga dan sama sekali tidak mengganggu privacy informan.
2. Teknik Observasi (Pengamatan)
Observasi yang akan digunakan adalah observasi langsung yang bersifat
partisipasi, sehingga peneliti akan tinggal di lokasi penelitian. Observasi atau
para tokoh Desa Pakraman Ubud, baik yang terkait dengan pola pemertahanan
identitas etnik maupun pola hubungan yang diterapkan desa pakraman dengan
etnik-etnik non-Bali. Agar observasi partisipasi dapat berjalan terarah, maka
dibuat panduan atau pedoman observasi (lihan lampiran 06). Adapun aspek yang
diobservasi, adalah: (1) Latar (setting); (2) Pelibat (participant); (3) Kegiatan dan
interaksi (activity and interaction); (4) Frekuensi dan durasi (frequency and
duration); (5) Faktor subtil (subtle factor); (6) Peralatan yang mereka gunakan; (7)
Waktu berlangsungnya kegiatan; (8) Ekspresi wajah pada saat melakukan
kegaiatan ; dan (9) Produk yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan
(Alwasilah, 2002).
Aspek-aspek yang diamati ditelusuri dari aspek bentuk, fungsi dan
pemaknaan kontekstualnya. Segala hal yang diobservasi direkam secara verbal
manual, maupun dengan menggunakan alat perekam visual atau kamera
(pemotretan). Gambar atau foto yang dihasilkan digunakan sebagai ilustrasi dalam
penyajian hasil penelitian, sehingga ketepatan penggambaran, daya tarik, dan daya
imajinasi hasil penelitian dapat ditingkatkan secara lebih optimal.
3. Studi Dokumen
Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi
dokumen. Dokumen yang dikaji antara lain data statistik yang tersedia di Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gianyar, Monografi/Profil Desa Dinas dan Desa
Pakraman Ubud, Awig-awig Desa Pakraman Ubud, Perarem Desa/Banjar Ubud,
dan segala aturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan institusi sosial-religius
dan krama desa maupun dengan warga pendatang. Dokumen juga berasal dari
134
Dokumen ini berupa Kurikulum Pendidikan, perangkat pembelajaran dan silabus
khususnya untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu, Bahasa Bali, dan
Muatan Lokal.
Ketiga teknik pengumpulan data di atas akan digunakan secara
bersama-sama dan/atau saling melengkapi dengan tujuan untuk memperkaya temuan,
sekaligus sebagai prosedur Triangulasi Data maupun Triangulasi Sumber Data
yang diperlukan sebagi proses validitas data.
F. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal instrumen penelitian yang baku
sebagai perangkat penelitian sebagaimana penelitian kuantitatif, karena dalam
penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri (Creswell,
1994; 1998 ; Bungin, 2003; 2004; Alwasilah, 2002). Namun sebagai pedoman di
lapangan, agar penelitian berlangsung sesuai arah yang dikehendaki berdasarkan
fokus permasalahan, disusun pedoman wawancara (interview guide) dan pedoman
observasi sebagai instrumen penelitian (lihat lampiran 04 dan 05). Selain itu
dilengkapi pula dengan perangkat keras berupa alat perekam, baik untuk merekam
kegiatan berupa gambar atau foto, maupun perekam hasil wawancara. Ini sejalan
dengan apa yang dikemukakan Wallace (1990: 57), bahwa untuk penelitian ilmu
sosial, instrumen yang biasa digunakan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian,
yakni yang melibatkan organ inderawi manusia tanpa dilengkapi dengan bantuan
teknologi selain keahlian, dan organ inderawi manusia yang dilengkapi dengan
G. Teknik Verifikasi Data
Teknik verifikasi data digunakan untuk memperoleh data yang memenuhi
standar kualitas, sehingga proses penggalian data maupun data yang dihasilkan
dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Mengacu pada Creswell (1998:
2001-2003) terdapat delapan prosedur teknik verifikasi, yakni: (1) Perpanjangan waktu
kerja dan observasi yang gigih (prolonged engagement and persistent observation)
di lapangan, termasuk membangun kepercayaan dengan para partisipan,
mempelajari budaya, dan mencek informasi yang salah yang berasal dari distorsi
yang diperkenalkan oleh peneliti atau informan. Di lapangan peneliti membuat
keputusan-keputusan apa yang penting dan menonjol untuk dikaji, relevan dengan
maksud kajian, dan perhatian untuk difokuskan. Proses ini akan menghasilkan
penelitian etnografis yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan;
(2) Triangulasi (triangulation) data, dengan menggunakan seluas-luasnya
sumber-sumber yang banyak dan berbeda, metode-metode, data dari para peneliti, dan
teori-teori untuk menyediakan bukti-bukti yang benar (corroborative evidence);
(3) Reviu sejawat (peer reviuw) atau debriefing, dengan menyiapkan suatu cek
eksternal dari proses penelitian; teman sejawat itu menanyakan
pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang metode, makna dan interpretasi; (4) Analisis kasus
negatif (negative case analysis). Si peneliti memperbaiki lagi hipotesis-hipotesis
kerjanya selagi penelitian berlangsung berdasarkan bukti/evidensi yang negatif atau
tidak memastikan (disconfirming evidence); (5) Klarifikasi bias peneliti (clarifying
researcher bias) yang penting dilakukan sejak awal penelitian, sehingga pembaca
memahami posisi peneliti dan setiap bias atau asumsi-asumsi yang berdampak pada
136
memohon (solicit) pandangan-pandangan para informan tentang kredibilitas dari
temuan-temuan dan interpretasi-interpretasi. Pendekatan ini sangat umum dalam
kajian kualitatif, termasuk mengambil data, analisis, interpretasi dan
kesimpulan-kesimpulan; (7) Deskripsi yang kaya dan tebal (rich and thick description), yang
memungkinkan pembaca membuat keputusan-keputusan mengenai kemampuannya
untuk ditransfer (transferability) karena penulis menggambarkan dengan rinci para
partisipan atau keadaan/lingkungan (setting) yang sedang dikaji, (8) Odit luar
(external audits), dengan memperkenalkan konsultan luar, oditor untuk memeriksa
proses dan produk/hasil dari laporan/kisah (account), mengakses akurasinya.
Berdasarkan delapan prosedur verifikasi tersebut, dalam penelitian ini
peneliti menggunakan tiga teknik di antaranya, yakni:
(1) Teknik perpanjangan waktu kerja dan observasi yang gigih (prolonged
engagement and persistent observation). Di sini peneliti membuat
keputusan-keputusan penting dan menonjol untuk dikaji, yang relevan
dengan maksud dan tujuan penelitian. Proses ini diawali dengan
membangun kepercayaan dengan para informan/partisipan, mempelajari
budaya, karakteristik, kebiasaan, maupun perilaku sehari-hari masyarakat
Desa Pakraman Ubud.
(2) Teknik triangulasi (triangulation). Teknik ini digunakan sebagai kelanjutan
teknik perpanjangan waktu dan observasi, yang dimaksudkan untuk mencek
dan ricek data, mengecek informasi yang berasal dari informan, dengan
menggunakan seluas-luasnya sumber data, metode, maupun teori-teori,
guna mendapatkan bukti-bukti yang benar (corroborative evidence).