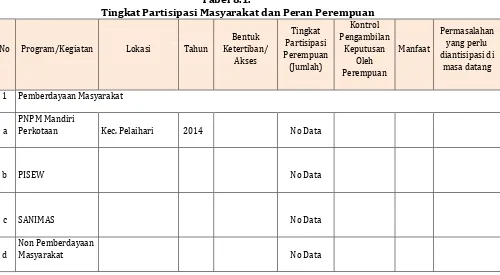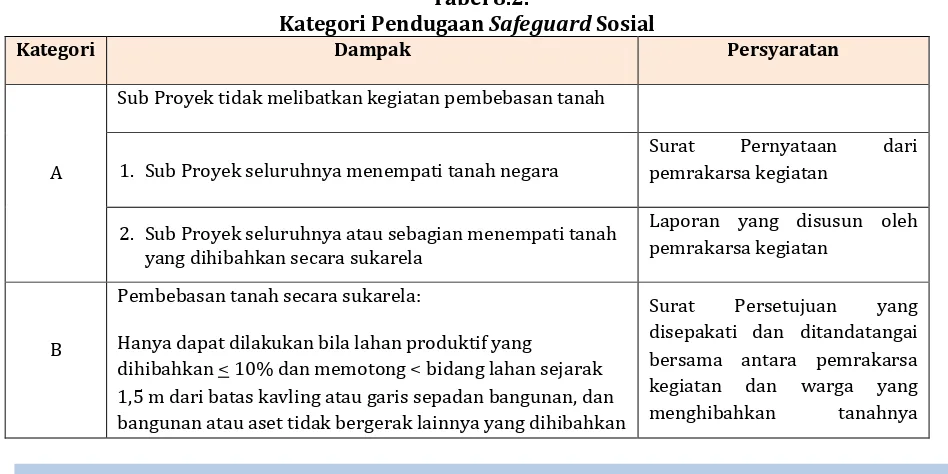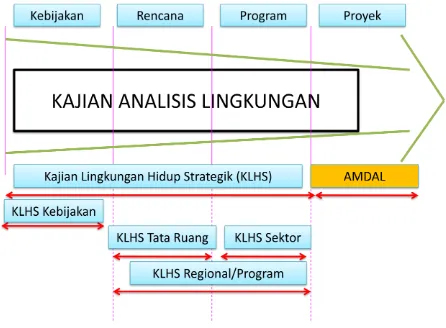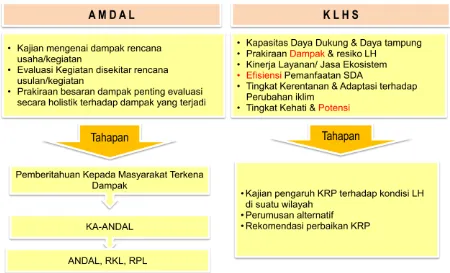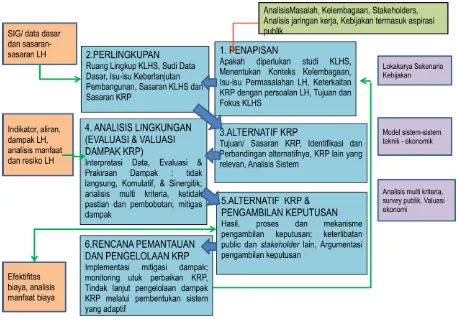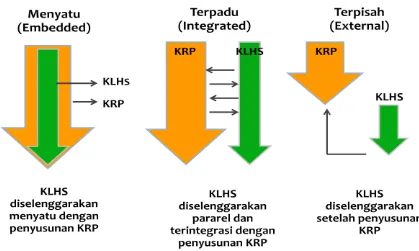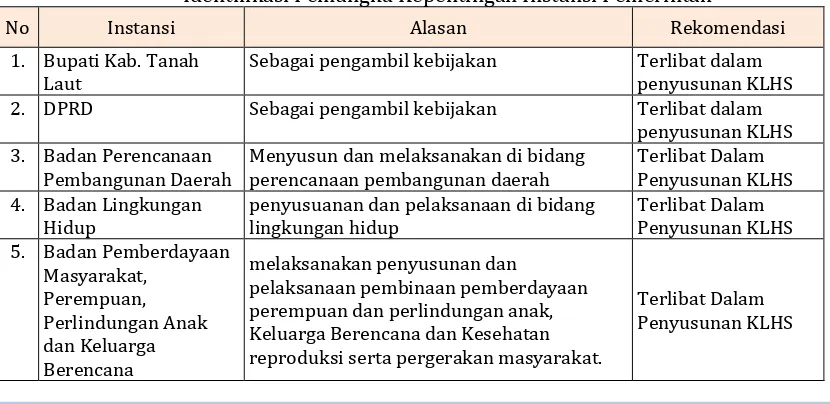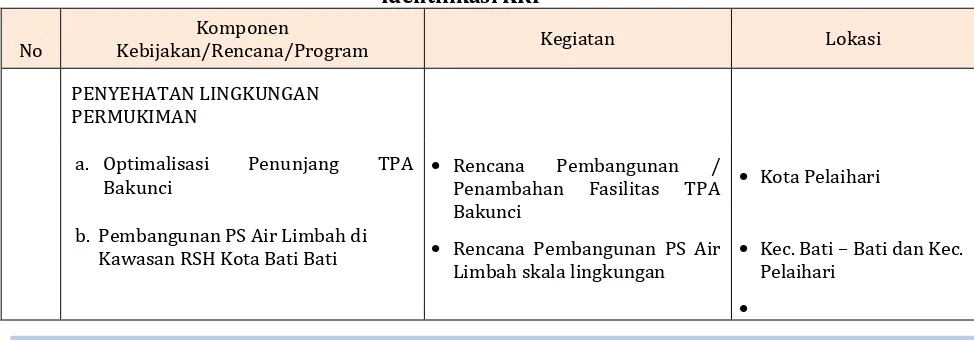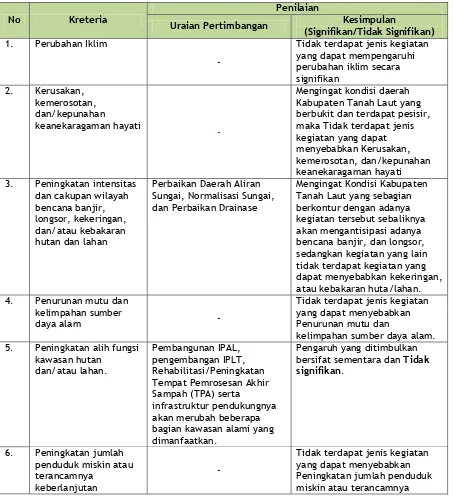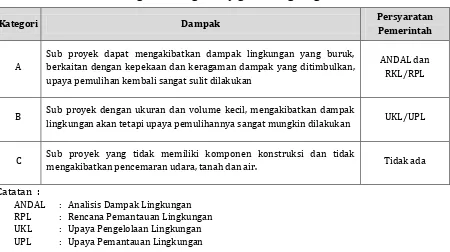LAPORAN ANTARA 4-
1
BAB
4
ANALISIS SOSIAL EKONOMI
DAN LINGKUNGAN
4.1 ANALISIS SOSIAL
Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur kepada
masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca
pembangunan/pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur
permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan
isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarusutamaan
gender. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan masyarakat terkena dampak
sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian
kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau
pengelolaan perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur tersebut membawa
manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
Dasar peraturan perundang-undangan yang menyatakan perlunya memperhatikan
aspek sosial adalah sebagai berikut:
1. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan sosial juga dilakukan
dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang
kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di
wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di
tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender. 2. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi
Pasal 3 : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin
kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
3. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014:
Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program
pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan
kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan
percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan
partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan.
4. Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan
Pasal 1: Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Menginstruksikan kepada Menteri untuk melaksanakan pengarusutamaan gender
guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif
gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Komponen sosial dalam hal ini terkait pengadaan tanah dan keresahan
masyarakat karena rencana investasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Pengadaan tanah biasanya terjadi jika kegiatan investasi berlokasi di atas tanah yang
bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat selama lebih dari
satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua langkah yang diambil
harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama terkait dengan ganti
rugi atau ganti untung dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan standar
LAPORAN ANTARA 4-
3
Aspek Sosial Pada Tahap Perencanaan PembangunanKemiskinan
Aspek sosial pada perencanaan pembangunan diharapkan mampu melengkapi
kajian perencanaan teknis sektoral. Salah satu aspek yang perlu ditindak-lanjuti adalah isu
kemiskinan sesuai dengan kebijakan internasional MDGs dan Agenda Pasca 2015, serta
arahan kebijakan pro rakyat sesuai direktif presiden.
Menurut standar BPS terdapat 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan
keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok
tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m2,
buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya
dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-
seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang
modal lainnya
Pengarusutamaan Gender
Selain itu aspek yang perlu diperhatikan adalah responsivitas kegiatan
pembangunan terhadap gender. Saat ini telah kegiatan responsif gender bidang Cipta
Karya meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan,
Infrasruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasia Masyarakat (PAMSIMAS), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(PPIP), Rural Infrastructure Support (RIS) to PNPM, Sanitasi Berbasis Masyarakat
(SANIMAS), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Studi Evaluasi Kinerja
Program Pemberdayaan Masyarakat bidang.
Tabel 8.1.
Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Peran Perempuan
No Program/Kegiatan Lokasi Tahun
Bentuk Ketertiban/
Akses
Tingkat Partisipasi Perempuan
(Jumlah)
Kontrol Pengambilan
Keputusan Oleh Perempuan
Manfaat
Permasalahan yang perlu diantisipasi di
masa datang
1 Pemberdayaan Masyarakat
a
PNPM Mandiri
Perkotaan Kec. Pelaihari 2014 No Data
b PISEW
No Data
c SANIMAS
No Data
d
Non Pemberdayaan
Masyarakat No Data
Perlindungan Sosial Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan pembangunan bidang secara lokasi, besaran kegiatan, dan durasi
berdampak terhadap masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya konflik dengan
masyarakat penerima dampak maka perlu dilakukan beberapa langkah antisipasi, seperti
konsultasi, pengadaan lahan dan pemberian kompensasi untuk tanah dan bangunan,
serta permukiman kembali. 1. Konsultasi masyarakat
Konsultasi masyarakat diperlukan untuk memberikan informasi kepada
masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang mungkin terkena dampak akibat
pembangunan di wilayahnya. Hal ini sangat penting untuk menampung aspirasi
LAPORAN ANTARA 4-
5
proses perencanaan. Konsultasi masyarakat perlu dilakukan pada saat persiapan
program, persiapan AMDAL dan pembebasan lahan.
2. Pengadaan lahan dan pemberian kompensasi untuk tanah dan bangunan
Kegiatan pengadaan tanah dan kewajiban pemberian kompensasi atas tanah
dan bangunan terjadi jika kegiatan pembangunan bidang cipta karya berlokasi di atas
tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh swasta/masyarakat
selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah adalah bahwa semua
langkah yang diambil harus dilakukan untuk meningkatkan, atau memperbaiki,
pendapatan dan standar kehidupan warga yang terkena dampak akibat kegiatan
pengadaan tanah ini
3. Permukiman kembali penduduk (resettlement)
Seluruh proyek yang memerlukan pengadaan lahan harus
mempertimbangkan adanya kemungkinan pemukiman kembali penduduk sejak tahap
awal proyek. Bilamana pemindahan penduduk tidak dapat dihindarkan, rencana
pemukiman kembali harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga penduduk yang
terpindahkan mendapat peluang ikut menikmati manfaat proyek. Hal ini termasuk
mendapat kompensasi yang wajar atas kerugiannya, serta bantuan dalam
pemindahan dan pembangunan kembali kehidupannya di lokasi yang baru.
Penyediaan lahan, perumahan, prasarana dan kompensasi lain bagi penduduk yang
dimukimkan jika diperlukan dan sesuai persyaratan
Pengadaan tanah dan permukiman kembali atau land acquisition and resettlement
untuk kegiatan RPI2-JM mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini:
1. Transparan : Sub proyek dan kegiatan yang terkait harus diinformasikan secara
transparan kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak. Informasi harus
mencakup, antara lain, daftar warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman, dan
lainnya) yang akan terkena dampak.
2. Partisipatif : Warga yang berpotensi terkena dampak/dipindahkan (DP) harus terlibat
dalam seluruh perencanaan proyek, seperti: penentuan batas lokasi proyek, jumlah
dan bentuk kompensasi, serta lokasi tempat permukiman kembali.
3. Adil : Pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.
Masyarakat tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai,
dan asetnya. Biaya terkait lainnya, seperti biaya pindah, pengurusan surat tanah, dan
pajak, harus ditanggung oleh pemrakarsa kegiatan. Masyarakat harus diberi
kesempatan untuk mengkaji rencana pengadaan tanah ini secara terpisah di antara
mereka sendiri dan menyetujui syarat-syarat dan jumlah ganti rugi dan/atau
permukiman kembali.
4. Warga yang terkena dampak harus sepakat atas ganti rugi yang ditetapkan atau jika
memungkinkan, secara sukarela mengkontribusikan/hibah sebagian tanahnya pada
kegiatan. Dalam kasus dimana tanah dihibahkan secara sukarela, DP akan melakukan
musyawarah dalam forum stakeholder untuk menjamin bahwa hibah benar-benar
dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun;
5. Kontribusi/hibah tanah secara sukarela hanya dapat dilakukan bila:
DP mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga
tanah miliknya (dibuktikan dengan perhitungan yang disepakati kedua belah
pihak); dan
Tanah yang dihibahkan nilainya ≤ 10 % dari nilai tanah, bangunan atau aset lain
yang produktif dan nilainya < 1 (satu) juta Rupiah.
Kesepakatan kontribusi sukarela tersebut harus ditandatangani kedua belah pihak
setelah DP melakukan diskusi secara terpisah. Safeguard Monitoring Team atau SMT harus
dapat menjamin bahwa tidak ada tekanan pada DP untuk melakukan kontribusi tanah
secara sukarela. Persetujuan tersebut harus didokumentasikan secara formal;
1. Kegiatan investasi harus sudah menentukan batas-batas lahan yang diperlukan,
jumlah warga yang terkena dampak, informasi umum mengenai pendapatan serta
status pekerjaan DP, dan harga tanah yang berlaku yang diusulkan oleh pemrakarsa
kegiatan dan didukung oleh NJOP, sebelum pembebasan tanah (dengan atau tanpa
pemukiman kembali/resettlement) dilakukan;
2. Kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak pada lebih dari 200 orang atau 40 KK,
atau melibatkan pemindahan lebih dari 100 orang atau 20 KK, harus didukung dengan
Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau RTPTPK yang
menyeluruh.
3. Jika kegiatan investasi hanya akan mengakibatkan dampak pada kurang dari 200
LAPORAN ANTARA 4-
7
melakukan pemindahan penduduk secara temporer (sementara) selama masa
konstruksi, harus didukung dengan RTPTPK sederhana.
4. RTPTPK menyeluruh atau RTPTPK sederhana dan pelaksanaannya menjadi tanggung
jawab pemrakarsa kegiatan, dimonitor oleh Tim Pemantauan.
5. Perhitungan ganti rugi bagi DP. Terdapat beberapa alternatif cara untuk menghitung
ganti rugi, yakni:
Perhitungan ganti rugi tanah berdasarkan nilai pasar tanah di lokas yang memiliki
karakteristik ekonomi yang serupa pada saat pembayaran kompensasi ganti rugi
dilakukan;
Perhitungan kompensasi ganti rugi bangunan berdasarkan nilaipasar bangunan
dengan kondisi yang serupa di lokasi yang sama;
Perhitungan ganti rugi untuk tanaman berdasarkan nilai pasar tanaman yang sama
ditambah dengan biaya atas kerugian non material lainnya; dan
Perhitungan ganti rugi untuk aset lainnya diganti dengan aset yang paling tidak
sama, atau ganti rugi uang tunai setara dengan harga untuk memperoleh aset yang
sama.
Pihak yang dapat terkena dampak pembebasan tanah dan/atau pemukiman
dipindahkan dalam kegiatan sub proyek dapat berupa warga/individu, entitas, atau
badan hukum. Adapun bentuk dampak yang diakibatkan dapat berupa:
Dampak fisik, seperti dampak pada tanah, bangunan, tanaman dan aset produktif
lainnya; dan
Dampak non-fisik, seperti dampak lokasi, akses pada tempat kerja atau prasarana,
dan sebagainya.
6. Berkenanaan dengan hak hukum atas tanah, DP dapat dikelompokkan menjadi:
Warga yang memiliki hak atas tanah pada saat pendataan dilakukan, termasuk hak
adat;
Warga yang tidak memiliki hak atas tanah, akan tetapi menguasai/menggarap
lahan atau aset lannya (hak garap);
Warga yang menguasai tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah (hak
sewa);
Warga yang menguasai/menempati tanah/lahan tanpa landasan hukum ataupun
Warga yang mengelola tanah wakaf (tanah yang dihibahkan untuk kepentingan
agama).
Prosedur pelaksanaan pembebasan tanah dan permukiman kembali terdiri dari
beberapa kegiatan utama yang meliputi: penyiapan awal dari usulan kegiatan untuk
melihat apakah kegiatan yang bersangkutan memerlukan pembebasan tanah atau
kegiatan permukiman kembali atau tidak; pengklasifikasian/kategorisasi dampak
pembebasan tanah dan permukiman kembali dari sub proyek yang diusulkan sesuai tabel
V.4 perumusan surat pernyataan bersama (jika melibatkan hibah sebidang tanah secara
sukarela) atau perumusan Rencana Tindak Pembebasan Tanah dan Permukiman Kembali
(RTPTPK) sederhana atau menyeluruh sesuai kebutuhan didukung SK Bupati.
Pembebasan tanah dan permukimkan kembali yang telah dilaksanakan sebelum
usulan sub proyek disampaikan, harus diperiksa kembali (recheck) dengan tracer study.
Tracer study ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pembebasan tanah telah
sesuai dengan standar yang berlaku, tidak mengakibatkan kondisi kehidupan DP menjadi
lebih buruk, dan mekanisme penanganan keluhan dilaksanakan dengan baik.
Kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan perlidungan social seperti
konsultasi masayarakat, Pemindahan Penduduk/Kompensasi ke masayarakat dan
Permukiman Kembali diantaranya sebagai berikut :
1. Pembangunan Rusunawa
2. Normalisasi Sungai
3. Pembangunan Kawasan RSH
Tabel 8.2.
Kategori Pendugaan Safeguard Sosial
Kategori Dampak Persyaratan
A
Sub Proyek tidak melibatkan kegiatan pembebasan tanah
1. Sub Proyek seluruhnya menempati tanah negara
Surat Pernyataan dari
pemrakarsa kegiatan
2. Sub Proyek seluruhnya atau sebagian menempati tanah yang dihibahkan secara sukarela
Laporan yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan
B
Pembebasan tanah secara sukarela:
Hanya dapat dilakukan bila lahan produktif yang
dihibahkan < 10% dan memotong < bidang lahan sejarak 1,5 m dari batas kavling atau garis sepadan bangunan, dan bangunan atau aset tidak bergerak lainnya yang dihibahkan
Surat Persetujuan yang
disepakati dan ditandatangai bersama antara pemrakarsa kegiatan dan warga yang
LAPORAN ANTARA 4-
9
Kategori Dampak Persyaratan
senilai < Rp. 1 Juta. dengan sukarela
C
Pembebasan tanah berdampak pada < 200 orang atau 40 KK atau < 10% dari aset produktif atau melibaykan pemindahan warga sementara selama masa konstruksi
RTPTPK sederhana
D Pembebasan tanah berdampak pada > 200 orang atau
memindahkan warga > 100 orang RTPTPK menyeluruh
Pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya secara lokasi di Kabupaten Tanah
Laut tidak banyak mengalami kendala dan hambatan terhadap masyarakat. Hal ini
dikarenakan lokasi pembangunan kegiatan cipta karya sebagian besar milik Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada masalah yang berarti kalaupun ada lahan yang
bukan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu sudah dibebaskan dengan cara
dibayarkan kepada pemilik lahan tersebut. Hanya saja Untuk meminimalisir terjadinya
konflik dengan masyarakat penerima dampak maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
melakukan sosialisasi melalui pemerintah kelurahan / desa setempat dimana lokasi
kegiatan Cipta Karya dilaksanakan dan melibatkan warga setempat yang belum
mendapatkan pekerjaan untuk bekerja sesuai keahliannya.
Perlindungan Sosial Pada Tahap Pasca Pelaksanaan Pembangunan
Output kegiatan pembangunan seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat.
Manfaat tersebut diharapkan minimal dapat terlihat secara kasat mata dan secara
sederhana dapat terukur, seperti
1. Kemudahan mencapai lokasi pelayanan infrastruktur dimana akses jalan masyarakat
dapat dilalui, selain itu waktu tempuh yang menjadi lebih singkat, hingga
pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk untuk mendapatkan akses
pelayanan tersebut.
2. Terciptanya Lingkungan Permukiman yang aman, dan nyaman. Dimana lingkungan
permukiman masayarakat menjadi lebih sehat akibat pembanguanan infrastruktur di
sekitar lingkungan masyarakat dan terwujudnya kelayakan sanitasi lingkungan.
3. Meningkatnya taraf hidup perekonomian masayarakat, dimana adanya recruitment
lowongan kerja akan dibuka dan jumlah tenaga kerja setempat yang dapat terserap
dapat digunakan dalam operasional
4. Berkurangnya kecemburuan social di masayrakat, dimana dengan adanya
pembangunan infrastruktur yang merata di setiap kawasan, warga masyarakat
mendapatkan fasilitas yang sama.
Output kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya harus memberi manfaat bagi
masyarakat. Manfaat tersebut diharapkan minimal dapat terlihat secara kasat mata dan
secara sederhana dapat terukur, seperti kemudahan mencapai lokasi pelayanan
infrastruktur, waktu tempuh yang menjadi lebih singkat, hingga pengurangan biaya yang
harus dikeluarkan oleh penduduk untuk mendapatkan akses pelayanan tersebut.
4.2 ANALISIS EKONOMI
Sesuai PP no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
diamanatkan bahwa kewenangan pembangunan bidang Cipta Karya merupakan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten/Kota terus didorong untuk meningkatkan belanja pembangunan prasarana
Cipta Karya agar kualitas lingkungan permukiman di daerah meningkat. Di samping
membangun prasarana baru, pemerintah daerah perlu juga perlu mengalokasikan
anggaran belanja untuk pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana yang
telah terbangun. Namun, seringkali pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal
dalam mendanai pembangunan infrastruktur permukiman.Pemerintah daerah cenderung
meminta dukungan pendanaan pemerintah pusat, namun perlu dipahami bahwa
pembangunan yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dilakukan sebagai stimulan dan
pemenuhan standar pelayanan minimal.Oleh karena itu, alternatif pembiayaan dari
masyarakat dan sektor swasta perlu dikembangkan untuk mendukung pembangunan
bidang Cipta Karya yang dilakukan pemerintah daerah.
Dengan adanya pemahaman mengenai keuangan daerah, diharapkan dapat
disusun langkah-langkah peningkatan investasi pembangunan bidang Cipta Karya di
daerah. Pembahasan aspek pembiayaan dalam RPIJM pada dasarnya bertujuan untuk:
a. Mengidentifikasi kapasitas belanja pemerintah daerah dalam melaksanakan
LAPORAN ANTARA 4-
11
b. Mengidentifikasi alternatif sumber pembiayaan antara lain dari masyarakat dan
sektor swasta untuk mendukung pembangunan bidang Cipta Karya,
c. Merumuskan rencana tindak peningkatan investasi pembangunan bidang Cipta
Karya.
4.2.1 ARAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BIDANG CIPTA KARYA
Pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya perlu memperhatikan arahan
dalam peraturan dan perundangan terkait, antara lain :
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah
diberikan hak otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, kecuali urusan pemerintahan
yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah: untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah,
pemerintah daerah didukung sumber-sumber pendanaan meliputi Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain yang Sah, serta Penerimaan
Pembiayaan. Penerimaan daerah ini akan digunakan untuk mendanai pengeluaran
daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan: Dana
Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi
Khusus. Pembagian DAU dan DBH ditentukan melalui rumus yang ditentukan
Kementerian Keuangan.Sedangkan DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus
yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional.Penentuan lokasi dan
besaran DAK dilakukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria
teknis.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota: Urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemerintahan
daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang
umum.Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman
pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh
Pemerintah.Urusan wajib pemerintahan yang merupakan urusan bersama diserahkan
kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana,
serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah: Sumber pinjaman
daerah meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank
dan Non-Bank, serta Masyarakat. Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan
pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, tetapi diteruskan melalui pemerintah
pusat. Dalam melakukan pinjaman daerah Pemda wajib memenuhi persyaratan:
a. total jumlah pinjaman pemerintah daerah tidak lebih dari 75% penerimaan APBD
tahun sebelumnya;
b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan
pinjaman yang ditetapkan pemerintah paling sedikit 2,5;
c. persyaratan lain yang ditetapkan calon pemberi pinjaman;
d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari
pemerintah;
e. pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan
DPRD.
6. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (dengan perubahan Perpres 13/2010 & Perpres
56/2010): Menteri atau Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur. Jenis infrastruktur permukiman yang dapat dikerjasamakan
dengan badan usaha adalah infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah
permukiman dan prasarana persampahan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (dengan perubahan Permendagri 59/2007 dan Permendagri
21/2011): Struktur APBD terdiri dari:
a. Pendapatan daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
dan Pendapatan Lain yang Sah.
LAPORAN ANTARA 4-
13
c. Pembiayaan Daerah meliputi: Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan
Pengeluaran.
8. Peraturan Menteri PU No. 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur: Kementerian PU menyalurkan DAK untuk
pencapaian sasaran nasional bidang Cipta Karya, Adapun ruang lingkup dan kriteria
teknis DAK bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :
a. Bidang Infrastruktur Air Minum
DAK Air Minum digunakan untuk memberikan akses pelayanan system
penyediaan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dikawasan
kumuh perkotaan dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan
permukiman nelayan. Adapun kriteria teknis alokasi DAK diutamakan untuk
program percepatan pengentasan kemiskinan dan memenuhi sasaran/target
Millenium Development Goals (MDGs) yang mempertimbangkan:
- Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;
- Tingkat kerawanan air minum.
b. Bidang Infrastruktur Sanitasi
DAK Sanitasi digunakan untuk memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah,
persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses
pemberdayaan masyarakat. DAK Sanitasi diutamakan untuk program
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi sasaran/target MDGs
yang dengan kriteria teknis:
- kerawanan sanitasi;
- cakupan pelayanan sanitasi.
9. Peraturan Menteri PU No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenanangan Pemerintah dan
Dilaksanakan Sendiri.
Dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dana APBN, Kementerian PU
membentuk satuan kerja berupa Satker Tetap Pusat, Satker Unit Pelaksana Teknis
Pusat, dan Satuan Non Vertikal Tertentu. Rencana program dan usulan kegiatan yang
diselenggarakan Satuan Kerja harus mengacu pada RPIJM bidang infrastruktur
penyelenggaraan urusan kementerian yang dilaksanakan di daerah dalam rangka
keterpaduan pembangunan wilayah dan pengembangan lintas sektor.
Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkup sumber dana
kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya yang dibahas dalam RPIJM meliputi :
1. Dana APBN, meliputi dana yang dilimpahkan Ditjen Cipta Karya kepada Satuan Kerja
di tingkat provinsi (dana sektoral di daerah) serta Dana Alokasi Khusus bidang Air
Minum dan Sanitasi.
2. Dana APBD Provinsi, meliputi dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) dan dana
lainnya yang dibelanjakan pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur
permukiman dengan skala provinsi/regional.
3. Dana APBD Kabupaten/Kota, meliputi dana daerah untuk urusan bersama (DDUB)
dan dana lainnya yang dibelanjakan pemerintah kabupaten untuk pembangunan
infrastruktur permukiman dengan skala kabupaten/kota.
4. Dana Swasta meliputi dana yang berasal dari skema kerjasama pemerintah dan
swasta (KPS), maupun skema Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Dana Masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.
6. Dana Pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
Dana-dana tersebut digunakan untuk belanja pembangunan, pengoperasian dan
pemeliharaan prasarana yang telah terbangun, serta rehabilitasi dan peningkatan
prasarana yang telah ada. Oleh karena itu, dana-dana tersebut perlu dikelola dan
direncanakan secara terpadu sehingga optimal dan memberi manfaat yang
sebesar-besarnya bagi peningkatan pelayanan bidang Cipta Karya
Sebagai langkah konkrit dalam pembiayaan investasi infrastruktur sebagai fokus
pembangunan sesuai amanat APBN, maka Pemerintah telah menerbitkan PP No. 1/2008
tentang Investasi Pemerintah, menggantikan PP No. 8/2007. PP No. 1/2008 memberikan
perluasan cakupan investasi, tidak hanya dalam bentuk Public Private Partnership (PPP),
melainkan investasi dalam bentuk surat berharga maupun investasi langsung.
Investasi Pemerintah yang dimaksudkan PP No.1/2008 adalah penempatan
sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat
berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam
LAPORAN ANTARA 4-
15
Investasi Pemerintah sesuai PP No. 1/2008 ini dilaksanakan oleh Badan Investasi
Pemerintah dalam bentuk :
a) investasi surat berharga, dan/atau,
b) investasi langsung.
Badan ini merupakan unit pelaksana investasi atau badan hukum yang
kegiatannya melaksanakan investasi pemerintah berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan.Investasi langsung dimaksudkan utuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya. Investasi langsung dilakukan dengan cara :
a) public private partnership (PPP) yang dapat berupa Badan Usaha dan/atau BLU,
b) non public private partnership yang dapat berupa Badan Usaha, BLU, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing,
c) investasi langsung meliputi bidang infrstruktur dan bidang lainnya yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Sedangkan investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham
dan/atau surat utang melalui pasar modal, yakni melalui :
Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan
perusahaan.
Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang
diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain (hanya dapat dilakukan
apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali).
Dalam pelaksanaannya, investasi dengan kedua cara tersebut dilakukan
didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh
Penasihat Investasi. Investasi dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk
mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini diperlihatkan pada gambar berikut:
Dari urtaian diatas, maka dalam rencana pembiayaan investasi di bidang Cipta
Karya, terdapat beberapa sumber dana untuk pembiayaan investasi tersebut, antara lain
melalui :
1. APBN
2. APBD Provinsi
3. APBD Kabupaten/Kota
4. Pinjaman Perbankan
6. Coorporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan
7. Dana Hibah
8. Dan Lain-Lain
4.2.2 ARAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BIDANG CIPTA KARYA
A. Komponen Penerimaan Pendapatan
Sebagaimana dijelaskan dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
menjelaskan bahwa kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan
merupakan hak daerah dalam 1 (satu ) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang
dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai arti pendapatan yang dianggarkan
tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain
dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ini ditetapkan berdasarkan perkiraan terukur
secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan.
Pendapatan daerah dikelompokan kedalam sumber-sumber penerimaan daerah
yang terdiri dari sumber penerimaan :
a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),
b. Dana Perimbangan dan,
c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah.
Termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah :
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Yang Sah.
B. Komponen Pengeluaran Belanja
Selanjutnya Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun
2006,untuk belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan
pemerintah daerah selama tahun anggaran yang berkenaan dan dialokasikan dalam 2 (
LAPORAN ANTARA 4-
17
a. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait
secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari ini terdiri dari :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kabupaten dan Pemerintah
Desa
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kabupaten dan
Pemerintah Desa
8. Belanja Tidak Terduga
Belanja langsung terdiri dari :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
C. Komponen Pembiayaan
Komponen ini adalah sebagai pengimbang perbedaaan antara pendapatan dan
biaya dalam anggaran daerah. Unsur utama dalam komponen ini adalah sisa anggaran
tahun lalu yang merupakan saving keuangan daerah. Komponen Pembiayaan tersebut
adalah :
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman Daerah
4.3 ANALISIS LINGKUNGAN
4.3.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
A. Pemahaman KLHS
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan
membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Program KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan instrument yang
relative baru dikembangkan sebagai penguatan program untuk menyusun rumusan
kebijakan rencana program berorientasi pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu konsep
pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup
dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal itu mengacu pada pertumbuhan dengan
memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan kemampuan institusi masyarakat
didalam melaksanakan pembangunan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
merupakan dasar didalam menyusun program program pembangunan. Disamping itu
pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi
lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan.
Fungsi dari KLHS adalah untuk :
1. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan melalui penyusunan
Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meningkatkan manfaat
LAPORAN ANTARA 4-
19
2. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP, mengurangi kemungkinan
kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan
kebijakan, rencana, atau program pembangunan;
3. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi
atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi
kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
Gambar 8.2. Perbedaan KLHS dengan AMDAL
Beberapa manfaat dari disusunnya KLHS adalah sebagai berikut :
1. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan;
2. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian
sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia;
3. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang
pengambilan keputusan yang lebih tinggi;
4. Mencegah kesalahan investasi berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang
tidak berkelanjutan sejak dini;
5. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak
(stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan
partisipasi;
6. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin
berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;
7. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan
LAPORAN ANTARA 4-
21
KLHS menjadi instrumen penting dalam perencanaan penataan ruang karena
pengambil keputusan harus semakin mempertimbangkan dampak jangka panjang dan
kumulatif dari berbagai proyek. Selain itu integrasi aspek lingkungan yang saat ini
menggunakan instrumen AMDAL tidak mampu untuk mengukur dampak kumulatif
secara sistematis. KLHS dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik
dan dapat memperkuat serta mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana
kegiatan. Secara rinci tujuan dari penyusunan KLHS adalah :
a. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam
penyusunan kebijakan, rencana, atau program (KRP) ;
b. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP ;
c. Membantu mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan
dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha
atau kegiatan.
B. Kaidah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak
lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan- tujuan keberlanjutan
pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program
pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah
pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan
sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (selfassessment) agar keseluruhan
proses bersifat lebih efisien dan efektif. Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan
yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah :
• Keterkaitan (interdependency)
• Keseimbangan (equilibrium)
• Keadilan (justice)
Keterkaitan (interdependency) menekankan pertimbangan keterkaitan antara
satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara
satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global,
keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.
Keseimbangan (equilibrium) menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek,
diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan
pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang
dengan pengelolaan dampaknya,dan lain sebagainya.
Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana
dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap
sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada
sekelompok orang tertentu.
Atas dasar kaidah diatas, maka penerapan KLHS terhadap KRP bertujuan untuk
mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut :
• Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah KRP?
• Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat KRP dengan lingkungan
hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam?
• Apa lingkup interaksi tersebut? Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan
kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup? Apakah interaksi tersebut
akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat?
• Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya
dikembangkan?
• Apabila KRP mengintegrasikan seluruh upaya pengendalian atau mitigasi atas
efek-efek tersebut dalam muatannya, apakah masih timbul pengaruh negatif KRP tersebut
terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan secara umum.
C. Metode Penyusunan KLHS
Ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penyusunan KLHS harus meliputi hal hal
sebagai berikut :
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
LAPORAN ANTARA 4-
23
KLHS adalah proses untuk mempengaruhi penentuan pilihan-pilihan
pembangunan yang diusulkan dalam KRP yang terutama dilakukan melalui kegiatan
konsultasi dan dialog secara tepat dan relevan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan KLHS
harus sesuai dengan kebutuhan tanpa terpaku dalam metoda dan prosedur yang baku.
Melalui penyusunan KLHS maka semua kebijakan, rencana dan program yang akan
dilakukan oleh Pemerintah Kota akan mendorong lahirnya pemikiran untuk alternatif –
alternatif baru pembangunan melalui tahapan atau proses sebagai berikut :
a. Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang perlu
dipertimbangkan dalam KRP;
b. Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu
yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi;
c. Mengkaji paling tidak dampak kumulatif yang mendasar dari KRP dan memberi
masukan untuk optimalisasi.;
d. Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para
pengambil keputusan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS adalah
sebagai berikut :
a. Melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan.
b. Melakukan pengumpulan data, peta dan informasi terkait
c. Melakukan pekerjaan yang terkoordinasi untuk menjaring masukkan mengenai
pengembangan infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut
d. Melakukan survey dan observasi untuk kelengkapan data.
e. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil survey dan observasi.
f. Menyelenggarakan presentasi hasil evaluasi dan analisisnya.
Mekanisme penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan
dengan tahapan atau proses sebagai berikut :
1. Penapisan;
Penapisan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu
KRP perlu dilengkapi dengan KLHS atau tidak. Penentuan KRP telah memenuhi
kriteria pelaksanaan KLHS dilakukan melalui kesepakatan pihak-pihak yang
berkepentingan.
Pelingkupan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menetapkan nilai penting
KLHS, tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan kerincian
penulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal kapasitas
kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan metodologis
yang memenuhi kaidah ilmiah. Mengingat terbatasnya waktu dan sumber daya yang
tersedia, dalam kajian ini tidak dilakukan proses konsultasi publik.
3. Pengkajian;
Pengkajian adalah rangkaian langkah-langkah untuk melakukan kajian ilmiah,
pemetaan kepentingan, dialog dan konsultasi serta penemuan pilihan-pilihan
alternatif rumusan maupun perbaikan dan penyempurnaan terhadap rumusan yang
sudah ada. Tim kajian melakukan serangkaian diskusi dan konsultasi dengan para
pihak (stakeholders) terkait, khususnya dengan instansi pemerintah dan Lembaga
Swadaya Masyarakat.
4. Perumusan dan pengambilan keputusan
Perumusan dan pengambilan keputusan adalah rangkaian langkah-langkah
persetujuan rekomendasi hasil KLHS dan interaksi antar pihak berkepentingan dalam
rangka mempengaruhi hasil akhir KRP.
Keseluruhan hasil pengkajian ini secara lengkap dituangkan dengan jelas dan
sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman pembangunan berkelanjutan yang
LAPORAN ANTARA 4-
25
Gambar 8.3. Mekanisme Penyelenggaraan KLHSPada tahap analisa atau pengkajian, harus dilakukan serangkaian kajian dengan
menerapkan daftar uji pada setiap langkah proses KRP, meliputi : 1. Uji Kesesuaian Tujuan dan Sasaran KRP.
Kepentingan pengujian adalah untuk memastikan bahwa :
a) tujuan dan sasaran umum KRP memang jelas,
b) berbagai isu keberlanjutan maupun lingkungan hidup tercermin dalam tujuan dan
sasaran umum KRP,
c) sasaran terkait dengan keberlanjutan akan bisa dikaitkan langsung dengan
indikator-indikator pembangunan berkelanjutan,
d) keterkaitan KRP dengan KRP-KRP lain bisa dijelaskan dengan baik,
e) konflik kepentingan antara KRP dengan KRP-KRP lain segera bisa teridentifikasi.
2. Uji Relevansi Informasi yang Digunakan.
Kepentingan utama pengujian ini adalah bukan menilai kelengkapan dan validitas
data, tetapi identifikasi kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan yang
tersedia serta cara mengatasinya. Hal ini terasa penting ketika KRP diharuskan
memperhatikan kesatuan fungsi ekosistem dan wilayah-wilayah rencana selain
wilayah administratifnya sendiri.
Selanjutnya pengujian juga lebih mengutamakan relevansi informasi dan sumbernya
agar proses kerja bisa efektif namun tetap memperhatikan kendala-kendala
setempat.
3. Uji Pelingkupan Isu-isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan dalam KRP.
Pengujian ini ditujukan untuk memandu penyusun KRP memperhatikan isu-isu
lingkungan hidup maupun keberlanjutan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun
internasional, dan melihat relevansi langsung isu-isu tersebut terhadap wilayah
perencanaannya.
4. Uji Pemenuhan Sasaran dan Indikator Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.
Pengujian ini efektif bila konsep rencana sudah mulai tersusun, sehingga dapat
dilakukan penilaian langsung atas arahan-arahan rencana terhadap indikator-indikator
merupakan iterasi atau pengembangan dari uji yang dilakukan di awal proses
penyusunan KRP sebagaimana dijelaskan pada nomor 1. 5. Uji Penilaian Efek-efek yang Akan Ditimbulkan.
Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk dapat memperkirakan dimensi besaran
dan waktu dari efek-efek positif maupun negatif yang akan ditimbulkan. Bentuk
pengujian ini dapat disesuaikan dengan kemajuan konsep maupun ketersediaan data,
sehingga pengujian dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengujian secara
kuantitatif maupun kualitatif sama-sama bernilai apabila diikuti dengan verifikasi
berupa proses konsultasi maupun diskusi dengan pihak-pihak yang terkait.
6. Uji Penilaian Skenario dan Pilihan Alternatif.
Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk memperoleh pilihan alternatif yang
beralasan, relevan, realistis dan bisa diterapkan. Keputusan pemilihan alternatif bisa
dilakukan dengan sistem pengguguran (memilih satu opsi dan menggugurkan yang
lainnya) atau mengkombinasikan beberapa pilihan dengan penyesuaian.
7. Uji Identifikasi Timbulan Efek atau Dampak dampak Turunan maupun Kumulatif. Pengujian ini merupakan pengembangan dari jenis pengujian nomor 5, dimana
jenis-jenis KRP tertentu diperkirakan juga akan menimbulkan efek-efek atau
dampak-dampak lanjutan yang lahir dari dampak-dampak langsung yang ditimbulkan, maupun
akumulasi efek dalam jangka waktu panjang dan pada skala ruang yang besar.
Kelompok-kelompok pengujian ini bisa dilakukan dengan cara :
• mengemasnya dalam berbagai model daftar pertanyaan, misalnya model daftar uji
untuk menilai mutu dokumen, model daftar uji untuk menilai konsistensi muatan
KRP terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, model daftar uji untuk menuntun
pengambil keputusan mempertimbangkan kriteria-kriteria dan opsi-opsi yang
mendukung keberlanjutan, dan lain sebagainya
• melakukannya secara berurut sejalan dengan proses persiapan, pengumpulan
data, kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana
• melakukannya secara berulang/iteratif
• mengembangkan atau memodifikasi jenis pertanyaan-pertanyaannya sesuai
LAPORAN ANTARA 4-
27
Gambar 8.4. Kerangka Kerja dan Metodologi KLHSDalam pelaksanaannya, penyusunan KLHS dilakukan terhadap 3 kondisi KRP, yaitu
KRP yang sudah disusun atau dilaksanakan sebelumnya, KRP yang masih dalam proses
perencanaan atau penyusunan dan yang terakhir adalah KRP yang sedang dalam proses
penyusunan. Pendekatan pelaksanaan KLHS terhadap ketiga kondisi KRP tersebut
Gambar 8.5. Integrasi Pelaksanaan KLHS dalam Perencanaan KRP
Gambar 8.6. Skema Alternatif Pelaksanaan Integrasi KLHS
D. Rencana Penyusunan KLHS Usulan Program
Berdasarkan hasil analisa pada Bab 6 sebelumnya, didapatkan rumusan beberapa
usulan program Cipta Karya tahun 2015-2019 yang akan direncanakan di Kabupaten Tanah
LAPORAN ANTARA 4-
29
perlu dilakukan studi KLHS terlebih dahulu. Proses penyusunan KLHS RPI2-JM dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Identifkasi Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan yang akan terlibat baik dalam proses penyusunan
KLHS maupun terkena dampak dari penerapan KRP, terdiri dari pemangku
kepentingan pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sebagai
berikut :
Dinas/Instansi/institusi Pemerintahan
Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P
Pejabat yang bertanggung jawab menyetujui K/R/P
Institusi lingkungan hidup
Institusi terkait lainnya
Institusi/Lembaga Non Pemerintahan
Dewan Perwakilan
LSM/Ormas
Perguruan Tinggi/Akademisi/Asosiasi Profesi
Asosiasi/Dunia Usaha
Lembaga yang mewakili masyarakat terkena
dampak
Seberapa besar keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan
KLHS dilihat keterkaitan peran dan fungsi sebagaimana tertuang dalam tupoksi
masing-masing SKPD terkait, serta potensi dampak yang kan diterima SKPD tersebut
atas penerapan KRP tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksinya. Kajian
keterlibatan SKPD dalam KLHS adalah sebagai berikut :
Tabel 8.3.
Identifikasi Pemangku Kepentingan Instansi Pemerintah
No Instansi Alasan Rekomendasi
1. Bupati Kab. Tanah Laut
Sebagai pengambil kebijakan Terlibat dalam
penyusunan KLHS
2. DPRD Sebagai pengambil kebijakan Terlibat dalam
penyusunan KLHS 3. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Menyusun dan melaksanakan di bidang perencanaan pembangunan daerah
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS 4. Badan Lingkungan
Hidup
penyusuanan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS 5. Badan Pemberdayaan
Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi serta pergerakan masyarakat.
No Instansi Alasan Rekomendasi
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyusunan dan pelaksanaan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi, dan
kemasyaraktan serta politik dalam negeri.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
7. Badan Kepegawaian Daerah
Tugas membantu Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negri Sipil, yang meliputi pengadaan, seleksi dan mutasi, pengembangan, pembinaan dan
kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
8. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Kota dan Kebersihan
Penyusunan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan Kebersihan, keindahan kota dan capaian SPM
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyusunan dan pelaksanaan di bidang informasi dan pengaduan, perijinan, jasa usaha dan perijinan tertentu.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS 10. Dinas Pendidikan Tugas pembantuan di bidang pembinaan
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan informal serta pengelolaan sarana dan prasarana.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
11. Dinas Kesehatan tugas pembantuan di bidang kesehatan keluarga, pengendalian penyakitdan penyehatan lingkungan
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
12. Dinas Sosial Tugas pembantuan di bidang social, rehabilitasi social dan pelayanan serta pemberdayaan 30ndust.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tugas pembantuan di bidang penempatan, perluasan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta
pembinaan transmigrasi.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tugas pembantuan di bidang pembinaan system transportasi, lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan danau, serta komunikasi dan informatika
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan
tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi 30ndustry logam, mesin, elektronika dan aneka 30ndustry kimia, argo dan hasil hutan serta perdagangan
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
16. Dinas, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga
tugas pembantuan di bidang pembinaan kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
17. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Banguanan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bukan Pendapatan Asli Daerah, anggaran dan belanja, akutansi dan asset daerah
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
18. Dinas Pertanian Perkebunan Perikanan dan Peternakan
Tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan
holtikultura, perkebunan, serta peternakan
LAPORAN ANTARA 4-
31
No Instansi Alasan Rekomendasi
dan kesehatan hewan
19. Dinas Kehutanan Tugas pembantuan di bidang kehuutanan yag meliputi planologi kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Tugas pembantuan di bidang pembinaan kelembagaan, usaha, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
Tidak Terlalu Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, perencanaan dan perkembangan kependuduk serta pengelolaan data dan informasi.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
22. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
tugas pembantuan dibidang perumahan, bidang penatan ruang dan bangunan, bidang pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan serta bidang kebersihan.
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
23. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan Pengairan
Tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pembinaan Konstruksi
Terlibat Dalam Penyusunan KLHS
2. Identifkasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
Pada prinsipnya semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan
dalam rangka memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu pencapaian
tujuan tersebut dapat Berdasarkan usulan program kegiatan sebagaimana yang
diaparkan pada bab 6, maka terdapat beberapa usulan program yang masuk kategori
dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang perlu dilakukan kajian atau
penyusunan KLHS sebelum diimplementasikan, yaitu terdiri dari : a. Pertanahan & Tata Ruang
1) Kesenjangan Perkembangan Wilayah & struktur Ruang
2) Pemanfaatan Lahan Basah Untuk Budidaya Perikanan di Sepanjang Jaringan
Irigasi
3) Perubahan Kawasan Lindung Mangrove, Sempadan Pantai, Sempadan
Sungai dll
4) Optimalisasi Pemanfaatan DAS
5) Penataan Sempadan Sungai Perubahan Rona Lingkungan Pada Kawasan
DAS
7) Penanganan & Pengelolaan Daerah Tangkapan Resapan Air
8) Pengendalian Pemanfaatan Lahan Gambut dengan ketebalan > 3 m yang
tidak sesuai daya dukungnya
9) Penurunan Ruang Terbuka Hijau (Permukiman)
10) Permasalahan Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan
11) Berkurangnya luasan lahan pertanian tanaman pangan & holtikultura
12) Pemantapan Kawasan Hutan
13) Penyelesaian Kegiatan Non Kehutanan dalam Kawasan Hutan (Forest-Land
Tenure)
b. Ekonomi Wilayah
1) Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat di Wilayah Perdesaan &
Perkotaan
2) Berkurangnya peluang usaha masyarakat kecil karena eksploitasi sumber
daya yang tidak berkelanjutan
3) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Wilayah & pengembangan
potensi ekonomi sektoral & geografi
4) Belum optimalnya kesempatan kerja serta daya saing & industri hilir masih
rendah
5) Penurunan/Rendahnya Produksi Pertanian karena anomali iklim, OPT
(organisme pengganggu tanaman), terbatasnya penerapan teknologi,
terbatasnya Prastan & alih fungsi lahan c. Infrastruktur Wilayah
1) Belum optimalnya Penanganan & Pengelolaan air bersih dan Sanitasi
2) Keterbatasan Akses Transportasi Darat
3) Kurang Optimalnya Pemanfaatan Transportasi Sungai (pendangkalan)
4) Belum Berkembangnya MRT (mass rapid transportation) untuk Transportasi
Umum
5) Terdapatnya hambatan samping jalan Raya/Bahu Jalan
6) Belum optimalnya jaringan listrik
7) Belum optimalnya jaringan komunikasi
8) Belum optimalnya jaringan irigasi & drainase
LAPORAN ANTARA 4-
33
1) Perubahan Perilaku & Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
2) Migrasi Penduduk pada Kawasan Cepat Tumbuh
3) Kualitas SDM masih rendah
4) Belum Terkendalinya Pertumbuhan & Penyebaran Penduduk
e. Dampak Lingkungan
1) Terjadinya Pemanasan global
2) Terjadinya Banjir karena pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan
lingkungan
3) Sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan
4) Perubahan Ekosistem karena pengurugan rawa/ pengeringan lahan
5) Penurunan Kualitas & Kuantitas Air Tanah
6) Erosi & Perambahan Hutan
7) Pencemaran Lingkungan akibat Aktifitas Tambang, Industri & Transportasi
f. Kelembagaan
1) Keterbatasan Informasi & Promosi Potensi Daerah
2) Belum berkembangnya koperasi/Bumdes
3) Belum optimalnya koordinasi antar lembaga
3. Identifkasi KRP
Berdasarkan usulan program kegiatan sebagaimana yang dipaparkan pada bab 6,
maka terdapat beberapa usulan program yang masuk kategori dalam Kebijakan, Rencana
dan Program (KRP) yang perlu dilakukan kajian atau penyusunan KLHS sebelum
diimplementasikan, yaitu terdiri dari :
Tabel 8.4.
Identifikasi KRP
No
Komponen
Kebijakan/Rencana/Program Kegiatan Lokasi
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
a. Optimalisasi Penunjang TPA
Bakunci
Rencana Pembangunan /
Penambahan Fasilitas TPA Bakunci
Kota Pelaihari
b. Pembangunan PS Air Limbah di
Kawasan RSH Kota Bati Bati Rencana Pembangunan PS Air
Limbah skala lingkungan
Kec. Bati – Bati dan Kec. Pelaihari
No
Komponen
Kebijakan/Rencana/Program Kegiatan Lokasi
c. Pembangunan Prasarana Sarana (PS) TPS 3R
Pembangunan Prasarana
Sarana TPS 3R
Desa Tabanio, Kota Pelaihari , Ds Batakan,
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Infrastruktur Permukiman Kawasan
Kumuh
Kawasan Tabanio, Kec. Takisung
Kota Pelaihari
b. Infrastruktur Kws. Penunjang Metropolitan Kawasan Kumuh Nelayan
Rencana Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kws. Penunjang Metropolitan Banjar Bakula
Kawasan Sawahan dan Perintis
Kaw. Jorong
Kumuh Nelayan Kaw. Muara Asam-Asam
Desa Banyu Hirang, Kec. Bati-Bati
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
a. Tata Ruang
Dukungan Percontohan RTH
Kijang Mas Permai Kota
Pelaihari Tahap II
Pembangunan RTH Hasan
Basri Tahap II
Raperda perumahan permukiman
Rencana Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan
Penataan Revitalisasi Kawasan
Pantai Takisung
LAPORAN ANTARA 4-
35
NoKomponen
Kebijakan/Rencana/Program Kegiatan Lokasi
b. Revitalisasi Jaringan Pipa PDAM
Perpipaan dan Aksesoris
Pembangunan IPA Baja Kap
20L/Dtk dan Bangunan
Penunjang IKK Jorong Kab.
Tanah Laut
Pembuatan Bangunan IPA Air
Minum
Pembangunan IPA - Jar
Distribusi/ SR/ HU Rencana Pembangunan /
Peningkatan / perbaikan Sarana dan Prasarana Jaringan Pipa PDAM
Kawasan Kurau, Kota
Pelaihari Jorong
Kota Pelaihari
Ds Batakan-Tj Dewa
Untuk bahasan KLHS dalam RPI2-JM ini hanya sampai pada tahap identifikasi KRP
yang diperkirakan akan berdampak atau berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan,
mengingat pembahasan KLHS merupakan suatu kajian tersendiri yang harus dilakukan
dengan seksama dan mendalam serta dikaji secara komprehensif dengan melibatkan
pemangku kepentingan terkait, demikian pula pembahasannya dilakukan secara
bertahap dalam beberapa kali forum focus group discussion (FGD). Jika dipaksakan
pembahasan pada penyusunan dokumen RPI2-JM ini maka selain prosesnya tidak
memungkinkan dilakukan secara intensif dan komprehensif, juga waktu pembahasannya
sangat terbatas dan pada akhirnya output yang diharapkan tidak akan maksimal dan
akurat menghasilkan rekomendasi perbaikan KRP yang diharapkan. Untuk itu dengan
telah teridentifikasinya beberapa KRP yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap
pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan studi KLHS lebih lanjut terhadap KRP
tersebut.
Sebagai gambaran awal untuk menuju ke studi KLHS, usulan Program dalam
RPIJM yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan dilakukan
penapisan untuk masing-masing sektor dengan mempertimbangkan isu pokok:
1) Perubahan iklim,
2) Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati,
3) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan,
4) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam,
5) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan,
6) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan
sekelompok masyarakat; dan/atau,
Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Isu-isu tersebut
menjadi kriteria apakah rencana/program yang disusun teridentifikasi menimbulkan
resiko atau dampak terhadap isu-isu tersebut.
Tabel 8.5.
Kreteria Penapisan Usulan Program / Kegiatan Bidang Cipta Karya Di Kab. Tanah Laut
No Kreteria
Penilaian
Uraian Pertimbangan Kesimpulan
(Signifikan/Tidak Signifikan)
1. Perubahan Iklim
-
Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat mempengaruhi Kabupaten Tanah Laut yang berbukit dan terdapat pesisir, maka Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Kerusakan, kemerosotan, dan/kepunahan keanekaragaman hayati 3. Peningkatan intensitas
dan cakupan wilayah Tanah Laut yang sebagian berkontur dengan adanya kegiatan tersebut sebaliknya akan mengantisipasi adanya bencana banjir, dan longsor, sedangkan kegiatan yang lain tidak terdapat kegiatan yang dapat menyebabkan kekeringan, atau kebakaran huta/lahan.
4. Penurunan mutu dan
kelimpahan sumber
daya alam -
Tidak terdapat jenis kegiatan yang dapat menyebabkan Penurunan mutu dan
kelimpahan sumber daya alam. 5. Peningkatan alih fungsi
kawasan hutan bagian kawasan alami yang dimanfaatkan.
Pengaruh yang ditimbulkan bersifat sementara dan Tidak signifikan.
6. Peningkatan jumlah
penduduk miskin atau terancamnya
keberlanjutan
-