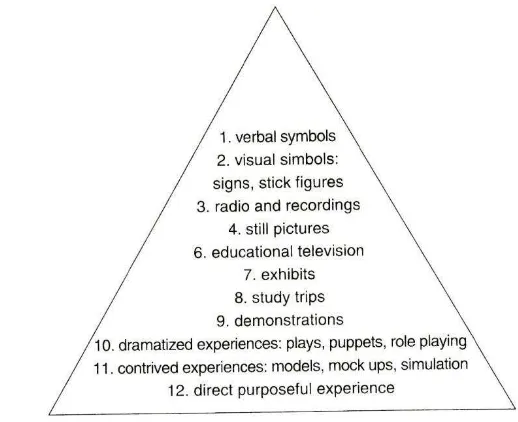PENGEMBANGAN KURIKULUM TEORI DAN PRAKTEK
KATA PENGANTAR
Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah maupun nasional. Semua orang berkepentingan dengan kurikulum, sebab kita sebagai orang tua, sebagai warga masyarakat, sebagai pemimpin formal ataupun informal selalu mengharapkan tumbuh dan berkembangnya anak, pemuda, dan generasi muda yang lebih baik, lebih cerdas, lebih berkemampuan. Kurikulum mempunyai andil yang cukup besar dalam melahirkan harapan tersebut.
Buku ini disusun dengan tujuan membantu para guru, dosen, instruktur, widyaiswara, para pengembang, pengelola, penentu kebijaksanaan, dan siapa saja yang terlibat dan berminat dalam pengembangan kurikulum; untuk menambah wawasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana pengembangan kurikulum. Meskipun dalam buku ini diusahakan menyajikan materi yang bervariasi dengan cara penyajian yang moderat, tetapi mungkin saja sajian ini belum bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Untuk itu penulis meminta maaf dan menantikan saran-saran bagi penyempurnaannya.
Isi buku ini merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya yang berjudul Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum, yang ditulis dengan bantuan Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Depdikbud, untuk kepentingan Program Pascasarjana. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pimpinan P2LPTK, serta para pimpinan teras Depdikbud, yang telah mendorong penulisan serta memberi izin menerbitkan kembali buku ini oleh lembaga di luar P2LPTK.
Bandung, 1997
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
BAB 1 Konsep Kurikulum
A. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan B. Konsep kurikulum
C. Kurikulum dan teori-teori pendidikan BAB 2 Teori Kurikulum 1
A. Apakah teori itu? B. Teori pendidikan C. Teori kurikulum
BAB 3 Landasan Filosofis dan Psikologis Pengembangan Kurikulum
A. Landasan filosofis B. Landasan psikologis
BAB 4 Landasan Sosial-Budaya, Perkembangan Ilmu dan Teknologi dalam Pengembangan Kurikulum
A. Pendidikan dan masyarakat B. Perkembangan masyarakat C. Perkembangan ilmu pengetahuan D. Perkembangan teknologi
E. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi BAB 5 Macam-Macam Model Konsep Kurikulum
A. Kurikulum subjek akademis B. Kurikulum humanistik
C. Kurikulum rekonstruksi sosial D. Teknologi dan kurikulum BAB 6 Anatomi dan Desain Kurikulum
BAB 7 Proses Pengajaran
A. Keseimbangan antara isi dan proses B. Isi dan kurikulum
C. Proses belajar D. Kesiapan belajar
E. Minat dan motif belajar BAB 8 Pengembangan Kurikulum
A. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum B. Pengembangan kurikulum
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi D. Artikulasi dan hambatan
E. Model-model pengembangan kurikulum BAB 9 Evaluasi Kurikulum
A. Evaluasi dan kurikulum B. Konsep kurikulum
C. Implementasi dan evaluasi kurikulum D. Peranan evaluasi kurikulum
E. Ujian sebagai evaluasi sosial F. Model-model evaluasi kurikulum BAB 10 Guru dan Pengembangan Kurikulum
A. Guru sebagai pendidik profesional B. Guru sebagai pembimbing belajar
C. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum D. Pendidikan guru
BAB 1
KONSEP KURIKULUM
A. Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan
Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun rnasyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa rencana tertulis,Orang tua sering tidak mempunyai rencana yang jelas dan rinci ke mana anaknya akan diarahkan, dengan cara apa mereka akan dididik, dan apa isi pendidikannya. Orang tua umumnya mempunyai harapan tertentu pada anaknya, mudah-mudahan is menjadi orang soleh, sehat, pandai, dan sebagainya, tetapi bagaimana rincian sifat-sifat tersebut bagi mereka tidak jelas. Juga mereka tidak tahu apa yang harus diberikan dan bagaimana memberikannya agar anak-anaknya memiliki sifat-sifat tersebut.
Interaksi pendidikan antara orang tua dengan anaknya juga sexing tidak disadari. Dalam kehidupan keluarga interaksi pendidikan dapat terjadi setiap saat, setiap kali orang tua bertemu, berdialog, bergaul, dan bekerja sama dengan anak-anaknya. Pada saat demikian banyak perilaku dan perlakuan spontan yang diberikan kepada anak, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan mendidik besar sekali. Orang tua menjadi pendidik juga tanpa dipersiapkan secara formal. Mereka menjadi pendidik karena statusnya sebagai ayah atau ibu, meskipun mungkin saja sebenarnya mereka belum siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Karena sifat-sifatnya yang tidak formal, tidak memiliki rancangan yang konkret dan ada kalanya juga tidak disadari, maka pendidikan dalam lingkungan keluarga disebut pendidikan informal. Pendidikan tersebut tidak memiliki kurikulum formal dan tertulis.
dibina untuk memiliki kepribadian sebagai pendidik. Lebih dari itu mereka juga telah diangkat dan diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi guru, bukan sekadar dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang, tetapi juga dengan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Guru melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan rencana dan persiapan yang matang. Mereka mengajar dengan tujuan yang jelas, bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis dan rinci, dengan cara dan alat-alat yang telah dipilih dan dirancang secara cermat. Di sekolah guru melakukan interaksi pendidikan secara berencana dan sadar. Dalam lingkungan sekolah telah ada kurikulum formal, yang bersifat tertulis. Guru-guru melaksanakan tugas mendidik secara formal, karena itu pendidikan yang berlangsung di sekolah sering disebut pendidikan formal.
Dalam lingkungan masyarakat pun terjadi berbagai bentuk interaksi pendidikan, dari yang sangat formal yang mirip dengan pendidikan di sekolah dalam bentuk kursus-kursus, sampai dengan yang kurang formal seperti ceramah, sarasehan, dan pergaulan kerja. Gurunya juga bervariasi dari yang memiliki latar belakang pendidikan khusus sebagai guru, sampai dengan yang melaksanakan tugas sebagai pendidik karena pengalaman. Kurikulumnya juga bervariasi, dari yang memiliki kurikulum formal dan tertulis sampai dengan rencana pelajaran yang hanya ada pada pikiran penceramah atau moderator sarasehan, atau gagasan keteladanan yang ada pada pemimpin. Interaksi pendidikan yang berlangsung di masyarakat, yang memiliki rancangan dan dilaksanakan secara formal sebenarnya dapat dimasukkan dalam kategori pendidikan formal. Interaksi yang rancangan dan pelaksanaannya kurang formal dapat kita sebut sebagai pendidikan kurang formal (less formal). Karena adanya variasi itu, Para ahli pendidikan masyarakat lebih senang menggunakan istilah pendidikan luar sekolah bagi interaksi pendidikan yang berlangsung di masyarakat ini.
pendidikan berlangsung dalam lingkungan tertentu, dengan fasilitas dan alat serta aturan-aturan permainan tertentu pula.
Pendidikan formal memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pendidikan informal dalam lingkungan keluarga. Pertaina, pendidikan for- mal di sekolah memiliki lingkup isi pendidikan yang lebih luas, bukan hanya berkenaan dengan pembinaan segi-segi moral tetapi juga ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kedua, pendidikan di sekolah dapat memberikan pengetahuan yang lebih tinggi, lebih luas dan mendalam.
Sejarah pendirian sekolah diawali karena ketidakmampuan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi dan mendalam. Ketiga, karena memiliki rancangan atau kurikulum secara formal dan tertulis, pendidikan di sekolah dilaksanakan secara berencana, sistematis, dan lebih disadari. Karena yang memiliki rancangan atau kurikulum formal dan tertulis adalah pendidikan di sekolah, maka dalam uraian-uraian selanjutnya yang dimaksud dengan pendidikan atau pengajaran itu, lebih banyak mengacu pada pendidikan atau pengajaran di sekolah.
Telah diuraikan sebelumnya, bahwa adanya rancangan atau kurikulum formal dan tertulis merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah. Kalau kurikulum merupakan syarat mutlak, hal itu berarti bahwa kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Dapat kita bayangkan, bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan atau pengajaran di sekolah yang tidak memiliki kurikulum.
iidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu terjadi dalam lingkungan tertentu, yang mencakup antara lain lingkungan fisik, alam, sosial budaya, ekonomi, politik, dan religi. Pertautan antara satu komponen dan komlumen pendidikan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut.
BAGAN 1.1 Komponen-komponen utama pendidikan
Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Mauritz Johnson (1967, hlm. 130) kurikulum "prescribes (or at least anticipates) the result of in- struction". Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Di samping kedua fungsi itu, kurikulum juga merupakan suatu bidang studi, yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum, yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoretis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan..
B. Konsep Kurikulum
Banyak orang tua bahkan juga guru-guru, kalau ditanya tentang kurikulum akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata-mata pelajaran. Lebih khusus mungkin kurikulum diartikan hanya sebagai isi pelajaran.
Pendapat-pendapat yang muncul selanjutnya telah beralih dari menekankan pada isi menjadi lebih memberikan tekanan pada pengalaman belajar. Menurut Caswel dan Campbell dalam buku mereka yang terkenal Curriculum Development (1935), kurikulum ... to be composed of all the experi-ences children have under the guidance of teachers. Perubahan penekanan pada pengalaman ini lebih jelas ditegaskan oleh Ronald C. Doll (1974, hlm. 22):
The commonly accepted definition of the curriculum has changed from
content of courses of study and list of subjects and courses to all the
experiences which are offered to learners under the auspices or direction
of the school..
Definisi Doll tidak hanya menunjukkan adanya perubahan penekanan dari isi kepada proses, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan lingkup, dari konsep yang sangat sempit kepada yang lebih luas. Apa yang di maksud dengan pengalaman siswa yang diarahkan atau menjadi tanggung jawab sekolah mengandung makna yang cukup luas. Pengalaman tersebut berlangsung di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat, bersama guru tanpa guru, berkenaan langsung dengan pelajaran ataupun tidak. Definisi tersebut juga mencakup berbagai upaya guru dalam mendorong terjadinya pengalaman tersebut serta berbagai fasilitas yang mendukungnya.
Menurut Johnson kurikulum adalah ... a structured series of intended learning outcomes (Johnson, 1967, him. 130).
Terlepas dari pro dan kontra terhadap pendapat Mauritz Johnson, beberapa ahli memanciang kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran. Salah seorang di antara mereka adalah Mac Donald (1965, hlm.
Menurut dia, sistem persekolahan terbentuk atas empat subsistem, yaitu mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum. Mengajar (teaching) merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru. belajar (learning) merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa. Sebagai respons terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Keluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan (lengan terjadinya interaksi belajar-mengajar disebut pembelajaran (instruction). Kurikulum,(curriculum) merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar.
Kurikulum juga sering dibedakan antara kurikulum sebagai rencana (curriculum plan) dengan kurikulum yang fungional (functioning curricu- lum). Menurut Beauchamp (1968, him. 6) "A curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school". Beauchamp lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. Pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran. Selanjutnya, Zais menjelaskan bahwa kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, melainkan harus dinilai dalam proses pelaksanaan fungsinya di dalam kelas. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional yang beroperasi dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum (curriculum document or inert curriculum), sedangkan kurikulum yang dioperasikan di kelas merupakan kurikulum fungsional (functioning, live or operative curriculum).
berkenaan dengan cakupan tujuan isi dan metode yang lebih luas atau lebih umum, sedangkan yang lebih sempit lebih khusus menjadi tugas pengajaran. Menurut Taba keduanya membentuk satu kontinum, kurikulum terletak pada ujung tujuan umum atau tujuan jangka panjang, sedangkan pengajaran pada ujung lainnya yaitu yang lebih khusus atau tujuan dekat.
BAGAN 1.2 Kontinum kurikulum dan pengajaran
Menurut Taba, batas antara keduanya sangat relatif, bergantung pada tafsiran guru. Sebagai contoh, dalam kurikulum (tertulis), isi harus digambarkan serinci, sekhusus mungkin agar mudah dipahami guru, tetapi cukup luas dan umum sehingga memungkinkan mencakup semua bahan yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa serta kemampuan guru. Kurikulum memberikan pegangan bagi pelaksanaan pengajaran di kelas, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab guru untuk menjabarkannya.
Bidang cakupan teori atau bidang studi kurikulum meliputi: konsep kurikulum, penentuan kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum.
Selain sebagai bidang studi menurut Beauchamp, kurikulum juga sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem (sistem kurikulum) yang merupakan bagian dari sistem persekolahan. Sebagai suatu rencana pengajaran, kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran dan jadwal waktu pengajaran. Sebagai suatu sistem, kurikulum m.erupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem ‘.ekolah. Kurikulum sebagai suatu sistem menyangkut penentuan segala kebijakan tentang kurikulum, susunan personalia dan prosedur pengemhangan kurikulum, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya. Fungsi utama sistem kurikulum adalah dalam pengembangan, penerapan, ovaluasi, dan penyempurnaannya, baik sebagai dokumen tertulis maupun aplikasinya dan menjaga agar kurikulum tetap dinamis.
Mengenai fungsi sistem kurikulum ini, lebih lanjut Beauchamp (1975, 111m. 60) menggambarkan:
...(1) the choice of arena for curriculum decision making, (2) the selection
and involvement of person in curriculum planning, (3) organization for
and leachniques used in curriculum plannning, (4) actual writing of a
curriculum, (5) implementing the curriculum, (6) evaluation the
curriculum, and (7) providing for feedback and modification of the
curriculum.
Apa yang dikemukakan oleh Beauchamp bukan hanya menunjukkan tnnlsi tetapi juga struktur dari suatu sistem kurikulum, yang secara garis berkenaan dengan pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
C. Kurikulum dan Teori-Teori Pendidikan
penerapan dari suatu teori pendidikan. Untuk lebih memahami hubungan kurikulum dengan pendidikan, dikemukakan beberapa teori pendidikan dan model-model konsep kurikulum dari masing-masing teori tersebut. Minimal ada empat teori pendidikan yang banyak dibicarakan para ahli pendidikan dan dipandang mendasari pelaksanaan pendidikan, yaitu pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan interaksional, dan teknologi pendidikan.
1. Pendidikan klasik
Pendidikan klasik atau classical education dapat dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Konsep pendidikan ini bertolak dari asumsi seluruh warisan budaya, yaitu pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir terdahulu. Pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan semua warisan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Guru atau para pendidik tidak perlu susah-susah mencari dan menciptakan pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai baru, sebab sentuanya telah tersedia, tinggal menguasai dan mengajarkannya kepada anak. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Isi pendidikan atau materi ilmu tersebut diambil dari khazanah ilmu pengetahuan, berupa disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli tempo dulu. Materi ilmu pengetahuan yang diambil dari disiplindisiplin ilmu tersebut telah tersusun secara logis dan sistematis.
tetapi sebagai penerima informasi sesungguhnya mereka pasif. Meskipun demikian dalam pendidikan klasik siswa bekerja keras menguasai apa-apa yang diajarkan dan ditugaskan oleh guru. Pendidikan lebih menekankan perkembangan segi-segi intelektual daripada segi emosional dan psikomotor.
Ada dua model konsep pendidikan klasik, perenialisme dan esensialisme. Walaupun didasari dengan konsep-konsep yang sama, keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Parenialisme maupun esensialisme mempunyai pandangan yang sama tentang masyarakat, bahwa masyarakat bersifat statis. Pendidikan berfungsi memelihara dan mewariskan pengetahuan, konsep-konsep dan nilai-nilai yang telah ada. Pengetahuan dan nilai-nilai yang akan diajarkan diambil dari materi disiplin ilmu yang telah disusun dan dikembangkan oleh para ahli. Dalam penyusunan kurikulum, matamata pelajaran dipilih dan ditentukan oleh sekelompok orang ahli, disusun secara sistematis dan logis, dan diarahkan pada perkembangan kemampuan berpikir.
Parenialisme berkembang di Eropa dalam masyarakat aristokralisagraris. Mereka lebih berorientasi ke masa lampau dan kurang hivmen tingkan tuntutan-tuntutan masyarakat yang berkembang saat sekarang pendidikan lebih menekankan pada humanitas, pembentukan pribadi, dan sifat-sifat mental. Konsep-konsep filosofis lebih banyak mewarnai pendidikan ini. Isi pendidikan lebih banyak bersifat pendidikan umum (general education atau liberal art) dengan model mengajar yang bersifat ekspositori, sedangkan model belajarnya adalah asimilasi. Pendidikan menurut pandangan mereka adalah bebas nilai (value free) dan bebas dari kebudayaan (culture free) artinya tidak terikat atau diwarnai oleh nilai-nilai dan karakteristik masyarakat sekitar.
Like perennial education, essentialism is conservative, seeking to maintain
and pass on to the new generation the convictions of the older generation.
But unlike perennialism, essentialism is nonreflective, nonphilosophical. It
is far more prone to activity-to doing-than to wasting time on extensive
philosophical speculation. Looking to the present rather than the past, and
to science rather than to the humanities, it is primarily practical and
pragmatic. (Lapp, Dianna, et. al., 1975, hlm. 32).
Para esensialis bersifat praktis, mengutamakan kerja dan kompetisi di tramping kerja sama. Mereka menghargai seni, keindahan, dan humanitas sepanjang hal itu mendukung kehidupan sehari-hari, kehidupan produktif. Tujuan utama pendidikan, menurut para esensialis, adalah (1) memperoleh pekerjaan yang lebih baik, (2) dapat bekerja sama lebih baik dengan orang dari berbagai tingkatan/lapisan masyarakat, (3) memperoleh penghasilan lehih banyak. Mereka berpikiran praktis bahwa pendidikan adalah suatu Han untuk mencapai sukses dalam kehidupan, terutama sukses secara ekonomis.
Kurikulum pendidikan klasik lebih menekankan isi pendidikan, yang diambil dari disiplin-disiplin ilmu, disusun oleh para ahli tanpa mengikutsertakan guru-guru, apalagi siswa. Isi disusun secara logis, sistematis, dan berstruktur, dengan berpusatkan pada segi intelektual, sedikit sekali memperhatikan segi-segi sosial atau psikologis peserta didik. Guru mempunyai peranan yang sangat besar dan lebih dominan. Dalam pengajaran, ia menentukan isi, metode, dan evaluasi. Dialah yang aktif dan bertanggung jawab dalam segala aspek pengajaran. Siswa mempunyai peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari guru.
2. Pendidikan pribadi
petani adalah mengusahakan tanah yang gembur, pupuk, air, udara, dan sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tanaman (peserta didik). Pendidikan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik menjadi subjek pendidikan, dialah yang menduduki tempat utama dalam pendidikan. Pendidik menempati posisi kedua, bukan lagi sebagai penyampai informasi atau sebagai model dan ahli dalam disiplin ilmu. Ia lebih berfungsi sebagai psikolog yang mengerti segala kebutuhan dan masalah peserta didik. la juga berperan sebagai bidan yang membantu siswa melahirkan ide-idenya. Guru adalah pembimbing, pendorong (motivator), fasilitator, dan pelayan bagi siswa.
Teori ini juga memiliki dua aliran, yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik. Tokoh pendahulu pendidikan progresif adalah Francis Parker yang membawa aliran ini dari Eropa ke Amerika. Aliran ini menjadi lebih terkenal di Amerika berkat percobaan-percobaan yang dilakukan John Dewey dengan sekolah-sekolah laboratoriumnya. John Dewey menerapkan prinsip belajar sambil berbuat (learning by doing). Dalam pendidikan progresif, siswa merupakan satu kesatuan yang utuh, perkembangan emosi dan sosial sama pentingnya dengan perkembangan intelektual. Isi pengajaran berasal dari pengalaman sisvva sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupanhya. Berkat refleksinya itu is memahami dan dapat menggunakannya bagi kehidupan. Guru lebih merupakan ahli dalam metodologi daripada dalam bahan ajar. Guru membantu perkembangan siswa sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing.
Rousseau memandang pendidikan sebagai a lifelong personal growth process rather than an information and skill gathering process that exists only during the
school years (Diane Lapp, et. al., 1975, hlm. 154).
Pengalaman merupakan isi sekaligus guru alamiah bagi anak. Anak tidak diajari, tetapi didorong untuk belajar. Guru menyediakan lingkungan belajar, memberikan kebebasan agar anak belajar dan berkembang sendiri, dan mewujudkan rasa ingin tahunya. Ia dibiarkan untuk mengalami sendiri, mewujudkan dorongan-dorongannya, dan tumbuh sesuai dengan polanya. Guru juga berperan sebagai sumber lingkungan belajar, yang selalu siap memberikan bantuan kepada siswa. Ia berusaha mencegah hal- hal yang mungkin mengganggu perkembangan siswa.
Kurikulum pendidikan pribadi lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan siswa. Materi ajar dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru- guru dengan melibatkan siswa. Tidak ada suatu kurikulum standar, yang ada adalah kurikulum minimal yang dalam implementasinya dikem- bangkan bersama siswa. Isi dan proses pembelajarannya selalu berubah sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
3. TeknOlogi pendidikan
Teknologi pendidikan mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Keduanya juga mempunyai perbedaan, sebab yang diutamakan dalam teknologi pendidikan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Mereka lebih berorientasi ke masa sekarang dan yang akan datang, tidak seperti pendidikan klasik yang lebih melihat ke masa lalu.
Perkembangan teknologi pendidikari dipengaruhi clan sangat diwarnai oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Hal itu memang sangat masuk akal, sebab teknologi pendidikan bertolak dari dan merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu dan teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah masuk ke semua segi kehidupan, termasuk dalam pendidikan.
Our technologies to day are so powerful, so prevalent, so deliberately
bring about changes in the physical world which tecnologies have always
done but also in our insti- tutions, attitudes, and expectations, values,
goals, and in our very conceptions of the meaning of existence (Holtzman,
1970, hlm. 237).
Gambaran manusia tentang dunia dan makna kehidupan merupakan sintesis dari pengalaman-pengalaman dasarnya. Menurut pandangan klasik, pengalaman ini bersifat menetap, sama dari tahun ke tahun, berbeda dengan pandangan teknologi pendidikan. Menurut mereka, pengalaman tersebut selalu berubah, hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari Mi. Kehidupan dan perkembangan itu selalu baru.
Karena sifat ilmiahnya, konsep pendidikan ini mengutamakan segi-segi empiris, informasi objektif yang dapat diamati dan diukur serta dihitung secara statistik. Mereka kurang menghargai hal-hal yang bersifat kualitatif dan spiritual. Bagi mereka, dunia ini adalah dunia material, dunia empiris. Meskipun lebih kompleks, manusia pada dasarnya tidak berbeda dengan binatang, ia mereaksi terhadap perangsang-perangsang dari lingkungannya, perilakunya dapat dibentuk dengan teknologi perilaku, seperti yang dinyatakan Skinner.
Man totally determined by his environment. Therefore, if we wish to relate
to him for better to educate him, we need only learn scientifically, how to
control his environment in such away as to reshape his behavior. What we
need is a technology of behavior (Skinner, 1972).
Dalam konsep teknologi pendidikan, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa data-data objektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vocational. Isi disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika (kaset audio, video, film, atau komputer) dan para siswa belajar secara individual. Siswa berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola-pola kegiatan secara efisien tanpa refleksi. Keterampilan-keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Guru berfungsi sebagai direktur belajar, lebih banyak melakukan tugas-tugas pengelolaan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Apabila digunakan media elektronika, ierbehas dari tugas pengembangan segi-segi nonintelektual.
Kurikulum pendidikan teknologi menekankan kompetensi atau kemampuan- kemampuan praktis. Materi disiplin ilmu dipelajari termasuk dalam kurikulum, apabila hal itu mendukung penguasaan kemampuan-kemampuan tersebut. Dalam kurikulum, materi disiplin ilmu tersebut disusun terjalin dalam kemampuan. Penyusunan kurikulum dilakukan para ahli dan atau guru-guru yang mempunyai kemampuan mengembangkan kurikulum. Perangkat kurikulum cukup lengkap mulai dari struktur dan sebaran mata pelajaran sampai dengan rincian bahan ajar yang dipelajari oleh siswa, yang tersusun dalam satuan-satuan bahan ajar dalam bentuk satuan pelajaran, paket belajar, modul, paket program audio, video ataupun komputer. Dalam satuan-satuan bahan ajar tersebut tercakup pula kegiatan pembelajaran dan bentuk-bentuk serta alat penilaiannya.
4. Pendidikan interaksional
kemajuan seperti yang dialami oleh I wang-orang yang hidup bersama dengan orang lain.
Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja ama dan interaksi. Dalam pendidikan klasik dan teknologi interaksi terjadi sepiliak dari guru kepada siswa, sedangkan dalam pendidikan romantik don progresif terjadi sebaliknya dari siswa kepada guru. Pendidikan lideraksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada siswa dan lari siswa kepada guru. Lebih luas, interaksi ini juga terjadi antara siswa dengan bahan ajar dan dengan lingkungan, antara pemikiran siswa dengan kehidupannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog.
Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih dari sekadar mempelajari fakta-fakta. Siswa mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupannya. Setiap siswa, begitu juga guru, mempunyai rentetan pengalaman dan persepsi sendiri. Dalam proses belajar, persepsi-persepsi yang berbeda tersebut digunakan untuk menyoroti masalah bersama yang muncul dalam kehidupannya. Dalam proses seperti itu dialog berlangsung, setiap siswa dan guru saling mendengarkan, memberikan pendapat, sal ing mengajar dan belajar. Pemahaman yang muncul dari situasi demikian melebihi jumlah seluruh sumbangan para peserta. Siswa tidak hanya berperan sebagai siswa, tetapi juga sebagai guru, dan guru juga pada suatu saat berperan sebagai siswa yang turut belajar bersama para siswanya.
Interaksi juga terjadi antara siswa dengan bahan ajar. Interaksi ini bukan hanya pada tingkat apa dan bagaimana, tetapi lebih jauh yaitu pada tingkat mengapa, tingkat mencari makna baik makna sosial (socially conscious) maupun makna pribadi (self conscious). Isi atau bahan ajar ini berkenaan dengan lingkungan sosial-budaya yang mereka hadapi saat ini. Setelah mengetahui makna dari fakta-fakta dan nilai-nilai sosial budaya, mereka mengadakan evaluasi, kritik dari sudut kepentingannya bagi kesejahteraan umat manusia.
keterbatasan lingkungan mempengaruhi individu siswa. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan siswa. Interaksi juga terjadi antara pemikiran siswa dengan kehidupannya. Suatu kebenaran tidak akan diyakininya apabila tidak dicobakan dan dihayati dalam kehidupannya sehari-hari.
Sekolah berbeda dengan pendidikan, tetapi mempunyai peranan penting dalam sistem masyarakat. Sekolah merupakan pintu untuk memasuki masyarakat, menentukan stratifikasi sosial, dan memberikan kesiapan untuk melakukan berbagai pekerjaan. Sekolah menyiapkan anak dengan berbagai keterampilan sosial juga keterampilan bekerja. Lebih jauh, sekolah juga berperan dalam membina sikap positif terhadap dunia kerja, disiplin kerja, dan sebagainya. Pendidikan berperan dalam mengembangkan identitas pribadi, memperbaiki modus dari kehidupan.
Proses belajar dalam model interaksional terjadi melalui dialog dengan orang lain apakah dengan guru, teman, atau yang•lainnya. Belajar adalah kerja sama dan saling kebergantungan dengan orang lain. Siswa belajar memperhatikan, menerima, menilai pendapat orang lain, dan belajar menyatakan pendapat dan sikapnya sendiri. Melalui interaksi tersebut muncul pengetahuan, pendapat, sikap, dan keterampilan-keterampilan baru. Guru berperan dalam menciptakan situasi dialog dengan dasar saling mempercayai dan saling membantu. Bahan ajar diambil dari lingkungan sosial-budaya yang dihadapi para siswa sekarang. Mereka diajak untuk menghayati nilai-nilai sosial-budaya yang ada di masyarakat, memberikan penilaian yang kritis, kemudian mereka mengembangkan persepsinya sendiri terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
D. Buku Acuan
Schubert, William H. 1986. Curriculum: Perspective, Paradigm and Possibility. New York: Macmillan Publishing Co.
Dilatarbelakangi oleh minat pribadi yang sangat mendalam terhadap pendidikan, khsusunya kurikulum, penulis memandang bahwa kurikulum merupakan bidang yang sangat penting. Kurikulum menentukan jenis dan kualitas pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan orang atau seseorang mencapai kehidupan dan penghidupan yang baik. Dilengkapi dengan pengalamannya yang begitu banyak dalam bidang pendidikan, penulis menyajikan suatu tulisan yang komprehensif mendasar, dalam arti bertolak dari teori yang kuat, dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat praktis. Buku ini merupakan buku teks pada bidang kurikulum baik untuk tingkat S1 maupun S2 sebab isinya menyangkut hal-hal yang sangat prinsip. Secara sistematis dan logis, seluruh isi buku ini terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama menguraikan perspektif kurikulum, baik dari segi konsep atau teori, sejarah maupun perkembangannya. Bagian kedua membahas paradigma, yang berisi tujuan, misi, proses, organisasi, dan ovaluasi, serta pelaksanaan. Bagian ketiga membahas problema-problema kurikulum, profesionalisasi, dan pengembangan kurikulum.
Beane, James A. et. al., 1986. Curriculum Planning and Development. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
Johnson, Mauritz. 1977. Intensionality in Education. Albany, New York: Center for Curriculum Research and Services.
Judul buku ini adalah intensionality in Education, suatu judul yang bertemakan pendidikan, dan isinya lebih banyak menyangkut kurikulum. Isi buku ini sangat berharga bagi para pakar pendidikan, pakar kurikulum, para perencana pengajaran, dan juga guru-guru. Dalam buku ini disajikan suatu model konseptual kurikulum dan rencana pengajaran, serta evaluasinya. Dipisahkan dengan tegas oleh penulis antara kurikulum dan pengajaran. Kurikulum berkenaan dengan apa yang akan diajarkan, sedangkan pengajaran berkenaan dengan bagaimana cara mengajarkannya. Dengan konsep scperti itu penulis mengemukakan suatu model kurikulum yang disebutnya sebagai model P-I-E, dan dijelaskan pula bagaimana pengembangannya. Dalam pengembangan tersebut diuraikan secara rinci bagaimana merumuskan tujuan, isi, struktur kurikulum, serta sumbersumber kurikulum. Selanjutnya diuraikan juga rencana pengajaran, evaluasi, serta pengelolaannya.
Goodlad, John I. (Ed). 1979. Curriculum Inquiry, The Study of Curriculum Practice. New York: McGraw Hill Book, Co.
BAB 2
TEORI KURIKULUM
Dewasa ini berkembang suatu anggapan bahwa pendidikan bukan lagi merupakan suatu ilmu, melainkan suatu teknologi. Hal ini disebabkan oleh upaya pengembangan dan penyempurnaan pendidikan, khususnya kurikulum, lebih banyak datang dari pengalaman praktik di sekolah, dibandingkan dengan dari penerapan teori-teori yang sudah mapan. Perubahan atau penambahan isi kurikulum sering diadakan karena adanya kebutuhan-kebutuhan praktis. Karena selalu menekankan pada hal-hal praktis itulah, masa berlaku suatu kurikulum tidak bisa lama. Pada bab ini akan diuraikan apa, mengapa, dan bagaimana teori, khususnya pentingnya ilasar-dasar teoretis dalam pengembangan suatu kurikulum.
A. Apakah Teori Itu?
Mengenai apakah teori itu, telah ada beberapa kesepakatan di antara para ahli, tetapi juga ada beberapa perbedaan pendapat. Kesepakatan yang telah diterima secara umum, bahwa teori merupakan suatu set atau sistem pernyataan (a set of statement) yang menjelaskan serangkaian hal. Ketidaksepakatannya terletak pada karakteiistik pernyataan tersebut.
Di antara sekian banyak pendapat yang berbeda, ada tiga kelompok karakteristik utama sistem pernyataan suatu teori. Pertama, pernyataan dalam suatu teori bersifat memadukan (unifying statement). Kedua, pernyataan tersebut berisi kaidah-kaidah umum (universal preposition). Ketiga, pernyataan bersifat meramalkan (predictive statement). Karakteristik memadukan (unifying statement) banyak disetujui oleh para perumus teori, seperti yang dikemukakan Kaplan (1964, him. 295).
A theory is a way of making sense of a disturbing situation, so as to allow us most
effectivelly to bring to bear our reverfoice of habits, and even more impor- tant, to
modify habits or discard them together, reflacing new ones as the situa - tion
demands. And the reconstructed logic, accordingly, theory will appear as the
them to fit data unanticipated in their formation, and guiding the enter - prise of
discovering new and more powerful generalizations.
Hall dan Lindsay (1970, him. 11) menekankan hal yang sama yaitu sifat unifying, seperti mereka nyatakan bahwa "... a theory is set of conventions that should contain a cluster of relevant assumption systematically related to each
other and a set of empirical definitions".
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Snow (1973, hlm.78).
In its simplest form, a theory is a symbolic instruction designed to bring gener
-alizable fact (or laws) into systematic connection. It consist of a) a set of units
(facts, concepts, variables), and b) a system of relationships among the units.
Karakteristik lain berupa kaidah-kaidah yang bersifat universal, kita temukan dalam definisi teori Rose (1953, him. 52).
A theory may be defined as an integrated body of definitions, assumptions and
general prepositions covering a given subject matter from which a comprehensive
and consistent set of specific and testable hypotheses can be deducted logically.
Menurut Rose, karakteristik pernyataan (set of statement) tersebut meliputi definisi, asumsi, dan kaidah-kaidah umum. Dalam rumusan yang lebih kompleks, teori ini juga menyangkut hukum-hukum, hipotesis, dan deduksi-deduksi logis-matematis. Definisi teori Abel umpamanya menunjukkan hal seperti itu.
A general theory is built upon the facts discovered by means of the use of
theo-rems and other conceptual models from empirical data and which have been
ex-pressed in the form of laws, correlations, or other type of generalizations. It
in-volves synthesis and is directed to the formulation of propositions about
uni-versals.
Suatu rumusan yang lebih menyeluruh, yang mengandung tiga karakteristik utama suatu teori (unifying, universal prepositions, dan predictive) kita temukan dalam definisi Kerlinger (1973, hlm. 9).
A theory is a set of interelated constructs (concepts), definitions, and prepositions
that present a systematic view of phenomena by specifying relations among
variables, with the purpose of explaining and predicting phenomena".
Dengan bermacam-macam rumusan teori itu diharapkan sampai pada suatu kesimpulan, walaupun bersifat tentatif bahwa suatu teori lahir dari suatu proses, yang berbeda dengan yang lainnya. Suatu teori hanya menjelaskan hal yang terbatas, teori lain menjelaskan hal yang lebih luas.
Teori menjelaskan suatu kejadian. Kejadian ini bisa sangat luas atau sangat sempit. Suatu kejadian yang dijelaskan oleh suatu teori menunjukkan suatu set yang universal. Set universal ini terbentuk oleh tiga bagian. Bagian pertama, kejadian yang diketahui, yang dinyatakan sebagai fakta, hukum, atau prinsip. Bagian kedua yang dinyatakan sebagai asumsi, proposisi, dan postulat. Bagman ketiga adalah bagian dari set universal atau bagian dari keseluruhan yang belum diketahui. Visualisasi hubungan antara bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.
Tugas seorang teoretisi adalah merumuskan istilah-istilah dan pernyataan yang akan menjelaskan isi bagian-bagian dan hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Hal yang sangat penting dalam pekerjaan seorang ilmuwan adalah penggunaan istilah-istilah. Ia dituntut untuk menggunakan istilah dengan makna yang tepat dan konsisten. Gordon dan teman-temannya (1967) membagi istilah-istilah yang digunakan dalam suatu teori atas tiga kelas: primitive terms, key terms, and theoretical terms. Primitive terms tak dapat didefinisikan secara operasional. Contohnya, konsep titik (point) dalam geometri. Key terms adalah istilah-istilah yang dapat didefinisikan secara operasional seperti pemecahan masalah. Theo- retical terms dapat didefinisikan secara operasional, tetapi dalam hubungannya dengan key terms.
Beauchamp (1975, hlm. 15) membedakan adanya tiga kelompok istilah, yaitu "general language terms, basic concepts, dan theoretical contructs". General language terms merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu pengetahuan atau bahasa secara umum. Istilah-istilah tersebut tidak perlu didefinisikan secara operasional karena telah dikenal secara umum. The basic concept merupakan istilah-istilah yang sangat dasar dan penting dalam menjelaskan suatu set kejadian, oleh karenanya perlu didefinisikan secara operasional. Sebagai contoh, istilah molekul dalam kimia, istilah kurikulum dalam pendidikan. Yang ketiga adalah theoretical constructs, yang merupakan istilah yang punya makna khusus dalam set kejadian yang akan dijelaskan suatu teori, tetapi tidak dapat diketahui melalui pengamatan langsung. Contoh istilah minat, kebutuhan dalam pengajaran.
Hal lain yang juga sangat penting dalam pekerjaan ilmuwan adalah pernyataan. Suatu teori terdiri atas serangkaian pernyataan, di dalam pernyataan tersebut ada istilah-istilah. Seperti halnya istilah, pernyataan pun ada pengkategoriannya. Pernyataan dapat menunjuk kepada faktafakta, definisi, proposisi, hipotesis, generalisasi, dalil, postulat, teorem, asumsi, dan hukum. Sering terdapat tumpang tindih atau pertukaran pengertian dari istilah-istilah tersebut, juga penggunaannya sering amat terbatas hanya dalam teori atau konsep tertentu.
merupakan perumusan arti dalam bentuk pernyataan formal. Proposisi merupakan suatu pernyataan formal yang memperkuat atau menolak keberadaan sesuatu hal tentang suatu subjek. Hipotesis, generalisasi, aksioma, postulat, teorem, dan hukum-hukum merupakan bentuk-bentuk khusus proposisi. Hipotesis terbentuk oleh satu proposisi atau lebih untuk menjelaskan suatu set kejadian. Generalisasi adalah suatu proposisi yang memperkuat atau menegaskan kedudukan suatu anggota atau beberapa anggota kolas, hal itu disimpulkan dari hasil pengamatan atas sejumlah hubungan peristiwa. Aksioma atau postulat adalah suatu proposisi yang diterima sebagai suatu kebenaran. Teorem adalah suatu proposisi yang berasal dari pemikiran atau diturunkan dari aksioma. Hukum adalah suatu proposisi yang sudah bersifat tetap, yang memberikan kondisi yang tidak berubah.
1. Apakah fungsi teori?
Minimal ada tiga fungsi teori yang sudah disepakati para ilmuwan yaitu; (1) mendeskripsikan, (2) menjelaskan, dan (3) memprediksi. Untuk tiga fungsi tersebut, Brodbeck (1963, hlm. 70) menambahkan fungsi lain. "A theory nol only explains and predict, it also unifies phenomena". Khusus dalam penelitian Gawin (1963) mengemukakan fungsi teori sebagai: ... the theory help teioire,/ searcher to analyze data to make shorthand summarization or synopsis of data an
relations, and to suggest new thing to try out.
Dalam usaha mendeskripsikan, menjelaskan, dan membuat prediksi, para ahli terus mencari dan menemukan hukum-hukum baru dan hubungan-hubungan baru di antara hukum-hukum tersebut. Melalui proses demikian mungkin terjadi di dalam suatu "set kejadian", semua hukum dan interealasinya dapat dinyatakan dan teori itu telah berkembang menjadi hukum yang lebih tinggi. Para ahli teori mencari hubungan baru dangan menggabungkan beberapa "set kejadian" menjadi suatu "set kejadian yang baru yang lebih universal". Hal itu mendorong pencarian dan pengkajian selanjutnya, untuk menemukan hukum-hukum baru dan hubungan baru dalam suatu teori baru. Fungsi yang lebih besar dari suatu leori adalah melahirkan teori baru.
1. A theoretical system must permit deduction which be tested empirically, 2. A theory must be compatible both with observation and with previously
validated theories,
3. Theories must be stated in simple terms, that theory is best which explains the most in the simplest form,
4. Scientific theories must be based on empirical facts and relationships. Bagaimana proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses herteori berlangsung, melalui beberapa langkah.
Pertama, pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan.
Kedua, klasifikasi yaitu pengelompokan informasi-informasi yang revan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan wugelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang
.mogen, tetapi tidak menjelaskan interelasi antarkelompok atau interaksi fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok.
Ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan pernyataan- pernyataan teoretis setelah pendefinisian dan pengklasifikasian. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum.
Keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukkan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi-inferensi yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari teori yaitu memberikan prediksi, teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi.
memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian.
Keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya sub-subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan.
B. Teori Pendidikan
Pendidikan merupakan suatu ilmu terapan (applied science), yaitu terapan dari ilmu atau disiplin lain terutama filsafat, psikologi, sosiologi, dan humanitas. Sebagai ilmu terapan, perkembangan teori pendidikan berasal dari pemikiran-pemikiran filosofis-teoretis, penelitian empiris dalam praktik pendidikan. Dengan latar belakang seperti itu, beberapa ahli menyatakan bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu yang "belum jelas". Hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa cukup sulit untuk dapat merumuskan teori pendidikan. Teori-teori pendidikan yang ada lebih menggambarkan pandangan filosofis, seperti teori pendidikan Langeveld, Kohnstam, dan sebagainya, atau lebih menekankan pada pengajaran seperti teori Gagne, Skinner, dan sebagainya.
Boyles (1959) menyatakan bahwa teori pendidikan di Amerika Serikat berada dalam a state of suspended animation, penggambarannya masih tertangguhkan. Masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk menampilkan dengan jelas teori pendidikan ini. Menurut Beauchamp (1975, hlm. 34), teori pendidikan akan atau dapat berkembang, tetapi perkembangannya pertama-tama dimulai pada sub-subteorinya. Yang menjadi subteori dari teori pendidikan adalah teori-teori dalam kurikulum, pengajaran, evaluasi, bimbingan-konseling, dan administrasi pendidikan.
Susunan hierarki teori pendidikan dengan subteori dan teori yang memayunginya dapat dilihat pada Bagan 2.2.
BAGAN 2.2 Susunan hierarki teori pendidikan dan kurikulum
pandang ilmu lain, seperti filsafat, psikologi, dan lain-lain. Kedua, perkembangan ilmu pendidikan dari praktik pendidikan. Keduanya dapat ding membantu, melengkapi, dan memperkaya. Dalam kenyataan, tidak selalu terjadi hal yang demikian. Hanya sedikit hasil-hasil pengkajian leoretis yang diterapkan para pelaksana pendidikan. Sebagai contoh, teori IT Rousseau yang menekankan pendidikan alam dengan peranan anak sebagai subjek yang penuh potensi, hampir tidak ada yang melaksanakanIlya secara penuh, kecuali beberapa prinsip utamanya, itu pun dengan keberapa modifikasi. Sebaliknya para pendidik di lapangan melaksanakan praktik pendidikan yang lebih didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan prakt is, sekalipun tidak banyak dilandasi oleh teori-teori yang kuat.
Seharusnya tidak terjadi hal yang demikian, sebab seharusnya praktik dilandasi oleh teori, tidak ada praktik yang baik tanpa teori yang mapan. Anima teori dengan praktik memang terdapat perbedaan, tetapi keduanya ingat berkaitan erat. Mengenai perbedaan antara teori dengan praktik, beauchamp menjelaskan: Theory by its nature is impractical. The world of practicality is built around
clusters of specific events. The world of theory derives from generalization law a
axiomes and theorems explaining specific events and the relationships among
Walaupun terdapat perbedaan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Teori menjadi pedoman bagi praktik dan praktik memberi umpan balik bagi pengembangan teori. Sebagai ilmu dari segala ilmu, filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu pendidikan dan teori pendidikan. Ada dua kategori teori yaitu teori deskriptif dan preskriptif. Teori deskriptif terdiri atas serangkaian proposisi yang berinterelasi secara logis. Dari proposisi-proposisi tersebut diturunkan secara deduktif informasi- informasi baru, juga dari proposisi-proposisi tersebut hubungan antara beberapa hal dirumuskan. Teori deskriptif terdiri atas serangkaian rencana kegiatan atau proposisi mengenai sesuatu kerangka masalah. Pengembangan teori deskriptif berhubungan dengan pendekatan ilmiah (scientific approach), sedangkan pengembangan teori preskriptif berhubungan dengan pendekatan atau teknik-teknik filosofis (techniques of philosophy).
Filsafat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Kebanyakan teori pendidikan yang ada, kalau tidak berlandaskan psikologi maka bersumber pada filsafat. Filsafat khususnya filsafat pendidikan memberikan pedoman bagi perumusan aspek-aspek pendidikan. Mendidik atau pendidikan berkenaan dengan perbuatanperbuatan yang tidak lepas dari nilai, atau dengan kata lain perbuatan mendidik selalu menyangkut nilai. Teori pendidikan selalu menyangkut tentang teori nilai, etika, yang keduanya merupakan bahasan dari bidang filsafat. Antara keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. John Dewey seorang ahli filsafat pendidikan progresif, umpamanya menyatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan.
Hugh C. Black dalam bukunya A Four fold Classification of Educational Theories (1966) mengemukakan empat teori pendidikan, yaitu teori tradisional, teori progresif, teori hasil belajar, dan teori proses belajar. Teori tradisional menekankan fungsi pendidikan sebagai pemelihara dan penerus warisan budaya, teori progresif memandang pendidikan sebagai penggali potensi anak-anak, dalam teori ini anak menempati kedudukan sentral dalam pendidikan. Teori hasil belajar sesuai dengan namanya mengutamakan hasil, sedangkan teori proses belajar mengutamakan proses belajar.
Teori pendidikan bukan saja berkembang melalui pemikiran p.mikiran filosofis atau teori preskriptif, juga dikembangkan melalui ponglojfisn
pengkajian ilmiah (teori deskriptif). Harry S. Broudy menyatakan perlunya suatu teori pendidikan yang utuh yang membentuk satu kesatuan. Teori pendidikan yang demikian sangat diperlukan mengingat hal-hal sebagai berikut.
a. The present and projected kinds of knowledge and personality traits
re-quired for citizenship, vocation, and self development.
b. A unified theory must be judicious about the latest development in
learn-ing theory and teachlearn-ing technology.
c. A unified theory has to provide for general and special education, for
dif-ferences in ability and bent (Broudy, 1960, hlm. 24).
Brouner mengidentifikasi enam teori pendidikan yang berkembang di merika Serikat pada tahun 1960-an. Keenam teori tersebut dapat dilihat pada Bagan 2.3.
Dalam simposium di Universitas John Hopkins tahun 1961, dibahas hvherapa makalah yang menguraikan apakah pendidikan merupakan
suatu disiplin ilmu atau bukan? Beberapa makalah mengakui pendidikan sebagai disiplin ilmu, makalah lainnya menyangkalnya. Mereka yang menyangkal, memandang pendidikan merupakan aplikasi dari berbagai disiplin. Pendidikan hanyalah suatu profesi, yang ditandai sejumlah pelayanan yang diberikannya.
March Beth dalam buku Education as a Discipline (1965) menegaskan bahwa pendidikan adalah suatu disiplin. la menolak pandangan bahwa pendidikan hanyalah aplikasi dari disiplin-disiplin lain. Pendidikan adalah suatu bidang studi (suatu disiplin) dalam bidangnya. Studi tentang pendidikan merupakan suatu kajian tentang bagaimana cara atau model-model inkuiri disusun, digunakan, dikembangkan, dan disusun kembali. Lebih jauh berisi kajian tentang model-model yang cocok pada suatu tempat, saat, serta syarat-syarat yang diperlukan bagi pelaksanaan model tersebut..
Menurut Beth, studi tentang pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Sejarah tentang teori dan model-model pendidikan
2. Prinsip-prinsip dan prosedur analisis dari model-model pendidikan.
3. Studi tentang fungsi dari model-model yang ada, sebagai bahan dan alat untuk mempelajari dan mengembangkannya.
5. Pelaksanaan model sesuai dengan kondisi waktu, kemampuan para pelaksana, serta fasilitas yang ada.
Terlepas dari apakah pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu atau bukan, pendidikan tetap merupakan suatu bidang studi. Dalam bidang studi tersebut, teori-teori pendidikan dikembangkan. Beauchamp (175, hlm. 43) menyatakan bahwa Irrespective of label, evidence mounts that education is
sufficiently mature to become an organized field of study.
Pengembangan teori pendidikan menjadi semakin besar dan pesat dengan berkembangnya sub-subteori pendidikan, yaitu bimbingan clan konseling, kurikulum, penyuluhan, pengajaran, evaluasi, dan administrasi pendidikan.
C. Teori Kurikulum
Telah diuraikan sebelumnya bahwa teori merupakan suatu perangkat pernyataan yang bertalian satu sama lain, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Perangkat pernyataan tersebut dirumuskan dalam bentuk definisi deskriptif atau fungsional, suatu konstruksi fungsional, asumsi-asunro hipotesis, generalisasi, hukum, atau teorem-teorem. Isi rumusan-rumusan tersebut ditentukan oleh lingkup dari rentetan kejadian yang dicakup, jumlah pengetahuan empiris yang ada, dan tingkat keluasan_ dan kedalaman teori dan penelitian di sekitar kejadian-kejadian tersebut.
1. Konsep kurikulum
Konsep terpenting yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.
Konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, suatu kurikulum, dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara.
Konsep kedua, adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara me- nyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyem- purnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.
Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.
melaksanakan model-model kurikulum. Keempat tuntutan tersebut menjadi kewajiban seorang ahli teori kurikulum. Melalui pencapaian keempat hal tersebut baik sebagai subtansi, sebagai sistem, maupun bidang studi kurikulum dapat bertahan dan dikembangkan.
2. Perkernbangan teori kurikulum
Perkembangan teori kurikulum tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya. Perkembangan kurikulum telah dimulai pada tahun 1890 dengan tulisan Charles dan McMurry, tetapi secara definitif berawal pada hasil karya Franklin Babbit tahun 1918. Bobbit sering dipandang sebagai ahli kurikulum yang pertama, ia perintis pengembangan praktik kurikulum. Bobbit adalah orang pertama yang mengadakan analisis kecakapan atau pekerjaan sebagai cara penentuan keputusan dalam penyusunan kurikulum. Dia jugalah yang menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi kecakapan pekerjaan dan kehidupan orang dewasa sebagai dasar pengembangan kurikulum.
Menurut Bobbit, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumah kecakapan pekerjaan. Pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Kecakapan-kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan sangat bermacam-macam, bergantung pada tingkatannya maupun jenis lingkungan. Setiap tingkatan dan lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, apresiasi tertentu. Hal-hal itu merupakan tujuan kurikulum. Untuk mencapai hal-hal itu ada serentetan pengalaman yang harus dikuasai anak. Seluruh tujuan beserta pengalaman-pengalaman tersebut itulah yang menjadi bahan kajian teori kurikulum.
Werrett W. Charlters (1923) setuju dengan konsep Bobbit tentang analisis kecakapan/pekerjaan sebagai dasar penyusunan kurikulum. Char ters lebih menekankan pada pendidikan vokasional.
ilmiah dalam pendidikan yang dipelopori oleh El. Thorndike, Charles Judd, dan lain-lain. Kedua, keduanya bertolak pada asumsi bahwa sekolah berfungsi mempersiapkan anak bagi kehidupan sebagai drang dewasa. Untuk mencapai hal tersebut, perlu analisis tentang tugas-tugas dan tuntutan dalam kurikulum disusun keterampilan, pengetatitian, sikap, nilai, dan lain-lain yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan orang dewasa. Bertolak pada hal-hal tersebut mereka itionyusun kurikulum secara lengkap dalam bentuk yang sistematis.
Mulai tahun 1920, karena pengaruh pendidikan progresif, berkembang gerakan pendidikan yang berpusat pada anak (child centered). Teori kurikulum berubah dari yang menekankan pada organisasi isi yang diarahkan pada kehidupan sebagai orang dewasa (Bobbit dan Charters) kepada kl•hidupan psikologis anak pada saat ini. Anak menjadi pusat perhatian
Isi kurikulum harus didasarkan atas minat dan kebutuhan alswa. Pendidikan menekankan kepada aktivitas siswa, siswa belajar nu lalui pengalaman. Penyusunan kurikulum harus melibatkan siswa.
Perkembangan teori kurikulum selanjutnya dibawakan oleh Hollis I swell. Dalam peranannya sebagai ketua divisi pengembang kurikulum beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Tennessee, Alabama, Ida, Virginia), ia mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau pekerjaan (society centered) maka Caswell mengembangkan kurikulum yang bersifat interaktif. Dalam pengembangan kurikulumnya, Caswell menekankan pada partisipasi guru-guru, Ism dalam menentukan kurikulum, menentukan struktur dari penyusunan kurikulum, dalam merumuskan pengertian dalam merumuskan tujuan, memilih isi, menentukan kegiatan belajar, kurikulum, menilai hasil, dan sebagainya.
Ralph W. Tylor (1949) mengemukakan empat pertanyaan pokok yang menjadi inti kajian kurikulum:
1. Tujuan pendidikan yang manakah yang ingin dicapai oleh sekolah?
2. Pengalaman pendidikan yang bagaimanakah yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?
3. Bagaimana mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif?
4. Bagaimana kita menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai?
Empat pertanyaan pokok tentang kurikulum dari Tylor ini banyak dipakai oleh para pengembangan kurikulum berikutnya. Dalam konferensi nasional perhimpunan pengembang dan pengawas kurikulum tahun 1963 dibahas dua makalah penting dari George A. Beauchamp dan Othanel Smith. Beauchamp menganalisis pendekatan ilmiah tentang tugas-tugas pengembangan teori dalam kurikulum. Menurut Beauchamp, teori kurikulum secara konseptual berhubungan erat dengan pengembangan teori dalam ilmu-ilmu lain. Hal-hal yang penting dalam pengembangan teori kurikulum adalah penggunaan istilah-istilah teknis yang tepat dan konsisten, analisis dan klasifikasi pengetahuan, penggunaan penelitianpenelitian prediktif untuk menambah konsep, generalisasi atau kaidah-kaidah, sebagai prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam menjelaskan fenomena kurikulum.
Dalam makalah kedua, Othanel Smith menguraikan peranan filsafat dalam pengembangan teori kurikulum yang bersifat ilmiah. Menurut Smith, ada tiga sumbangan utama filsafat terhadap teori kurikulum, yaitu dalam (1) merumuskan dan mempertimbangkan tujuan pendidikan, (2) memilih dan menyusun bahan, dan (3) perumusan bahasa khusus kurikulum.
membantu para ahli teori kurikulum rnenentukan jenis dan lingkup konseptualisasi yang diperlukan dalam teori kurikulum.
Broudy, Smith, dan Burnett (1964) menjelaskan masalah persekolahan dalam suatu skema yang menggambarkan komponen-komponen dari keseluruhan proses mempengaruhi anak. Skema persekolahan dari Broudy dan kawan-kawannya dapat dilihat pada Bagan 2.4.
Beauchamp merangkumkan perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai dengan 1965. Ia mengidentifikasi adanya enam komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu: landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori.
Thomas L. Faix (1966) menggunakan analisis struktural-fungsional yang berasal dari biologi, sosiologi, dan antropologi untuk menjelaskan konsep kurikulum. Fungsi kurikulum dilukiskan sebagai proses bagaimana memelihara dan mengembangkan strukturnya. Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam analisis struktural-fungsional ini. Topik dan subtopik dari pertanyaan ini menunjukkan fenomena-fenomena kurikulum Pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut: (1) pertanyaan umum tentang fenomena kurikulum, (2) sistem kurikulum, (3) unit analisk (Ian unsur unsurnya, (4) struktur sistem kurikulum, (5) Fungsi sistem kurikulum, (6) proses kurikulum (7) prosedur analisis structural fungsional.
BAGAN 2.4 Skema persekolahan dari Broudy, Smith, dan Bunett. CURRICULUM
Content Categories of instruction Modes of Teaching
Facts Symbolic studies Situational
Concept Basic Sciences Modes
Desriptive Developmental studies Operational
Principles Testhetics studies Modes
Attitudes and values systems Associative meanings
and images Intellectual Operations Excecutive Operations Assessment system:
Examinations Tests: Essay-Objective
Teacher Judgements Self evaluation Self inventory"
Alizabeth S. Maccia (1965) dari hasil analisisnya menyimpulkan adanya empat teori kurikulum, yaitu: (1) teori kurikulum (curriculum theory), (2) teori kurikulum-formal (formal-curriculum theory), (3) teori kurikulum valuasional (valuational curriculum theory), dan (4) teori kurikulum praksiologi (praxiological curriculum theory).
Teori kurikulum (curriculum Theory atau event theory) merupakan teori yang menguraikan pemilihan dan pemisahan kejadian/peristiwa kurikulum atau yang berhubungan dengan kurikulum dan yang bukan. Menurut Maccia, kurikulum merupakan bagian dari pengajaran, teori kurikulum merupakan subteori pengajaran. Teori kurikulum formal memusatkan perhatiannya pada struktur isi kurikulum. Teori kurikulum yaluasional mengkaji masalah-masalah pengajaran apa yang berguna/ berharga bagi keadaan sekarang. Teori kurikulum praksiologi merupakan suatu pengkajian tentang proses untuk mencapai tujuan-tujuan kurikulum. Walaupun mungkin, kita tidak setuju dengan seluruh pendapat Maccia, tetapi ia telah berhasil menunjukkan sejumlah dimensi kurikulum yang cukup berharga untuk menjelaskan teori kurikulum.
pengembangan kurikulum, tetapi sistem pengembangan bukan kurikulum. Menurut Johnson, kurikulum merupakan seperangkat tujuan belajar yang terstruktur. Jadi, kurikulum berkenaan dengan tujuan dan bukan dengan kegiatan. Berdasarkan rumusan kurikulum tersebut, pengalaman belajar anak menjadi bagian dari pengajaran.
Johnson menganalisis enam unsur kurikulum, yaitu:
1. A curriculum is a structured series of intended learning out comes.
2. Selection is an essential aspect of curriculum formulation.
3. Structure is an essential charactistic of curriculum.
4. Curriculum guide instruction
5. Curriculum evaluation involeves validation of both selection and
structure.
6. Curriculum is the criterion for instructional evaluation.
Jack R. Frymier (1967) mengemukakan tiga unsur dasar kurikulum, yaitu aktor, artifak, dan pelaksanaan. Aktor adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum. Artifak adalah isi dan rancangan kurikulum. Pelaksanaan adalah proses interaksi antara aktor yang melibatkan artifak. Studi kurikulum menurut Frymier meliputi tiga langkah: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Ada beberapa masalah atau isu substansial dalam pembahasan tentang teori kurikulum, yaitu definisi kurikulum, sumber-sumber kebijaksanaan kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, peranan nilai dalam pengembangan kurikulum, dan implikasi teori kurikulum.
tujuan-tujuan tersebut? Apakah kurikulum perlu mengadakan rumusan yang lebih spesifik tentang rencana dan bahan pengajaran? Apakah perlu ada spesifika4i tentang makna perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum?
1. Sumber Pengembangan Kurikulum
Dari kajian sejarah kurikulum, kita mengetahui beberapa hal yang menjadi sumber atau landasan inti penyusunan kurikulum. Pengembangan kurikulum pertama bertolak dari kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Karena sekolah mempersiapkan anak bagi kehidupan orang dewasa, kurikulum terutama isi kurikulum diambil dari kehidupan orang dewasa. Para pengembang kurikulum mendasarkan kurikulumnya atas hasil analisis pekerjaan dan kehidupan orang dewasa.
Dalam pengembangan selanjutnya, sumber ini menjadi luas meliputi .sernua unsur kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, hidup dalam Iingkungan budaya, dan turut menciptakan budaya. Untuk dapat hidup dalam Iingkungan budaya, ia harus mempelajari budaya, maka budaya menjadi sumber utama isi kurikulum. Budaya ini mencakup ..einua disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan para pakar, itilai-nilai adat-istiadat, perilaku, benda-benda, dan lain-lain.
Sumber lain penyusunan kurikulum adalah anak. Dalam pendidikan *Wm pengajaran, yang belajar adalah anak. Pendidikan atau pengajaran I iiikan memberikan sesuatu pada anak, melainkan menumbuhkan potensipolensi yang telah ada pada anak. Anak menjadi sumber kegiatan pengajaran, ia menjadi sumber kurikulum. Ada tiga pendekatan terhadap anak sebagai sumber kurikulum, yaitu kebutuhan siswa, perkembangan serta minat siswa. Jadi, ada pengembangan kurikulum bertolak dari ,hutuhan-kebutuhan siswa, tingkat-tingkat perkembangan siswa, serta hal hal yang diminati siswa.
keputusan yang dinamis. Pertanyaan pertama yang muncul dalam kurikulum yang berdasarkan nilai adalah: Apakah yang harus diajarkan di sekolah? Ini merupakan pertanyaan tentang nilai. Nilai-nilai apakah yang harus diberikan dalam pelaksanaan kurikulum? Nilai-nilai apa yang digunakan sebagai kriteria penentuan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum.
Terakhir yang menjadi sumber penentuan kurikulum adalah kekuasaan sosial-politik. Di Amerika Serikat pemegang kekuasaan sosial-politik yang menentukan kebijaksanaan dalam kurikulum adalah board of education lokal yang mewakili negara bagian. Di Indonesia, pemegang kekuasaan sosial- politik dalam penentuan kurikulum adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dirjen Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Balitbangdikbud. Pada pendidikan dasar dan menengah, kekuasaan penyusunan kurikulum sepenuhnya ada pada pusat, sedangkan pada perguruan tinggi rektor diberi kekuasaan untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penyusunan kurikulum.
2. Desain dan Rekayasa Kurikulum
Telah diutarakan sebelumnya bahwa ada dua subteori dari teori kurikulum, yaitu desain kurikulum (curriculum design) dan rekayasa kurikulum (curriculum engineering).
Desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses