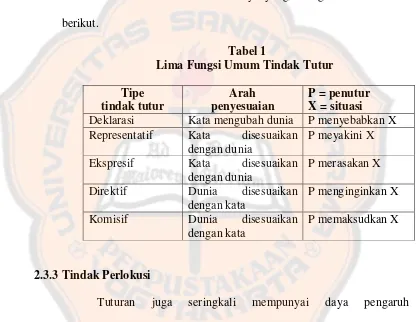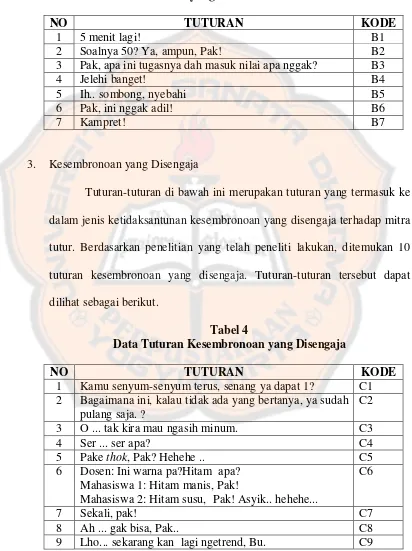i
PROGRAM STUDI PBSID, FKIP, USD, ANGKATAN 2009—2011
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
Disusun oleh:
Olivia Melissa Puspitarini 091224034
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
iv
MOTTO
“D iberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan”
(Yeremia 17:7)
“Kesuksesan bukan kunci kebahagian, tetapi kebahagian adalah kunci kesuksesan. Jika kamu
mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan sukses”
(Albert Schwitzer)
“Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi penghakiman bahwa sesuatu yang lain
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Kary a ini k upersembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus y ang selalu memberikan
berkat dan cinta untukk u.
Orang tua say a, Bapak Cornelius S upriy anto dan Ibu Ch. Asih, terima kasih
untuk doa, dukungan, nasihat, kasih say ang Bapak dan Ibu hingga saat ini
Adik say a, Alvin Christianto,
terima kasih untuk doa dan canda tawany a.
Teman-teman seperjuangan, Elizabeth Rita, Agustina Galuh Eka N, dan
Caecilia Petra Gading May W, terima kasih untuk setiap duk ungan, doa,
dan bantuan y ang luar biasa.
S emua sahabat y ang say a kasihi, terima kasih untuk setiap semangat, doa,
viii
ABSTRAK
Melissa Puspitarini, Olivia. 2013. Ketidaksantunan Linguistik dan Pragmatik Berbahasa antara Dosen dan Mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, Angkatan 2009—2011. Skripsi. Yogyakarta: PBSID, JPBS, FKIP, USD.
Penelitian ini membahas ketidaksantunan linguistik dan pragmatik antara dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, USD, angkatan 2009—2011. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan wujud ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa antara dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, angkatan 2009—2011, (2) mendeskripsikan penanda ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, angkatan 2009—2011, dan (3) mendeskripsikan makna ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, angkatan 2009—2011.
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa Program Studi PBSID. Data penelitian berupa tuturan lisan yang tidak santun. Instrumen penelitian ini adalah panduan wawancara, daftar pertanyaan pancingan, dan daftar kasus. Metode pengumpulan data adalah metode simak dan metode cakap. Teknik pengumpulan data dari metode simak diwujudkan dengan teknik dasar yaitu teknik sadap. Teknik dasar ini diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik simak libat cakap. Teknik tersebut diakhiri dengan teknik catat. Teknik pengumpulan data dari metode cakap adalah teknik pancing sebagai teknik dasar. Teknik dasar ini diikuti dengan teknik cakap semuka dan tansemuka. Teknik tersebut diakhiri dengan teknik rekam dan catat. Teknik rekam dan catat ini diwujudkan peneliti dengan mengintepretasikan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi. Peneliti menganalisis data dengan mengutip data dan konteks tuturan. Langkah terakhir yaitu peneliti mengintepretasikan makna tuturan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontekstual.
ix ABSTRACT
Melissa Puspitarini, Olivia. 2013. Linguistic and Pragmatic Language Impoliteness between Lecturers and Students at PBSID, USD, Academic Year 2009—2011. Thesis.Yogyakarta: PBSID, JPBS, FKIP, USD.
This research aims to discuss abous the Linguistic and Pragmatic Language Impoliteness Between Lecturers and Students at PBSID, USD, academic year 2009—2011. The purpose of this research are (1) to describe the form of linguistic and pragmatic language impoliteness between lecturers and students in the PBSID, FKIP, USD, academic year 2009—2011, (2) to describe the language impoliteness marker linguistic and pragmatic used by lecturers and students in the PBSID, FKIP, USD, academic year 2009—2011, and (3) describe the meaning language impoliteness linguistic and pragmatic used by PBSID, FKIP, USD, academic year 2009—2011.
The type of research include descriptive qualitative research. The subjets of this research are lecturers and students of PBSID, USD, academic year 2009— 2011. The objects of this research were the speeches not impolite. This research instrument is a guideline or interview guide, inducement, and a list of cases. The instruments used in this research are interview, elicitation, and cases studies using language impoliteness theory. The roundup data method used are grouping and interview. The collecting data method uses tapping method as a basic method, the continuation technique is direct interview and the last technique is written data recording.Interview technique is an elicitation technique as a basic technique. The follow up technique is direct interview and indirect interview. Both the techniques can be applied both in grouping and interview. The researcher can use those two techniques both in grouping and interview by inventoring, indentifying, clarifying, and alayzing the data. In analyzing the data, the research cites the data and the spoken language. The final step done by the researcher is interpreting the meaning of the language. The data analysis used in this research is contextual analysis method.
x
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Ketidaksantunan Linguistik Dan Pragmatik Berbahasa Antara Dosen Dan Mahasiswa Program Studi PBSID, FKIP, USD, Angkatan 2009/2011” ini dengan baik. Sebagaimana disyaratkan dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (PBSID), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, penyelesaian
skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini berhasil diselesaikan karena bantuan,
doa, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dari lubuh hati terdalam mengucapkan terima kasih kepada:
1. Rohandi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma
2. Dr. Yuliana Setiyaningsih, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
3. Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum., selaku Wakil Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah sekaligus dosen pembimbing II yang bijaksana memberikan bimbingan, motivasi, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum., selaku dosen pembimbing I selalu
memberikan nasihat, bimbingan, motivasi, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah yang ramah, selalu mendukung, dan memberikan perhatian, bantuan, pengarahan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan penulis
xi
6. Sdr. Robertus Marsidiq, selaku staf sekretariat PBSID yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan adminitrasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Cornelius Supriyanto dan Ibu Ch. Asih yang penuh kasih sayang dan ketulusan memberikan doa dan motivasi. Serta adikku, Alvin Christianto, terima kasih dukungan, semangat, dan doanya.
8. Para sahabatku Elizabeth Rita, Agustina Galuh Eka, Caecilia Petra Gading, dan OMK se-Paroki Pakem, terima kasih untuk waktu, pikiran, tenaga, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan
skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan PBSID angkatan 2009 terima kasih atas dukungan, doa, kebersamaan, canda tawa, kerja sama, dan pertemanan kita yang luar biasa.
10. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah angkatan 2009—2011 yang telah bersedia menjadi sumber data dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna seperti pepatah tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan keterbatasan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
xii DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………... ii
HALAMAN PENGESAHAN ……….... iii
HALAMAN MOTTO ………. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ………. v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ……… vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH …………. vii
ABSTRAK ………..………. viii
ABSTRACT ………..……… ix
KATA PENGANTAR ………..……….. x
DAFTAR ISI ………..………. xii
DAFTAR TABEL ………..………. xvii
DAFTAR BAGAN ………..……… xviii
BAB I PENDAHULUAN ………..……… 1
1.1 Latar Belakang Masalah ………..………… 1
1.2 Rumusan Masalah ………..…………..…… 6
1.3 Tujuan Penelitian ………..……… 7
1.4 Manfaat Penelitian ………..…………..…… 7
1.5 Batasan istilah ………..………….…… 8
1.6 Sistematika Penyajian ………..……….…… 9
BAB II KAJIAN TEORI ………..……….…… 11
2.1 Penelitian yang Relevan ………..……….. 12
2.2 Teori Ketidaksantunan Berbahasa ………..……….. 15
2.2.1 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Locher ……..….. 15
xiii
2.2.3 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Culpeper …..….. 19
2.2.4 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Terkourafi …….. 21
2.2.5 Teori Ketidaksantunan Berbahasa dalam Pandangan Locher and Watts 22 2.2.6 Rangkuman ………..…………....…… 24
2.3 Tindak Tutur ………..…………....…....…… 25
2.3.1 Tindak Lokusi ………..……… 25
2.3.2 Tindak Ilokusi ………..……… 26
2.3.3 Tindak Perlokusi ………..……… 30
2.3.4 Rangkuman ………..…………....…… 32
2.4 Konteks Tuturan ………..…………...…… 33
2.4.1 Penutur dan Lawan Tutur ………..…………...…… 36
2.4.1.1 The Utterer dan The Interpteter………..…………...….. 39
2.4.1.2 Aspek-aspek MentalPengguna Bahasa ……..…………...….. 40
2.4.1.3 Aspek-aspek Sosialdan Budaya Pengguna Bahasa ……...….. 42
2.4.1.4 Aspek-aspek FisikPengguna Bahasa ………..…………....…… 45
2.4.2 Konteks Sebuah Tutur ………..…………....…… 46
2.4.3 Tujuan Sebuah Tuturan ………..…………..…… 48
2.4.4 Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Kegiatan: Tindak Ujar …..…… 49
2.4.5 Tuturan Sebagai Produk Tindak Verbal ………..………. 50
2.4.6 Rangkuman ………..…………....……. 53
2.5 Bunyi Suprasegmental ………..…………...…… 51
2.5.1 Tinggi-rendah (Nada, Tona, Pitch) 52 2.5.2 Keras-lemah (Tekanan, Aksen, Stress) ………..…………..…… 53
2.5.3 Intonasi ………..…………...…… 54
2.5.4 Rangkuman ………..…………....…… 55
2.6 Pilihan Kata ………..…………....…...…… 55
2.6.1 Bahasa Standar dan Nonstandar ………..…………....….... .….. 57
2.6.2 Kata Ilmiah dan Kata-kata Populer ………..…………....…...….. 59
xiv
2.6.4 Kata Percakapan ………..…………....…... 60
2.6.5 Slang ………..…………....…... 61
2.6.6 Idiom ………..…………....…... 62
2.6.7 Bahasa Artifisial ………..…………....…... 62
2.6.8 Kata Seru ………..…………....…... 63
2.6.9 Kata Fatis ………..…………....…... 63
2.6.10 Rangkuman ………..…………....…... 64
2.7 Kerangka Berpikir………..…………....…... 65
BAB III METODELOGI PENELITIAN ………..…………....…... 67
3.1 Jenis Penelitian ………..…………....…... 67
3.2 Subjek Penelitian ………..…………....…... 67
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data ………..…………....…... 68
3.4 Instrumen Penelitian ………..…………....…... 70
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data ………..…………....…... 71
3.6 Sajian Hasil Data ………..…………....…... 73
3.7 Trianggulasi Hasil Analisis Data ………..…………....…... 74
BAB IV PEMBAHASAN ………..…………....…... 75
4.1 Deskripsi Data ………..…………....…... 75
4.2 Hasil Analisis Data ………..…………....…... 79
4.2.1 Melecehkan Muka ………..…………....…... 79
4.2.1.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik ………....…... 82
4.2.1.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ………....…... 83
4.2.1.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik……....…... 85
4.2.1.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ……....…... 86
4.2.1.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa yang Melecehkan Muka .... 88
4.2.2 Memain-mainkan Muka ………..…………....…... 89
xv
4.2.2.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ………..…………... 92
4.2.2.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………..…………... 93
4.2.2.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………..…………... 94
4.2.2.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa Memainkan Muka ... ... 96
4.2.3 Kesembronoan yang Disengaja ………..………... 97
4.2.3.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik ………..………... 99
4.2.3.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ………..………... 100
4.2.3.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………..………... 102
4.2.3.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………..………... 103
4.2.3.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa Kesembronan Sengaja ... 104
4.2.4 Menghilangkan Muka ………..…………....…... ... 105
4.2.4.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik .…………....…... ... 108
4.2.4.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik …………....…... ... 108
4.2.4.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………....…... 110
4.2.4.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………....…... 111
4.2.4.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa Menghilangkan Muka ... 113
4.2.5 Mengancam Muka Sepihak ………..…………....…... 113
4.2.5.1 Wujud Ketidaksantunan Linguistik ……..…………....…... 116
4.2.5.2 Wujud Ketidaksantunan Pragmatik ……..…………....……... 117
4.2.5.3 Penanda Ketidaksantunan Linguistik ………....…... 118
4.2.5.4 Penanda Ketidaksantunan Pragmatik ………....…... 119
4.2.5.5 Makna Ketidaksantunan Berbahasa yang Mengancam Muka ... 121
4.3. Pembahasan ………..…………....…... 122
4.3.1 Melecehkan Muka ………..…………....…... 123
4.3.2 Memain-mainkan Muka ………..…………....…... 136
4.3.3 Kesembronoan yang Disengaja ……..…………....…... 150
4.3.4 Menghilangkan Muka ………..…………....…... 166
xvi
BAB V PENUTUP ……….……. 199
5.1 Simpulan ………..……….……. 199
5.1 Saran ………..…………...……. 204
DAFTAR PUSTAKA ………..…………..……. 206
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Lima Fungsi Umum Tindak Tutur ……….…….. 30 Tabel 2. Tuturan Ketidaksantunan yang Melecehkan Muka ………. 76
xviii
DAFTAR BAGAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan alat untuk
menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Hal penting yang
berkenaan dengan keberhasilan berkomunikasi adalah melalui pengaturan
interaksi sosial yang mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur.
Keberhasilan ini menciptakan suasana kesantunan yang memungkinkan
transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur dan mitra tutur.
Keberhasilan berkomunikasi juga ditentukan oleh konteks atau situasi antara
penutur dan mitra tutur.
Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Bahasa diartikan
sebagai sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para
anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi,
dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 2008:46). Linguistik dipelajari
sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu lain seperti kesusasteraan, filologi,
pengajaran bahasa, penerjemahan, dan sebagainya. Satuan gramatikal
linguistik adalah fonetik, fonologi, sintaksis, dan semantik. Satuan gramatikal
tersebut masih memandang bahasa dari segi linguistiknya (stuktural), analisis
bahasa yang mengfokuskan penggunaan bahasa yaitu konteks dan latar
Penelitian bahasa selama ini hanya mengkaji dari struktural saja.
Hal tersebut memungkinkan untuk melakukan pembenahan bahwa
analisis bahasa bukan hanya dipandang dari segi struktural (internal
bahasa) tetapi bahasa perlu dikaji dari segi eksternal bahasa, dalam hal
ini pragmatik menawarkan paradigma ilmu baru untuk menganalisis
tuturan bahasa. Studi bahasa yang mempelajari makna yang
disampaikan penutur dan ditafsirkan oleh mitra tutur disebut pragmatik.
Pragmatik merupakan ilmu baru yang menganalisis apa yang
dimaksudkan seseorang dengan tuturan-tuturan melalui kata atau frasa
yang digunakan. Penafsiran maksud yang disampaikan tidak lepas dari
konteks diperlukan pertimbangan penyampaian maksud dengan orang
lain yang mereka ajak bicara, di mana, kapan, dan dalam keadaan apa.
Oleh karena itu, pragmatik disebut pula studi tentang makna
kontekstual (Yule, 2006:4).
Alasan lain pentingnya bahasa dikaji dari segi pragmatik yaitu
kebanyakan peneliti linguistik formal hanya meneliti sebuah satuan
bahasa tanpa kaitan dengan pemakaian bahasa sehari-hari. Peneliti tidak
akan mempermasalahkan mengapa dan bagaimana sebuah kalimat atau
tuturan muncul. Padahal, dalam pemakaian bahasa sehari-hari, terdapat
unsur-unsur penting yang memengaruhi pemakaian bahasa. Unsur
tersebut adalah konteks. Konteks sangat memengaruhi bentuk bahasa
peneliti linguistik terhadap unsur konteks itulah, hasil analisisnya
menjadi tidak memadai (Nugroho, 2009:117).
Menurut Rahardi (2007:20), konteks tuturan diartikan sebagai
semua latar belakang (background knowledge) yang diasumsikan
sama-sama dimiliki dan dipahami bersama-sama oleh penutur dan mitra tutur, serta
yang mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksudkan
oleh si penutur dalam proses keseluruhan proses bertutur. Dengan kata
lain, sebuah tuturan tidak hanya dianalisis dari segi struktural saja,
keterlibatan konteks sangat memengaruhi daya pragmatik (pragmatic
force) dalam sebuah peristiwa tutur.
Penekanan aspek konteks dalam pragmatik memberikan
kejelasan mengenai analisis linguistik dan analisis pragmatik. Kajian
pragmatik adalah situasi dan latar belakang penutur. Oleh karena itu,
perpaduan penelitian analisis linguistik dan pragmatik memperjelas
maksud dan tujuan dari penutur sehingga terjadi komunikasi yang
lancar tanpa ada persinggungan yang tidak diinginkan.
Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa
dengan konteks yang menjadi dasar dari penjelasan tentang pemahaman
bahasa. Bentuk-bentuk pragmatik adalah implikatur, tindak tutur,
maksim, dan kesantunan. Banyak peneliti mengkaji bentuk-bentuk
pragmatik itu dalam komunikasi di masyarakat, tertulis ataupun lisan.
kesantunan. Banyak ahli bahasa menganalisis teori-teori kesantunan
berbahasa dalam lingkup masyarakat yang menjadi sebuah patokan
berkomunikasi. Fraser dalam Gunarwan (1992) mendefinisikan
kesantunan adalah “property associated with neither exceeded any right
nor failed to fullfill any obligation”. Dengan kata lain, kesantunan
adalah properti yang diasosiasikan dengan ujaran dan di dalam hal ini
menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya
atau tidak mengingkari memenuhi kewajibannya. Pernyataan tersebut
dimaksudkan bahwa kita dalam berkomunikasi haruslah santun, tidak
boleh menyinggung perasaan orang lain sehingga tidak akan timbul
perselisihan.
Pranowo (2009:13) menjelaskan bahwa pemakaian bahasa yang
santun merupakan bentuk pengaktualisasi diri secara terbuka tanpa harus
ada perasaan takut. Selain fenomena kesantunan, ada pula fenomena
ketidaksantunan berbahasa yang banyak terjadi di kalangan masyarakat
penutur bahasa. Ketidaksantunan berbahasa mengakibatkan interaksi
antara penutur dan mitra tutur tidak lancar. Teori-teori yang membahas
ketidaksantunan berbahasa masih jarang dikupas sehingga timbul
ketimpangan studi antara teori kesantunan dan ketidaksantunan. Hal
tersebut mengakibatkan fenomena pragmatik tidak dikaji secara
mendalam, tidak akan bermanfaat banyak bagi perkembangan ilmu
Berbahasa yang santun sudah selayaknya dipraktikkan di
lingkungan masyarakat terutama dalam lingkungan yang formal,
misalnya saja di lingkungan pendidikan. Berbahasa yang santun
selayaknya terjadi dalam interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam
suasana formal. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi pelanggaran
kesantunan yang disebut ketidaksantunan berbahasa. Bentuk-bentuk
ketidaksantunan berbahasa harus dihindari dalam praktik
berkomunikasi, terutama di lingkungan pendidikan.
Penulis memfokuskan indikator ketidaksantunan berbahasa ranah
pendidikan di lingkungan universitas. Kesantunan berbahasa selayaknya
tercipta di lingkungan kampus yaitu kesantunan berbahasa antara dosen
dan mahasiswa. Kesantunan berbahasa dalam lingkungan pendidikan
merupakan wujud pembentukan karakter bangsa. Subjek penelitian ini
adalah dosen dan mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra.
Alasan pemilihan subyek penelitian tersebut karena jurusan tersebut
lebih menekankan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Penulis memilih angkatan 2009—2011 dengan alasan bahwa peristiwa
ketidaksantunan biasanya terjadi antara orang yang mempunyai
kedekatan secara emosional maupun fisik.
Pemakaian bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan
bahasa sesuai dengan situasi atau konteks sedangkan benar yaitu sesuai
Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia itu yang
benar dan baik terutama berbicara dengan orang yang lebih tua misalnya
dosen. Oleh karena itu, kita berkomunikasi kita harus mengetahui siapa
lawan bicara kita dan tempat kita berbicara. Orang Jawa mengatakan
bahwa dalam berkomunikasi harus ada unggah-ungguh atau tata
kramanya terutama saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua.
Dari fenomena-fenomena di atas, penulis beranggapan bahwa penelitian
mengenai kesantunan berbahasa di lingkungan pendidikan terutama di
universitas antara dosen dan mahasiswa sangat menarik dan perlu untuk
dilakukan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, secara terperinci
masalah-masalah yang akan ditelti sebagai berikut.
1. Wujud ketidaksantunan linguistik dan pragmatik apa saja yang
diucapkan antara dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,
angkatan 2009—2011?
2. Penanda ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa apa
saja yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,
3. Apa makna ketidaksantunan linguistik dan pragmatik berbahasa
yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,
angkatan 2009—2011?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah seperti di atas, tujuan penelitian
ini secara terperinci sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan wujud ketidaksantunan linguistik dan pragmatik
berbahasa antara dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP, USD,
angkatan 2009—2011.
2. Mendeskripsikan penanda ketidaksantunan linguistik dan pragmatik
berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP,
USD, angkatan 2009—2011.
3. Mendeskripsikan makna ketidaksantunan linguistik dan pragmatik
berbahasa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa PBSID, FKIP,
USD, angkatan 2009—2011.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian kesantunan berbahasa dalam ranah pendidikan
khususnya antara dosen dan mahasiswa ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi para pihak yang memerlukan. Ada dua manfaat yang dapat
1. Manfaat teoretis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah
memberikan sumbangan untuk perkembangan teori-teori pragmatik
dan memperluas kajian dan memperkaya khasanah teoretis tentang
ketidaksantunan dalam berbahasa sebagai fenomena pragmatik baru.
Teori-teori tersebut menjadi referensi bagi praktisi yaitu dosen, guru,
mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan sebagai tambahan
pengetahuan dan wawasan mengenai ketidaksantunan berbahasa.
2. Manfaat secara praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah
memberikan masukan para praktisi dalam bidang pendidikan yaitu
dosen, guru, mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan untuk
mempertimbangkan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dan
menghindari bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa.
1.5 Batasan Istilah
a. Ketidaksantunan
Ketidaksantuan berbahasa adalah perilaku berbahasa seseorang yang
mengancam muka dan ancaman terhadap muka itu dilakukan secara
sembrono (gratuitous), hingga akhirnya tindakan sembrono itu
menimbulkan konflik bahkan pertengkaran tersebut dilakukan
dengan kesengajaan (purposeful), maka tindakan berbahasa itu
b. Linguistik
Linguistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bahasa sebagai
bagian kebudayaan berdasarkan struktur bahasa tersebut (Parera,
1982:20).
c. Pragmatik
Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari apa saja yang termasuk
struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dengan mitra
tuturnya sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa yang sifatnya
ekstralinguistik (Verhaar, 1996:9).
d. Konteks
Konteks adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik
dan sosial sebuah tuturan. Leech (dalam Nugroho, 2009:119)
menambahkan bahwa konteks adalah suatu pengetahuan latar
belakang yang secara bersama dimiliki oleh penutur dan petutur, dan
konteks membantu petutur menafsirkan atau menginterpretasikan
maksud tuturan penutur.
1.6 Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan penelitian dijabarkan beberapa hal, yang
meliputi pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian
dan pembahasan, dan penutup. Bab I adalah pendahuluan, yang berisi
tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) batasan istilah, dan (6)
sistematika penyajian. Keenam hal tersebut yang menjadi alasan
peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Ketidaksantunan
Linguistis dan Pragmatis Antara Mahasiswa dan Mahasiswa PBSID
Angkatan 2009—2011 di Universitas Sanata Dharma”.
Bab II adalah kajian teori yang berisi tiga pokok bahasan yaitu
(1) penelitian yang relevan, (2) kajian pustaka, dan (3) kerangka
berpikir. Kajian hasil penelitian yang terdahulu haruslah memiliki
relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua teori berkaitan
dan menjadi landasan penelitian.
Bab III metode penelitian yang berisi enam hal yaitu (1) jenis
penelitian, (2) subjek penelitian, (3) metode dan teknik pengumpulan
data, (4) instrumen penelitian, (5) metode dan teknik analisis data, (6)
hasil analisis data.
Bab IV hasil dan pembahasan yang berisi tiga hal yaitu (1)
deskripsi data, (2) hasil analisis data, dan (3) pembahasan. Bab V
penutup yang berisi dua hal yaitu (1) kesimpulan dan (2) saran. Selain
beberapa bab di atas, peneliti juga menyajikan daftar pustaka dan
11
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1Penelitian yang Relevan
Penelitian biasanya beranjak dari penelitian lain yang dapat dijadikan
sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Dengan demikian, peninjauan
terhadap penelitian lain sangat penting, sebab bisa digunakan untuk
mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang
akan dilakukan. Selain itu, peninjauan penelitian sebelumnya dapat
digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian
yang akan dilakukan.
Penelitian yang dilakukan oleh A. S. Joko Sukoco (2002) dalam
skripsinya yang berjudul “Penanda Lingual Kesantunan Berbahasa Indonesia
dalam Bentuk Tuturan Imperatif: Studi Kasus Pemakaian Tuturan Imperatif
di Lingkungan SMU Stela Duce Bantul Tahun 2002”. Penelitian ini
mendasari penanda kesantunan dalam tuturan imperatif. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan teknik catat. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa adanya tuturan imperatif berdasarkan
makna komunikasinya terbagi menjadi tuturan imperatif larangan, tuturan
imperatif permintaan, dan tuturan imperatif ajakan. Penanda kesantunan
dalam tuturan imperatif dapat diwujudkan dari intonasi tuturan, isyarat
imperatif yang santun berimplikasi pada terbentuknya tutur kata dan
perilaku peserta yang baik sehingga menjadi orang yang berbudi luhur.
Penelitian juga dilakukan oleh Weny Anugraheni (2011) dalam
skripsisnya yang berjudul “Jenis Kesantunan dan Penyimpangan
Kesantunan dalam Tuturan Imperatif Guru kepada Siswa Kelas VII SMP
Negeri 1 Pringsurat Temanggung dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Tahun 2011”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
ada dua jenis kesantunan dalam tuturan imperatif yaitu kesantunan
imperatif tuturan deklaratif dan kesantunan imperatif tuturan imperatif.
Kedua jenis tuturan tersebut masih dibagi lagi menjadi bermacam-macam
jenis sesuai dengan tuturan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
tuturan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pringsurat Temanggung
melakukan penyimpangan kaidah kesantunan berbahasa kepada siswa
yang disebabkan tidak konsistennya keingianan guru dalam praktik
pemakaian tutura, kaidah kesantunan belum sepenuhnya dimiliki oleh guru
bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia belum sepenuhnya memahami
bagaimana pemakaian bahasa yang baik dan santun.
Penelitian juga dilakukan oleh Rahardi (1999) dalam penelitiannya
yang berjudul “Imperatif dalam Bahasa Indonesia: Penanda-penanda
Kesantunan Lingustiknya”. Penelitian tersebut mendasari adanya empat
dalam bahasa Indonesia. Keempat pemarkah tersebut adalah (1) panjang
pendek tuturan, (2) urutan tutur, (3) intonasi dan isyarat kinesik, (4)
ungkapan-ungkapan penanda kesantunan.
Kesantunan dalam berbahasa bukan menjadi hal baru bagi linguis
dan pragmatisis. Penelitian tentang kesantunan berbahasa sudah banyak
dilakukan dan bukan menjadi fenomena baru lagi. Orang berbicara pasti
mempertimbangkan diksi, ungkapan santun, dan struktur kalimat yang
benar. Sebaliknya, orang yang berniat buruk pasti akan menimbulkan
konflik dengan ditandai diksi, ungkapan, atau struktur kalimat yang tidak
benar dan tidak santun. Kesantunan berbahasa Indonesia mampu
menghaluskan budi dan perilaku pemakaiannya. Brown dan Levinson
(dalam buku Miriam A Locher, 2008:3) menjelaskan kesantunan sebagai a
universal concept and as technical term to describe relational work that is
carried out to mitigate face-threatening acts. Dengan demikian, kesopanan
adalah bagian dari fenomena pragmatik yang menggambarkan perilaku
seseorang untuk mengurangi ‘wajah-mengancam’.
Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan di atas merupakan salah
satu penelitian kesantunan berbahasa yang sudah banyak dibahas oleh
banyak ahli. Namun, penelitian mengenai fenomena pragmatik yaitu
ketidaksantunan berbahasa belum banyak yang mengkaji.
Penelitian-penelitian kesantunan yang dijelaskan di atas menjadi dasar Penelitian-penelitian
ketidaksantunan sebab penelitian kesantunan merupakan pioner dari
fenomena baru dalam penelitian bahasa. Penelitian tersebut dikatakan
sebagai fenomena baru karena banyak peneliti yang meneliti kesantunan
berbahasa namun jarang peneliti yang membahas ketidaksantunan
berbahasa. Hal tersebut mengakibatkan kelangkaan studi ketimpangan
fakta studi ketidaksantunan dan kesantunan dan menyisyaratkan berjalan
lambatnya studi pragmatik.
Kelangkaan studi ketidaksantunan berbahasa ini diperkuat oleh
pendapat Locher (melalui Rahardi, 2010:67) yang menyatakan bahwa
enormous imbalances exists between academic interest in politeness
phenomena as oppsed to impoliteness phenomena. Pernyataan demikian
mengindikasikan bahwa bukan hanya ketimpangan dalam pengertian yang
biasa-biasa saja, namun Locher menjelaskan lebih lanjut bahwa fenomena
pragmatik mengalami ketimpangan yang sangat besar yaitu dalam studi
kesantunan dan ketidaksantuan berbahasa. Hal tersebut mengakibatkan
pemahaman pragmatik mengenai ketidaksantunan kepada mahasiswa atau
ahli pragmatik tidak tuntas. Senada dengan pendapat Rahardi (2010:66)
bahwa studi yang fenomena pragmatik selama ini tidak akan memberikan
kontribusi signifikan terhadap perbaikan sikap dan perilaku mereka
2.2Teori Ketidaksantunan Berbahasa
Ketidaksantunan berbahasa merupakan bentuk pertentangan
kesantunan bersama. Ketidaksantunan bahasa sering terjadi di kalangan
masyarakat, terutama di kalangan pendidikan. Teori-teori yang mendasari
teori ketidaksantunan dalam berbahasa yaitu
2.2.1 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher
Teori pandangan kesantunan klasik menjelaskan bahwa perilaku
mengancam muka merupakan perilaku berbahasa tidak santun. Locher
(2008:3) memberikan pendapat mengenai ketidaksantunan dalam
berbahasa yang dapat dipahami sebagai, ‘… behaviour that is
face-aggravating in a particular context.’ Intinya bahwa ketidaksantunan
berbahasa itu bukan hanya sekedar mengancam muka tetapi perilaku
‘melecehkan’ muka (face-aggravate). Intepretasi lain yang berkaitan
dengan definisi Locher ini adalah tindakan berbahasa bukanlah sekedar
perilaku yang melecehkan muka melainkan juga tindakan
“memain-mainkan muka” (Rahardi, 2010:68). Tuturan (1) pada bagian berikut
dapat memperjelas pernyataan ini
(1) “Kamu itu bodoh tidak konsultasi dengan saya dulu. Kok langsung observasi!”
(2) “Kamu tu gimana? Malah corat-coret.”
Informasi Indeksal
Tuturan (1) pada contoh di atas dituturkan oleh seorang dosen
kepada mahasiswanya di dalam sebuah ruang dosen. Pada saat itu,
Mahasiswa itu melakukan obervasi tanpa meminta bimbingan kepada
dosennya sebelumnya. Tuturan (2) dituturkan oleh seorang dosen
kepada mahasiswa di dalam kelas. Saat itu dosen sedang meneliti
pekerjaan mahasiswa lalu ia melihat salah satu mahasiswa
mencorat-coret buku teori bukan menulis di buku catatan. Hal tersebut membuat
dosen marah.
Tuturan (1) dan (2) merupakan bentuk ketidaksantunan
berbahasa yaitu melecehkan muka karena penutur berusaha mengatakan
langsung kesalahan mitra tutur tanpa ada kata-kata yang diperhalus.
Tuturan (1) penutur mengatakan mitra tutur bodoh secara langsung,
tanpa ada penghalusan kata misalnya kurang pandai. Pernyataan
tersebut mengakibatkan mitra tutur merasa dilecehkan atas
perbuatannya. Tuturan (2) penutur mengatakan lebih halus, penutur
ingin menyalahkan mitra tutur yang hanya bermain-main saja dalam
perkulihan. Tuturan itu juga membuat mitra tutur merasa dilecehkan.
Locher (2008:3) juga mendefinisikan bahwa kesantunan adalah bentuk
memain-mainkan muka. Tuturan (3) pada bagian berikut dapat
memperjelas pernyataan ini
Informasi Indeksal
Tuturan (3) dituturkan oleh seorang dosen yang menguji ujian di
kelas. Tuturan itu teradi pada saat mahasiswa tidak segera mengerjakan
soal ujian. Dosen kesal melihat mahasiswanya ada yang ribut saat ujian
sehingga dosen mengeluarkan kata-kata tersebut. Dosen tersebut
biasanya memberikan waktu dan kesempatan kepada mahasiswa untuk
berpikir namun kali ini dosen itu berbeda tuturan penutur terkesan tidak
sabar. Tuturan tersebut termasuk bentuk ketidaksantunan yaitu
memain-mainkan muka karena tindakan dosen yang biasa ramah berubah
menjadi galak dan terkesan tidak sabar. Jadi, tuturan (1), (2), dan (3)
merupakan contoh bentuk ketidaksantunan yaitu melecehkan muka dan
memain-mainkan muka. Tuturan melecehkan muka terjadi bila penutur
tidak menyukai tindakan atas mitra tutur yang seenaknya saja
sedangkan memain-mainkan muka terjadi bila tuturan yang tidak biasa
dikeluarkan atau dilontarkan kepada penutur, saat itu terjadi karena
adanya keadaan yang tidak disukai penutur terhadap mitra tutur.
2.2.2 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Bousfield
Sementara itu menurut pandangan Bousfield (dalam buku
Bousfield and Miriam A Locher, 2008:3) ketidaksantunan dalam
berbahasa dipahami sebagai, ‘The issuing of intentionally gratuitous
and conflictive face-threatening acts (FTAs) that are purposefully
‘kesembronoan’ (gratuitous), dan konfliktif (conflictive) dalam praktik
berbahasa yang tidak santun itu. Jadi perilaku berbahasa seseorang yang
mengancam muka dan ancaman terhadap muka itu dilakukan secara
sembrono (gratuitous), hingga akhirnya tindakan sembrono itu
menimbulkan konflik bahkan pertengkaran, dan tindakan tersebut
dilakukan dengan kesengajaan (purposeful), maka tindakan berbahasa
itu merupakan realitas ketidaksantunan berbahasa.
Ada beberapa indikasi penentu kesembronan yaitu tuturan
dinyatakan secara langsung, tuturan negatif, tuturan positif, tuturan
mengandung implikatur, dan kesantunan yang ditahan. Tuturan–tuturan
pada bagian berikut akan memperjelas pernyataan ini.
(4) “Ah ... bajigur!” (5) “Su, kabarmu pie?”
(6) “Bajumu itu gak cocok ama kulitmu, mil!” (7) “Eh... kamu potong ya.”
(8) A : “Ini buat kamu. Aku buat sendiri lho.” B : “Oo.. ya ntar tak makan.”
Informasi Indeksal
Tuturan (4) dituturkan oleh seorang mahasiswa di ruang dosen.
Wujud kebahasaan yang disampaikan kepada dosen karena penutur
kecewa dengan perlakuan kasarnya saat mahasiswa sedang konsultasi
pekerjaannya. Tuturan (5) dituturkan oleh seorang mahasiswa menyapa
mahasiswa lain yang sudah berteman sangat lama. Kata su bisa
diartikan buruk namun penutur mengatakan dengan langsung dan mitra
tersebut termasuk wujud ketidaksantunan karena dapat menimbulkan
konflik. Tuturan (6) dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa
di ruang dosen saat mahasiswa konsultasi laporan akhir. Penutur
mengomentari pakaian yang dikenakan mitra tutur. Penutur merasa
pakaian mitra tutur tidak pantas dikenakan di kampus. Tuturan (7)
dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada mahasiswa lain di dalam
kelas saat akan memulai perkulihaan. Penutur melihat mitra tutur
potong rambut. Menurut penutur, potongan rambut mitra tutur tidak
cocok dengan bentuk wajahnya. Bentuk kebahasan yang dipakai tidak
mengatakan langsung tetapi menggunakan kata-kata yang menyindir.
Tuturan (8) dituturkan oleh mahasiswa kepada mahasiswa lain. Penutur
membuatkan kue kesukaan mitra tutur. Penutur berasumsi bahwa mitra
tutur akan mengucapkan terima kasih ternyata mitra tutur tidak
mengatakan. Bentuk kebahasan itu dapat membuat konflik antara
penutur dan mitra tutur.
2.2.3 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Culpeper
Pemahaman Culpeper (dalam buku Bousfield and Locher,
2008:3) tentang ketidaksantunan berbahasa adalah, ‘Impoliteness, as I
would define it, involves communicative behavior intending to cause the
“face loss” of a target or perceived by the target to be so.’ Dia
memberikan penekanan pada fakta ‘face loss’ atau ‘kehilangan
konsep ‘kelangan rai’ (kehilangan muka) bisa diartikan menjatuhkan
orang lain secara langsung.
Jadi, ketidaksantunan dalam berbahasa itu merupakan perilaku
komunikatif yang diperantikan secara intensional untuk membuat orang
benar-benar kehilangan muka (face loss), atau setidaknya orang tersebut
‘merasa’ kehilangan muka. Pernyataan tersebut dapat diartikan pula,
ketidaksantunan berbahasa itu berusaha menjatuhkan orang lain dengan
mengungkapkan kesalahan secara langsung kepada lawan bicara.
Tuturan (9) pada bagian berikut akan memperjelas pernyataan ini.
(9) “Wah, kamu itu. Sudah IP rendah, mengerjakan soal gampang saja tidak bisa. Wis bali wae lek rabi.”
Informasi Indeksal
Tuturan (9) dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa di
dalam kelas saat perkulihan. Penutur memberikan soal kepada
mahasiswa. Mitra tutur mengatakan kesulitan mengerjakan tugas itu.
Penutur berasumsi semua mahasiswa mampu mengerjakan tugas itu
dengan cepat dan tepat. Tuturan mitra tuturan yang mengatakan tidak
bisa mengerjakan tugas itu, penutur berasumsi bahwa mitra tutur tidak
serius mengikuti perkulihan. Bentuk kebahasan yang sampaikan di
depan semua mahasiswa sehingga mitra tutur merasa dijatuhkan oleh
2.2.4 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Terkourafi
Terkourafi (dalam buku Bousfield and Locher, 2008:3)
memandang ketidaksantunan sebagai, ‘impoliteness occurs when the
expression used is not conventionalized relative to the context of
occurrence; it threatens the addressee’s face but no face-threatening
intention is attributed to the speaker by the hearer.’ Jadi perilaku
berbahasa dalam pandangannya akan dikatakan tidak santun bilamana
mitra tutur (addressee) merasakan ancaman terhadap kehilangan muka
(face threaten), dan penutur (speaker) tidak mendapatkan maksud
ancaman muka itu dari mitra tuturnya. Mitra tutur merasa ‘kehilangan
muka’ dalam bahasa Jawa kelangan rai bila penutur tidak mengetahui
maksud mitra tutur. Tuturan (10) pada bagian berikut akan
memperjelas pernyataan ini.
(10) “Kamu itu sudah semester bontot, mencari kajian teori yang relevan kok tidak bisa.”
Informasi Indeksal
Tuturan (10) dituturkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa
di dalam ruang dosen. Mitra tutur sedang mengkonsultasikan
skrispinya. Penutur menemukan beberapa kesalahan ejaan dan beberapa
kalimat tidak koheren. Melihat kenyataan tersebut, penutur merasa
jengkel dengan mitra tutur yang sudah semester akhir tidak bisa
menyusun kata-kata dengan benar. Bentuk kebahasan tersebut
merasa dipermalukan karena angkatan tua belum bisa menyusun
kalimat dengan benar. Mitra tutur merasa terancam atas tuturan dari
penutur.
2.2.5 Teori ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher and
Watts
Locher and Watts (dalam buku Bousfield and Locher, 2008:5)
berpandangan bahwa perilaku tidak santun adalah perilaku yang secara
normatif dianggap negatif (negatively marked behavior), lantaran
melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Juga
mereka menegaskan bahwa ketidaksantunan merupakan peranti untuk
menegosiasikan hubungan antarsesama (a means to negotiate meaning).
Selengkapnya pandangan mereka tentang ketidaksantunan tampak
berikut ini, ‘…impolite behaviour and face-aggravating behaviour
more generally is as much as this negation as polite versions of
behavior.’
Setiap daerah mempunyai norma atau peraturan yang mengatur
perilaku masyarakat. Peraturan itu bersifat wajib dan mengikat. Selain
daerah atau wilayah tertentu, suatu organisasi atau lembaga pendidikan
pasti mempunyai peraturan yang berfungsi mengatur perilaku atau
tindakan semua warga yang bernaung di lembaga tersebut. Universitas
adalah salah lembaga pendidikan, warga masyarakat di lembaga
Norma yang telah ditetapkan itu adalah bentuk kesempakatan
bersama antara yang membuat norma dan pelaksana norma. Norma juga
suatu bentuk kerja sama antar hubungan sesama bila norma mampu
direalisasikan dengan baik tidak akan ada perselisihan. Namun, bila
terjadi pelanggaran norma akan terjadi pertengkaran – bentuk
kebahasan ketidaksantunan – konflik antar penutur dan mitra tutur.
Tuturan (11) pada bagian berikut akan memperjelas pernyataan ini.
(11)Lho ... mang harus tepat ya, bu! Kan bisa nelat sedikit.
Informasi Indeksal
Tuturan (11) dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada dosen
di ruang dosen. Penutur memberikan tugas tidak sesuai dengan waktu
yang disepakati bersama yaitu pukul 11.00 namun mengumpulkan tugas
12.00. Tindakan penutur membuat geram mitra tutur, namun penutur
tidak merasa bersalah. Penutur berasumsi bahwa tindakannya itu dapat
ditoleransi oleh mitra tutur karena kebiasan orang Indonesia yang suka
mengulur-ulur waktu. Tuturan tersebut merupakan wujud kebahasan
yang normatif dianggap negatif oleh penuturnya sehingga terjadi
2.2.6 Rangkuman
Sebagai rangkuman dari sejumlah teori ketidakasantunan yang
disampaikan di awal, dapat ditegaskan bahwa
1. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher adalah sebagai
berbahasa yang melecahkan dan memainkan muka.
2. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Bousfield adalah
perilaku berbahasa seseorang yang dilakukan secara sembrono hingga
akhirnya tindakan berkategori sembrono demikian itu mendatangkan
konflik.
3. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Culpeper adalah perilaku
komunikatif yang diperantikan secara intensional untuk membuat
orang benar-benar
4. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Terkourafi adalah mitra
tutur (addressee) merasakan ancaman terhadap kehilangan muka (face
threaten), dan penutur (speaker) tidak mendapatkan maksud ancaman
muka itu dari mitra tuturnya.
5. Ketidaksantunan berbahasa dalam pandangan Locher and Watts adalah
perilaku tidak santun adalah perilaku yang secara normatif dianggap
negatif (negatively marked behavior), lantaran melanggar
norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
Kelima teori ketidaksantunan berbahasa itu semuanya akan
digunakan sebagai kaca mata untuk melihat praktik berbahasa yang tidak
2.3 Tindak Tutur
Yule (1996:81) menjelaskan bahwa dalam usaha untuk mengungkapkan
dirinya, penutur tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung
kata-kata dan struktur-struktur gramatikal saja, tetapi penutur juga memperlihatkan
tindakan-tindakan melalui tuturan-tuturan itu. Tindakan-tindakan yang
ditampilkan lewat tuturan itu biasanya disebut tindak tutur. Searle melalui
bukunya Speech Acts An Essay in The Philosophy of Language (dalam
Wijana, 2011:21) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya
ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni
tindak lokusi (locutionary act), tindak ilokusi (illocutionary act), dan tidak
perlokusi (perlocutionary act).
2.3.1 Tindak Lokusi
Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu
(Wijana, 2011:21). Tindak tutur ini dinamakan the act of saying
something. Konsep lokusi sendiri berkenaan dengan proposisi kalimat.
Kalimat di sini dimengerti sebagai suatu satuan yang terdiri dari dua
unsur, yakni subjek/topik dan predikat/comment (Nababan, 1987:4
dalam Wijana:22). Sebagai satuan kalimat, pengidentifikasian tindak
lokusi cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan
yang tercakup dalam situasi tutur. Jadi, tindak tutur lokusioner adalah
tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang
dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri (Rahardi, 2012:17)
menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Perhatikan
contoh berikut.
(1) Makanan khas Yogyakarta adalah sayur gudeg. (2) Anjingnya lucu.
(3) Ayah pergi ke Jakarta.
Kalimat (1) dan (2) dituturkan oleh penuturnya semata-mata
untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan
sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Pada kalimat (1),
informasi yang dituturkan adalah nama masakan khas Yogyakarta
adalah sayur gudeg, kalimat (2) anjing yang disaksikan penutur itu lucu,
kalimat (3) juga berfungsi untuk mengutarakan informasi bahwa Ayah
sedang pergi ke Jakarta.
Berdasarkan contoh-contoh itu, dapatlah dilihat bahwa ihwal
maksud tuturan yang disampaikan oleh penutur tidak dipermasalahkan
sama sekali. Dengan demikian, tindak tutur lokusioner adalah tindak
menyampaikan informasi yang disampaikan oleh penutur.
2.3.2 Tindak Ilokusi
Sebuah tuturan berfungsi untuk mengatakan atau menyampaikan
sesuatu dan untuk melakukan sesuatu. Tuturan yang berfungsi untuk
menyampaikan sesuatu disebut tindak lokusi, sedangkan tuturan yang
berfungsi untuk melakukan sesuatu dinamakan tindak ilokusi (Wijana,
2011:23). Tindak tutur ini disebut the act of doing something. Tindak
dan fungsi tertentu di dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya.
Tindak tutur ilokusioner cenderung tidak hanya digunakan untuk
menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi
tuturnya dipertimbangkan dengan seksama. Perhatikan contoh-contoh
yang diberikan Wijana (2011:23) berikut ini.
(4) Saya pulang kantor agak malam. (5) Gula pasir di dapur sudah habis. (6) Ada orang gila.
Kalimat (4) sampai dengan (6) tidak saja memberikakan
informasi tertentu (sesuai isi kalimat itu) tetapi kalimat tersebut juga
memberikan maksud tertentu jika dipertimbangkan situasi tutur berikut
ini. Kalimat (4) bila dituturkan oleh suami kepada istrinya yang tidak
bisa pulang tepat waktu karena harus rapat di luar kota sehingga sang
istri jangan menunggu makan malam di rumah. Kalimat (5) bila
dituturkan oleh seorang ibu akan membuat teh atau kopi ternyata ibu
menemukan gula pasir di dapur sudah habis. Kalimat tersebut bukan
hanya pemberitahuan tetapi untuk memberi perintah untuk membeli
gula pasir. Kalimat (6) bila diucapkan oleh seorang kepada orang yang
melewati jalan atau salah satu rumah yang dianggap ada orang gila
yang tinggal disitu. Kalimat tersebut bukan saja sebagai pemberitahuan
akan tetapi dapat sebagai larangan melewati jalan atau rumah tersebut.
Gambaran contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa tindak
ilokusi sangat sukar diidentifikasi karena terlebih dahulu harus
tindak tutur itu terjadi; dan sebagainya. Selain itu, tindak ilokusi
ditampilkan melalui penekanan komunikatif suatu tuturan. Itulah
sebabnya tindak ilokusi menjadi bagian yang sentral untuk memahami
tindak tutur. Tindak tutur ilokusi sering menjadi kajian utama dalam
bidang pragmatik (Rahardi, 2012:17). Searle (dalam Rahardi,
2007:72—73) menggolongkan tindak tutur ilokusi dalam lima macam
bentuk tuturan, yakni
(1) Asertif (assertives) atau representatif, yaitu bentuk tutur yang
mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan,
misalnya menyatakan (stating), menyarankan (suggeting),
membual (boasting), mengeluh (complaining), dan mengklaim
(claiming). Menurut Searle (melalui Leech, 1993:164) dari segi
sopan santun ilokusi-ilokusi ini cenderung netral termasuk kategori
bekerja sama.
(2) Direktif (direcitives) yakni bentuk tutur yang dimaksudkan
penuturnya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan
tindakan, misalnya memesan (ordering), memerintah
(commanding), memohon (requesting), menasihati (advising), dan
merokomendasi (recommeding). Jenis ilokusi ini sering
dimasukkan dalam kategori kompetitif karena itu mencakup
kategori-kategori ilokusi yang membutuhkan sopan santun negatif,
namun ada ilokusi direktif yang memang sopan seperti
(3) Ekspresif (expressives) yakni bentuk tutur yang berfungsi untuk
menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap
suatu keadaan, misalnya berterima kasih (thinking), memberi
selamat (congrangtulating), meminta maaf (pardoning),
menyalahkan (blaming), memuji (praising), dan berbelasungkawa
(condoling). Ilokusi ekspresif cenderung menyenangkan karena itu
secara intrinsik ilokusi ini sopan kecuali tentunya ilokusi-ilokusi
ekspresif seperti mengecam dan menuduh (melalui Leech,
1993:165).
(4) Komisif (cummissives) yaitu bentuk tutur yang berfungsi untuk
menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji (promosing),
bersumpah (vowing), dan menawarkan sesuatu (offering). Menurut
Searle, ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan dan kurang
bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada kepentingan penutur
tetapi pada kepentingan petutur (melalui Leech, 1993:164).
(5) Deklarasi (declarations) yaitu bentuk tutur yang menghubungkan
isi tuturan dengan kenyataannya, misalnya berpasrah (resigning),
memecat (dismissing), membaptis (christening), memberi nama
(naming), mengangkat (appointing), mengucilkan
(excommuningcating), dan menghukum (sentencing). Searle
(melalui Leech, 1993:165) mengatakan bahwa tindakan-tindakan
tersebut merupakan kategori tindak ujar sangat khusus karena
dalam sebuah kerangka acuan kelembagaan diberi wewenang
melakukannya, misalnya hakim yang menjatuhkan hukuman,
pendeta yang membaptis, penjabat yang memberi nama pada kapal
baru, dan sebagainya.
Searle (dalam Yule, 2006:95) memberikan fungsi-fungsi umum
tindak tutur beserta sifat-sifat kuncinya yang terangkum dalam tabel
berikut.
Tabel 1
Lima Fungsi Umum Tindak Tutur
Tipe tindak tutur
Arah penyesuaian
P = penutur X = situasi
Deklarasi Kata mengubah dunia P menyebabkan X Representatif Kata disesuaikan
dengan dunia
P meyakini X
Ekspresif Kata disesuaikan dengan dunia
P merasakan X
Direktif Dunia disesuaikan dengan kata
P menginginkan X
Komisif Dunia disesuaikan dengan kata
P memaksudkan X
2.3.3 Tindak Perlokusi
Tuturan juga seringkali mempunyai daya pengaruh
(perlocutionary force), atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek
atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja
dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya
dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak
affecting something. Wijana (2011:24—26) memberikan beberapa
contoh berikut.
(7) Uang jajan saya habis. (8) Kemarin saya sakit demam.
(9) Saya tidak membawa tempat pensil.
Kalimat (7), (8), dan (9) mengandung lokusi dan ilokusi bila
dipertimbangkan konteks situasi tuturnya, serta perlokusi jika penutur
mengkreasikan daya pengaruh tertentu kepada lawan tuturnya. Bila
kalimat (7) diutarakan oleh seorang mahasiswa yang berkuliah di luar
kota, maka ilokusinya secara tidak langsung menginformasikan bahwa
uang yang dimiliki penutur sudah habis. Adapun efek perlokusinya
yang mungkin diharapkan orang tua penutur mengirimkan uang jajan.
Bila kalimat (8) diutarakan tidak dapat menghadiri undangan rapat
kepada orang yang mengundangnya, kalimat ini merupakan tindak
ilokusi untuk memohon maaf, dan perlokusi (efeknya) yang diharapkan
adalah orang yang mengundang dapat memakluminya. Bila kalimat (9)
diutarakan oleh mahasiswa atau siswa kepada temannya pada saat
pelajaran sedang berlangsung. Penutur tidak membawa tempat pensil,
kalimat tersebut tidak hanya mengandung lokusi tetapi juga
mengandung ilokusi yang berupa perintah meminjamkan pensil atau
bolpen kepada mitra tutur. Tindak perlokusi adalah mitra tutur bersedia
meminjamkan pensil atau bolpen kepada penutur.
Tindak tutur perlokusioner mengandung daya pengaruh bagi
(10)Baru-baru ini Walikota telah membuka Kurnia Department Store yang terletak di pusat perbelanjaan dengan tempat parkir yang cukup luas.
Kalimat (10) selain memberikan informasi, juga secara tidak
langsung merupakan undangan atau ajakan untuk berbelanja ke
department store bersangkutan. Letak department store yang strategis
dengan tempat parkirnya yang luas diharapkan memiliki efek untuk
membujuk para pembacanya. Wacana seperti ini seringkali dijumpai
pada bentuk wacana iklan. Secara sepintas, wacana iklan seperti ini
merupakan berita, tetapi daya ilokusi dan perlokusinya sangat besar
terlihat.
2.3.4 Rangkuman
Pemaparan tindak tutur oleh Searle ada tiga jenis tindakan yang
dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi
(locutionary act), tindak ilokusi (illocutionary act), dan tidak perlokusi
(perlocutionary act). Pertama, tindak lokusi adalah tindak tutur untuk
menyatakan sesuatu yang berkenaan dengan konsep proposisi kalimat.
Kedua, tindak ilokusi adalah sebuah tuturan berfungsi untuk
mengatakan atau menyampaikan sesuatu dan untuk melakukan sesuatu.
Penggolongan tindak tutur ilokusi ada lima macam yaitu assertif atau
representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Penjelasan yang
ketiga, tindak perlokusi adalah tuturan yang mempunyai daya pengaruh
2.4 Konteks Tuturan
Penelitian sebuah bahasa tidak dapat lepas dari unsur yang
memengaruhi pemakaian bahasa itu. Unsur itu adalah konteks. Konteks
sangat memengaruhi bentuk bahasa yang digunakan oleh seorang penutur.
Dahulu, konteks belum terlalu diperhatikan oleh ahli bahasa sehingga
penelitian mereka hanya mengkaji bahasa dari segi fonologi, morfologi,
sintaksis, dan semantik. Hasil penelitian tersebut lazimnya berupa sistem
bahasa yang bentuknya gramatikal saja. Hal tersebut tidak akan menjawab
sebuah fenomena yang berhubungan dengan mengapa dan bagaimana sebuah
tuturan atau kalimat itu muncul. Oleh karena itu, sejak permulaan tahun
1970-an para ahli linguistik menyadari pentingnya konteks dalam penafsirkan
kalimat atau tuturan itu.
Seorang para pakar linguistik dan pragmatik, Malinowsky, pada tahun
1923, membicarakan tentang konteks, khususnya konteks yang berdimensi
situasi atau ‘context of situation’. Secara khusus Malinowsky mengatakan,
seperti yang dikutip di dalam Vershueren (1998:75), ‘Exactly as in the reality
of spoken or written languages, a word without linguistics context is a mere
figment and stands for nothing by itself, so in the reality of a spoken living
tongue, the utterance has no meaning except in the context of situation.’ Jadi,
dalam pandangannya sesungguhnya dinyatakan bahwa kehadiran konteks
situasi menjadi mutlak untuk menjadikan sebuah tuturan benar-benar
Hymes (melalui Nugroho, 2009:119) mnyebutkan bahwa konteks
terdiri dari latar fisik dan psikologi (setting and scene), peserta (participants),
tujuan komunikasi (ends), pesan yang disampaikan (act sequence), nada tutur
(key), norma tutur (norm), dan jenis tutur (genre). Penjelasan agak panjang
terkait konteks dikemukan Levinson (melalui Nugroho, 2009:119). Levinson
mengemukakan konteks dari definisi Carnap, yaitu istilah yang dipahami
yang mencakup identitas partisipan, parameter, ruang dan waktu dalam situasi
tutur, dan kepercayaan, pengetahuan, serta maksud partisipan di dalam situasi
tutur. Selanjutnya Levinson menjelaskan bahwa untuk mengetahui sebuah
konteks, seseorang harus membedakan antara situasi aktual sebuah tuturan
dalam semua keserbaragaman ciri-ciri tuturan mereka, dan pemilihan ciri-ciri
tuturan tersebut secara budaya dan linguistis yang berhubungan dengan
produksi dan penafsiran tuturan. Untuk mengetahui konteks, Levinson
(melalui Nugroho, 2009:119—120) mengambil pendapat Lyons yang
membuat daftar prinsip-prinsip universal logika dan pemakaian bahasa, yaitu
seperti di bawah ini:
(1) Pengetahuan ihwal aturan dan status (aturan meliputi aturan dalam
situasi tutur seperti penutur atau petutur, dan aturan sosial,
sedangkan status meliputi nosi kerelativan kedudukan sosial);
(2) Pengetahuan ihwal lokasi spasial dan temporal;
(3) Pengetahuan ihwal tingkat formalitas;
(4) Pengetahuan ihwal medium; kira-kira kode atau gaya pada sebuah
(5) Pengetahuan ihwal ketepatan sesuatu yang dibahas; dan
(6) Pengetahuan ihwal ketepatan bidang wewenang (atau penentuan
domain register sebuah bahasa).
Mey (dalam Rahardi, 2011:2), ‘… context is more than a matter of
reference and of understanding what things are about, practically speaking.
Context is also what gives our utterances their deeper meaning.’ Pada bagian
lain Mey (dalam Rahardi, 2011:2), menegaskan ‘the context is also of
paramaount importance in assigning a proper value to such phenomena as
propositions, implicature, and the whole sets of context-oriented features …’
Jadi, dengan kehadiran konteks itu, sebagaimana yang dimaksudkan Mey di
atas, sangat dimungkinkan dipahami entitas kebahasaan secara lebih
komprehensif dan mendalam, bukan sekadar menunjuk pada hal-hal yang
sifatnya referensial.
Yule (2006:31—36) membahas konteks dalam kaitannya dengan
kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi referen-referan yang
bergantung pada satu atau lebih pemahaman orang itu terhadap ekspresi yang
diacu. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Yule membedakan konteks dan
koteks. Konteks ia definisikan sebagai lingkungan fisik di mana sebuah kata
dipergunakan. Koteks menurut Yule adalah bahan linguistik yang membantu
memahami sebuah ekspresi atau ungkapan. Koteks adalah bagian linguistik
dalam lingkungan tempat sebuah ekspresi dipergunakan.
Rahardi (2007:20) menuturkan bahwa konteks tuturan diartikan sebagai