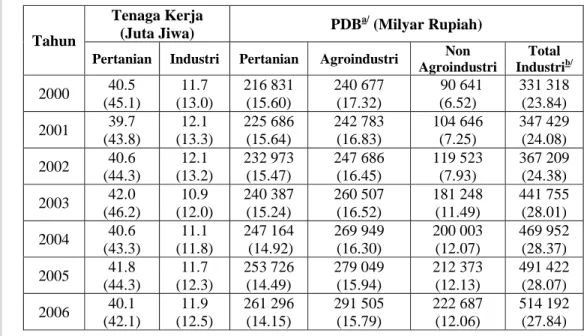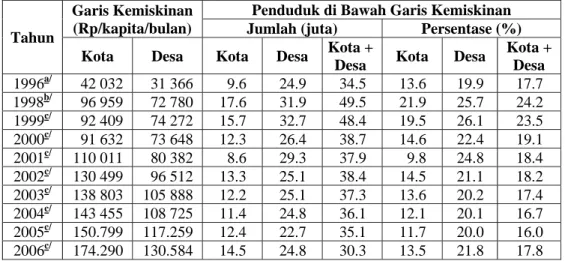1.1. Latar Belakang
Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam
perekonomian Indonesia. Hal ini dapat diukur dari pangsa sektor pertanian dalam
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber
pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan,
perolehan devisa melalui ekspor non migas, penciptaan ketahanan pangan
nasional dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain.
Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar
yang potensial bagi sektor industri.
Pada saat perekonomian nasional dilanda krisis, ternyata sektor pertanian
terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Pengalaman krisis
multidimensi tahun 1997-1998 memberikan pelajaran berharga betapa
strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat
bagi sistem perekonomian nasional. Sementara itu, sektor-sektor lainnya
mengalami keterpurukan sebagai akibat krisis ekonomi tersebut, terutama industri
yang banyak komponen impornya (foot loose industries).
Sepanjang tahun 2000-2006, lebih dari 40 juta jiwa atau sekitar 44 persen
angkatan kerja di Indonesia menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian.
Namun demikian, apabila dilihat dari sumbangannya terhadap PDB pada periode
yang sama, ternyata sektor pertanian hanya mampu memberikan kontribusi sekitar
15 persen (Tabel 1).
Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja
rumahtangga yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian juga
menjadi relatif lebih rendah. Sementara itu, peran sektor industri terhadap
perekonomian nasional menunjukkan gejala yang cukup menggembirakan.
Menurut Oktaviani dan Sahara (2005), sektor industri dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu agroindustri dan nonagroindustri. Secara umum definisi agroindustri
adalah industri yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian. Sementara itu,
menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), yang termasuk dalam
agroindustri meliputi kegiatan yang mengolah bahan dan kegiatan yang
menyediakan sarana produksi pertanian (misalnya benih, pupuk dan pestisida).
Tabel 1. Tenaga Kerja dan Nilai Output Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan di Indonesia, Tahun 2000-2006 Tahun Tenaga Kerja (Juta Jiwa) PDB a/ (Milyar Rupiah)
Pertanian Industri Pertanian Agroindustri Non Agroindustri Total Industrib/ 2000 40.5 (45.1) 11.7 (13.0) 216 831 (15.60) 240 677 (17.32) 90 641 (6.52) 331 318 (23.84) 2001 39.7 (43.8) 12.1 (13.3) 225 686 (15.64) 242 783 (16.83) 104 646 (7.25) 347 429 (24.08) 2002 40.6 (44.3) 12.1 (13.2) 232 973 (15.47) 247 686 (16.45) 119 523 (7.93) 367 209 (24.38) 2003 42.0 (46.2) 10.9 (12.0) 240 387 (15.24) 260 507 (16.52) 181 248 (11.49) 441 755 (28.01) 2004 40.6 (43.3) 11.1 (11.8) 247 164 (14.92) 269 949 (16.30) 200 003 (12.07) 469 952 (28.37) 2005 41.8 (44.3) 11.7 (12.3) 253 726 (14.49) 279 049 (15.94) 212 373 (12.13) 491 422 (28.07) 2006 40.1 (42.1) 11.9 (12.5) 261 296 (14.15) 291 505 (15.79) 222 687 (12.06) 514 192 (27.84) Sumber: BPS (2007).
Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase.
a/
PDB dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000.
b/
Industri yang dimaksud disini merupakan industri non migas
Pada Tabel 1, nampak bahwa apabila dikaji dari kontribusinya terhadap
dari 24 persen, dimana lebih dari separuhnya merupakan sumbangan subsektor
agroindustri. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu
menyerap tenaga kerja lebih dari 12 juta jiwa selama tahun 2000-2002, walaupun
pada tahun 2003 sempat mengalami penurunan menjadi hanya 10.9 juta jiwa dan
meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya.
Transformasi struktur perekonomian dari dominasi sektor pertanian ke
dominasi sektor industri menghendaki adanya kaitan yang kuat antara sektor
pertanian dan sektor industri. Melalui keterkaitan tersebut, diharapkan nilai
tambah komoditas pertanian dan penyerapan tenaga kerja menjadi semakin
meningkat. Selain itu, melalui keterkaitan tersebut proses industrialisasi dapat
berjalan mulus karena industri yang dikembangkan menggunakan bahan baku
yang tersedia.
Dewasa ini, dan terlebih lagi di masa yang akan datang, orientasi sektor
pertanian telah berubah dari orientasi produksi kepada orientasi pasar. Dengan
berlangsungnya perubahan preferensi konsumen yang makin menuntut atribut
produk yang lebih rinci dan lengkap serta adanya preferensi konsumen akan
produk olahan, maka motor penggerak sektor pertanian harus berubah dari
usahatani kepada industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri). Menurut
Departemen Pertanian (2002), untuk mengembangkan sektor pertanian yang
modern dan berdaya saing, maka agroindustri harus menjadi lokomotif dan
sekaligus penentu kegiatan subsektor usahatani dan selanjutnya akan menentukan
subsektor agribisnis hulu.
Menurut Departemen Pertanian (2005a), paling sedikit ada lima alasan
utama mengapa agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan
1. Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif
menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), yang pada akhirnya akan
memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia.
2. Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar, sehingga
kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian
nasional secara keseluruhan.
3. Memiliki keterkaitan yang besar, baik ke hulu maupun ke hilir (forward and backward linkages), sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. 4. Memiliki basis bahan baku lokal (keunggulan komparatif) yang dapat
diperbaharui sehingga terjamin sustainabilitasnya.
5. Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional
dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya.
Berdasarkan grand strategy pengembangan agroindustri yang telah disusun oleh Departemen Pertanian (2005b), program pengembangan agroindustri
diarahkan untuk hal-hal berikut:
1. Mengembangkan cluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya.
2. Mengembangkan industri pengolahan skala rumahtangga dan kecil yang
didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar.
3. Mengembangkan industri pengolahan yang mempunyai daya saing tinggi untuk
meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun
prioritas utama pengembangan agroindustri difokuskan pada sinergi antara
keunggulan komparatif sumberdaya dengan orientasi pasar, yakni: (1) industri
pengolahan hasil perkebunan seperti industri pengolahan minyak sawit dan
kopi bubuk/instan, dan industri teh olahan, (2) industri pengolahan hasil
tanaman pangan dan hortikultura seperti industri buah dan sayur dalam kaleng,
industri minuman sari buah, industri tepung tapioka dan derivatnya, industri
pakan ternak, dan industri makanan ringan, (3) industri pengolahan hasil
peternakan seperti industri susu olahan, industri daging dalam kaleng, dan
industri penyamakan kulit, serta (4) industri pengolahan hasil ikutan/samping
seperti industri agrocomposting, industri pakan ternak, industri coco fiber dan coco peat, industri karbon aktif, industri minuman dari buah jambu mete, dan lain-lain.
Namun demikian, selama ini proses industrialisasi di Indonesia berjalan
masih sangat lambat. Hal ini terlihat antara lain dari semakin senjangnya ekonomi
desa-kota. Dualisme ekonomi desa-kota telah mengakibatkan kota menjadi pusat
segala-galanya dan ekonomi perdesaan hanyalah pendukung ekonomi perkotaan.
Dalam jangka panjang apabila dualisme ekonomi desa-kota tidak dapat diatasi,
maka dapat dipastikan akan muncul masalah lain yang lebih rumit, seperti
urbanisasi besar-besaran, rusaknya kultur asli bangsa seperti gotong royong dan
kekeluargaan, kriminalitas yang meningkat, serta semakin melebarnya
kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat kaya pemilik modal di
perkotaan akan semakin kaya, sementara itu penduduk miskin di perdesaan
semakin bertambah besar (Departemen Pertanian, 2005a).
Pengembangan agroindustri dapat menjadi pilihan yang strategis dalam
menanggulangi permasalahan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.
Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang tinggi dari sektor agroindustri
dalam hal perluasan kesempatan kerja. Pengembangan agroindustri yang berbasis
banyak tenaga kerja dan menjamin perluasan berusaha, sehingga akan efektif
dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan.
Berkembangnya agroindustri juga akan meningkatkan penerimaan devisa dan
mendorong terjadinya keseimbangan pendapatan antara sektor pertanian dan
nonpertanian. Dengan demikian, kebijakan pembangunan agroindustri diharapkan
mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah produksi pertanian
dan mendorong penawaran hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan agroindustri.
Dalam kaitannya dengan peran agroindustri dalam menurunkan
kemiskinan perdesaan, Gandhi et al. (2001) melakukan studi tentang pembangunan agroindustri untuk petani kecil dan perdesaan di India. Hasil studi
menunjukkan bahwa sektor agroindustri mampu memberikan sumbangan yang
besar terhadap kesempatan kerja. Peran sektor agroindustri dalam mendorong
kegiatan pembangunan dan menurunkan kemiskinan perdesaan dicerminkan oleh
kemampuannya dalam peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja perdesaan,
khususnya bagi kelompok petani berlahan sempit.
Stanton (2000) melakukan studi tentang peran agroindustri dalam
peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan di Mexico. Hasil studi
menunjukkan bahwa perusahaan agroindustri pada tingkat lokal mampu
menghasilkan nilai tambah dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan
masyarakat perdesaan. Sementara itu, Holloway et al. (2000) melakukan studi tentang industrialisasi pertanian melalui inovasi biaya transaksi kelembagaan,
koperasi dan pengembangan pasar susu di pegunungan Timur Afrika. Hasil studi
menunjukkan bahwa kegiatan produksi susu untuk pasar lokal mampu
industri pertanian adalah peran lembaga pemasaran bersama yang mampu
menekan biaya transaksi.
Beberapa studi di atas relevan dengan kondisi di Indonesia. Berdasarkan
data Sensus Penduduk tahun 2000, sebagian besar (60 persen) penduduk
Indonesia masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan, yang
dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan masih
tingginya tingkat kemiskinan.
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara
sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian
masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap
manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia,
sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran
kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu
mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik, sehingga
menyebabkan kualitas SDM dari aspek intelektual dan fisik rendah, akibatnya
produktivitasnya rendah. Selain itu, rendahnya kualitas SDM menyebabkan
kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi, politik, sosial budaya dan
psikologi, sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik
dalam sistem sosial ekonomi masyarakat (Sumedi dan Supadi, 2004).
Walaupun pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini secara
signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di
Indonesia, namun terpaan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi
menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan
proporsi penduduk miskin, terutama di perdesaan. Fenomena di atas secara jelas
Tabel 2. Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan
Tahun
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Jumlah (juta) Persentase (%) Kota Desa Kota Desa Kota +
Desa Kota Desa Kota + Desa 1996a/ 42 032 31 366 9.6 24.9 34.5 13.6 19.9 17.7 1998b/ 96 959 72 780 17.6 31.9 49.5 21.9 25.7 24.2 1999c/ 92 409 74 272 15.7 32.7 48.4 19.5 26.1 23.5 2000c/ 91 632 73 648 12.3 26.4 38.7 14.6 22.4 19.1 2001c/ 110 011 80 382 8.6 29.3 37.9 9.8 24.8 18.4 2002c/ 130 499 96 512 13.3 25.1 38.4 14.5 21.1 18.2 2003c/ 138 803 105 888 12.2 25.1 37.3 13.6 20.2 17.4 2004c/ 143 455 108 725 11.4 24.8 36.1 12.1 20.1 16.7 2005c/ 150.799 117.259 12.4 22.7 35.1 11.7 20.0 16.0 2006c/ 174.290 130.584 14.5 24.8 30.3 13.5 21.8 17.8 Sumber: BPS (2007)
Keterangan: a/ Menggunakan garis kemiskinan menurut definisi BPS tahun 1998.
b/
Menggunakan data Susenas Desember 1998 (khusus).
c/
Menggunakan data Susenas Reguler.
Pada Tabel 2, nampak bahwa dari 30.3 juta penduduk miskin (17.8 persen
dari total penduduk), lebih dari 24 juta orang miskin tersebut berada di daerah
perdesaan, yang umumnya terlibat atau berhubungan dengan sektor pertanian.
Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi sektor pertanian memiliki potensi
ekonomi dan sumberdaya yang melimpah, namun di lain pihak petani yang
merupakan konstituen terbesar masih terjerat kemiskinan.
Dengan penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang terus bertambah,
sementara luas lahan pertanian cenderung berkurang, maka penyerapan tenaga
kerja di sektor pertanian menjadi semakin tidak produktif. Oleh karena itu,
industrialisasi pertanian merupakan pilihan yang strategis untuk menciptakan
lapangan kerja produktif guna menekan angka kemiskinan yang sekaligus mampu
meningkatkan kinerja sektor pertanian di perdesaan. Berkenaan dengan hal ini,
maka perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang dampak industrialisasi
1.2. Perumusan Masalah
Proses industrialisasi pertanian di Indonesia telah dilakukan semenjak
lama, yang kemudian mendapat penekanan pada tahun 1970-an yang dikenal
dalam pembangunan pertanian melalui ”revolusi hijau” untuk pangan padi dan
ekspansi tanaman perkebunan berskala kecil dan menengah. Proses industrialisasi
telah memperkenalkan keragaman jenis teknologi mulai dari bibit unggul,
pengolahan hasil pertanian, teknologi pasca panen, pergudangan, alat pertanian,
dan sebagainya. Semua itu telah merubah kinerja sektor pertanian, seperti
penambahan jumlah output yang dihasilkan.
Peningkatan jumlah output yang dihasilkan oleh sektor pertanian tersebut
dimungkinkan karena adanya introduksi teknologi di sektor yang bersangkutan.
Secara agregat, dampak perubahan teknologi digambarkan sebagai faktor
penggeser Kurva Kemungkinan Produksi (KKP) ke kanan, yang secara grafis
dapat dilihat pada Gambar 1.
Komoditas Pertanian Tanaman Pangan (Q1) KKPt2 KKPt1 Komoditas Pertanian 0 Non Pangan (Q2)
Pada Gambar 1, nampak bahwa dengan adanya perubahan teknologi di
sektor pertanian akan menggeser KKP ke kanan dari KKPt1 ke KKPt2. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan sumberdaya yang ada, maka akan diperoleh jumlah
output sektor pertanian, baik komoditas pertanian tanaman pangan (Q1) maupun
komoditas pertanian non pangan (Q2), yang lebih besar.
Dengan terjadinya peningkatan produksi komoditas pertanian seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1, diharapkan pendapatan petani dapat ditingkatkan.
Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan pertanian yang selama ini
dilakukan oleh pemerintah yaitu peningkatan produksi komoditas pertanian, yang
ditempuh melalui empat usaha pokok (catur usaha) yaitu intensifikasi,
ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Namun demikian, mengingat
permintaan komoditas pertanian yang bersifat tidak elastis, maka peningkatan
produksi komoditas pertanian justru akan menurunkan penerimaan (revenue) yang diterima oleh petani. Secara grafis, fenomena tersebut secara jelas disajikan pada
Gambar 2. P S1 S2 A P1 B P2 D 0 Q1 Q2 Q
Gambar 2. Pergeseran Kurva Penawaran dengan Kurva Permintaan yang Tidak Elastis
Pada Gambar 2, nampak bahwa penerimaan mula-mula sebesar segiempat
OP1AQ1. Pergeseran kurva penawaran (S) dari S1 ke S2 (dengan kurva permintaan
D yang inelastis), maka penerimaan petani menjadi sebesar segiempat OP2BQ2 yang lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan semula (OP2BQ2 < OP1AQ1).
Dengan penerimaan yang relatif lebih rendah di satu pihak, di pihak lain biaya
produksi usahatani yang semakin meningkat atau setidaknya tidak berubah, maka
pendapatan petani justru akan mengalami penurunan.
Secara empiris, hal tersebut di atas ditunjukkan oleh hasil penelitian
Ratnawati et al. (2004) bahwa peningkatan produktivitas pertanian akan menurunkan harga output di tingkat petani berkisar antara 0.28 persen (untuk
komoditas hasil kebun lain) sampai 10.08 persen (untuk komoditas tebu). Lebih
lanjut ditemukan bahwa kenaikan produktivitas pertanian juga akan menurunkan
pendapatan rumahtangga perdesaan berkisar antara 2.10 persen (untuk
rumahtangga berpendapatan tinggi di sektor nonpertanian di perdesaan) sampai
3.10 persen (untuk rumahtangga petani pemilik lahan > 1.0 hektar).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut
di atas adalah dengan peningkatan kegiatan-kegiatan industri pengolahan hasil
pertanian (industrialisasi pertanian). Melalui industrialisasi pertanian diharapkan
selain mampu meningkatkan nilai tambah (value added) juga akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian sebagai bahan baku industri pengolahan
hasil pertanian. Peningkatan produksi komoditas pertanian yang diimbangi oleh
peningkatan permintaannya, diharapkan akan mampu meningkatkan penerimaan
petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
Masalah lain yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah belum
terpadunya pengelolaan pertanian sebagai suatu sistem agribisnis secara utuh,
mulai dari subsistem sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil, sampai dengan
subsistem pemasaran, serta subsistem lembaga penunjang. Dampak dari kondisi
ini adalah tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu tidak menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Padahal tujuan pembangunan pertanian pada
hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Salah satu tolok ukur untuk mengukur dinamika kesejahteraan petani
adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Hasil penelitian Siregar (2003) menunjukkan
bahwa secara agregat NTP mempunyai tendensi (trend) yang menurun (negatif) yaitu sebesar –0.68 persen per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara
riil tingkat kesejahteraan petani dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan.
Hal ini selaras dengan data yang dipublikasikan oleh BPS (2007) yang
menunjukkan bahwa pada tahun 2006 dari total penduduk miskin di Indonesia
yang berjumlah 30.3 juta jiwa, sebanyak 81.85 persen (24.8 juta jiwa) bermukim
di kawasan perdesaan, yang sebagian besar dari mereka bermata pencaharian
sebagai petani.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan utama penelitian
ini adalah sejauh mana dampak industrialisasi pertanian, khususnya dampak
kemajuan teknologi yang ditandai oleh peningkatan produktivitas industri
pertanian, terhadap kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan
rumahtangga dan kemiskinan perdesaan belum banyak dilakukan kajian. Selama
ini alat analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut masih
bersifat parsial, seperti yang dilakukan oleh Susilowati (2007) dan Justianto
(SNSE). Demikian juga halnya dengan Yudhoyono (2004), Herjanto (2003) dan
Asnawi (2005) yang menggunakan pendekatan model makroekonometrika.
Padahal permasalahan tersebut bersifat multi sektor yang akan membawa
implikasi yang cukup luas, tidak hanya pada sektor industri pertanian, tetapi juga
pada sektor-sektor perekonomian lainnya, terutama pada sektor pertanian dan
kemiskinan perdesaan. Oleh karena itu, pendekatan yang paling sesuai adalah
dengan model ekonomi keseimbangan umum atau Computable General Equilibrium (CGE) .
Keunggulan model CGE dibandingkan dengan model keseimbangan
parsial adalah bahwa model CGE sudah memasukkan semua transaksi antar
pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan, baik di pasar faktor produksi maupun
di pasar komoditas. Dengan demikian dampak dari suatu kebijakan akan dapat
dianalisis pengaruhnya secara kuantitatif terhadap kinerja ekonomi, baik secara
makro maupun sektoral.
Dibandingkan dengan model SNSE, model CGE selain sudah
memasukkan persamaan nonlinier, juga sudah memasukkan harga sebagai
variabel endogen. Selain itu, dalam model CGE juga sudah memasukkan
kemungkinan substitusi antar faktor produksi, sehingga jika terjadi perubahan
harga relatif suatu faktor produksi, maka produsen merubah komposisi
penggunaan faktor produksi ke arah faktor produksi yang harganya relatif lebih
murah. Sementara itu, pada model SNSE sistem persamaan yang digunakan
adalah persamaan linier dengan anggapan model Leontief, substituasi antar faktor
tidak dimungkinkan, dan harga merupakan variabel eksogen. Perbedaan yang
cukup mendasar lain adalah pada model SNSE diasumsikan penawaran komoditas
adanya pembatasan supply. Dibandingkan dengan model makroekonometrika bahwa dengan model CGE hubungan antara makroekonomi dan mikroekonomi
dapat diketahui, sementara itu pada model makroekonometrika bahwa analisis dan
dampak dilakukan di tingkat makroekonomi saja.
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka secara
umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak industrialisasi pertanian
terhadap kinerja sektor pertanian dan kemiskinan perdesaan. Adapun secara
khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
1. Mengkaji dampak peningkatan produktivitas industri pertanian terhadap
kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan
kemiskinan perdesaan.
2. Mengkaji dampak peningkatan produktivitas industri pertanian dan sektor
pertanian terhadap kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan
rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.
3. Mengkaji dampak peningkatan produktivitas industri pertanian, sektor
pertanian dan sektor lembaga keuangan terhadap kinerja ekonomi sektoral,
ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.
1.3.2. Manfaat Penelitian
Penelitian terapan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya
informasi atau pengetahuan dan menyediakan analisis yang mendalam mengenai
makro, pendapatan rumahtangga dan kemiskinan perdesaan. Hal ini karena
selama ini belum terdapat kajian industrialisasi pertanian yang dikaitkan dengan
kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan
kemiskinan perdesaan secara mendalam, dengan mengagregasikan sektor-sektor
dalam perekonomian dan rumahtangga. Selain itu, model yang dibentuk dalam
penelitian ini adalah model CGE recursive dynamic yang belum banyak diaplikasikan untuk kasus Indonesia.
Secara khusus manfaat penelitian ini adalah diperolehnya sebuah model
CGE yang recursive dynamic dengan data dasar model menggunakan data dari tabel Input Output (I-O) dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia. Selain itu, model ini juga menggunakan data makroekonomi dan parameter terbaru yang mencerminkan kondisi
perekonomian Indonesia pada masa kini dan tertangkapnya dampak industrialisasi
pertanian terhadap kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan
rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.
1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam lingkup nasional (Indonesia) dengan
mengkaji dampak industrialisasi pertanian terhadap kinerja ekonomi sektoral,
ekonomi makro, pendapatan rumahtangga dan kemiskinan perdesaan.
Industrialisasi pertanian yang dimaksud didekati dari sisi supply yaitu peningkatan produktivitas, baik produktivitas sektor industri pertanian maupun produktivitas
sektor pertanian (sebagai pemasok bahan baku) dan produktivitas sektor lembaga
keuangan (sebagai lembaga penunjang). Dampak terhadap kinerja ekonomi
kerja. Adapun dampak terhadap kinerja ekonomi makro meliputi pertumbuhan
GDP riil, konsumsi rumahtangga, investasi, ekspor, impor, neraca perdagangan
dan inflasi.
Model CGE yang digunakan adalah model CGE recursive dynamic, yang merupakan kombinasi dari model CGE ORANI-F (Horridge et al., 1993), INDOF (Oktaviani, 2000), WAYANG (Wittwer, 1999), dan ORANIGRD (Horridge,
2002). Simulasi kebijakan dilakukan untuk jangka waktu selama 10 tahun yaitu
tahun 2003-2013.
Sektor industri pertanian yang dicakup dalam penelitian ini dibatasi pada
10 jenis industri, yaitu: (1) industri pengolahan hasil peternakan, (2) industri
pengolahan hasil perikanan, (3) industri minyak dan lemak, (4) beras (industri
penggilingan padi), (5) industri tepung segala jenis, (6) industri gula, (7) industri
rokok, (8) industri bambu, kayu dan rotan, (9) industri pupuk dan pestisida, serta
(10) industri pengolahan karet. Pemilihan sektor industri pertanian ini didasarkan
atas beberapa pertimbangan. Pertama, agroindustri yang tercakup kedalam 10
industri prioritas pembangunan industri nasional seperti yang tertuang dalam
Peraturan Presiden No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional. Kesepuluh industri prioritas ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut oleh
Departemen Perindustrian sebagai kebijakan nasional pembangunan industri
(Departemen Perindustrian, 2005). Kedua, agroindustri yang berbahan baku sektor
pertanian terpilih. Ketiga, agroindustri yang mempunyai prospek untuk
dikembangkan di masa datang, berdasarkan sumbangannya terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor dan penyerapan angkatan kerja.
Keterbatasan penelitian ini adalah model yang digunakan tidak
parameter yang diadopsi dari studi-studi sebelumnya untuk negara lain, karena
parameter-parameter tersebut di Indonesia sebagai negara berkembang tidak