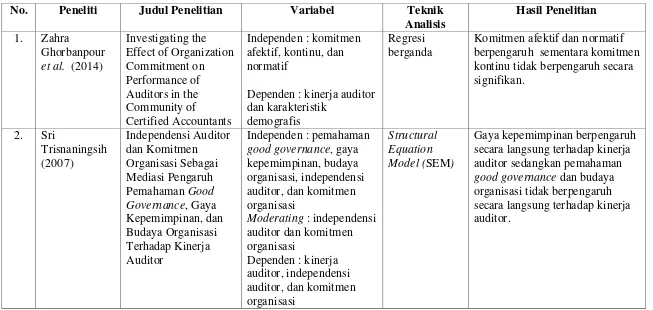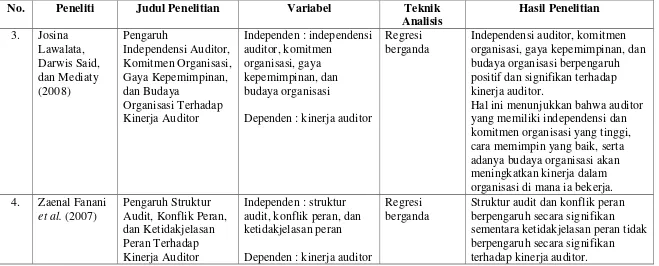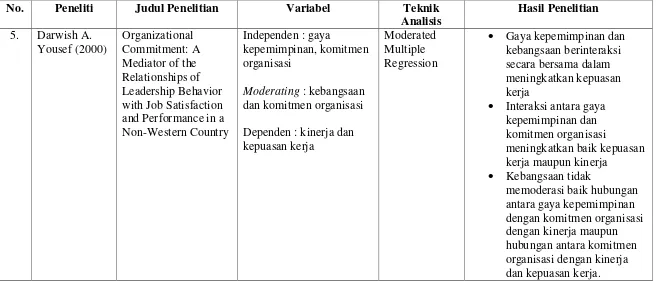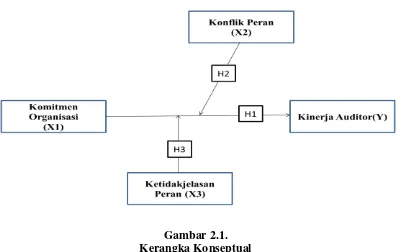BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Tinjauan Literatur 2.1.1.Kinerja Auditor
Untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat kinerja
sumber daya manusianya. Kinerja auditor berkontribusi terhadap kinerja dan
citra kantor akuntan publik di mata masyarakat. Secara etimologis, kinerja
berasal dari kata job performance (prestasi kerja) atau actual performance
(prestasi sesungguhnya yang dapat dicapai seseorang) yang merupakan hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya (Mangkunegara, 2009:9). Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dicapai atau pun prestasi yang
diperlihatkan. Kinerja organisasi menurut Daft (2000) adalah kegiatan suatu
organisasi yang dalam mencapai tujuannya menggunakan sumber daya yang
ada secara efektif (dikutip dalam Ghorbanpour et al., 2014). Pernyataan yang
sama juga dikemukakan oleh Ricardo (2001) yang menyatakan bahwa kinerja
organisasi itu mengacu pada kegiatan organisasi yang dilakukan untuk
mengupayakan tujuan dan sasarannya (dikutip dalam Abo-jarard, Yousof, dan
Nikbin, 2010). Definisi kinerja organisasi di atas sama-sama mengacu pada
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sementara, kinerja auditor adalah
evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri
Mangkunegara melihat kinerja berdasarkan hasil kerja menurut kualitas dan
kuantitas, di sisi lain Neely et al. (1996) memandang kinerja dari perspektif
kualitas atas efisiensi dan efektivitas dari suatu pekerjaan yang telah
dilakukan. Neely bermaksud menjelaskan dua komponen utama dalam
definisi yang ia berikan yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berbicara
mengenai ketepatan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk
menghasilkan barang dan jasa. Sementara, efektivitas berkaitan dengan
pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang dimaksud di sini
biasanya dinyatakan dalam hal kesesuaian (hasil mampu menjawab
kebutuhan pelanggan), ketersediaan (prioritas dalam distribusi dan jaraknya
secara fisik), serta kualitas (tingkat realisasi atas standar yang ditetapkan)
(Dollery dan Worthington, 1996).
Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja
organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi
kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan.
Kinerja individu akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya
kerja (work effort), dan dukungan organisasi (Mangkunegara, 2009:15).
Selain itu, Mangkunegara (2009:16) juga menyetujui pandangan teori
konvergensi William Louis Stern bahwa faktor-faktor penentu kinerja
individu adalah faktor pembawaan (individu) dan faktor lingkungan kerja
organisasi. Sementara, kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja
Selain pembagian kinerja di atas, terdapat faktor-faktor yang
memengaruhi kinerja. Hennry Simamora (1995:500) dalam Mangkunegara
(2009:14) menyatakan ada tiga faktor yang memengaruhi kinerja
(performance), yaitu :
1) Faktor individual yang terdiri dari :
a. Kemampuan dan keahlian
b. Latar belakang
c. Demografi
2) Faktor psikologis yang terdiri dari :
a. Persepsi
b. Attitude
c. Personality
d. Pembelajaran
e. Motivasi
3) Faktor organisasi yang terdiri dari :
a. Sumber daya
b. Kepemimpinan
c. Penghargaan
d. Struktur
e. Job design
Untuk mengetahui seberapa baik kinerja yang dihasilkan oleh auditor
perlu diketahui pengukuran yang digunakan untuk menilainya. Reza Surya
kerja individu tersebut yang melampaui peran atau target yang telah
ditentukan sebelumnya. Demikian pula, Miner (1988) menyatakan bahwa
dimensi kinerja adalah ukuran penilaian dari perilaku yang aktual di tempat
kerja dan mencakup :
a. Quality of Output, kinerja seseorang individu dinyatakan baik apabila
kualitas output yang dihasilkan lebih baik atau paling tidak sama dengan
target yang telah ditentukan.
b. Quantity of Output, yaitu kinerja seseorang juga diukur dari jumlah
output yang dihasilkan. Seseorang dinyatakan mempunyai kinerja yang
baik jika kuantitas output yang dicapai dapat melebihi atau setidaknya
sama dengan target yang telah ditentukan serta tidak mengabaikan
kualitas output yang bersangkutan.
c. Time at Work, yaitu dimensi waktu juga menjadi pertimbangan di dalam
mengukur kinerja seseorang. Hal ini berarti dengan tidak mengabaikan
kualitas dan kuantitas output yang harus dicapai, seseorang dinilai
mempunyai kinerja yang baik jika individu tersebut dapat menyelesaikan
pekerjaan secara tepat waktu atau bahkan melakukan penghematan
waktu.
d. Cooperation with Others’ Work, yaitu kinerja juga dinilai dari
kemampuan seorang individu untuk tetap bersifat kooperatif dengan
pekerja lain yang harus menyelesaikan tugasnya masing-masing.
Selain pengukuran, evaluasi juga penting untuk melihat apakah kinerja
adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui
peningkatan kinerja dari auditor suatu KAP. Agus Sunyoto (1999:1) dalam
Mangkunegara (2009:10) mengemukakan tujuan evaluasi kinerja secara lebih
spesifik, yaitu :
a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan
kinerja.
b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka
termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya
berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan
dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau
terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga
karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan
kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui
rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja
(performance) auditor adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh auditor
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan
kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan
memerhatikan kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, dan sikap kooperatifnya
kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan sedangkan
berdasarkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun
waktu tertentu. Ketepatan waktu adalah kesesuaian antara waktu yang dapat
dicapai untuk menyelesaikan kerja dengan waktu yang telah direncanakan.
2.1.2.Komitmen Organisasi
Komitmen setiap anggota dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting
agar organisasi tersebut tetap going concern apapun bentuk organisasinya
termasuk kantor akuntan publik. Komitmen mengindikasikan keinginan anggota
untuk tetap loyal dan mengabdikan dirinya pada organisasi tempat ia bekerja.
Robbins (2001) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan dimana
seorang individu memihak pada suatu organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan
keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.
Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang
mengikat seorang karyawan pada organisasinya sehingga mengurangi tingkat
turnover (Allen dan Meyer, 1990) dan sebagai pola pikir yang berbeda bentuknya
yang mengikat individu untuk melakukan suatu tindakan yang relevan dengan
sasaran tertentu (Meyer dan Herscovitch, 2001). Sementara Aranya et al. (1981)
menyatakan komitmen profesional yang juga berlaku bagi komitmen organisasi
sebagai :
1. Rasa percaya yang kuat dan penerimaan seseorang terhadap tujuan dan
nilai-nilai organisasi,
2. Keinginan seseorang untuk melakukan usaha secara sungguh-sungguh demi
3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu
organisasi.
Dengan demikian, individu dengan komitmen yang tinggi pada pekerjaannya
akan berusaha melakukan yang terbaik untuk organisasinya yang akan berdampak
pada keberhasilan atau kegagalan internal pekerjaannya (Gifford, 2003). Ada dua
jenis komitmen, yaitu :
1. Attitudinal commitment
2. Behavioral commitment
Mowday et al. (1982) menguraikan perbedaan di antara keduanya. Attitudinal
commitment merupakan pola pikir dimana individu memerhatikan keselarasan
tujuan dan nilai-nilai mereka dengan orang-orang dari organisasi yang
mempekerjakan mereka. Sementara, behavioral commitment adalah proses
dimana perilaku individu di masa lalu dalam sebuah organisasi mengikat mereka
kepada organisasinya. Baik attitudinal maupun behavioralcommitment memiliki
beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Aspek attitudinal antara lain :
1. Diidentifikasikan dengan organisasinya
2. Partisipasi dan keterlibatan dalam peran organisasi
3. Kesetiaan kepada organisasinya
Demikian pula yang termasuk aspek behavioral adalah :
1. Usaha yang sangat besar
Sifat saling melengkapi antara attitudinal commitment dan behavioral
commitment tak terpisahkan dalam konseptualisasi model multidimensional
komitmen organisasi Meyer dan Allen (1991).
Meyer dan Allen (1991) menyimpulkan bahwa komitmen mencerminkan
keinginan, kebutuhan, dan kewajiban untuk mempertahankan keanggotaan dalam
sebuah organisasi. Hal ini mewujudkan tiga komponen model komitmen
organisasi yang dikategorikan oleh Meyer dan Allen (1991) yaitu, komitmen
afektif (affective commitment), komitmen kontinu (continuance commitment), dan
komitmen normative (normative commitment).
1. Komitmen Afektif (Affective Commitment)
Komitmen afektif didefinisikan sebagai keterikatan emosional,
identifikasi, dan keterlibatan yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap
organisasinya (Mowday et al., 1997; Meyer dan Allen, 1993). Porter et al.
(1974) mencirikan komitmen afektif dalam tiga faktor, yaitu:
1) Kepercayaan dan penerimaan sasaran dan nilai organisasi
2) Keinginan untuk memusatkan usaha dalam pencapaian tujuan organisasi,
dan
3) Keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.
Individu memandang pekerjaannya sebagai bagian dari identitasnya dan
ingin berkontribusi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan (Smith dan Hall,
2008). Komitmen ini timbul ketika karyawan ingin menjadi bagian dari
organisasi di mana ia berada. Komitmen afektif ini juga timbul melalui
pengalaman profesional yang positif atau keahlian profesional yang
berkembang (Hall et al. 2005).
2. Komitmen Kontinu (Continuance Commitment)
Komitmen ini merupakan komitmen yang dimiliki oleh individu yang
merasa bahwa mereka harus tetap berada dalam profesi di mana ia berada
sekarang dengan pertimbangan akumulasi modal atau kurangnya alternatif
yang sebanding (Smith dan Hall, 2008). Komitmen ini didasarkan pada teori
Becker yang menyatakan bahwa orang-orang berkomitmen pada
organisasinya karena modal terakumulasi dalam organisasi tersebut atau
kurangnya alternatif yang sesuai (Hall et al., 2005). Teori Becker juga
menjelaskan bahwa individu berinvestasi di organisasinya, dan komitmennya
pada organisasi dan pekerjaannya berkaitan langsung dengan jumlah
investasinya.
Komitmen kontinu ini merupakan penyebab mengapa orang tetap berada
di posisinya yaitu karena adanya biaya yang tinggi jika harus meninggalkan
organisasi dan pekerjaannya. Kondisi pasar tenaga kerja yang tidak sesuai
dan adanya keahlian dan investasi yang tidak dapat dipindahtangankan seperti
dana pensiun dan hubungan dengan rekan sekerja menyebabkan terjadinya
peningkatan komitmen kontinu (continuance commitment).
Singkatnya, komitmen ini ada ketika karyawan tetap bertahan pada
organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain atau
menjelaskan bahwa karyawan yang bersama-sama memiliki komitmen
kontinu dengan atasannya membuat mereka sulit untuk meninggalkan
organisasi tersebut.
3. Komitmen Normatif (Normative/Mandatory Commitment)
Komitmen ini menjelaskan keadaan auditor yang menyadari bahwa
mereka harus tetap berada dalam organisasi tersebut karena paksaan (Smith
dan Hall, 2008). Komitmen organisasi normatif ini timbul saat auditor
benar-benar ingin tetap menjadi bagian dari organisasi atau setelah menerima
keuntungan mereka merasa harus membalansya (take and give) dan
merupakan hal yang timbal balik. Selain itu, juga timbul ketika auditor
menerima keuntungan yang cukup besar dengan berada pada suatu posisi atau
dengan mengalami sejumlah tekanan dari keluarga atau rekan-rekan kerja
yang menekan mereka saat berada di posisi tersebut (Hall et al., 2005).
Sederhananya, komitmen ini timbul dari nilai-nilai diri auditor. Auditor
bertahan menjadi anggota suatu kantor akuntan publik karena memiliki
kesadaran bahwa komitmen terhadap KAP tempat ia bekerja merupakan hal
yang sudah seharusnya dilakukan karena ia berkewajiban untuk itu.
2.1.3.Stres Peran (Role Stress)
Stres bersifat personal. Setiap orang memiliki tingkat toleransi yang
berbeda-beda terhadap tekanan tertentu. Sehingga, untuk tekanan yang sama
tidak selalu menghasilkan stres. Stres merupakan respon psikologis yang
penting untuk pertumbuhan, perubahan, perkembangan, dan kinerja auditor
baik di rumah maupun di tempat kerja (Quick dan Quick, 1984:1) tetapi
bagaimana auditor tersebut akan merespon stressor tergantung pada berbagai
faktor individual. Stres kerja sering timbul dalam situasi ketika seeorang
tidak dapat memenuhi kebutuhan kerja yang bersangkutan (French dan
Caplan, 1972). Artinya, orang akan mengalami stres ketika mereka tidak
dapat mengendalikan pekerjaannya atau ketika tuntutan kerja melebihi
kemampuan yang mereka miliki. Stres tidak selalu dianggap sebagai hal
yang buruk karena ada stres yang berdampak baik tetapi ada juga yang
berdampak buruk.
Stres yang buruk (distress) merupakan hasil dari situasi seperti
kehilangan pekerjaan. Sementara, stres yang baik (eustress) dapat berupa
situasi yang akhirnya akan mengondisikan kegembiraan misalnya stres yang
dialami ketika seseorang ingin mendapatkan promosi kerja mendorong
seseorang untuk bekerja dengan lebih baik untuk mencapainya (Larson,
2004). Namun, salah mengatur stres yang dimiliki organisasi berdampak
pada stres dan ketegangan individual yang mengganggu baik individu itu
sendiri maupun organisasinya. Stres berpengaruh baik pada fisik maupun
proses mental yang keduanya akan memengaruhi bagaimana seseorang
berperilaku di bawah tekanan yang berat dan memengaruhi tingkatan di mana
ia bisa melanjutkan perannya, di rumah dan di tempat kerja, secara efektif dan
Stres yang terjadi di lingkungan tempat kerja dan disebabkan oleh hal-hal
yang berhubungan dengan pekerjaan disebut stres kerja. Tuntutan peran
berkaitan dengan tekanan yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari
fungsi peran tertentu yang dimainkannya dalam organisasi tersebut (Eko
Sasono, 2004:123). Fogarty et al. (2000:32) menegaskan bahwa tekanan
peran terbagi atas tiga, yaitu konflik peran, ketidakjelasan peran, dan
kelebihan peran.
Stres peran bersifat berbahaya karena membuat auditor tidak memiliki
kepastian akan tujuan-tujuan dan harapan-harapannya dalam organisasi.
Sopiah (2008) menerangkan stres karena peran atau tugas termasuk kondisi
dimana auditor mengalami kesulitan dalam memahami apa yang menjadi
tugasnya dan merasa perannya terlalu berat atau memainkan peran yang
banyak pada tempat mereka bekerja. Pemicu stres memiliki empat penyebab
utama, yaitu:
a. Konflik Peran (Role Conflict)
Ketika di antara rekan sekerja bersaing menghadapi berbagai tuntutan
maka terjadi konflik peran ini. Ada beberapa jenis konflik peran dalam
setting organisasional, antara lain :
a) Inter-role conflict, terjadi ketika seseorang memiliki dua peran yang
masing-masing berlawanan dalam suatu organisasi.
b) Intra-role conflict, terjadi saat seseorang menerima pesan
c) Person-role conflict, terjadi saat kewajiban-kewajiban dalam
pekerjaan dan nilai-nilai organisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai
pribadi.
b. Ketidakjelasan Peran (Role Ambiguity)
Stressor ini terjadi dan dialami oleh para karyawan saat mereka merasa
bimbang tentang tugas-tugas mereka, harapan kinerja, tingkat kewenangan,
dan kondisi kerja yang lain. Hal ini cenderung terjadi saat orang memasuki
situasi yang baru, seperti menjadi anggota suatu organisasi atau mengambil
suatu tugas pekerjaan yang asing karena bimbang dengan harapan sosial dan
tugas-tugasnya.
c. Beban Kerja (workload)
Beban kerja adalah pemicu stres yang berhubungan dengan peran atau
tugas lain yang terjadi karena pegawai merasa beban kerjanya banyak. Hal
ini dapat terjadi karena para karyawan merasa beban kerjanya banyak. Hal
ini dapat terjadi misalnya karena perusahaan mengurangi tenaga kerjanya dan
melakukan restrukturisasi pekerjaan, membebani pegawai yang ada dengan
tugas yang banyak dan waktu serta sumber daya yang sedikit untuk
menyelesaikannya.
d. Karakteristik Tugas (Task Characteristics)
Beberapa tugas yang potensial memicu stres adalah ketika membuat
keputusan, memantau perlengkapan, atau saling bertukar informasi.
Pengendalian yang kurang, aktivitas dalam pekerjaan yang terlalu banyak,
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa stres peran
adalah stres yang disebabkan oleh tuntutan peran yang dilakoni oleh
seseorang ketika kemampuannya kurang memadai untuk memenuhi tuntutan
fungsi peran tersebut. Ada beberapa jenis stres peran yang diketahui.
Namun, penelitian ini hanya menggunakan konflik peran dan ketidakjelasan
peran sebagai variabel moderating.
2.1.4.Konflik Peran (Role Conflict)
Konflik peran adalah suatu situasi yang terjadi karena seseorang tidak
bekerja sesuai dengan aturan, norma, dan etika profesional. Konflik dapat
menyebabkan dampak negatif terhadap perilaku individu yang akhirnya akan
berujung pada penurunan kinerja auditor secara keseluruhan (Fanani et al.,
2007). Konflik peran merupakan gambaran kondisi karena diterimanya dua
perintah atau lebih yang berbeda secara bersamaan sehingga terabaikannya
perintah yang lain sementara perintah yang satu dilaksanakan. Konflik peran
menimbulkan harapan-harapan yang kemungkinan sulit untuk dipenuhi
(Robbins dan Judge, 2009). Demikian pula, Patelli (2007) mengemukakan
bahwa konflik peran terjadi saat dua atau lebih peran dilakukan secara
bersamaan sehingga pelaksanaan atas satu tekanan menghambat pelaksanaan
tekanan yang lainnya. Stres yang dialami secara terus-menerus selain
merugikan kinerja auditor juga menyebabkan timbulnya reduced personal
accomplishment yang mengakibatkan kepuasan kerja dan keinginan untuk
tetap bekerja di kantor akuntan publik menjadi rendah. Gibson et al. (2006)
a. Konflik Peran Pribadi (Person-Role Conflict)
Konflik ini terjadi ketika peran yang ada bertentangan dengan peran
dasar, sikap, dan kebutuhan individu yang memainkan peran tersebut.
b. Konflik Intraperan (Intrarole Conflict)
Konflik ini terjadi ketika individu terkait peran memiliki harapan yang
berbeda dengan definisi peran yang sebenarnya ia lakoni sehingga ia sulit
untuk memenuhi semua permintaan perannya.
c. Konflik Antarperan (Interrole Conflict)
Konflik ini terjadi ketika individu mengerjakan banyak peran yang
memiliki harapan yang saling bertentangan secara bersamaan.
Teori peran menegaskan bahwa ketika individu tidak memiliki
kekonsistenan terhadap perilaku-perilaku yang diharapkan darinya maka ia
akan mengalami stres yang berdampak pada efektivitas organisasi yang
menurun. Rizzo et al. (1970) melihat konflik peran sebagai penyebab
menurunnya kepuasan individu dan efektivitas organisasi. Role conflict dan
role ambiguity merupakan dua ketegangan psikologis yang memengaruhi
baik kesehatan mental maupun fisik (Jackson, 1983).
Umar Nimran (2004) menyebutkan ciri-ciri seseorang yang berada dalam
konflik peran, yaitu :
a. Mengerjakan hal-hal yang tidak perlu.
b. Terjepit di antara dua atau lebih kepentingan yang berbeda (atasan dan
c. Mengerjakan sesuatu yang diterima oleh pihak yang satu tetapi tidak oleh
pihak yang lain.
d. Menerima perintah yang bertentangan.
e. Mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan keadaan dimana saluran
komando dalam organisasi tidak terpenuhi.
Beberapa definisi mengenai konflik peran di atas dapat disimpulkan
bahwa konflik peran (role conflict) adalah suatu ketegangan psikologis yang
dihadapi oleh seseorang yang terjepit di antara situasi yang menempatkannya
di keadaan yang tidak sesuai antara perintah yang diberikan dengan sikap,
komitmen, dan kebutuhan dari individu yang memainkan peran tersebut.
Fanani et al. (2008) menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kinerja auditor. Konflik peran berdampak buruk
terhadap perilaku individu yang memicu dampak buruk lainnya yang hasilnya
adalah kinerja yang buruk.
2.1.5.Ketidakjelasan Peran (Role Ambiguity)
Ketidakjelasan peran adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak, hak
istimewa dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan
(Gibson et al., 1997). Zaenal Fanani et al. (2007) menyatakan bahwa role
ambiguity terjadi ketika informasi yang dimiliki tidak cukup, tidak adanya
arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian otoritas, kewajiban dan
hubungan dengan yang lainnya, serta adanya ketidakpastian sanksi dan
menjelaskan bahwa ketidakjelasan peran terjadi saat pemahaman tentang
harapan peran tidak jelas dan individu tidak memiliki kepastian akan apa
yang harus dikerjakannya. Hal ini dapat terjadi pada semua orang tak
terkecuali auditor sendiri. Ketidakjelasan peran dapat membuat orang-orang
sulit untuk menyesuaikan diri dengan organisasinya karena mereka tidak
mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan darinya. Oleh karena itu,
mereka mengharapkan penjelasan sehingga mereka mengerti apa yang harus
dan tidak harus dikerjakan.
Menurut teori peran, ketidakjelasan peran yang dialami dalam waktu
yang lama dapat mengikis kepercayaan diri, memupuk ketidakpuasan kerja,
dan menghambat kinerja. Penelitian Jackson (1983) menemukan bahwa role
ambiguity berkorelasi negatif dengan kesehatan psikologis dan kesejahteraan
fisik. Demikian pula, teori klasik menyatakan bahwa setiap kedudukan dalam
struktur organisasi formal harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang
khusus dan jelas. Seperti Rizzo et al. (1970) menyatakan bahwa jika
seseorang tidak tahu dengan pasti otoritas yang sebenarnya yang dimilikinya
untuk mengambil keputusan, apa yang diharapkan untuk dicapai, dan
bagaimana dia akan dinilai maka ia akan ragu untuk membuat keputusan dan
harus mengandalkan pendekatan trial and error dalam memenuhi
harapan-harapan pemimpinnya. Hal ini tentunya akan menempatkannya pada situasi
yang tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan perannya yang sebenarnya
Umar Nimran (2004) menggambarkan ciri-ciri mereka yang berada
dalam ketidakjelasan peran sebagai berikut :
a. Tidak mengetahui dengan jelas apa tujuan peran yang dimainkannya.
b. Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor
kepadanya.
c. Tidak cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
d. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan darinya.
e. Tidak memahami dengan benar peranan pekerjaannya dalam rangka
mencapai tujuan secara keseluruhan.
Maka, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan peran (role ambiguity)
merupakan kurang memadainya informasi yang dimiliki oleh seseorang untuk
mengerti perannya secara utuh dan memahami kewajiban-kewajiban dan
hak-haknya dalam organisasi sehingga ia tidak dapat melakukan tugasnya sesuai
dengan tuntutan peran yang dimilikinya. Fanani et al. (2008) menemukan
bahwa ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap ketidakjelasan peran.
Sementara, Fried (1998) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran
berpengaruh pada level kinerja yang lebih rendah. Seperti konflik peran,
ketidakjelasan peran pun berbahaya bagi kesehatan psikologis dan fisik
karena merupakan memicu stress.
2.2.Penelitian Terdahulu
Adapun hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik
Tabel 2.1
Penelitian-penelitian Terdahulu
No. Peneliti Judul Penelitian Variabel Teknik
Tabel 2.1. (Lanjutan)
No. Peneliti Judul Penelitian Variabel Teknik
Analisis
Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki independensi dan komitmen organisasi yang tinggi, cara memimpin yang baik, serta adanya budaya organisasi akan meningkatkan kinerja dalam organisasi di mana ia bekerja. 4. Zaenal Fanani
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Peneliti Judul Penelitian Variabel Teknik
2.3.Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting (Umar Sekaran, 1992). Kerangka konseptual yang baik merupakan
jaringan hubungan antarvariabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan,
dan dielaborasi dari perumusan masalah yang diidentifikasi melalui baik proses
wawancara, observasi, maupun survei literatur. Untuk mencapai tujuan bersama,
kantor auditor harus memperhatikan kinerja para auditornya. Komitmen
organisasi dipandang sebagai faktor yang meningkatkan kinerja auditor. Di sisi
lain, stres peran diketahui sebagai pemicu yang memperlemah hubungan di antara
keduanya.
Secara skematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada
gambar berikut ini:
2.4.Hubungan Antarvariabel dan Perumusan Hipotesis
2.4.1.Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Komitmen organisasi mengindikasikan keinginan anggota untuk tetap
loyal dan mengabdikan dirinya pada organisasi tempat ia bekerja. Auditor
yang percaya pada nilai-nilai organisasinya akan merasa ikut memiliki
organisasi tersebut. Oleh karena itu, mereka yang merasa bahwa dirinya
terikat dengan nilai-nilai tersebut akan melakukan pekerjaannya dengan
senang hati sehingga kinerjanya pun meningkat.
Penelitian Meyer et al. (1989) menunjukkan korelasi yang positif antara
komitmen afektif dengan kinerja. Sebaliknya, komitmen kontinu berkorelasi
secara negatif dengan kinerja. Sementara, Somers dan Birnbaum (1998)
menyatakan bahwa baik komitmen afektif maupun kontinu tidak berpengaruh
terhadap kinerja.
Komitmen merupakan suatu konsistensi wujud keterikatan seseorang
terhadap suatu hal seperti karir, keluarga, lingkungan sosial, dan sebagainya.
Komitmen dapat menjadi dorongan bagi seseorang untuk bekerja dengan
lebih baik atau sebaliknya dapat menyebabkan seseorang justru meninggalkan
pekerjaannya karena tuntutan komitmen lainnya. Komitmen yang tepat akan
memberikan dampak yang baik terhadap kinerjanya dalam suatu pekerjaan.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut :
H1 : Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
2.4.2.Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan Konflik Peran Terhadap Kinerja Auditor
Komitmen organisasi didefinisikan sebagai bentuk identifikasi
keterlibatan seseorang dalam suatu bagian organisasi (Mowday, et al., 1992).
Komitmen organisasi dapat tumbuh ketika harapan kerja dapat terpenuhi oleh
organisasi dengan baik. Seseorang yang merasa jiwanya terikat dengan
nilai-nilai organisasi akan merasa senang bekerja sehingga kinerja meningkat.
Ghorbanpour et al. (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi
berhubungan secara positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.
Konflik peran adalah suatu konflik yang timbul karena mekanisme
pengendalian birokrasi tidak sesuai dengan norma, etika, aturan, dan
kemandirian profesional. Konflik peran dapat menimbulkan rasa tidak
nyaman dalam bekerja sehingga berdampak negatif terhadap perilaku
individu yang akhirnya menurunkan kinerja auditor secara keseluruhan.
Khoo dan Sim (1997) meneliti tentang konflik peran auditor di Korea. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa auditor di Korea mengalami konflik peran
yang signifikan sehingga dalam bekerja mereka cenderung berkompromi
dengan motif ekonomi dan kurang memperhatikan etika profesional.
Akibatnya, kinerjanya terabaikan.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut :
H2 : Interaksi antara komitmen organisasi dengan konflik peran
2.4.3.Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan Ketidakjelasan Peran Terhadap Auditor
Ketidakjelasan peran merupakan keadaan yang menjelaskan tidak
diketahuinya gambaran peran secara jelas. Gibson et al. (1997)
mendefinisikannya sebagai kurangnya pemahaman atas hak-hak, hak
istimewa dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melakukan
pekerjaannya. Komitmen organisasi diketahui sebagai bentuk loyalitas dan
keterlibatan seseorang di dalam organisasinya. Semakin sering seseorang
terlibat dan loyal dalam suatu organisasi maka dapat diartikan semakin tinggi
komitmennya terhadap organisasinya. Keterlibatan yang terus-menerus
terjadi di dalam suatu organisasi membuat seseorang akan semakin
mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam tugas-tugasnya dan mengetahui
apa yang menjadi haknya. Penjelasan ini memberikan arti bahwa semakin
tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap organisasinya maka akan
semakin rendah ketidakjelasan peran yang dialaminya. Ketidakjelasan peran
yang semakin tinggi akan memperburuk kinerja. Fanani et al. (2007)
menyatakan bahwa ketidakjelasan peran berpotensi menurunkan motivasi dan
kinerja secara keseluruhan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut :
H3 : Interaksi antara komitmen organisasi dengan ketidakjelasan peran