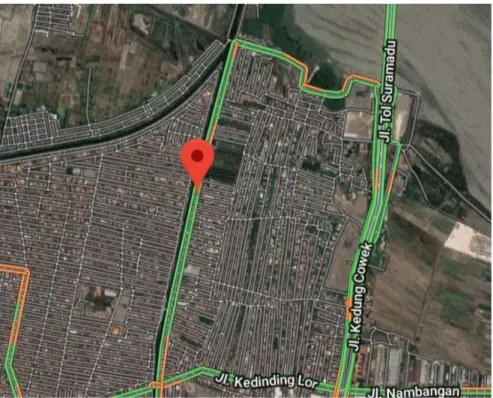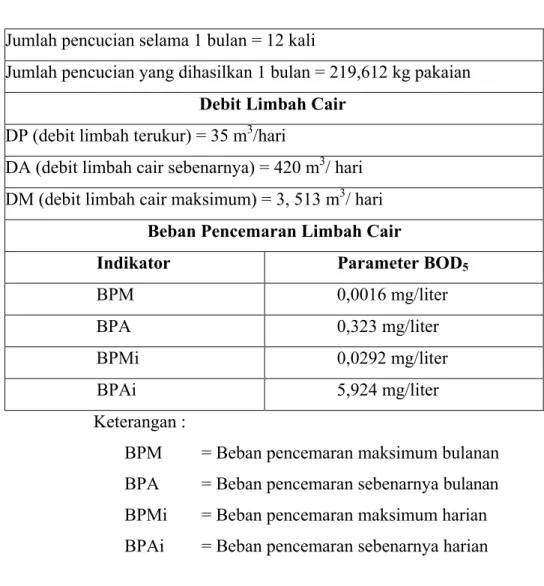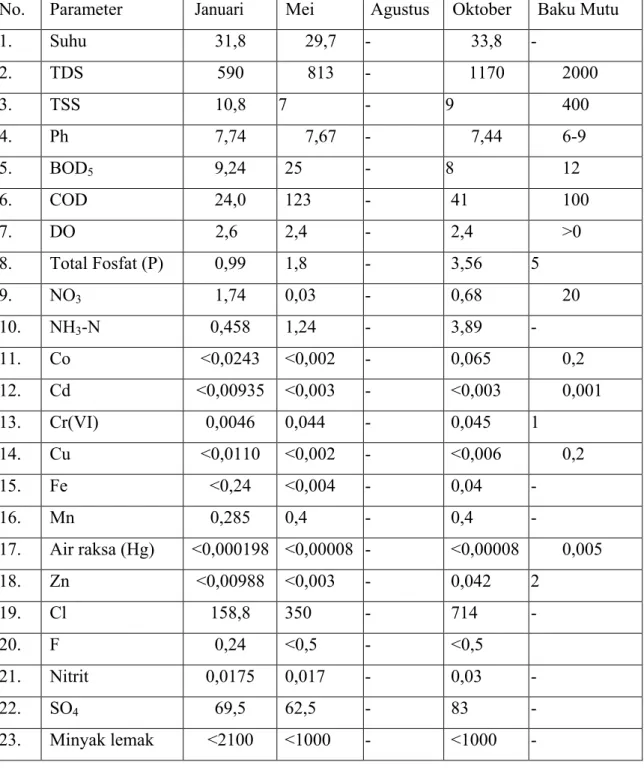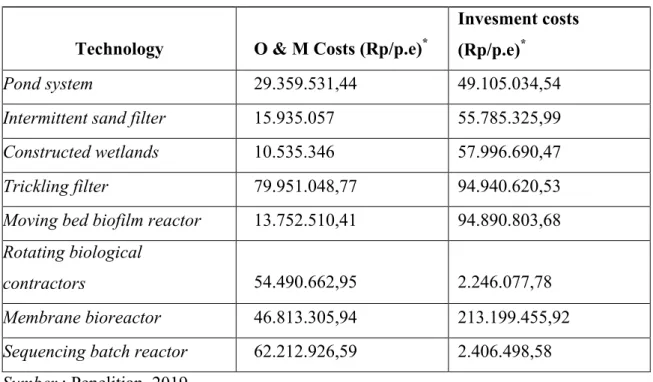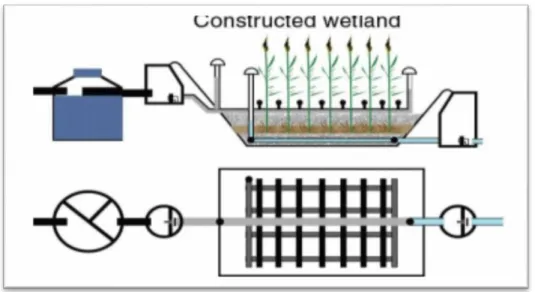BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Permasalahan pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran bukan merupakan hal baru. Telah banyak hasil penelitian dan kajian-kajian saintifik yang menunjukkan bahwa perairan tersebut telah tercemar. Salah satu penelitian mengenai pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran dilakukan oleh Hutomo dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa kandungan logam berat di perairan Kenjeran telah jauh melebihi baku mutu air laut yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004. Dari hasil penelitian tersebut, kandungan tertinggi untuk logam berat timbal (Pb) dan tembaga (Cu) di perairan Kenjeran masing-masing sebesar 13,5933 mg/Kg dan 30,7187 mg/Kg, sementara baku mutu air laut untuk kedua logam berat tersebut hanya 0,008 mg/L.
Namun demikian, belum ada penelitian atau kajian mengenai valuasi
ekonomi dampak lingkungan akibat pencemaran yang terjadi di wilayah
pesisir Kenjeran tersebut. Valuasi ekonomi dampak lingkungan merupakan
proses kuantifikasi dan pengenaan nilai moneter terhadap dampak
lingkungan setelah sebelumnya dilakukan proses atau tahapan identifikasi
terlebih dahulu. Valuasi ekonomi dampak lingkungan ini penting dilakukan
mengingat wilayah pesisir Kenjeran merupakan salah satu kawasan strategis
yang menurut Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) Kota Surabaya berada
pada Unit Pembangunan 3. Menurut RTRW Kota Surabaya, kawasan ini akan dikembangkan sesuai fungsinya sebagai wilayah pemukiman, perdagangan, wisata, jasa dan konservasi.
Sebelumnya, peneliti telah melakukan kajian serupa tekait valuasi ekonomi dampak tumpahan minyak di perairan Cilacap (Mauludiyah, 2016).
Melalui pendekatan valuasi ekonomi total (total economic valuation, TEV) diperoleh total biaya kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di perairan Cilacap dari skenario yang telah ditentukan mencapai Rp. 1,9 triliun. Perhitungan biaya kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak pada penelitian ini dilakukan dengan memperhitungkan ekosistem terdampak dan kematian satwa burung.
Valuasi ekonomi dampak lingkungan diperlukan sebagai upaya
untuk menunjukkan bahwa aspek lingkungan merupakan potensi penting
untuk jangka panjang dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan dan bukan
sebagai halangan bagi jalannya pembangunan. Dengan demikian upaya
mengkuantifikasi nilai lingkungan tersebut perlu dilakukan untuk
mengingatkan para pengambil kebijakan akan pentingnya memperhatikan
dampak yang timbul dari sebuah kegiatan terhadap lingkungan hidup.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa biaya yang ditimbulkan dari pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Kenjeran.
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi biaya yang ditimbulkan dari pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Kenjeran.
1.4 Kajian Penelitian Terdahulu
1. Monika Elisabeth Gabriel, Arya Rezagama, Badrus Zaman. 2017.
Valuasi Ekonomi Lingkungan Dampak Abrasi Menggunakan Metode Replacement Cost, Hedonic Pricing dan Loss of Income (Studi Kasus: Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang). Dipublikasikan pada Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6,
No. 1: 1-12.Latar belakang penelitian ini adalah abrasi yang terjadi di
wilayah Kelurahan Mangunharjo yang berdampak pada banyak hal,
mulai dari kualitas air yang menurun hingga kehilangan pendapatan
sawah dan tambak bagi masyarakat setempat. Kualitas air yang menurun
dikarenakan terjadinya peningkatan salinitas air bersih. Hal ini
menyebabkan penduduk harus membayar lebih untuk pemenuhan
kebutuhan air bersih. Selain itu, kerusakan dan penurunan kualitas
lingkungan ini berpotensi mempengaruhi harga lahan di wilayah tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak abrasi serta mengestimasi valuasi ekonomi lingkungan akibat dampak abrasi. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak abrasi digunakan metode analisis deskriptif. Untuk analisis valuasi ekonomi lingkungan akibat dampak abrasi digunakan: 1) metode replacement cost untuk menghitung biaya pengganti air bersih baik dari penyediaan sumur dan air isi ulang akibat dampak abrasi,2) metode hedonic pricing (dilakukan dengan uji regresi linier berganda) untuk melihat pengaruh kondisi lingkungan akibat dampak abrasi terhadap harga lahan, 3) dan metode loss of income untuk mengetahui pendapatan yang hilang dari petani dan petambak di Kelurahan Mangunharjo akibat dampak abrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan
kondisi lingkungan semakin memburuk akibat dampak abrasi. Biaya
pengganti air bersih sebesar Rp 2.916.466.336 selama satu tahun
(berdasarkan perhitungan pada tahun 2015). Faktor yang berpengaruh
terhadap harga lahan yaitu status kepemilikan lahan dan aksesibilitas,
sedangkan biaya air bersih dan frekuensi genangan air laut tidak
berpengaruh. Rata-rata pendapatan yang hilang dari petambak selama 1
tahun sebesar Rp 49.595.803, rata-rata pendapatan yang hilang dari
petani yang menjadi petambak sebesar Rp 18.161.400 dalam setahun
dan rata-rata pendapatan yang hilang selama 1 tahun dari petani sebesar Rp 10.639.733 akibat abrasi.
2. Deni Kusumawardani. Estimasi Biaya Pencemaran Air Sungai:
Studi Kasus pada Kali Surabaya sebagai Air Baku untuk Produksi Air Minum. Dipublikasikan pada Majalah Ekonomi Tahun XXII, No. 2 Agustus 2012, hal 116-124.
Penelitian ini dilatarbelakangi fakta bahwa salah satu kerusakan
lingkungan yang paling serius di Indonesia adalah pencemaran air
sungai, termasuk pencemaran air Kali Surabaya. Tercemarnya air sungai
yang menyediakan lingkungan bagi barang dan jasa untuk manusia,
misalnya sebagai air baku untuk memproduksi air domestik,
menjadikan beban ekonomi semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan
untuk memperkirakan beban ekonomi pencemaran air Kali Surabaya
sebagai air baku untuk produksi air domestik. Dari hasil perhitungan dan
analisis yang dilakukan didapatkan bahwa estimasi biaya ekonomi dari
pencemaran air Kali Surabaya adalah sekitar Rp 15,9 miliar pada tahun
2005 dan meningkat menjadi Rp 21 miliar di tahun 2009. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tren biaya polusi meningkat setiap
tahunnya yang menunjukkan peningkatan tingkat pencemaran air.
3. Dwight RH, Fernandez LM, Baker DB, Semenza JC, Olson BH.
2005. Estimating the economic burden from illnesses associated with recreational coastal water pollution--a case study in Orange County, California. Dipublikasikan pada Journal Environmental
Management. 2005 Jul; 76(2): 95-103.Penelitian ini menggunakan kerangka kerja perhitungan beban kesehatan dari penyakit yang terkait dengan paparan air laut yang tercemar untuk pemanfaatan wisata dan rekreasi. Biaya penyakit dihitung berdasarkan data kesehatan dan pendapatan. Dengan menggunakan data keparahan penyakit akibat paparan air pantai yang tercemar dan perkiraan rata-rata gaji tahunan dan biaya medis (disesuaikan dengan nilai tahun 2001) untuk penduduk Orange County, California, diperkirakan bahwa beban ekonomi per penyakit gastrointestinal (GI) berjumlah 36,58 dolar, beban per penyakit pernapasan akut adalah 76,76 dolar, beban penyakit per telinga adalah 37,86 dolar, dan beban penyakit per mata adalah 27,31 dolar.
Biaya-biaya tersebut dapat menjadi beban kesehatan masyarakat
yang substansial ketika jutaan paparan per tahun terhadap air pantai
yang tercemar mengakibatkan ratusan ribu penyakit. Analisis lebih
lanjut menunjukkan bahwa kombinasi beberapa bahkan banyak penyakit
yang terkait dengan pencemaran air pantai menghasilkan beban
kesehatan masyarakat kumulatif hingga mencapai 3,3 juta dolar per
tahun untuk dua pantai di wilayah Orange County, California. Pada
penelitian ini juga ditunjukkan variabel biaya kesehatan masyarakat
yang dapat diterapkan dalam analisis biaya-manfaat ketika
mengevaluasi strategi pengurangan pencemaran, khususnya pencemaran
di wilayah pesisir dan laut.
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pencemaran Laut
Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi kelautan, maka mau tidak mau penerapan teknologi kelautan akan membawa serta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak tidak langsung dari kegiatan penerapan teknologi kelautan meliputi dampak sosial ekonomi yang dipacu oleh tersedianya barang dan jasa dengan nilai tambah lebih tinggi. Sedangkan dampak langsung penerapan teknologi kelautan berupa dampak lingkungan, yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya hasil samping pada proses transformasi sumberdaya untuk peningkatan nilai tambah (Mukhtasor, 2007).
Hasil samping tersebut seringkali disebut limbah, yang umumnya
dipandang tidak mempunyai nilai tambah, dan oleh karenanya dibuang ke
lingkungan, khususnya lingkungan laut. Keberadaan limbah di suatu
lingkungan akan meningkatkan beban ekosistem dan merugikan
kepentingan masyarakat. Kerugian tersebut mencakup penurunan kualitas
lingkungan, tingkat kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Secara sederhana,
penurunan kualitas lingkungan laut ini dikaitkan dengan apa yang disebut
pencemaran laut.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Secara lebih spesifik, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH, 1991) mendefinisikan bahwa pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi, secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut termasuk daerah pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik terhadap sumberdaya alam hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut serta menurunkan kualitas tempat tinggal dan rekreasi.
Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pencemaran
didahului dengan proses masuknya polutan seperti zat, makhluk hidup atau
energi yang menjadi pencemar. Secara garis besar, ada dua cara bahan
pencemar masuk ke lingkungan pesisir dan laut, yaitu (1) secara alami,
misalnya karena gelombang tsunami yang membawa polutan ikutan,
ataupun (2) melalui kegiatan manusia (anthropogenic), misalnya kecelakaan
kapal tanker yang menyebabkan pencemaran minyak tumpah ke laut, atau
pembuangan bahan hasil pengerukan pelabuhan yang menyebabkan
kekeruhan air laut (Mukhtasor, 2007).
Selanjutnya polutan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu energi dan substansi. Energi yang dapat mencemari laut dapat berupa: (1) energi radiasi nuklir dan (2) energi panas. Contoh pencemaran dalam kategori pencemaran energi adalah pembuangan limbah nuklir dan pembuangan air pendingin mesin (cooling water) yang memiliki energi panas yang relatif besar (ditandai dengan suhu yang lebih tinggi daripada suhu lingkungan laut). Energi radiasi dan energi panas yang masuk ke lingkungan laut dapat mengganggu keseimbangan kehidupan ekosistem di kawasan tersebut.
Sedangkan substansi pencemar dapat dibedakan menjadi tiga jenis,
yaitu: (1) polutan fisik, yaitu polutan yang keberadaannya atau karakter
fisiknya menyebabkan pencemaran. Contohnya adalah padatan tersuspensi
pada kegiatan pengerukan pelabuhan atau pada proses sedimentasi di muara
sungai, dan zat pewarna atau bahan organik yang mengubah warna atau bau
perairan. (2) polutan kimia, yaitu polutan yang memiliki struktur kimia tidak
stabil dan cenderung bereaksi dengan zat lain. Polutan ini dikategorikan
menjadi dua jenis, yaitu organik (yang tersusun utamanya oleh atom C, H
dan O, misalnya pestisida, pupuk, minyak, limbah makanan dan minuman)
dan jenis anorganik (misalnya asam, alkali dan logam-logam berat dari
industri konstruksi baja dan tambang mineral). (3) polutan biologis, yaitu
polutan yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme dari limbah
domestik berupa pembuangan sanitasi atau tinja (biasa disebut juga dengan
sewage) dan dari industri pengolahan makanan.
2.2 Valuasi Ekonomi
Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan adalah upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumberdaya alam dan lingkungan, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Hal ini berupa nilai ekonomi total, nilai pemulihan kerusakan pencemaran, serta nilai pencegahan kerusakan/pencemaran (Dhewanti dkk., 2007). Secara umum valuasi ekonomi bertujuan untuk (Suparmoko, 2006):
1. Menentukan nilai ekonomi total (Total Economic Value, TEV) dari suatu sumberdaya alam dan lingkungan yang berada dalam suatu kawasan ekosistem tertentu
2. Menentukan nilai jasa lingkungan tertentu dari suatu ekosistem atau sumberdaya alam dan lingkungan
3. Menentukan nilai kerusakan lingkungan dengan tujuan menentukan nilai ganti rugi
4. Menentukan nilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan 5. Menentukan nilai lingkungan (kerusakan lingkungan, nilai SDA dan
lingkungan, dan lain-lain) dengan tujuan menyusun neraca SDA dan lingkungan
6. Menentukan nilai lingkungan untuk menyusun PDRB Hijau
Secara lebih spesifik, valuasi ekonomi dampak lingkungan adalah
proses kuantifikasi dan pemberian nilai ekonomi terhadap dampak
lingkungan setelah dilakukan identifikasi terlebih dahulu (Pearce, 1987
dalam Kay dan Alder, 1999). Seperti misalnya, biaya kerusakan (damage cost) yang berupa resiko penurunan jumlah wisatawan pada suatu daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata. Hal ini dikatakan oleh Coccossis dan Nijkamp (1995) dalam Kay dan Alder (1999) bahwa penurunan jumlah wisatawan lebih sering disebabkan karena terjadinya degradasi lingkungan yang signifikan akibat pengembangan perencanaan yang seadanya dan dampak adanya wisatawan itu sendiri pada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah penggunaan lokasi daerah wisata tetapi juga terlindungi, dengan kata lain menjadikan daerah pantai dan pesisir yang lebih menarik (enjoyable) dan aman (safe) bagi kegiatan wisata (Kay dan Alder, 1999).
Dalam kegiatan valuasi ekonomi, ada beberapa pendekatan yang dapat
digunakan dalam proses kuantifikasi dan pemberian nilai ekonomi terhadap
dampak lingkungan, diantaranya Contingent Valuation Method (CVM) dan
pendekatan produktivitas (Effect of Production, EOP). CVM merupakan
metode yang digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar nilai
suatu barang/jasa berdasarkan estimasi seseorang/individu. Fungsi
barang/jasa tersebut umumnya tidak ada dalam struktur pasar (non-marketed
goods and services). CVM juga dapat diartikan sebuah pendekatan untuk
mengetahui seberapa besar nilai yang diberikan seseorang untuk memperoleh
suatu barang (willingness to pay, WTP) dan seberapa besar nilai yang
diinginkan untuk melepaskan suatu barang (willingness to accept, WTA).
Pendekatan produktivitas (EOP) dalam penilaian ekonomi sumberdaya alam dilakukan dengan asumsi bahwa sumberdaya alam dipandang sebagai input bagi suatu produk final yang bernilai bagi publik, dan kapasitas produksi dari sumberdaya alam tersebut dinilai dari seberapa besar kontribusi sumberdaya alam tersebut kepada produksi produk final (Grigalunas and Congar, 1995 dalam Suparmoko, 2006).
2.3 Contingent Valuation Method (CVM)
Contingent valuation method (CVM) merupakan metode penilaian ekonomi terhadap barang dan jasa lingkungan. Contingent valuation method adalah metode teknik survei untuk menyatakan nilai atau harga yang diberikan terhadap komoditi yang tidak memiliki harga pasar (Anissa, 2015).
Contingent Valuation Method (CVM) digunakan untuk menghitung nilai ameniti atau estetika lingkungan dari suatu barang publik (public good). FAO (2000) menyatakan bahwa penilaian berdasarkan preferensi (Contingent Valuation) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar nilai suatu barang berdasarkan estimasi seseorang.
Contingent valuation method (CVM) merupakan teknik untuk
mengukur nilai barang publik secara langsung dengan menanyai orang-
orang tentang nilai tempat yang mereka tinggali. Jika digunakan secara
tepat, metode ini merupakan teknik paling tepat untuk mengestimasi nilai ekonomis suatu barang publik (Saptutyningsih, 2007).
Contingent Valuation Method (CVM) telah banyak digunakan untuk mengukur dengan menggunakan metode yang tepat untuk mengagregasi nilai estimasi rata-rata atau nilai tengah willingness to pay untuk berbagai kelompok dalam masyarakat telah memfokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terkait dengan karakteristik yang tidak dapat diobservasi.
2.4 Willingness to Pay (WTP)
Berdasarkan (Fauzi, 2004) valuasi ekonomi merupakan pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya secara formal. Konsep ini disebut keinginan membayar (willingness to pay atau WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan.
Kesediaan membayar adalah jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan seseorang untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan.
Willingness to Pay merupakan suatu teknik untuk mengukur berapa nilai harga kerugian yang timbul kerena polusi tetapi kita tidak dapat secara langsung mengetahui harga pasar (Suparmoko, 2008). Menurut (Eman, 2003) metode yang terdapat dalam Wilingness to Pay adalah:
Metode dengan menggunakan batasan keinginan (Haab dan
Kenneth, 1997:1) Pada metode ini keinginan untuk membayar
mempunyai batas bawah 0 dan batas atas adalah pendapatan.
Tujuannya adalah untuk menentukan batasan atas dan batasan bawah pada keinginan untuk membayar. Keuntungan model ini adalah memfokuskan pada pendistribusian keinginan untuk membayar dan pada informasi perespon
Metode Validitas (Loomis,et al,1997:450). Terdapat 2 bentuk uji validitas yaitu eksperimen lapangan dan eksperimen laboratorium.
- Eksperimen lapangan digunakan untuk mengukur pembayaran aktual.
- Eksperimen laboratorium membandingkan secara aktual
dengan hipotesa WTP yang memberi keuntungan dalam
mengkontrol prosedur lebih hati-hati.
BAB 3
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, sebelum melakukan penilaian dampak akibat pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran secara kuantitatif maka dilakukan terlebih dahulu identifikasi dampak yang mungkin timbul akibat pencemaran di wilayah tersebut. Identifikasi dampak dilakukan dengan menggunakan survey lapangan dan wawancara terstruktur. Pada tahapan ini juga dilakukan pengumpulan data terkait resiko yang mungkin timbul akibat pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran, diantaranya: konsentrasi limbah pencemar, jumlah wisatawan, jumlah penduduk, dan tingkat produktivitas perikanan. Data lain terkait pengolahan hasil perikanan, daur ulang, dan pariwisata di wilayah pesisir Kenjeran juga akan diidentifikasi. Hal ini disesuaikan dengan potensi pengembangan wilayah untuk pesisir timur Surabaya (Bapemas-KB Surabaya, 2010 dalam Pustika, 2013).
Selanjutnya, analisis ekonomi dampak akibat pencemaran di wilayah
pesisir Kenjeran dapat dilakukan dengan pendekatan penilaian langsung
(direct approach) dan tidak langsung (indirect approach). Pendekatan
penilaian langsung pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode penilaian Contingent Valuation Method (CVM), sedangkan
pendekatan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan teknik Effect on
Production (EoP). Metode perhitungan nilai ekonomi dampak akibat
pencemaran ini dilakukan menggunakan kuesioner dan diolah lebih lanjut
dengan analisis regresi. Pengolahan data lebih lanjut juga dilakukan menggunakan metode perhitungan berdasarkan referensi terkait, seperti misalnya perhitungan tingkat resiko kesehatan dengan menggunakan persamaan yang dibangun oleh Cabelli dkk. (1982) dalam Kay dan Wyer (1990).Anali D
ampa
Gambar 3.1. Lokasi Penelitian Kelurahan Tambak Wedi
3.1 Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini untuk mengambil sampel digunakan metode purposive random sampling yaitu sampling yang dilakukan berdasarkan keputusan peneliti.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:
A. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.
Wawancara merupakan pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung. Sedangkan
kuesioner dilakukan dengan menyebarkannya kepada
responden. Adapun data primer yang dgunakan dalam
penelitian ini yaitu data kesediaan membayar
(willingness to pay) masyrakat data pendukung lainya.
B. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diambil dari literatur pada dinas sebagai informasi yang menunjang penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan cara-cara sebagai berikut:
Interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada responden terkait apa saja yang berkaitan dengan penelitian.
Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dulu lalu menyebarkan angket tersebut kepada masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
3.4 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Untuk mengolah data primer
digunakan contingen valuation method (CVM) untuk mencari nilai
willingness to pay (WTP). Melalui CVM responden diberi pertanyaan
sejauh mana kesediaan rumah tangga membayar pengelolaan sampah di
perairan Tambak Wedi. Untuk menghitung nilai WTP digunakan rumus total kesediaan membayar (TWTP) sebagai berikut (Ismail & Bryan, 2011):
Dimana :
TWTP = Total WTP
WTPi = WTP individu kelas-i
ni = jumlah responden kelas-i yang bersedia membayar sebesar WTPi
N = Jumlah sampel
P = Jumlah populasi i (1,2,3...)
Teknik yang digunakan dalam mendapatkan nilai
penawaran dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan
metode bidding game dan close ended question yang berarti
menawarkan kepada responden sejumlah uang tertentu sebagai
titik awal dan menanyakan apakah responden bersedia
membayar pada nilai tersebut untuk memperoleh perbaikan
kualitas perairan. Respon yang diberikan responden terhadap
titik awal akan dilanjutkan dengan proses tawar menawar
hingga memperoleh besarnya nilai maksimum yang disepakati.
Selanjutnya analisis data yang digunakan untuk mengetahui estimasi biaya pengelolaan limbah deterjen dengan menggunakan acuan Molinos- Senante et al. (2012).
i