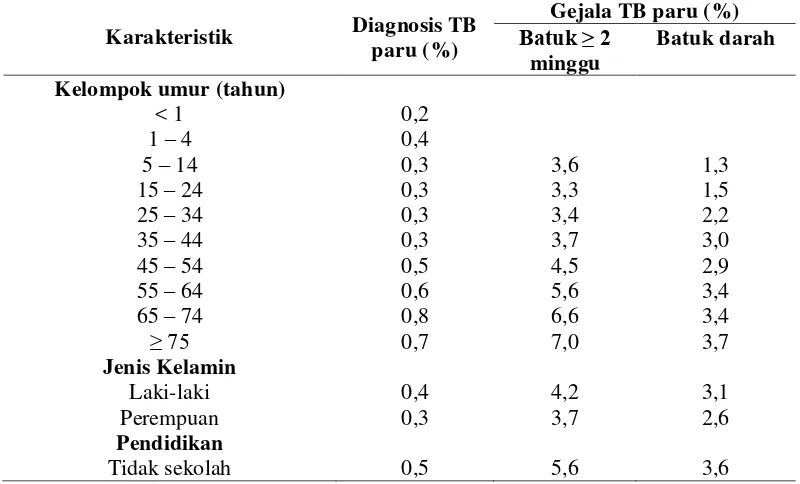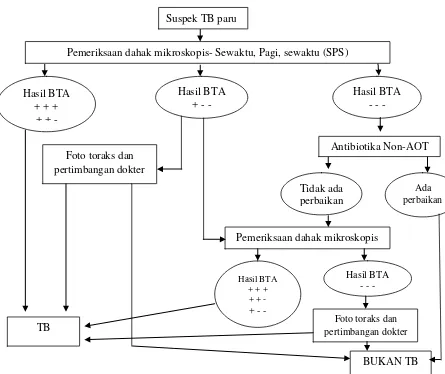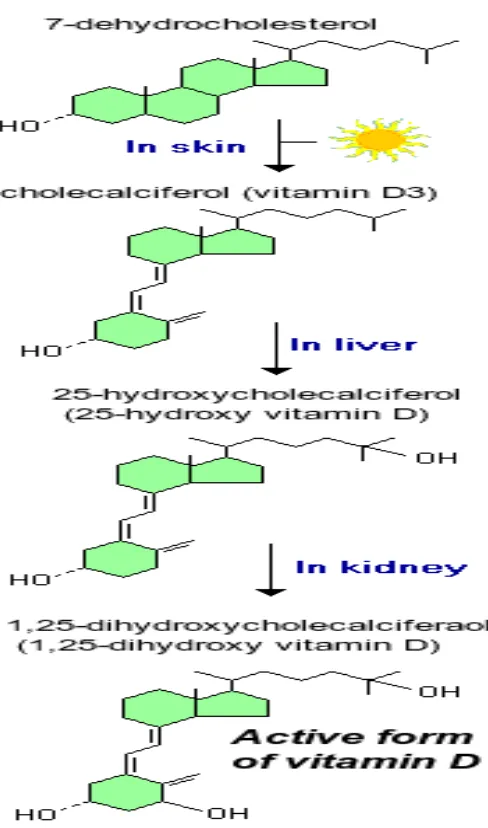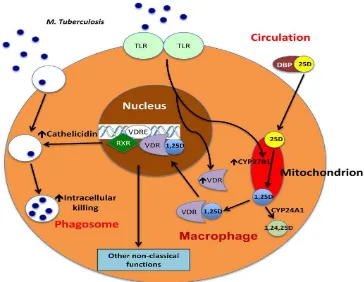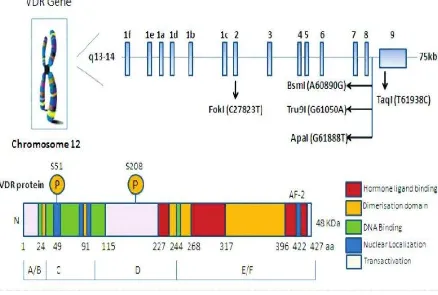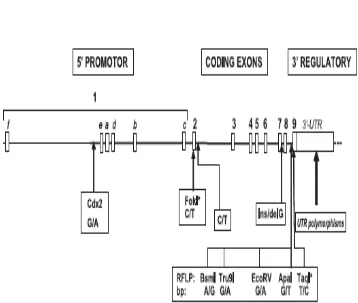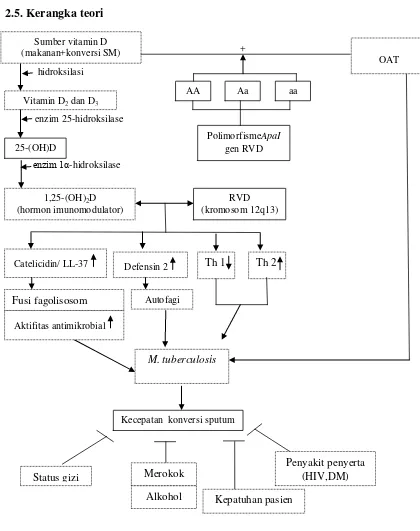BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tuberkulosis Paru
Penyakit tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih
menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian yang
disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar
melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Prevalensi
didefenisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu
dan mortalitas/ kematian didefenisikan sebagai jumlah kematian akibat
tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu (Kemenkes, 2014).
Penemuan kasus TBdilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari
pemeriksaan fisik dan laboratorium, menentukan diagnosis, menentukan
klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB sehingga dapat dilakukan pengobatan agar
pasien sembuh dan tidak menularkannya kepada orang lain. Gejala utama pasien
TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti
dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas,
badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat
malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Setiap
pasien yang datang dengan gejala-gejala tersebut dianggap sebagai tersangka
(suspek) pasien TB dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis
langsung. Untuk menegakkan diagnosisTB pada pasien dilakukan pemeriksaan
laboratorium kulturM. tuberculosis dan pemeriksaan foto toraks (Kemenkes,
2.1.1. Epidemiologi
Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu penyakit menular yang paling
mematikan di dunia. Pada tahun 2013, diperkirakan 9,0 jutaorang terinfeksiTB
dan 1,5 juta meninggal karena penyakit ini, 360.000 di antaranya adalah
HIV-positif. TB secara perlahanmenurun setiap tahun dan diperkirakan 37
jutakehidupan diselamatkan antara tahun 2000 dan 2013 melalui diagnosis dan
pengobatan efektif. Namun, mengingat bahwa sebagian besar kematian
disebabkanTB dapat dicegah, angka kematian akibat penyakit inimasih sangat
tinggi dan upaya untuk memeranginya harusdipercepat sesuai target
globalMillennium Development Goals 2015 (MDGs) (WHO, 2014).
Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh
Mycobacterium tuberculosis. Sekitar 75% pasien TB adalah kelompok usia yang
paling produktif secara ekonomis (15 – 50 tahun). Indonesia berada pada ranking
kelima negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Estimasi prevalensi TB semua
kasus adalah sebesar 660.000 (WHO, 2010) dan estimasi insiden berjumlah
430.000 kasus baru per tahun. Jumlah kematian akibat TB diperkirakan 61.000
kematian per tahunnya (Kemenkes, 2011).
Probabilitas terjadinya resistensi obat TB lebih tinggi di rumah sakit dan
sektor swasta yang belum terlibat dalam program pengendalian TB nasional
sebagai akibat dari tingginya ketidakpatuhan dan tingkat drop out pengobatan
karena tidak diterapkannya strategi DOTS. Proporsi kasus TB dan BTA negatif
sedikit meningkat dari 56% pada tahun 2008 menjadi 59% pada tahun 2009
2.1.2. Prevalensi TB
Hasil survei tingkat prevalensi TB paru dengan pemeriksaan bakteriologis
dari 177(165-189) per 100.000 penduduk (semua umur) pada tahun 1990, 160
(142-177) per penduduk 100.000(semua usia) pada tahun 2000 dan 119 (113-135)
per 100.000 penduduk usia ≥15 tahun pada tahun β010. Sesuai usia dan jumlah
TB paru, diperkirakan angka prevalensi keseluruhan per 100.000pendudukturun
dari 215 (200-230) pada tahun 1990 menjadi 108 (93-123) per 100.000penduduk
pada tahun 2010. Tingkat penurunan prevalensi ini mencapai 2,2% per tahun
antara tahun 1990 dan 2000, dan 4,7% per tahun antara tahun 2000 dan 2010.
Penurunan jumlah prevalensi TB ini diperkirakan cenderungkonservatif, karena
metode skrining ditingkatkan dari waktu ke waktu (misalnya, Sinar-Xtoraks yang
diambil pada tahun 2010 dibandingkan dengan penggunaan fluoroscopy kurang
sensitif pada tahun 2000) sehingga kasus lebih mungkin terdeteksi dalam survei
berturut-turut (WHO, 2011).
Menurut hasil Riskesdas 2013, prevalensi TB berdasarkan diagnosis
sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000
penduduk Indonesia terdapat 400orang yang didiagnosis kasus TB oleh
tenaga kesehatan. Penyakit TB paru dinyatakan pada responden untuk kurun
waktu ≤ 1 tahun berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh tenaga
kesehatan melalui pemeriksaan dahak, foto toraks atau keduanya. Hasil
Riskesdas 2013 tersebut tidak berbeda dengan Riskesdas 2007 yang
menghasilkan angka prevalensi TB paru 0,4%.Prevalensi TB paru berdasarkan
gejala batuk ≥ β minggu secara nasional sebesar γ,9% dan prevalensi TB paru
Data Kemenkes 2014 mencatat provinsi dengan prevalensi TB paru
berdasarkan diagnosis tertinggi yaitu Jawa Barat sebesar 0,7%, DKI Jakarta
dan Papua masing-masing sebesar 0,6%. Sedangkan Provinsi Riau, Lampung,
dan Bali merupakan provinsi dengan prevalensi TB paru
berdasarkandiagnosis terendah yaitu masing-masing sebesar 0,1%.Berdasarkan
karakteristik, semakin tinggi kelompok umur semakin tinggi pula prevalensi
TB paru, kecuali untuk kelompok umur 1-4 tahun dengan prevalensi yang
cukup tinggi (0,4%). Sebaliknya berdasarkan tingkat pendidikan, semakin
tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah prevalensi TB paru.Tabel berikut
ini memperlihatkan angka prevalensi TB paru berdasarkan diagnosis dan gejala
menurut karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan, dan tempat
tinggal.Prevalensi TB paru pada laki-laki sebesar 0,4%, lebih tinggi
dibandingkan dengan perempuan yang sebesar 0,3%. Prevalensi TB paru pada
penduduk di perkotaan sebesar 0,4%,lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk
di pedesaan yang sebesar 0,3% (Kemenkes, 2014).
Tidak tamat SD/MI 0,4 4,5 3,0
sebanyak 196.310kasus, menurun bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang
ditemukan tahun 2012 sebesar 202.301 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang
dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa
Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus baru BTA+ di tiga provinsi tersebut
hampir sebesar 40% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia.Menurut jenis
kelamin, kasus BTA+ pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu hampir
1,5 kali. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus BTA+
lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Disparitas paling
tinggi antara laki-laki dan perempuan terjadi di Sumatera Utara, kasus
padalaki-laki dua kali lipat dari kasus pada perempuan.Menurut kelompok umur, kasus
baru yang ditemukan paling banyak pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu
sebesar 21,40% diikuti kelompok umur 35-44 tahun sebesar 19,41% dan pada
kelompok umur 45-54 tahun sebesar 19,39% (Kemenkes, 2014).
2.1.3. Diagnosis TB paru
Diagnosis TB paru ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisis,
pemeriksaan bakteriologi, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya. Gejala
klinis tuberkulosis dibagi menjadi 2 golongan, yaitu gejala sistemik dan gejala
dan berat badan menurun. Pada paru akan timbul gejala respiratoriberupa batuk ≥
2 minggu, batuk darah, sesak napas dan nyeri dada (Kemenkes, 2011).
Kurangnyadiagnosisyang akuratdancepat menjadi hambatan utamauntuk
kemajuandalampenanggulangan TB. Lebih90% daribeban tuberkulosis seluruh
duniadi negara-negarapendapatan rendah dan menengahdimanadiagnosis TB
masihsangat bergantung padapemeriksaan mikroskopis sputumdanradiologidada.
Teknik iniseringtidak memuaskandantidak tersediasebagai titik kontak pertama
pasien dengansistem kesehatan. Kebutuhan akan kecepatan diagnosis yang efektif
sangat dibutuhkan untuk penanganan yang lebih cepatdi semua tingkatsistem
kesehatandandi masyarakat (Lawn and Zumla, 2011).
Diagnosis TB paru dapat ditegakkan berdasarkan gejala klinik, pemeriksaan
fisik/jasmani, pemeriksaan bakteriologik, radiologik dan pemeriksaan penunjang
lainnya. Pemeriksaan bakteriologik untuk menemukan kuman tuberkulosis
mempunyai arti yang sangat penting dalam menegakkan diagnosis. Bahan untuk
pemeriksaan bakteriologik ini dapat berasal dari dahak (sputum). Metode yang
sering dipakai adalah SPS (Sewaktu-Pagi Sewaktu), dengan cara pengambilan
dahak 3 kali, setiap pagi 3 hari berturut-turut. Pemeriksaan standar selanjutnya
ialah foto toraks PA dengan atau tanpa foto lateral. Pada pemeriksaan foto toraks,
diperlukan pertimbangan dokter dalam mendiagnosis tuberkulosis paru
Gambar 2.1 Alur diagnosisTBparu (Kemenkes, 2014) 2.1.3.1. Pemeriksaan BTA
Pemeriksaan mikroskopis BTA dari sputum memegang peran dalam
mendiagnosis awal dan pemantauan pengobatan tuberkulosis paru. Rangkaian
kegiatan yang baik diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat, mulai dari
cara pengumpulan sputum, pemilihan bahansputum yang akan diperiksa dan
pengolahan sediaan dibawah mikroskop. Teknik pewarnaan yang digunakan
adalah Ziehl Nielsen yang dapat mendeteksi BTA dengan menggunakan
mikroskop(Susanti,2013).
Mycobacterium tuberculosis pertama kali ditemukan oleh ilmuan Jerman
Robert Koch pada 24 Maret 1882. Mycobacterium tuberculosis merupakan Pemeriksaan dahak mikroskopis- Sewaktu, Pagi, sewaktu (SPS)
organisme komplek yang dapatmenyebabkan penyakit TBpada
manusia.Mycobacteriumtuberculosisbersifatpatogenintraselulerobligatyangdapat
menginfeksi beberapaspesies hewan, meskipunmanusiaadalah hostutama.
Karakteristik lain adalah aerobik, acid-fast, non-motil, tidak punya kapsul
dantidak membentuk sporabasil. Tumbuhpalingbaik dijaringandengan
oksigentinggi, seperti paru-paru. Dibandingkandengandinding selbakterilain,
dinding sel bakteri ini kaya lipid, serta kandungan asam mycolic relatif
tinggi(Lawn and Zumla, 2011).
Pemeriksaan sputum mikroskopis berfungsi untuk menegakkan diagnosis,
menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan
dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen
dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa
Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS) sebagai berikut:
S (sewaktu) : dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang berkunjung
pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk
mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua.
P (pagi) : dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah
bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas
fasilitas pelayanan kesehatan.
S (sewaktu) : dahak ketiga diambil setelah menyerahkan dahak pagi hari
kedua kunjungan dan dikumpulkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemeriksaan biakan dilanjutkan untuk menentukan apakah spesimen BTA
positif atau negatif dengan pewarnaan Ziehl Nielsen. Tuberkulosis BTA positif
BTA positif, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada
menunjukkan gambaran tuberkulosis, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif
dan biakan kuman TB positif dan 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif
setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA
negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT,
sedangkan kasus yang tidak memenuhi defenisi padaTB paru BTA positif
merupakan tuberkulosis paru BTA negatif dengan karakteristik : paling tidak 3
spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif, foto toraks abnormal sesuai dengan
gambaran tuberkulosis, tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non
OAT, dan ditentukan atau dipertimbangkan oleh dokter untuk diberi pengobatan
(Kemenkes, 2011).
Pembacaan hasil pemeriksaan sediaan dahak dilakukan dengan
menggunakan skala IUATLD (rekomendasi WHO) sebagai berikut :
Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, disebut negatif.
Ditemukan 1 – 9 BTA dalam 100 lapang pandang, ditulis jumlah kuman yang
ditemukan.
Ditmukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang, disebut + atau (1+).
Ditemukan 1 – 10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut ++ atau (2+),
minimal dibaca 50 lapang pandang.
Ditemukan > 10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut +++ atau (3+),
minimal dibaca 20 lapang pandang.
Bila ditemukan 1 – 3 BTA dalam 100 lapang pandang, pemeriksaan harus diulang
dilaporkan negatif. Bila ditemukan 4 – 9 BTA, dilaporkan positif (Kemenkes,
2011).
2.1.3.2. Foto toraks
Foto toraks merupakan pemeriksaan radiologi yangdilakukan untuk
menegakkan diagnosis TB. Foto paru standar pada orang dewasa adalah foto
posteroanterior (PA). Karena struktur yang membentuk pernapasan terletak di
dalam rongga toraks, sering diperlukan radiografi dalam kasus pulmonologi atau
respirologi sebagai fasilitas penunjang diagnostik. Indikasi untuk melakukan foto
toraks ada tiga :
Foto toraks rutin yang dilakukan pada seseorang yang mempunyai riwayat
kontak dengan pasienTB paru; pada general medical check up; dan pada
pemeriksaan berkala pada pekerja dalam lingkungan yang udaranya tidak
bersih (polusi).
Terdapat gejala yang menimbulkan kecurigaan adanya lesi dalam rongga
dada.
Terdapat gejala umum yang menimbulkan kecurigaan adanya lesi di rongga
dada, seperti demam yang tidak diketahui penyebabnya, juga untuk
mengetahui apakah tedapat metastasis keganasan ke paru.
Foto toraks pelengkap lateral kiri dibuat bersamaan dengan permintaan foto toraks
PA untuk mendapatkan apresiasi tiga dimensi. Foto lateral berguna untuk melihat
lesi kecil di meastinum dan massa dibagian anterior paru yang berdekatan dengan
2.2. Vitamin D
Vitamin adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu.
Vitamin dan metabolitnya sangat penting dalam jumlah besar pada proses fisiogis
tubuh, berperan sebagai hormon, antioksidan, regulator pertumbuhan jaringan,
perkembangan embrio dan metabolisme kalsium (Rosenberg, 2007). Vitamin D
telah dikenal berperan penting pada kesehatan tulang selama hampir satu abad.
Namun, peran lain vitamin D hanya mendapat perhatian selama dua dekade
terakhir, yang meliputi peran vitamin D dalam imunitas bawaan manusia .
Peran vitamin D sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap TB
melalui aksinya pada peningkatan fagositosis makrofag. Vitamin D baik secara
endogen diproduksi (vitamin D3) atau dikonsumsi (vitamin D2 atau vitamin D3),
harus diaktifkan untuk menghasilkan efek. Pada kasus TB yang menggunakan
obat anti tuberkulosis menjadikan TB resisten pada sebagian pasien, vitamin D
sebagai hormon imunomodulator dijadikan sebagai salah satu terapi
penyembuhannya (Sutaria, 2014).
2.2.1. Metabolit Vitamin D
Pada tahun1968 metabolit aktif pertama dari vitamin D diisolasi dalam
bentuk zat kimia murni yang dikenal dengan 25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D3).
Setelah itu 1,25(OH)D ditemukan sebagai bentuk aktif dari vitamin D (Feldman,
2011). Meskipun bentuk aktif vitamin D adalah 1,25(OH)D, namun tidak
dianggap sebagai biomarker yang baik karena mempunyai waktu paruh pendek.
Kadar 25(OH)D serum adalah biomarker status vitamin D yang sangat baik,
penelitian menunjukkan bahwa kadar 25(OH)D lebih stabil karena banyak beredar
Gambar 2.2Skema aktivasi molekul vitamin D3 (Kauffman, 2009) Prekursor 7-dehydrocholesterol dengaan sinarUV-B (290-315 nm) dari sinar
matahari diubahmenjadi vitaminD. Paparan vitamin D baikdari kulitatau yang
dimetabolismedi hatiberedarbanyak dalam bentuk utama, 25-hydroxyvitaminD di
darah. Penelitian tentang vitamin D banyak menggunakan metabolit 25 (OH)D
sebagai parameter yang diukur.Pengukuran kadar metabolit ini di Amerika pada
musim dingin mencapai 18ng/mL dan30ng/mLpada musim panas, sedangkan
Spektrum ultraviolet (UV) dari sinar matahari dengan panjang gelombang
290-310 nmyang terpapar pada kulit manusia mengkonversi 7-dehydrocholesterol
yang ada dalam lemak subkutan menjadi pro-vitamin D dan dilanjutkan
prosesisomerisasi termal menjadi vitamin D3 dan D2.Vitamin D3 dan D2 tidak
alami dijumpai dalam makanan yang dikonsumsi oleh sebagian besar orang-orang
dari sub-benua India. Pigmentasi kulit manusia oleh energi matahari berguna
untuk melindungi kita dari kanker yang secara bersamaan menghalangi
kemampuan kulit dalam mensintesis vitamin D. Proses hidroksilasi 7,8
dehidrokolesterol menjadi 25-hidroksivitamin D(25 [OH]) D3 oleh enzim 25
hidroksilaseterjadi di hati, kemudianmenjadi bentuk akhir 1,25-dihydroxyvitamin
D (1,25[OH]2D)oleh enzim mitokondria 1 α-hydroxylase CYP27B1, di proksimal
sel tubulus ginjal yang dikenal sebagai bentuk aktif dari vitamin D (Kochupillai,
2008).
Kebutuhan vitamin D berbeda untuk tiap orang berdasarkan usia dan kondisi
khusus sepeti kehamilan. Para ahli mengelompokkan status vitamin D dalam
tubuh berdasarkan kadar 25 hidroxivitamin D menjadi defisiensi, insufisiensi,
optimal dan toksik.
Tabel.2.2 Status vitamin D berdasarkan kadar 25(OH)D
No. Status Kadar Vitamin D
pengikatnya disebut Vitamin D Binding protein (DBP). Molekul DBP manusia
dikenal sebagai GC globulin.Hasil analisa PCR,DNA sequence GC globulin
adalah GC1 yang terletak pada region asam amino 416 dan GC2 pada region
asam amino 420. Afinitas DBP dalam mengikat molekul vitamin D berbeda
dimana afinitas 25(OH)2D> 1,25(OH)2D>vitamin D. Konsentrasi plasma DBP
adalah 20 kali lebih tinggi dari jumlah total metabolit vitamin D dan 99% adalah
protein terikat. Protein terikat vitamin D memiliki akses yang terbatas untuk
mengikat sel-sel sehingga peningkatan waktu paruh beredar ditingkatkan. Akibat
proses metabolisme sel,vitamin D menjadi kurang rentan terhadap metabolisme di
hati dibandingkan metabolisme di saluran empedu. Hal ini menyebakan vitamin D
dan metabolitnya memiliki waktu paruh sirkulasi yang tinggi. Hanya fraksi bebas
dari vitamin D yang dimetabolisme dan ketersediaan metabolit vitamin D
ditentukan oleh fraksi bebas sama halnya seperti hormon (Kochupillai, 2008).
Konsentrasi 1, 25 (OH)2 D bebas tetap konstan bahkan jumlah DBP berubah
sebagai akibat dari self regulatory dari metabolism vitamin D. Vitamin D aktif
diangkut dengan diikat reseptornya yang dimediasi brush border dari tubulus
ginjal proksimal sel yang berbelit-belit dan bukan oleh proses difusi-melalui
baso-lateral surface.Karena kekurangan DBP pengikatan secara bebas vitamin D
terjadi melalui endositosis untuk proses ini difasilitasi megalin (Cooke dalam
Kochupillai, 2008).
2.2.3. Peran Vitamin D dalam respon imunitas
Peran vitamin D khususnya metabolit vitamin D (1,25(OH)2D3) pada sistem
imun sudah diketahui lebih dari 20 tahun yang lalu. Beberapa hasil penelitian
proliferasi sel T; Bhallaet al, 1986 membuktikan metabolit aktif vitamin D ini
menurunkan ekspresi interleukin-2 (IL-2), interferon- (IFN- ) mRNA danRichel
et al, 1987 menurunkan protein di sel T; dan Meehan et al,1992 menurunkan
CD8+ T-cell-mediated cytotoxity. Efek dari metabolit aktif ini diawali dengan
keterlibatan Toll Like Receptor (TLR) dimana ekspresi reseptor vitamin D dan
CYP27B1 meningkat di efektor sel T. Peran vitamin D pada respon imun adaptif
memiliki efek menghambat diantaranya induksi sitokin IFN- sel Th-1 dihambat,
penurunan proliferasi sel B, penurunan differensiasi sel plasma dan penurunan
sekresi IgG. Efek pada innate imunity adalah sebagai stimulator yang memiliki
efek langsung pada peningkatan produksipeptida anti-bakteri oleh sel seperti
catelicidin dan defensin (Selvaraj, 2011).
Pasien TB memiliki kadar vitamin D yang rendah dalam tubuhnya bila
dibandingkan dengan populasi sehat. Penelitian tentang peran vitamin D terhadap
tuberkulosis sudah banyak dilakukan. Penelitian di Spanyol menyebutkan bahwa
orang yang lebih sering berhubungan dengan pasien TB memiliki kadar 25(OH)D
yang rendah dan diduga kadar 25(OH)D yang rendah ini disebabkan proses
imunitas tubuh dalam melawan tuberkulosis yang dibuktikan dengan konversi
tuberculin skin test (TST). Hal ini mendukung hipotesis bahwa status defisiensi
vitamin D adalah faktor resiko TB (Dini and Bianchi,2012). Sedangkan penelitian
di India membuktikan bahwa vitamin D berhubungan dengan kerentanan terhadap
TB dan resiko perkembangan infeksi menjadi penyakit TB (Salahuddin, 2013).
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Talat et al, di Pakistan dengan desain
kohort pada 129 pasien terbukti defisiensi vitamin D menambah resiko
Minyak hati ikan cod dan sinar matahari adalah sumber terbaik dari
25-hydroxyvitamin D yang bisa digunakan dalam penyembuhan TB. Penelitian yang
dilakukan di India oleh Salahuddin et al, membuktikan bahwa suplementasi
vitamin D dosis tinggi secara klinis menunjukkan perbaikan radiologi pada pasien
TB dan meningkatkan aktifitas sistem imun pasien dengan baseline kadar vitamin
D dalam serum (Salahuddin, 2013).
Gambar 2.3 Aktivasiinnate imunity dalam makrofag dimediasi vitamin D(Sutaria, 2014)
Vitamin D memiliki peran sebagai immunomodulator yang dimediasi oleh
reseptor vitamin D di monosit, makrofag dan limfosit (Deluca et al 2001 dan
Haussler et al, 1998 dalam Kang et al, 2011). Metabolit aktif
(1,25-dihydroxycholecalciferol) dari vitamin D(25-hydroxycholecalciferol) akan
mengaktifkan makrofag sedangkan defisiensi vitamin D menambah resiko
berikatan dengan reseptornya (RVD) dan dipengaruhi polimorfisme gen RVD
(Kang, et al 2011). Pada tahun 2006 Liu et al, membuktikan bahwaM.
tuberculosis oleh TLR 2/1 (Toll Like Receptor) meningkatkan ekspresi Reseptor
vitamin D (RVD) dan CYP 27B1 di dalam monosit. Sintesis
1,25-didydroksivitamin D yang ditangkap oleh RVD akan mengaktifkan antimikroba
intraseluler makrofag yang dimediasi oleh catelicidin. Selain itu makrofag juga
mengeluarkan peptide catelicidin manusia LL37 yang berperan dalam proses
innate imunity melawan M. tuberculosis(Chocano, 2009).
Gambar 2.4Efekvitamin D pad sel target (Valdivielso&Fernandez, 2006) Vitamin D merupakan pusat kendali tulang dan homeostasis kalsium.
vitamin D telah diduga berpengaruh pada penyakit lain selain tuberkulosis,
diantaranya penyakit kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Peran vitamin
D tidak terlepas dari polimorfisme gen RVD. Sebagian besar aktifitas metabolit
1,25(OH)2D3 dimediasi oleh reseptor afinitas tinggi yang bertindak sebagai
ligand-activated transcription factor. Langkah utama yang terlibat dalam
pengendalian gen transkripsi oleh reseptor vitamin D (RVD) termasuk ligand
binding, heterodimerization dengan retinoid x receptor (RXR),
bindingheterodimer untuk respon vitamin D elemen (RVDEs) dan perekrutan
protein nuclear lainnya ke kompleks prainisiasi transkripsi. Perubahan genetik
gen RVD dapat menyebabkan cacat penting aktifitas gen, mempengaruhi
metabolisme kalsium, proliferasi sel, fungsi kekebalan tubuh, dll, yang dapat
dijelaskan dengan perubahan urutan protein (Valdivielso and Fernandes, 2006).
2.3. Polimorfisme gen RVD
Reseptor vitamin D(RVD) secara sitogenetik terletak pada kromosom
12q13, gen ini terdapat di semua sel dan diekspresikan di sel monosit, limfosit T,
dan limfosit B. Reseptor vitamin D memiliki berat sekitar 48.3 KD dan terdiri dari
427 asam amino. Protein pada RVD terdiri dari Zink Finger DNA Binding dan
mengaktifkan proses transkripsi pada intisel. Fungsi lain dari Reseptor vitamin
D(RVD) secara klasik diketahui untuk meningkatkan penyerapan Ca dan mineral
PO4. Selain itu RVD juga memiliki fungsi yang baru yaitu memodulasi
makrofag.Reseptor vitamin D(RVD) merupakan bagian dari kelompok reseptor
steroid. Semua organ target memiliki Reseptor vitamin D (RVD) pada inti selnya.
Reseptor vitamin D memiliki afinitas yang besar terhadap calcitriol. Setelah
masuk kedalam sel dan berinteraksi dengan RVD membentuk 1,25(OH)2D-RVD
kompleks. Terdapat hubungan sebab akibat antara fungsi 1,25(OH)2D-RVD
kompleks dengan imunitas tubuh terhadap infeksi. Perubahan pada fungsi RVD
akibat mutasi mengakibatkan masuknya infeksi mikrobakteria atau infeksi virus
kedalam tubuh (Hatta, 2012 dalam Lestari, 2014).
Gambar 2.5Struktur gen reseptor vitamin D
Beberapa tahun lalu polimorfisme gen RVD telahdiindentifikasi dengan
analisa restriction fragment length polymorphism (RFLP) diantaranyaFokIpada
ekson II, TaqI pada ekson IX, BsmI dan ApaI terletak di intron antara ekson VIII
dan IX. Perubahan ekspresimRNA RVD diperlihatkan dengan varian genotip dari
gen RVD(Bid et al, 2009).Varian polimorfisme gen RVD dipengaruhi suku
berperan penting dalam hubungannya dengan kerentanan dan resistensi terhadap
TB yaitu FokI, BsmI, ApaI, dan TaqI (Martineau, 2011).
Gambar 2.6Polimorfisme gen reseptor vitamin D (Uitterlinden, 2004) Polimorfisme TaqIgen RVDgenotip tt memperlihatkan hubungannya
dengan penurunan risiko TB padapopulasi Gambia. Genotip ff dari polimorfisme
FokI dan defisiensi vitamin D memperlihatkan hubungan yang erat dengan TB
paru pada populasi India Gujarati yang tinggal di London. Penelitian sebelumnya
memperlihatkan bahwa genotip tt berhubungan dengan kerentanan dan genotip
TT berhubungan dengan resistensi terhadap TB paru pada wanita. Penelitian
terhadap TB pada laki-laki (Wilkinson, 2000 dalam Selvaraj, 2008).Pada populasi
Mesir polimorfisme FokIgen RVD tidak berhubungan dengan kerentanan
terhadap tuberkulosis (Mahmoud and Ali, 2014). Penelitian meta analisis pada
populasi eropa menunjukkan polimorfismeApaIalel homozigot dan polimorfisme
BsmIalel heterozigot berhubungan dengan peran protektif terhadap perkembangan
tuberkulosis (Chen,2013).
2.3.1. Polimorfisme ApaIgen RVD
Polimorfisme ApaIgen Reseptor vitamin Dterletak antara ekson 8 dan 9,
hasil dari perubahan T G (alel T ditandai „A‟ dan alel Gditandai „a‟). Karena
ApaI bersifat intronik, dianggap netral karena tidak mempengaruhi suatu fungsi
protein, akan tetapi mempengaruhi proses splicing (splicing errors) atau kendali
transkripsi (Simon et al, 2013). Genotip homozigot aa berhubungan dengan
resistensi terhadap perkembangan penyakit tuberkulosis dan AA berhubungan
dengan resistensi terhadap tuberkulosis laki-laki bukan wanita. Genotip
heterozigot Aa berhubungan dengan kerentanan terhadap tuberkulosis (Haddad,
2014).
Polimorfisme gen RVD bersifat etnis, hal ini dibuktikan pada penelitian
polimorfisme TaqI dan ApaIgen RVDpada populasi orang sehat di Syiria.
Hasilnya menunjukkan distribusi polimorfisme gen TaqI dan ApaI dipengaruhi
etnis, ini menjelaskan bahwa faktor etnis mempengaruhi kerentanan seseorang
terhadap penyakit (Haddad, 2014).
2.3.2. Peran polimorfisme ApaIgen RVDdengan infeksi tuberkulosis
Beberapa penelitian tentang hubungan polimorfisme gen RVD dengan TB
TB yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan karena etnis yang berbeda,
interaksi gen dengan lingkungan, dan variasi dalam faktor lingkungan antara
daerah geografis yang dipisahkan (Selvaraj, 2011).
Peran gen RVD yang dibuktikan secara signifikan berpengaruh terhadap
respon imun terhadap tuberkulosis dihubungkan dengan vitamin D. Pada beberapa
penelitian terdahulu polimorfisme gen ApaI dihubungkan dengan penyakit
tuberkulosis pada populasi India, Afrika Barat dan Afrika Selatan menunjukkan
genotip AA berhubungan dengan penurunan resiko terhadap tuberkulosis
(Areeshi, 2014). Pada populasi Eropa hasil penelitian meta analisis polimorfisme
gen ApaI varian alel homozigot (AA) menunjukkan peran protektif terhadap
perkembangan tuberkulosis (Chen, 2013). Polimorfisme gen ApaI pada populasi
Iran tidak menunjukkan hasil yang signifikan dihubungkan dengan kerentanan
terhadap tuberkulosis. Hasil analisa polimorfisme gen RVD dengan konsentrasi
vitamin D plasma menunjukkan hasil yang signifikan yaitu frekuensi genotip yang
tinggi terdapat pada konsentrasi vitamin D plasma rendah ≥ β0 ng/ml(Rashedi,
2015).
Penelitian kohort yang dilakukan Babb et al, 2007 pada pasien TB paru
pada populasi campuran Afrika Selatan untuk menentukan apakah polimorfisme
ApaI, FokI dan TaqIgen RVD berhubungan dengan kerentanan TB dan waktu
konversi sputum, serta melihat faktor klinis dengan demografi lainnya yang
mempengaruhi terhadap tingkat respon pengobatan. Selama perawatan, konversi
sputum lebih cepat pada genotip RVDApaI AA danTaqITT dan Tt dibandingkan
dengan genotip ApaI aa dan TaqI tt. Kategorisasi antara responden cepat dan
lebih cepat pada gen RVD ApaI alel A dan FokI alel f. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan individu untuk mengkonversi
sputum menjadi negatif saat terapi anti TB bisa secara independen diprediksi
dengan genotip RVD (Selvaraj, 2011).
Hasil analisis penelitian berdasarkan etnis,polimorfisme ApaI gen RVD
berbeda pada setiap populasi. Areeshi et al, 2014 dalam meta analisisnya
menyimpulkan bahwa polimorfisme ApaIgen RVD secara signifikan berhubungan
dengan penurunan resiko terhadap TB pada populasi India. Beberapa penelitian
lain yang dilakukan menunjukkan hasil polimorfismeApaIgen RVD pada populasi
Asia tidak berpengaruh terhadap kerentanan atau resistensi terhadap TB. Populasi
Afrika menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada kerentanan atau resistensi
terhadap TB antara bentuk alel heterozigot. Polimorfisme ApaIgen RVD pada
populasi Eropa dan Timur Tengah tidak diteliti (Sutaria, 2014).
2.4. Manfaat Pemberian Vitamin D pada Terapi TB paru
Vitamin D dengan metabolit aktif calcitriol diketahui mempunyai aktivitas
antibakteri, metabolit ini memodulasi respon pejamu tehadap infeksi
mikobakteria dengan cara menginduksi reactive nitrogen and oxygen
intermediates, menghambat enzim matrix metalloproteinase yang berperan dalam
proses pembentukan kavitas dengan upregulasi reseptor IL-10 sehingga
menginduksi sintesis IL-10, dan menginduksi aktivitas antimikroba cathelicidin
yang menginduksi autofagi. Calcitriol memodulasi respon imun dengan
mengikat reseptor vitamin D yang diekspresikan oleh antigen precenting cellsdan
limfosit untuk meregulasi proses transkripsi gen yang responsif terhadap vitamin
Manfaat vitamin D telah banyak diteliti dalam peranannya pada terapi TB.
Penelitian yang dilakukan adalah suplementasi vitamin D pada pasien TB baik
oral maupun injeksi dihubungkan dengan konversi sputum yang lebih cepat atau
perbaikan radiologi dibandingkan dengan yang tidak diberikan vitamin D. Efek
pemberian vitamin D terhadap terapi TB telah banyak diteliti diantaranya pada
populasi di Indonesiadiantaranya pasien TB di RS. Cipto Mangunkusumo
Jakarta(Nursyam, 2006), di kota Malang (Siswanto, 2009), dan di Wonosobo
(Pratiwi, 2013) dengan hasil terapi vitamin D terbukti secara signifikan
mempercepat konversi sputum. Penelitian yang sama pada populasi di luar negeri
diantaranya, populasi Arab Saudi(Salahuddin, 2013), dan di London (Coosens,
2012) dengan hasil penelitian suplementasi vitamin D menyebabkan pemulihan
radiologi dan mempercepat konversi sputum.
Manfaat suplementasi vitamin D pada pasien TB paru terhadap konversi
sputum dikaitkan dengan polimorfisme gen RVD telah dilakukan oleh Martineau
et al, 2011 pada populasi London dengan gen RVD FokI dan TaqI.Hasilnya
menyatakan bahwa suplmentasi vitamin D tidak mempengaruhi konversi sputum
secara signifikan pada populasi penelitian, tetapi pada pasien dengan
polimorfisme gen RVD TaqI genotip tt secara signifikan mempercepat konversi
sputum. Di Indonesia sendiri belum ada laporan penelitian polimorfisme gen
RVD ApaI pada pasien TB dewasa etnis Batakdikaitkan dengan pemberian
vitamin D.
Hasil penelitian polimorfisme gen reseptor vitamin D pada pasien
tuberkulosis paru menyatakan dipengaruhi oleh suku bangsa dan geografi. Suku
bangsa atau etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan
yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama,
bahasa, dan sebagainya. Perbedaan karakteristik membedakan satu etnis dan etnis
lain yang terlihat dari bahasa, sejarah, leluhur (nyata atau imajinasi), agama, gaya
berpakaian serta cara berdandan dan perhiasan. Frederich Barth (1988)
menambahkan istilah etnis menunjuk pada kelompok tertentu yang karena
kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut
terikat pada sistem nilai budayanya (Panjaitan, 2013).
Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tiap
suku memiliki budaya lokal yang menjadi cara hidup masyarakat setempat serta
identitas suku itu sendiri. Identitas suatu kelompok etnis dapat dilihat secara visual
dan non visual seperti budaya ritual adat, bahasa, dll. Suku Batak merupakan salah
satu dari ratusan kelompok etnis di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata “Batak” memiliki dua arti. Pertama berarti orang dari sub-etnis yang
tinggal di Sumatera Utara dan yang kedua berarti petualang atau pengembara. Suku
Batak terdiri dari enam kelompok etnis, yaitu suku Mandailing dan Angkola di bagian
selatan pulau, Toba di bagian tengah, Pakpak atau Dairi di bagian barat utara, Karo di
bagian utara dan Simalungun di bagian timur utara Mereka mempunyai sistem
sosial, religi, dan linguistik yang berbeda. Perbedaan linguistik paling jelas adalah
antara kelompok Karo dan Pakpak-Dairi-Dairi di utara dan barat--dengan
kelompok Toba, Mandailing, Angkola, dan Sipirok di Selatan. Simalungun berada
Kotamadya Medan sebagai ibukota Sumatera Utara memiliki letak yang
strategis. Kota ini dilalui Sungai Deli dan Sungai Babura. Keduanya merupakan
jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai.Kota ini merupakan wilayah yang
subur di wilayah dataran rendah timur dari propinsi Sumatera Utara dengan
ketinggian berada di 22,5 meter di bawah permukaan laut.Secara geografis,
Medan terletak pada 3,30°-3,43° LU dan 98,35°-98,44° BT dengan topografi
cenderung miring ke utara. Sebelah barat dan timur Kota Medan berbatasan
dengan Kabupaten Deli dan Serdang. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat
Malaka. Letak yang strategis ini menyebabkan Medan berkembang menjadi pintu
gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik itu domestik maupun
internasional. Kota Medan beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata
2000-2500 mm per tahun. Suhu udara di Kota Medan berada pada maksimum
32,4°C dan minimum 24°C. Kotamadya Medan memiliki 21 Kecamatan dan 158
Kelurahan (Medan, 2002).
Keterlibatan faktor genetik cukup berperan untuk timbulnya beberapa
penyakit seperti TB paru, tumor dan kanker. Faktor genetik yang terlibat
diantaranya adalah gen human leucocyte antigen (HLA) dan gen non HLA seperti
gen reseptor vitamin D. Beberapa penelitian yang dilakukan pada etnis Batak
diantaranya Munir, β006 “Peran Gen HLA-DQB1 pada Penyebab Kerentanan
Karsinoma Nasofaring Suku Batak”. Gen ini di turunkan secara heterozigot dan
bersifat kodominan. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan HLA tertentu akan
menghadapi risiko terjadinya penyakit tertentu. Untuk bangsa Indonesia yang
terdiri dari berbagai suku dan terpengaruh oleh berbagai bangsa akibat migrasi di
Penelitian lain Sinaga et al. 2014, yang melihat hubungan polimorfisme reseptor
vitamin D dengan kerentanan terhadap TB paru pada etnis Batak yaitu gen FokI
dan BsmI. Hasil penelitiannya didapatkan bahwa pada populasi Indonesia etnik
Batak, tidak ada hubungan antara polimorfisme FokI gen RVD dan kerentanan
terhadap TB paru. Pada polimorfisme BsmI gen RVD, genotip bb berhubungan
dengan penurunan risiko terhadap TB paru. Penelitian yang dilakukan pada etnis
Batak menunjukkan adanya karakteristik secara genetik yang berbeda dari etnis
2.6. Kerangka konsep
Keterangan :
= variabel bebas = variabel terikat = variabel antara
Gambar 2.8Skema kerangka konsep Pasien TB paru
etnis Batak
OAT + Vitamin D
OAT + Plasebo
Kecepatan konversi
sputum
Polimorfisme ApaI
gen RVD