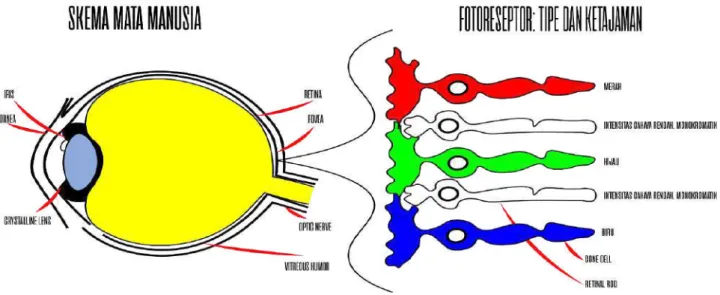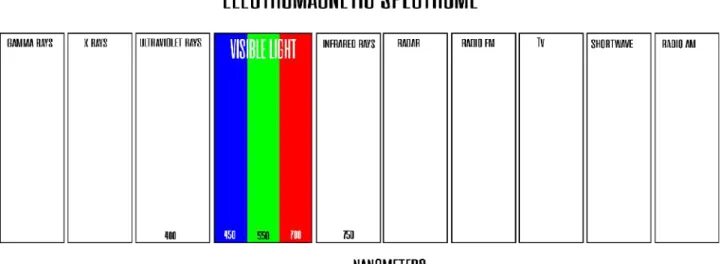Volume 12 No.2 - Juli 2021
Volume 12 Jurnal
IMAJI Nomor
2 Jakarta
2021Juli
ISSN
1907-3097 E-ISSN
2775-6033 DOI 10.52290
Diterbitkan oleh:
Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta
Panorama Mengamplifikasi Gagasan
melalui Media Audio-Visual
Jurnal
IMAJI Volume
12 Nomor
2 Jakarta
2021Juli
ISSN
1907-3097 E-ISSN
2775-6033 DOI 10.52290
Diterbitkan oleh:
Fakultas Film dan Televisi
Institut Kesenian Jakarta
Jurnal IMAJI
ISSN : 1907 - 3097 E-ISSN : 2775-6033 DOI : 10.52290
Volume 12 No.2 - 29 Juli 2021 49 halaman
Alamat Penyuntingan dan Tata Usaha Fakultas Film dan Televisi
Institut Kesenian Jakarta Jalan Cikini Raya 73 E-mail: [email protected]
Diterbitkan Oleh:
Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta
Dewan Redaksi
Editor
Reviewer
Copyeditor
Layout
Dr. Marselli Sumarno, M.Sn.
Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum.
M. Ariansah, M.Sn.
Dr. Bramantijo
Dr. Slamet Mangundiharjo Damas Cendekia, M.Sn.
Bawuk Respati, S.Sn., M.Si.
Muhammad Aditya Pratama, S.Sn.
Anies Wildani S.Sn
Jurnal IMAJI mewadahi kumpulan berbagai topik kajian film/audio visual yang berisi gagasan, penelitian, maupun pandangan kritis, segar dan inovatif mengenai perkembangan fenomenal perfilman khususnya dan audio visual pada umumnya.
Jurnal ini bertujuan untuk memberikan sumbangan penelitian terhadap medium film serta audio visual yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perfilman, termasuk fotografi, televisi dan media baru di Indonesia, agar menjadi unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan di dunia internasional.
IV | Volume 12 No.2 - Juli 2021
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film Maman Wijaya
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter Maria Hartiningsih
The Lady dan Wajah Politik Negara Myanmar Nia Sari
Antara Rusia dan Indonesia:
Petualangan film dan budaya dari Awal Uzhara Gilang Bayu Santoso
Hiburan Film yang Mengeksploitasi Kesedihan Sebagai Sarana Eskapisme dalam Realitas Kehidupan Manusia Suryana Paramitha
Warna dalam Dunia Visual Dedih Nur Fajar Paksi Wawancara: Joko Anwar
54 - 61
62 - 70
72 - 76
78 - 82
84 - 89
90 - 97
99 - 103
V | Volume 12 No.2 - Juli 2021
Daftar Isi
Author Guidelines Jurnal IMAJI
Film, Fotografi, Televisi dan Media Baru
Naskah
Naskah harus merupakan artikel penelitian asli yang cukup memberikan kontribusi baru untuk film, fotografi, televisi, dan media baru. Penulis diminta untuk mengirimkan makalah secara elektronik dengan menggunakan prosedur pengiriman Jurnal IMAJI: film, fotografi, televisi, dan media baru. Penulis terkait juga harus memberikan pernyataan bahwa naskah tersebut tidak sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan di tempat lain. Editor akan mengabaikan kiriman yang tidak mengikuti prosedur ini.
Struktur Naskah
Judul. Judul artikel harus singkat, jelas dan informatif, tidak lebih dari 12-15 kata.
Nama penulis dan institusi. Nama penulis harus disertai dengan institusi penulis dan alamat email. Untuk makalah bersama, salah satu penulis diberitahukan kepada penulis terkait.
Abstrak dan kata kunci. Abstrak harus kurang dari 150-200 kata. Harap berikan abstrak dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kata kunci harus terdiri dari 3 sampai 5 kata atau frase, ditulis menurut abjad.
Pengantar. Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat dan tujuan pembuatan naskah. Yang penting juga harus menunjukan signifikansi dan kebaruan penelitian. (15-20% dari total panjang artikel).
Pembahasan. Bagian ini menjelaskan alat analisis yang berisi deskripsi, teknik pengumpulan data, analisis data serta pemaparan analisis data (40 – 60% total panjang artikel).
Kesimpulan. Bagian ini menyimpulkan dan memberikan hasil temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan.
Daftar Pustaka. Bagian ini memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Daftar rujukan ini minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan harus merupakan sumber primer (artikel, buku, laporan penelitian atau jenis publikasi lain yang dirujuk dalam badan manuskrip.
Format Penulisan Umum
Naskah dibuat dalam format kertas A4, (double-sided, and single line spacing).
Paragraf baru harus dimulai 0.5 mm dari margin kiri, menggunakan jenis font Times-New—Romans ukuran 12.
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
VI | Volume 12 No.2 - Juli 2021
Naskah harus terdiri dari 10 sampai 25 Halaman (3000-6000 kata).
Margin atas dan bawah 1,5 dan 0,8 inci.
Judul ditulis dengan huruf kapital hanya pada kata pertama atau nama khusus (contoh: nama lokasi), ukuran huruf 14, posisi tengah.
Sub judul ditulis dengan gaya UPPERCASE BOLD berukuran 11 font, dimulai dari margin kiri.
Sub judul, (jika ada), ditulis dengan huruf kapital hanya pada kata pertama atau nama khusus. Harus dimulai dari margin kiri.
Sub dari sub judul, (jika ada), ditulis dengan huruf kapital hanya di awal setiap kata kecuali kata penghubung, semuanya dicetak miring. Harus dimulai dari margin kiri.
Referensi harus dari publikasi sepuluh tahun terakhir (> 80%), kecuali untuk referensi kunci (80%). Merujuk ke buku teks apa pun harus diminimalkan (<20%).
Sitasi
Sitasi di badan teks harus menggunakan nama keluarga dan halaman yang dikutip.
Contoh:
Yang dimaksud dengan teori film adalah ... (Bordwell 5).
Penulis disarankan untuk menggunakan software Mendeley Reference.
Daftar Pustaka
Naskah diharapkan melibatkan sekitar 10 – 20 referensi utama dan terbaru untuk menegaskan kontribusi berkualitas tinggi untuk pengembangan pengetahuan.
Kutipan dan referensi harus mengikuti gaya MLA (Modern Language Association of America) Referensi harus mencakup hanya karya yang dikutip di dalam teks naskah. Mengonsultasikan manual gaya MLA (https://style.mla.org/) sangat disarankan untuk menyelesaikan pengirimaan naskah. Silahkan gunakan alat referensi (Mendeley)!
Bagaimana mengirim naskah
Naskah dalam Microsoft word harus dikirim melalui Online di Situs Web kami atau Offline melalui alamat email kami [email protected].
Mengirimkan biodata singkat yang memuat nama lengkap, gelar akademik, institusi, telepon/nomor handphone, dan lain-lain harus dicantumkan pada kolom data pada saat mendaftar online pada pengajuan website kami.
VII | Volume 12 No.2 - Juli 2021
Keputusan akhir
Dengan mempertimbangkan hasil dari proses peer-reviewing, keputusan tentang penerimaan setiap naskah untuk publikasi akan diberitahukan kepada penulis melalui sistem situs web dan email kami dalam kesimpulan alternatif berikut:
Diterima tanpa revisi, atau Diterima dengan revisi kecil, atau Diterima dengan revisi besar, atau Ditolak.
Pemberitahuan Hak Cipta
Hak cipta artikel yang diterima akan dilimpahkan pada jurnal sebagai penerbit jurnal. Hak cipta dimaksud meliputi hak untuk mempublikasikan artikel dalam berbagai bentuk (termasuk cetakan ulang). Jurnal memiliki hak penerbitan atas artikel yang diterbitkan.
Penulis diizinkan untuk menyebarkan artikel yang telah diterbitkan dengan membagikan link / DOI artikel tersebut di jurnal. Penulis diperbolehkan menggunakan artikelnya untuk tujuan hukum yang dianggap perlu tanpa izin tertulis dari jurnal dengan pemberitahuan publikasi awal jurnal ini.
Pernyataan Privasi
Nama dan alamat email yang dimasukkan dalam situs jurnal ini akan digunakan secara eksklusif untuk tujuan jurnal ini dan tidak akan tersedia untuk tujuan lain atau pihak lain mana pun.
Biaya Penulis
Jurnal ini membebankan biaya penulis berikut.
Pengiriman Artikel : 0,00 (IDR) Publikasi Artikel : 0,00 (IDR)
VIII | Volume 12 No.2 - Juli 2021
Riwayat Singkat Penulis
Maman Wijaya
Doktor lulusan Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Indonesia.
Maria Hartiningsih
Wartawan senior harian Kompas dan penerima penghargaan Yap Thiam Hien untuk tahun 2003.
N ia Sari
Dosen di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
Gilang Bayu Santoso
Sutradara film dokumenter dan lulusan ISBI Bandung Jurusan Tv dan Film Fakultas Media dan Budaya.
Suryana Paramitha
Dosen di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
Dedih Nur Fajar Paksi
Dosen di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
IX | Volume 12 No.2 - Juli 2021
Menjelang terbitnya jurnal IMAJI wajah baru edisi Juli 2021 ini, situasi pandemi masih meruyak di mana-mana, termasuk di Indonesia. Apa boleh buat, tugas penerbitan jurnal harus terus berjalan.
Topik-topiknya cukup menarik. Antara lain suatu pengamatan atas pengalaman horor oleh wanita berkebangsaan Belanda yang ikut terseret di zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Wanita itu, Jan Ruff, ikut menjadi budak pemuas nafsu seks para prajurit Jepang. Namun baru setelah 50 tahun kemudian, jadi di pertengahan tahun 90an, pengakuannya diterbitkan dalam bentuk buku tebal dan sebuah film dokumenter. Testimoni Jan Ruff menggedor rasa kemanusiaan dan baik media buku maupun film dokumenter itu telah membawakan perannya dengan baik.
Di awal tahun 60an, Presiden Soekarno mengirim seratusan lebih orang muda Indonesia untuk mendalami kesenian di berbagai bidang di Eropa, terutama ke Rusia. Pecah tragedi nasional 1965 dan nasib kebanyakan kaum muda itu jadi terkatung-katung. Apakah terus menetap di Eropa atau pulang ke Indonesia namun dengan resiko akan dipenjarakan, mengingat Presiden Soekarno punya kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia dan Rusia sebagai yang sudah lama menggenggam ideologi komhnisme.
Salah satu orang muda itu adalah Awal Azhura.
Setelah perkembangan teknologi digital merasuk ke jantung masyarakat di mana-mana, lahir persoalan propaganda dan perkara budaya itu sendiri.
Persoalan-persoalan budaya menyeruak dan berebut perhatian melalui berbagai tayangan audio visual, yang intinya adalah tarung propaganda.
Suara pertarungan itu riuh rendah, bersifat mencerahkan atau malah berupa disinformasi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mengelola representasinya kepada masyarakat luas?
Ada rubrik baru yang kami tampilkan, yaitu rubrik wawancara yang untuk perdana kami fokuskan pada sosok sutradara berbakat Joko Anwar. Jawaban-jawabannya masih tergolong ringkas-ringkas sehingga lain kesempatan kepada para pembuat film masih dimungkinkan untuk menggali pemikiran-pemikiran personal mereka mengenai film.
Itulah antara lain tiga topik yang ada dalam edisi jurnal IMAJI kali ini.
Selamat membaca dan salam sehat Corona.
Dr. Marselli Sumarno M.Sn
Kata Pengantar
Panorama Mengamplifikasi Gagasan melalui Media Audio-Visual
X | Volume 12 No.2 - Juli 2021
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film
Maman Wijaya Doktor Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: [email protected]
ABSTRACT
Representing cultural and ideological propaganda has a higher level of complexity than simply representing informative messages. This article aims to examine the consequences of cultural and ideological propaganda is represented in films. The discussion is qualitative using data from several film articles plus the author's experience in interacting with filmmakers and the experience of watching films with the community. The study is more focused on ordinary viewers who do not know the theory of Semiotics as the audience in general.
The results concluded that there were five consequences, namely: (1) the emergence of audience perceptions that were different from what was expected; (2) the emergence of differences in audience behavior as a result of different interpretations of the representations they receive; (3) Third, the impact of communication, namely the message represented in the film is irreversible; (4) the emergence of the assumption that in the process of making films, there are ethical problems; and (5) the impression of the totality of the film's contents is blurred due to the double message represented.
Keywords: Representation, Propaganda, Culture, Ideology, Film
ABSTRAK
Merepresentasikan propaganda budaya dan ideologi memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar merepresentasikan pesan informatif. Artikel ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi dari propaganda budaya dan ideologi jika direpresentasikan di dalam film.
Pembahasannya bersifat kualitatif menggunakan data dari beberapa artikel film ditambah pengalaman Penulis dalam berinteraksi dengan para pembuat film, serta pengalaman menonton film bersama masyarakat. Kajiannya lebih dititikberatkan pada perspektif penonton awam yang tidak mengetahui teori semiotika. Hasilnya disimpulkan melalui lima konsekuensi, yaitu: (1) munculnya persepsi penonton yang berbeda dari yang diharapkan; (2) munculnya perbedaan perilaku penonton akibat dari perbedaan interpretasi terhadap representasi yang diterimanya; (3) dampak dari sifat komunikasi, yaitu pesan yang direpresentasikan dalam film bersifat irreversible; (4) munculnya anggapan bahwa dalam proses pembuatan film ada problem etika; dan (5) kesan totalitas isi film menjadi kabur akibat pesan ganda yang direpresentasikan.
Kata Kunci: Representasi, Propaganda, Budaya, Ideologi, Film
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 54
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 55
PENDAHULUAN
Film merupakan karya seni dan budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi. Dari seluruh referensi yang tersedia, tidak ada satu pun penulis yang menolak pandangan bahwa film merupakan sarana efektif untuk menyampaikan pesan. Bahkan lebih dari itu, film bisa digunakan juga untuk propaganda (Mirnawati 1), (Asri 6). Propaganda adalah penyampaian pesan berupa ajakan atau imbauan keras. Dody Pradana Eryanto mengistilahkan propaganda sebagai upaya sengaja dan sistematis untuk mengendalikan opini publik sesuai keinginan pemberi propaganda (Eryanto 3).
Karena peran dan kemampuannya itulah maka film banyak digunakan untuk propaganda budaya maupun propaganda ideologi oleh sejumlah pembuat film. Film Transformers (2007) atau Rambo (1982), misalnya, menggambarkan secara masif, sebagai bagian dari propaganda budaya, atau bisa juga propaganda ideologi dalam merepresentasikan bagaimana perkasanya negara Amerika Serikat (Eryanto 5). Ada juga Film Merah Putih (2009) yang merepresentasikan pentingnya cinta tanah air yang bisa dikatakan sebagai propaganda ideologi bagi Bangsa Indonesia (Akbar 6). Selain itu juga ada film yang di dalamnya bisa merepsentasikan perjuangan politik (Mirnawati 4), atau perjuangan budaya dan ideologi seperti pada film Sultan Agung (2018) (Prasetya 3–4).
Representasi adalah proses menghadirkan pesan- pesan yang akan disampaikan kepada khalayak.
Pengemasan pesan-pesan tersebut biasanya dalam tanda-tanda seperti gambar, suara, warna, maupun gerakan yang ditampilkan di dalam film sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai (Manesah 4–5). Pemilihan bentuk representasi akan menentukan efektif atau tidaknya penyampaian pesan tersebut.
Tanda-tanda yang direpresentasikan sebagai makna dari pesan itu selanjutnya dibaca oleh penerima pesan, yang kemudian oleh penerima pesan, yang dalam hal ini adalah penonton, bisa dibaca dengan berbagai cara. Pada kajian film, tata cara pembacaan tanda itu umumnya mengadopsi ilmu semiotika. Semiotika adalah
ilmu membaca tanda (Ambarini & Umaya 32–
34). Ada beberapa teori yang biasa digunakan dalam telaah semiotika film, di antaranya adalah teori Roland Barthes (Agustina 15) dan John Fiske (Fatima 9).
Permasalahannya adalah, apakah para penonton film mengetahui ilmu semiotika dan menggunakannya dalam membaca tanda-tanda dari film yang ditontonnya? Jika tidak, apa yang terjadi? Apakah penonton bisa memahami arti tanda-tanda itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuatnya? Atau, penonton bahkan memiliki arti lain dari tanda yang dibacanya itu?
Apa akibatnya jika hal itu terjadi? Lalu, bagaimana mengatasinya, terutama bagi film yang ditujukan untuk propaganda budaya dan ideologi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat menarik untuk ditelaah dan didiskusikan secara mendalam melalui pemahaman yang komprehensif. Namun demikian, di dalam artikel ini sajiannya terbatas pada deskripsi kualitatif berdasarkan kajian teori dari beberapa artikel film terkait representasi, propaganda budaya dan ideologi, serta berdasarkan latar belakang pengalaman Penulis sebagai penonton awam. Tujuannya adalah mencari tahu duduk persoalan representasi propaganda budaya dan ideologi dalam film.
Penelitian mengenai representasi budaya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya menyimpulkan bahwa budaya, diplomasi budaya, dan nilai-nilai kebangsaan, menurut versi peneliti tersebut umumnya sudah digambarkan secara baik (Christina & Yudhi, 2017), (Rahardjo, 2016), (Puspasari 2019), (Manesah 2016), dan (Fatima 2019). Namun tidak secara tegas hal itu bisa dikategorikan sebagai propaganda budaya atau tidak.
Begitu juga tentang representasi paham ideologi, beberapa kajian yang telah dilakukan peneliti terdahulu hasilnya menunjukan bahwa resepsentasi paham ideologi dalam film yang ditelaahnya cukup memadai (Eryanto 2015), (Akbar 2017), dan (Mirnawati 2019). Akan tetapi, representasi ideologi tersebut belum bisa dikatakan sepenuhnya sebagai propaganda, karena masih bisa diperdebatkan mengenai efektivitasnya.
Kajian-kajian tersebut, baik mengenai representasi budaya maupun paham ideologi, adalah pendapat versi peneliti, dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan dasar teori dari ilmu semiotika. Sebagai contoh, Puspasari di tahun 2019, meneliti tentang representasi budaya dalam film Salawaku (2016) dengan menggunakan teknik analisis menurut Edgar H.
Schein (Puspasari 5). Contoh lainnya, analisis representasi perilaku masyarakat dalam film yang dilakukan oleh Rionaldo Herwento di tahun 2014 juga menggunakan dasar teori, yaitu semiotika model Roland Barthes (Herwendo 5). Lalu, bagaimana menurut penonton awam yang tidak mengetahui ilmu semiotika mengenai representasi propaganda budaya dan ideologi dalam film yang ditontonnya?
Berdasarkan uraian di atas, analisis kajian dalam artikel ini akan sedikit ditambahkan mengenai diskusi versi penonton yang bukan ahli teori semiotika sebagaimana latar belakang yang Penulis miliki. Pembahasannya fokus pada masalah konsekuensi representasi perjuangan, propaganda budaya, dan propaganda ideologi dengan pengkajian yang lebih dititikberatkan pada perspektif penonton awam sehingga interpretasi terhadap isi film itu cenderung bersifat subyektif.
Konsekuensi Representasi Perjuangan di dalam Film
Perjuangan bisa didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, perjuangan itu bentuknya bisa bermacam-macam, begitu juga dengan tingkatannya. Siswa berjuang untuk memperoleh nilai yang bagus. Lulusan sarjana berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Perantau melakukan perjuangan untuk mempertahankan hidup.
Atau, para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan ideologi dan keyakinan. Tingkatan perjuangan yang dimaksud adalah urutan kerumitan dan dampak yang ditimbulkan dari perjuangan tersebut. Semakin sulit perjuangan itu dilakukan dan semakin luas dampaknya bagi kehidupan, maka tingkatan perjuangan itu semakin tinggi.
Di dalam film, urutan tingkat perjuangan tersebut juga berlaku. Pertama, ada film yang digambarkan sebagai perjuangan untuk mencari kehidupan individu semata agar menjadi lebih baik, seperti digambarkan oleh Manesah tentang telaah film Anak Sasada (2011) (Manesah 1).
Kedua, ada perjuangan untuk mempertahankan hak-hak sipil seperti perjuangan kesetaraan perempuan, sebagaimana ulasan yang diuraikan oleh Christina untuk film Kartini (Christina
& Yudhi 6). Gambaran yang kedua ini tingkat perjuangannya lebih rumit dari yang pertama.
Ketiga, ada pula film yang digambarkan sebagai perjuangan level yang lebih tinggi lagi dengan dampak perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan ideologi dan kepentingan bangsa-bangsa pada umumnya, antara lain seperti digambarkan dalam hasil kajian tentang perjuangan ideologi yang ditulis oleh Prasetya mengenai film Sultan Agung (2018) (Prasetya 1), propaganda politik karya Mirnawati (Mirnawati 1), dan problem etika karya Budi Wibawa (Wibawa 1).
Merepresentasikan perjuangan di dalam film memiliki sebuah konsekuensi. Perjuangan yang kompleksitasnya semakin tinggi akan semakin rumit juga cara merepresentasikannya.
Akibatnya, kemungkinan munculnya perbedaan makna pesan antara yang direpresentasikan oleh pembuat film dengan yang diinterpretasikan oleh penonton akan semakin besar, sehingga tujuan dari pembuatan film ada kemungkinan tidak tercapai. Berdasarkan pengalaman Penulis selama berinteraksi dengan para pembuat film, hal ini jarang menjadi perhatian khusus mereka.
Konsekuensi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film
Pengertian propaganda dalam kehidupan sehari- hari mirip dengan pengertian propaganda di dalam film, yaitu sebuah upaya yang sistematis untuk memengaruhi pihak lain agar mengikuti arahan sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diinginkan oleh pemberi propaganda. Mahmudi menjelaskan bahwa dalam propaganda terdapat unsur-unsur seperti memengaruhi opini publik,
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 56
memanipulasi emosi, dan menggalang dukungan atau penolakan (Mahmudi 4).
Sementara, yang dimaksud dengan upaya sistematis dalam propaganda, adalah seperangkat teknik yang digunakan untuk menciptakan ketiga unsur seperti memengaruhi opini publik, memanipulasi emosi, dan menggalang dukungan atau penolakan (Mahmudi 4). Sebagai contoh, Mirnawati, dalam membedah representasi propaganda di dalam film, menggunakan tujuh teknik seperti yang sudah biasa dilakukan oleh para peneliti film propaganda pada umumnya, yaitu Name Calling, Glittering Generalities, Transfer, Testimonial, Palin Folks, Card Stacking, dan Band Wagon (Mirnawati 5). Ketujuh teknik ini sesungguhnya adalah senjata bagi para pembuat film propaganda. Dengan senjata tersebut para pembuat film propaganda melakukan ikhtiar untuk menciptakan ruang-ruang dialog di alam bawah sadar para penonton agar pesan-pesan yang disampaikan benar-benar bisa dicerna secara bulat dan utuh.
Propaganda melalui film diuntungkan, sebab selain dengan tujuh teknik tadi yang sepenuhnya ada di tangan pembuat film, ruang dialog juga bisa dibangun melalui frame film yang mampu membatasi lingkup pandangan penonton, dan dengan perpaduan antara unsur naratif dengan unsur sinematik. Frame itulah yang membuat film berbeda dengan realitas kehidupan, yang bisa memisahkan logika berpikir antara filmic space dengan reality space (Pratiwi 6).
Sebaliknya, perpaduan yang sempurna antara unsur naratif dengan unsur sinematik dapat membuat film menjadi sebuah reality space (Elizabeth 13). Namun jika perpaduannya tidak sempurna, maka representasi propaganda akan gagal. Pratiwi yang mengkaji film Roma dengan studi kasus terkait deep focus dan long take menyatakan bahwa film Roma disimpulkan tidak berhasil dalam mengangkat gagasan realisme, sebab agenda terselubung dalam film Roma (2018) yang dikemas dengan teknik sinematik yang sarat dengan estetika dan ditangani dengan cukup baik itu tidak disertai muatan ideologi yang pas dalam unsur naratifnya (Pratiwi 11).
Kegagalan dalam merepresentasikan propaganda dapat berakibat pada kegagalan misi propaganda itu sendiri. Khusus untuk propaganda budaya dan ideologi, - atau bila boleh ditambah, misalnya, dengan keyakinan pada agama tertentu – konsekuensinya akan semakin berat dan akan sangat sensitif. Jadi, representasi propaganda itu memiliki sejumlah konsekuensi. Macam-macam konsekuensi itu di antaranya adalah, pertama, mengenai munculnya perbedaan persepsi. Saat ingin membentuk persepsi penonton melalui pemanipulasian kognisi, ternyata penonton kemudian memiliki persepsi lain yang berbeda.
Bahkan di antara penonton itu sendiri pun bisa saja satu sama lain terjadi perbedaan persepsi dari makna konotasi yang diterima oleh mereka.
Sebab, makna konotasi bekerja pada ranah subjektif, dan penonton hanya memainkan makna konotasi, bukan makna denotasi (Rahardjo 6–7).
Akibatnya, film akan menjadi bersifat debatable, sangat bisa diperdebatkan.
Repotnya lagi, pembuat film tidak bisa melakukan klarifikasi pada setiap saat di mana film itu diputar.
Tidak akan ada juga pihak yang bisa membantu memberikan penjelasan tambahan pada saat itu mengenai persepsi yang seharusnya dipahami penonton. Contoh kemunculan persepsi yang berbeda itu digambarkan oleh Galeh Eka Prasetya yang mengkaji film Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, dan Cinta (2018) dalam artikelnya tentang peran konflik dalam membangun karakter tokoh utama (Prasetya 2). Jika melihat judul filmnya, tokoh utama yang diusung, dibangun, dan dipandang sebagai pahlawan itu adalah Sultan Agung, bukan yang lain. Namun Prasetya dalam analisisnya menyimpulkan berbeda. Menurutnya, karakter pahlawan bukan hanya milik Sultan Agung, tetapi juga milik tokoh lain seperti tokoh Lembayung dan tokoh Kelana. Dari konflik-konflik yang dibangun itu membuat Prasetya mendapat kesan bahwa Lembayung dan Kelana memiliki karakter kuat sebagai pahlawan dan penolong, bukan hanya Sultan Agung (Prasetya 25). Dalam tulisan Prasetya itu tidak disebutkan apakah Prasetya mengkonfirmasi hasil pengamatannya itu kepada pembuat film Sultan Agung atau tidak.
Terkait film Sultan Agung (2018) ini Penulis juga memiliki pengalaman yang sama dalam
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 57
hal kemunculan persepsi yang berbeda dari representasi bagian film itu, yang kebetulan Penulis mendapat kesempatan turut serta memberikan review film tersebut bersama produser, sutradara dan seluruh kru, yang durasi filmnya waktu itu masih tiga jam lebih. Persepsi Penulis di antaranya berkaitan dengan peristiwa ketika Sultang Agung berdialog keras dengan Tumenggung Notoprojo.
Pada dialog dalam film tersebut, menurut Sultan Agung, VOC itu penjajah, tidak boleh diajak kerjasama dan tidak boleh ada negosiasi, melainkan harus diperangi. Bangsa Mataram harus melawan. Sementara Tumenggung Notoprojo berpendapat lain. Menurut Tumenggung Notoprojo, jika VOC menawarkan bantuan untuk membangunkan jembatan, jalan, lumbung-lumbung padi, dan rakyat Mataram bisa menikmatinya, mengapa tidak. Sultan Agung murka, lalu mencekik Tumenggung Notoprojo sambil membentak.
Dialog pada bagian itu menurut Penulis topiknya sangatlah berat. Itu menyangkut ideologi politik sebuah bangsa. Lagi pula dialognya direpresentasikan dengan relasi kuasa yang tidak berimbang. Sultan Agung itu raja, Notoprojo sebatas Tumenggung. Sudah bisa diduga, yang menang perdebatan adalah raja. Hal itu bisa salah interpretasi. Pratiwi berpendapat bahwa representasi relasi kuasa bisa membuat tokoh terombang-ambing menjadi tidak jelas posisinya (Pratiwi 11). Mataram kemudian berperang melawan VOC, dan Mataram kalah. Pada bagian akhir film ditunjukkan sejumlah perempuan yang kehilangan suaminya, serta anak-anak kecil yang kehilangan orangtuanya karena gugur di medan perang. Sultan agung sendiri akhirnya kembali merawat padepokan yang mengurusi seni dan budaya.
Penulis memiliki persepsi bahwa akibat keputusan Sultang Agung mengambil jalan ideologi politik yang ditentukan oleh karena kekuasaannya itu berakibat pada kondisi kehidupan kaum perempuan dan anak-anak di Mataran, termasuk pada kehidupan Sultan Agung itu sendiri.
Bila persepsi Penulis itu benar, maka Penulis menganggap film ini merupakan film propaganda ideologi agar tidak mengambil keputusan seperti
Sultan Agung. Penulis kemudian bertanya kepada sutradara apakah yang Penulis persepsikan sesuai dengan pesan yang diusung oleh film yang dibuatnya itu. Jawabannya ternyata persepsi Penulis keliru. Adegan-adegan dalam film seperti diuraikan di atas, tidak dimaksudkan untuk propaganda sebagaimana yang Penulis tangkap.
Konsekuensi representasi propaganda yang kedua adalah, berupa konsekuensi lanjutan dari akibat perbedaan interpretasi terhadap pesan yang diterima penonton, yaitu perubahan perilaku.
Ketika pembuat film sebagai pengemban misi propaganda mengarahkan perilaku penonton dengan tujuh teknik yang ada atau dengan menampilkan fakta-fakta tertentu saja yang bisa memperkuat arah agar memiliki perilaku tertentu, penonton justru berperilaku sebaliknya dari yang diinginkan. Dampaknya bisa berupa sikap antipati, kecaman, penentangan, atau perlawanan terhadap misi yang diemban dalam propaganda, baik terhadap bagian tertentu maupun keseluruhan isi film. Kejadian seperti itu sering terjadi terhadap film Indonesia, seperti terhadap film Lima (2018), Kucumbu Tubuh Indahku (2018), atau bahkan pada film anak, yaitu Naura
& Geng Juara (2017). Mengenai “menampilkan fakta-fakta tertentu saja”, dalam misi propaganda itu bisa dibenarkan, sepanjang faktanya benar dan mampu memperkuat misi propaganda. Mahmudi mengemukakan bahwa pada level representasi untuk propaganda, konteks sejarah yang tidak memperkuat atau malah mengurangi misi, tidak perlu ditampilkan (Mahmudi 13).
Konsekuensi ketiga, yaitu dampak dari sifat komunikasi. Karena film merupakan media komunikasi (Herwendo 2), dan komunikasi itu bersifat irreversible (Mukarom 45) maka konsekuensinya adalah pesan-pesan yang direpresentasikan di dalam film itu bersifat irreversible. Artinya, sekali pesan-pesan itu tersampaikan melalui film kepada penonton, maka pesan-pesan tersebut tidak bisa ditarik kembali. Akibatnya apa yang sudah terlanjur memengaruhi perilaku penonton tidak bisa dikembalikan lagi ke keadaan semula, walaupun, umpamanya, pembuat film tersebut meralatnya.
Dampak ini pengaruhnya bisa lebih jauh dari sekadar perbedaan persepsi atau perubahan perilaku, sebab bersifat massal.
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 58
Keempat, konsekuensi problem etika. Hal ini terjadi manakala propaganda terlalu dipaksakan oleh si pembuat dengan cara yang sporadis. Budi Wibawa menyebutnya sebagai “menghalalkan”
pemanipulasian (Wibawa 39). Hal itu bisa merusak tatanan kebebasan berekspresi. Problem etika tersebut bisa terjadi pada level realitas, pada level representasi realitas, dan pada level ideologi. Pada level realitas, problem etika itu antara lain terkait dengan keabsahan narasumber.
Contohnya sebagaimana dipaparkan oleh Budi Wibawa, yaitu penggunaan narasumber palsu atau penggunaan narasumber asli tapi dengan cara tidak sah (Wibawa 39). Problem etika pada level representasi bisa berupa manipulasi rekonstruksi yang tendensius. Sedangkan pada level ideologi, problem etika itu bisa berupa upaya penyimpangan secara sengaja terhadap sifat dan arah dari doktrin atau norma yang disampaikan (Hidayatullah 12).
Kelima, kesan totalitas isi film menjadi kabur, tidak tampak jelas apakah film tertentu itu berupa propaganda budaya, propaganda ideologi, atau bukan kedua-duanya. Hal itu terjadi bisa karena propagandanya lemah, bumbu-bumbu ceritanya terlalu banyak, atau juga karena intrik tambahannya lebih menarik perhatian daripada pesan utama. Mungkin itulah juga salah satu penyebab artikel-artikel yang membahas perjuangan budaya, propaganda budaya atau ideologi, tentang film Indonesia, jumlahnya tergolong sedikit. Atau boleh jadi, pada artikel yang ada pun, itu hanyalah berupa kesimpulan penulis artikelnya saja bahwa film yang dikajinya itu merupakan film budaya, padahal menurut pembuatnya bukan.
Film Salawaku (2016), misalnya, yang dibahas oleh Puspasari mengenai representasi budaya (Puspasari 1) menggambarkan betapa indahnya pesona alam Maluku dan wisata kuliner lokalnya. Film yang bergenre road movie itu dipandang baik oleh Puspasari, sebagai film yang mampu merepresentasikan budaya. Tetapi secara keseluruhan dari isi film, sulit untuk bisa dikategorikan secara penuh sebagai film perjuangan, promosi buaya, apalagi sebagai propaganda budaya. Kendalanya terletak pada bumbu cerita yang melibatkan percintaan sampai hamil di luar nikah.
Dalam hal ini tentu pembuat film bukan berarti telah melakukan kesalahan. Penonton yang memiliki penilaian lain juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Itu adalah pilihan-pilihan yang bisa diambil. Hanya saja, setiap pilihan itu menimbulkan konsekuensi. Kegamangan pengkategorian film budaya atau perjuangan ideologi juga terjadi pada film-film lain seperti, sebut saja, film Kartini (2017) atau film Ketika Bung di Ende (2014). Berdasarkan pengalaman Penulis memutar kedua film tersebut dengan sejumlah kalangan, banyak di antara penonton yang kecewa dengan level ketokohan yang digambarkan di dalam film.
Mereka rata-rata berkomentar, sebelum menonton filmnya, gambaran Kartini dan Bung Karno di benak mereka itu adalah sosok yang luar biasa hebatnya. Namun kenyataanya dalam film ternyata tidak seberapa. Terjadilah konflik batin. Akhirnya munculah anggapan, -- semacam menghibur diri karena ketokohan yang sudah tertanam di hati tidak ingin tereduksi -- bahwa kedua film itu hanyalah sekadar cerita dari perjalanan hidup Kartini dan cerita suka-duka Bung Karno ketika menjalani pengasingan di Ende. Reaksi penonton semacam itu pun adalah konsekuensi dari totalitas isi film.
Dari kelima konsekuensi di atas bisa dipahami bahwa dampak dari kegagalan representasi propaganda di dalam film bukan hanya menimpa penonton tetapi juga bisa berbalik ke pembuat film. Bagi pembuat film, di antara dampaknya adalah hukuman sosial dari penonton yang bisa mengikis kredibilitas, legitimasi dan reputasi, yang biasanya menjadi andalan dan sangat dijaga oleh para pembuat film. Oleh karena itu, konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi perlu diantisipasi untuk dikurangi atau dihilangkan. Caranya, tentukan arah yang jelas garis utama perjuangan atau propaganda yang akan dibangun, tetapkan proporsi yang memadai antara topik utama dengan “hiasan” tambahan, gunakan perpaduan dari keunggulan naratif dan sinematik untuk memperkuat garis utama misi, dan selalu berada di pihak penonton agar setiap representasi dan ideologi benar-benar dalam pertimbangan yang jelas sehingga detail konsekuensi bisa dikontrol.
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 59
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsekuensi representasi propaganda yang mungkin akan ditemui setidaknya ada lima macam. Pertama, munculnya persepsi penonton yang berbeda dari yang diharapkan. Kedua, munculnya perbedaan perilaku penonton akibat dari perbedaan interpretasi terhadap representasi yang diterimanya. Ketiga, dampak dari sifat komunikasi, yaitu pesan yang direpresentasikan dalam film bersifat irreversible. Keempat, munculnya anggapan bahwa dalam proses pembuatan film terdapat problem etika. Kelima, kesan totalitas isi film menjadi kabur akibat pesan ganda yang direpresentasikan.
Konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan terjadi itu bisa dikurangi atau dihilangkan dengan cara: (1) tentukan arah yang jelas garis utama perjuangan atau propaganda yang akan dibangun; (2) tetapkan proporsi yang memadai antara topik utama dengan “hiasan” tambahan;
(3) gunakan perpaduan dari keunggulan naratif dan sinematik untuk memperkuat garis utama;
(4) dan beradalah selalu di pihak penonton agar setiap representasi dan ideologi benar-benar dalam pertimbangan yang jelas sehingga detail konsekuensi bisa dikontrol.
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, B. Analisis Semiotika Unsur-unsur Kebudayaan Palembang dalam Film Ada Surga Di Rumahmu. [FDK - Universitas Islam Negeri Raden Fatah]
2017. http://eprints.radenfatah
ac.id/1426/1/Belia Agustina 13530014 pdf Akbar, K. M., Hanief, L., & Alif, M. Semangat
Nasionalisme dalam Film (Analisis Isi Kuantitatif dalam Film Merah Putih).
Jurnal ProTVF, Kajian Televisi Dan Film, Universitas Lambung Mangkurat, 1(2), 125–138, 2017 http://jurnal.unpad.ac.id protvf/article/download/19872/9069.
Ambarini, A., & Umaya, N. M. (2018). Semiotika Teori dan Aplikasi pada Karya Sastra. IKIP PGRI Press. http://eprints.upgris
ac.id/311/1/buku semiotika.pdf, 2018
Asri, R. (2020). Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Aanalisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini (NKCTHI).”
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia, 1(2), 1–13. https://media.neliti.com media/publications/327015-membaca film-sebagai-sebuah-teks-analisi 0fcef4fb.pdf
Christina, & Yudhi, L. Representasi Film sebagai Diplomasi Budaya (Analisis Semiotika Barthes Film Me VS Mami sebagai Diplomasi Budaya Padang. UBM Jurnal, 65–104, 2017 https://journal.ubm.ac.id index.php/semiotika/article
download/949/839
Elizabeth, R. Analisis Tema pada Film 1911 Karya Jackie Chan dan Film di Balik 98 Karya Lukman Sardi: Kajian Sastra Bandingan [Universitas Sumatra Utara] 2018. http://repositori.usu.ac.id/
bitstream/handle/123456789/
7456/130710019.pdf?sequence=
1&isAllowed=y
Eryanto, D. P. Ideologi Imperialisme dalam Film Transformers. Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi FISIP Universitas
Diponegoro, 1–11. 2015. https://media.
neliti.com/mediapublications/187301-ID- pesan-propaganda-ideologi-
imperialisme-d.pdf
Fatima, A. A. Representasi Nilai Kebangsaan dalam Film Soekarno (Analisis
Semiotika John Fsike) [Institut Agama Islam Negeri Purwokerto] 2019. http://
repository.iainpurwokerto.ac.id/5204/1 COVER _BAB I_BAB V-DAFTAR PUSTAKA .pdf
Herwendo, R. Analisis Semiotika Representasi Perilaku Masyarakat Jawa dalam Film Kala. Wacana, XIII(3), 230–245, 2014.
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/
articlephp?article=808369&val=
13180&title= ANALISIS
SEMIOTIKA REPRESENTASI PERILAKU MASYARAKAT JAWA DALAM FILM KALA
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 60
Hidayatullah, N. A. REPRESENTASI KEKERASAN DALAM FILM
“JAGAL” THE ACT OF KILLING ( ANALISIS SEMIOTIK ) [Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. 2016.
http://repository.iainpurwokerto.
ac.id/2279/2/COVER_ABSTRAK_
DAFTAR ISI_BAB_I_BAB V_
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Mahmudi, M. A. Propaganda dalam Film (Analisis Teknik Propaganda Anti Iran dalam Film Argo). Jurnal Komunikasi PROFETIK, 06(2), 83–96, 2013. https://media.neliti.com/
media/publications/224300-propaganda- dalam-film-analisis-teknik-pr.pdf
Manesah, D. Representasi Perjuangan Hidup dalam Film “Anak Sasada” Sutradara Ponty Gea. Jurnal Proporsi, 1(2),
179–189, 2016. http://e-journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/PROPORSI/
article/download/523/662
Mirnawati, Ali, N. H., & Zalpa, Y. Film dan Propaganda Politik (Studi atas Film
“G-30S/PKI” dan“Jagal”). Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 19(2), 70–91, 2019. http://jurnal.
radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/
article/download/4470/2779
Mukarom, Z. Teori-Teori Komunikasi (A. I.
Setiawan (ed.); 1st ed., Vol. 1 2020).
Jurusan Manajemen Dakwah,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. http://
digilib.uinsgd.ac.id/31495/1/ZM Book Teroi-teori Komunikasi.pdf
Prasetya, G. E. Peran Konflik dalam
Membangun Karakter Tokoh Utama pada Film “Sultang Agung: Tahta, Perjuangan, dan Cinta” [Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2020]. http://
digilib.isi.ac.id/8364/3/
JURNAL_1510750032.pdf
Pratiwi, J. . “Depth of Field (II) –Sebuah Telaah Ideologis Ruang Ketajaman: Studi Kasus Terhadap Film Roma (2018)”. IMAJI:
Film, Fotografi, Televisi, &Amp; Media Baru, vol. 11, no. 2, Feb.
2020, pp. 4-12, https://imaji.ikj.ac.id/
index.php/IMAJI/article/view/8.
Puspasari, C., Masriadi, & Yani, R. Representasi Budaya dalam Film Salawaku. Jurnal Ilmu Komunikasi - Jurnalisme,
Universitas Malikussaleh, 9(1), 18–37, 2020. https://ojs.unimal.ac.id/
jurnalisme/article/view/3097/pdf
Rahardjo, D. D. F. Representasi Budaya Populer dalam Film “Slank Nggak ada Matinya”
Karya Fajar Bustomi. EJurnal Ilmu Komunikasi - FISIP Unmul, 4(3), 344–358, 2016. https://ejournal.ilkom.
fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/
uploads/2016/08/Artikel Jurnal Upload Dwi (08-23-16-04-56-33).pdf
Wibawa, B. . “Problem Etika Dalam Kasus Dokumenter Jagal (2012) Dan Senyap (2014)”. IMAJI:Film, Fotografi, Televisi,
&Amp; Media Baru, vol. 11, no. 2, Feb.
2020, pp. 38-50, https://imaji.
ikj.ac.id/index.php/IMAJI/article view/12.
Konsekuensi Representasi Propaganda Budaya dan Ideologi dalam Film | 61
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter | 62
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter
Maria Hartiningsih Program Studi Kajian Gender
Pascasarjana Universitas Indonesia, lulus tahun 2003 E-mail: [email protected]
ABSTRACT
After 50 Years of Silence Voiced by Books and Documentary Film. Not many people read the news of Jan Ruff-O'Herne's return on the morning of August 19, 2019 at his home, in Adelaide, Australia, surrounded by his children, grandchildren and great-grandchildren. She is 96 years old. Jan Ruff-O'Herne left a trail of more than five decades of fighting to campaign against rape in war and spent the rest of his life reclaiming his dignity. She was the first European woman who dared to testify publicly. He tore the silence of the black history that was denied for a very long time by the party that did it. For that, he received various awards, including from the Australian Government, the Dutch Government, and the Vatican. O'Herne was one of the few European women in the Japanese occupied territories during World War II who were forced into sex slavery. Most of them come from Asia, namely Korea (the largest), Indonesia, the Philippines, China and Taiwan. She is the only survivor who struggles to resist the use of the term "comfort women". Comfort means something soft, safe and friendly. "We are victims of wartime rape and sexual assault by the Imperial Japanese Army." O'Herne demanded an apology from the Japanese Government personally and was among the survivors who refused monetary compensation from the Asian Women's Fund. He also emphasized how rape is a tool for subjugation in war so it should be seen as a war crime and a crime against humanity. And another interesting thing is that this testimony to Jan Ruff-O'Herne was also made into a documentary film produced in Australia by director Ned Lander, entitled 50 Years of Silence (1994).
Keywords: Jan Ruff-O’Herne, rape, sex slave
ABSTRAK
Tak banyak orang membaca berita mengenai kepulangan Jan Ruff-O’Herne pada pagi tanggal 19 Agustus 2019 di rumahnya, di Adelaide, Australia, dikelilingi oleh anak, cucu dan cucu buyutnya.
Usianya 96 tahun. Jan Ruff-O’Herne meninggalkan jejak perjuangan selama lebih lima dekade untuk berkampanye melawan pemerkosaan dalam perang dan menghabiskan sisa hidupnya untuk merebut kembali martabatnya. Dia adalah perempuan Eropa pertama yang berani bersaksi di depan publik secara terbuka. Dia merobek kebisuan sejarah hitam yang ditolak untuk waktu yang sangat lama oleh pihak yang melakukannya. Untuk itu, dia menerima berbagai penghargaan, di antaranya dari Pemerintah Australia, Pemerintah Belanda, dan Vatikan. O’Herne adalah salah satu dari sedikit perempuan Eropa di wilayah pendudukan Jepang selama Perang Dunia II yang dipaksa menjadi budak seks. Sebagian besar berasal dari Asia, yakni Korea (terbesar), Indonesia, Filipina, China dan Taiwan.
Dia menjadi satu-satunya survivor yang berjuang untuk menolak penggunaan istilah “comfort women”.
Comfort mengandung arti sesuatu yang lembut aman dan ramah. “Kami ini korban perkosaan dan serangan seksual dalam masa perang oleh tentara Kerajaan Jepang”. O’Herne menuntut permintaan maaf Pemerintah Jepang secara pribadi dan berada dalam barisan survivor yang menolak kompensasi berupa uang dari Asian Women Fund. Dia juga menekankan bagaimana perkosaan menjadi alat
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter | 63
untuk menundukkan dalam perang sehingga harus dilihat sebagai kejahatan kriminal perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang menarik lainnya adalah testimoni atas Jan Ruff-O’Herne ini juga dibentuk menjadi sebuah film dokumenter yang diproduksi di Australia dengan sutradara Ned Lander, berjudul 50 Years of Silence (1994).
Kata Kunci: Jan Ruff-O’Herne, pemerkosaan, budak seks
PENDAHULUAN
Saya menemuinya di Tokyo pada tahun 2000 dan di Den Haag pada tahun 2001.1
Den Haag, awal Desember 2001
Dari atas panggung Lucent Danstheatre, Den Haag, Belanda, Jan Ruff- O’Herne (78 tahun) mengangkat tinggi-tinggi kopi dari 240 halaman Final Judgment yang diberikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Gabrielle Kirk McDonald, siang, waktu setempat, tanggal 4 Desember 2001.
Mulutnya komat-kamit. Air matanya tergenang.
Keputusan itu diambil setelah Majelis Hakim mendengarkan kesaksian 35 dari 75 penyintas yang hadir selama proses pengadilan di Tokyo (Tokyo Tribunal) tahun 2000. Pengadilan Rakyat itu merupakan jawaban atas kegagalan Jepang memenuhi tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan bagi sekitar 200.000 perempuan di Asia yang dipaksa menjadi budak seks di ‘comfort stations’ bagi para serdadu Jepang selama Perang Dunia II.
Final Judgment itu merupakan simbol diakhirinya pengampunan atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, yang oleh ketiadaan mekanisme memungkinkan pelakunya kebal hukum.
Singkatnya, Majelis Hakim menyatakan bersalah kepada Kaisar Hirohito, Kaisar Showa yang antara tahun 1937-1945 adalah Kepala Negara Jepang dan Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan Jepang; Rikichi Ando, Komando Angkatan Perang untuk wilayah Cina Selatan mulai Oktober 1940, dan lain-lain.
1 Semua bahan diambil dari laporan Maria Hartaningsih antara tahun 2000 dan 2001 di Harian Pagi Kompas.
“Lega rasanya,” ucapnya pelan, “Tetapi, lebih dari itu, saya merasakan solidaritas yang sangat tinggi dari semua survivor.” Kemudian dia memeluk Ema Kastimah (75 tahun), survivor dari Cimahi, Jawa Barat. Dua perempuan ini untuk beberapa saat tenggelam dalam perasaan yang hanya diketahui oleh keduanya.
Situasi siang di Den Haag pada awal musim dingin itu sangat berbeda dengan situasi di Tokyo setahun sebelumnya.
Tokyo, 26 Desember 2000
Ketika mendengar musik latar yang mirip lagu- lagu mars ciptaan komponis Jerman Richard Wagner mengiringi gladi resik di panggung Kudan Kaikan, Tokyo, Jepang, Kamis (7/12) petang, Jan Ruff-O’Herne (77 tahun) segera meninggalkan tempat duduknya. Wajah Jan tampak pucat dan kedua tangannya menutup telinganya. “Bisa tolong diganti musiknya,” suaranya bergetar saat menemui seorang anggota panitia penyelenggara.
Ketika suara musik berangsur melemah, Jan berangsur tampak lebih tenang.
Selama puluhan tahun dalam hidupnya, Jan, yang dipaksa menjadi budak nafsu serdadu Jepang di Semarang selama tiga bulan, mulai bulan Februari tahun 1944, mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD). Selama puluhan tahun ia tidak bisa mendengar atau melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang.
Jan adalah anak ketiga dari empat bersaudara anak keluarga O’Herne-campuran Perancis- Belanda, yang dilahirkan di Cepiring, Jawa Tengah, tahun 1923. Kebahagiaan itu direnggut oleh pendudukan Jepang di Jawa pada tahun 1942. Keluarga O’Herne ditempatkan di kamp konsentrasi Ambarawa sampai bulan Februari
1944, ketika Jan bersama sembilan gadis peranakan Eropa lainnya dipaksa ikut tentara Jepang ke Semarang.
Tidak ada satu pun yang kemudian mampu mengembalikan apa yang telah dihancurkan oleh perbuatan biadab para serdadu Jepang di dalam kamar-kamar gedung “The House of the Seven Seas”, sebuah klub pelesiran untuk para perwira Jepang di Semarang.
“Saya dibebaskan dari rumah neraka itu, tetapi lukanya tak pernah sembuh. Bayangan di rumah bordil itu tidak pernah pergi dari ingatan saya…”
Jan Ruff menceritakan seluruh kebenaran mengenai dirinya kepada Tom O’Herne sebelum mereka menikah. “Waktu itu Tom menangis tanpa suara, tetapi cintanya pada saya tidak pernah berubah. Kami kemudian berjanji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa pun.”
Dalam kehidupan perkawinannya yang bahagia dengan Tom Ruff, warga Inggris yang kemudian bermigrasi ke Australia dan menetap di Adelaide, Tasmania, Jan selalu mengingatkan kepada sanak keluarga dan seluruh kerabatnya, agar tidak pernah memberinya bunga pada hari-hari bahagia mereka. Ibu dua anak dan nenek dua cucu itu tak mampu menjelaskan bahwa bunga selalu mengingatkannya pada vas bunga berisi jenis bunga tertentu yang selalu ditaruh di ruang tidurnya di “The House of the Seven Seas”.
Dia juga tak pernah mau mengunjungi dokter kalau tidak amat sangat terpaksa. Sosok dokter di dalam sebuah ruang praktik selalu mengingatkannya pada dokter di “The House of the Seven Seas” yang dia pikir bisa menolongnya, tetapi malah dengan brutal memperkosanya.
Setelah 50 tahun melewati malam-malam dengan mimpi yang mengerikan, pada awal tahun 1992, secara kebetulan, Jan melihat kesaksian di televisi dari beberapa perempuan Korea yang dijuluki sebagai “comfort women” pada masa pendudukan Jepang. “Tiba-tiba saya tahu apa yang harus saya lakukan...”
Keberanian para perempuan Korea itu memberikan kekuatan kepada Jan untuk berani melakukan satu tindakan radikal yang dia
katakan sebagai proses penyembuhan. “Saya harus bersaksi mengungkapkan kebenaran. Saya harus membuka seluruh rahasia hidup saya. Apa yang terjadi pada saya bukanlah aib saya, tetapi aib Pemerintah Jepang.”
Bukunya 50 Years of Silence: Comfort Women of Indonesia (1994) ditulis dengan dukungan seluruh keluarga, melengkapi seluruh referensi mengenai masalah perkosaan dalam perang.
Sementara versi film dokumenternya berdurasi 57 menit, versi bukunya 300-an halaman. Apakah film dokumenternya mampu merangkum trauma psikologis yang diderita Jan Ruff? Tentu saja sulit sekali. Sebab, ketika sastra telah berbicara, film menjadi bungkam. Demikian sebaliknya, ketika film sudah berbicara, sastra menjadi tenggelam.
Satu hal, film dokumenternya dengan narasi bahasa Inggris berusaha setia dengan substansi tekstual dari bukunya.
PEMBAHASAN
Isu ‘perempuan penghibur’ berkembang menjadi isu sentral dalam perdebatan sejarah tentang perang, terkait nasionalisme, patriotisme, agama, dan pengalaman dalam hal gender, seksualitas, ras dan bangsa.
Pada tahun 1966, Kementrian Pendidikan Jepang memasukkan isu ‘perempuan penghibur’
sebagai bagian dari pelajaran sejarah untuk siswa sekolah menengah pertama. Sejak April 1997, masalah wanita penghibur telah diajarkan di SMP sebagai fakta sejarah. Namun, ada dua kelompok yang memiliki perspektif berbeda dan memperebutkan deskripsi atau definisi mengenai
‘perempuan penghibur’ dalam buku teks sekolah menengah di Jepang.
Kelompok yang disebut oleh Rebecca Clifford (2004) sebagai neonasionalis-revisionis, menegaskan bahwa ‘perempuan penghibur’ Asia yang memasok seks kepada serdadu Jepang bukanlah ‘budak seks militer’ yang dipaksa oleh tentara kekaisaran, melainkan pelacur biasa yang melakukannya secara sukarela. Kelompok ini meminta pemerintah Jepang menarik kembali permintaan maaf kepada negara-negara di Asia
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter | 64
yang diduduki selama perang, khususnya Korea dan China, dan menghapus lembar hitam itu dari buku pelajaran sejarah sekolah menengah.
Termasuk di dalam kelompok yang menentang cap ‘penjahat perang’ pada Jepang adalah pakar pendidikan Fujioka Nobukatsu dan kartunis Kobayashi Yoshinori. Mereka khawatir anak- anak mempelajari sejarah yang negatif sehingga tidak dapat menghargai budaya Jepang. Feminis dan profesor antripologi kultural, Tomomi Yamaguchi (2017), menganalisis fenomena “The Japan is Great” dengan sangat menarik.2
Kelompok lain, sering disebut sebagai pacifis- revisionis, menekankan hak asasi manusia.
Dalam pengadilan tahun 2000 itu, sejarawan Jepang, Akira Yamada dan Yoshiaki Yoshimi, meyakinkan Majelis Hakim bahwa sistem comfort stations dirancang secara rapi dan sistematis oleh para komando militer Jepang yang mempunyai akses pribadi kepada kaisar. Cara ini merupakan tanggapan atas terjadinya pemerkosaan massal di Nanking, Tiongkok, tahun 1937.
Sejarawan Yoshiaki Yoshimi (1995) menulis, ada anggapan umum bahwa perempuan penghibur merupakan alat untuk pembebasan seksual prajurit militer. Hak asasinya sebagai manusia dikoyak. Banyak prajurit Jepang menggenggam mitos bahwa laki-laki ‘sejati’ adalah laki-laki yang ‘mengenal’ perempuan. Oleh karena itu, setelah ketegangan selama berperang, para prajurit didorong pergi ke ‘comfort stations’.
Yoshimi menghubungkan cara berpikir yang maskulinis-patriarkis itu mendukung prostitusi berlisensi di Jepang dan koloni-koloni mereka dan sistem ‘comfort Stations’ di medan perang (223-24). Istilah ‘comfort women’ digunakan untuk melegitimasi perbuatan kriminal dalam perang. Pada tahun 1994-1997, beberapa pejabat tinggi Jepang menyatakan, comfort women adalah relawan. Ini menyangkali adanya
2 Lebih jauh baca Tomomi Yamaguchi, “The
“Japan Is Great!” Boom, Historical Revisionism, and the Government”, The Asia-Pacific Journal, March 15, 2017 Volume 15, Issue 6, Number 3, Article ID 5021,
https://apjjf.org/2017/06/Yamaguchi.html
penipuan, pengancaman, pemaksaan, dan penculikan terhadap korban.
Kegagalan negara mempertanggungjawabkan perbuatan kriminal itu sudah terjadi dalam Pengadilan Internasional Kriminal Perang untuk Timur Jauh di Tokyo, April 1946-November 1948.
Pengadilan itu sama sekali tidak menyinggung kasus perbudakan seks oleh militer Jepang.
Pemerintah Jepang melakukan pelanggaran tanggung jawab negara dengan menghancurkan berbagai dokumen, termasuk beberapa dokumen yang berkaitan dengan sistem perbudakan seksual dalam perang.
Isu ‘perempuan penghibur’ menawarkan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali konstruksi ideologis historis dan kontemporer tentang gender dan seksualitas dan membawa perdebatan melampaui diskursus dominan yang sangat male-centric.
Terkait dengan subjektivitas seksual dan gender, maka buku otobiografi dan memoir yang ditulis oleh korban—yakni perempuan yang dipaksa menjadi budak seks serdadu Jepang dalam perang—merupakan representasi dalam narasi pribadi. Subjektivitas ini, betapa pun juga dibentuk melalui perbedaan ras dan kebangsaan.
Keberanian Jan Ruff-O’Herne untuk menulis dan mengungkapkan seluruh pengalamannya itu merupakan tindakan yang luar biasa.
Selama 50 tahun dia berada di dalam ‘gua perlindungan’ di dalam dirinya. Dalam isu ini dia adalah ‘minoritas’ berganda: perempuan Eropa, Katolik, dan bermukim di negara maju dengan kehidupan berkeluarga yang relatif tentram dan aman. Sementara sebagian korban dari Asia, Indonesia khususnya, sebagian besar berada pada kondisi ekonomi subsisten, menyandang stigma dan untuk waktu yang lama diabaikan keberadaannya oleh negara.
Dalam otobiografinya, Ruff-O’Herne menulis bahwa ketika semua korban pemerkosaan perang Tentara Kekaisaran Jepang dikumpulkan oleh tentara Jepang di tempat terpisah di kamp penjara wanita Keramat, perempuan Belanda dari kamp bagian lain menghina mereka,
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter | 65
dengan menyebut mereka sebagai ‘pelacur’ dan
‘pengkhianat’ (Ruff-O’Herne 115).
Mereka menyalahkan korban dan menarik garis tegas di antara sesama korban, dengan memandang O’Herne sebagai ‘liyan’. Reaksi itu, selain menunjukkan bekerjanya wacana patriarkis yang dominan, juga terjadi ‘dehumanisasi sistematik’ (Bell Hokks, 1984) dalam komunitas korban.
Penghinaan itu berimbas kepada adik perempuannya.
Dukungan dari seorang biarawati Katolik yang memiliki hubungan dengan Ruff-O’Herne tidak mampu melepaskannya dari kubangan rasa malu di dalam ruang dirinya, yang membuat dia terbisukan.
Banyak angle bisa dipilih untuk membedah otobiografi Jan Ruff-O’Herne. Saya mencoba menelaah proses di dalam dirinya untuk tiba pada keputusan membuka rahasia terbesar dirinya secara terbuka di ranah publik.
Ruff-O’Herne tidak berbicara secara terbuka tentang pengalamannya sampai tahun 1992, sebelum melihat di televisi tiga perempuan Korea korban perbudakan seksual serdadu Jepang pada masa perang menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari pemerintah Jepang.
Acara di televisi itu memicu proses penyadaran dalam diri Ruff-O’Herne, membuat dia paham bahwa seluruh pengalaman personalnya mempunyai akar struktural. Namun, dia juga paham, untuk menghasilkan perubahan yang signifikan, diperlukan kerja kolektif.
Proses itu membuat pergulatan selama puluhan tahun di dalam ruang diri Ruff-O’Herne yang tersembunyi, seperti menemukan titik terangnya.
Ruang tersembunyi ini oleh Vaclav Havel disebut sebagai hidden sphere, suatu ruang di dalam diri di mana kenyataan yang baru diuji kembali dan ditanggapi; suatu ruang di mana kehidupan dihidupi secara terbuka dalam kebenaran (Havel, 1986; Bouvard, 1994).
Hidden’s sphere merupakan suatu kekuatan politik yang dahsyat. Ruang tersembunyi ini dari perspektif kekuasaan merupakan wilayah paling berbahaya, karena dia seperti gejolak yang bisa
tiba-tiba menampakkan wujudnya ke dalam sistem. Kalau hidden’s sphere ini terbuka, maka biasanya sudah terlambat untuk menutupnya kembali. Dari ruang tersembunyi itu lah manusia bisa menciptakan situasi yang menyebabkan paniknya rezim yang berkuasa, betapa pun sederhananya tindakan itu.
Ruff-O’Herne kemudian melihat dunia dengan caranya sendiri dan bisa mengambil keputusan.
Dengan keputusan itu, Ruff-O’Herne menjadi bagian dari gerakan yang menuntut permintaan maaf pemerintah Jepang atas kebrutalannya selama perang.
Dalam Audiensi Publik Internasional tentang Kejahatan Perang Jepang di Tokyo pada bulan Desember 1992, Ruff-O’Herne memecah kebisuan dengan membagikan kisahnya. Pada tahun 1994, dengan dukungan seluruh keluarga, dia menerbitkan memoar pribadi, Fifty Years of Silence: Comfort Women of Indonesia, yang mendokumentasikan pergulatannya menjalani kehidupan sebagai penyintas perkosaan dan perbudakan seksual dalam perang. Keputusan itu tidak mudah.
Betapa pun, wacana penyintas atau survivor bersifat kontradiktif, apalagi kebiadaban tentara Kekaisaran itu masih terus menjadi kontroversi atas nama ‘nasionalisme’, ‘martabat bangsa’ dan lain-lain, sambil terus menganggap korban tidak bermartabat, bahkan tidak ada. Maka, rasa sakit akibat penghinaan lebih dominan, membuat ingatan akan serangan pada tubuh itu sulit dihapus (Mardorossian, 2002).
Ruff-O’Herne menunjukkan proses perjuangannya melalui ruang ‘a-politis’ untuk berbicara: ruang personal. Namun demikian, mengutip Carol Hanisch (1969), yang a-politis itu sesungguhnya sangat politis apalagi ketika digemakan di ruang publik.3
Suatu gerakan dimulai dari proses di dalam diri tiap-tiap individu. Melalui consciousness raising
3 Carol Hanisch, “The Personal is Political”, dalam Shulamith Firestone and Anne Koedt, Ed, (1970), Notes from the Second Year: Women Liberation. NY;
Radical Feminism
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter | 66
atau membangkitkan kesadaran (selanjutnya disebut CR), perempuan memahami posisi dan situasinya dalam suatu struktur sosial, sekaligus melakukan identifikasi subjektif atas dirinya sebagai anggota suatu kelompok. CR diyakini oleh para feminis sebagai suatu proses yang berhasil menghadirkan perempuan dengan cara baru untuk mendefinisikan dan menamakan ulang dunia.4
Dalam proses penyadaran, hubungan-hubungan kekuasaan dan pengalaman korban tidak ditelaah hanya secara sosiologis karena di situ ada klaim kebenaran dari pemilik kekuasaan.
Klaim kebenaran ini selalu digunakan untuk merebut posisi tawar politik karena kekuasaan yang menindas diawali dengan mempersepsikan realitas perempuan dan kemudian terus mereproduksinya.
Proses penyadaran penting supaya sampai pada yang epistemologis. Saat kesadaran terbentuk—
yaitu perempuan tiba pada posisi “mengetahui”
realitasnya—dia tidak berada pada status kognitif dan psikologis, tetapi dapat menunjuk kepada tindakan sosial yang bermakna dan bisa merebut klaim kebenaran dari pihak yang berkuasa.
Kegiatan epistemik untuk menyingkapkan kenyataan bahwa ada pengalaman, pengetahuan, dan subjektivitas yang selama ini diabaikan ini sangat penting karena klaim kebenaran akan selalu digunakan untuk merebut posisi tawar politik kekuasaan.
Oleh karena itu, seperti diingatkan Hirsch (1995), ingatan yang berhubungan dengan pengalaman individual merupakan locus politik karena akan selalu dikompetisikan oleh berbagai kelompok untuk memperoleh posisi tawar politik terkuat.
Ini juga sangat berkaitan bagaimana sejarah dikonstruksikan dan diinterpretasikan.
Isi sebuah klaim ‘saya tahu’ lebih dari sekadar
4 Lebih jauh dapat dibaca dalam Catharine A.
MacKinnon. (1991), Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge & London: Havard University Press.
Hal. 83-105
menegaskan sebuah preposisi.5 Di sini pandangan Austin menjadi penting. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia mengetahui maka ia bukan semata-mata menyampaikan sebuah status kognitif atau psikologis, melainkan menunjukkan sebuah tindakan sosial yang bermakna. Kesaksian atau testimoni di depan publik, bisa dilihat sebagai upaya kelompok masyarakat korban merebut klaim kebenaran.
Proses tersebut tidak seragam karena setiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda.
Namun pengalaman itu menjadi dasar bagi diri perempuan untuk membangun pengetahuan tentang realitas sosialnya, agar ia dapat mendefinisikan sendiri situasinya. Itulah inti dari seluruh proses CR pada perempuan, karena realitas sosial perempuan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibangun kembali.
Di sini ada beberapa sebab. Pertama, realitas sosial perempuan dan situasinya sudah didefinisikan oleh kekuasaan yang menindas dengan diciptakannya ideologi tentang
‘perempuan baik-baik’. Kedua, kalau kita tidak memahami ideologi dominan dari otonomi moral dalam kebudayaan kita, juga definisi moral dari mereka yang memiliki hak istimewa, maka suara perempuan akan terus terbisukan.
5 J.L. Austin dalam “Other Minds” mengatakan, “…
saying ‘I know’ is not saying ‘I have performed an especially striking feat of cognition, superior, in the same scale as believing and being sure, to being quite sure. Just as promising is not something superior, in the same scale as hoping and intending, even to merely fully intending; for there is nothing in that scale superior is fully intending.
When I say, ‘I know’, I give others my word: I give others my authority for saying that ‘S is P’. If you say you know something, the most immediate challenge takes the form of asking, ‘Are you in a position to know?’: that is, you must undertake to show not merely that you are sure of it, but that it is within your cognizance.” Dalam J.O Urmson dan G.J. Warnoch (ed), 1970, hlm.99 dan hlm.100.
“Saya tahu” dalam hal ini juga bisa mengacu pada apa yang disebut Giddens sebagai discursive consciousness, yang mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. B. Herry-Priyono, Anthony Giddens, Suatu Pengantar, 2002, hlm.28-29, atau yang disebut Paulo Freire dalam Paedagogy of the Opressed (1978) sebagai kesadaran kritis.
Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter | 67